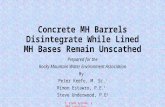MH
-
Upload
dessy-vinoricka-andriyana -
Category
Documents
-
view
2 -
download
1
description
Transcript of MH
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi dan Sinonim
Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi yang kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang bersifat intraseluler obligat, yang menyerang saraf tepid an kemudian menimbulkan suatu kelainan kulit (Kosasih A, 2005).
Kuman penyebab penyakit Kusta, ditemukan pertama kali oleh sarjana dari Norwegia Gerhard Hendrik Armauer Hansen pada tahun 1873, maka dari itu Kusta dikenal juga dengan nama Morbus Hansen, sesuai dengan penemu kuman penyebab kusta tersebut. Kata lepra disebut dalam kitab injil, terjemahan dari bahasa Hebrew zaraath (Kosasi A, 2005).
2.2 Epidemiologi
Penyebaran penyakit Morbus Hansen dari suatu tempat ke tempat lain sampai tersebar di seluruh dunia disebabkan oleh perpindahan penduduk yang terinfeksi penyakit tersebut. Penderita kusta tersebar di seluruh dunia, walaupun terbanyak di daerah tropik dan subtropik. Penyebarannya terutama di benua Afrika, Asia, Amerika Latin serta masyarakat yang social ekonominya rendah (Harahap, 2000) (Kosasih A, 2005).
Morbus Hansen dapat menyerang semua umur, anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa. Di Indonesia penderita anak-anak dibawah umur 14 tahun didapatkan 13%, tetapi anak dibawah umur 1 tahun jarang sekali. Frekuensi tertinggi trdapat pada kelompok umur antara 25-35 tahun (Kosasih A, 2005).
Menurut Ress (1975) dapat ditarik kesimpulan bahwa penularan dan perkembanyan penyakit Morbus Hansen hanya tergantung dari dua hal yakni jumlah atau keganasan Micobaterium leprae dan daya tahan tubuh penderita. Disamping itu faktor-faktor yang berperan dalam penularan ini adalah (Zulkifli, 2003):
Usia: Anak-anak lebih peka dari pada orang dewasa, insidens rate 10-20 tahun; puncak prevalensi 30-50 tahun.
Jenis kelamin: laki-laki lebih banyak yang terjangkit
Ras: bangsa Asia dan Afrika lebih banyak terjangkit
Kesadaran social: Umumnya Negara-negara endemis adalah Negara-negara tingkat social ekonomi rendah
Lingkungan: fisik, biologi, sosial,yang kurang sehat.
Demografi: penyakit yang berkembang di seluruh dunia; 600.000 kasus baru per tahun; 1,5-8 juta total kasus di seluruh dunia. Lebih dari 80% kasus terdapat di India, China, Myanmar, Indonesia, Brazil, Nigeria (Wolff dkk, 2005).
2.3 Etiologi
Penyebab Morbus hansen adalah Mycobacterium leprae, yang ditemukan oleh warganegara Norwegia, G.A Armauer Hansen pada tahun 1873 dan sampai sekarang belum dapat dibiakkan dalam media buatan. Kuman Mycobacterium leprae berbentuk basil dengan ukuran 3-8 Um X 0,5 Um, tahan asam dan alkohol serta bersifat Gram positif. Mycobacterium lepraehidup intraseluler dan mempunyai afinitas yang besar pada sel saraf (Schwan cell) dan sistem retikulo endothelial (Kosasih A dkk, 2005).
2.4 Patogenesis
Spektrum klinis dari Morbus Hansen tergantung pada variasi batasan imunologi host untuk mengembangkan Cell mediated Imunity yangefektif terhadap M. Leprae. Organism dapat menginvasi dan bereplikasi pada syaraf tepid an menginfeksi endotel dan sel fagosit pada banyak organ.
Bila basil M. leprae masuk kedalam tubuh seseorang, dapat timbul gejala klinis sesuai dengan kerentanan orang tersebut. Masa inkubasi yaitu 20-40 tahun (kebanyakan 5-7 tahun). Bakteri ini pertama kali menyerang saraf tepi, yang selanjutnya dapat menyerang kulit, mukosa mulut, saluran nafas bagian atas, system retikuloendotelial, amta, otot, tulang dan juga testis, kecuali susunan saraf pusat. Morbus Hansen merupakan penyakit menahun jangka panjang yang dapat menyebabkan anggota tubuh penderita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Kosasih A, 2005)
Cara-cara penularan penyakit Morbus Hansen sampai saat ini masih merupakan tanda Tanya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa penularan penyakit ini adalah:
Melalui secret hidung, basil yang berasal dari secret hidung penderita yang sudah mongering, diluar masih dapat hidup 2-7 x 24 jam.
Kontak kulit dengan kulit. Syarat-syaratnya adalah harus dibawah umur 15 tahun, keduanya harus ada lesi baik mikroskopis maupun makroskopis, dan adanya kontak yang lama dan berulang-ulang/
M. leprae mempunyai patogenitas yang rendah, sebab penderita yang mengandung kuman lebih banyak belum tentu memberikan gejala yang lebih berat bahkan dapat sebaliknya. Ketidakseimbangan antara derajat infeksi dengan derajat penyakit, tidak lain karena respon imun yang berbeda yang menyebabkan timbulnya reaksi granuloma setempat atau menyeluruh yang dapat sembuh sendiri atau progresif. Oleh karena itu penyakit ini dapat disebut sebagai penyakit imunologik. Gejala klinisnyanya lebih sebanding dengan tingkat reaksi selularnya daripada intensitasnya infeksi (kosasih A, 2005).
2.5 Gejala Klinis
Manifestasi klinis dari lepra sangat beragam, namun terutama mengenai kulit, saraf, dan membran mukosa.Gejala dan keluhan penyakit bergantung pada multiplikasi dan diseminasi kuman M. Leprae, respon imun penderita terhadap kumanM. Lepraeserta komplikasi yang diakibatkan oleh kerusakan saraf perifer.
Adapun gejala-gejala khas Morbus Hansen adalah (Zulkifli, 2003):
Muncul gambaran kulit yang lebih putih (hipopigmentasi) bersisik, yang tidak gatal dan lama-lama meluas.
Pada lesi tersebut terjadi anastesi. Hal ini menandakan bahwa bakteri telah menyerang saraf tepi.
Gejala yang berat mencakup kerontokan rambut, kekakuan sendi, putusnya jari-jari sampai timbulnya luka-luka (ulkus) akibat kusta.
Apabila terdapat gejala yang mengarah ke kusta, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari mikobakterium tersebut dengan suatu pengecatan basil tahan asam.
Dapat pula disertai pembengkakan saraf tepi maupun cabang-cabang saraf tepi terutama pada saraf ulnaris, medianus, auricularis magnus serta peroneus.
Kelenjar keringat kurang kerja sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat.
Adanya bintil-bintil kemerahan (leproma, nodul) yang tersebar pada kulit
Alis rambut rontok
Muka berbenjol-benjol dan tegang yang disebut fasies leomina (muka singa).
2.6 Klasifikasi
Klasifikasi penyakit kusta berdasarkan spektrum klinik, guna menentukan penatalaksanaan dan penentuan prediksi terjadinya kecacatan, dapat digunakan klasifikasi sebagai berikut :
1. Klasifikasi Madrid
Klasifikasi Madrid merupakan klasifikasi yang paling sederhana yang ditentukan atas dasar kriteria klinik, bakteriologik, dan histopatologik. Ini sesuai dengan rekomendasi Internasional Leprosy Association di Madrid tahun 1953. Klasifikasi Madrid tersebut memutuskan bahwa penyakit kusta dibagi atas : tipe indeterminate (I), tipe tuberkuloid (T), tipe borderline-dimorphous (B) dan tipe lepromatosa (L) (Kosasih A, 2005).
2. Klasifikasi Ridley & Jopling
Klasifikasi penyakit kusta ini lebih dikaitkan dengan spektrum klinik kusta yang sangat lebar rentangnya. Bisa dari kekebalan paling rendah seorang penderita sampai pada kekebalan yang tinggi. Maka klasifikasi ini didasarkan gejala klinik, bakteriologik, histopatologik, dan imunologik. Menurut klasifikasi ini terdapat 5 (lima) tipe klinik penyakit kusta yang erat hubungannya dengan sistem kekebalan yaitu:
Tipe I: macula hipopigmentasi berbatas tegass, anastesi dan anhidrasi, pemeriksaan bakteriologik (-), tes lepromin (+)
Tipe TT (polar tuberkuloid): macula eritomatosa bulat atau lonjong, permukaan kering, batas tegas, bagian tengah sembuh, bakteriologik (-), tes lepromin positif kuat.
Tipe BT (borderline tuberkuloid): macula eritematosa tidak teratur, batas tak tegas, kering. Mula-mula ada tanda kontraktur, anastesi, pemeriksaan bakteriologik (+/-), tes Lepromin (+/-).
Tipe BB (midborderline): macula eritematosa, menonjol, bentuk tidak teratur, kasar, ada lesi satelit, penebalan syaraf dan kontraktur, pemeriksaan bakteriologik (+), tes Lepromin (-).
Tipe BL (borderline Lepromatous): macula infiltrate merah mengkilat, tak teratur, batas tak tegas, pembengkakan saraf, pemeriksaan bakteriologik ditemukan banyak basil, tes Lepromin (-).
Tipe LL (lepromatous): infiltrate difus berupa nodula simetris, permukaan mengkilat, saraf terasa sakit, anastesi. Pemeriksaan bakteriologis positif kuat, tes Lepromin (-) (Sjamsoe, 2007).
Konsep ini dapat digunakan untuk menentukan keadaan imunitas yang stabil dan keadaan imunitas yang labil, dimana pada tipe polar tuberkuloid dan polar lepromatosa merupakan keadaan imunitas yang stabil sedangkan tipe borderline lepromatosa, mide lepromatosa dan bordeline tuberkuloid merupakan keadaan imunitas yang lebih.
3. Klasifikasi WHO
Sejak program eliminasi kusta dilaksanakan secara merata di seluruh dunia oleh WHO dengan memperkenalkan MDT, maka klasifikasi kusta perlu ada standarisasi dengan lebih disederhanakan, oleh karena itu WHO menyepakati untuk membagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu:
Table 1. Klasifikasi kusta berdasarkan WHO
PB
MB
Lesi Kulit
1-5 lesi
Hipopigmentasi/eritema
Distribusi tidak simetris
Hilangnya sensasi yang jelas
> 5 lesi
Distribusi lebih simetris
Hilangnya sensasi kurang jelas
Kerusakan saraf
Hanya satu cabang
Banyak cabang saraf
(Kosasih A, 2005).
2.7 Kusta Reaktif
Reaksi kusta termasuk dalam pembahasan imun patologik, yaitu terjadi gangguan pada cell mediated immunity dan terjadi peningkatan aktivitas makrofag, natural killer cel, peran komplemen juga berpengaruh, sebetulnya reaksi imun itu dapat menguntungkan, tetapi bisa juga merugikan seperti kusta reaktif (Djuanda A, 2007).
Kusta reaktif adalah interupsi dengan episode akut pada perjalanan penyakit yang sebenarnya sangat kronik. Adapun patofisiologiknya belum jelas betul, terminology dan klasifikasinya masih bermacam-macam. Mengenai patofisiologisnya yang belum jelas itu akan diterangkan secara imunologik (Djuanda A, 2007).
Reaksi imun dapat menguntungkan, tetapi dapat pula merugikan yang disebut reaksi imun patologik, dan reaksi kusta ini tergolong di dalamnya dalamnya. Dalam klasifikasi yang bermacam-macam itu, yang tampaknya paling banyak dianut pada akhir-akhir ini, yaitu (Djuanda A, 2007):
Tipe 1 :Reaksi Reversal, ini merupakan contoh imunopatologi reaksi hipersensitivitas tipe IV.
Gejala klinik reversal umumnya terdapat rasa nyeri dan terderness pada saraf, adanya neuritis dan inflamasi yang begitu cepat pada kulit. Keadaan yang dulunya hipopigmentasi menjadi eritema, lesi eritema makin menjadi eritematosa, lesi macula menjadi infiltrate, yang infiltrate makin infiltratif dan lesi lama makin bertambah luas.
Secara histology ditemukan epitheloid dari sel granuloma, dan sel limfosit yang banyak, ditemukannya basil lepra yang banyak, ephiteloid mensekresi TNF.
Tipe 2:Eritema Nodusum Leprosum (ENL), ini merupakan hipersensivitas humoral yaitu peran Ig M Ig G dan komplomen, suatu contoh imunopatologi hipersensitivitas tipe III.
ENL terutama timbul pada tipe lepromatosa polar dan dapat pula pada BL, berarti makin tinggi tingkat multibasilnya makin besar kemungkinan timbulnya ENL. Pada kulit akan timbul gejala klinis yang berupa nodus eritema, dan nyeri dengan tempat predileksi di lengan dan tungkai. Bila mengenai organ lain dapat menimbulkan gejala seperti iridosiklitis, neuritis akut, limfadenitis, arthritis, orkitis, dan nefritis yang akut dengan adanya proteinuria (disertai non pitting oedema). ENL dapat berkembang menjadi perbaikan setelah mendapatkan kontrikosteroid, secara histologi ditemukannya foamy histiocyte, dan limfosit tidak banyak.
Fenomena Lucio: merupakan reaksi kusta bentuk lain, yang sebetulnya merupakan reaksi kusta tipe 2 yang sangat berat. Kusta tipe ini terutama ditemukan di Meksiko dan Amerika Tengah, namun dapat juga dijumpai di negeri lain dengan prevalensi rendah. Gambaran klinis dapat berupa plak atau infiltrate difus, berwarna merah muda, bentuk tak teratur dan terasa nyeri. Lesi terutama di ekstrimitas, kemudian meluas ke seluruh tubuh. Lesi yang berat tampak lebih eritematosa, disertai purpura, dan bula, kemudian dengan cepat terjadi nekrosis serta ulserasi yang nyeri. Lesi lambat menyembuh dan akhirnya terbentuk jaringan parut. Titer kompleks imun yang beredar dan krioglobulin sangat tinggi pada semua penderita.
Reasi kusta reversal muncul umumnya 6 (enam) bulan setelah pengobatan dengan obat anti kusta, sedangkan obat lain seperti progesterone, vitamin A, Mycobacterium leprae yang mati dan hancur menjadi banyak fragmen artinya banyak sekali antigen yang dilepaskan dan bereaksi dengan antibodinya serta mengaktifkan sistem komplemen membentuk kompleks imun (Bryceson & Jopling, 2003). Potassium idide merupakan faktor presipitasi, pada tipe ENL lebih banyak terjadi pada pengobatan tahun kedua.
Kompleks imun terus beredar di dalam sirkulasi darah yang akhirnya dapat bersarang diberbagai organ seperti kulit dan timbul gejala klinis yang berupa nodul, eritema dan nyeri dengan predileksi di lengan dan tungkai. Pada organ mata akan menimbulkan gejala iridosiklitis, pada saraf perifer gejala neuritis akut, pada kelenjar getah bening gejala limfadenitis, pada sendi nefritid yang akut dengan adanya protein urin (Murata, 2003).
Tipe reversal dapat menimbulkan kerusakan jaringan dan destruksi saraf yang bersifat irreversibel, sehingga mengalami ketidakmampuan dalam fungsi organ normal, kondisi diperberat dengan cell mediated immunity gagal menghadapi antigen Mycobacterium leprae (Eric Spierings, 2001).
2.8 Komplikasi
Menurut WHO (1980) batasan istilah dalam cacat akibat kusta adalah (Sofianty, 2009):
Impairment: segala kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi yang bersifat psikologik, fisiologik atau anatomic, misalnya leproma, ginekomastia, madarosis, claw hand, ulkus dan absorbs jari.
Disability: segala keterbatasan atau kekurangmampuan (akibat impairment) untuk melakukan kegiatan dalam batas-batas kehidupan yang normal bagi manusia. Diassability ini merupakan objektivitas impairment, yaitu gangguan pada tingkat individu termasuk ketidakmampuan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya memegang benda atau memakai baju sendiri.
Handicap: kemunduran pada seorang individu (akibat impairment atau diability) yang membatasi atau menghalangi penyelesaian tugas normal yang bergantung pada umur, seks, dan faktor sosial budaya. Handicap ini merupakan efek penyakit kusta yang berdampak sosial, ekonomi, dan budaya.
Deformity: kelainan struktur anatomis
Dehabilitation: keadaan/proses pasien kusta (handicap) kehilangan status sosial secara progresif, terisolasi dari masyarakat, keluarga dan teman-temannya.
Destution: dehabilitasi yang berlanjut dengan isolasi yang menyeluruh dari seluruh masyarakat tanpa makanan atau perlindungan (shelter).
2.9 Pemeriksaaan Penunjang
Adapun pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosa Morbus hansen antara lain:
Pemeriksaan anastesi dengan jarum atau air dingin/air panas
Tes keringat dengan pensil tinta: pada lesi akan hilang, sedangkan pada kulit normal ada bekas tinta (tes Gunawan)
Pemeriksaan histopatologi diperlukan untuk klasifikasi penyakit
Tes lepromin digunakan untuk klasifikasi penyakit
Pemeriksaan bakteriologik untuk menentukan indeks bakteriologik (IB) dan indeks morfologi (IM). Pemeriksaan ini penting untuk menilai hasil pengobatan dan menentukan adanya resistensi pengobatan.
2.10 Diagnosis
Diagnosis penyakit Morbus hansen didasarkan gambaran klinis, bakterioskopis, dan histopatologis. Diantara ketiganya, diagnosis secara klinislah yang terpenting dan paling sederhana. Hasil bakteriologis memerlukan waktu paling sedikit 15-30 menit, sedangkan histopatologik 10-14 hari (Kosasih A, 2005).
Kerokan dengan pisau skalpel dari kulit, selaput lendir hidung bawah atau biopsi dari kuping telinga, dibuat sediaan mikroskopis pada gelas alas dan diwarnai dengan teknis Ziehl Neelsen. Biopsi kulit atau saraf yang menebal memberikan gambaran histologis yang khas (Zulkifli, 2003).
2.11 Diagnosis Banding
Diagnosa banding untuk Morbus Hansen yaitu hipopigmentasi dengan granuloma, sarcoides, leishmaniasis, lupus vulgaris, lymphoma, granuloma annulare (Wolff dkk, 2005)
2.12 Pengobatan
Tujuan utama program pemberantasan kusta adalah menyembuhkan pasien kusta dan mencegah timbulnya cacat serta memutuskan mata rantai penularan dari pasien kusta terutama tipe yang menular kepada orang lain untuk menurunkan insiden penyakit (Pramesemara, 2009).
Regimen pengobatan kusta di Indonesia disesuaikan dengan rekomendasi WHO (1995), yaitu program Multi Drug Therapy (MDT) dengan kombinasi obat medikamentosa utama yang terdiri dari Rifampisin, Klofazimin (Lamprene) dan DDS (Dapson/4,4-diamino-difenil-sulfon) yang telah diterapkan sejak tahun 1981 (Pramesemara, 2009).
Gambar 1. Regimen MDT (Obat Kombinasi) Kusta
Regimen MDT (Obat Kombinasi) yang dianjurkan oleh WHO adalah:
a. Penderita Kusta Pausibasiler (PB)
Dewasa:
Pengobatan bulanan: Hari pertama (dosis yang diminum di depan petugas) 2 kapsul Rifampisin dan 1 tablet Dapsone.
Pengobatan harian: Hari ke 2 sampai hari ke 28 (dibawa pulang) 1 tablet Dapsone. Penderita akan memperoleh obat MDT dari Puskesmas sebanyak 6 Blister untuk diminum selama 6-9 bulan.
Tabel 2. Obat dan dosis regimen MDT-PB
Obat & Dosis MDT-Kusta PB
Dewasa
Anak
BB < 35 Kg
BB > 35 kg
10-14 tahun
Rifampisin (diawasi petugas)
450 mg/bulan
600 mg/bulan
450 mg/bulan
(12-15 mg/kgBB/bulan)
Dapsone (swakelola)
50 mg/hari
(1-2 mg/kgBB/hr)
100 mg/hr
50 mg/hr
(1-2 mg/kgBB/hr)
Pengobatan MDT untuk kusta tipe PB dilakukan dalam 6 dosis minimal yang diselesaikan dalam 6-9 bulan dan setelah selesai minum 6 dosis maka dinyatakan RFT (Released From Treatment = berhenti minum obat kusta meskipun secara klinis lesinya masih aktif). Menurut WHO (1995) tidak lagi dinyatakan RFT teetapi menggunakan istilag Completion of Treatment Cure dan pasien tidak lagi dalam pengawasan.
b. Penderita Kusta Multibasiler (MB)
Dewasa:
Pengobatan bulanan: Hari pertama (dosis yang diminum didepan petugas) 2 kapsul rifampisin, 3 kapsul Lampren (Clofazimine), dan 1 tablet Dapsone.
Pengobatan harian hari ke 2-28: 1 tablet Lampren dan 1 tablet Dapsone diminum setiap hari. Setiap penderita kusta tipe MB akan mendapatkan 12 blister obat MDT dari Puskesmas untuk diminum selama 12 bulan.
Tabel 3. Obat dan Dosis regimen MDT-MB
Obat & Dosis MDT-Kusta MB
Dewasa
Anak
BB < 35 Kg
BB > 35 kg
10-14 tahun
Rifampisin (diawasi petugas)
450 mg/bulan
600 mg/bulan
450 mg/bulan
(12-15 mg/kgBB/bulan)
Klofazimin
300 mb/bulan (diawasi petugas) dan dilanjutkan esok 50 mg/hari (swakelola)
200 mg/bulan (diawasi) dan dilanjutkan esok
50 mg/hari (swakelola)
Dapsone (swakelola)
50 mg/hari
(1-2 mg/kgBB/hr)
100 mg/hr
50 mg/hr
(1-2 mg/kgBB/hr)
Pengobatan MDT untuk kusta tipe MB dilakukan dalam 24 dosis yang diselesaikan dalam waktu maksimal 36 bulan. Sesudah selesai minum 24 dosis maka dinyatakan RFT meskpun klinis lesinya masih aktif dan pemeriksaan bakteri BTA positif. Menurut WHO (1998) pengobatan MB diberikan untuk 12 dosis yang diselesaikan dalam 12-18 bulan dan pasien langsung dinyatakan RFT.
Namun dibalik program MDT, ternyata masih terdapat efek samping yang ditimbulkan MDT yang dilaporkan. Berikut ini tindak lanjut terhadap efek samping MDT yang mungkin terjadi (Rekomendasi UPK Kusta Depkes RI dan WHO, tahun 2000), yaitu sebagai berikut:
Tabel 4. Efek ssamping MDT dan tindak lanjut
Regimen MDT
Efek Samping
Tindak Lanjut
Obat Substitusi
Rifampisin
Urin, tinja, keringat berwarna merah
Obat MDT dapat diteruskan
-
Klofazimin
Warna kulit menjadi hitam (hiperpigmentasi)
Obat MDT dapat diteruskan
Etionamid dan Protionamid
(Tidak dianjurkan, RS hepatotoksik)
Dapsone
Gatal, merah pada kulit. Bila berat kulit kepala dan seluruh tubuh dapat terkelupas
Stop dapsone dan segera rujuk penderita ke RS
-
Setelah minum obat tersebut diatas maka penderita dinyatakan: Release From Treatment (RFT/Sembuh).
Terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan sehingga penderita mendapat penjelasan sebelum diberikan pengobatan MDT, antara lain:
1. Lama pengobatan
2. Cara minum obat
3. Kusta dapat disembuhkan, bila minum obat teratur dan lengkap
4. Bahaya yang terjadi bila minum obat tidak teratur yaitu dapat menularkan kepada keluarga dan orang lain, dan juga dapat menjadi cacat.
5. Bila ada keluhan selama masa pengobatan diminta segera periksa ke Puskesmas.
6. Bila penderita kehilangan rasa raba atau sakit, jelaskan pentingnya perawatan diri untuk mencegah cacat
7. Penderita yang sudah cacat fisik tidak akan kembali normal, tetapi perawatan diri tetap diperlukan supaya cacat tidak berlanjut.
Walaupun saat ini terdapat pengobatan MDT terbaru dengan sistem ROM (Rifampicin-Ofloksasin-Minosiklin) dan pengembangan obat alternatif (Klaritromisin, Eritromisin, Roksitromisin dan sebagainya), tetapi tetap masih dianjurkan regimen MDT-WHO (1995) dengan Rifampisin-Klofazimin-DDS sebagai terapi medikamentosa utama dari penatalaksanaan Kusta di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Djuanda A, Hamzah M, dkk. Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin. Edisi Kelima. Cetakan Kedua. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2007. Hal. 73-88.
Kosasih A, Made Wisnu I, Emmy S.J, Linuwih S. M, Kusta, dalam : Juanda,
Adhi, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, edisi IV, FKUI, Jakarta,2005;73-88.
Harahap, Mawardi (2000), Penyakit Kulit, Hipokrates, Jakarta.
Zulkifli. Penyakit Kusta dan Masalah yang Ditimbulkannya. (Online), 2003. (http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-zulkifli2.pdf, diakses tanggal 29 Maret 2011).
Wolff, K. Johnson, RA. Suurmond, D. Mycobacterial Infection. Fitzpatricks Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology. Fifth Edition. 2005. New York: MCGraw-Hill. Hal 655-661.
Sjamsoe. 2007. Diagnosis dan Pengobatan Penyakit Kusta. Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUI/RSCM. (Online). (http://journal.lib.FKUI.acid.
Sofianty D. Memahami Seluk Beluk Penyakit Kusta. (Online). 2009. (http://www.surabaya-ehealth.org/administrator/berita/memahami-seluk-beluk-penyakit-kusta.
Pramesemara. Penatalaksanaan Kusta di Indonesia. (Online). 2009. (http://pramareola14.wordpress.com/2009/12/09.penatalaksanaan-kusta-di-indonesia/.

![Mh vkj Mh vks · Mh vkj Mh vks J`a[kyk 31 fujh{k.k@nkSjk dk;ZØe 34. Mh vkj Mh vks. lekpkj. vkbZ ,l ,l ,u % 0971 & 4391. gekjs laoknnkrk. vgenuxj % ys¶VhusaV duZy ,- ds- flag] okgu](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f33c7f82671374b9b3f4cc3/mh-vkj-mh-vks-mh-vkj-mh-vks-jakyk-31-fujhkknksjk-dkze-34-mh-vkj-mh-vks.jpg)