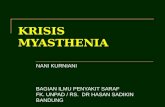KRISIS LAHAN
-
Upload
patty-siska-lumbantoruan -
Category
Documents
-
view
40 -
download
0
description
Transcript of KRISIS LAHAN
UUSISTEMATIKA PENULISANA. Bagian Awal :Halaman Judul, Lembar Pengesahan, Kata Pengantar, Abstraksi, Daftar isi dan Daftar lain yang diperlukan.B. Bagian Inti :I. Pendahuluan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan.II. Telaah Pustaka, berisi tentang uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji, uraian mengenai penelitian dan pemecahan masalah yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. III. Metode Penulisan.IV. Pembahasan, berisi tentang analisis permasalahan yang didasarkan pada data dan atau informasi dari telaah pustaka yang dilakukan untuk menghasilkan model pemecahan masalah dan gagasan yang kreatif.V. Kesimpulan dan Saran.Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan.C. Bagian Akhir :I. Daftar PustakaII. Daftar Riwayat Hidup Penulis dan Pembimbing III. Lampiran (jika diperlukan)PERSYARATAN PENULISAN1. Naskah ditulis minimal 15 halaman dan maksimal 30 halaman. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan jumlah halaman tersebut dapat mengurangi penilaian.2. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan, sederhana, jelas, satu-kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah dimengerti, menggunakan kalimat yang efektif serta tidak menggunakan singkatan seperti tdk, dll , tsb, yg, dgnsbb.PENGETIKAN Tata Letak1. Karya tulis diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran A4 (font 12, Times New Roman Style).2. Batas Pengetikan:a. Samping kiri 4 cm.b. batas atas 4 cm.c. samping kanan dan batas bawah masing -masing 3 cm.
3. Jarak pengetikan dan perinciannya:a. Jarak pengetikan antara Bab dan Sub Bab 3 Spasi, sub-bab dan kalimat dibawahnya 1,5 spasib. Judul Bab ditulis ditengah-tengah dengan huruf besar tanpa digaris bawahic. Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas seperti yang, dari, dan, atau. Pengetikan KalimatAlenia baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 2 spasi. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. Penomoran Halaman1. Bagian awal memakai angka romawi dan diketik sebelah tengah bawah (i, ii dan seterusnya).2. Bagian inti dan akhir ditulis dengan angka arab diketik sebelah tengah bawah (1, 2, 3 dan seterusnya).PENJILIDANUntuk pengumpulan naskah, naskah dijilid dengan jilid lakban dengan kertas cover di bagian belakang (warna bebas) dan kertas cover transparan di bagian depan.PA UNTUK PETANI : TELAAH KRITIS TERHADAP KRISIS LAHAN PERTANIAN DI INDONESIA
Indonesia di masa datang ingin menjadi negara makmur supaya rakyatnya dapat ikut serta pada kebudayaan dunia dan mempertinggi peradaban. Untuk mencapai kemakmuran, politik perekonomian Indonesia mestilah disusun berdasarkan kenyataan sekarang yaitu Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karena tanah merupakan faktor produksi yang utama maka hendaknya peraturan pemilikan tanah memperkuat kedudukan tanah sebagai sumber kemakmuran bagipetani.Pernyataan Soekarno tersebut membangkitkan kesadaran kolektif bangsa ini untuk melaksanakan pembangunan yang bercorak agraris. Harapan tersebut mulai termanifestasi dengan disahkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kehadiran UUPA sekaligus menandai transformasi hukum pertanahan kolonial yang berwatak imperialisme dan feodalisme menjadi hukum pertanahan nasional yang bercorak agraris. Terbentuknya Indonesia sebagai negara agraris ditopang oleh dua faktor utama yaitu wilayah Indonesia yang luas dan subur serta mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.UUPA sebagai politik agraria nasional memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sektor pertanian. Perhatian UUPA terhadap pertanian merupakan hal yang wajar jika dipandang dari faktor sosiologis maupun ekonomis. Dari sisi sosiologis, sektor pertanian merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011, sektor pertanian menyerap 33,51% dari total angkatan kerja nasional atau sejumlah 39,33 juta orang[1]. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 41,49 juta orang. Dari sisi ekonomis, sektor pertanian telah berkontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan menyumbangkan devisa negara yang cukup besar.Substansi UUPA yang sangat ideal dalam melindungi dan memberdayakan sektor pertanian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7, 10 dan 14 ayat (2)[2]ternyata belum terimplementasi dengan baik.Implikasi utama dari hal tersebut adalah penguasaan lahan oleh para petani yang jauh dari ideal. Berdasarkan data BPS tahun 2009, 56,5% atau 39 juta petanihanya menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 ha jauh dari idealnya yaitu 2 ha[3]. Luas lahan yang dikuasai oleh petani bersifat paralel dengan tingkat kesejahteraan petani. Makin sempit lahan yang dikuasai petani maka makin rendah juga tingkat kesejahteraan petani tersebut.Sempitnya penguasaan lahan oleh petani disebabkan oleh perubahan orientasi pembangunan dari pertanian menjadi industri. Perubahan orientasi ini dimulai pada masa orde baru hingga kini. Orientasi pembangunan yang cenderung mengejar pertumbuhan dan bertumpu pada strategi industrialisasi tanpa perencanaan penggunaan tanah yang baik berakibat pada pengalihfungsian tanah-tanah pertanian untuk kegunaan yang lain. Ketimpangan penguasaan tanah ini terlihat dalam dataKonsorsium PembaruanAgraria(KPA) yang menyatakan bahwa 0,2 % penduduk negeri ini menguasai56 % aset nasional yang sebagian besar dalam bentuk tanah[4].Timpangnya penguasaan lahan antara pengusaha dan petani tidak sesuai dengan esensi UUPA. Dalam pasal 7 UUPA dinyatakan bahwa penguasaan tanah yang melampaui batas maksimum tidak diperkenankan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luaspenguaan lahan, batas maksimum penguasaan tanah tersebut adalah 25 ha. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengambil alih penguasaan lahan yang melampaui batas oleh kelompok pengusaha tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 ayat (3) UUPA.Penguasaan lahan oleh hanya sekelompok pengusaha mengakibatkan terjadinya polarisasi kekayaan di Indonesia dan memiskinkan kaum tani. Polarisasi kekayaan dan kemiskinan kaum tani merupakan hal yang membuktikan bahwa tujuan utama UUPA belum tercapai. Tujuan utama UUPA sebagai turunan pasal 33 UUD 1945 adalah untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di sisi lain, ini juga tidak sesuai dengan prinsip tanah untuk tani dalam UUPA. Realitas tersebut menunjukan bahwa UUPA sebagai transformasi sistem pertanahan yang feodal menjadi sistem pertanahan bagi bangsa Indonesia belum terwujud dalam kehidupan petani.Penguasaan tanah yang sangat luas oleh pengusaha berbanding terbalik dengan penguasaan lahan oleh para petani. Petani Indonesia saat ini hanya menguasai lahan seluas 8,9 juta ha[5].Luas lahan pertanian tersebut sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan jumlah petani yang mencapai angka 39 juta orang. Makin sempitnya lahan pertanian ini disebabkan oleh makin maraknya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat bahwa sejak tahun 1992-2002 laju konversi lahan pertanian pertahun adalah 110 ribu ha dan meningkat menjadi 145 ribu ha selama empat tahun terakhir[6]. Konversi lahan pertanian ini sangat tidak sesuai dengan esensi UUPA. UUPA menghendaki usaha-usaha dalam bidang agraria diatur untuk meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamim derajat hidup yang baik bagi setiap WNI[7].Peningkatan konversi lahan pertanian membawa implikasi terhadap berbagai sektor kehidupan berbangsa. Dari sisi ekonomi, hal ini akan menyebabkan bangsa ini kehilangan devisa negara dan tidak mampu menciptakan ketahanan pangan nasional. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor pangan dari negara lain. Suatu hal yang sangat ironis karena Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pertanian yang besar tapi harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dari sisi sosial, hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pertanian merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Hal ini akan menciptakan pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.Pemusatan penguasaan lahan pertanian kepada kelompok tertentu yang berbanding terbalik dengan penguasaan tanah oleh petani jelas bertentangan dengan substansi UUPA. Hal ini disebabkan UUPA telah mengatur mengenai batas minimum kepemilikan lahan untuk satu keluarga petani. Bahkan, batas kepemilikan minimum tanah untuk petani merupakan salah satu asas yang mendasari UUPA[8]. Untuk mengatasi masalah kepemilikan tanah petani ini maka perlu diadakan sebuah reformasi agraria. Dalam kondisi sosiologis petani sekarang ini maka reformasi agrarian tersebut dapat dikaitkan dengan substansi pasal 15 dan pasal 11 ayat 2 UUPA yang menyatakan bahwa pengelolaan tanah harus memperhatikan dan melindungi pihak ekonomi lemah. Dalam konteks ini, petani merupakan pihak ekonomi lemah yang perlu untuk diperdayakan dan diproteksi.Menyadari hal tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mengambil langkah positif untuk merevitalisasi peran petani sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat (2) UUPA. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembentukan lembaga bank tanah untuk pertanian. Bank tanah berfungsi menetapkan zona-zona pertanian yang tidak dapat dikonversi menjadi lahan non pertanian. Bank tanah ini dapat dibentuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Konsekuensi dari bentuk tersebut adalah pemerintah daerah harus berperan dalam pemodalan maupun operasionalisasi bank tanah. Hal ini sesuai dengan isi pasal 14 ayat (2) UUPA.Operasionalisasi bank tanah dapat dilaksanakan melaluipertama,penghimpunan tanah. Tanah-tanah yang dihimpun adalah tanah negara, tanah-tanah terlantar, tanah guntai dan mengkonsolidasi lahan yang telah digunakan untuk kepentingan non pertanian di zona pertanian. Bank tanah dapat menghimpun 12.418.0563 ha tanah terlantar dan didistribusikan kepada petani-petani kecil dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar[9]. Jika rata-rata satu keluarga tani mendapatkan 2 hektar tanah untuk digarap maka terdapat 6.209.028 keluarga petani yang akan mendapatkan sumber penghidupan yang layak. Disamping itu, ketahanan pangan nasional akan tercapai.Kedua, melakukan zonasi. Pengadaan zonasi ini sesuai dengan substansi pasal 14 ayat 1 UUPA. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah harus membuat rencana umum persediaan dan peruntukan tanah. Dalam melakukan zonasi, bank tanah dapat bekerjasama dengan Dinas Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Penentuan zonasi ini dengan menggunakan beberapa indikator yaitu luas lahan, tingkat kesuburan, ketersediaan irigasi dan jumlah petani di daerah tersebut.Ketiga, distribusi lahan pertanian. Dalam proses distribusi, petani-petani kecil dan penggarap harus diutamakan. Hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para petani kecil dan penggarap.Eksistensi bank tanah sebagai implementasi UUPA di bidang pertanian dapat memberikan beberapa keuntungan. Adapun keuntungan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguasaan lahan pertanian yang lebih luas, merevitalisasi sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, mewujudkan ketahanan pangan nasional dan upaya nyata melanjutkan programland reformyang sempat terhenti pada masa orde baru.Revitalisasi peran petani melalui penguasaan lahan pertanian yang ideal merupakan bentuk implementasi UUPA. UUPA merupakan politik agraria nasional yang bertujuan menciptakan kemakmuran rakyat khususnya petani. Implementasi UUPA secara konsekuen dan holistik dalam kondisi sosial ekonomi petani saat ini merupakan sebuah keharusan.Sumber: Afif. 2012. http://afifbodoh.blogspot.com/2012/04/uupa-untuk-petani-telaah-kritis.html. Diakses pada tanggal 22 Maret 2013
Indonesia Mengalami Krisis Lahan untukPangan
Senin,24 September 2012PERTANIANIndonesia Mengalami Krisis Lahan untuk PanganJakarta, Kompas Lahan pangan Indonesia semakin kritis. Ketersediaan lahan pangan sekarang tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Krisis lahan pangan ini bakal semakin akut.
Di tengah ketatnya persaingan pemanfaatan lahan, pemerintah semakin tidak percaya kepada petani. Kebijakan pemerintah semakin memberi peluang masuknya korporasi dalam sistem penyediaan pangan nasional.
Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, Minggu (23/9), di Jakarta, semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memberikan perlindungan akses lahan kepada petani. Kenyataannya semangat itu mulai digerus arus korporasi dan liberalisasi pangan yang mendorong kemiskinan, kelaparan, konflik agraria, dan kriminalisasi terhadap petani.
Dua arus tersebut dengan deras merampas dan menggusur lahan melalui ekspansi dan eksploitasi lahan untuk perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, industri, pertanian pangan skala luas, dan pusat-pusat perdagangan, tutur Henry.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir dalam berbagai kesempatan mengatakan, melihat minimnya lahan baku pertanian pangan, sejatinya Indonesia sudah masuk dalam situasi krisis lahan pangan. Winarno menekankan persoalan lahan pertanian harus ditangani dengan serius.
Mengacu data Badan Pusat Statistik, ketersediaan lahan pangan untuk produksi empat komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, dan gula, tahun 2012 hanya setara dengan luas panen 18,5 juta hektar.
Dengan rincian, luas panen padi 13,44 juta hektar, jagung 3,99 juta hektar, kedelai 600.000 hektar, dan gula 450.000 hektar. Dengan luas panen tersebut, luas lahan baku untuk budidaya keempat komoditas itu tidak lebih dari 10 juta hektar.
Padahal, untuk mencapai swasembada keempat komoditas itu tahun 2014, setidaknya butuh lahan baku 2 juta hektar sampai 2,2 juta hektar. Perinciannya, kedelai dan gula butuh 1 juta hektar sampai 1,2 juta hektar.
Adapun padi dan jagung butuh sekitar 1 juta hektar lahan baru. Perkiraan tambahan lahan itu belum menghitung pertambahan jumlah penduduk yang rata-rata naik 1,4 persen per tahun atau setara dengan 3 juta orang.
Dengan asumsi, lahan pangan yang ada tak menyusut dan produktivitas per hektar sama dengan saat ini. Kalaupun produktivitas dipacu setinggi-tingginya, tetap harus membutuhkan dukungan lahan pangan yang baru.
Prof Anne Booth dari SOAS University of London saat memberikan kuliah internasional di Institut Pertanian Bogor mengatakan, tidak cukup lahan di Indonesia untuk pengembangan pangan. Kalaupun ada, akan sangat sulit dimanfaatkan karena status kepemilikan.
Di sisi lain, konversi lahan pangan terus terjadi. Konversi itu baik sebagai dampak fragmentasi lahan maupun dampak pertumbuhan sektor industri yang mendorong alih fungsi lahan.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan, salah satu solusi untuk meningkatkan produksi pangan adalah dengan penambahan areal tanam. Penambahan areal tanam bisa dilakukan kalau ada tambahan lahan pertanian baru.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, banyaknya konversi lahan juga mesti menjadi pertimbangan dalam menghitung luas panen dan produksi beras nasional. Konversi lahan terus terjadi dan belum bisa dihentikan.
Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan, sudah saatnya masalah ketahanan pangan tak hanya diselesaikan melalui pendekatan produksi, tetapi juga konsumsi.
Kalau pendekatannya terus dari aspek produksi, sampai kapan pun tidak akan mampu mengejar pertumbuhan permintaan. Karena itu, pola konsumsi juga harus diatur, ujarnya.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan mengatakan, pencetakan lahan baru terkendala pada komitmen petani. Sebenarnya, tugas PU hanya hingga jaringan irigasi utama dengan air dari waduk. Namun, buat apa infrastruktur itu tanpa ada niat untuk membuka persawahan baru? ujarnya.
Persoalannya, menurut Hasan, sering kali setelah waduk dibangun dan jaringan irigasi selesai dikerjakan ternyata petani tidak menanam tanaman seperti padiyang membutuhkan banyak air. Di banyak lokasi, malah dibangun perkebunan sawit, ujar dia. (RYO/MAS)
Sumber: Indonesia Companies News. 2012. http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2012/09/24/indonesia-mengalami-krisis-lahan-untuk-pangan/. Diakses pada tanggal 22 Maret 2013
Krisis Lahan Pertanian
Dalam negara agraris, kata Bung Hatta, tanah menjadi alat produksi yang penting. Dengan demikian, baik-buruknya penghidupan rakyat tergantung pada keadaan lahan pertanian.
Namun, dalam beberapa tahun kedepan, Indonesia akan mengalami defisit lahan pertanian seluas 730.000 hektare. Dan menurut Kementerian Pertanian, jika tidak ditangani, defisit lahan itu akan meningkat menjadi 2,21 juta hektare pada 2020. Dan akan terus bertambah menjadi 5,38 juta hektare pada 2030.
Di sisi lain, kebutuhan konsumsi pangan kita, khususnya beras, terus meningkat. Sekarang ini setiap orang Indonesia menghabiskan rata-rata 139 kilogram beras per tahun. Untuk 2013, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 230 juta orang. Artinya, untuk tahun ini saja, Indonesia membutuhkan sedikitnya 31.97 juta ton beras. Dan untuk memproduksi beras sebanyak itu diperlukan 12 juta hektar.
Pada tahun 2015, dengan perkiraan jumlah penduduk 255 juta orang, Indonesia membutuhkan lahan 13,38 juta hektar. Artinya, Indonesia dituntut menambah luas areal pertaniannya. Pada kenyataannya, lahan pertanian di Indonesia justru menyusut.
Menurut Khudori, anggota POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (20102014), dalam rentang waktu 1999-2002, laju tahunan konversi lahan baru 110.000 hektar. Pada periode 2002-2006 melonjak menjadi 145.000 hektar per tahun. Akan tetapi, rentang 2007-2010 di Jawa saja laju konversi rata-rata 200.000 hektar per tahun.
Dia menambahkan, lahan (sawah beririgasi teknis, nonteknis, dan lahan kering) di Jawa pada 2007 masih 4,1 juta hektar, kini hanya tinggal 3,5 juta hektar. Lahan sawah Indonesia hanya 8,06 juta hektar dan tegalan/kebun 12,28 juta hektar. Artinya, dalam beberapa tahun kedepan, Indonesia mengalami krisis lahan pertanian. Sudah begitu, seperti ditemukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), sebanyak 75 persen lahan pertanian di Indonesia sudah kritis karena mengalami penurunan kesuburan.
Kenapa bisa terjadi krisis lahan pertanian? Pertama, banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, jalan tol, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan lain-lain.
Kedua, peruntukan lahan di Indonesia sangat berorientasi profit (keuntungan), seperti untuk perkebunan sawit, pemanfaatan hasil hutan kayu, pertambangan, dan lain-lain. Artinya, penguasaan dan pengolahan tanah itu lebih banyak dikangkangi oleh korporasi. Data menyebutkan, 35% daratan Indonesia dikuasai oleh perusahaan pertambangan. Sangat sedikit lahan itu yang dikonversi untuk kebutuhan lahan pertanian.
Ketiga, terjadi konsenstrasi penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia. Indeks Gini kepemilikan tanah juga meningkat tajam: dari 0,50 (1983) menjadi 0,72 (2003). Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto pernah membeberkan bahwa hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen aset nasional. Dari aset yang dikuasai tersebut, 87 persen dalam bentuk tanah.
Situasi ini akan membawa dampak buruk. Krisis lahan ini akan berdampak pada merosotnya produksi pangan. Indonesia pun tidak akan pernah berdikari di bidang pangan. Sekarang saja kita sudah menjadi importir pangan terbesar di dunia.
Situasi ini membawa rakyat Indonesia dalam situasi rawan: krisis pangan. Kita tahu, harga pangan dunia dikontrol oleh segelintir korporasi dan itupun fluktuatif sesuai permainan di pasar spekulasi. Padahal, mayoritas rakyat Indonesia masih bergantung pada konsumsi beras.
Menurunnya lahan pertanian berarti penciutan jumlah petani. Artinya, penyerapan tenaga kerja merosot. Ini akan memicu apa yang disebut prosesde-peasantization, yaitu fenomena petani atau rumah tangga petani telah kehilangan kapasitas mereka sebagai produsen atau unit ekonomi. Maklum, petani yang kehilangan alat produksi tidak serta-merta akan terserap oleh industri di kota-kota. Maklum, Indonesia juga mengalami proses de-industrialisasi.
Pemerintah harus tegas untuk melaksanakan moratorium konversi lahan pertanian. Jika tidak, penyusutan lahan pertanian tidak akan terkendali. Selain itu, peruntukan dan pengelolaan tanah harus lebih diperuntukkan untuk kepentingan rakyat banyak.
Kita harus kembali ke politik agraria yang benar. Bung Hatta menegaskan, tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas atau memeras kehidupan orang banyak. Konsekuensinya, perusahaan besar swasta tidak boleh diijinkan menguasai tanah terlalu luas.
Selain itu, pemerintah juga harus segera melaksanakan Land-reform. Ini untuk mengatasi dua hal: pertama, mengakhiri ketidakadilan agraria di Indonesia; kedua, mentransformasikan pertanian Indonesia yang masih terbelakang dan subsisten agar terjadi modernisasi pertanian sebagai basis mensejahterakan kaum tani dan keluarganya.
Untuk itu, pemerintah harus segera melaksanakan politik agraria yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dan UU nomor 5 tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Sumber Artikel:http://www.berdikarionline.com/editorial/20130226/krisis-lahan-pertanian.html#ixzz2OF4n4pi0Follow us:@berdikarionline on Twitter|berdikarionlinedotcom on FacebookSalah satu solusinya adalah alih fungsi lahan pertanian segera dihentikan dan sebalik justru pemerintah mencetak lahan-lahan untuk pertanian. Selain itu juga, pemerintah perlu mempraktekkan pertanian terpadu dengan didukung dengan pengembangan teknologi dan peternakan
peran aktif pemerintah dan bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengatur lahan yang ada di tiap kota, mana yang harus dibuka untuk perumahan, pusat perdagangan dan mana yang khusus untuk lahan pangan dan tidak bisa diganggu gugat.