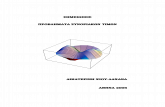dftar.doc
Transcript of dftar.doc
Daftar Pustaka
104
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ardianto, Elvinaro, dkk, 2007. Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung : Simbiosa Rekatama Media.
Effendy, Onong, Uchjana, 2004. Dinamika Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Effendy, Onong, Uchjana, 2003. Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Kusumaningrat, Hikmat, dan Kusumaningrat. Purnama, 2006. Jurnalistik Teori dan Praktek, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyana, Deddy, 2002. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Nazir, Moh, 1983. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia.
Rakhmat, Jalaludin, 2000. Metode Penelitian Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Rakhmat, Jalaludin, 1997. Metode Penelitian, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Rakhmat, Jalaludin, 1998. Metode Penelitian, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Rakhmat, Jalaludin, 2003. Psikologi Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Romli, Asep, Syamsul, 2003. Jurnalistik Praktis, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Sudjana, 1996. Metode Statistik, Bandung : PT. Tarsito.
Sumadiria, Haris, 2005. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature, Bandung : Simbiosa Rekatama Media.
Suprapto, Tommy, 2006. Pengantar Teori Komunikasi, Yogyakarta : Media Pressindo.
Surakhmad, Winarto, 1985. Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik), Bandung: TarsitoEffendi, Onong Uchjana. 2006. Teori dan Praktik Ilmu Komunikasi. Bandung: Resdakarya.
Effendi, Onong Uchjana. 1984. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Fisher, Aubrey, 1990. Teori-teori dan Komunikasi, Remaja Rosdakarya, BandungSumber lain :
1. Ali, Sugiban, 41803803, 2007. Laporan Kerja Praktek Unikom, Bandung.
2. Company Profile, 2007. PT. Mangle Panglipur, Bandung.
3. Lembaga Basa dan Sastra Sunda, 1981. Kamus Umum Basa Sunda, Bandung : Tarate.
4. Majalah Mingguan Bahasa Sunda Mangle Edisi Agustus Desember 2007
5. Poerwadarminta, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Balai Pustaka.
Internet :
1. www.google.com2. www.digilib.unikom.ac.id.
3. www.pikiran-rakyat.com4. www.dewey-petra.ac.id5. www.wikipedia.orgPertanian adalah salah satu sektor dimana didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan,bahan baku industri dan sumber energi. Bagian terbesar penduduk dunia adalah bermata pencaharian dalam bidang bidang pertanian dan pertanian juga mencakup berbagai bidang,tetapi pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia.
Amerika Serikat pada awal 1900-an 40 persen masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, namun pada 1940-an jumlahnya menurun hingga 2,5 persen dan saat ini tinggal dua persen.Begitupula di Perancis lanjut Pengamat Pasar Modal tersebut, angkatan kerja di sektor pertanian hanya dua persen.
SejarahIndonesiasejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan dataBPStahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.
Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.
Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.
Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya. Inti dari ilmu-ilmu pertanian adalahbiologidanekonomi. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, sepertiilmu tanah,meteorologi,permesinan pertanian,biokimia, danstatistika, juga dipelajari dalam pertanian.
Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (intensive farming). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.
Peranan Sektor PertanianSektor pertanian mengkontribusikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk yaitu:
a.Kontribusi Produk, Penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri: tekstil, barang dari kulit, makanan dan minuman.
b.Kontribusi Pasar, Pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi.
c. Kontribusi Faktor Produksi, Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain.
d. Kontribusi Devisa, Pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.
Kontribusi Produk.Dalam sistem ekonomi terbuka, besar kontribusi produk sektor pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dengan sektor non pertanian.
Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestic didominasi oleh produk pertanian dari luar negeri seperti buah, beras & sayuran hingga daging.
Dari sisi keterkaitan produksi, Industri kelapa sawit & rotan mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri, karena bahan baku dijual ke luar negeri dengan harga yg lebih mahal.
Kontribusi Pasar.Negara agraris merupakan sumber bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian seperti pengeluaran petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dll) dan produk konsumsi (pakaian, mebel, dll).
Keberhasilan kontribusi pasar dari sektor pertanian ke sektor non pertanian tergantung:
Pengaruh keterbukaan ekonomi, Membuat pasar sektor non pertanian tidak hanya disi dengan produk domestic, tapi juga impor sebagai pesaing, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani tidak menjamin pertumbuhan yang tinggi sektor non pertanian.
Jenis teknologi sector pertanian, Semakin modern, maka semakin tinggi demand produk industri non pertanian.
Kontribusi Faktor Produksi.Faktor produksi yang dapat dialihkan dari sektor pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanian tenaga kerja dan modal.
Di Indonesia hubungan investasi pertanian dan non pertanian harus ditingkatkan agar ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untuk merealisasi hal tersebut:
Harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke luar sektornya. Market surplus ini harus tetap dijaga dan hal ini juga tergantung kepada faktor penawaran Teknologi, infrastruktur dan SDM dan faktor permintaan nilai tukar produk pertanian dan non pertanian baik di pasar domestic dan luar negeri.
Petani harus net savers Pengeluaran konsumsi oleh petani < produksi.
Tabungan petani > investasi sektor pertanian.
Kontribusi Devisa.Kontribusinya melalui :
* Secara langsung ekspor produk pertanian dan mengurangi impor.
*Secara tidak langsung peningkatan ekspor & pengurangan impor produk berbasis pertanian seperti tekstil, makanan dan minuman, dll.
Kontradiksi kontribusi produk dan kontribusi devias peningkatan ekspor produk pertanian
menyebabkan suplai dalam negari kurang dan disuplai dari produk impor. Peningkatan ekspor produk pertanian berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri. Untuk menghindari trade off ini dua hal yg harus dilakukan:
*Peningkatan kapasitas produksi.
*Peningkatan daya saing produk produk pertanian.
Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Stabilitas NasionalSektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling tahan terhadap fluktuasi ekonomi internasional. Pasca krisis ekonomi 1997, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil banyak berpengaruh pada siklus ekonomi. Saat investasi, manufaktur, dan indikator runtuh, ternyata pertanian tetap bertahan karena kebutuhan dan keberadaannya menjadi pokok utama ekonomi rakyat.
Pengaruh sektor pertanian dan perkebunan sangat erat dengan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, implikasi serius dari naiknya harga beras bukan hanya pada persoalan mikro. Harga beras yang melonjak akan memicu inflasi. Bulan November 2006, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya ekonomi Indonesia tidak lagioverheated, karena inflasi bisa diredam sampai satu digit. Menjaga keseimbangan harga dan stok harus diperhatikan. Jika inflasi naik lagi maka itu merupakan pertanda bahwa stabilitas nasional akan terganggu.
Faktor eksternal yang bisa membuat sektor pertanian hancur, misalnya serbuan impor dan penyelundupan. Faktor tersebut harus diperketat karena negara sangat dirugikan dengan penyelundupan komoditas seperti gandum, kedelai, jagung, beras yang diperkirakan mencapai jutaan ton per tahun.
Di sektor perkebunan pernah terjadi hambatan dalam ekspor minyak kelapa sawit ke India karena adanya ketentuan beta karoten yang diberlakukan pemerintah India sejak Agustus 2003. Hal ini dikarenakan 90% minyak kelapa sawit Indonesia tidak memenuhi kadar beta karoten 500-2500mg/kg yang ditentukan India. Permasalahan pada pertanian dan perkebunan hendaknya menjadi koreksi untuk masa depan perekonomian Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi perekonomian bangsa, karena pertanian dan perkebunan merupakan sektor utama dalam perekonomian.
Pertanian dan Membangun PerekonomianIndonesia secara ekonomi masih sangat relevan jika bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan kini banyak dilirik perusahaan-perusahaan karena menjanjikan. Perusahaan-perusahan besar dan telah sukses dengan berbasis pertanian bermunculan di dunia, misalnya Pioneer Hybrid, Monsanto, Unilever, Pizza Hut, dan sebagainya.
Apabila kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian, maka tidak perlu impor karena di dalam negeri sudah terpenuhi. Peningkatan peran kelembagaan juga sangat diperlukan untuk mencapai kejayaan agribisnis. Pada tahun 2005, pertanian menyumbangkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 13,41%. Sedangkan total tenaga kerja yang diserap melalui pertanian sekitar 46,7 juta jiwa.
Produk perkebunan seperti gula dan minyak goreng mempunyai peran penting dalam memelihara ketahanan pangan, karena ketahanan pangan merupakan syarat penting bagi ketahanan nasional. Penyediaan lapangan kerja pada sektor perkebunan mempunyai kontribusi yang signifikan. Sektor perkebunan mempunyai wilayah strategis dalam pengembangan wilayah di pedesaan, marginal, dan terpencil. Hingga tahun 2003, tenaga kerja yang terserap mencapai sekitar 17 juta jiwa.
Selama periode 2000-2003, laju pertumbuhan sektor perkebunan selalu diatas laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Misalnya pada tahun 2001, laju pertumbuhan ekonomi secara nasional sekitar 3,4% dan sektor perkebunan tumbuh dengan laju sekitar 5,6%. Dapat diketahui bahwa perkebunan dapat menjadi andalan dalam perekonomian bangsa kita. Selain itu, sektor ini mempunyai nilai penting dalam penciptaan nilai tambah pada PDB. PDB perkebunan terus meningkat dari sekitar Rp 33,7 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar Rp 47,0 triliun pada tahun 2003, atau meningkat dengan laju sekitar 11,7% per tahun. Dari ekspornya, sektor perkebunan turut menyumbang devisa. Lebih dari 50% dari total produksi adalah untuk ekspor.
Dengan faktor ekonomi diatas pembangunan bisa berfokus pada pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam di Indonesia. Keberpihakan pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung sektor ini. Penyediaan insentif dari pemerintah bagi dunia usaha dibutuhkan untuk menghidupkan produsen dan pasar domestik.
Dalam Munas Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) tahun 2003 disimpulkan bahwa sektor pertanian harus mengalami rekonstruksi dan restrukturisasi. Pertanian harus menjadi jantung bagi pembangunan nasional.
KesimpulanPertanian adalah salah satu sektor yang berperan dalam perekonomian suatu negara. Terutama untuk negara-negara agraris yang mana penduduknya sebagian besar adalah petani. Namun banyak masalah yang membuat pertanian suatu negara sulit untuk maju baik faktor teknik maupun sektor non-teknik. Maka dari itu perlu peran serta pemerintah dalam dunia pertanian untuk menanggulangi masalah- msalah yang terjadi dan untuk meningkatkan hasil pertanian Indonesia agar dapat memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian Indonesia.
Sumberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pertanianhttp://metrotvnews.com/read/analisdetail/2010/06/09/23/Sektor-Pertanian-dan-Struktur-Perekonomian-Indonesiahttp://organisasi.org/definisi-pengertian-pertanian-bentuk-hasil-pertanian-petani-ilmu-geografihttp://www.deptan.go.id/index1.phphttp://ayienice.wordpress.com/2010/04/07/menjaga-hidup-ekonomi-bangsa-melalui-sektor-pertanian-dan-perkebunan/retno.staff.gunadarma.ac.id//SEKTOR+PERTANIAN+DAN+INDUSTRI.ppt
https://sidikaurora.wordpress.com/2011/03/24/sektor-pertanian/Pembahasan di mulai
PENDAHULUAN
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.
Pertanian mempunyai banyak fungsi. Antara lain adalah fungsi ketahanan pangan. Dalam ketahanan pangan, hal hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah, kualitas pangan, kesehatan pangan, ketersediaan pangan dalam jangka panjang, dan juga keanekaragaman jenis pangan. Karena arah ketahan pangan yang salah, membuat keanekaragaman pangan berkurang, dan mulai bergantung pada beras. Padahal tidak semua tempat cocok untuk menanam padi. Itu membuat dibeberapa tempat mengalami kelaparan. Karena mereka tergantung pada beras. Padahal pada zaman dulu, keaneka ragaman pangan yang banyak membuat mereka bisa bertahan. Sebagai contoh, di Irian Jaya makanan pokok mereka adalah sagu, karena disana sagu dapat dengan mudah ditemukan. Tapi sekarang, sagu mulai ditinggalkan, dan mereka mulai beralih pada beras. Itu menjadi salah saatu penyebab kelaparan disana.
Negara indonesia merupakan negara agraris, yang berarti sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sekitar 46% penduduk Indinesia bekerja di sektor pertanian, akan tetapi hasil pertanian kita masih kalah dibandingkan dengan negara India dan Malaisia. Padahal sumber daya alam kita jauh lebih banyak dibanding 2 negara tetangga tersebut.
Padahal Indonesia mempunyai banyak keunggulan dbandingkan negara lain. Keunggulan tersebut antara lain :
1. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan iklim kepulauan yang sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya tanaman.
2. Indonesia terletak di luar zona angin topan yang dapat merusak tanaman.
3. Suhu di negara indonesia yang cocok untuk pertumbuhan maksimal.
4. Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Dan keanekaragaman hayati darat terbanyak kedua di dunia.
5. Intensitas sinar matahari sagat tinggi
POKOK BAHASAN
Ketahan pangan merupakan hal paling utama dari pentingnya pertanian. Hal makanan yang menjadi prioritas seseorang pertama kali dalam hidup dan juga bila dilihat dari sisi pemerintahan. Dengan demikian, pertanian dianggap sebagai dasar stabilitas politik dan sosial dari sebuah bangsa sejak dahulu kala.
Selain itu, sektor pertanian memainkan peran penting dalam bidang penyediaan lapangan pekerjaan dalam skala besar untuk rakyat. Besar dan sedang mempekerjakan pekerja peternakan besar untuk melakukan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan dan perawatan dari peternakan hewan. Sebagian besar negara di dunia, sektor pertanian masih tetap merupakan sektor terbesar yang bertanggung jawab untuk membuka lapangan pekerjaan.
Pertanian juga penting dari sudut pandang appraising standar pembangunan suatu negara, berdasarkan kompetensi para petani. Buruk para petani tidak dapat menerapkan metode yang maju dan teknologi baru. Yang menonjol dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan pertanian cukup jelas dari kata-kata Deng Xiaoping
Pengembangan pertanian tergantung pada kebijakan pertama dan kedua tentang sains. Tidak ada batas untuk setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun untuk peran yang mereka dapat bermain di bidang pertanian pertumbuhan .
Walaupun pertanian sering memainkan peran yang bekerja di Produk Domestik Bruto PDB dari banyak negara, meskipun demikian ia memerlukan dorongan substansial dari baik lokal maupun masyarakat internasional.
Pertanian secara tradisional berdasarkan produksi massal. Pemanenan dilakukan satu kali dalam satu musim, sebagian besar kali dan stocked dan digunakan nanti. Bahkan, beberapa pemikir berpendapat bahwa orang-orang mulai mengadopsi batch processing dan kaos di industri manufaktur, sebagai akibat dari praktek pertanian berpikir. Sebelum industrialisasi, rakyat dengan saham terbesar dari makanan dan perlengkapan lainnya yang dianggap lebih stabil, dan mereka mampu untuk menghadapi tantangan alam tanpa harus kelaparan.
Jadi penting adalah peran pertanian yang baru konsep tetap cropping up untuk memberikan aktivitas tradisional modern berbelok. Salah satu konsep baru di dunia ocehan adalah tentang hari-hari ini adalah pentingnya pertanian organik. Ada bukti bahwa, terlepas dari berbagai manfaat lainnya, peternakan organik yang lebih berkelanjutan dan lingkungan suara, pertanian memberikan dimensi baru.
Pentingnya praktek pertanian yang lebih lanjut dibuat bila makanan organik mulai sebagai gerakan kecil dekade yang lalu, dengan petani dan gardeners menolak penggunaan konvensional non-organik praktek. Dengan perkembangan pasar makanan organik sekarang outpacing banyak industri makanan, banyak perusahaan besar telah ventured ke dalamnya. Dengan munculnya perusahaan multi-nasional, dan dengan pembuatan kerangka hukum sertifikasi seperti Tanah Association, ada keraguan bahwa setiap yang dimaksud dengan makanan organik akan berubah, sehingga lebih dari kegiatan komersial dibandingkan sebelumnya.
Bahkan, pertanian modern telah mengalami perubahan dari laut purba kali. Saat ini, pertanian pentingnya terletak pada kenyataan bahwa ia adalah baik untuk dipraktekkan subsisten serta alasan komersial.
Selain dibidang pangan, pertanian juga berperan penting disektor ekonomi.Selama periode sepuluh tahun terakhir kontribusi pertanian terhadap pendapatan nasional atau PDB Indonesia mengalami penurunan dari sekitar 50% pada tahun 60-an menjadi 20,2% pada tahun 1997. Pada tahun 1998 kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan PDB secara absolute masih menurun, walaupun sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan (0,26%), diantara perpaduan seluruh sektor ekonomi yang mencapai minus 14%.(data kontribusi pertanian-PDB)
Sebelum krisis ekonomi berlangsung, pertumbuhan sektor pertanian secara umum juga tidak secerah sektor-sektor perekonomian lainnya, yaitu tidak lebih dari 3% pertahun selama pelita V khususnya, sangat jauh jika dibandingkan dengan sektor industri yang mengalami pertumbuhan sampai 2 digit. Pada tahun 1996, pertumbuhan sector pertanian juga masih berkisar 3% pertahun, sedangkan pada tahun 1997 sektor pertanian juga masih belum mengalami lonjakan pertumbuhan yang berarti atau tumbuh tidak sampai mencapai 3% (Arifin, 2001).
Teori ekonomi pembangunan modern umumnya sepakat bahwa semakin berkembang suatu Negara, maka akan semakin kecil kontribusi sektor pertanian atau sektor tradisional dalam PDB. Jika pendapatan meningkat, maka proporsi pengeluaran terhadap bahan makanan akan semakin menurun. Dalam istilah ekonomi, elastisitas permintaan terhadap makanan semakin kecil dari satu atau tidak elastis (inelastic). Karena fungsi sektor pertanian yang paling penting adalah untuk menyediakan bahan-bahan makanan, maka peningkatan terhadap bahan makanan tidaklah sebesar permintaan terhadap barang-barang hasil industridan jasa. Dengan sendirinya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB akan semakin kecil dengan semakin besarnya tingkat pendapatan pada sektor non-pertanian. Secara sederhana dapat dituliskan dalam bentuk persamaan:
Keterangan:
P = Net produk nasional
Pa = Net produk Pertanian
Pna = Net produk non-pertanian
Sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam PDB khususnya dan gairah perekonomian pada umumnya, pemerintah harus mampu menciptakan integrasi kebijakan industrialisasi nasional yang berbasis pada pertanian. Kebijakan yang lebih memilih berpihak pada sector industri dengan mengabaikan integrasi antara industri dan pertanian harus diubah. Pengambil kebijakan selama ini menganggap bahwa pembangunan adalah identik dengan pertumbuhan ekonomi sehingga kebijakan yang diambil juga, menurut Lypton dalam Momose (2001), adalah bias perkotaan yang dicirikan: 1) memprioritaskan industri daripada pertanian, 2) pengalokasian sumber daya yang lebih besar ke masyarakat kota daripada masyarakat desa, 3) memprioritaskan industri daripada pertanian.
Sebagai Negara agraris seharusnya sektor pertanian diprioritaskan lebih dulu, jika industrialisasi akan dilakukan. Keberhasilan sector industri tergantung dari suatu pembangunan pertanian yang dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi. Menurut rahardjo (1990) ada dua alasan mengapa sektor pertanian harus dibangun terlebih dahulu:
1. Barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, maka pendapatan mereka perlu ditingkatkan melalui pembangunan pertanian.
2. Industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian dan karena itu produksi hasil pertanian menjadi basis bagi pertumbuhan industri itu sendiri.
Alasan kedua diatas dapat memberikan petunjuk bahwa industri yang cocok untuk Negara agraris adalah industri yang berbasis pada pertanian atau agroindustri. Masing-masing industri harus mempunyai keterkaitan antara hulu sampai ke hilir.
Kenyataan sekarang ini dari ketiga subsistem yang ada hulu (penyedia sarana produksi, onfarm/ (usahatani), dan hilir (pengolah hasil)- dalam semua subsektor komoditi berjalan tersekat-sekat. Maing-masing berjalan sendiri-sendiri dan memikirkan keuntungan sendiri. Sebagai pihak yang lemah petani sering menjadi objek eksploitasi dari subsistem hulu dan hilir.
Contoh kasus, produk pertanian sering ditolak atau dihargai murah oleh industri pengolahan hasil pertanian dengan alasan kandungan pestisida yang tinggi atau alasan lain semisal tidak terpenuhinya kualitas. Pada kasus pestisida sebenarnya sektor hulu juga berperan dalam mendorong petani menggunakan pestisida, bagaimana mereka mempromosikan produknya untuk digunakan dalam pemberantasan hama penyakit tanaman.
Pertanian juga menyumbang sangat besar terhadap perolehan devisa negara. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam PJP II adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju dengan system distribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badan usaha koperasi, negara, dan swasta serta pendayagunaan sumber daya alam yang optimal yang kesemuanya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju, produktif, dan profesional, iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam PJP II pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan industri dan pertanian serta sektor produktif lainnya ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sektor pertanian terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, dan mampu melanjutkan proses industrialisasi, serta makin terkait dan terpadu dengan sektor industri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif.
Selanjutnya, mengenai Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI), GBHN1993 menggariskan bahwa pertanian dalam arti yang luas perlu terus dikembangkan agar makin maju dan efisien, dan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian, melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dengan memanfaatkan iptek, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta kebutuhan bahan baku industri.
GBHN 1993 juga mengamanatkan bahwa industri pertanian dan industri lain yang terkait terus didorong perkembangannya sehingga makin mampu memanfaatkan peluang pasar dalam dan luar negeri, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup petani dan masyarakat pada umumnya.
Pembangunan pertanian dalam PJP II dan Repelita VI disusun dan diselenggarakan dengan berlandaskan pada arahan GBHN 1993 seperti tersebut di atas. Dalam bab ini akan dibahas pembangunan sektor pertanian dalam PJP II dan Repelita VI, sedangkan mengenai pembangunan pangan, irigasi, dan kehutanan dibahas dalam bab-bab tersendiri.
Sebelum PJP I dimulai, sebagian besar penduduk yang umumnya berada di perdesaan, hidup di bawah garis kemiskinan, baik dalam arti tingkat pendapatan maupun dalam arti keadaan gizi. Produksi pertanian mengalami hambatan dan tingkat inflasi serta pengangguran sangat tinggi. Jumlah devisa yang dimiliki sangat terbatas sehingga kemampuan untuk mengimpor barangbarang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri juga sangat terbatas. Dalam keadaan semacam itu, per-baikan taraf hidup hanya mungkin dicapai jika pembangunan sektor pertanian dapat digerakkan.
Dalam PJP I prioritas pembangunan bidang ekonomi adalah pada sektor pertanian dan telah banyak menghasilkan kemajuan. Dalam pembangunan bidang ekonomi, peranan pembangunan pertanian sangat besar, yang tercermin antara lain dengan telah meningkatnya produksi pangan dan kesejahteraan petani. Pembangunan sektor pertanian telah mewujudkan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Perekonomian menjadi relatif stabil dan strukturnya makin berimbang.
Sektor pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata 3,6 persen per tahun. Pembangunan pertanian telah pula memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan sehingga rakyat telah makin menikmati hasilnya serta lebih aktif terlibat dalam upaya pembangunan. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini meningkat dari 24,9 juta orang pada tahun 1969 menjadi 36,5 juta orang pada tahun 1993. Jumlah keluarga yang bekerja di sektor pertanian meningkat dari 12,2 juta keluarga pada tahun 1963 (Sensus Pertanian 1963) menjadi 19,5 juta keluarga pada tahun 1983 (Sensus Pertanian 1983), serta 21,5 juta keluarga pada tahun 1993 dengan pemilikan rata-rata lahan 0,83 hektare per rumah tangga pertanian (Sensus Pertanian 1993).
Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja dan penyediaan pangan nasional. Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam memperkuat keterkaitan antarindustri, konsumsi dan investasi.
Hasil pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, pada tahun 2004 telah menghasilkan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,1 persen dan 3,8 persen pada tahun 2005. Kemampuan sektor pertanian untuk menyerap tenaga kerja sebesar 40,6 juta dan 40,7 juta pada periode yang sama dan kontribusi terhadap PDB sebesar 15,4 persen di tahun 2004 dan 15,3 persen di tahun 2005. Khusus untuk subsektor perikanan, pada tahun 2003, memberikan kontribusi sebesar 2,5 persen dari PDB nasional, belum termasuk pengolahan produk perikanannya. Dalam tahun 2004 dan 2005 diperkirakan kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional naik masing-masing menjadi 2,7 persen dan 2,8 persen.
Sumbanganterbesar pembangunan pertanian selama PJP I adalah tercapainya swasembada pangan, khususnya beras dalam tahun. Dari hal tersebut Indonesia mampu mengekspor beras ke beberapa negara miskin sehingga dapat menambah devisa. Dampak nyata dari swasembada pangan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, kualitas gizi, serta penghematan devisa negara. Selain itu, swasembada pangan juga telah meningkatkan kestabilan ekonomi nasional.
Sumbangan sektor pertanian terhadap pembangunan dan devisa negara ditentukan oleh produktivitas dari sektor ini. Karena masih cukup besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, rendahnya produktivitas sektor pertanian dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, rendahnya produktivitas di sektor pertanian akan memperdalam kesenjangan. Keadaan itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Rendahnya produktivitas sektor pertanian, selain disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor ini, juga disebabkan oleh masih besarnya proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Sekitar 49 persen dari angkatan kerja bekerja di sektor pertanian. Padahal, pangsa produk domestik bruto pertanian dalam produk domestik bruto nasional hanyalah sekitar 22 persen pada tahun 1990. Apabila kondisi tersebut berlanjut, produktivitas sektor pertanian akan terus menurun. Demikian pula, kesenjangan produktivitas antara sektor pertanian dengan sektor lain terutama industri makin melebar. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah kemampuan sektor nonpertanian untuk menyerap tenaga kerja di perdesaan masih terbatas. Dalam pada itu, kualitas tenaga kerja yang tersedia juga belum dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat bekerja di sektor industri. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga tercapainya pertumbuhan sektor pertanian agar dapat memberikan sumbangan bagi devisa negara, tantangan pembangunan pertanian selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja di samping memperluas kesempatan kerja di sektor pertanian.
Selama ini sektor pertanian merupakan penghasil devisa nonmigas yang penting. Penerimaan devisa tersebut sebagian besar diperoleh dari ekspor komoditas tradisional seperti karet, kopi, teh, dan komoditas perkebunan lainnya, sedangkan ekspor komoditas pertanian lain seperti produk perikanan dan peternakan baru mencapai tahap perkembangan awal. Terbukanya perekonomian nasional ke dalam situasi perdagangan internasional dengan persaingan yang makin ketat, disertai oleh perubahan yang makin cepat, merupakan permasalahan yang perlu diamati secara seksama. Dalam memasuki pasar dunia permasalahannya terletak pada kemampuan meningkatkan daya saing atau keunggulan bersaing. Mengingat peningkatan daya saing di pasar internasional merupakan faktor utama untuk dapat meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor, tantangan dalam meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor hasil pertanian adalah meningkatkan daya saing komoditas ekspor yang dimiliki Indonesia. Hal itu berarti meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil pertanian Indonesia
KESIMPULAN
Indonesia merupakan negara yang berbasis petanian. Pertanian merupakan sektor yang menjadi tulang punggung dalam pembangunan dan perbaikan perekonomian Indonesia.
Ketahanan pangan merupakan salah satu yang terpenting dari pertanian. Dengan adanya ketahanan pangan, maka rakyat akan terbebas dari kelaparan. Dalam ketahanan pangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, kuantitas, kualitas, gizi, keberagaman, keberlangsungan dalam jangka panjang.
Selain ketahanan pangan, pertanian juga berperan penting dalam penyedia lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Sekitar 46% rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Setiap tahun terjadi perbaikan pendapatan rakyat dari pedesaan yang sebagian besar bekerja menjadi petani. Selain membagun perekonomian Idonesia melalui penyediaan lapangan pekerjaan, pertanian juga menyumbang sangat banyak untuk devisa negara.
Diposkan olehSyarwan Firmansyahdi06.22CATEGORIES:ADMISI IPB,INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB),LOMBA IPB,PENGETAHUAN,PERTANIAN,PERTANIAN - IPB,PERTANIAN - IPB. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan pedesaan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi lokal pedesaan menjadi faktor utama pengembangan pertanian. Saat ini disadari bahwa pembangunan pertanian tidak saja bertumpu di desa tetapi juga diperlukan integrasi dengan kawasan dan dukungan sarana serta prasarana yang tidak saja berada di pedesaan (baca : kota). Struktur perekonomian wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah dari segi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan kelembagaan.
Berangkat dari kondisi tersebut perlu disusun sebuah kerangka dasar pembangunan pertanian yang kokoh dan tangguh, artinya pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet, dan mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga, serta teknologi sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian harus berdasarkan asas keberlanjutan yakni, mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi (Wibowo, 2004).
Konsep pertanian yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan perencanaan wilayah yang berbasiskan sumberdaya alam yang ada di suatu wilayah tertentu. Konsep perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan nasional karena perencanaan merupakan suatu proses persiapan secara sistematis dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan yang mencakup siapa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efesien.
Perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.
Pertanian sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah dan perekonomian dengan, pertanian harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Peranan pertanian/agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secaraberkelanjutan.Halini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terutama pada masa kirisis ekonomi yang dialami Indonesia, satu-satunya sektor yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 hanyalah sektor agribisnis, dimana agribisnis memiliki pertumbuhan yang positif.
Dalam jangka panjang, pengembangan lapangan usaha pertanian difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, seperti pengembangan agroindustri. Salah satu lapangan usaha pertanian yang berorientasi ekspor dan mampu memberikan nilai tambah adalah sektor perekebunan. Nilai PDB sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Jika diperhatikan dengan baik, peranan sektor pertanian masih dapat ditingkatkan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Indonesia. Secara empirik, keunggulan dan peranan pertanian/agribisnis tersebut cukup jelas, yang pertama dilihat hdala peranan penting agribisnis (dalam bentuk sumbangan atau pangsa realtif terhadap nilai tambah industri non-migas dan ekspor non-migas), yang cukup tinggi.
Penting pula diperhatikan bahwa pangsa impor agribisnis relatif rendah, yang mana ini berarti bahwa agribisnis dari sisi ekonomi dan neraca ekonomi kurang membebani neraca perdagangan dan pembayaran luar negeri. Sehingga dengan demikian sektor agribisnis merupakan sumber cadangan devisa bagi negara. Diharapkan sektor pertanian mampu menjadi sumber pertumbuhan perekonomian status bangsa, terutama negara-negara berkembang yang perekonomiannya masih 60persen bertumpu pada sektor pertanian.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumberdaya alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan daratan yang cukup luas yang tersusun rapi oleh ribuan pulau yang ada seolah menetapkan bahwa negara kita adalah negara agraris. Memang tak dapat dipungkiri, namun hal tersebut lah yang menjadi sumber mata pencaharian dari sekitar 60 % rakyatnya yang kemudian menjadi salah satu sektor rill yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara.
tambahan :
1. Dapat menyerap banyak tenaga kerja
Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional tersebut diindikasikan juga dengan besarnya penyerapan tenaga kerja. Indikasi ini didukung kenyataan bahwa sektor pertanian masih bersifat padat karya (labor intensive) dibandingkan padat modal (capital intensive). Data BPS menunjukkan bahwa kemampuan sektor pertanian menyerap tenaga kerja mengalami peningkatan dari 43,3 persen pada tahun 2004 menjadi 44,0 persen pada tahun 2005. Bahkan data BPS Februari 2006 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 44,5 persen.2. Memenuhi ketahanan pangan.
Pada umumnya masyarakat Indonesia yang dijadikan bahan pangan adalah padi (beras), sementara saat ini produksi padi petani di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia belum mencukupi. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand guna memenuhi stok beras dalam negeri yang aman. Menurut pemerintah untuk memenuhi stok beras yang aman guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun harus tersedia stok beras 1,5 juta ton. Sementara kini stok beras yang ada hanya sebesar 963.000 juta ton, sehingga pemerintah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 600.000 ton.
Pada tahun 2010 produksi padi dalam negeri diperkirakan mencapai 64,9 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 36,5 juta ton beras naik sebesar 0,88 persen dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 64,3 juta ton GKG. Sementara untuk kebutuhan dalam negeri untuk satu tahun diperkirakan 35,3 juta ton beras. Kecilnya kenaikan hasil produksi padi pada tahun 2010 di karenakan perubahan iklim yang ekstrim seperti terjadi banjir, angin besar yang membuat tanaman padi menjadi roboh dan mati serta adanya hama penyakit
3. Merupakan kebutuhan pokok manusia
Sektor pertanian merupakan sumber kehidu pan manusia dan juga sektor yang menjanjikan bagi perekonomian Indonesia. Pertanian salah satu pilar bagi kehidupan bangsa. Bertani adalah pekerjaan yang mulia, selain untuk kehidupannya sendiri, juga penting bagi kelestarian alam dan makluk hidup lainnya.4. Di dukung oleh alam di Indonesia
Dengan kegiatan di sektor pertanian,, masyarakat memperoleh pangan yang merupakan kebutuhan pokok untuk keberlanjutan hidup dan kehidupannya. Manusia tidak dapat hidup dengan baik tanpa makan yang berkecukupan baik jumlah dan mutunya. Oleh karena itu kemampuan negara atau daerah untuk menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya melalui kemandirian pangan adalah kewajiban.Satu hal yang paling penting disini adalah, program pertanian ini sudah ada dan terbina sejak puluhan tahun yang lalu. Tinggal meneruskan dan merawat yang sudah ada, program pertanian juga sangat minim KKN, mudah terdeteksi jika terjadi korupsi ( banyak yang bisa menghitung kebutuhan dananya) mungkin inilah alasan utama, program2 pertanian di tinggalkan ( disisihkan) dari program2 pemerintah.
Kendala-kendala apa saja ?
Seiring dengan usaha-usaha pembangunan pertanian, muncul masalah-masalah baru yang kemudian memperlambat laju perkembangan pertanian di Indonesia. Mulai dari kerusakan alam yang diakibatkan oleh pelaku produksi dan konsumen pertanian sampai minimnya pendidikan petani. Hal ini disebabkan adanya pola hidup yang berubah dari petani itu sendiri, minimnya pengetahuan akan pemanfaatan dan pengembangan pertanian modern, politik pertanian serta pudarnya nilai-nilai budaya dan spirit yang dimiliki oleh pelaku pertanian. Belum lagi masalah adanya pertentangan antara pertanian modern dengan pertanian berkelanjutan yang semestinya dapat dikombinasikan dalam sistem pertanian terpadu, kepemilikan hak paten atas produk pertanian asli Indoneia yang tak dimiliki lagi oleh bangsa kita dan segelintir masalah-masalah lainnya.
Di sisi lain, saat ini penyebab sulitnya perkembangan sektor pertanian adalah karena masalah lahan pertanian, seperti ;
(1) Luas pemilikan lahan petani kini semakin sempit, setengah dari petani memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar sehingga sebagian besar bekerja sebagai buruh tani. Sebagai solusinya dengan membangun agroindustri di perdesaan dalam upaya merasionalisasi jumlah petani dengan lahan yang ekonomis.
(2) Alih fungsi lahan produktif ke industri maupun perumahan. Saat ini lahan pertanian yang tersedia sekitar 7,7 juta hektar, padahal untuk memenuhi kebutuhan lahan dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan petani membutuhkan lahan seluas 11-15 hektar. Sebagai solusinya pemerintah agar bisa membatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Di samping itu, perlu juga penggalakan sistem pertanian yang berbasis pada konservasi lahan serta pemanfaatan lahan tidur untuk lahan pertanian.
(3) Produktifitas lahan menurun akibat intansifikasi berlebihan dalam penggunaan pupuk kimia secara terus menerus, sebagai solusinya perlu dikembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan (organik).
Dengan melihat beberapa permasalahan sektor pertanian sebagai mana tersebut di atas tentunya kita semua harus semakin berhati-hati, sebab jika masalah tersebut tidak segera di atasi mungkin 5 hingga 10 tahun kedepan sektor pertanian di Indonesia tidak akan bisa lagi memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga bukan tidak mungkin krisis pangan pun akan bisa saja terjadi.
Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melakukan impor bahan pokok (pangan) seperti kedelai, beras maupun gula pasir. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sektor pertanian di Indonesia belum kokoh.
Namun demikian setidaknya ada program guna antisipasi dini agar bangsa ini terhindar dari rawan pangan. Program ini bisa disebut sebagai program peningkatan ketahanan pangan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kegiatan pokok yang di lakukan dalam program ini meliputi :
Pertama. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intersifikasi serta optimalisasi dan perluasan area pertanian.
Kedua, Peningkatan distribusi pangan, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.
Ketiga, Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi petanian untuk menurunkan kehilangan hasil panen.
Keempat, Diservikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan altematif/pangan lokal.
Persoalan mendesak dan tantangan nyata pertanian Indonesia saat ini bukan masalah sekedar impor atau tidak impor beras, akan tetapi mengurangi kebergantungan Indonesia pada impor beras dari pasar global dan membangun kembali swasembada beras secepatnya, jika tidak maka keamanan pangan hanya tersedia bagi si kaya tetapi menjadi suatu kemewahan bagi si miskin. Setiap upaya pembangunan harus di arahkan pada peningkatan produksi pangan domestik agar kebergantungan pada impor makin berkurang.
https://adventuspratama.wordpress.com/%E2%80%A2mengapa-pertanian-itu-begitu-penting-di-perekonomian-indonesia/