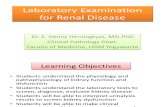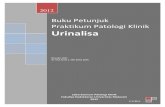42059089-Pemeriksaan-Patologi-Klinik-1
-
Upload
elvan-dwi-widyadi -
Category
Documents
-
view
903 -
download
60
description
Transcript of 42059089-Pemeriksaan-Patologi-Klinik-1
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan perlunya sisterm belajar mengajar dua arah Dosen-Mahasiswa, maka
dipandang perlu untuk menerbitkan Diktat Pegangan Kuliah Patologi Klinik I dengan tujuan
agar dapat dipelajari mahasiswa sebelum kuliah diberikan, sehingga dapat dikembangkan
diskusi/Tanya-jawab yang intensif.
Diktat pegangan kuliah Patologi Klinik I dibuat dalam 2 jilid, yaitu untuk kuliah tengah
semester pertama dan kedua. Tengah semester pertama mencakup materi kuliah tentang
Handling Specimen, hematopoiesis, Darah Rutin, Urinalisis, Dasar Pemeriksaan Imunologi.
Dan tengah semester kedua mencakup materi kuliah tentang pemeriksaan Imunologi. Dan
tengah semester kedua mencakup materi kuliah tentang Pemeriksaan feses, Golongan
Darah dan Transfusi, Transudat, LCS, Asam Basaa dan Elektrolit, Aspek Laboratorium
Gastroenterologi, Aspek laboratorium Ginjal.
Semoga ditat kuliah ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam menambah bahan referensi
kuliah.
Semarang, 24 February 2009
Ketua Bagian
Dr. Imam Budiwiyono SpPK (K)
NIP : 131 125 893
DAFTAR ISI
Diktat Pegangan Kuliah Patologi Klinik I Jilid I
1. Hematopoiesis
2. Eritropoesis
3. Leukopoiesis
4. Trombopoiesis
5. Hematologi Urin
6. Urinalisis
7. Urin Khusus
8. Imunologi Dasar
9. Dasar-dasar pemeriksaan laboratorium Imunologi
HEMATPOIESIS
By : dr. Imam Budiwiyonio, SpPK
Proses produksi dan perkebangan sel-sel darah
Induk sel darah :
- Hematopoietic stem cell
- Stem cell
Tugas : memproduksi sel – sel darah untuk mengganti sel-sel darah yang rusak/mati.
Beberapa teori :
1. Monophyletic (uniphyletic) : Maximov dkk. 1948 : semua sel darah berasal dari satu
sel induk (banyak dianut)
2. Polyphyletic : Sabin dkk. 1936 : masing masing sel darah terdapat stem sel yang
tertentu dan terpisah
3. Intermediate : teori antara monophyletic an polyphyletic. : teori dualis, teori trialis,
teori neo Unitarian
Supaya jumlah sel-sel darah tetap, stem cell mengadakan regulasi dengan proliferasi dan
diferensiasi.
Faktor factor yang meregulasi pembentukan dan diferensiasi sel-sel darah :
- Eritropoietin : untuk pembentukan eritrosit
- Leukopoietin : untuk pembentukan leukosit
- Tromboietin : untuk pembventukan trombosit
Pembentukan sel-sel darah tempatnya berlainan untuk masing-masing decade umur:
A. Pada embrio dan fetus : 3 stadium
1. Stadium mesoblastik
Minggu ke 3-6 kehamilan sampai dengan bulan 3-4 kehamilan : sel-sel
mesenchym dari yolk sac (eritrosit : inti dan sel : besar umurya pendek –
megaloblas)
Minggu ke 5 kehamilan produksi turun diganti organ lain.
2. Stadium hepatic
Minggu ke-6 kehamilan sampai dengan bulan ke 10 kehamilan kemudian turun
Waktu : relative singkat stadium selanjutnya.
Organ : limpa, hepar, kelenjar limfe
Produksi seri : granullosit, megakariosit/trombosit, eritrosit
3. Stadium myeloid
Bulan ke-6 kehamilan sampai dengan lahir.
Organ : sum-sum tulang
Produksi : eritrosit, leukosit megakariosit
Pembentukan eritrosit di organ lain : tidak ada (-)
B. Pembentukan sel darah : anak lahir sampai dengan dewasa
Organ : sumsum tulang.
Pada keadaan normal tidak diproduksi di hepar dan limpa.
Pada keadaan abnormal : dibantu organ-organ lain.
1. Hemopoiesis meduler
Lahir sampai dengan 20 tahun. Seluruh sumsum tulang memproduksi sel-sel
darah. Lebih dari umur 20 tahun corpus tulang panjang berangsur-angsur diganti
jaringan lemak produksi menurun, sehingga pada orang dewasa dijumpai
pada sumsum tulang merah yaitu pada : tulang panjang, tuang pendek dan
tulang pipih.
2. Hemopoiesis ekstra meduler
Dapat terjadi pada keadaan tertentu,
Misalnya pada
- Eritroblastosis fetalis
- Anemia pernisiosa
- Thalasemia
- Anemia sel sickle
- Sferositois heredirter
- Leukemia
Organ-oran :
- Limpa
- Hati
- Limfonodi
- kelenjar adrenal
- tulang rawan
- ginjal dan lain-lain.
Anemia aplastil : jarang di produksi ekstra meddler
GAMBAR…
ERITROPOIESIS
By : dr. Imam Budiwiyono, SpPK
Perkembangan dan pembetukan system sel darah merah :
Eritrosit (SDM) berasal dari Hemositoblas Proeritroblas *berinti) Basofilik Eritroblas
Polikromatik Eritroblas Ortokromatik Eritrlblas Retikulosit Eritrosit (tidak berinti)
dan membelah secara mitosis.
Seluruh perkembangan dan pembentukan : Eritropoiesis.
Proses :
Terjadi 3 (tiga) macam proses : Hemositoblas (sumsum tulang) sel masak (aliran darah)
1. Proses pembelahan (mitosis)
2. Proses pemasakan (maturasi)
3. Proses pembebasan (sumsum tulang aliran darah)
1. Proses Pembelahan
- Normal pada sumsum tulang : 1% dari sel-sel lain.
- Hiperplastik : 5%
- Mitosis eritroblas > granulosit
- Aktif sampai dengan stadium polikromatik eritroblas
- Pada stadium ortokromatik eritroblas mitosis tidak ada (-)
2. Proses Pemasakan (maturasi)
- Struktur
- fungsi
3. Proses Pembebasan
Dari sumsum tulang (bebas) masuk ke pembuluh darah (aliran darah),
menembus lapisan endothelial pembuluh dara hsecara dapedesis (proses hamper
sama di lien).
Seluruh proses eritropoieses dalam sumsum tulang diperlukan waktu 7 (tujuh) hari.
Terdapat 3 ciri perkembangan sel darah merah (SDM) yaitu :
1. Penyusutan ukuran sel
Makin tua stadiumnya, besar sel menjadi makin kecil
2. Perubahan warna sitoplasma
Pada pengecatan Romanowksy, mula-mulas sel yang paling muda berwarna
basofilik, makin tua warnanya akan berkurang dan menjadi warna asidofilik.
Perubahan ini oleh karena :
- Sintesis Hb berlebih
- Berkurangnya RNA
3. Perubahan inti
- Nucleoli makin hilang
- Ukuran makin kecil
- Sitoplasma relative makin banyak disbanding inti
- Kromatin makin tua, makin padat dan tebal
- Warna inti makin gelap
Sel-sel Eritrositik :
A. PROERITROBLAS (RUBRIBLAS)
Bentuk besar dan bulat
Ukuran 12-20 µ
Kadang-kadang pada tepinya terdapat tonjolan sitoplasma yang ujungnya tumpul
Inti :
- Relative besar
- Hamper mengisi seluruh sel
- Kromatin halus
- Nucleoli dijumpai (+)
Sitoplasma :
- Relative sedikt, mengelilingi inti
- Warna : biru tua (lebih gelap daripada mna hitam/biru homogenyeloblas)
- Kadang-kadang : halo perinuclear (daerah terang mengelilingi inti) positif.
- Tidak bervakuola
B. BASOFILIK ERITROBLAS (PRORUBRISIT)
Bentuk : besar dan bulat (lebih kecil)
Ukuran : 10-16 µ
Inti :
- Relative masih besar
- Benang kromatin lebih tebal
- Susunan kromatin lebih padat
- Anyaman kromatin lebih padat
Sitoplasma
- Biru muda (agak basofilik)
- Ratio sitoplasma : inti = lebih besar lagi
C. POLIKROMATIK ERITROBLAS (RUBRISIT)
Ukuran : 8-14 µ
Inti :
- Mengecil
- Kromatin : lebih besar
- Susunan kromatin padat
- Nucleoli hilang
Sitoplasma :
- Sudah tampak asidofil (oleh karena sintesis Hb >)
D. ORTOKROMATIK ERITRIOBLAS *METARUBRISIT)
Ukuran 8-10 µ
Inti :
- Lebih kecil
- Pada yang tua : piknotik
- Berwarna hitam /biru homogeny
- Benang-benang kromatin tak tampak
Sitoplsma : lebih asidofil
E. RETIKULOSIT
Ukuran : lebih kecil lagi
Inti : tidak ada (-)
Sitopplasma :
- Dengan cat Romanowsky terlihat berwarna ungu
- Dengan cat supravital (BCB) terlihat substansia granula filamentosa (banyaknya
tergantung umur)
- Makin tua makin hilang
F. ERITROSIT
Ukuran : 7,2 µ
Inti : tidak ada (-)
Sitoplasma : warna keunguan
Bentuk : dari atas bulat, dari samping bikonkafk di bagian sentral terdapat cekungan
yang disebut central pallor (2-3µ) – 1/3 sel. Pada anemia defisiensi Fe, central pallor
melebar menjadi anulosit.
Sifat dinding : fleksibel, kondisi ini penting untuk saat melalui lien.
Dibagian luar terdiri atas membrane yang melindungi :
- Hb
- Protein
- Enzim
Di dalamnya terdiri atas lapisan :
- Glukoprotein (mukopolisakarida yaitu : antigen-antigen pada golongan darah)
- Fosfolipid
Membran bersifat : semipermeabel
- Semipermeabel untuk air, anion, kation
- Impermeable untuk : Hb
Permukaan bermuatan (-)
Susunan :
- 61% air
- 28% Hb
- 7% lemak
- 3-4% karbohidrat, elektrolit, enzim, protein metabolit
Hb merupakan konjugasi protein, terdiri atas :
4 molekul heme, 1 molekul glbin.
Heme:
- Protoporfirin (20-40 ugr/dl)
- Fe++
Globin :
- 4 inti pirol
- Enzim (sitokrom katalase dan mikrosom)
BM : 68.000
Tiga bentuk Hb dewasa (normal) yaitu :
1. Hb. A (adult) terdiri atas : 2 rantai α, 2 rantai β (97%)
2. Hb. F (foetal) terdiri atas : 2 rantai α 2 rantai γ (1%)
3. Hb. A2 terdiri atas : 2 rantai α, w rantai δ (2%)
Hb F : pada kehidupan intra ulterin tinggi kemudian menurun sampai dengan bayi
berusia 4-6 bulan (3-4%) dewasa lebih kecil dari 2 %.
Metabolisme SDM :
1. Glukolisis
2. Metabolisme gluthation.
Energi glukolisis (glukosa menjadi asam laktat) diperlukan untuk menjaga dan
mempertahankan :
- Keutuhan membrane
- Mengatur pergantian Na+ dan K+ sehingga Hb dapat membawa O2 secara efisien.
Fungsi :
1. Buffer (mempertahankan pH darah) CO2 O2
2. Pertukaran gas yang dibutuhkan (oleh karena bentuk bikonkaf dan luas)
1 gr. Hb ~ mengikat 1,34 ml O2
Umur : 100-120 hari (dari sirkulasi darah)
Tiap hari ± 1 % diganti baru.
Bahan-bahan yang dibutuhkan eritropoiesis :
1. Asam amino (protein)
Untuk sintesis globin. Anemia karena hipoprotein jarang.
Sebelum terjadi anemia ↑
Hipoprotein Hb ↓ kebutuhan O2 ↓ produksi eritropoietin ↑
2. Fe
Sintesis haem
3. Vitamin B12 dan asam folat
Sintesis nucleic acid < DNA terganggu perkembangan inti sel terganggu
megaloblastik.
4. Vitamin C
Bersama metabolism asam folat menambah keadaan anemia megaloblastik
5. Vitamin B
B2 (riboblaf n) : < anemia normokrom normositik dengan retiklositopenia.
Asam nikotin <
Asam pantotenat < anemia pada binatang, tidak pada manusia.
Vitamin B6 < : anemia hipokrom oleh karena metabolism Fe terganggu, misalnya
pada anemia sideroblastik.
6. Vitamin E
< : Anemia hemolitik
7. Mineral
Cu : sebagai katalisator sintesis Hb.
Co : menstimuli eritropoieses (polisitemia)
Nilai rujukan :
Sel darah merah (SDM) :
- Laki-laki : 4,5 – 6,5 juta;mm3
- Wanita : 3,8 – 5,8 juta mm3
Hemoglobin (Hb)
- Laki-laki : 13-18 gr/dl
- Wanita : 11,5-16,5 gr/dl
PCV (packed sell volume) : Ht (hematokrit)
- Laki –laki : 40 – 54 %
- Wanita : 37 – 47 %
Retikulosit : 0,5 – 1,5 %
Mean corpuscular value (MCV)
(Nilai eritrosit rata –rata indeks eritrosit)
- MCV (mean corpuscular volume) Ht %
----------- X 10 µL (N : 77-93 fl) E juta/mm3
- MCH (mean corpuscular hemoglobin) Hb gr%
----------- X 10 µgr (N : 27-32 pg) E juta/ mm3
- MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) Hb gr%
----------- X 100 % (N :31-35%) Ht %
Beberapa keadaan Eritrosit :
1. Ukuran dan bentuk :
- Anisositosis : suatu keadaan ukuran /besar eritrosit tidak sama : ditemukan
makrosit/mikrosit atau keduanya.
- Poikilositosis : suatu keadaan bentuk-betuk eritsrosit tidak sama : ditemukan bentuk-
bentuk oval, pear shape, tear drop, target cell, dan lain-lain.
2. Berdasarkan pengecatan
- Hipokrom : bila warna kurang dari normal, bila central pallor lebih besar
- Hiperkrom : warna lebih gelap, central pallor hilang. Bukan konsentrasi hemoglobin
yang meningkat tapi membrane sel tebal dan selnya besar.
- Polikromasi : warna biru ke unguan, sel darah muda : RNA belum hilang sempurna
(retikulosit). Bila jumlah ↑ (meningkat) menunjukkan banyak sel regenerasi.
Kelainan-kelainan eritropoiesis :
1. Anemia : <
2. Polisitemia : >
3. Eritrolekemia : proliferasi ganas seri eritrositik.
LEUKOPOIESIS
By : dr. Imam Budiwiyono, SpPK
Asal : dibentuk di organ hemopoietik
Granulosit : hanya di sumsum tulang
Limfosit : - LN (limfonodus)
- Jaringan limmfoid
- Sebagian sumsum tulang
Monosit :- Lien
- Jaringan limfoid
- Sebagian sumsum tulang
Produksi dan masa hidup :
Siklus netrofil : 14-23 hari.
SP dilepaskan dari jaringan hemopoeitik aliran darah jaringan tubuh.
Stem cell granulosit : 2 stadium.
1. Stadium pembelahan : mieloblas, promielosit dan mielosit ; mengalami 1 x ;
pembelahan
2. Stadium pemasakan : Metamielosit, staf dan segmen : pembelahan (-), pematangan
dengan cepat.
Fungsi :
Bermacam- macam tergantung dari macam SDP.
Umumnya : mempertahankan tubuh dan melawan infeksi, mempunyai dinding gelatin
yang dapat menggelembung.
Neutrofil polimorfonuklear
- Untuk pertahanan, melwaan infeksi akut bergerak aktif dan fagositosis menuju
tepat infeksi/jaringan yang rusak memakan dan membunuh mikroorganisme.
Eosinofil :
- Daya fagositosis dan gerak : lebih lamban.
- Tertarik oleh adanya interaksi antigen-antibodi di jaringan khususnya protein asing.
- Missal : penyakit alergi dan parasit.
Limfosit
- Bergerak aktif
- Berperan dalam system imunologik
Monosit
- Mempunyai daya fagositik terhadap kuman, benda asing, leukosit yang mati
- Daya imunologik lain.
Basofil
- Fungsi tidak begitu jelas
- Tidak mempunyai sifat fagositik
- Berisi heparin
- Sering ditemukan besama eosinofil
Sel darah putih
- Seri granulosit
- Seri agranulosit
Sel darah putih :
- Seri granulosit
- Seri agranulosit
Seri granulosit : dengan pengecatan Romanowksy/Giemsa : terlihat bergranula.
- Eosinofil
- Neutrofil
- Basofil
Seri agranulosit : tak bergranula
- Limfosit
- Monosit
Harga Normal
Dewasa : 4.000 – 10.000 / mm3
Infant : 10.000 – 25.000 / mm3
1 tahun : 6000 – 18.000 / mm3
4-7 tahun : 6.000 – 15.000 / mm3
8-12 tahun : 4.500 – 13.000 / mm3
Differential Count
Harga relative Harga absolut
Eosinofil : 1-4 % 50-400
Basofil : 0-1 % 0-100
Neutrofil Staf : 2-5 % 200-500
Neutrofil batang : 50-70 % 2500-7000
Limposit : 20-40 % 800 – 4000
Monosit : 2-8 % 80-800
Pemasakan sel PMN ditandai :
- Perkembangan granula spesifik
- Mengilangnya warna basofilik sitoplasma
- Ditandai dengan bentuk semen
- Geraknya lebih cepat
- Kemampjan fagositosis bergtabag kuat (>>)
SDP yang masuk dilepaskan ke sirklasi darah dan menuju ke jaringan, tidak kembali ke
sirkulasi lagi. Sel-sel granulosit di dalam darah tidak seterusnya bersirkulasi, tergantung
pembatas sepanjang dinding pembuluh darah.
Dikenal 2 penyebaran sel granulosit ;
1. Yang bersirkulasi bebas
2. Yang berada di tepi
Ada pertukaran continue antara 1 & 2, yang ukurannya sama besar hanya bersirkulasi
sampai di darah tepi. Sel granulosit yang masak ditimbun di sumsum tulang (20-25 kali
dari jumlah granulosit di darah) bila diperlukan akan dilepaskan ke darah perifer.
Waktu generasi sel primitive sampai dengan masak : 10 hari.
Half life : 7 hari setengahnya akan meninggalkan sirkulasi selama 7 hari.
Metabolisme ;
Energy yang digunakan untuk fagositosis dan melawan infeksi adalah dari glikolisis.
- Enzim polymorphonuclear ; untuk mencernakan zat-zat yang difagositosis
- Neutrofil alkali fosfatase
- Muramidase (lisozim)
SEL SEL GRANULOSITIK :
MIELOBLAS :
- BESAR 15 – 20 µ
- Bentuk bulat . lonjong
- Sitoplasma ; biru, tidak bergranula, ada daerah yang terang (gelanggang) di dekat
inti dan tidak bervakuola.
- Inti : bulat/ lonjong berwarna jingga, benang kromatin halus, tersebar rata di seluruh
inti
- Nucleoli : 2-4 buah.
PROMIELOSIT :
- Besar : 15-20 µ (kadang-kadang lebih besar)
- Bentuk : bulat. Lonjong
- Sitoplasma : biru (lebih muda dari mieloblas), bergranula non spesifik (azurofilik),
kadang-kadang ada daerah terang dekat inti, tidak bervakuola.
- Inti : sudah mulai ada lekukan, benang kromatin mulai menebal, nucleoli kadang-
kadang masih ada / sudah berkurang.
MIELOSIT
- Besar : 10 – 15 µ
- Bentuk bulat .
- Sitoplasma : lebih muda lagi, tidak bergelanggang, tidak bervakuola.
- Inti : bulat/lonjong/sedikit mendatar pada 1 sisi. Benang kromatin kasar sebagian
mulai berkelompok.
- Granula eosinofil : kasar, bulat, regular tersebar rata, tak menutupi inti, warna
kemerahan.
- Granula neutrofil : halus, merata, warna jingga
- Granula basofil : kasar, tak rata, tak teratur ada yang menutupi inti, warna biru
kehitam-hitaman.
METAMIELOSIT:
- Besar : 10-15 µ/ lebih kecil lagi
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : biru (lebih muda lagi), bergranula spesifik ( eosinofil, neutrofil, basofil)
- Inti : mulai melekuk seperti ginjal (±1/3), kromatin mengelompok kasar
STAF :
- Besar : 10-15 µ/ lebih kecil lagi
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : bergranula spesifik (eosinofil, neutrofil, basofil)
- Inti : melekuk lagi (seperti buah pisang/pita), (lebar yang terpendek : lebar yang
terpanjang - > 1 : 3)
SEGMEN :
- Besar 10-16 µ
EOSINOFIL :
- Besar : 14 – 16 µ
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : bergranula merah, kasar, bulat, regular, tersebar rata, tidak menutupi
inti.
- Inti : segmen / tembereng (2-4) berlobi-lobi
NETROFIL :
- Besar : 12 – 14 µ
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : bergranula halus, jingga, rata
- Inti ; berbentuk segmen (2-5)
- Wanita : appendix (drum stick) ± 6 sel / 500 sel leukosit
- Laki-laki : tak ada drum stick
BASOFIL
- Besar : 13-16 µ
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : bergranula biru kehitam-hitaman, kasar tak teratr
- Inti ; berbentuk segmen (daun semanggi)
SEL-SEL SERI LIMFOSITIK :
LIMFOBLAS
- Besar : 15-20 µ
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : biru (lebih tua daripada ieloblas), tak bergranula
- Inti : bulat, kromatin relative lebih kasar & difus, nukeoli (+), lebih sedikit daripada
mieloblas
PROLIMFOSIT ;
- BESAR : 15-18 µ
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : biru muda, tak bergranula
- Inti : bulat, kromatin lebih muda lagi & difus, nukeoli kadang-kadang masih ada
bayangan
LIMFOSIT
- Besar : limfosit besar 12-16 µ, limfosit kecil : 9-12 µ
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : biru, tak bergranula
- Inti ; ublat, kromatin rata & difus, nukeoli (-)
SEL-SEL SERI MONOSITIK :
MONOBLAS
- BESAR 16 – 22 µ
- Bentuk : lonjong / bulat tepi tak rata, membrane sel tebal
- Sitoplasma : biru tua, tak bergranula
- Inti : bulat/ berlekuk, kromatin halus, tersusun longgar, nukeoli (+) 1-2
PROMONOSIT :
- Besar 16-20 µ
- Bentuk lonjong/ bulat
- Sitoplasma : biru, bergranula azurofilik, vakuola positif (+)
- Inti : berlekuk, kromatin kasar, tak rata, nukeoli tidak ada (=)
MONOSIT
- BESAR 16-20 µ
- Bentuk : lonjong, tepi tak rata, membrane sel terdapat tonjolan tumpul
- Sitoplasma : biru, bergranula. (azurofilik) halus, vakuola (+)
- Inti berlekuk (huruf E / perasan_, kromatin kasar tak rata, nukeoli (+) 1-2
SEL – SEL SERI PLASMOSITIK :
PLASMOBLAS
- Besar : 8 – 25 µ
- Bentuk : bulat
- Sitoplasma : biru tua, tidak bergranula, halo (gelanggang)
- Inti : bulat, eksentris, kromatin padat
PROPLASMOSIT :
- Besar : 15 – 25 µ
- Bentuk : bulat / oval
- Sitoplasma : bir tua, tidak bergranula, halo (gelanggang), vakuola (+)
- Inti : bulat, eksentris, kromatin padat, tersusun teratur
PLASMOSIT :
- BESAR : 8 – 20 µ
- Bentuk : bulat/ oval
- Sitoplasma : biru tua, tidak bergranula, halo (gelanggang), vakuola positif (+)
- Inti : bulat, kecil, eksentris, kromatin padat. (gelap)
HUBUNGAN SE CHROMOSOME dengan SDP
Wanita : drum stick : ± 6 / 500 sel, Cessile nocule, small club
KEADAAN PATOLOGIS :
Shift to the left : sel-sel muda SDP > N
Penyebab : infeksi, toksemia, perdarahan akut
Shift to the right : sel-sel tua lebih normal, hipersegmentasi.
Penyebab penyakit hati, anemia megaloblastik, herediter
LEUKOSITOSIS : Jumlah SDP lebih dari normal
Penyebab :
Fisiologis :
- Latihan jasmani yang berlebiihan
- Trimester akhir kehamilan
- Partus
- Neonates
Patologis :
- Infeksi
- Perdarahan
- Trauma
- Penyakit keganasan
- Penyakit jantung
- Keracunan obat & bahan kimia
- Kelainan metabolic
- Penyakit – penyakit kolagen
- Miscellaneous
LEUKOPENI : jumlah SDP kurang dari normal
Penyebab :
- Obat-obatan
- Depresi sumsum tulang
- Radiasi
- Keracunan (benzene, Au, Urethan)
- Obat-obatan sitostatika
- Infeksi : bakteri, virus, riketsia, protozoa
EOSINOFILIA:
- Alergi
- Parasit
- Penyakit kulit
- Infeksi
- Zat-zat kimia (Ni/ nikel)
EOSINOPENI :
- Steroid berlebihan
- ACTH
- Tifoid
BASOFILIA :
- CML
- Polisitemia vera
- Mielofibrosis
- Stadium konvalesen
- Penyakit infeksi
- Post splenektomi
BASOPENIA :
- Pengobatan steroid
- Sinar X
- Obat-obatan (busulfan)
- Tirotoksikosis
- urtikaria
TROMBOPOIESIS
BY : dr. Imam Budiwiyono, SpPK
Asal : sitoplasma megakariosit
Pembentukan : di sumsum tulang
Pembelahan : inti beberapa kali, tanpa sitoplasma
Besar : 100 µ
Sitoplasma : membentuk membrane dan membentuk tonjola-tonjolan
Megakariosit masuk sinusoid dalam sumsum tulang sitoplasma pecah
pembuluh darah
Dari 1 megakariosit terbentuk 3000-4000 trombosit.
Nilai rujukan dalam darah : 150.000 – 400.000/mm3
Umur : 10 hari
Waktu paruh 3 hari
3 zone sesuai fungsinya :
1. daerah tepi : adhesi, aggegasi
2. Daerah sol gel : struktur, mekanisme kontraksi
3. Daerah organel : pengeluaran isi
Ad. 1 : daerah tepi
Zat amorf terdiri atas :
- Mukopolisakarida
- Glikoprotein
- Factor-faktor pembekuan
- PF3 (platelet factor 3)
Ad. 2 So gel :
- Rangka untuk stabilitas bentuk
- Mikrofilamen enghasilkan trombosistein
Ad. 3 organel :
- Respirasi
- Ekskresi
- Produksi
- Menyimpan / melepaskan energy
HEMATOLOGI RUTIN
By: dr. Indranila KS, SpPK
Pemeriksaan darah rutin
Pemeriksaan darah pendahuluan pada setiap penderita dimana hasilnya sebagai
edoman untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Termasuk pemeriksaan darah rutin :
1. Hemoglobin (Hb)
2. Jumlah leukosit
3. Laju endap darah (LED)
4. Hitung jenis leukosit (preparat darah tepi)
Hemoglobin
Pemeriksaan hemoglobin digunakan sebagai salah satu parameter dalam menentukan
diagnose dan derajat berat ringannya anemia, monitoring hasil pengobaan anemia.
Harga normal hemoglobin (Dacie 1984)
Dewasa laki – laki 155 ± 25 gr/l
Dewasa perempouan 140 ± 25 gr/l
Bayi < 3 bulan 165 ± 30 gr/l
Bayi > 3 bulan 115 ± 20 gr/l
Anak 1 tahun 120 ± 15 gr/l
Anak 3 – 6 tahun 130 ± 10 gr/l
Anak 10 – 12 tahun 130 ± 15 gr/l
Nilai normal sel darah merah (menurut AV Hoffbrand) :
Pria : 13,5 – 17,5 g/dl
Wanita : 11,5 -15,5 g/dl
Neonatus : 15,0 – 21,0 g/dl
3 bulan : 9,5 – 12,5 g/dl
1 tahun pubertas : 11,0 – 13,5 g/dl
Penurunan kadar hemoglobin :
A. Fisiologis : kehamilan
B. Patologis ;
- Thalassemia
- Hemoglobinopathi
- Anemia kurang besi
- Perdarahan akut
- Perdarahan kronik
- Anemia sideroblsatik
- Infeksi kronik
- Leukemia
Penurunan kadar hemoglobin :
- Polisitemia
- Dehidrasi
Konsentrasi hemoblobin dalam darah kurang dari batas nilai rujukan, baras terendah
disebut anemia. Setelah kehilangan darah banyak akut, anemia tidak segera tampak
nyata, karena volume darah total berkurang. Volume plasma darah memerlukan waktu
satu hari untuk diganti dengan demikian tampak anemia. Regenerasi masa hemoglobin
memakan waktu lebih lama, oleh karena itu, gambaran klinis mula-mula dari kehilangan
darah akut dan banyak adalah disebabkan karena penurunan volume darah bukan
karena anemia.
Gejala penurunan hemoglobin biasanya :
Napas seksak, kelemahan , letargi, palpitasi dan sakit kepala. Pada orang yag lebih tua
dapat timbul gejala : payah jantung, angina pectoris, klaudikasio intermiten dan
kebingungan.
Gangguan penglihatan karena perdarahan retina dapat menjadi komplikasi anemia /
penurunan Hb yang sangat berat, khususnya anemia yang timbul cepat / rapid onset.
Gambaran klinik pada pasien dengan anemia berat bias tanpa gejala atua tanda
sedangkan orang lain dengan anemia ringan bias sangat lemah.
Gambaran klinik dipengaruhi/ tergantung dari :
1. Cepat timbulnya (rapid onset) : anemia yang lambat muncul lebih banyak waktu
penyesuaian dalam sistim kardiovaskuler dan kurve disosiasi oksigen hemoglobin.
2. Deraja / severity ; anemia ringan sering tidak menimbulkan gejala, anemia berat
(konsentrasi Hb kurang dari 6 gr/dl) dapat memberikan gambaran klinsi ringan
karena timbul perlahan pada orang muda dengan fisik yang sehat.
3. Usia penderita ; orang tua kurang tahan terhadap anemia disbanding orang muda
karena pengaruh kurangnya oksigen dan system kardiovaskuler yang terganggu.
4. Kurva disosiasi oksigen hemoglobin ; pada umumnya peninggian 2,3 DPG dalam sel
darah merah dan denga npergeseran kurva disosiasi oksigen ke kanan oksigen
mudah dilepas.
Gambaran kadar hemoglobin dan ukuran sel darah merah menyatakan jenis aneminya
dan menyatakan sifat cacat yang mendasarinya oleh karena itu pemeriksaan lebih lanjut
diperlukan untuk memastikan sebab dan diag nosis lainnya.
Jumlah leukosit :
Jumlah leukosit normal (Dacie)
Dewasa : 7,5± 3,5 x 10 gr/l
Bayi lahir : 18± 8 x 10 gr/l
1 tahun : 12± 6 x 10 gr/l
4-7 tahun : 10± 5 x 10 gr/l
8-12 tahun : 0 ±4,5 x 10 gr/l
Hitung jumlah darah putih normal (AV hoffbrand)
Dewasa :
Leukosit total : 4 – 11 x 109/l
Neutrofil : 2,5 – 7,5 x 109/l
Eosinofil : 0,04 – 0,4 x 109/l
Monosit : 0,2 – 0,8 x 109/l
Basofil : 0,01 – 0,1 x 109/l
Limfosit : 1,5 – 3,5 x 109/l
Anak-anak:
Leukosit total : 10 – 25 x 109/l
Bayi batu lahir: 6,0 – 18 x 109/l
1 tahun : 6 – 15 x 109/l
4 – 7 tahun : 6 – 15 x 109/l
8 – 12 tahun : 4,5 – 3,5 x 109/l
Sel leukosit dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya : fagosit dan imunosit :
Granulosit terdiri dari tiga jenis : neutrofil polimorf, eosinofil dan bbasofil. Ketiganya
bersama dengan monosit merupakan fagosit. Limfosit dan sel plasma membentuk
populasi imunosit. Normal hanya fagosit dan limfosit ditemukan di darah tepi. Fungsi
fagosit dan imunosit melindungi tubuh, melawan infeksi dan bekerja sama dengan
system protein tubuh yang larut : immunoglobulin dan komplemen.
gambar
Neutrofil :
Neutropeni :
Batas bawah hitung neutrofil adalah 2,5 x 109 / l bila kadar turun dibawah 1,0 x 109 /l
pasien cenderung mengalami infeksi berulang (rekuren) dan bila turun sampai < 0,2 x
109 /l risiko sangat serius. Neutropeni bias selektif (berdiri sendiri) atau terjadi sebagai
bagian pansitopeni.
Sebab-sebab Neutropeni :
A. Neutropeni selektif
1. Obat-obatan
a. Obat anti radang : aminopirin, fenilbutazon
b. Obat antibakteri : kloramfenikol, kotrimoksazol
c. Antikonvulsi : feniotin
d. Antitiroid : karbimazol
e. Obat hipoglikemik : tolbutamid
f. Fenotiazin : klorpromazin, prometazin
g. Macam-macam : mepakrin, fenindion dll
2. Benigna : ras/familial
3. Siklikal : periodic
4. Lain-lain :
a. Infeksi virus : hepatitis, influenza
b. Infeksi bakteri ganas (fulminan) : tifus abdominalis, tuberculosis milier
c. Hipersensitivitas dan anafilaksis
d. Netropeni otoimun
e. Sindroma Felty
f. Systemic lupus erythematosis
B. Panstiopeni :
1. Kegagalan sumsum tulan
2. splenomegali
Leukositosis neutrofil :
Peningkatan neutrofil yang beredar melebihi batas nilai rujukan , leukositosis neutrofil
sering disertai demam karena pembebasan pirogen leukosit.
Gambaran khas lain adanya :
a. neutrofilia reaktif : pergeseran ke kiri (shift to left) dalam hitung jenis darah putih.
b. Granula toksik sitoplasma dan benda Dohle (kondensasi RNA)
c. Peninggian kadar fosfatase lindi neutrofil
Sebab-sebab :
1. Infeksi bakteri : piogenik setempat/generalisata
2. Peradangan dan nekrosis jaringan : miositis, vaskulitis, infark miokard, trauma
3. Penyakit metabolic : uremia, eklampsia, asidosis, gout
4. Neoplasma : karsinoma, lmfoma, melanoma
5. Perdarahan atau hemolisis akut
6. Terapi kortikosteroid
7. Penyakit mielploriferatif : leukemia granulositik kronik, polisitemia vera dan
mielosklerosis)
Eosinofilia:
Peningkatan eosinofil darah di atas 0,4 x 109/l terjadi pada ;
1. Penyakit alergi : hipersensitivitas atopic (asma bronchial, hay fever, urtikaria, alergi
makanan)
2. Penyakit parasit amubiasis, cacing tambang, askariasis, cacing pita, filariasis,
skistosomiasis dan trikinosis
3. Pemulihan infeksi akut
4. Penyakit kulit tertentu : psoriasis, pemfigus dan dermatitis herpetiformis
5. Eosinofilia pulmoner dan sindroma hipereosinofilik
6. Sensitivitas terhadap obat
7. Poliargeritis nodosa
8. Penyakit Hodgkin dan beberapa tumor lain
9. Leukemia eosinofilik (jarang)
Monositosis:
Kenaikan hitung jenis monosit darah diatas 0,8 x 109/l disebabkan oleh keadaan :
1. Infeksi bakteri kronik : tuberculosis, bruselosis, endokarditis bakterialis, tifus
abdominalis.
2. Penyakit protozoa
3. Neutropenia kronik
4. Penyakit Hodgkn
5. Leukemia mielomonositik dan monositik
Basofilia:
Peningkatan basofil darah di atas : 0,1 x 109/l terjadi pada keadaan :
1. Kelainan mieloproliferatif : leukemia granulositik kronis, polisitemia vera
2. Peningkatan basofil reaktif : myxedeme, infeksi cacar atau cacar air, colitis ulserativa
Reaksi leukomoid :
Leukositosis reaktif berlebihan ditandai oleh adanya sel muda : blas, promielosit dan
mielosit dalam darah tepi. Sebagain besar reaksi leukemoid melibatkan granulosit tetapi
kadang-kadang reaksi limfositik terjadi kelainan yang menyertai : infeksi berat atau
kronis, haemolisis hebat atau kanker metastatic. Reaksi leukemoid sering menonjol
khusus pada anak-anak. Perubahan granulosit : granulasi toksik dan benda Dohle dan
fosfatase lindi yang tinggi membedakannya reaksi leukemoid dengan leukemia
granulositik kronik adanya proporsi besar melosit dan khromosom Philadelphia
memastikan leukemia granulositik kronik.
GAMBAR
Sel darah putih : a. neutrofil, b. eosinofil, c. basofil, d. monosit, e. limfosit
Reaksi leukoeritroblastik :
Eritroblas dan sel darah putih primitive ditemukan dalam darah tepi, ditemukan pada :
1. Mielosklerosis ; metaplasia myeloid
2. Leukemia myeloid
3. Infiltrasi sumsum tulang : karsinoma, fibrosis, tuberculosis, myeloma, limfoma
4. Perdarahan hebat, hemolisis atau anemia megaloblatik
5. Lipidosis
6. Penyakit tulang marmer (Aibers-Schoenberg, osteoporosis)
Limfositosis:
1. Infeksi
a. Akut : mononucleosis infeksiosa, rubella, pertusis, limfositosis infeksiosa akut,
hepatitis infeksiosa, virus sitomegalik
b. Kronik : tuberculosis, toksoplasmosis, bruselosis
2. Tirotosikosis
3. Leukemia limfositik kronik dan beberapa limfoma
Limfopeni :
Jarang tetapi dapat terjadi pada :
a. Kegagalan sumsum tulang
b. Terapi kortikosteroid dan imanosupresi
c. Penyakit Hodgkia
d. Penyinaran luas
Hitung jenis leukosit :
Nilai abnormalitas SDP :
1. Hipersegmen :
Polimorfonuklear (pmn) neutrofil bentuknya lebih besar dan mengandung lobus yang
jumlahnya lebih dari 6 buah. Dijumpai pada : anemia defisiensi besi.
2. Virosit
Bentuknya besar : bias sampai 20 mikron, termasuk seri limfosit yang mengalami
reaksi akibat infeksi virus, sitoplasma berwarna biru tua, kadang-kadang berbuih dan
bervakuola. Limfosit plasma biru (LPB) : virosit yang ditemukan pada penyakit
Dengue Haemorrhagic Fever. LPB : sitoplasma biru tua, berbuih dan kromatin inti
yang lebih kasar serta pattern kromatin-parakromatin yang nyata.
3. Sel Downey :
Termasuk grup virosit, lazim dijumpai pada penyakit infeksius. Dikenal ada 3 tipe:
- Tipe I : monsitoid, bentuk inti bulat, kacang atau ginjal, berlobi tetapi umumnya
bentuk inti seperti inti monosit. Sitoplasma lebih basofilik dan terkadang foamey.
- Tipe II : plasmasitoid , sitoplasma lebih tua, kadang gambaran radial/periferi
basofilia sehingga kadang-kadang seperti ballerina skirt. Kromatin kasar dan tidak
mengandung nucleoli.
- Tipe III : blastoid : sel besar, sitoplasma biru, inti besar, kromatin halus tersusun
seperti ayakan dengan satu/lebih lubang besar yang merupakan nukeoli,
menyerupai sel blas. Sel-sel ini dijumpai pada penyakit virus, virus dengue / DHF,
Epstein Barr dan lain-lain.
4. Limfosit atipikal :
Disebut limfosit reaktif, karena morfologinya serupa sel plasma akibat adanya
rangsangan abnormal yang konvensional, ada yang menyebutnya dengan limfosit
plasmasitoi.
5. Toksik granulasi
Granula neutrofil pada granulosit bertambah kasar dan berwarna lebih gelap.
6. Vakuolisasi
Granulosit dengan vakuola dalam sitoplasma karena proses degenerasi
7. Benda Dohle (kondensasi RNA)
Inklusi dala msitoplasma SDP netrofil, berwarna biru muda atau abu-abu bentuk oval
atau bentuk spindle
8. Benda supras
Inklusi tak teratur bulat atau bersegi terdapat dalam sitoplasma SDP muda sering
pada sel blas, berwarna jingga.
9. Batang Auer :
Inklusi dalam sitoplasma granulosit muda bentuk blas, warna jingga, bentuk seperti
jarum, terdapat pada leukemi mielositik akut.
10. Sel Rieder
Sel limfosit dengan inti bercelah (cleft), pada penyakit lifoproliferatif.
11. Hiposegmentasi
Hamper semua PMN mempunyai jumlah lobus hanya 2-3 buah. Terdapat pada
anomaly Pelger Huet dan bentuk pseudo Pelger Huet yang tidak herediter, dijumpai
pada MDL dan MDS.
12. Shift to the left
Dalam hitung jenis leukosit terdapat peningkatan jumlah bentuk batang dan
kehadiran kadang-kadang sel yang lebih primitive seperti, metamielosit dan mielosit.
Terdapat pada : infeksi, toksemia, hemorrhagi, neutropeni kronik pada anak-anak.
13. Shift to the right
Kebanyakan dari sel neutrofil mempunyai inti dengan 4 inti terdapat pada:
- Penyakt hepar
- Anemi megaloblastik karena defisiensi vit B12 dan asam folat
- Sepsis(lebih sering shift to the left)
- Hipersegmentasi herediter
- Defisiensi besi
- Rheumatoid arthritis
LED (laju endap darah)
Nilai normal :
Laki-laki : 0-5 mm/jam
Wanita : 0-7 mm/jam
Laju endap darah dipengaruhi oleh :
1. Sel darah merah
- Ukuran makrosit, menyebabkan LED meninggi dibaning mikrosit
- Bentuk : sickle cell / sferosit menyebabkan LED meninggi
- Anemia, konsentrasi sel darah merah menurun, LED meninggi
- Tendensi rouleaux dan glutinasi menyebabkan LED meninggi
2. Komposisi plasma
- Fibrinogen menyebabkan LED meninggi
- Globulin α1 dan α2 menyebabkan LED meninggi
3. Kesalahan teknik, letak tabung, getaran, suhu pemeriksaan menyebabkan LED
meninggi. Kenaikan LED terjadi pada :
- Infeksi akut dan kronik
- Demam reumatik
- Theumatoid arthritis
- Infark miokard
- Nefrosis
- Hepatitis akut
- Mestruasi
- Hipotiroidosis
- hipertiroidosis
URINALISIS
By : dr. Lisyani B. Suromo, SpPK(K)
Pendahuluan
Urinalisis ialah suatu analisis untuk mendapatkan keterangan mengenai ada tidaknya
kelainan hasil pemeriksaan laboratorium urin seorang penderita yang dapat dipakai untuk
menunjang diagnosis suatu penyakit.
Urin merupakan suatu larutan kompleks yang terdiri dari air (± 96 %) dan bahan-bahan
organic dan anorganik (± 4 %) yang dikeluarkan oleh ginjal, berasal dari pembuangan hasil
metabolism tubuh dan makanan. Kandungan bahan organic yang penting antara lain urea,
asam urat, kreatinin dan bahan anorganik yang penting antara lain NaCl, Sulfat, fosfat,
ammonia.
Thomas Addis (1948), mengemukakan pendapatnya bahwa pemeriksaan urin merupakan
suatu bagian yang sangat penting dari pemeriksaan fisik seorang enderita. Dari hasil
pemeriksaan urin dapat diperkirakan kemungkinan adanya kelainan baik yang mengenai
ginjal saluran kemih sendiri maupn di luar ginjal saluran kemih, sebagai berikut :
- kelainan di dalam ginjal-saluran kemih antara lain
# peradangan : ditemukan sel darah putih dalam jumlah melebihi batas nilai
rujukan
# perdarahan : ditemukan sel darah merah dalam jumlah melebihi batas nilai
rujukan (gross ataupun mikroskopik). Batu dapat menyebabkan iritasi
sehingga menimbulkan keadaan hematuria mikroskopik (dengan ataupun
tanpa disertai penemuan Kristal), dapat pula menimbulkan inflamasi / infeksi
sehingga menimbulkan keadaan leukosituria / piuria. Keganasan juga dapat
menimbulkan hematuria.
# Penyakit ginjal dapat pula ditandai dengan penemuan-penemuan seperti
proteinuria persisten, silinderuria patologis, berat jenis urin puasa yang selalu
rendah.
- Kelainan sistemik / di luar ginjal-saluran kemih antara lain:
# Diabetes mellitus : glukosuria, volume urin bertambah dengan berat jenis
tinggi, benda keton positif
# Diabetes insipidus : colume urin bertambah dengan berat jenis urin rendah
# Penyakit perdarahan : hematuria atau hemoglobinnuria
# Penyakit perdarahan : hematuria atau hemoglobinuria
# Kehamilan : proteinuria, reaksi reduksi positif, hormone human chorionic
gonadotropin (HCG) positif.
# Payah jantung : proteinuria, volume urin berkurang pada fase udem dan
bertambah pada pengeluaran cairan udem.
# Hepatitis : bilirubinuria urobilinogenuria / urobilinuria.
# Multipel myeloma ; protein Bence Jones positif.
# Panas / febris : proteinuria hematuria mikroskopik.
Macam pemeriksaan urin :
1. Pemeriksaan rutin
Merupakan pemeriksaan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk
pemeriksaan lebih lanug. Pemeriksaan ini dikerjakan pada setiap penderita tanpa
indikasi.
2. Pemeriksaan penyaring
Merupakan pemeriksaan awal yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkirakan
suatu penyakit / menyingkirkan kemungkinan terhadap suatu penyakit tertentu.
3. Pemeriksaan khusus
Berdasarkan indikasi untuk menunjang diagnosis suatu penyakit tertentu.
Macam sampel urin :
1. Urin sewaktu :
urin yang dikemihkan sewaktu-waktu. Sampel ini hanya baik untuk pemeksaan yang
bersifat kualitatif.
2. Urin pagi
Urin paling pagi yang dikemihkan pertama kali setelah bangun tidur pagi (puasa 8-10
jam, sebelum makan minum). Sampel ini paling pekat, mengandung unsure-unsur
paling banyak, pH paling rendah, dapat dipakai untuk pemeriksaan rutin dan
kehamilan.
3. Urin pagi II
Beberapa peneliti menganjurkan pemeriksaan urin yang dikemihkan beberapa waktu
berikutnya setelah urin terpagi dikemihkan sehabis-habisnya (selang waktu kira-kira
45 menit sampai 1 jam) dengan tujuan khusus untuk mencari unsure-unsur yang
berasal dari ginjal.
4. Urin 2 jam setelah makan (2 jam post prandial) : untuk pemeriksaan glukosa
5. Urin tampung : 24 jam, 12 jam (siang/malam). Digunakan untuk pemeriksaan yang
bersifat kuantitatif.
6. Urin 2 gelas/ gelas : sampel ini untuk mengetahui lokasi kelainan pada bagian-
bagian saluran kemih kelamin.
Urin 2 gelas : gelas I : 50 – 75 ml, gelas II sisanya
Urin 3 gelas : gelas I : 20 – 30 ml, gelas II : semua urin berikutnya kecuali bebrapa
ml terakhir, gelas 3 beberapa ml terakhir.
Keterangan :
Gelas I berisi bahan-bahan dari saluran kemih bagian bawah (uretra)
Gelas II berisi bahan-bahan dari kandung kemih
Gelas III berisi bahan-bahan dari kandung kemih dan getah prostat yang terperas
pada akhir kencing.
7. Residual urine : sisa urin dalam kandung kemih yang dikeluarkan setelah penderita
berkemih sehabis-habisnya. Residual urine diambil dengan kateter. Tujuannya
untuk mengetahui apakah ada hambatan dalam mengeluarkan urine.
Cara pengambilan bahan
a. Tanpa kateter : penderita berkemih sendiri, diambil pancaran tengah (mid stream)
b. Dengan kateter: untuk pemeriksaan kuman ,pemeriksaan residual urine bila perlu.
Syarat-syarat untuk urin yang akan diperiksa : bar / segar (sebaiknya 3-6 jam)
alasannya :
- Warna belum berubah
- pH belum berubah (lama-lama menjadi alkalis dan unsure-unsur mikroskopik
tertentu akan menjadi rusak)
- zat –zat tertentu belum berubah atau menguap (urobilnogen menjadi urobilin, keton
menguap)
- bakteri belum berkembang biak,
Bila pemeriksaan ditunda perlu diawetkan
Cara mengawetkan
a. dismpan dalam lemari es suhu 4oC.
b. diberi bahan – bahan kimia antara lain :
- toluene : dapat dipakai untuk pemeriksaan rutin dan aseton
- timol : kejelekannya menimbulkan positif palsu terhadap protein
- larutan formaldehid 40% : dapat dipakai untuk pemeriksaan sedimen. Kejelekannya
menganggu pemeriksaan urobilin, bilirubin, protein glukosa dan indikan
- asam sulfat pekat ; dapat dipakai untuk pemeriksaan Ca (menghindari pengendapan
garam calcium), nitrogen (menghindari keluarnya N dari ammonia), dan zat-zat
anorganik lainnya.
- Asam chloride pekat Dapat dipakai untuk pemeriksaan ammonia, urea nitrogen.
Kejelekannya akan mengendapkan asam urat
- Natrium karbonat : untuk pemeriksaan urobilinogen dengan menjaga urin dalam
keadaan alkalis.
- Chloroform ; menghambat pertumbuhan bakteri dalam urin dan membuat urin jenuh.
Kejelekannya ;m empengaruh pemeriksaan glukosa.
- Natirum fluoride atau asam benzoate : dapat dipakai untuk pemeriksaan glukosa
dengan menghambat glikolisis.
PEMERIKSAAN URIN RUTIN
Secara garis besar dengan metode konvensional dibedakan menjadi :
A. Pemeriksaan makroskopik / fisik :
1. Warna
2. Kejernihan
3. Buih
4. bau
B. Pemeriksan kimia
1. Keasaman
2. Protein
3. Reduksi
C. Pemeriksaan mikroskopik
A. Pemeriksaan makroskopik / fisik :
Ad. 1 warna
Normal : berwarna kuning muda sampai kuning tua, urin encer warnanya lebih
muda daripaa urin pekat dan urin asam biasanya berwarna lebih tua dari urin alkalis.
Kelainan : dapat bersifat patologis / tidak patologis
a. Tidak patologis : karena makanan, obat-obatan.
Makanan : wortel (kuning tua0, makanan yang mengandung fosfat / urat
(seperti susu), kue-kue yang diberi zat pewarna.
Obat-obatan : antipirin (merah), fenil salisilat (hijau), metilen blue (biru
kehijauan), fenol (coklat hitam).
b. Patologis : bilirubin (seperti teh), darah(merah), melanin (hitam), biliverdin
(hijau), kiius (seperti susu), nanah (putih keruh).
Ad. 2 : kejernihan
Normal : biasanya jernih
Keruh : dibedakan :
a. Keruh sejak dikemihkan
Contoh : fosfat (amorf) dalam jumlah banyak, makin lama makin banyak karena
urin makin menjadi alkalis.
Tidak mempunyai arti klinis :
- Nanah, disebabkan karena peradangan, mikroskopik dijumpai sel-sel darah putih.
Dan epitel dalam jumlah melebihi normal, sisa-sisa jaringan dan bakteri.
- Kilus seringkali disebabkan karena filariasis (bendungan aliran limfe)
- Darah (gross hematuria) menyebabkan urin berwarna merah coklat, keruh dan
berkabut.
b. Keruh setelah didiamkan beberapa waktu :
- Fosfat amorf
- Perkembang biakan bakteri.
Ad.3 : buih
Normal : bila urin dikocok akan berbuih putih dan cepat hilang.
Kelainan : bilirubin menyebabkan buih berwarna kuning. Protein menimbulkan buih putih
yang bertahan lama.
Ad.4 : bau
Normal: biasanya tidak berbau keras, disebabkan karena adanya asam-asam dalam
urin yang mudah menguap.
Kelainan : dapat bersifat tidak patologik / patologik. Contoh :
- Tidak patologik : karena makanan (durian, petai, jengkol), obat-obatan (toluene,
mentol).
- Patologik : benda-benda keton (bau buah – buahan), perombakan ureum (bau
amoiak), perombakan albumin (bau asam sulfide), perforeasi usus ke dalam
kandung kemih (bau tinja), karsinoma saluran kemih-kelamin (bau busuk).
Ad. 5 : berat jenis (BJ)
Rujukan :
- Urin pagi : 1,015 – 1,025
- Urin sewaktu : 1,003- 1,030
Tidak normal : rendah (diabetes insipidus, kegagalan ginjal), tinggi (dehidrasi, diabetes
mellitus).
Guna pemeriksaaan BJ : sebagai prasyarat untuk pemeriksaan sedimen, protein dan
untuk menilai kemungkinan gangguan daya pemekatan ginjal.
B. Pemeriksaan Kimia
Ad.1 : keasaman
Rujukan : 4,6 – 8 (urin 24 jam ± 6,2)
Kelainan : dapat bersifat tidak patologik / patologik
Contoh
- Tidak patologik : karena makanan (buah – buahan, sayur – sayuran), obat-obatan
(bikarbonas natrikus, kalsium asetat)
- Patologik asam : diabetes mellitus, diare/ keadaan metabolic asidosis, alkalis :
muntah, infeksi / keadaan alkalosis
Guna pemeriksaan keasaman :
1. Mempermudah interpretasi terhadap unsure-unsur sedimen urin
2. Membantu pemeriksaan protein yang harus dilakukan dalam suasana asam.
3. Membantu menguatkan diagnosis / terapi (keadaan asidosis / alkalosis).
Ad.2 : protein
Pemeriksaan protein dapat dikerjakan dengan menggunakan reagen asam asetat 6
% asam sulfosalisilat 20 % atauppun dengan bermacam-macam sticks / stix. Secara
rutin pemeriksaan protein tersebut umunya ditekankan pada kemungkinan adanya
protein (proteinuria) khususnya fraksi albumin (ingat syarat pemeriksaan protein).
Proteinuria
Menurut sebabnya dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Fungionil / fisiologis
2. Organis
1. Fungsionil / Fisiologis
- Plasma albumin dan sedikit globulin
- Bersifat ringan
- Tidak disertai gejala-gejala penyakit ginjal / kelainan-kelainan ginjal yang berarti.
- Dijumpai secara intermiten
Penyebab:
1. Aktivitas fisik / psikis yang berat / stress
2. Udara dingin
3. Premenstruasi
4. Kehamilan (bebrerapa minggu terakhir, beberapa hari setelah partus).
5. Postural albuminuria : albuminuria yang timbul disebabkan karena kelainan
bentuk tubuh (postur), disebut juga dengan nama-nama lain seperti
proteinuria ortostatik (proteinuira timbul bila berdiri dan menghilang bila
tiduran)/ siklik / adolescence (pada dewasa/muda) benigna.
2. Proteinuria Organis
Dibedakan :
a. Sebelum ginjal
Plasma albumin dan globulin
- Penyakit primer bukan pada ginjla
- Hilang setelah penyakit primer sembuh Contoh : gangguan sirkulasi ginjal karena
keadaan dehidrasi, bendungan ginjal pasif, kenaikan tekanan intra abdominal.
Efek toksik penyakit difteri, tifoid, radang akut streptokolus, keracunan, kehamilan.
b. Ginjal
- Plasma albumin dan globulin
- Proteinuria hamper selalu disertai penemuan torak / slinder, kecuali pada stadium
lebih lanjug. Contoh : radang tuberkulosa lues, nefritis akut/ kronik, sindrom nefrotik
infark, karsinoma, ginjal polikistik, pielonefritis, nefrosklerosis.
c. Sesudah ginjal
- Bukan plasma protein
- Proteinuria seringkali hanya sangat ringan, dapat disebabkan karena perdarahan /
peradangan setelah ginjal. Catatan : perlu diperhatikan kemungkinan pencemaran
yang berasal dari vagina atau semen, efek toksik obat seperti salsilat, kina, sulfa
dapat mempengaruhi keadaan baik pad ginjal maupun di bawah ginjal.
Ad. 3 Reduksi
Emeriksaan reduksi dapat dikerjakan dengan cara Fehling, Benedict atau dengan
bermacam – macam sticks. Secara rutin pemeriksaan reduksi ditekankan terhadap
kemungkinan adanya glukosa dalam urin (glukouria). Ingat reaksi positif terhadap jenis
gula lain.
Glukosuria
Terjadi apabila nilai ambang ginjal terhadap glukosa (140 – 160 mg %) dilampaui. Nilai
ambang ginjal ini berbeda-beda untuk setiap individu.
Macam-macam glukosuria :
1. Tanpa hiperglikemia
Contoh :
a. Renal glukosaria = renal diabetes – glukosuria benigna
Sebab-sebabnya : nilai ambang ginjal dan daya reabsorbsi ginjal menurun.
Ciri – cirinya
- Kadar gula darah puasa maupun 2 jam setelah makan normal
- Kurva glucose tolerance test (GTT) normal
- Glukosuria ditemukan pada semua porsi urin baik pada keadaan puasa maupun
setelah makan.
- Tidak ada gangguan metabolism lemak
- Penggunaan karbohidrat normal
b. Alimentary glucosuria : tejadi karena makan karbohidrat terlalu banyak
c. Hamil : pada akhir kehamilah
d. Sindrom Fanconi : disini terjadi gangguan pertumbuhan tubulus ginjal sehingga
rabsorbsi terhadap glukosa berkurang. Sindrom falconi ini terdiri dari : glukosuria,
rakitis, pertumbuhan badan tidak sempurna, ekskresi zat-zat antara lain calcium,
fosfat, ammonia, asam-asam organic (meninggi).
2. Dengan hiperglikemia
Contoh :
- Diabetes mellitus
- Hipertiroid
- Hiperpuitarisme
- Hiperadrenalisme
- Penyakit hepar
- Kelaparan yang lama
- Ketakutan / kecemasan / marah
C. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIK
Syarat :
- urin segar
- berat jenis > 1,018
Unsur – unsure dalam sedimen dibedakan menjadi :
1. yang perlu dilaporkan jumlahnya dalam lapang pandang kecil (LPK)
2. yang perlu dilaporkan jumlahnya dalam lapang pandang besar (LPB)
3. yang dilaporkan bila ada (tak perlu dihitung jumlahnya)
1. yang perlu dilaporkan jumlahnya dalam LPK
a. sel epitel
macam – macam sel epitel :
1. gepeng / squamous ; berasal dari pencemaran vagina, uretra
2. transisional kolumnar / silindris ; berasal dari kandung kemih, ureter,
pelvis renis.
3. Kuboid / polygonal : berasal dari tubulus ginjal
Normal : sel epitel hamper selalu dijumpai dalam jumlah sedikit dan terutama
terdiri dari sel epitel gepeng / squamous. Perhatkan kemungkinan adanya
oval fat bodies yaitu sel epitel tubulus yang mengalami degenerasi lemak. Di
jumpai antara lain pada sindrora nefrotik, diabetes mellitus.
b. torak / silinder/ cast
proses terbentuknya :
Tamm- horsfall protein (THP) yaitu suatu mukoprotein yang disintesis oleh
tubulus ginjal atau kadang-kadang bahan protein antara lain eksudasi dari
darah, produk degenerasi sel epitel yang memasuki lumen tubulus dan
keasaman memungkinkan untuk terjadinya presipitasi, akan tercetak dalam
lumen tubulus dan keluar dalam bentuk cetakan tersebut.
- Sempit : terbentuk dalam tubulus sempit
- Sedang terbentuk dalam tubulus distal
- Lebar terbentuk dalam tubulus pengumpul. Torak yang lebar ini disebut juga sebagai
renal failure cast. Contoh sel epitel gepeng : 2-5 / LPK, silinder hialin : 0-1 / LPK.
Macam-macam torak/silinder
a. Hialin : kurang mempunyai arti klinik hang penting dibandingkan dengan torak
yang lain sejumlah sedikit torak ini dijumpai pada keadaan : panas 9febris),
aktvitas fisik berlebihan.
b. Hyaline cellular cast ; torak hialin yang berisi sel-sel, dapat berisi satu macam
atau bermacam / campuran (mixed cellular cast) sel. Bila jumlah sel-selnya
banyak maka disebut dengan nama tersendiri sesuai dengan jenis selnya seperti
torak epitel, torak sel darah putih (leukosit), torak epitel, torak sel darah merah
(eritrosit).
c. Hyaline granular cast / torak berbutir
Butir-butir ini dapat berasal dari degenerasi sel ataupun dari agretasi protein.
Dibedakan :
- Berbutir halus : kurang mempunyai arti klinik penting kecuaili bila dijumpai bersama
–sama dengan torak lain (butir dalam silinder berbutri halus saja, kemungkinan
butiran tersebut berasal dari agregasi protein).
- Berbutis kasar : dijumpai antara lain pada, glumerulonefritis akut, keadaan febrile
albuminuria dengan bendungan pasif.
d. Hyaline fatty cast / torak lemak
Yorak ini berisi butir-butir lemak yang berasal dari sel epitel tubulus yang
mengalami degenerasi lemak. Dijumpai antara lain pada stadium akhir dari
glomerulonefritis akut/sub akut/ kronik, nefrosis.
e. waxy cast / torak lilin
terjadi karena degenerasi berat pada ginjal yang berlangsung dalam waktu lama.
Torak/ silinder harus dibedakan dengan : benang-benang mukosa, pseudocast,
hifa jamur.
2. Yang perlu dilaporkan jumlahnya dalam LPB
a. Sel darah merah : rujukan dapat dijumpai sampai 3 / LPB. Hematuria
mikroskopik dapat terjadi karena : kerja fisik yg berat, febris, iritasi/
perdarahan lain sepanjang traktus urogenital.
b. Sel darah putih
Rujukan laki-laki sampak 5 / LPB, wanita 15 / LPB. Piuria dapat terjadi karena
adanya peradangan. Perhatikan kemungkinan adanya sel Glitter. (contoh : s
d m 2-3 LPB, s d p 5-10/LPB).
3. Yang dilaporkan bila ada
a. Sperma
b. Bakteri
Normal : urin yang berasal dari kandung kemih bebas bakteri, tetapi sering
terjadi cemaran sewaktu melewati uretra. Secara kasar masih dalam batas
normal bila dijumpai 10 bakter / LPB.
Patologis : bakteri patologis yang sering dijumpai antara lain :
- Starilokokus
- Salmonella typhi, dapat ditemukan pad a30 % kasus tifoid.
- Mikobakterium tuberkulosa
- Streptokokus
- Escherichia colli
c. Parasit
- Trichomonas vaginalis
- Larva cacing : filarial, menyebabkan hematuria berat atau kiluria
- Ascari lumbiricoides, enterobius vermicularis, Strongyloides dan lain-lain.
d. Kristal-kristal
a. Kristal yang sering (normal ditemukan dalam urin antara lain :
- Amorf urat, asam urat, calcium oxalate, calcium sulfat, ditemukan dalam suasana
asam
- Amorf fosfat, triple fosfat, calcium carbonate, calcium fosfat, ditemukan dalam
suasana alkalis.
b. Kristal yang mempunyai arti patologis / berasal dari katabolisme dalam
tubuh :
- Cystine berarti adanya defek dari tubulus (inborn metabolic defect) sehingga
reabsorbsi cystine, arginin, lisin, ornitin terganggu.
- Kolesterol : dijumpai pada nefritis, pielitis, radang kandung kemih, kiluria.
- Leucine dan tirosin : dijumpai pada penderita dengan penyakit yang berat.
- Bilirubin dijumpai pada kasus penyakit hati dengan bilirubinuria
- Kristal yang berasal dari makanan / obat-obatan dan seringkali menimbulkan
keluhan antara lain jengkol, sulfa.
URIN KHUSUS
By : dr. Banundari Rachmawati, SpPK
PENDAHULUAN
Urinalisis atau penmeriksaan urin merupakan salah satu indicator yang penting untuk
melakukan deteksi kelainan renal atau metabolic. Dapat juga digunakan untuk menegakkan
diagnosis dan memonitor hasil pengobatan penakit ginjal, traktus urinarius atau kelainan
metabolic yang lain.
Pemeriksaan urin terdiri dari urin rutin dan urin khusus. Pemeriksaan urin rutin adalah
pemeriksaan penyaring yang dilakukan tanpa indikasi khusus. Pemeriksaan urin khusus
adalah pemeriksaan urin atas darar indikasi, dengan kata lain permeriksaan urin khusus
diminta atau dilakukan sesudah dilakukan pemeriksaan urin rutin atau pemeriksaan
laboratorium lain. Sebagai contoh setelah diperiksa Dakar glukosa darah penderita hasilnya
tinggi, curiga terjadi ketoasidosis maka dapat diperiksa kadar keton dalam urinnya.
Pemeriksaan urin khusus ada bermacam-macam, seperti cara konvensional, menggunakan
tablet, tetapi yang paling sederhana, urah, mudah, dapat dilakukan penderita sendiri adalah
dengan dipstick/ tes strip atau carik celup. Dengan carik celup dapat diperiksa pH, protein,
berat jenis, glukosa (termasuk pemeriksaan urin rutin) maupun keton, bilirubink
urobilinogen, nitrit, eritrosit, lekosit dan lain-lain (urin khusus).
Dasar pemeriksaan carik celup adalah reaksi kimia pereaksi pada carik celup dengan urin.
Caranya dengan mencelupkan carik celup ke dalam urin yang akan memberikan
perubahan warna tertentu pada carik celup, ditunggu beberapa saat, sesuai petunjuk pada
leaflet, kemudian dicocokkan dengan standar warna. Kekuatan reaksi didasarkan atas
gradasi perubahan warna carik celup sehingga sangat penting untuk mengikuti petunjuk
yang ada pada leaflet agar didapatkan hasil yang akurat.
1. BENDA KETON
Benda keton merupakan hasil metabolism lemak dan asam lemak yang terdiri dari 3
bentuk yaitu :
-asam asetoasetat 20%
-aseton 2 %
-3 Hidroksi Butirat 78%
Asam aseto asetat dapat mengalami dekarboksilasi (ireversibel) menjadi aseton,
dan dapat berubah menjadi 3 hidroksi butirat (reversible). Pada orang normal,
metabolism benda keton berlangsung di hepar dan akan habis dimetaboliser untuk
energy pada respirasi normal, kerja otot jantung an kortek ginjal sehingga tidak akan
dijumpai benda keton di urin, tetapi pada keadaan di mana metabolism karbohidrat
terganggu sehingga energy utama didapatkan dari metabolism lemak, atau protein
maka akan terbentuk lebih banyak benda keton. Benda keton tersebut akan dibuang
lewat urin yang akan mengakibatkan ketonuria, bila kadarnya sangat tinggi akan
menyebabkan ketonemia. Asam aseto asetat akan mengalami dekarboksilasi
menjadi aseton dan akan dibuang lewat paru-paru, akibatnya nafas berbau aseton.
Indikasi Pemeriksaan Ketonuria
- Penderita DM terutama yang tidak terkontrol dengan baik ketonuria merupakan
pertanda terjadinya ketoasidosis yang data menyebabkan terjainya koma
diabetikum. Pada penderita DM dengan terapi oral yang sedang mengalami infeksi,
respons pengobatan oral tidak memuaskan sehingga kemungkinan terjadinya
ketonuria juga besar.
- Penderita asidosis : untuk mengetahui berat ringan asidosis atau memonitor hasil
pengobatan
- Penderita hamil
Deteksi ketonuria pada awal kehamilan sangat penting karena ketoasidosis
merupakan penyebab penting terjadinya kematian intrauterine.
1.1 Macam Ketonuria
1.1.1. Ketonuria diabetic
Dialami pada penderita diabetes mellitus yang
-mengalami ketosis atau ketoasidosis
-muda atau anak-anak
-mengalami infeksi
Perlu diperiksa pada penderita DM yang glukosa urinnya mencapai 1-2 g/dl
1.1.2. Ketonuria non diabetic
Terjadi pada :
-bayi atau anak dalam ekadaan toksik, panas tinggi, muntah atau diare hebat
-wanita hamil yang mengalami muntah obat
-kurang makan
-akibat penggunaan obat anestesi
-diit rendah karbohidrat dengan tinggi lemak
-pekerjaan fisik yang berat
1.1.3. Laktik asidosis
Terjadi pada :
-Penderita DM yang shock
-gagal ginjal
-gangguan hati berat
-infeksi
-penggunaan obat-obatan seperti penformin, salisilat
1.2 Pemeriksaan ketonuria
1.2.1. Cara carik celup
Pada pemeriksaan carik celup, hal-ha yang perlu diperhaitkan adalah sebagai
berikut :
- keton mudah menguap
- Menggunakan urin tanpa pengawet
- harus disertakan control negative atau positif
Dapat dipengaruhi obat :
- Insulin
- Ether
- Medformin
- Pyridium
- Phenformin
- Paraldehida dan sebagainya
Ciri reagen carik celup
- Reagen berisi Sodium Nitroferrisianida
- Kemampuan deteksi bervariasi ada yang dapat mendeteksi asam aseto asetat dan
aseton, ada yang hanya dapat mendeteksi asam aseto asetat dan aseton, ada yang
hanya dapat mendeteksi asam aseto asetat.
- Sensitivitas bervariasi ada yang dapat mendeteksi asam aseto asetat 5-10 mg/dl
dan 70 mg/dl aseton.
- Reagen sangat tidak stabil sehingga harus sering di ganti
1.2.2. Cara Konvensional
- Gerhard
Pemeriksaan cara ini hanya dapat mendeteksi asam aseto asetat, reagen berisi
ferriklorik dengan sensitifitas 2,5-50 mg/dl. Cara Gerhard kurang peka dibandingkan
cara Rothera, hasil dilaporkan sebagai positif atau negative. Tes positif bila hasil
akhir reaksi berwarna merah anggur.
Positif palsu bila urin mengandung :
* Fenol
* Salsilat
* Antipirin
* Natrium bikarbonat
- Legal
Reagen berisi Nitroferrisanida atau NItroprusid
- Tablet Nitroprusid
Tablet ini sangat peka terhadap suasana lembab, dapat digunakan untuk urin, serum
plasma dan whole blood.
- Rothera
Cara ini merupakan cara konvensional yang paling banyak dipakai, reagen berisi
NItroprusid dengan ssensitifitas 1-5 mg/dl asam asetoasetat dan 10-25 mg/dl
aseton, lebih peka jika dibandingkan cara Gerhard. Hasil dinilai sebagai positif dan
negative, positif bila terbentuk cincin berwarna merah ungu pada batas kedua
cairan.
1.3 Stabilitas keton dan dalam urin
- Adanya bakteri dalam urin akan menyebabkan asam asetat hilang
- Aseton dalam urin menguap pada temperature ruang sehingga sebaiknya disimpan
dalam tempat tertutup atau dimasukkan dalam almari es.
2. BILIRUBIN
Bilirubin dibentuk pada system retikuloendotel lien dan sumsum tulang dari
pemecahan hemoglobin. Ditemukannya bilirubin di urin menunjukkan adanya
gangguan hepatoseluler, intrahepatal atau obstruksi saluran empedu : ekstra
hepatal. Jumlah bilirubin dalam urin sesuai dengan berat ringan penyakit yang
mengakibatkan peningkatan bilirubin conjugatd (Direct). Pada keadaan normal
bilirubin tidak dijumpai (sangat sedikit dalam urin. Mekanisme terjadinya bilirubin urin
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
GAMBAR
Bilirubinuria terdapat pada :
- Obstruksi empedu
- Batu empedu
- Bilirunimenia
- Ikterus parenkimatosus oleh obat atau virus
- Kolestasis oleh karena obat
- Hepatitis alkoholik
2.1. Pemeriksaan laboratorium
Syarat umum
- Urin segar
Karena bilirubin tidak tahan sinar matahari, dan akan pecah karena proses oksidasi
dan hidrolisis, sehingga akan menyababkan hasil negative palsu
- Segera diperiksa
Ada 2 macam pemeriksaan bilirubin :
2.1.1. Tes strip / carik celup
- Dasar reaksiDiazo
- Terdapat bermacam-macam merek
- Sensitifitas : 0,5-0,8 mg / dl
- Dipengaruhi oleh :
Vitamin C dan Nitrit yang akan menyebabkan negative palsu
Rifamicin dan Chorpromazin akan menyebabkan positif palsu
2.1.2. Tes konvensional
- Diazo tablet
- Menggunakan reagen Ictotest
- Sensitifitas : 0,05-0,1 mg/dl
- Rosin
- Busa
- Fouchet/Harrison (praktikum)
3. UROBILINOGEN
Bilirubin bebas akan berubah menjadi :
- Urobilinogen
- Mesobilirubin
- Sterkobilin
Pemeriksaan urobilinogen dalam urin dapat mendeteksi kelainan hepar, hemolytic
disease dan obstruksi empedu. Di samping itu juga dapat membantu memantau
perkembangan penyakit dan terapi.
Nilai rujukan : 0,5 – 2,5 mg/24 jam.
Meningkat pada :
- Penyakit hati oleh karena :
Virus
Toksik
Cirrhosis
- Destruksi eritrosit berlebihan
Anemi hemolitik
Ikterus hemolitikus
Anemi pernisiosa
Malaria
- Penyakit jantung kongestif
- Infectious mononucleosis dan lain-lain
Menurun atau tidak dijumpai pada :
- Xholelithiasis
- Kanker caput pancreas
- Ikterus obstruktivus
3.1. Pemeriksaan laboratorium
Syarat : urin segar, urobilinogen labil pada urin asam atau cahaya
3.1.1. Carik Celup
- Tidak spesifik
- Positif palsu pada pemakaian obat-obatan :
Phorfobilinogen
PAS
Antipyrn
Phenothiazin
Bromsulphothalen
Sulfonamide
Aspirin
Procain
Metildopa
3.1.2. Metode konvensional
- Erlicn (Watson Scwartz)
- Urobilinogen cahaya urobilin (tes sclesinger)
- Wallace Diamond
Semikuantitatif
Positif : terbentuk warna merah, harus dibaca paling lama 5 menit
Bilirubin akan menganggu reaksi sehingga harus dihilangkan dengan
menambahkan kalsium hidroksida.
Catatan :
Kadar puncak pada pukul 14.00 – 16.00
Bila penderita minum antibiotika, flora usus akan mati dan urobilinogen tidak
akan terbentuk.
4. NITRIT
Ada dua macam cara untuk mendeteksi adanya bakteri dalam urin yaitu
berdasarkan pemeriksaan mikroskop sedimenuri dan dengan pemeriksaan nitrit
menggunakan carik-celup. Nitrit positif berarti terdapat bakter pemecah nitrat dalam
urin seperti tampak pada reaksi dibawah ini :
GAMBAR
NItrat ^(Ensim bakteri :, E xolli, enterobacter, Klebsia, proteus) Nitrit
Pemeriksaan laboratorium
Carik celup
Syarat
- Urin sear, segera diperiksa
- Urin pagi pancaran tengah
- Sensitifitas : 0,05 – 0,75 mg/dl
- Bila pemeriksaan nitrit positif harus dilakukan kultur untuk mengetahui jenis kuman.
- Bila hasil negative tidak berarti bakteri negative
- Bila hasil negative tidak berarti bakteri negative
- Positif palsu ole karena obat-obatan seperti phenazopyrimidine
- Negative palsu disebabkan karena :
Vitamin C
Kadar urobilinogen urin tinggi
pH urin asam < 6
Nitrat ^bakteri, Nitrit nitrogen
Urin kurang dari : 4 jam berada di vesica urinaria
- Negative pada :
Urin tidak mengandung nitrat
Bakteri tidak mengandung nitrat
5. SEL DARAH MERAH
Darah dalam urin biasanya dalam bentuk utuh tetapi dapat terhemolisir sehingga
kadang-kadang tidak dapat terdeteksi pada pemeriksaan mikroskopis. Ada3 macam
sel darah merah dalam urin :
1. Hematuria
Hematuraia adalah dijumpainya sel darah merah intact pada urin biasanyakarena
perdarahan pada tracctus urinarius (dapat diperiksa secara mikroskopis).
Hematuria palin sering terjadi dibandingkan dengan heoglobinuria atau
mioglobinuria. Dijumpai pada keadaan : (trauma, iritasi batu, infeksi akut, infark
radiokard, keganasan, hipertensi, Glomerulonefritis, ginjal poliksitik, obat zat
nefrotoksik, exercises yang berlebihan).
2. Hemoglobinuria
Hemoblobinuria adalah dijumpai hemoglobin bebas dalam urin. Biasanya
menggambarkan keadaan di luar tractus urinarius, seperti terjadinya hemolisis
eritrosis yang berlebian sehingga RESS tidak dapat memetabolisir hemoglobin
bebas. (tidak terdeteksi dengan pemeriksaan mikroskopis).
Penyebab :
- Hemolisis intravaskuler
- Urin encer dengan pH alkali
- Urin terlalu lama pada temperature ruang
- Berat jenis < 1,010 akan menyebabkan SDM lisis
Dijumpai pada keadaan :
- Luka bakar
- Reaksi transfuse
- Panas tinggi
- Kimia dan alkaloid seperti bias ular atau jamur beracun
- Malaria
- Irigasi dengan air pada operasi prostat
- Anemi hemolitik
- Paroksismal hemoblobinuria
- Exercise berlebihan
- Trauma langsung pada pembuluh darah
Penyebab kematian dan hemoglobinuria
- Trauma pad sel darah merah oleh karena exercises yang berlebihan, trauma
otot atau pembulluh darah.
- Malaria, C. Welchii
- Defisiensi enzim lucosa 6 phosphat Dehidrogenase
- Uniable hemoglobin disease
- Obat oksidan
- Imun : Warm dan cold antibodi
3. Mioglobinuria
Mioglobinuria adalah dijumpainya mioglobin dalam urin, kejadiannya sangat
jarang (Tidak dapat terdeteksi dengan pemeriksaan makroskopis)
Dijumpai pada keadaan :
- Trauma otot berat seperti pada kecelakaan mobil, sepak bola, tersengat
listrik.
- Muscular dystrophy
- Keracunan mono-oksida atau ikan
Pemeriksaan laboratorium adanya SDM dalma urin
Syarat : sampe urin homogeny
a. Tes strips / carik cellup
- Dapat mendeteksi hematuri, hemoglobinuria dan mioglobinuria
- Sensitifitas : 0,05 – 0,3 mg Hb/dl urin
- Akan berkurang pada keadaan (reagen lama, BJ alkali, Proteinuri berat)
- Negatif palsu karena (vit C, Formalin)
- Positif palsu karena ( detergent, ISK oleh karena kuman penghasil
peroksidase, obat-obatan yang nefrotoksik seperti bacitrasin dan
amphotericin, obat yang menyebabkan perdarahan seperti coumarin, obat
yang menyebabakan hemolisis SDM seperti aspirin)
b. Benzidine test
- Sangat sensitive sehingga sering terjadi positif palsu
- Possitif palsu oleh karena : (Iodida, asam nitrat, Formalin)
- Negatif palsu karena (Vitamin C, H2O2 lama)
- Reagen lama
c. Hematest
- Reagen berbentuk tablet untuk pemeriksaan darah samar
- Kurang sensitive
- Positif bila SDM urin 200/LPB dimana < 10 % nya sudah lisis
- Positif palsu pada sama dengan pada penggunaan tes strips
6. SEL DARAH PUTIH
- Pada urin khusus ini yang dibahas bukan sel darah putih mikroskopis terapi adala
darah putih yang mempunyai aktiitas esterase dan diperiksa dengan menggunakan
tes strips/carik celup.
- Konfirmasi tes : pemeriksaan sedimenuri (mikroskopis)
- Sampel : urin pagi porsi tengah
- Positif palsu bila urin terkontaminasi dengan cairan vagina. Dapat dilihat pada
pemeriksaan sedimenuri akan dijumpai epitel squamous berlebihan dan bakteri, atau
karena adanya zat okidator.
- Tes strips akan memberikan hasil positif sesuai dengan jumlah SP dan tidak
bereaksi terhadap SDM atau epitel
- Negatif palsu karena :
Vitamin C
Formalin
Nitrofurantoin
7. PROTEIN
Proteinuri dapat diperiksa dengan cara (gambar 3)
Pada tuisan ini hanya dibahas untuk pemeriksaan urin khusus
Normal : proteinuri sampai 150 mg/24 jam
Proteinuria terdiri dari :
- Albumin
- Glikoprotein tamm hosfall (normal disekrei olehtubulus ginjal)
- Globulin
Macam pemeriksaan proteinuri khusus
7.1. Kadar
- Bila hasil pemeriksaan urin rutin , proteinuri > positif 1
- BIla hasil +3 atau +4 maka urin harus diencerjkan dulu 2,4 atau 8 kali
- Cara : Esbach dengan tabung Esbach, Spektrofotometer
- Sampel : urin tampunf 24 jam dan bereaksi asam
7.2. Fraksi/ jenis protein
- Indikasi sindroma nefrotik, myeloma multiple)
- Syarat sampel harus dipekatkan
- Cara : Elektroforesis (terdiri dari : Tamm Horsfali, Albumin, alfa 1,2, beta, gama
globulin), teknik imunologi (untuk proteinuri selektif seperti : transferin, albumin
(protein dengan berat molekul kecil)).
Catatan : proteinuri non selektif, di mana yang dieksresi protein dengan berat
molekul besar dan kecil.
7.3. Protein abnormal Bence Jones
- Protein bence jones merupakan protein endogen abnormal
- BM kecil sekitar 44.000
- Terdiri dari rantai kappa tanda immunoglobin
- Diproduksi sel plasma oleh karena keganasan
- Sifatnya : larut pada temperature kamar dan mendekati mendidih tetapi mengendap
pada suhu 40-60 oC
- Dijumpai pada : Mieoma multiple (35 – 80 % kasus), pada stadium akhir disertai
slinderuria, proteinuria dan hiperkalsiuri, limfoma, leukemi, makroglobulinemia,
amiloidosis, keganasan tulang.
8. NATRIUM
Natrium berperan pada regulasi asam basa bersama-sama dengan klorida dan
bikarbonat, juga pada keseimbangan elektrolit intrasel dan ekstrasel bersama-sama
dengan kalium. Pemeriksaan Natrium urin biasanya diminta kalau ada gangguan
reabsorbsi tubulus. Kadarnya dipengaruhi intake, penguapan dan adanya gangguan
traktus gastorintestinalis.
Pemeriksaan laboratorium
- Metode fantus
- Flame fotometer
- Sampel :urin tampung 24 jam
Kadarnya meningkat pada :
- Dehidrasi
- Kelaparan
- Keracunan salisilat
- Insufisiensi korteks adrenal
- Diuretic yang mengandung chlorothiazid dan mercuri
- Gagal ginjal kronik
- Diabetic asidosis
9. CHLORIDA
Penetapan chloride dalam klinik sering dipakai jika ingin memonitor pengeluaran
chloride dari hari ke hari. Penetapan ini menggunakan sampel urin 25 jam dengan
memakai metode. Fantuds dengan cara titrasi menggunakan perak nitart dan ion
khromat sebagai indicator.
10. CALSIUM
Normal ekskresi kalsium : 50 – 300 g/24 jam
Pengaturannya dilakukan oleh paratiroid dan dipengaruhi oleh intake dan keadaan
tulang
Pemeriksaan laboratorium
- Tes sukkowitch
- Fame fotometer
Sampel urin tampung 24 jam
Kadarnya meningkat pada :
- Hiperparatiroid
- Hipertiroid
- Myeloma multiple
- Tumor tulang
- Sindroma fanconi
- Batu ginjal
- Keracunan vitamin D
Menurun pada :
Hipoparatiroid
11. VMA (VANILYL MANELIC ACID – Asam Vanilil mandelik)
Pemeriksaan VMA diminta biasanya untuk mengetahui fungsi medulla adrenal pada
penderita hipertensi yang diduga disebabkan oleh pheochromocytoma atau tumor
pada medulla adrenal. VMA merupakan hasil metabolism katekolamin.
Pemeriksaan laboratorium :
Dengan cara thin layer chromatography
Sampel : urin tampung 24 jam
Normal : sampai 9 mg/24 jam
Meningkat pada :
- Pheochromositoma
- Neuroblastoma
- Ganglioneuroma
- Ganglioblastoma
Hal lain yang dapat meningkatkan kadar VMA :
Makanan dan minuman : (the, kopi, coklat, vanilla, nanas, keju dan lain lain)
Obat-obatan : (aspirin sulfa, oksitetrasiklin, gliseril guayakolat dan lain-lain)
12. MELANIN
Pada penderita melanoma yang meluas dan menyebar mengeluarkan semacam
derivate indol (melanogen) ke dalam urin (tidak berwarna hitam) yang dapat
berpolimerisasi menjadi melanin yang berwarna hitam.
Pemeriksaan laboratorium
- Tes thormalen menggunakan larutan natrium nitroprusid daam KOH 10%
- Tes strips
13. FENILKETONURIA
Pemeriksaan fenilketonuria dilakukan pada bayi untuk mendeteksi kemungkinan
terjadinya retardasi mental bila tidak di terapi. Penderita ini tidak mempunyai enzim
fenilalanin hidrokilase yang dihasilkan hati sehingga fenilalanin (yang berasal dari
makanan) tidak dapat diubah menjadi tirosin. Akibatnya jumlah di dalam darah
meningkat dan akan dibuang di urin. Pada keadaan normal fenilalanin tidak dijumpai
di urin.
Pemeriksaan laboratorium
- Tes ferrichlorida
- Tes strips
Sampel urin segar.
IMUNOLOGI DASAR
By :
Dr. Lisyani B. Surono, SpPK (K)
PENDAHULUAN
Pengertian istilah :
- Imunitas : dulu imunitas diartikan sebagai proteksi / perlindungan terhadap penyakit
khususnya infeksi. Sekarang diketahui bahwa mekanisme proteksi yang merupakan
respons normal tersebut ternyata dapat menyebabkan sakit, maka respons imunitas
merupakan reaksi tubuh terhadap masuknya substansi asing.
- Respons imun : meruakan kumpulan respons terdapat substansi asing yang
terkoordinasi
- System imun : merupakan sel dan molekul (yang larut) yang bertanggung jawab di
dalam imunitas.
- Imunologi : dalam arti modern merupakan suatu experimental science di mana
fenomena imunologik didasarkan atas penelitian experimental dan kemudian dibuat
kesimpulan daripadanya.
Suatupenyakit dapat berjalan akut kronis, laten, asimtomatik. Suatu infeksi dapat ditularkan
dari sorang ke orang lain termasuk dari ibu ke anak yang dikandungnya sehingga dapat
menimbulkan keguguran, cacat bawwaan. Suatu infeksi juga dapat menetap di dalam tubuh
individu bahkan dapat pula mengubah wujud atau fungsi suatu sel tubuh sedemikian
sehingga memungkinkan terjadinya penyakit autoimun atau keganasan. Banyak macam
pemeriksaan laboratorium khususnya laboratorium imunologi dapat dikerjakan untuk
menunjang / mengetahui/ memantau keadaan-keadaan tersebut di atas, untuk dapat
melakukan pemilihan terdapat macam pemeriksaan secara tepat, perlu dipelajari aspek
imunologik yang perlu diawali dengan pengetahuan dasar imunologi.
Lingkungan hidup kita terdiri dari bermacam-macam antigen asing / penyebab infeksi
seperti virus, bakteri, fungi, parasit.
Tubuh memiliki system pertahanan terhadap masuknya antigen tersebut yang dapat berupa
:
- Factor-faktor yang larut
- Sel/kumpulan sel (jaringan) yang tersebar di seluruh tubuh.
DIbedakan 2 macam system imun yaitu :
1. System imun bawaan (the innate immune system): dapat menimbulkan respon
imunologik non spesifik
2. System imun diperoleh (the adaptive/acquired immune system) : dapat menimbulkan
respons imunologik spesifik.
1. System Imun bawaan :
Sebelum antigen asing berhasil masuk, tubuh berusaha mencegahnya dengan
cara :
a. Mekanik/fisik a.l.:
- Kulit yang utuh, sukar untuk ditembus
- Sel bersilia misalnya pada saluran pernafasan menolak masuknya antigen
- Sel mukosa yang menghasilkan lendir
b. Biokimia a.l.:
- Sekresi kelenjar keringat
- Lisosim – suatu enzim yang terdapat pada air mata, saliva, telinga, dst. Berfungsi
mencegah ikatan pada dinding sel dari bermacam-macam bakteri.
- Organism komensal pada usus dan vagina.
- Spremin dalam semen
Apabila kemudian antigen berhasil masuk, maka tubuh juga memiliki pertahanan
pertama dari system imun bawaan ini yang terdiri dari :
Factor-faktor yang larut antara lain :
a. C-reactive protein (CRP)
Yaitu suatu acute phase protein yang kadarnya akan naik sampai 100 x lipat pada
adanya infeksi akut/kerusakan jaringan dan tetap naik selama infeksi berlangsung
CRP disintesis oleh sel-sel hati. Penetapan kadar CRP dipakai untuk menunjang
keadaan tersebut dan memantau perjalanan penyakit.
Fungsi CRP :
CRP akan melapisi bakteri kemudian mengaktivasi komplemen sehingga dengan
demikian menaikkan penangkapan bakteri oleh fagosit. Proses dimana CRP
melapisi bakteri / fungi sehingga menyebabkan suasana yang menyenangkan bagi
proses fagositosis disebut opsonisasi.
b. Interferon
Dihasilkan oleh sel tubh yang terinfeksi oleh virus
Fungsi interferon :
- Mengaktivasi sel natural killer (NK) untuk membunuh virus tersebut.
- Membuat sel-sel jaringan disekitar sel yang terinfeksi menjadi resisten terhadap
virus tersebut, dengan demikian virus tidak tersebar.
c. Transferin, laktoferin : dapat mengurangi / mencegah pertumbuhan bakteri.
d. Komplemen
Terdiri dari banyak kompleks protein yang berbeda satu denagn yang lain, tetapi
berkaitan kerjanya/saling mengaktifkan satu terhadap yang lain seperti halnya
system pembekuan darah. Kompleks protein tersebut secara fungsional diwujudkan
dalam 9 (Sembilan) komponen komplemen dengan kode nama sebagai berikut : C 1
= q, r, s; C 2 = a, b; C 3 = a, b; C 4 = a, b; C 5 : a, b; C 6; C 7; C 8; C 9.
Konsentrasi C3 dibandingkan dengan lain-lainnya adalah paling banyak, dengan
demikian pengukuran kadar C3 di dalam serum merupakan gambaran biologic dari
seluruh konsentrasikomplemen. Defisiensi C3 menyebabkan infeksi mudah kambuh /
mudah terjadi septicemia. Urutan kode angka adalah sesuai dengan urutan
penemuan komponen tersebut, bukan menurut cara kerjanya. Normal komplemen
beredar dalam darah dalam keadaan tidak aktif.
Aktivasi terjadi bila :
- Ada interaksi antara antigen – antibody, biasanya dari kelas Ig G/ Ig M dimana lg M
mempunyai daya ikat terhadap komplemen lebih besar dari IgG.
- Kontak dengan dinding sel sasaran (terjadi lisis spontan melalui jalur alternative)
Ada 3 jalur reaksi dalam system komplemen :
a. Jalur klasik (jalur intrinsic)
Secara garis besar reaksi komplemen melaluijalur kalasik terdiri atas bebearapa
mekanisme yaitu :
- Pengenalan
Merupakan proses pengikatan C1q pada fragen Fc dari antibody yang
melapisi sel darah merah disusul dengan pengikatan C1r dan C1s untuk
membentuk C1qrs (esterase).
- Aktivasi
C1esterase kemudian :
1. Mengaktivasi C4 dan menguraikannya menjadi fragmen C4a yang tidak
aktif dan C4b. kemudian melekat pada permukaan sel darah merah
tersebut sedangkan C4a yang tidak aktif bergerak bebas di sekeliling sel
atau di larutan yang mengandung sel yang tidak disensitasi.
2. Menguraikan C2 menjadi C2 aktif dan C2 tidak aktif. C2 aktif melekat pada
C4b membentuk C4b2a yang bersama ion Mg membentuk kompleks C3
konvertase yang merupakan ensim yang bersifat proteolitik. C3 konvertase
memecah C3 menjadi fragmen C3a dan C3b. C3b kemudian melekat pada
kompleks antigen antibody pada permukaan sel darah merah membentuk
C4b-2a – 3b yang akan menghasilkan C3 peptidase. C3 peptidase akan
menguraikan C5 menjadi C 5a dan C 5b. C 5b merupakan titik tolak
pemecahan sel darah merah. C5a bersama-sama dengan C3a berada
bebas dalam serum dan mempunyai fungsi biologic yang lain.
- Penghancuran
Fragmen C5b yang aktif akan mengaktivasi / mengikat komponen berikutnya
yaitu C6 dan C7 membentuk C 5-6-7 akan mengikat molekul C8. C5-6-7-8-yang
menimbulkan kerusakan pada membrane sel disertai lisis yang terjadi secara
berlahan-lahan. Selanutnya molekul C5-6-7-8 mengikat lagi 6 molekul C9 yang
menyebabkan lisis sel dipercepat (hemolisis).
b. Jalur alternative (jalur ekstrinsik)
Disini proses lisis terjadi tanpa peristiwa respons imunologik spesifik.
Komplemen tidak diaktifkan mulai dari komponen C1 tetapi langsung melalui C3.
Beberaa substansi biokimia dapat menjadi factor pencetus terjadinya jalur
alternative ini antara lain :
- Endotoksin (lipopolisakarida dinding sel bakteri gram negative)
- Zymosin (poliskaarida dinding sel ragi)
- Antibody kelas immunoglobulin yang tidak dapat mencetuskan jalur klasik misalnya
Ig A
- Bias ular kobra
Dalam keadaan normal, konstan dan dalam jumlah sedikit C3 mengalami
hidrolisis spontan menjadi C3a dan C3b. jalur alternative teraktivasi bila molekul
C3b terikat pada suatu sasaran. Ikatan ini kemudian berkombinasi dengan
plasma protein factor B. bila factor B terikat dengan C3b maka oleh plasma
protein factor D, factor B tersebut dipecah menjadi 2 fragmen yaitu Bad an Bb,
kemudian factor Bb akan tetap terikat pada C3b embentuk komplek C3bBb.
Komplek C3bBb ini bertindak seperti C4b aktif atau C3K konvertase pada jalur
klasik.
c. Jalur lektin (lectin pathway)
Jalur ini dipicu oleh suatu protein plasma yang disebut mannose binding lectin
(MBL) yang mengenal residu manose terminal pada glikoprotein dan glikolipid
milik mikroba. Ikatan MBL dengan mikroba mengaktifkan komplemen dari jalur
klasik tanpa adanya antibody.
Disamping fungsi sistolik komplemen mempunyai fungsi biologic lain, misalnya :
- Anafilatoksin : C3a, C4a dan C5a merupakan anafilatoksin yang dapat :
a. Melepaskan histamine dari basofil dan mast cell yang akan meningkatkan
permeabilitas kapiler dan memudahkan kompleks komplemen antibody serta sel
darah putih masuk ke dalam jaringan di mana terjadi reaksi imun.
b. Menyebabkan agregasi trombosit yang dapat mengakibatkan terjadinya
disseminated intravascular coagulation (DIC).
- Kemotaksis : C3a , C5a dan C5-6-7 yang menyebabkan sel darah putih berkumpul ke
tempat berlaangsungnya reaksi imun sehingga dapat meningkatkan proses
fagsitosis.
- Kinin : C2 bebas akan meningkatkan permiabilitas kapiler
- Immunoadherens : sel-sel netrofil, makrofag, trombosit, limfosit B mempunyai
resepto : terhadap C3b, dan C4b sehingga sel-sel tersebut menggumpal bila pada
permukaannya melekat komponen komplemen tersebut.
Disamping adanya factor-faktor yang “membantu” rangkaian kerja komplemen terdapat
pula factor-faktor yang menghambat aktivitas komplemen, misalnya ;
- C1 esterase inhibitor, menghambat C4a
- Inaktivator C3b, menguraikan C3b menjadi fragmen-fragmen yang tidak aktif
- Inaktivator anafilatoksin – menghaambat aktivitas biologic C3a, C4a, dan C5a
- Inaktivator C5, C6, C7 dan C5-6-7
Kumpulan sel-sel :
Terdiri dari sel NK, fagosit (segmen netrofil, segmen eosinofil, monosit/makrofag) sel
basofil. Bersama dengan factor-faktor yang larut, sel-sel tersebut dapat melakukan
respon imunologik non spesifik sebagai berikut :
1. sel NK
merupakan sub populasi sel limfosit (dari populasi sel Null). Sel NK yang memiliki
sifat sitotoksik dapat mengenali perubahan pada permukaan sel yang terinfeksi
oleh irus atau yang menjadi ganas, kemudian membunuhya. Sel NK ini diaktivasi
oleh interferon.
2. fagositosis
berperan dalam proses fagositosis yaitu fagosit dari system retikuloendotel.
Fagosit yang dimaksud yaitu makrofag/monosit, segmen netrofil PMN, segmen
eosinofil. Fungsi fagosit terhadap partikel antigen sasaran yaitu memakan,
memasukkannya ke dalam badan fagosit dan menghancurkannya.
Untuk dapat melakukan fagositosis maka fagosit dibantu oleh :
- komponen komplemen
C3a, C5a, dan C5-6-7 yang bersifat kemotaksis sehingga fagosit bergerak
menuju ke arah sasaran.
C3b : fagosit mempunyai reseptor terhadap C3b pada permukaannya.
Perlekatan C3b pada partikel / antigen sasaran tersebut sehingga melekat
padanya.
- opsonin/ immunoglobulin yang melapisi permukaan antigen sasaran
sehingga mudah difagositosis. Di samping factor factor yang meningkatkan
proses fagositosis terdapat pula factor-faktor yang menghambatnya yaitu
inaktivator factor kemotatik dan inhibitor leukotaktil.
3. reaksi inflamasi
adalah reaksi tubuh terhadap masuknya penyebab infeksi yang ditandai dengan
kenaikan :
- supply pembuluh darah pada daerah terinfeksi
- permeabilitas kapiler disebabkan karena retraksi sel-sel endotel yang
memungkinkan mediator-mediator tertentu menembus endotel tersebut.
Mediator-mediator imunitas ini dilepaskan oleh beberapa jenis sel antara lain
:
# basofil yang melepaskan histamine
# trombosit yang melepaskan vaso-active amine
- Migrasi sel darah putih teruama PMN (juga sedikit makrofag) kea rah lokasi
masuknya antigen sebagai akibat pelepasan mediator tersebut.
2. System imun diperoleh (the acquired/adaptive immune system)
Imunitas dalam system ini dapat diperoleh secara :
- Aktif : badan secara aktif membuat antibody sendiri, contoh :
# Setelah tubuh terinfeksi atau sembuh dari suatu penyakit
# Imunisasi aktif
- Pasif : badan tidak membuat antibody sendiri contoh :
# Diperoleh bayi dari ibunya melalui plasenta / ASI
# Lewat imunisasi pasif
Dasar dari system ini diperoleh adalah :
A. Ingatan (memori
B. Spesifitas (specificity)
Ingatan tersebut adalah spesifik terhadap jenis antigen yang masuk ke tubuh
tersebut dan tidak memberikan perlindungan terhadap jenis antigen yang lain.
Contoh : seseorang yang sembuh dari penyakit campak akan menjadi imun
terhadap serangan virus campak berikutnya tetapi tidak terhadap virus polio /
parotitis.
C. Distribusi kedua hal di atas (ingatan spesifik) setelah suatu respons yang terjadi
local kemudian akan menimbulkan imunitas (antara lain antibody) yang tersebar
ke seluruh tubuh.
Antigen :
Merupakan molekul kimia yang terdapat pada permukaan badan virus bakteri dan
seterusnya mempunyai sifat :
- Dapat melekatkan antibody secara selektif pada yang disebut antigenic determinant,
bagian structural(epitop) molekul antigen tersebut.
- Dapat merangsang pembentukan antibody.
Antigen yang memiliki kedua sifat tersebut disebut sebagai imunogen.
Antigen yang “baik” mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
1. Berat molekul : makin besar makin tinggi sifat antigeniknya.
Protein dengan BM > 40.000 merupakan antigen yang baik, sedangkan BM <
10.000 merupakan imunogen yang lemah atau tidak bersifat imunogen sama
sekali. Sifat antigen dapat dipertinggi dengan pemberian adjuvant misalnya
partikel carrier latex.
2. Kekakuan struktur : antigen yang mempunyai bentuk tetap (non flexible) akan
lebih bersifat antigenic.
3. Keasingan molekul : makin asing makin bersifat antigenic.
4. Larut/tidak :
- Immunogen yang larut : akan cepat menginduksi pembentukan antibody.
- Antigen yang tidak larut : mula-mua di fagositosis oleh makrofag menjdai fragmen
imunogenik yang terus bergabung dengan human leucocyte antigen (HLA) yang ada
pada makrofag sebelum di transfer ke limfosit.
5. Cepat / tidaknya dihancurkan oleh sel-sel tubuh.
6. Jumlah antigen : jumlah yang optimal akan membentuk antibody yang cukup
tinggi.
Dikenal beberapa jenis antigen antara lain :
- Antigen heterofil/heterogenic : antigen non spesifik yang terdapat pada berbagai
macam spesies hewan dan tumbuhan.
- Forsman antigen : antigen heterofil yang terdapat pada beberapa spesies tertentu.
- Antigen isogenik / alogenik : berasal dari hewan atau individu lain dengan jenis yang
sama.
- Antigen heterologus : dari individu denagn spesies berbeda.
- Self antigen : self antigen yang dianggap asing oleh tubuhnya sendiri
- Not self antigen : berasal dari luar tubuh
- Organ specific antigen : dikandung oleh organ tertentu di dalam tubuh
- Autoantigen : antigen tubuhnya sendiri yang dapat menimbulkan respons imun.
Selain antigen dikenal pula :
- Hapten : zat dengan BM rendah, mempunyai struktur molekul tertentu, tidak bersifat
antigenic/imunogenik tetapi dapat bereaksi dengan antibody. Hapten dapat
merupakan antigen apabila dikonjugasikan dengan protein hapten carrier. Gabungan
tersebut disebut sebagai compound antigen yang dapat bertindak sebagai imunogen
antibody yang ditimbulkannya dapat bereaksi dengan molekul hapten murni, tetapi
compound antigen tersebut tidak dapat menjadi carrier hapten lain.
- Allergen : suatu antigen yang dapat menimbulkan antibody khusus yang disebut zat
regain dengan akibat yang tidak menguntungkan tuan rumah yaitu timbulnya reaksi
hipersensitivitas. Di samping itu allergen juga dapat menyebabkan inaktivasi atau
blockade terhadap sel-sel imunitas sehingga timbul toleransi.
Respons imunologik spesifik : dimulai dengan aktivitas makrofag (antigen presenting
cell) yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimblkan
interaksi dengan sel-sel system imun (tersensitasi). Sel-sel system imun kemudian
berubah bentuk (transformasi), berproliferasi dan berdiferensiasi hingga menjadi sel
yang memiliki kompotensi imunologik dan mampu meniadakan antigen. Ada 3 (tiga)
macam respons imunologik spesifik yaitu :
- Respons imunologik seluler
- Respons imunologik humoral
- Interaksi antara respons imunologik seluler dengan respons imunologik humoral
yaitu yang disebut antibody dependent cell mediated immune responds.
Berperan dalam respon immunologic spesifik ini ialah limfosit, sel ini mempunyai
fungsi untuk mengatur dan bekerja sama dengan sel-sel lain dalam system
retikuloendotel untuk menibulkan respons imunmologik spesifik.
Di dalam jaringan yang tergolong jaringan limfoid primer (timus dan sumsum tulang),
limfosit berproliferasi dan berdifernsiasi tanpa ketrergantungan pada antigen,
sedangkan dalam jaringan limfoid sekunder (kelenjar limfe, limpa, jaringan limfoid
dalam dinding usus), limfosit berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel efektor
serta menyusun sel yang memproduksi antibody atas rangsangan antigen.
Macam populasi limfosit :
a. Limfosit T(berperan dalam respons imunologik seluler)
Diferensiasi stem cell kea rah sel-sel limfoid yang kompeten berperan dalam
respons imunologik seluler, selama perkembangannya berada di bawah
pengaruh kelenjar timus. Sel-sel limfoid tersebut dapat dipengaruhi secara
langsung oleh epitel timus ataupun lewat hormone timosin untuk kemudian
bberubah menjadi sel limfosit T. bila terjadi kontak dengan antigen asing, maka
limfosit T berproliferasi dan berdiferensiasi lagi menjadi specifically sensitized
lymphocyte cell (SSLC), yang segera memperlihatkan aktivitas imunitas
selulernya.
Lokasi limfosit T ; lien dan kelenjar limfe yaitu pada masing-masing daerah
periorterioler, parakortikal dan perifolikuler.
Jumlah ±65 % - 85 % daripada total limfosit dalam darah.
Ciri-ciri:
- Ukuran kecil
- Permukaan rata
- Jumlah villi pada permukaan sedikit
- Dapat membentuk rosette dengan sel darah merah domba.
Jenis – jenis Limfosit T / SSLC antara lain
T-efektor/ T-sitotoksik : dengan masuknya antien, limfosit T berproliferasi
dan berdiferensiasi menjadi sel T efektor / T sitotoksik yang dapat
menghancurkan antigen secara langsung atau dengan cara
mengeluarkan limfokin.
T-Penolong (helper)
T-Penekan (suppressor), sel ini berfungsi untuk mengatur aktivitas sel T
efektor dan juga mengatur produksi antibody oleh sel limfosit B / sel
plasma.
b. Limfosit B (berperan dalam respon imunologik humoral)
Diferensiasi stem cell menjadi sel-sel limfoid yang kompeten berperan dalam
respons imunologik humoral selama perkembangannya dipengaruhi oleh suatu
organ yang pada burung disebut bursa fabricius, sedangkan pada manusia
diduga pada sumsum tulang dan yang termasuk system gut associated lymphoid
tissues seperti misalnya tonsil, usus buntu dan seterusny. Sel limfoid ini
kemudian berkembang menjadi sel limfosit B. bila terjadi kontak dengan suatu
antigen asing sel ini akan melanjutkan diferensiasinya menjadi sel-sel plasma
yang matang dan sanggup memproduksi antibody serta mensekresikannya ke
dalam sirkulasi darah.
Lokasi limfosit B :
- Lien pada daerah sentrum germinal
- Kelenjar limfe pada daerah sentrum germinal, antara kortek-medula dan medulla
Jumlah : 10 % - 15 %dari total limfosit dalam darah.
Ciri-ciri :
- Ukuran sedang/besar
- Permukaan kasar mengandung immunoglobulin
- Jumlah villi lebih banyak
- Tidak membentuk rosette dengan sel darah merah domba
Jenis : :omfosit B juga merupakan populasiy ang heterogen, terdiri atas subpopulasi
yang masing-masing dapat membentuk suatu kelas antibody terhadap antigen
tertentu, dengan demikian terdapat banyak jenis sel limfosit B dengan spesifitas
yang berbeda-beda.
Fungsi : limfosit B memproduksi immunoglobulin (Ig). Bila Ig bereaksi dengan
antigen, maka akan membentuk kompleks antigen-antibodi yang berada bebas
dalam sirkulasi serta melekat / mengendap pada permukaan sel yang mengandung
antigen tanpa menghan curkan antigen tersebut denagn bantuan komplemen
barulah antigen dapat dihancurkan..
c. Limfosit non T – non B (sel null)
Populasi sel null dapat dibedakan lagi menjadi :
- Sel killer (K) berperan dalam interaksi respons imunologik seluler dan humoral. Sel K
mempunyai kemampuan untuk membunuh sel sasaran yang permukaannya dilapisi
oleh antibody tanpa melibatkan komplemen. Reaksi ini disebut : antibody dependent
cell-mediated cytotoxicity. Sel K tidak memiliki spesifisitas terhadap sel sasaran.
Pada permukaan sel K terdapat reseptoruntuk immunoglobulin tersebut.
- Sel NK (natural killer) : berperan dalam system imun bawaan.
IMUNOBLOBULIN (Ig)
Secara kolektif molekul antibody merupakan suatu protein yang disebut immunoglobulin.
Immunoglobulin dibentuk oleh sel-sel plasma yang berasal dari limfosit B. tiap sel plasma
hanya membentuk satu jenis immunoglobulin yaitu satu tipe rantai berat (heavy-chain) dan
satu tipe rantai ringan (light – chain).
Suatu populasi sel plasma yang berasal dari satu clone akan membentuk immunoglobulin
yang sama (homogeny) dan disebut immunoglobulin monoclonal. Pada umumnya
immunoglobulin yang ada dalam serum merupakan immunoglobulin poliklonal yaitu
berasala dari berbagai populasi plasma. Dengan demikian dalam keadaan normal
ditemukan immunoglobulin yang heterogen. Macam immunoglobulin : Ig M, Ig G, Ig A, Ig D,
dan Ig E.
Ig M :
Merupakan immunoglobulin dengan berat molekul yang paling besar. Ig m ini banyak
erdapat pada permukaan limfosit B. pada suatu respons imunologik ig M biasaya dibentuk
paling dulu dan dalam waktu relative lebih cepat daripadaproduksi Ig g. kebanyakan natural
antibody yang terdapat dalam darah tersusun atas molekul Ig M. Ig M bervalensi 5 10, BM
900.000, sedimentasi koefisien 19 S/
Kemampuan Ig M
- Menetralkan toksin bakteri
- Dapat menyebabkan aglutinasi seara efisien sekali
- Dapat memfiksasi system komplemen dengan efektif sekali, namun Ig M tidak dapat
melewati barrier plasenta.
Contoh antibody yang terdiri dari Ig M :
- Salmonella typhi
- Antibody terhadap Treponema pallidum kadar dewasa normal. (60-280) mg %
Ig G
Paling mudah berdifusi ke dalam jaringan ekstra vaskuler dan merupakan :
- Immunoglobulin yang paling banyak terdapat dalam serum terutama setelah respons
sekunder.
- Daya pertahanan tubuh yang pertama pada bayi dalam bulan-bulan pertama setelah
lahir yang dieroleh dari ibunya.
Ig G bervalensi 2, B.M ± 150.000 ; sedimentasi koefesien 7 S mempunyai kemampuan :
- Meneutralkan toksin bakteri
- Mengikat mikroorganisme sehingga proses fagosiosis ditingkatkan
- Fiksasi komplemen
Pada umumnya semua jenis antien dapat menimbulkan antibody yang tersusun atas semua
subkelas Ig G, kecuali di antaranya antibody terhadap factor VIII (hemofili) dan antibody
antiplatelet hanya terdiri dari sub kelas tertentu.
Ig A
Hanya sedikit fungsinya di dalam serum dan diduga lebih bermanfaat di daerah mukosa
tubuh sebagai daya pertahanan tubuh pertama yaitu dalam bentuknya sebagai secretory Ig
A. Imunoglobulin ini lebih tahan terhadap serangan enzim proteotik yang biasa terdapat di
daerah mukosa tubuh.
Ig A bervalensi 2-8, BM 150.000 – 600.000 ; sedimentasi koefisien 7 S – 17 S, mempunyai
kemampuan :
- Melindungi tubuh terhadap infeksi local mencegah masuknya antigen ke dalam
tubuh dengan cara melapisi antigen sedemikian rupa sehingga tidak dapat melekat
pada mukosa.
- Bekerja sama dengan lisosim dan komplemen dapat membunuh mikroorganisme
tertentu dengan cara bakteriolisis.
Ig A tidak dapat menembus plasenta tetapi cukup banyak terdapat dalam kolostrum. Contoh
: secretory Ig A terdapat dalam saliva, secret bronkus, air mata, secret hidung, secret
mukosa saluran cerna, secret vagina, secret prostat dan seterusnya. Kadar Ig A dalam
serum dewaa normal (90 – 450) mgr %.
Ig D
Bervalensi 2, B.M. ± 180.000, sedimentasi koefisien 7 S.
Fungsi pada manusia normal belum jelas diketahui. Beberapa ahli menyatakan bahwa Ig D
mempunyai aktivitas antibody terhadap beberapa jenis antigen, misalnya :
- Insulin
- Penisilin
- Toksoid difteri
- Antigen nucleus
- Antigen tiroid
Ig D seringkali terdapat pada permukaan limfosit B bersama-sama dengan Ig M, sehingga
diduga keduanya bekerja sama dan berfungsi sebagai :
- Reseptor antigen’
- mengatur aktivasi maupun penekanan limfosit
immunoglobulin ini palin tidak tahan terhadap panas dan enzim proteolitik. Kadar dalam
serum dewasa normal : (0,5 – 3,0) mgr %.
Ig E
Hanya sedikit sel plasma yang membentuk Ig E sehingga kadarnya dalam serum normal
juga rendah. Immunoglobulin ini juga sebaai reagen yang banyak dihubungkan dengan
keadaan / penyakit alergi.
Ig E bervalensi 2, BM ± 190.000, sedimentasi koefisien 8 S, mempunyai fungsi :
- melindungi tubuh terhadap antigen yang masuk melalui mukosa.
- Sebagai perantara dalam perubahan permiebilitas kapiler.
Antigen yang tidak tertahan oleh Ig A, dapat diikat oleh Ig E. Ig E mempunyai daya ikat
spesifik terhadap permukaan sel mast dan basofil.
Pengikatan suatu antigen/allergen oleh Ig E mengakibatkan :
- Sel-sel tersebut mengalami degranulasi dan melepaskan histamine
- Aktivasi komplemen dan pelepasan factor kemotaktik. Dengan demikian akan
merangsang migrasi sel PMN dan eosnofil, peningkatan dinding-dinding vaskuler di
daerah itu, menimbulkan gejala alergi antara lain urtikaria.
Catatan :
System imun tubuh bawaan dapat menimbulkan respon imun nonspesifik, sedangkan
system imun didapat dapat menimbulkan respon imun spesifik. Di dalam kenyataannya
kerja dari factor-faktor di dalam respon imun non spesifik dan spesifik itu tidak dapat
dipisahkan secara tehas, bahkan seringkali bekerja sama / saling melengkapi, sebagai
contoh antara lain :
- Aktivitas fagositosis (factor seluler respon imun non spesifik) tidak hanya dapat
dibantu oleh komplemen (sesame factor non spesifik : humoral) tetapi juga dapat
ditingkatkan apabila permukaan antigen sasaran dilapisi antibody / opsonisasi
dengan antibody factor humoral respon imun spesifik).
- Aktivasi jalur klasik komplemen (factor humoral respon imun non spesifik) dipicu
apabila ada antibody Ig M/Ig G (factor humoral respon imn spesifik) melapisi antigen
sasaran.
Imunitas merupakan suatu reaksi tubuh terhadap masuknya substansi asing. Reaksi
tersebut dapat menguntungkan atau merugikan. Respon imun merupakan kumpulan
respons yang pada hakekatnya dapat melibatkan semua jenis sel yang berasal dari
hematopoetic stem cells. Semua factor yang berperan di dalam system imun memerlukan
pengatur yang berarti di samping factor yang “memacu” diperlukan pula factor yang
“menghambat kerja imun tersebut. mekanisme homeostatic dapat tercapai.
Contoh :
- Setelah selesai diperlukan, aktivitas komplemen dikendalikan oleh inhibitor (antara
lain C1 esterase inhibitor), inaktivator (antara lain inaktivator anafilatoksin).
- Respons imun spesifik dikendalikan aktivitasnya oleh sel T penekan dan jarring
idiotip=antiidiotip.
Gangguan pengendalian memungkinkan timbulnya keadaan yang tidak menguntungkan
tubuh seperti misalnya penyakit autoimun, keganasan.
APLIKASI KLINIK IMUNOLOGI LABORATORIK:
Beberapa contoh sebagai berikut :
- Infeksi bakteri
Dapat menimbulkan respon imun nonspesifik :
# Humoral : peningkatan protein fase akut antara lain C – reactive protein
(CRP). Kadarnya kemudian akan menurun sejalan dengan kesembuhan
penyakit.
# Seluler : peningkatan mumlah leukosit (leukositosis) dengan peningkatan sel-
sel PMN, monosit.
- Infeksi virus
Virus dapat menyerang dari satu sel ke sel lain, menyebabkan kerusakan sel, dapat
pula menetap di dalam inti sel dan menyebabkan mutasi genetic serta mengubah
fungsi sel. Infeksi virus dapat menmbulkan respons imun :
# Non spesifik : adanya interferon (humoral), aktivitas sel NK (seluler)
# Spesifik : timbulnya antibody (humoral), aktivitas sel T sitotoksik (seluler)
- Penyakit autoimun
Merupakan suatu penyakit sebagai akibat dari kehilangan / gangguan kemampuan
untuk membedakan sel / jaringan tubuh sendiri dengan sel / jaringan asing, timbul
kerusakan jaringan sendiri karena respon imunologik baik seluler maupun humoral.
Autoimunitas berarti respon imun yang ditujukan terhadap antigen diri sendiri.
Penyakit autoimun ditandai dengan aktibitas abnormall berlebihan dari sel-sel
efektor (limfosit B, limfosit T, makrofag), penyebabnya adalah multifaktorial. Salah
satu diantaranya, autoimunitas. Dapat terjadi sebagai akibat pembentukan
neoantigen dari autoantigen karena perombakan oleh / penggabungan denagn
obat/virus.
Contoh keadaan / penyakit autoimun antara lain :
# Proses ketuaan
# Sistemk lupus eritematosus (dapat dideteksi sel LE, antibody antinuclear /
ANA)
# Arthritis rheumatoid (dapat dideteksi factor rheumatoid/ RF).
Contoh autoantiodi :
# Factor rheumatoid,
# Antibody anti-nuklear
# Anti-tiroglobulin
# Tyroid stimulating antibody
- Human leucocyte antigen (HLA)
Tergolong dalam major histocompatibility system (MHC system) yang terdapat pada
lenganpendek kromosom 6. Pada lengan pendek tersebut dikenal lokus – lokus
genetic yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelas yaitu :
# MHC kelas I (lokus HLA A, B, C. Antigen HLA kelas ini dapat dijumpai pada
hamper semua sel yang berinti).
# MHC kelas II
Lokus HLA D, DR, DP, DQ
Antigen HLA kelas II terutama dijumpai pada permukaan sel imunokompeten
yaitu makrofat/ monosit, limfosit B, limfosit T teraktivasi.
# MHC kelas III : komplemen (C2, C4, factor B)
HLA berperan dalam regulasi system imun.
Pemeriksaan HLA banyak digunakan untuk :
# Cangkok organ / transplantasi
# Mengetahui resiko relative penyakit
# Mengetahui status orang tua / keayahan
- Petanda tumor
Merupakan senyawa kimia yang dapat diukur kadarnya secara kuantitatif, terbentuk
pada atau akibat dari pertumbuhan ganas. Pemeriksaan petanda tumor mepunyai
kegunaan untuk :
Uji saring, pemantauan (diagnosis dini, kekambuhan, metastasis), menilai prognosis.
Pemeriksa petanda tumor harus dilakukan dalam suatu panel pemeriksaan
(beberapa macam bersama-sama), karena tidak ada satupun hasil pemeriksaan
tunggal yang spesifik untuk satu jenis tumor tertentu. Contoh antara lain :
Kanker hati : alfa-fetoprotein (AFP), carcinoembryoic antigen (CEA).
Kanker indung telur : cancer antigen 125 (CA 125), beta human chorionic
gonadotropin hormone Beta-hCG, (CEA)
Kanker prostat : prostatic acid phosphatase (PAP), prostate specific
antigen (PSA).
DASAR-DASAR PEMERIKSAAN LABORATORIM IMUNOLOGI
By :
Dr. Lisyani B. Surono,SpPK(K)
Pendahuluan
Perkembangan imunolog yang pesat membuka peluang bagi laboratorium imunologi untuk
berperan aktif di dalam menunjang diagnosis berbagai jenis penyakit serta
penatalaksanaan penderita. Penyakit yang dulu tidak diketahui sebab-sebabnya, kini dapat
dijawab berdasarkan imunologi. Pengetahuan tentang mekansisme respon imun serta
imunopatologi sangat diperlukan agar dapat memilih serta menilai hasil pemeriksaan
laboratorium imunologi dengan tepat.
System imun tubuh dibedakan :
- System imun bawaan, yang dapat menimbulkan respons imunoogik non spesifik
- System imun diperoeh, yang dapat menimbulkan respons imunologik spesifik
Pada masing-masing system imun tersebut secara umum konponen-komponen yang
berperan digolongkan dalam :
- Komponen sel (respons seluler)
- Komponen molekul atau komponen yang larut (respons humoral)
Terhadap komponen sel dapat dilakukan uji kuantitatif maupun uji jualitatif. Uji kualitatif atau
uji fungsi dalam pemeriksaan laboratorium merupakan uji biologic yang dikerjakan in vitro,
sehingga penafsiran erhadap hasilnya perlu dilakukan secara hati-hati.
Macam-macam pemeriksaan laboratorium imunologi.
1. Uji respons imunologi non spesifik
2. Uji repons imunologik spesifik
3. Deteksi antigen
1. Uji respons imunologi non spesifik
A. respons non spesifik seluler
berperan pada respons imunologk non spesifik seluler yaitu sel-sel efektor atau
sel pembunuh yang dikelompokkan sebagai fagosit, yaitu makrofat/monosit, sel-
sel polimorfonuklear/PMN (segmen neutrofil, kadang-kadang eosinofil). Fagosit
tersebut di dalam kerjanya in vivo seringkali mengadakan interaksi dengan
berbagai komponen respons imunologik sesame non spesifik sendiri maupun
dengan komponen respons imun spesifik. Dengan demikian kerja masing-masing
komponen ditingkatkan dan sebenarnya batasan antara repons imunologik non
spesifik tidak dapat dipisahkan (terlepas) sama sekali satu dengan lainnya.
Proses fagositosis secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 tahap yaitu :
- pengenalan dan peningkatan terhadap substansi asing
- penelanan/up take (ingestion)
- pencernaan (digestion)
Secara rinci tahapan tersebut meliputi proses kemotaksis / kemoatraksi,
opsonisasi, endositosis (meliputi pinositosis / up take terhadap non partikel
missal cairan dan fagositosis / ingestion terhadap partikel), pembunuhan intra sel
dan pencernaan. Gangguan proses fagositosis dapat terjadi pada salah satu
atau beberapa tahap tersebut.
1. Macam fagosit
- Fagosit mononuclear (monosit/makrofag)
a. Monosit / makrofag
Monosit yang berada di dalam sirkulasi dan makrofag yang berada di
dalam jaringan biasanya inaktif dan baru menjadi aktif bila ada
rangsangan. Dengan adanya rangsangan tersebut maka
monosit/makrofag akan mengalami perubahan baik morfologik
maupun fungsinya. Dibandingkan dengan fagosit PMN,
monosit/makrofag :
Memiliki enzim katalase, kurang memiliki protein kation dan
laktoferin
Peka terhadap leih banyak macam factor kemotaktik
Lebih mampu menelan antigen / sel sasaran yang dilapisi
antibody
Berumur panjang (berbulan-bulan/ tahun)
b. PMN neutrofil
Merupakan granulosit yang terbanyak jumlahnya dalam sirkulasi dan
merupakan sel-sel yang pertama kali datang berkumpul di daerah
infeksi (dalam 30 – 60 menit) karena adanya rangsangan factor
kemotaktik. PMN neutrofil memeang peran penting pada reaksi
inflamasi, sering disebut sebagai sel inflamator utama dan merupakan
populasi terbanyak dalam respons imun non spesifik untuk
meniadakan mikroba. PMN neutrofil hanya memasuki jaringan bila
diperlukan.
Dibandingkan dengan fagosit mononuclear, PMN neutrofil :
Memiliki enzim mieloperoksidase, protein kation dan laktoferin
Peka terhadap banyak factor kemotaktik
Lebih suka menangkap partikel antara lain lateks, efisien
terhadap fungi dan kurang mampu menelan antigen yang
dilapisi antibody.
Berumur pendek (2-3 hari)
c. PMN eosinofil
Sel eosinofil juga dapat berfungsi sebagai fagosit meskipun kurang
efisien bila dibandingkan dengan sel neutrofil. Jumlahnya pada
individu sehat hanya sedikit (kurang dari 1-2 % total leukosit), tetapi
dapat meningkat pada keadaan alergi dan invasi parasit tertentu. Isi
granulanya dapat dilepaskan oleh adanya sinyal tertent dan molekul-
molekul dapat membunuh secara ekstrasel parasit yang ukurannya
terlalu besar untuk difagositosis.
- Fagosit polimorfonuklear (segmen netrofil, kadang-kadang eosinofil)
2. Maam pemeriksaan
A. uji kelainan kuantitatif
dengan menghitung jumlah sel kleukosit dan melakukan hitung jenis sell
leukosit darah tepi secara konvensional ataupun automiatisasi. Contoh :
- leukositosis : pada infeksi kokus / piogenik dengan peningkatan
neutrofil PMN dan pergeseran ke kiri
- monositosis : dapat terjadi antara lain pada stadium penyembuhan
infeksi akut, infeksi tuberculosis, demam tifoid
- leukopeni : pada infeksi virus, tifoid, akibat obat tertentu dan lain-lain.
Keadaan leukopeni kronis menyebabkan terjadinya infeksi ulang.
- Eosinofilia : pada alergi, invasi parasit tertentu
B. uji kelainan kualitatif
manifestasi klinik yang tampak pada adanya gangguan fungsi fagositosis
ialah infeksi berat tanpa disertai demam. Dikenal beberapa macam
pemeriksaan untuk tujuan tersebut antara lain :
- uji hambatan migrasi leukosit :secara singkat caranya ialah dengan
memisahkan leukosit dari eritrosit (sampel darah heparin), emudian
leukosit tersebut dimasukkandihidsap ke dalam tabung kapiler dan
diinkubasi dalam media biakan. Dalam keadaan normal, leukosit akan
bermigrai ke luar tabung dan membentuk suatu kipas di ujung tabung.
- uji penyaringan gangguan fagositosis/pembunuhan mikroba dengan uji
nitrotublue tetrazolium (NBT). Dinilai penurunan reduksi NBT. Pada
individu normal bervariasi, tetapi umumnya tidak lebih dari 25 %.
- Uji kemampuan leukosit untuk bereaksi dengan factor kemotaksis.
- Uji jungsi membunuh mikroba dan lain-lain. Mikroba diinkubasikan
dengan PMN kemudian dibiakkan. Ada/tidaknya pertumbuhan mikroba
member gambaran kemampuan PMN dalam membunuh mikroba
tersebut.
B. repons non spesifik/humoral (molekul terlarut)
a. penetapan kadar CRP (C-reactive protein)
CRP merupakan salah satu protein fase akut yang akan meningkat kadarnya,
dapat sampai melebihi 100x normal yaitu pada keadaan infeksi/peradangan
dan kerusakan jaringan. Tinggi dan lamanya peningkatan CP tergantung dari
berat ringannya reaksi peradangan akut / kerusakan jaringan tersebut.
Penetapan kadar CRP member hasil yang lebih sensitive bila dibandingkan
laju endap darah (LED). Perbaikan / pengurangan keadaan peradangan
dapat diketahui lebih cepat.
b. Penetapan kadar komplemen
Pada umumnya tidak semua komponen komplemen perlu diperiksa.
Penetapan kadar komponen komplemen 3 dan 4 (C3, C4), factor B dan
properdin dapat dipakai untuk memberikan gambaran keadaan kadar
komplemen secara keseluruhan serta aktifasi jalur klasik/intrinsic atau
alternative / ekstrinsik.
2. Uji respons imunologik spesifik
A. Respons spesifik seluler
Limfosit T yang tersensitisasi oleh antigen akan mengalami transformasi,
berproliferasi dan berdeferensiasi menjadi limfosit T efektor (sitotoksik), T
pembantu (penolong / helper) dan T penekan (suppressor). Subset limfosit T
tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lain dengan mendeteksi reseptor
antigen / petanda-petanda permukaan (surface marker) yang terdapat pada
masing-masing jenis sel.
Petanda permukaan untuk limfosit T penolong ialah CD 4 (CD – cluster of
differensiation) dan CD 8 untuk limfosit T sitotoksik maupun T penekan. Pada
individu normal jumlah limfosit berkisar antara 75-85 % dari total limfosit dan
perbandingan CD 4 : CD 8 = ± 1,7 : 1
Uji kualitatif yang dapat dilakukan antara lain :
- Uji transformasi limfosit : 50-6- % limfosit T mampu memberikan respons
terhadap stimulasi dengan mitogen (antara lain phytohaemagglutinin dan
concanavalin A) yang dianggap menyerupai respons limfosit terhadap
antigen.
- Uji sitotoksisitas untuk mengukur kemampuan sitotoksisitas limfosit di dalam
menghancurkan sel sasaran
- Uji produksi limfokin : limfosit memproduksi bermacam-macam limfokin
setelah dirangsang oleh antigen atau mitogen. Limfokin berguna untuk
menghancurkan antigen sasaran.
Catatan :
semua uji kualitatif / uji fungsi merupakan uji in vitro (bioassay) yang dapat
memberikan hasil yang sangat bervariasi oleh karenanya iterpretasi harus
dilakukan secara berhati-hati, sebab tidak selalu mencerminkan keadaan in vivo
secara tepat.
B. Respons spesifik humoral
Limfosit B akan mengalami perubahan menjadi sel plasma untuk memproduksi
immunoglobulin/antibody. Pada individu normal jumlah limfosit B berkisar antara
10-15 dari total limfosit. Hasil pemeriksaan immunoglobulin baik secara
kuantitatif maupun kualitatif secara umum dapat dipakai untuk memberikan
gambaran kelainan fungsi limfosit B di dalam memproduksi antibody. Vaksinasi
dan pengukuran kadar antibody spesifik yang terbentuk memberikan gambaran
kemampuan respons seseorant terhadap rangsangan, baik respons primer
maupun sekunder. Pada kelainan imunodefisiensi, terjadi penurunan kadar
immunoglobulin yang dapat bervariasi antara defisiensi semua kelas atau kelas
tertentu secara selektif. Di dalam melakukan fungsinya, limfosit B tidak berdiri
sendiri, tetapi juga melibatkan factor-faktor lain seperti komplemen, limfosit T
(penolong maupun penekan), sel mast/basofil, sehingga pengujian terhadap
fungsi sel B tidak hanya terbatas pada kemampuannya memproduksi antibody
saja.
C. Uji immunoglobulin kuantitatif / kualitatif
1. Elektroforesis protein
Digunakan untuk memeriksa fraksi protein. Pada dasarnya merupakan
pergerakan fase padat terhadap fase cair di alam medium listrik dengan
menggunakan media penyangga antara lain paper selulosa asetat, agarose
dan lain-lain.
Protein terdiri dari molekul-molekul/partikel-partikel dengan ukuran serta
muatan listrik yang berbeda-beda bila diletakkan dalam medan listrik akan
bergerak dengan kecepatan berbeda pula, dengan demikian maka dapat
diperolah pemisahan molekul / partikel baik sebagian maupun lengkap. Dari
gambaran hasil elektroforesis dapat dinilai kelainan imunoproliferatif sebagai
berikut :
- Gamopati poliklonal : karena adanya stimulasi antigenic yang bersifat
kronik, produksi immunoglobulin merupakan protein yang bersifat
heterogen, sebagai akibat dari proliferasi sel plasma yang berasal dari
berbagai clone (gambaran kurve puncak tumpul, dasar lebar).
- Gamopati monoclonal : biasanya terjadi pada keganasan, produksi
immunoglobulin merupakan protein yang bersifat homogeny, sebagai
akibat dari proliferasi sel plasma secara tidak terkendali, yang berasal dari
satu clone (gambaran kurve puncak runcing, tinggi, dasar sempit disebut
M-spike)
Contoh : keadaan paraproteinemia, misalnya protein Bence Jones pada
multiple myeloma makroglobulinemia Waldenstrom.
2. Imunoelektroforesis
Pada dasarnya merupakan gabungan antara elektroforesis dengan
imunodifusi dan reaksi antigen-antibodi dalam medium gel. Fraksi-fraksi
protein yang telah terpisah dengan cara elektroforesis selanjutnya
direaksikan dengan antiserum yang mengandung antibody spesifik, sehingga
terbentuk presipitat dari masing-masing fraksi yang berwujud lengkungan-
lengkunagn. Tebal, panjang dan bentuk lengkungan dinilai dengan
dibandingkan terhadap control. Bahan pemeriksaan dapat berupa serum,
urin, cairan biologic lain.
Tehnik imunoelektroforesis dapat dipakai untuk mendeteksi antigen tertentu
dan mendeteksi perubahan kualitatif immunoglobulin sebagai berikut :
- Gamopati polikolnal : garis lengkung presipitasi (ig A, Ig G, Ig M) menebal
dan lebih panjang dibandingkan control.
- Gamopati monoclonal : garis lengkung presipitasi tampak mengalami
distorsi berupa bifurkasi, seperti sekop (scoping), menggembung
(bulging).
Catatan :
Selain limfosit T dan limfosit B dikenal pula populasi sel Null atau limfosit non
T non B yaitu :
- Sel Natural Killer (NK) yang berperan dalam respons imun seluler non
spesifik khususnya terhadap virus dan sel ganas.
- Sel killer (K) ; memiliki kemampuan sitotoksisitas seluler dengan bantuan
antibody, karena itu dikenal sebagai antibody dependent cell-mediated
cytotoxity (ADCC).
3. Deteksi antigen (dapat dilakukan dengan cara RIA, ELISA dan lain-lain)
Interaksi antigen-antibodi in vitro
A. Antigen
Merupakan molekul kimia (protein, karbohidrat, lemak) yang terdapat
pada badan virus, bakteri, fungi, parasit dan lain-lain yang mempunyai sifat dapat
merangsang pembentukan antibody serta dapat mengikat antibody secara
selektif pada bagian structural dari antigen tersebut yang disebut determinant
antigen atau epitop. Kebanyakan antigen memilike beberapa epitop.
Pengertian antigen serologi :
- Menurut bentuk kerja fisiknya dibedakan menjadi : precipitating dan
agglutinating antigen
- Menurut penggunaaan dan hubungannya dengan antibody dikenal :
# Antigen homolog : yaitu antigen yang mula-mula diunakan untuk imunisasi
(memacu pembentukan antibody kemudian antigen yang sama
direaksikan dengan antibodinya.
# Antigen heterologi : antigen yang diunakan bukan antigen yang sama
dengan yang dipakai untuk imunisasi, tetapi dapat bereaksi silang (cross
reactive) dengan suatu antibody produksi antigen lain.
# Antigen heterofil : merupakan antigen alami yang tersebar luas dan dapat
bereaksi silang dengan banyak macam antibody karena memiliki epitop-
epitop yang identik.
B. Antibody
- Dapat berikatan dengan antigen pada bagian antigen binding site
- Dapat mengikat komplemen
Beberapa pengertian yang perlu diperhatikan untuk antibody antara lain :
a. Antibody spesifik : yaitu antibody yang hana dapat berikatan dengan antigen
yang merangsang produksinya.
b. Antibody non spesifik : yaitu antibody yang dapat berikatan dengan antigen
lain yang tidak sama dengan yang merangsang produksinya namun memiliki
satu atau lebih epitop yang serupa.
c. Antibody poliklonal : setiap antigen umumnya dapat memacu banyak clones
sel plasma dan masing-masing clone dapat memproduksi satu macam
bentuk antibody akan berikatan dengan epitop-epitop yang sesuai
(kebanyakan antigen memiliki beberapa epitop).
d. Antibody monoclonal : adalah antibody yang beraasal hanya dari satu clone
sel plasma, merupakan antibody homogeny yang spesifik tunggal. Antibody
monoclonal dapat diperoleh dengan memanipulasi limfosit B in vitro dengan
teknik hibridoma.
C. Kekuatan yang mengikat antigen dan antibody
Antigen dapat berikatan dengan antibody karena :
- Daya coulombic atau daya elektrostatik : yaitu daya tarik menarik antara
gugus molekul antigen dengan antibody yang mempunyai muatan listrik
berlawanan. Makin dekat jarak antigen antibody makin cepat keduanya
berikatan.
- Daya van der waals : yaitu ikatan karena adanya kesesuaian / kecocokan
antibody dengan permukaan determinant antigen (epitop).
Ikatan antigen dengan antibody merupakan ikatan yang irreversible dan mudah
berdisosias. Kemudahan disosiasi tergantung pada kekuatan ikatan antigen-
antibodi tersebut seperti digambarkan dalam rumus :
Ag + Ab ↔Ag Ab
Ag = konsentrasi antigen
Ab = banyaknya antigen binding site paa antibody
K = konstanta = kekuatan ikatan
Bila antibody sesuai/cocok dengan antigen, reaksi akan bergeser kekanan,
makin sesuai maka kompleks antigen-antibodi makin sulit berdisosiasi. Antibody
tersebut dikatakan memiliki afinitas yang tinggi terhadap antigen yang
bersangkutan. Afinitas antibody ialah kekuatan interaksi antara antibody dengan
determinant antigen tunggal / monovalen.
Di dalam prakteknya seringkali antibody heterogen berikatan dengan antigen
multivalent, ikatan ini disebut dengan istilah aviditas antibody. Makin kuat avidita
antibody makin stabil kompleks antigen-antibodi atau makin sulit berdisosiasi.
Ikatan hydrogen dan daya hidrofobik.
D. Kategori interaksi antigen-antibodi in vitro
Dibedakan 2 macam kategori interaksi antigen – antibody in vitro yang
merupakan dasarimunokimia sebagai berikut :
1. Interaksi antien antibody primer : merupakan reaksi antigen-antibodi tingkat
molekuler. Reaksi ini biasanya tidak dapat terlihat dengan mata biasa
sehingga memerlukan suatu indicator antara lain dengan berbagai zat seperti
enzim, zat warna flouresein, radioisotope. Teknik pemeriksaan disebut sesuai
dengan label yang dipakai.
2. Interaksi antigen-antibodi sekunder : dapat mengakibatkan presipitasi atau
aglutinasi sebagai berikut :
a. Bila antigen berada dalam larutan kemudian direaksikan dengan antibody
spesifik, maka akan terbentuk kompleks antigen-antibodi yang besar yang
akan mengendap dan membentuk presipitasi.
b. Bila antigen terikat pada suatu partikel misalnya lateks/eritrosit, maka
interaksi antigen-antibodi akan membentuk gumpalan atau aglutinasi.
Contoh : teknik pemeriksaan berdasarkan keadaan ini yaitu : aglutinasi
lateks, hemaglutinasi, uji fiksasi komplemen, turbidimetri, nefelometri dan
lain-lain.
E. Sensitivitas dan spesifitas analitik
Interaksi antigen-antibodi in vitro dikembangkan dengan tujuan untuk mendeteksi
antigen atau antibody b aik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk mendeteksi
antien dipakai reagen yang mengandung antibody dan untuk mendeteksi
antibody dipakai reagen yang mengandung antigen. Banyak teknik pemeriksaan
telah dikenalkan dengan sensitivitas dan spesifisitas analitik yang berbeda-beda.
Sensitivitas analitik ialah kemampuan untuk mendeteksi antigen/antibody dalam
kadar yang sangat kecil atau sedikit. Sensitivitas analitik dapat ditingkatkan
dengan menggunakancara pendeteksian tingkat molekuler.
Spesifitas analitik ialah kemampuan reaksi spesifik antara antigen-antibodi yang
sesuai, sehingga makin sedikit / tidak ada reaksi silang tergadap antigen-antibodi
lain. Dengan demikian akan makin kecil kemungkinan / tidak ada reaksi positif
palsu.
Contoh : spesifitas analitik dapat ditingkatkan dengan penggunaan antibody
monoclonal. Pada umumnya makin sensitive suatu tekni pemeriksaan makin
spesifik pemeriksaan tersebut dan sebaliknya.
F. Beberapa contoh teknik pemeriksaan
a. Dengan dasar reaksi presipitasi : dapat dipakai untuk mengukur kadar
antigen atau antibody, reaki presipitasi dapat dilakukan dalam medium cair
atau gel (semisolid). Antibody yang direaksikan dengan antigen spesifik akan
membentuk kompleks / presipitat yang tidak larut dan dapat diukur dengan
berbagai cara. Dikenal antara lain teknik :
- Imunodifusi ganda
- Imunodifusi radial
- Elektroimunodifusi
- Imunoelektroforesis
- Rocket immunoelectrophoresis
- Imunoefelometri
Dalam reaksi presipitasi / antigen-antibodi, sangat penting perbandingan
antara jumlah antigen dengan jumlah antibody yang seimbang. Efek prozone
terjadi akibat kelebihan antibody sehingga kompleks antigen-antibodi tetap
berada dalam larugtan. Efek postzone terjadi akibat kelebihan antien
sehingga kompleks antigen-antibodi yang terbentuk kembali larut.
b. Dengan dassar reaksi aglutinasi : merupakan metode serologic klasik untuk
mendeteksi antigen atau antibody. Umumnya aglutinasi terjadi bila antigen
berbentuk partikel direaksikan dengan antibody spesifik. Dikenal antara lain
teknik sbb :
- Reaksi aglutinasi direk : yaitu bila antigen berbentuk sel atau partikel
seperti reaksi Widal, reaksi Weil Felix, penetapan golongan darah
- Reaksi aglutinasi indirek atau aglutinasi pasif untuk mendeteksi antigen
yang larut, antigen tersebut terlebih dahulu dilekatkan pada suatu partikel
yang disebut carrier misalnya carrier lateks, eritrosit, bentonit karbon.
- Reaksi aglutinasi pasif terbalik : pada teknik ini antibody dilekatkan pada
artikel kemudian direaksikan dengan antigen yang larut.
Bila carrier yang dipakai ialah eritrosit maka disebut revers passive
haemagglutination assay (RPHA).
Modifikasi teknik aglutinasi yaitu uji hambatan aglutinasi. Serum / cairan lain
yang akan diuji terlebih dulu direaksikan dengan antibody, kemudian baru
direaksikan dengan antigen yang dilekatkan pada suatu partikel, dengan
demikian bila serum mengandung antigen maka antibody akan terikat pada
antigen yang ada di dalam serum/cairan lain tersebut, sehingga tidak dapat
bereaksi dengan antigen pada partikel.
c. Dengan dasar interaksi antigen antibody primer/tingkat molekuler teknik yang
dikenal yaitu :
- Radioimmunoassay (RIA)
- Enzyme immunoassay (EIA) atau enzim linked immunosorbent assay
(ELISA). Prinsip pemeriksaan serupa RIA, disini digunakan enzim untuk
melabel antigen/antibody sebagai pengganti radioisotope. Teknik ELISA
cukup sensitive, peralatan yang dipakai adalah spektrofotometer biasa,
mudah dilakukan automatisasi dan tidak ada bahaya radioaktif..
Rujukan yang dipakai
- Kresno SB. Immunologi : Diagnosis dan prosedur laboraorium.ed.4. Jakarta. Balai
Penerbit FK UI, 2001
- Sheehan C, Principles and laboratory diagnosis clinical immunology. Philadelphia.
JB Lippincott Co, 1991
- Abbas AK, Kich Iman H, Pober JS, Celiuler and Moleculer
Immunology.Philadelphia.Saunders 2003
FESES (dr. Banundari Rachmawati, (SpPK)
PENDAHULUAN
Feses berasal dari intake air, makanan (peroral), saliva, cairan lambng, cairan yang berasal dari pancreas dan cairan
empedu yang semuanya berperan pada proses pencernaan maanan. Orang dewasa mengeluarkan feses antara 100
– 300 gram / hari dan 70 % di antarnya adalah air.
Feses terdiri dari :
- Sisa makanan yang tidak dapat dicerna
- Pigmen dan garam empedu
- Sekresi intestinal termasuk mucus
- Leukosit yang bermigrasi dari aliran darah
- Epitel
- Bakteri
- Material inorganic terutama kalsium dan fosfat
- Makanan yang tercerna (dalam jumlah yang sangat sedikit)
- Gas
Bentuk dan komposisi feses tergantung pada proses absorbs, sekresi dan fermentasi. Feses normal akan berwarna
kuning (berasal dari degradasi pigmen empedu olleh bakteri), tidak lembek dan tidak keras, berbau khas (berasal
dari Indol, skatol dan asam butirat). Protein yang tidak tercerna dengan baik akan menyebabkan bay uang kuat.
Cara pengumpulan sampel :
Sampel feses dapat berupa :
- Feses sewaktu
- Feses 24 jam
Cara memperoleh dapat dilakukan dengan :
- Spontan (dapat menggunakan pencahar)
- Rectal toucher
- Rectal swab dengan cotton wool (terutama pada bayi)
PERSIAPAN PENDERITA :
- Terangkan cara penampungan apa yang akan diperiksa
- Penderita diminta untuk defekasi pada penampung feses bermulut lebar
- Jangan kencing ditempat penampungan
- Jangan meletakkan kertas toilet pada penampung karena akan berpengaruh terhadap hasil
Syarat pengambilan :
Untuk mendapatkan sampel yang emenuhi syarat maka perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini :
- Feses harus dikumpu.kan pada tempat yang kering, bersih, bebas urin, kemudian dipindahkan ke
penampung dengan menggunakan, tunge spatel. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik maka harus
segera dikirim ke laboratorium pemeriksa.
o Feses yang masih hangat sangat baik untuk pemeriksaan telur dan parasit. Untuk keperluan ini
feses tidak boleh dimasukkan atau di simpan dalam lemari es.
o Feses yang disimpan dalam almari es tidak boleh langsung diperiksa tetapi sebaiknya dibiarkan
dulu pada temperature ruang.
o Tidak boleh di simpan dalam incubator.
- Sampel terbaik adalah yang fresh (baru)
- Pengumpulan sampel harus dilakukan sebelum terapi antibiotika dan diambil seawall mungkin pada saat
sakit
- Jumlah sampel yang dibutuhkan hanya sedikit, kira-kira sebesar ibu jari kaki bayi. Bila dijumpai mucus atau
darah maka sampel diambil dari tempat tersebut karena parasit biasanya terdapat disitu.
- Tidak boleh menggunakan feses yang ditampung di kloset atau terkontaminasi dengan barium atau produk
X ray.
- Beri label yang berisi identitas seperti nama, tanggal, alamat, pemeriksaan apa yang diminta.
Bila dilakukan penundaan pemeriksaan dapat dilakukan :
- Feses dimasukkan almari es
- Diberi formalin
- Diberi nitrogen
Indikasi pemeriksaan
Indikasi pemeriksaan feses secara umum adalah gangguan traktus gastro intestinalis seperti :
- Sembelit
- Berak darah lender
- Problem makanan
- Diare
Gangguan gastrointestinal dapat disebabkan karena :
- Kuman : salmonella, shigella dan sebagainya
- Bukan kuman : ulcus pepticum, carcinoma, invasi parasit, steatorrhoe (tinja dengan komposisi lemak yang
tinggi) dan lain-lain.
Frekuensi defekasi
Normal :
Frekuensi defekasi adalah 1-2 kali/hari
Abnormal terdapat pada :
- Surgical resection
- Fistel / shunt pada usus
- Diare : frekuensi defekasi > 4x/hari dan sifatnya cair
Diare
Diare ada bermacam-macam :
a. Cair
- Diare sekretorik disebabkan oleh beberapa sebab :
o Infeksi : staphylococcus, shigella, salmonella, protozoa, E.coli, Clostridium, kolera
o Pada mucosa luka
o Vagotomi
o hipertiroid
- Diare osmotic
Operasi tractus gastrointestinal, parasit, obat, defek pada mukosa, defisiensi immunoglobulin dan
sebagainya.
- Hipermotilitas
o Post vagotomi
o Kelainan fungsi gastrointestinal
o Hipokalemi
o Hipertiroid dan sebagainya
b. Steatorrhoe
- Maldigesti insufisiensi pancreas
- Mal absorbs tropical sprue
c. Diare sedikit-sedikit
Disebabkan rectum dan kolon yang bersifat iritabel
PEMERIKSAAN LABORATORIUM
Pemeriksaan laboratorium feses ada bermacam-macam yaitu :
1. Makroskopis
2. Mikroskopis
3. Kimia
4. Bakteriologis
Makroskopis
Pemeriksaan makroskopis meliputi :
- Warna
- Darah
- Lender
- Konsistensi
- Bau
- pH
- sisa makanan
Warna :
Ealam keadaan normal feses berwarna kuning muda, warna feses yang berbeda dapat disebabkan oleh karena
keadaan yang patologis, gangguan fungsi organ, perdarahan, diet an obat. Contoh :
Keadaan yang patologis :
- feses berwarna kuning hijau pada diare berat
- hitam, pada perdarahan TGI (tracktus gastrointestinalis) atas
- dempul, karena penurunan pigmen empedu yang masuk ke usus dank arena obstruksi saluran empedu.
- Merah karena perdarahan TGI bagian bawah
Faktor interfering :
- Kuning sampai kuning hijau pada bayi yang minum susu tetapi mengalami gangguan flora usus atau minum
antibiotika
- Hijau karena makan sayur
- Hitam atau coklat tua karena makan tablet Fe, Bismuth, atau makan cherry atau daging yang berlebihan.
- Pucat bila makanan sedikit daging atau mengkonsumsi susu
- Tanah liat, pada penderita dengan intake lemak berlebihan atau menggunakan barium X ray
- Merah karena obat bromsulthalein, salisilat, pyridium pamoate atau tetracycln syrup dll.
Darah
Darah yang keluar sejumlah 2,8 ml/hari pada TGI (tractus gastro intestinalis) suah memberikan tanda pada feses.
Darah pada feses biasanya disebabkan karena hemorrhoid atau karena fissure pada anus. Dapat dibedakan menjadi
darah segar dan tidak segar.
Darah segar :
Darah bersifatsegarn bila kelainan berada di sebelah distal lambung. Dijumpai pada :
- Hermorroid
Darah biasanya menetes, terdapat di permukaan dan diserai dengan rasa tidak enak pada anus.
- Ca calon
Bila lokasi di proksimal maka darah akan bercampur feses tetapi bila di distal maka darah tidak tercampur
feses.
- Disentri amoeba
Feses volume sedikit, frekuensi defekasi sering, disertai darah dan lender, dan rasa mules yang hebat.
Darah tidak segar :
Darah tidak segar bila kelainan ada di sebelah proksimal lambung. Dijumpai pada :
- Varices oeseopaghus
- Ulcus pepticum
- Carcinoma TGI
- Radang
Lendir
Lender pada feses dikeluarkan oleh kolon karena rangsangan saraf parasimpatis, jadi dijumpainya lender pada
fesees menggambarkan rangsangan pada saraf parasimpatis.
- Lender kental pada permukaan feses. Dijumpai pada keadaan :
o Konstipasi sspastik
o Colitis
o emosi
- Lender dan darah pada permukaan feses. Dijumpai pada keadaan :
o Neoplasma
o Iritasi pada rektum
- Lender disertai dengan nanah dan darah. Dijumpai pada keadaan :
o Colitis ulseratif
o Disentri basiler
o Ca kolon dengan ulserasi
o Diverticulitis akut
o TBC usus (dua keadaan yang terakhir sangat jarang.
Konsistensi
Pada keadaan normal ukuran feses dan konsistensi menggambarkan keadaan lumen dan mortalitas kolon. Pada
masing-masing orang keadaan ini berbeda, dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang.
Keadaan yang menyebabkan perubahan konsistensi
- Diare dengan lender dan darah : amoebiasis, typhoid, thypus abdominalis, cholera
- Seperti adonan tepung. Disebabkan karena lemak yang berlebihan.
- Keras disebabkan karena absorbs cairan yang meningkat, intake cairan yang tidak adekuat atau karena
defekasi ditahan.
Bau dan pH
Bau khas pada feses sangat dipengaruhi pH feses, pada keadaan normal pH feses adalah netral sampai sedikit
basa, sedangkan pH sangat dipengaruhi oleh fermentasi usus dan proses pembusukan, di mana akan dihasilkan
indol, skatol yang akan menyebabkan bau pada feses.
Makanan yang mengandung karbohidrat akan mengubah pH menjadi asam, sehingga feses akan berbau asam,
protein akan mengubah pH menjadi basa dan akan menyebabkan bau yang lebih tajam, sedangkan lemak akan
menyebabkan bau tengik.
Sisa makanan
Secara makroskopis, sisa makanan dapat dilihat brupa serat atau sayur yang tidak tercerna.
MIKROSKOPIS
Pemeriksaan feses terutama ditujukan untuk mencari protozoa dan telur cacing. Untuk mencari protozoa digunakan
larutan eosin 1-2 % atau lugol 1-2 %
Epitel :
Epitel berasal dari dinding usus sebelah distal dapat ditemukan dalam keadaan normal. Sel tersebut akan bertambah
banyak kalau ada perangsangan dan peradangan dinding usus.
Leukosit : normal akan ditemukan beberapa sel leukosit
Jumlah leukosit sangat meningkat pada :
- Colitis ulseratif kronik
- Disentri basiler kronik
- Abses yang terlokalisir
- Fistula pada sigmoid, rectum dan anus
Jumlah leukosit meningkat dan berbentuk polinuklear
- Shigellosis
- Salmonellosis
- Diare oleh karena E.Coli infasif
- Kolitis ulseratif
Jumlah leukosit meningkat dan berbentuk mononuclear
- Thypoid
Diare tanpa kenaikan leukosit :
- Cholera
- Non spesifik
- Virus
- E.coli yang tidak invasive, parasit : giardia lamlia, toksigenik : clostridium, staphylococcus
Eritrosit : normal tidak akan dijumpai eritrosit dalam feses dan akan dijumpai bila ada lesi pada kolon, rectum, atau
anus.
Makrofag : normal tidak akan dijumpai adanya makrofag. Cirri-cirinya : sel besar, dalam sitoplasmanya sering
dijumpai sel lain seperti leukosit.
Kristal : Kristal tidak mempunyai arti penting, kecuali Charcot leyden dan hematoidin. (Tripel fosfat, kalsium oksalat,
asam lemak), hematoidin terdapat pada perdarahan, charcot leyden terdapat pada penderita Eosinofilia.
Sel ragi
Sisa makanan : hamper selalu ditemukan, berasal dari makanan yang berasal dari daun (sayur) dan dari hewan
seperti serat otot. Sisa makanan dapat diperiksa juga dengan cara preparat langsung memakai larutan tertentu.
Karbohidrat : menggunakan lugol, akan tampak butiran biru.
Lemak : menggunakan lar Sudan III, akan tampak butiran jingga
Protein menggunakan reagen asam asetat 30 % akan tampak butiran kuning muda.
Telur dan jenti cacing (bagian parasitologi)
KIMIA
Darah samar
Cara pemeriksaan darah ada beberapa macam yaitu :
- Hematest, occult test (orthotoluidine) sensifitasnya 1-10 kali lebih baik dibandingkan cara benzidine
- Benzidine test Sensifitasnya 10 – 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan menggunakan Guaiac test.
Pemeriksaan menggunakan benzidine basa, dinilai bila terjadi perubahan warna menjadi hijau sampai biru.
Hasil positif palsu dapat disebabkan karena :
- = makanan : daging dalam jumlah banyak
- Terapi besi
- Iodium
- Oksidator
- Asam borat
- Bromide
- Colchinin
- Obat yang bersifat oksidator
Hasil negative palsu : Vit. C > 500 mg / hari
Guaiac test
Paling tidak sensitive dibandingkan cara yang lain. Untuk memperoleh hasil yang dapat dipercaya maka
pemeriksaan harus diulang paling tidak 3 kali dengan sampel yang berbeda.
Urobilinogen
Untuk melihat peningkatan bilirubin pada penderita anemia hemolitik. Sedangkan pada kelainan hepar akan
menyebabkan turunnya bilirubin pada usus dan akan berakibat turunnya urobilinogen di feses, bahkan bila terjadi
obstruksi, kadar urubilinogen akan sangat rendah. Terapi antibiotika peroral juga dapat mematikan flora usus dan
akibatnya juga akan menganggu metabolism bilirubin.
Bakteriologi (akan dibahas pada kuliah mikrobiologi)
GOLONGAN DARAH (dr. Lisyani B. Suromo, SpPK (K)
Pendahuluan
Seorang ilmuwan Jerman, Karl Landsteiner pada tahun 1900 telah melakukan suatu serial pemeriksaan terhadap
sampel darah dari 6 orang kawannya. Dilakukan pemisahan serum dan dibuat suspense eritrosit dalam salin.
Dijumpai adanya aglutinasi pada beberapa campuran serum dengan suspense eritrosit. Hal ini disebabkan karena
eritrosit memiliki antigen yang bereaksi dengan antibody (dalam serum) yang sesuai. Atas dasar ada tidakya
aglutinasi tersebut. Maka ditetapkan 3 macam golongan darah yaitu A, B, O. kemudian Decastello dan Sturli (1902)
menemukan golongan darah AB, semuanya termasuk dalam system ABO.
Pada penelitian selanjutnya ternyata golongan darah A dapat dibedakan dalam subgroup A1, A2 dan kemudian
dijumpai lagi A3, A4, A5, Ao, Ax, Az, dan lain-lain, bahkan kini dikenal juga subgroup golongan B. penelitian demi
penelitian terus berkembang, sejauh ini telah dikenal pula system golongan darah lain dari ABO yaitu system
Rhesus, Lewis, Kell, KIDD, Lutheran, P, Ii, MN, Duffy, Diego dan lain-lain namun yang penting adalah system ABO
dan Rhesus karena memiliki sifat antigenic yang kuat.
Sistem ABO
Gen pada system ABO
Lokus gen yang mengatur system ABO terletak pada lengan panjang kromosom 9. Teori Thompson dan kawan-
kawan (1930) menyatakan bahwa pada system golongan darah ABO terdapat 4 gen alelik yaitu A1, A2, B, O
sehingga dapat dibedakan 6 fenotip dan 10 fenotip sebagai berikut :
TABEL FENOTIP DAN GENOTIP Golongan darah ABO
Gen A1 dominan terhadap A2, A1-A2-B dominan terhadap O. tidak ada sebutan resesif untuk gen golongan darah,
dikenal sebutan silent gen atau gen atmorfik untuk gen yang tidak menampilkan produk pada fenotipnya. Gen
golongan darah diturunkan dari kedua orang tua menurut hokum mendel.
Antigen pada eritrosit goongan darah AB (agglutinogen)
Penentuan golongan darah ABO ditetapkan berdasarkan ada tidaknya antigen A dan atau B pada eritrosit. Ukuran
berat molekul antigen tsb. Besar sehingga bersifat imunogenik yang dapat menimbulkan respons imun apabila
dipindahkan kepada orang lain dengan golongan darah yang berbeda, dan disebut antigen karena dapat berikatan
dengan antibodinya yang juga dijumpai pada serum darah orang lain dengan golongan darah ABO yang berbeda
pula.
Diketahuinya adanya antigen H (gen pengatur terletak pada kromosom 19) yang merupakan precursor / Ag dasar
dari Ag A & B sebagai berikut :
- Bila sebagian besar antigen H diubah menjadi antigen A, maka terbentuk golongan darah A
- Bila sebagian besar antigen H diubah menjadi antigen B, maka terbentuk golongan darah B
- Bila antigen H tidak diubah maka terbentuk golongan darah O
Golongan O memiliki Ag H paling banyak, apabila dilakukan pemeriksaan terhadap banyaknya Ag H dengan
menggunakan reagen anti H, maka didapat hasil dengan urutan sebagai berikut :
O>A2>A2B>B>A1>A1B
Pada orang-orang tertentu dari golongan darah O, tidak memiliki antigen A, B, maupun H, namun di dalam serumnya
dijumpai anti A, B, H yang kuat. Golongan darah ini disebut golongan O Bombay klasik (Oh). Ag A, B, H juga dijumpa
pada sel lain seperti normoblas, trombosit, leukosit, sel epitel / endotel/ epidermis dan dalam cairan tubuh lain
(disebut substance) a.1. pada salva saliva, urin, semen, keringat, ASI, cairan pencernaan, serta tersebar luas di alam
bebas, dapat dijumpai pada hewan, tumbuhan dan bakteri seperti E.coli (Ag heterofil). Ag O diekspresikan oleh
semua individu sehingga semua individu menjadi toleran terhadap AgO.
Antibody dalam serum golongan darah ABO (agglutinin)
Golongan darah A : ditemukan anti – B
Golongan darah B ditemukan anti – A
Golongan darah O ditemukan anti – A dan anti – B
Golongan darah AB tidak ditemukan anti – A dan anti – B
Anti-A yang terdapat pada golongan B & O terdiri dari 2 sub populasi yaitu yang reaktif terhadap Ag A1 maupun A2
(disebut anti – A) dan yang hanya reaktif terhadap Ag A1 (anti – A1). Pada 1 – 2 % populasi subgroup golongan
darah A2, disamping anti B juga dapat ditemukan anti – A1.
Bentuk anti – A dan anti – B pada individu
- Dapat seluruhnya berbentuk Ig M
- Sebagian Ig M dan sebagian Ig G
- Sebagian Ig M dan sebagian Ig A
- Campuran Ig M + Ig G + Ig A
Berdasarkan terbentuknya, Ig M dapat dibedakan sebagai berikut :
- Secara alami, dipengaruhi factor lingkungan & genetic
- Akibat respons imun : Ig M anti A dan anti B imun dapat terbentuk sebagai akibat adanya paparan oleh Ag
asing a.1.substansi A atau B dari spesies lain, kehamilan, transfuse darah yang tidak cocok. Ig G lebih
sering dijumpai pada golongan darah O, terbentuk karena respons iun. Kadang – kadang antibody golongan
darah ABO juga dapat terbentuk karena autoimunitas (terbentuk autoantibody).
Ig G lebih sering dijumpai pada golongan darah O, terbentuk karena respons imun. Kadang-kadang antibody
golongan darah ABO juga dapat terbentuk karena autoimunitas (terbentuk autoantibody).
Sifat anti A dan anti B
- Seperti halnya sifat yang dimiliki antibody pada umumnya : Ig M tidak dapat menembus plasenta. Ig G
dapat menembus plasenta sehingga dapat menyebabkan hemolytic disease of the newborn (HDN). Hal
ini terjadi karena Ag golongan darah anak (tidak sama dengan bu) memacu respons imun ibu sehingga
terbentuk Ab (Ig G terhadap Ag anak) dalam serum ibu yang kemudian menembus plasenta dan terjadilah
reaksi Ag-Ab dalam tubuh anak sendiri yang mengakibatkan lisis eritrosit anak. Keadaan ini disebut
hemolisis isoimun (bukan autoimun). Hal ini jarang terjadi karena pada golongan darah ABO IgM
merupakan molekul predominan dan tidak dapat menembus plasenta.
- Antibody ABO dapat menyebabkan destruksi eritrosit asing yang mengandung antigen yang sesuai (reaksi
Ag-Ab). Ig M maupun Ig G lebih suka menyebabkan agglutinasi eritrosit pada suhu kamar (20oC – 24oC)
atau lebih rendah (40C – 200C) disebut antibody dingin (cold antibody) Ig M menyebabkan agglutinasi
dengan aviditas tinggi. Sangat jarang dapat dijumpai anti A1 yang menyebabkan agglutinasi pada suhu di
atas 250C (warm antibody).
- Ig M dan Ig G merupakan activator yang efisien terhadap komplemen pada suhu 370C (complement
mediated lytic).
- Antibody tak lengkap / “ incomplete Ab”/”blocking Ab” : kadang-kadang dijumpai Ab yang gagal
menyebabkan aglutinasi eritrosit dalam suspense salin / aCl 0,9 %, karena adanya asam sialik yang
menimbulkan muatan listrik negative pada permukaan eritrosit. Terbentuk zeta potential dalam larutan salin
tersebut, sehingga eritrosit tidak dapat berdekatan satu dengan yang lain. Jadi walaupun Ab merupakan Ab
yang dapat berikatan satu dengan Ag pada permukaan eritrosit namun tidak dapat menghubungkan 2
eritrosit / tidak dapat menyebabkan agglutinasi karena tidak mampu melawan zeta potential. Antibody ini
kebanyakan dalam bentuk Ig G, kadang-kadang Ig M, sebagian Ig A. cara mendeteksi Ab tak lengkap /
inkomplit tersebut ialah dengan tes Coomb.
Distribusi golongan darah ABO
Disetiap Negara tidak sama
Di Indonesia sebagai berikut :
- Golongan O : 40,77 %
- Golongan B : 26,68 %
- Golongan A : 25,48 %
- Golongan AB : 6,66 %
Pemeriksaan laboratorium untuk golongan darah ABO
Penentuan golongan darah ABO
- Tes rutin yang dilakukan menggunakan reagen anti A dan anti B (ada yang ditambah anti AB) disebut tes
langsung/ direk/ forward grouping/red blood cells grouping test yaitu untuk menentukan agglutinogen
A/B/AB yang ada pada eritrosit.
Caranya : eritrosit penderita direaksikan dengan serum yang diketahui antibodinya (Ab).
- Tes yang menggunakan eritrosit A1 dan B untuk menentukan agglutinin A/B yang ada dalam serum disebut
reverse grouping / confirmation grouping/ serum grouping tests (ada juga yang menambahkan eritrosit A2).
Caranya serum penderita direaksikan dengan eritrosit yang diketahui antigennya (Ag).
- Kedua cara tersebut sebaiknya dilakukan bersama-sama
- Sebelum melakukan pemeriksaan maka petunjuk yang diberikan oleh pabrik harus dibaca dengan teliti
Contoh :
Metoda slide test :
Dapat digunakan untuk forward grouping karena tidak memerlukan pemusingan untuk menimbulkan reaksi
agglutinasi.
Cara :
- Pada sebuah gelas objek yang bersih dan kering diteteskan masing-masing 1 tetes : anti A, anti B dan anti
AB
- Kemudian setetes kecil darah diteteskan pada masing-masing tetesan antisera tersebut
- Campur dengan ujung pengaduk / sapu lidi yang bersih
- Goyangkan kaca dengan membuat gerakan lingkaran pada campuran it uterus menerus selama 2 menit
- Baca/ nilailah agglutinasi yang terjadi sebagai berikut : TABEL eaksi aglutinas golongan darah ABO
- Perlu diperhatikan kesalahan / kesulitan pembacaan yang dapat terjadi antara lain karena kesalahan teknik,
adanya bentukan rouleaux pada eritrosit, reaksi lemah pada subgroup ABO, keadaaan
hipogamaglobulinemia, leukemia.
Metode tabung (tube test)
- Metode tabung dapat juga digunakan untuk forwar drouping, cara penilaian idem slide test
- Untuk reverse grouping / serum grouping umumnya digunakan metode tabung atau microplate test karena
Ab yang ada pada serum penderita / donor seringkali terlalu lemah untuk menyebabkan agglutinasi eritrosit
tanpa pemusingan.
Deteksi antibody ABO : dengan tes Coomb direk :
Tes comb disebut juga tes anti-immunoglobulin, dibedakan 2(dua) macam tes Coomb :
- Direk /langsung
- Indirek / tak langsung
Perbedaannya terletak pada mekanisme test, namun keduanya mempunyai prinsip sama yaitu menggunakan reagen
serum antiblobulin terhadap globulin manusia yang disuntikkan pada kelinci. Untuk golongan dari system ABO, Ab
inkomplit dideteksi dengan tes Coomb direk
Indikasi tes Coomb direk : untuk mendeteksi adanya Ab inkomplit yang melekat pada eritrosit in vivo.
Contoh :
- Ikterus neonatorum / hemolytic Disease of the Newborn / HDn
- Reaksi transfuse
- Anemia hemolitik auto imun penambahan serum antiblobulin Coomb in vitro menyebabkan agglutinasi
eritrosit tersebut.
Cara :
- Dalam sebuah tabung berkuran 10 x 75 mm, teteskan 1 tetes suspense eritrosit dalam salin 2 – 5 %
- Cuci eritrosit tersebut x dalam volume salin yang lebih banyak. Hati-hati menuang supernatant jangan
sampai eritrosit terbuang.
- Campur baik-baik
- Pusing selama 15 detik dengan kecepatan 3400 rpm
- Periksa adanya agglutinasi dengan bantuan alat optic. Goyangkan / kocok tabung secara halus agar
eritrosit tidak berada pada dassar batung dan agglutinasi merata dalam suspense.
- Lakukan control dengan Ig-sensitized red cells.
GAMBAR
Sistem Rhesus :
Merupakan system yang kompleks, mungkin yang paling kompleks di antara semua system golongan darah yang
dikenal.
Sejarah penemuan :
- System Rhesus (Rh) ini dikenal sejak Levine dan Stetson tahun 1939 melaporkan adanya antibody dalam
serum ibu setelah mendapat transfuse darah suaminya yang menyebabkan terjadinya reaksi transfuse pada
dirinya dan berakibat fatal pada janin yang dikandungnya karena menderita Hemolytic Disease of the
Newborn / HDN.
- 1940 Landsteiner dan Wiener menyuntik kelinci / marmot dengan darah kera rhesus (Macaca mullata),
kemudian Ab yang terbentuk ternyata dapat menyebabkan agglutinasi pada eritrosit kera dan kira-kirea 85
% eritrosit donor manusia.
- Pada tahun yang sama (1940) Wiener dan Peters menemukan Ab tersebut dalam serum individu tertentu
yang mengalami reaksi transfuse setelah mendaapat transfuse darah donor dengan golongan darah yang
cocok (system ABO compatible).
- Dilaporkan bahwa A ini tidak dapat dibedakan dengan Ab yang ditemukan oleh Levine dan Stetson.
- 1941 Levine dan kawan-kawan menunjkkan bahwa erythroblastosis fetalis (HDN) adalah sebagai akibat
dari ketidak cocokkan golongan Rh antara ibu dengan anak.
Gen pada system Rh :
Gen yang mengatur system Rh terletak pada lengan pendek kromosom 1. Genetika system Rh adalah sangat
kompleks / polimorf. Banyak terori yang berbeda telah dikemukakan tentang gen yang mengatur produksi antigen, 2
diantaranya pada tahun 1943 oleh :
- Fisher race : enyatakan adanya 3 lokus (liki), masing-maing ditempati gen dengan alelnya : C & c, D & d, E
& e. dari informasi ini gen Rh yang kompleks diasumsikan memiliki 8 kombinasi gen yang closely linked
sebagai berikut : ce, CDe, cDE, CDE, cde, Cde, cdE, CdE.
- Wiener : menggambarkan adanya alel multiple (jumlah tak terbatas) menempati kompleks lokus tunggal. 8
alel utama disebut : Ro, R1, R2, Rz,r,r’, r”, ry.
- Kedua teori gen ini dapat dibandingkan sebagai beikut :
TABEL : perbandingan nomenklatur gen FisherRace & Wiener
Antigen Rh
Atas dasar nomenklatur gen Fisher-Race tsb di atas maka Ag Rh disebug Ag C, D, E, c, d, e (Ag d maupun anti – d
sebenarnya tidak pernah ditemukan, enyebutannya hanya untuk menyatakan tidak adanya D) sedangkan menurut
Wiener Ag Rh disebut Rh 0, Rh 1, Rh 2, Rh x, rh, rh’, rh”, rh y.
Antigen Rhesus tidak diijumpai pada asel lain kecuali eritrosit, juga tidak dijumpai dalam saliva. Ag D, dianggap
sebagai Ag yang paling bermakna dalam klinik setelah system ABO, sebab bersifat sangat antienik / imunogenik.
Dari hasil pemeriksaan terhadap Ag D pada eritrositnya tanpa memandang adanya Ag C atau Ag E umum
dinyatakan sebagai Rh negative, sedangkan yang cukup Ag D dinyatakan sebagai Rh positif. Dulu Rh positif
seringkali disebut sebagai Rh o (D).
Antibodi Rh :
Ab dalam serum yang pertama kali dilaporkan oleh Levine & Stetson (1939) adalah terhadap Ag D. anti- D ini
ternyata tidak dapat dibedakan dengan Ab dalam serum manusia yang kemudian ditemukan oleh peneliti-peneliti
selanjutnya dan disebut human anti – Rh (sebutan human anti Rh ini untuk membedakan dengan factor Rh yang
timbul karena penyuntikan dengan eritrosit kera Rhesus, factor rh dari kera ini sekarang disebut anti L-W). pada
individu yang eritrositnya tidak / kurang mengandung Ag D, sangat jarang secara alami/natural dapat ditemukan anti
D dalam serumnya. Pembentukan Ab hamper selalu disebabkan karena pemaparan Ag G antara lain dengan cara
transfuse atau kehamilan dan timbul setelah 2 – 6 bulan. Dalam klinik Ab ini sangat penting karena dapat
menyebabkan reaksi transfuse dan HDN. Kebanyakan anti – Rh adalah Ig G (biasanya Ig G1, Ig G3), namun
dilaporkan bahwa Ig M juga dapat ditemukan dan Ig A dalam jumlah sedikit.
- Ig G lebih sering terdeteksi dengan tes antiglobulin dan dapat ditingkatkan dengan metode ensim.
Penambahan enzim (tripsin / papain/ fisin) dapat mengurangi “zeta potential” dari muatan listrik negative.
- Ig M lebih sering terdeteksi dengan tes salin.
- Ab Rh jarang mengaktifkan komplemen
Distribusi golongan darah Rh :
- Di Indonesia kurang lebih 99 % Rh Positif
Pemeriksaan laboratorium :
Penentuan golongan darah Rh :
Dilakukan hanya dengan indikasi tertentu :
- Family studies
- Paternity testing
- Transfuse darah : dilakukan pada donor karena resipien dengan golongan Rh negative harus mendapat
transfuse dengan donor Rh negative
- Prenatal testing, dalam usaha untuk mencegah HDN
Metode pemeriksaan :
Dikenal metoda slide, tube, saline – reactive serum :
- Teknik agglutinasi slide / tube tests digunakan secara rutin untuk menetapkan ada / tidaknya Ag D
(menyatakan Rh positif / negative).
- Metoda saline reactive serum hanya dilakukan bila terjadi agglutinasi spontan atau pembentukan rouleaux,
bila eritrosit dilapisi dengan anti D pada HDN, pada autoimmune hemolytic anemia, atau bila hasil tes slide /
tube meragukan.
- Petunjuk yang diberikan oleh pabrik harus dibaca denan teliti sebelum melakukan pemeriksaan
- Harus dilakukan tes control positif maupun negative.
- Harus diperhatikan kesalahan tehnik / halhal lain yang memungkinkan hasil positif maupun negative palsu
seperti misalnya : kontaminasi dengan bakteri (positif palsu), pembacaan hasil melebihi waktu yang
ditetapkan sehingga eritrosit dan anti-serum dibiarkan bercampur terlalu lama (negative palsu).
Deteksi anti-Rh/ anti –D
Tes Coomb direk :
Indikasi : untuk mendeteksi adanya anti Rh (Ab inkomplit) yang bebas dalam serum.
Cara :
- Pada tes ini terlebih dulu dilakukan pelapisan eritrosit normal dari golongan darah O/yang sesuaidengan
golongan serum yang akan diperiksa.
- Dalam sebuah tabung berukuran 10 x 75 mm, teteskan 2-6 tetes serum penderita
- Tambahkan 1 tete suspense erirsosit (washed) 5% (erirosit golongan O atau yang compatible) boleh
ditambahkan 2 tetes bovine albumin.
- Campur baik-baik
- Inkubasi pada suhu 370C selama 15 – 30 menit
- Keluarkan dari incubator segera pusingkan selama 15 detik dengan kecepatan 3400 rpm.
- Periksa adanya hemolisis dan agglutinasi dengan bantuan alat optic dan catat.
- Cuci 3-4x dalam salin, buang salin pada setiap pencucian sesempurna mungkin
- Tambahkan 1-2 tetes reagen antiglobulin
- Campu baik-baik
- Pusing selama 14 detik dengan kecepatan 3400 rpm
- Periksa adanya agglutinasi dengan bantuan alat optic.
- Catat hasilnya
- Tambahkan 1 tetes erirosit tersensitasi yang sudah diketahui pada semua hasil yang negative
- Pusing selama 15 detik dengan kecepatan 3400 rpm
- Periksa adanya agglutinasi, bila negative berarti tidak valid dan pemeriksaan harus diulang.
GAMBAR
Rujukan :
1. Bryant JB. An introcution to immunohematolog.3rd ed. Philadelphia : WB Saunders, 1994; p 98 – 128, 141 –
68
2. Walker Rh.Technical manual. 11th ed.Bethesda : American association of blood bank, 199; p 203 – 58
3. Rudmann SV. Textbook of blood and transfusion medicine. Philadelphia : WB Saunders, 1995 ; p 66 – 81,
98 – 115
4. Siti Boedina Kresno Pengantar hematologi dan imunohematologi. Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 1988; p
133 – 39
5. Abbas Ak, Lichtman AH, Pober JS. Celluler and moleculer immunology, 5th ed. Philadelphia : Saunders,
2003 ; p 369, 386-7, 503.
6. Benyamini E, Leskowitz S. Immunology a short course. 2th ed. New York : Wiley – Liss, 1991; p 101 – 2
7. Mollison PL, Engelfriet CP, Contreras M. Blood transfusion in clinical medicine, 10th ed. Singapore :
Blackewell Science, 1997; p 115 – 85
TRANSFUSI DARAH dr.Lisyani B. Suromo, SpPK(K)
Pendahuluan
Transfuse darah mempunyai tujuan yang menguntungkan, yaitu memperbaiki keadaan umum penderita sehingga
tercapai suasana homeostatic. Secara khusus tujuan utama transfuse darah ialah untuk : meningkatkan oksigenasi
jaringan, koreksi hipovolemia, hemostasis meningkatkan fungsi leukosit pada kasus-kasus tertent sesuai dengan
tujuannya maka transfuse darah dapat dilakukan dengan pemberian darah lengkap atau komponen darah.
Transfuse darah merupakan bentuk pengobatan sementara yang berlangsung sepanjang umur hidup sel-sel darah /
komnponen darah tersebut. Efek yang menguntungkan dari pemberian transfuse darah / komponen darah ini bukan
berarti bahwa transfuse darah selalu dapat berjalan tanpa risiko, karena ada kemungkinan akan timbul reaksi
tarnsfusi yang tidak menguntungkan, kira-kira 6,6 – 10 % dari resipien mengalami hal ini.
Reaksi transfuse dapat terjadi baik selama penderita masih mendapatkan transfuse maupun setelah transfuse
dihentikan. Reaksi transfuse dapat terjadi baik selama penderita masih mendapatkan transfuse maupun setelah
transfuse dihentikan. Reaksi transfuse yang tidak menguntungkan tersebut ada yang dapat dihindari, walaupu ada
juga yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu sebelum melakukan transfuse harus dipertimbangkan dengan
mantap indikasi – dan kontra indikasinya dan diantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Keberhasilan transfuse darah
harus dapat diupayakan semaksimal mungkin dengan cara memperhatikan persyaratan / persiapan pra transfuse,
seleksi donor, proses pengambilan ,pengolahan, penyimpanan, pemakaian bahan serta dilakukan pemantauan-
pemantauan terhadap petanda reaksi transfuse sedini mungkin.
1. Guna transfuse darah :
Transfuse darah dilakukan dalam upaya untuk
- Mengatasi keadaan gawat darurat (life saving)
- Pengobatan penunjang (supportive treatment)
- Pengobatan pencegahan (preventive treatment)
2. Bahan transfuse darah :
Diberikan dengan pertimbangan yang paling aman dan paling cocok untuk mengatasi keadaan penderita.
Macam bahan : dapat mengandung sel darah merah, dapat pula tidak, dibedakan sebagai berikut.
- Darah lengkap (whole blood)
- Komponen darah :
o Eritrosit pekat (packed cells)
o Washed red cells
o Eritrosit rendah leukosit (leukocyte poor red cells)
o Leukosit (granulosit)
o Trombosit
o Kriopresipitat / derivate plasma seperti factor BIII pekat, factor IX pekat, factor II, VII, IX, Xpekat,
albumin, fibrinogen, gammaglobulin.
Darah lengkap (whole blood)
Definisi
Darah lengkap adalah unit darah selengkapnya yang diperoleh dari donor tanpa ada pemisahan komponennya baik
sel maupun non sel.
Ketentuan standar : jumah darah 450 kurang lebih 45 ml dieri anti-koagulan / pengawet eritrosit
Modifikasi ehole blood yaitu dipisahkan kriopresipitat dan atau trombositnya.
Antikoagulan yang dipakai :
Yang mengandung dekstrose ; dekstrose diperlukan untuk nutrisi eritrosit. Contoh :
- Citrate – Phosphate – Dextrose / CPD
- Acid – Citrate – Dextrose / ACD ( dengan CPD atau ACD ini darah dapat disimpan sampai 21 hari)
- Citrate – Phosphate – Dextrose – Adenine – 1/CPDA-1 (dengan penambahan adenine darah dapat
disimpan sampai 35 hari). Dikenal antikoagulan CPDA-2, CPDA-3 yang mengandung adenine dan
dekstrose lebih tinggi daripada CPDA-1 sehingga eritrosit pekat dapat diawetkan sampai 7 minggu.
- CPD + AS-1 / AS-2 (AS = additive solution yang terdiri dari salin, desktorse, manitol, adenine)
- Citrate – Phosphate, Double Dextrose + AS (terdiri dari salin, dekstrose, adenine).
- Heparin : tidak ditambah destrose, sehingga usia simpan hanya sampai 48 jam.
Penyimpanan
- Temperature penyimpanan
Setelah darah diambil dari donor segera disimpan pada suhu antara 10 – 60C. pada suhu sekitar ini glikolisis
terjadi secara perlahan-lahan. Suhu penyimpanan terbaik ialah 40C, karena pada suhu ini asam laktat yang
terbentuk akan sangat menurunkan pH dan fungsi enzim heksokinase serta fosfofruktokinase sehingga
glikolisis terhenti. Di bawah 10C maka karena efek dari dekstrose eritrosit akan membengkan, menjadi
sangat fragil dan cenderung hemolisis. Di atas suhu 60C bakteri akan berkembang biak, sehingga umur
hidup eritrosit menjadi lebih pendek.
- Efek samping penyimpanan
Setelah disimpan maka store whole blood tidak lagi mengandung granulosit & trombosit yang dapat
berfungsi, demikian juga factor pembekuan yang labil (factor V, VII) menjadi rusak. Darah yang diambil dari
donor harus diperiksa lengkap selain golongan darah, deteksi antibody, juga tes untuk penyakit menular
yang memerlukan waktu cukup lama untuk melakukannya, sehingga darah harus di simpan. Di samping itu
tidak ada indikasi kuat yang menyokong keharusan menggunakan fresh whole blood / darah segar untuk
ditrasfusikan kepada resipien.
Darah ini mengandung leukosit yang masih mampu berfungsi membunuh bakteri,oleh karenanya bila
memang sangat diperlukan darah segar maka dapat dibiarkan pada temperature kamar dalam waktu
singkat, namun hal ini tidak direkomendasikan.
Indikasi penggunaan whole blood :
- Pada penderita dengan kehilangan darah sangat banyak / berat (mencapai 25 – 30 %), sehingga
menimbulkan gejala hipovilemi / syok. Pada keadaan ini whole blood diperlukan untuk mengembalikan atau
memelihara volume darah dan kapasitas mengangkut oksigen.
- Pada keadaan dimana diperlukan pengembalian volume darah yang seimbang / sama pentingnya dengan
komponen seluler.
- Untuk transfuse tukar (exchange transfusion) pada bayi baru lahir.
Kontra indikasi :
- Penderita dengan anemia kronik yang berat dimana telah terjadi kompensasi terhadap penurunan sel darah
merah yaitu dengan terjadinya peningkatan volume plasma / peningkatan cardia output sehingga kebutuhan
O2 jaringan dapat dipenuhi (anemia normovilemik). Penderita ini tidak memerlukan plasma yang ada dalam
whole blood, sehingga dapat terjadi kelebihan volume yang memingkinkan bahaya udem paru dan payah
jantung.
- Penderita yang hanya memerlukan pengembalian volume plasma, maka whle blood merupakan
kontraindikasi mengingat plasma mungkin mengandung mikroorganisme yang menular.
Komponen darah :
Pemakaian komponen darah mempunyai keuntungan secara umum sebagai berikut :
- Mengurangi kemungkinan circulatory overload
- Mengurangi kejangkitan reaksi transfuse
- Mengurangi volume antikoagulan dan elektrolit
- Darah dari satu donor dapat dimanfaatkan untuk lebih dari satu resipien
Eritrosit pekat (red cell concentratres – packed cells) :
Packed red cells adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan sel darah merah pekat yang
diperoleh setelah pemisahan plasma dari whole blood dengan cara pemusingan atau pengendapan pada suhu 40C.
eritrosit pekat ini sudah tidak mengandung granulosit maupun trombosit yang berfungsi, dan harus disimpan pada
suhu antara 1 – 6 0C.
Nilai hematokrit dari 1 unit eritrosit pekat bervarias tergantung dari medium suspensinya, berkisar antara 52 – 60 %.
Bila disimpan dengan menggunakan CPDA-1 sebagaiantikoagulan / pengawet, nilai hematokrit sekitar 70 – 80 %.
Indikasi penggunaan eritrosit pekat :
- Untuk penderita anemia normovolemik / yang tidak membutuhkan peningkatan volume darah, diberikan
dengan tuuan untuk meningkatkan kapasitas mengangkut oksigen.
Kontra Indikasi :
- Anemia kronik yang telah terkompensasi dengan baik seperti pada gagal ginjal kronik
- Anemia defisiensi besi, anemia pernisiosa.
Washed red cells :
Dilakukan pencucian darah sebanyak 2-3x dengan larutan garam fisiologik sehingga dapat dipisahkan leukosit dan
plasmanya. Washed rec cells sebainya tidak disimpan setelah selesai diolah, harus segera diberikan kepada
penderita dan bila terpaksa dapat disimpan dalam waktu sangat singkat pada temperature 10 – 60 C.
Indikasi penggunaan washed red cells :
- Penderita dengan febris dan reaksi alergik terhadap transfuse yang menggunakan eritrosit yang tidak dicuci
(leukosit sebagai penyebab kebanyakan febris, plasma reaksi alergik).
- Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
- Penderita dengan sensitivitas terhadap protein plasma
Leukocyte – poor red blood cells :
Eritrosit rendah leukosit juga dikenal sebagai leukocyte reduced red cells yaitu sekurang-kurangnya 70 – 80 % dari
jumlah leukosit yang semula ada telah dipisahkan, dapat diperoleh secara manual dengan cara mencuci sel darah
merah 4 – 6 x dalam larutan salin normal atau menggunakan alat pencuci automatic. Sediaan ini harus disimpan
pada suhu 10 – 60 C setelah pengolahan dan harus digunakan secepat mungkin dalam waktu 24 jam.
Indikasi penggunaan leukoscyt – poor red blood cells : diberikan kepada penderita untuk multitransfusi sebagai
berikut :
- Dengan riwayat febris berulang karena adanya antibody terhadap leukosit
- Dengan penyakit ginjal yang menjalani dialysis, untuk mengurangi risiko aloimunisasi terhadap Ag leukosit
dan trombosit.
Dalam upaya agar tidak / seminimal mungkin terjadi reaksi transfsi masih dikenal sediaan sel darah merah lain
seperti frozen – thawed red blood cells (sel darah merah cair yang dibekukan)/ frozen – deglycerolized red blood
cells dan lain-lain.
Leukosit (granulosit) concentrates:
Teknik untuk memperoleh granulosit ini tidak praktis bila diambil dari sediaan darah donor, karena butuh 30 – 50 unit
darah segar untuk 1 x transfuse, maka lebih disukai cara leukapheresis. Umumnya sediaan granulosit (neutrofil)
yang sudah diperoleh segera diberikan dan tidak boleh disimpan, bila terpaksa maka penundaan tidak boleh lebih
dari 24 jam serta harus disimpan pada temperature 20 – 240C, karena survival granulosit akanberkurang. Menurut
laporan para peneliti, setelah disimpan 8 jam maka granulosit berkurang kemampuannya untuk beredar dalam
sirkulasi dan bermigrasi ke lokasi inflamasi.
Indikasi penggunaan leukosit (granulosit) concentrates
- Diberikan kepada penderita dengan infeksi yang tidak terkontrol dengan antibiotika terpilih. Bila terjadi
disfungsi granulosit sepert pada keadaan neutropenia, granulomata kronik, dengan jumlah granulosit
kurang dari ,5 x 109 / L atau 0,5 x 103/mm3, dalam jumlah tersebut risiko terjadinya infeksi makin besar
(risiko infeksi terjadi bila jumlah granulosit turun di bawah 1 x 109/L). dilaporkan bahwa transfuse granulosit
bermanfaat pada neonates dengan infeksi berat karena fungsi neutrofil belum sempurna dan produksi
neutrofil terbatas.
- Penderita leukemia, transplantasi sumsum tulang, yang mendapat kemoterapi intensif.
Kontra Indikasi
- Pada infeksi yang dapat dikontrol dengan antibiotika
- Pada penyakit dengan prognosis jelek seperti keganasan, sebab efek granunosit hanya bersifat sementara.
Trombosit
Sediaan trombosit dapat diperoleh dengan cara cytapheresis atau secara manual dengan pemusingan fresh ehole
blood, dikerjakan dalam 6 – 8 jam setelah darah diambil dari donor.
Dikenal bermacam-macam sediaan trombosit antara lain :
- Berdasarkan jumlah trombosit & banyaknya volume plasma sebagai suspense dikenal : platelet
concentrates, platelet rich plasma. Platelet concentrates dengan cara pemusingan 1 unit whole blood
mengandung minimal 5,5 x 1010/ L trombosit, disuspensikan dalam kira-kira 50 ml plasma sedemikian
sehingga pH dapat mencapai 6,0 atau lebih pada akhir periode penyimpanan yang diperbolehkan dan
ditetapkan / diukur pada suhu penyimpanan. Dengan dara cytapheresis dari 1 donor tunggal dapat
diperoleh 1 unit platelet yang mengandung minimal 3x1011 /L trombosit. Jumlah tersebut ekuivalen dengan
6-8 unit whole blood bila dilakukan dengan cara pemusingan.
- Berdasarkan pengolahan dan penyimnpanannya : washed platelets, pooled platelets, irradiated platelets,
leukocyte – reduced platelets, frozen platelets dan lain-lain.
Suhu optimal untuk penyimpanan trom bosit adalah 220C dan harus konstan digerakkan secara halus, dalam kondisi
ini dengan system tertutup dapat disimpan selama 5 hari, sedangkan dengan system terbuka tidak boleh lebih dari
24 jam.
Indikasi penggunaan trombosit :
Banyak factor harus dipertimbangkan sebelum pemberian transfuse trombosit yang meliputi :
Kondisi klinik penderita, jumlah dan fungsi trombosit resipien, penyebab trombositopenia. Disamping itu perlu
diperhatikan adanya antigen HLA pada trombosit yang memungkinkan terjadinya reaksi penolakan bila antara
resipien donor tidak HLA compatible serta hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan untk meningkatkan
jumlah trombosit.
- Diberikan kepada penderita dengan trombositopenia karena penurunan produksi trombosit atau fungsi
trombosit yang abnormal, perdarahan.
- Untuk terapi pencegahan terhadap trombositopenia dan atau trombositopati di mana dapat terjadi
perdarahan tak terkontrol sebagai akibat dari tindakan operasi besar, perdarahan gastrointestinal.
Banyak perbedaan pendapat tentang jumlah trombosit yang perlu ditransfusi. Dissebutkan bahwa kecil trerjadinya
resiko perdarahan pada penderita dengan jumlah trombosit kurang lebih 20 x 109 / L. perdarahan yang serius baru
terjadi bila jumlah trombosit kurang dari 5 x 109 / L. perlu dicatat bahwa transfuse masih juga dapat menyebabkan
trombositopenia karena pengenceran trombosit akibat penambahan cairan dan penggunaan darah simpan.
Kontra indikasi :
- Sebaiknya tidak diberikan kepada penderita idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) karena trombosit
yang ditransfusikan akan cepat rusak, juga pada splenomegali, sepsis, karena dapat terjadi kegagalan
untuk meningkatkan jumlah trombosit.
- Thrombotic thrombocytopenic purpura, drugs / heparin – induced thrombocytopenia, DIC, karena pada
penderita ini bahaya pebentukan thrombus dapat segera terjadi setelah transfuse. Secara umum setiap unit
trombosit yang ditransfuikan diharapkan dapat meningkatkan jumah trombosit 5000 – 10000 / mikro L untuk
individu dengan BB 70 Kg.
Plasma dan komponen plasma
Sejak perang dunia II, pemakaina plasma tidak lagi dipandang bermanfaat sebagai volume expander untuk
mengatasi keadaan syok hemoragik. Dalam praktik kedokteran dewasa ini plasma dan komponen plasma
mempunyai banyak kegunaan lain dan permintaan-permintaan yang diajukan untuk menggunakannya makin
meningkat.
Plasma dapat dikumpulkan dari pemisahan darah whole blood atau dengan cara plasmapheresis manual atau
metode automatic.
Macam sediaan :
- Plasma segar beku (fresh – frozen plasma) yaitu plasma yang mengandung factor – factor pembekuan labil
(V, VIII) maupun stabil yang masih berfungsi. Hal ini diproses dengan memperhatikan antikoagulan
tercampur rata pada whole blood dan plasma yang diperoleh harus secepatnya dibekukan. Bila plasma
segar tidak dibekukan maka factor pembekuan labil tidak lagi berfungsi. Fresh-frozen plasma dapat
disimpan sampai 1 tahun dalam temperature konstan -180 C atau lebih rendah. Seelum dipakai maka harus
dicarikan pada suhu 30 – 370C dan diberikan kepada penderita dalam 2 jam setelah pencairan.
- Plasma simpan cair atau beku (stored plasma : liquid or frozen) : sediaan ini dapat diperoleh dari whole
blood setiap waktu dilakukan pemisahan, juga dapat diproses dari store whole blood yang sudah tidak
terpakai / kadaluwarsa sampai dengan 5 hari setelah tanggal kalauwarsa yang ditetapkan. Fresh frozen
plasma (plasma segar beku) yang tidak terpakai dalam 12 bulan dapat dijadikan stored plasma. Stored
plasma ini dapat digunakan untuk terapi defisiensi factor stabil terutama factor IX, tidak dapat dipakai untuk
volume expander. Plasma yang disimpan dalam keadaan cair pada suhu antara 1-60C hanya dapat
bertahan sampai 26 – 40 hari, sedangkan pada suhu 180 C atau lebih rendah sampai 5 tahun.
- Cryoprecipitated antihemophilic factor / factor VII concentrate
- Factor IX concentrate / prothrobin complex : terdiri dari factor pembekuan II, VII, IX, X
Plasma Albumin
Indikasi
- Untuk terapi syok hipovolemik karena perdarahan atau tindakan bedah
- Pada kebakaran untuk mengembalikan protein dan cairan
- Ntuk pengembalian (fluid replacement) selama penderita yang menjalani terapi plasma exchange secara
automatic
- Untuk memacu dieresis pada udem karena hipoalbuminemia
- Pada hiperbiliburinemia neonates untuk membantu mengikat bilirubin yang tidak terkonjugasi
Perlu diperhatikan pemberian albumin yang berlebihan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan onkotik plasma
sehingga cairan ekstravaskuler masuk ke dalam intravaskuler. Dikenal plasma subtitusi yang lain yaitu plasma
protein fraction yang terdiri dari 83 % albumin dan 17% globulin, perlu diperhatikan pula pemberian cairna yang
cepat memungkinkan terjadinya keadaan hipotensi sebagai akibat adanya vaoaktif kinin.
Dikenal pula volume expander sintetik yang terdiri dari salin normal, Ringer’s laktat, destran B.M besar atau kecil dan
pati hidroksietil. Dapat digunakan pada perdarahan dan syok karena kebakaran.
REAKSI TRANSFUSI
Istilah reaksi transfuse biasanya diartikan sebagai respons tidak meguntungkan yang terjadi setelah pemberian
transfuse darah uampun produk darah. Hal ini sebenarnya tidak tepart karena dapat pula terjadi respons yang
menguntungkan ,namun reaksi tidak menguntungkam merupakan masalah yang harus ditangani dengan cepat dan
tepat. Setiap reaksi yang tidak menguntungkan harus dipandang sebagai “mengancam jiwa penderita “ sampai
pemantauan klinik dan hasil pemeriksaan laboratorik menentukan laihn. Reasksi transfuse tidak selalu sebagai
akibat dari ketidak cocokan golongan darah dalam arti kata adanya reaksi antigen – antibody sehinggam
engakibatkan destruksi sel darah merah. Hal ini bahkan hanya dijumpai dalam persen relative kecil.
- Klasifikasi reaksi transfuse : - akut / tertunda (delayed) : disebut akut bila terjadi dalam 1-2 jam setelah
transfuse dikerjakan, sedangkan tertunda dapat terjadi berhari-hari, (lebih dari 2 hari), berbulan-bulan
bahkan bertahun-tahun setelah transfuse.
- Imunologik / nonimunologik Klasifikasi ini lebih disukai
Reaksi imunologik :
Reaksi ini timbul sebagai akibat adanya stimulasi alloantigen (Ag asing dari spesies yang sama tetapi berbeda
genetic) yang terdapat pada eritrosit, leukosit, trombosit & protein plasma darah donor yan g ditransfusikan. Respons
tersebut meliputi :
Febrile reaction:
Febrile reaction didefinisikan sebagai adanya peningkatan temperature 100C atau lebih di atas suhu normal selama
transfuse darah / komponen darah tanpa ada sebab lain. Demam umumnya timbul dalam 2 jam atau pada akhir
transfuse dan dapat disertai menggigil. Reaksi ini merupakan reaksi transfuse yang paling banyak dijumpai,
disebabkan karena adanya reaksi antara Ag pada leukosit & trombosit yang ditransfusikan dengan Ab dalam serum
penderita.
Leukosit dan trombosit memiliki Ag hLA dan Ag spesifik. HLA kelas I dijumpai pada hamir semua sel berinti dan
trombosit, sedangkan HLA kelas II dijumpai pada monosit / makrofag, limfosit B dan limfosit T teraktivasi. Reaksi
antara Ag HLA dengan anti- HLA memegang peran predominan di dalam timbulnya gejala febris & menggigil, namun
reaksi Ag spesifik leukosit/trombosit dengan Ab spesifik juga dapat terjadi. Febrile reaction terbanyak dijumpai pada
penderita multi transfuse dan multigravida.
Perlu dicatat bahwa febrile reaction juga dapat disebabkan karena substansi pirogen (cemaran polisakarid bakteri).
Pulmonary reaction juga dapat terjadi karena granulosit atau agregat/ kompleks imun Ag-Ab granulosit terkumpul di
daerah vaskuler paru.
Reaksi alergik atau anafilaktik:
Reaksi alergik menduduki urutan kedua setelah febrile reaction. Manifestasi klinik dapat ditandai dengan urtikaria,
eritema, gatal. Reaksi yang terjadi dapat ringan (palin sering terjadi dan ada yang menyebutnya sebagai anfilaktoid),
sedang, berat / mengancam jiwa penderita. Pada yang berat (feaksi tipe anafilaktik) penderita merasa panas dan
kulit memerah (flushing), dispneu, dapat hipotensi.
Bila dijumpai urtikaria maka transfuse perlu dientikan kecuali pada urikaria setempat (localized). Pathogenesis
urtikaria tidak jelas diketahui, namun dipandang merupakan akibat dari reaksi Ab dengan Ag terlarut (biasanya dalam
protein plasma). Kemungkinan sebagai penyebab kebanyakan dari tipe anafilaktik ialah interaksi antara Ig A sebagai
Ag dalam plasma yang ditransfusikan dengan anti-Ig A sebagai Ag dalam plasma yang ditransfusikan dengan anti –
Ig A dalam plasma resipien. Keadaan ini banyak dijumpai pada resipien dengan defisiensi Ig A.
Reaksi hemolitik
Ada hubungannya dengan ketidakcocokan Ag pada eritrosit (red cells incompatibility). Reaksi yang disebabkan oleh
ketidak cocokangolongan darah system ABO dapat dikatakan sangat jarang terjadi karena transfsi dilakukan hanya
pada ABO compatible, kecuali ada kesalahan teknik. Dalam hal ini Ag A / Ag B eritrosit donor berikatan dengan anti
– A / anti – b (predominan IgM) dan komplemen serum resipien mengakibatkan destruksi eritrosit donor
intravaskuler. Aktivasi komplemen juga akan melepaskan C3a dan C5a yang mempunyai aktivitas anafilatoksik, di
samping itu kompleks imun juga memacu mekanisme koagulasi melalui factor XII disertai pembentukan bradikinin
dan memacu trombosit untuk melepaskan histamine dan serotonin. Syok terjadi sebagai akbiat pelepasan substansi
vasoaktif ini. Reaksi hemolitik ini timbul segera setelah transfuse dan seringkali berakibat faal.
Incompatibility yang sering dijumpai ialah karena ketidak cocokan dalam system Rhesus, Kell juga dapat dijumpai
pada golongan Duffy dan Kidd, jarang pada lain-lain golongan darah. Apakah hemolisis terjadi segera, secara lambat
atau bahkan tidak terjadi, tergantung dari respons primer / sekunder, kuat-lemahnya reaksi Ag-Ab, banyak sedikitnya
kadar Ab dalam serum resipien yang akan berikatan dengan Ag donor. Pada respons primer terhadap Ag Rhesus,
Ab (anti-D) terbentuk minimal 4-8 minggu setelah pemaparan, bahkan dapat sampai 5-6 bulan, sehingga kadang-
kadang (jarang) bias terjadi reaksi hemolitik yang tertunda. Pada reaksi hemolitik yang tetunda, destruksi eritrosit
umunya ekstravaskuler di dalam system retikuloendotelial dan gejala lebih ringan daripada respons tipe segera.
Reisiko terjadinya reaksi Ag-Ab makin meningkat pada penderita yang mendapat multitransfusi, penderita
multigravisa (respons sekunder / anamnestik).
Graft versus host disease /GVHD
Merupakan reaksi imunologik yang terjadi karena transfuse mengandung limfosit T imunokompeten diberikan kepada
resipien dalam keadaan imunosupresi.
Reaksi non imunologik antara lain :
- Volume overload / circulatory overload : peningkatan volume darah menyebabkan kerja jantung diperberat
sehingga dapat mengakibatkan payah jantung kongestif dengan gejala batuk-batuk, sianosis, kesulitan
bernapas. Hal ini dapat dihindari dengan pemberian packed red cells untuk penderita yang membutuhkan
transfuse dalam keadaan normovolemik.
- Penularan penyakit antara lain hepatitis virus B, C, malaria, sifilis, HIV
- Kontaminasi dengan bakteri
- Pemakaian dekstrose 5 % dalam larutan hipertonik, bahan tikda dibekukan teratur, pemberian dilakukan
dengan tekanan kuat, darah diberikan dalam kondisi masih beku, darah hemolisis / terinfeksi / dipanaskan
berlebihan (overheated) dan lain-lain dapat menyebabkan hemolisis non imunologik
- Hemosiderosis pada multitransfusi : kadar besi berlebihan dan tertimbun dalam jaringan, antara lain pada
penderita talasemia mayor, anemia hemolitik congenital, anemia aplastik yang mendapat multitransfusi.
PEMERIKSAAN LABORATORIUM :
Meliputi pemeriksaan untuk :
- Seleksi donor
- Tes silang
- Tes pada reaks transfuse
Tes seleksi donor :
sebelum dilakukan pemeriksaaan laboratorium maka harus diperiksa secara fisik bahwa donor dalam kondisi sehat,
tidak hipertensi, berat badan cukup[ (minimal) 50 kg untuk dapat diambil darah sejumlah kurang lebih 450 ml. di
Indonesia umumnya darah diambil sebanyak 250 ml dan diambil 350 ml untuk donor berberat badan lebih dari 55 kg,
tidak sedang hamil, tidak ada ketergantungan obat, tidak mengidap penyakit kronis antara lain tuberculosis, berumur
17 – 65 tahun dan lain-lain. Darah donor diambil dalam 4-6 jam setelah makan.
Penentuan golongan darah :
Pemeriksaan ini harus dikerjakan karena syarat utam untuk dapat dilakukan transfuse ialah golongan darah
compatible antar donor dengan resipien. Golongan darah ABO adalah yang terpenting dan sebaiknya ditentukan
dengan forward and reverse grouping tests bersama –sama. Golongan darah yang kedua iala Rhesu, karena
resipien golongan Rh negative harus ditransfusi dengan Rh negative pula (cara pemeriksaan golongan darah lihat
kulia golongan darah).
Pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit;
Untuk dapat diperoleh jumlah darah 450 ml kurang lebih 45 ml, maka hb donor minimal 12,5 g/dl, atau hematokrit
minimal 38 %. Hb akan turun 1 gr/dl untuk setiap pengambilan 450 ml.
Skrining untuk kemungkinan adanya Ab dalam serum donor yang mempunyai riwayat pernah hamil / mendapat
transfuse.
Deteksi B dilakukan dengan teknik antiblobulin coomb indirek, tes ensimatik, low ionic strength solution /LISS
Te
Untuk mendeteksi penyakit menular :
Donor dengan hasil tes-tes tersebut dibawah positif maka tidak dapat diterima sebagai donor :
- Plasmodium malaria
- Seromarker virus hepatitis B C : HBs Ag, anti – HBc, anti – HVC
- Tes untuk sifilis :
Secara rutin tes untuk sifilis masih dikerjakan di banyak bank darah, namun tidak lagi direkomendasikan
oleh American Association of Blood Bank karena Spirochaeta tidak dapat bertahan hidup dengan baik bila
disimpan lebih dari 4 hari pada suhu penyimpanan 1-60C. hanya penggunaan darah segar (kurang dari 4
hari) dapat menularknan sifilis.
Tes VDRL (veneral disease research laboratory), RPR (Rapid plasma regain) dapat dipakai sebagai uji
saring / skrining. Tes ini dipakai untuk mendeteksi adanya antibody nontreponemal yang dissebut regain.
Bila hasilnya non reaktif pada 2 kali pmeeriksaan, besar kemungkinan donor tidak menderita sifilis. Apabila
ada kecurigaan kuat terhadap sifilis laten / lanjut maka perlu dilakukan tes TPHA (Treponema pallidum
hemagglutination assay) / FTA-ABS (fluorescence treponemal antibody absorption) / TPI (Treponema
pallidum immobilization test).
- Tes HIV : skrining dilakukan dengan metode Elisa (enzymelinked mmunosorbent assay) dan konfirmasi
dengan metode Western blot
- Tes CMV (Cytomegalovirus): Sangat perlu untuk resipien dalam keadaan immunocompromised seperti
transplantasi ginjal / sumsum tulang. Ig M anti CMV positif menunjukkan penyakit masih akut.
- Tes virus Ebstein-Barr : juga hanya penting untuk resipien yang menjalani transplantasi.
Tes silang / cross matching
Terupakan langkah akhir dan terpenting di dalam menetapkan compatibility antara donor dengan resipien,
khususnya terhadap golongan darah ABO, dengan tes ini baik antibody komplit maupun inkomplit dapat ditemukan.
Dibedakan 2 macam tes silang yaitu :
Mayor
Sel donor dicampur dengan serum resipien, bila dalam serum resipien terdapat Ab terhadap sel donor, maka terjadi
destruksi sel donor.
Minor
Serum donor dicampur dengan sel resipien, bila dala mserum donor terdapat Ab terhadap sel resipien, maka terjadi
destruksi sel resipien. Tes silang minor ini dibaynya bank darah di luar negeri tidak dikerjakan sebagai tes
pretransfusi karena secara rutin sudah dikerjakan tes skrining untuk mendeteksi adanya Ab dalam donor. Di
Indonesia dikerjakan bersama tes silang mayor.
Teknik untuk tes silang hanya dilakukan dengan metode tabung dan apabila hanya dikerjakan pada temperature
kamar maka tidak dapat menjamin kepastian compatibility karena ab golongan darah tertentu akan bereaksi pada
suhu tubuh / in vivo. Secara umum tes silang merupakan suatu seri pemeriksaan yang dilakukan tretransfusi untuk
menjamin kecocokan darah yang akan ditransfusikan bagi reipien dan mendeteksi kemungkinan adanya antibody
yang tidak diharapkan dalam serum resipien yang dapat mengurangi umur hidup atau menghancurkan eritrosit donor
(eritrosit berumur 120 hari).
Metode pemeriksaaan tes silang mayor :
Dalam larutan garam / salin (tes fase I)
Metode cepat / /immediate spin : caranya
- Dalam seuah tabung berukuran 10 x 75 mm, tetreskan 2 tetes serum resipien
- Tambahkan tetes suspense washed red cells donor
- Pusing segera selama 15 detik dengan kecepatan 3400 rpm
- Periksa/nilai secara makroskopik dan pastikan hasil negative secara mikroskopik metodi ini untuk keadaan
gawat darurat (emergency), bukan ntuk rutin dan hanya positif bila Ab sangat kuat.
Metode inkubasi 220C caranya :
- Dalam sebuah tabung berukuran 10 x 75 mm, teteskan 2 tetes serum resipien
- Tambahkan 1 tetes suspense washed red cells donor
- Inkubasi dulu pada temperature kamar selama 15 – 30 menit
- Pusing segera selama 15 detik dengan kecepatan 3400 rpm
- Periksa adanya hemolisis secara makroskopik dan ada/ tidaknya agglutinasi secara mikroskopoik
Metode inkubasi 37 0C
- Dalam sebuah tabung berukuran 10 x 75 mm, teteskan 2 tetes serum resipien
- Tambahkan 1 tetes suspense washer red cells donor
- Inkubasi dulu pada temperature 370C selama 15 – 30 menit
- Pusing segera selama 15 detik dengan kecepatan 3400 rpm
- Periksa adanya hemolisis secara makroskopik dan ada/tidaknya agglutinasi secara mikroskopik.
Dalam Albumin (tes fase II)
Penambahan albumin binatang seperti sapi (bovine) menciptakan kondisi yang lebih ideal / efektif untuk mendeteksi
Ab Rh/golongan darah lain dari ABO, terbentuknya agglutinasi lebih ditingkatkan. Kelemahan teknik ini ialah
kemungkinan dijumpainya aggretan nonspesifik secara mikroskopis yang akan membingungkan penilaian bagi yang
belu berpengalaman. Bentuknya halus dan berjejak (trail). Penetesan dengan salin akan melepaskan agregat tetapi
hal ini juga dapat menghancurkan agglunasi lema yang sebenarnya memang ada. Caranya :
- Dalam sebuah tabung berukuran 10 x 75 mm teteskan 4-6 tetes serum resipien
- Tambahkan 1 tetes suspense 5% dari washed red cells donor
- Tambahkan 2-3 tetes bovine albumin (polymerized), campur baik-baik
- Inkubasi pada suhu 370C selama 15 – 30 menit
- Pusing selama 15 detik (immediate-spin) atau 1 menit dengan kecepatan 1000 rpm
- Periksa secara makroskopik adanya heolisis dan agglutinasi secara mikroskopik
Tes antiglobulin Coomb indirek (tes fase III)
Ntuk mendeteksi Ab inkomplit yang bebas dalam sirkulasi (lihat kuliah golongan darah). Ab ini akan menyebabkan
agglutinasi eritroist in vitro. Tes ini dapat ditingkatkan sensitivitasnya dengan penambahan albumin (bovine) atau
ensim sehingga banyak macam IgG maupun Ig M yang tidak terdeteksi dengan metode salin menjadi dapat
terdeteksi. Sekarang bahkan untuk tes pretransfusi setelah penambahan antiglobulin Coomb dilanjutkan lagi dnegan
penambahan anti komplemen (C3d) sehingga hasilnya menjadi lebih handal.
Tes pada reaksi transfuse :
Bila terjadi reaksi transfuse, maka protap sebagai berikut dijalankan :
- Cek kembali semua data penderita, identitas, banyaknya unit yang ditransfusikan, riwayat transfuse
sebelumnya, dan lain-lain yntuk meyakinkan tidak ada kesalahan klerikal (clerical error)
- Dibutuhkan sampel darah sebagai berikut :
o Resipien sebelum terjadi reaksi transfuse
o Resipien sesudah terjadi reaksi transfuse (beri antikoaguan)
o Donor
Lakukan hal-hal sebagai berikut :
- Periksa adanya hemolisis pada semua sampel
- Ulangi pemeriksaan golongan darah ABO dan Rh pada semua sampel darah resipien dan donor
- Lakukan tes antiglobulin Coomb direk pada sampel resipien (a dan b) : untuk mendeteksi adanya Ab in-
komplit yang melekat pada erirosit resipien
- Ulangi tes silang mayor dan minor, lakukan tes skrining pada sampel a,b,d
- Bila terdeteksi Ab, maka identifikasi Ab tersebut ; bila Ab terdeteksi pada sampel b dan tidak pada a,
periksa benar / tidak adanya Ag pada sampel donor
- Lakukan pemeriksaan bakteri secara mikroskopik dan kultur pada sampel c/donor
Lakukan tes-tes tersebut sesuai gejala klinik :
- Menunjang hemolisis
o Haptoglobin pada sampel a dan b. haptoglobin berfungsi mengikat Hb (hemoglobin). Apabila
terjadi penurunan kadar haptoglobin atau tidak ada lagi pada b, berarti terpakai untuk mengikah Hb
yang dilepaskan dari eritrosit yang lisis. Kelebihan Hb yang bebas dapat menyebabkan
hemoblobinuria.
o Metehmalbumin pada sampel a dan b. apabila kapasitas haptoglobin ntuk mengikat hb sudah
jenuh, maka sebagian Hb bebas dalam plasma akan berikatan dengan albumin membentuk
methemalbumin. Methemalbumin menunjukkan adanya hemolisis intravaskuler yang berat /
berlanjut.
o Bilirubin pada sampel b. kadar bilirubin indirek meningkat pada adanya hemolisis
- Kadar kreatinin darah pada sampel b untuk menunjang gangguan fungsi ginjal
- Tes antiglobulin Coomb doirek pada sampel c untuk mendeteksi adanya Ab inkomplit melekat pada erirosit
donor
- Tes untuk mendeteksi adanya Ab leukosit dan trombosit sampel a dan b
- Tes untuk mendeteksi adanya anti Ig A pada sampel a dan b.
Rujukan :
1. Bryant JB. An introduction to immunohjematology.3rd ed.Philadelphia : WB Saunders, 1994;341-59, 477-96
2. Triwibowo. Indikasi transfuse darah. Komite transfuse darah RSUP Dr. Sardjito/PMI.Yogyakarta 1984
3. Rudmann SV. Textbook of blood banking and transfuision medicine. Philadelphia : WB Saunders,
1994;375-433
4. Lee GR, Bithell TC, Foerster J, Athens JW, Lukens JN. Winthrops Clinical hematology. Vol 1.9 th ed.
Philadelphia : Lea & Febiger, 1993; 651 – 700
5. Walker RH technical manual. 11th ed. Bethesda : American association of blood bank, 1993; 309-430
6. Sigal LH, Ron Y. immunology and inflammation basic mechanisms and clinical consequences. New York :
Mc Graw – Hill, 1994 ; 585-98.
7. Melani W. Kondisi transfuse darah di Indonesia Naskah lengkap Konas VIII PHTDI Surabaya, 1997: 1-8
TRANSUDAT DAN EKSUDAT (dr. Nyoman Suci Widyastiti
Pendahuluan
Rongga serosa dalam tubuh mengandung sejumlah kecil cairan yang mengalir diantara ruang intravaskuler dan
ruangan ekstra seluler. Cairan ini dipelihara dalam keadaan seimbang oleh tekanan osmose dalam kapile membrane
serosa tersebut. Cairan tersebut berfungsi sebagai pelumas agar membrane-membran yang dilapisi mesotel dapat
bergerak tanpa gesekan.
Jumlah cairan tersebut dalam keadaan normal tidak dapat diukur, karena sangat sedikit. Jumlah cairan tersebut
pada keadaan tertentu dapat bertambah jmlahnya, dan dapat berupa transudat atau eksudat.
Factor-faktor yang menaikkan kumpulan cairan ini dalam jumlah yang berlebihan :
- Turunnya tekanan osmotic koloid dalam darah
- Naiknya tekanan hidrostatik intrakapiler
- Kerusakan endotel kapiler atau peremeabilitas kapiler.
Transudat
Transudat : yakni kumpulan carian dalam suatu rongga tubuh yan g bukan berasal dari proses peradangan, dan
berkait dengan gangguan keseimbangan cairan badan.
Transudat mempunyai kecenderungan reseidif jika factor penyebab tidak dihilangkan. Menurut lokasinya transuedat
disebut dengan istilah
- Hidrotoraks
- Hidroperikardium
- Hidroperitoneum
- Hidroarrosis
Kelainan-kelainan yang dapat menimbukan transudat :
- Penurunan tekanan osmotic plasma karena hipoalbuminemi
- Sindroma nefrotik
- Cirrhosis hepatis
Peningkatan retensi Natrium dan air
- Penggunaan natrium dan air yang meningkat
- Penurunan ekskresi Natrium dan air (contoh : gagal ginjal)
Meningkatnya tekanan kapilaer / vena
- Kegagaln jantung
- Obstruksi vena porta
- Perikarditis constrictif
Obstruksi limfe
- Hidrothoraks
- Elephantiasis
- Pasca mastektomi radikal
Ciri-ciri transudat spesifik :
- Warna agak kekuningan
- Kejernihahan : jernih
- Berat jenis <1,018 (1,006 – 1,015)
- Tak ada bekuan, atau membeku lambat / dalam jangka waktu lama
- Bau tidak khas
- Protein < 2,5 gr % (tes rivalta negative)
- Glukosa = plasma
- Lemak : negative (kecuali bila chylous +)
- Jumlah lekosit : <500 mm3
- Jenis sel : > mononuclear
- Bakteri negative atau jarang +
Eksudat
Eksudat yakni kumpulan cairan dalam suatu rongga tubuh yang berasal dari proses peradangan atau iritasi. Eskudat
seringkali sembuh dan tak berulang bila telah dikeluarkan seluruhnya. Menurut lokalisasinya disebut :
- Pleuritis eksudativa
- Perikarditis eskudativa
- Perotinitis eksudativa
- Arthritis eksudativa
Sifat-sifat eksudat tergantung pada bahan-bahan yang dikandungnya, jadi eksudat dapat berbentuk :
- Serous
- Fibrinous
- Haemorrhagis
- Purulent
- Atau berbentuk kombinasi
Ciri-ciri eksudat spesifik :
- Warna (karakteristik purulen = putih – kuning, hemoragis = merah, dsb)
- Kejernihan keruh
- Berat jenis => 1,018 (1,018 – 1,030)
- Ada bekuan, atau membeku dalam jangka waktu cepat
- Bau tidak khas. Infeksi kuman anaerob / E.coli : bau busuk
- Protein > 3 gr % (tes rivalta positif)
- Glukosa << plasma
- Lemak mungkin positif (infeksi tuberculosis)
- Jumlah lekosit : 500 – 40.000 / mm3
- Jenis sel : > polinuklear
- Bakteri sering +
Efusi yakni kumpulan cairan dalam suatu rongga tubuh yang belum dapat kita pastikan apakah transudat atau
eksudat. Macam – macam efusi :
Pleural effusion :
Penyebab :
a. radang : menurut kuman yang menyebabkan dibagi menjadi
a. radang karena TBC : cairan bias any serous / serofibrinous dapat juga agak purulent atau
haemorrhagis
b. Radang karena kokus : streptokokus : serpourulent, pnemokokus : seropurulent purulent
c. Radang karena fungi
d. Radang karena parasit : abses hepar karena amuba yang pecah dan menerobos ke rongga pleura.
b. Bendungan
a. bendungan pembuluh darah, contoh padak eadaan dekompensasi kordis
b. bendungan saluran limfe (ductus thoracicus) misalnya trauma, tumor, tumor ganas paru – paru :
cairan haemoffhagis, sindroma dari Meigs (teridiri dari pleural effusion (hidrotorak), ascites, fibroma
ovarii), keistimewaan bila tumor diambil maka pleural effusion akan hilang dengan sendirinya
Parasit : filarial akiba yang akan timbul adalah terjadinya plerusal effusion yang berisi chylous
Penyakit alergi : disebug dengan eosinophilic pleural effusion.
Ascitres
Yaitu kumpulan cairan dalam rongga peritoneum (biasanya berupa transudat, tapi dapat juga eksudat) penyebab :
a. radang : perikarditis, abses hepar
b. Bendungan : dekompensasi kordis, cirrhosis hepatis, bendungan saluran limfe :efusi mengandung chylous
c. Tumor biasanya tumor ganas di dalam abdomen
Cairan Synovial :
Cairan yang terdapat rongga sendi, pada keadaaan normal hanya beberapa cc. volume bertambah disebabkan
karena peradangan baik radang spesifik dan non spesifik.
PEMERIKSAAN TRANSUDAT EKSUDAT
Pemeriksaan transudat – eksudat bertujuan unntuk menentukan jenisnya dan sedapat mungkin mengetahui
penyebabnya. Merupakan pemeriksaan yang berdasarkan indikasiTUjuan pemeriksaan :
1. Menentukan jenis (transugdat atau eksudat)
2. Sedapat mungkin memperoleh petunjuk causa/penyebab dalam praktek sering dijumpai cairan / efsi yang
mempunyai sifat transudat dan sebagain sifat eksudat, sehingga sulit dibedakan.
Cara memperoleh bahan :
- Dengan cara pungsi yang dilakukan secara aseptis
- Supaya tidak terjadi koagulasi sbelum diperiksa maka ditambahkan antikoagulan. Larutan Natrium Citrat
20% o,o1 ml steril untuk 1 ml cairan, heparin steril.
Jenis pemeriksaan
A. Makroskopis (jumlah, warna, kejernihan, bau, berat jenis, bekuan)
B. Mikroskopis (hitung jumlah sel, hitung jenis sel)
C. Kimia(protein, glukosa, lemak)
D. Bakteriologis
E. PA (jarang)
MAKROSKOPIS
Volume :
Ukurlah volume yang diperoleh apabila seluruh cairan dikeluarkan, maka volume itu dapat member petunjuk tentang
luasnya penyakit.
Warna :
Carian yang hanya terdiri dari serum/plasma berwarna kuning muda/tua tergantung dari kadar bilirubin dalam plasma
tersebut. Warna transudat biasanya kekuningan tergantung kadar bilirubin plasma warna eksudat tergantung causa
dan beratnya radang.
Pus putih kuning
Chylous seperti susu
Darah merah cokelat
Bakteri pyogeneous biru kehijauan
Kejernihan
Tergantung dari banyak sedikitnya partikel-partikel terutama sel-sel
Lekosit menyebabkan kekeruhan yang ringan sampai berat
Eritrosit menyebabkan kekeruhan yang kemerah-merahan
Butir-butir lemak menyebabkan kekeruhan seperti susu
Pada eksudat, jika mungkin sebutkan kekeruhan itu misalkan :
- Serofibrineus
- Seropuruent
- Fibrineus
- Haemorrhagis dst.
Bau
Transudat maupun eksudat biasanya tidak mempunyai bau yang berarti, kecualli bila terjadi pembusukan protein.
Bau seperti tinja karena kuman anaerob, Escherichia coli dst.
Berat jenis
Harus segera ditentukan sebelum terjadi bekuan. Dapat ditentukan dengan urino meter (bila volume cairan <= 25
ml). bila cairan sedikit, gunakan refraktometer.perhatikan kemungkinan terjadinya bekuan yang bias bersifat
halus/berkeping-keping ini dibentuk oleh fibrin yang berdapat dalam cairan itu.
Transudat : jarang erjadi bekuan / lambat terjadi
Eksudat : cepat terjadi bekuan (kecuali bila fibrin telah dirusak oleh bakteri / enzyme sel misalnya pada proses
purulent)
Untuk menghindari terjadinya bekuan maka diberi 1 ml larutan .Na Citrat 20 % untuk 100 ml cairan.
MIKROSKOPIS
Menghitung jumlah sel dalam cairan eksudat atau transudat tidak selalu mendatangkan manfaat.
Hitung jumlah leukosit
Hanya dilakukan pada cairan yang jernih atau agak keruh saja, karena hitung julah sel pada cairan keruh tidak
bermanfaat. Sel yang dihitung biasanya hanya leukosit (bersama sel berinti lain, misalnya sel mesotel, sel plasma).
Sel eritrosit tidak dihitung, karena tidak bermakna.
Bahan pengencer ialah NaCl 0,9% bukan larutan Turk, karena larutan Turk mungkin menyebabkan bekuan. Pada
cairan jernih dilakukan pengenceran sebagaimana hitung jumlah lekosit dalam cairan otak(pengenceran 10/9), bila
cairan agak keruh, gunakan pengenceran yang sesuai. Transudat : <500/mm3 Eksudat : >500mm3
Hitung jenis sel
Hitung jenis sel hanya membedakan dua golongan sel, haitu sel mononuclear (dinamakan golongan limfosit) dan
golongan sel polinuklear (dinamakan golongan segmen). Pemeriksaan hitung jenis tersebut akan member petunjuk
jenis radang yang menyebabkan atau menyertai eksudat. Cara pemeriksaan :
Pembuatan sediaan hpus
- Bila cairan keruh / purulen : tanpa pemusingan bila terdapat bekuan buat sediaan hapus dairi bekuan
tsb.
- Bila cairan jernih pusingkan 10-15 ml cairan, supernatant dibuang, lalu sedimen dicampur beberapa tetres
serum penderita sendiri buat sediaan hapus.
- Fiksasi dan dicat dengan cat Giemsa atau Rright
- Lakukan hitung jenis (hanya membedakan limfosit dan segmen) pada 100-300 sel.
PEMERIKSAAN KIMIA
Protein
Protein dalam transudat hanya fibrinogen saja.dalam transudat kadar fibrinogen fendah : 300 – 400 mg / dl,
sedangkan kadar protein eksudat : 4-6 g/dl
Pemeriksaan protein :
Kualitatif
Tes Rivalta : sereomusin
Cara :
- Ke dalam sebuah slilinder kita campur 100 ml aquadest + 1 tetes
- Teteskan satu 1 tetes cairan yang akan kita periksa ke dalam campuran di atas, dilepaskan kira-kira 1 cm
dari atas permukaan
- Perhatikan reaksi yang terjadi
Penilaian :
- Bila tidak terjadi kekeruhan sama sekali tes negative
- Kekeruhan ringan seperti kabut halus tes positive lemah
- Kekeruhan nyata seperti kabut / timbul precipitat putih tes positif
Kwantitatif :
Tetapkan berat jenis terlebih dahulu
Test Esbach
Cara :
- Bila B.J =< 1010 encerkan 5 – 10 x
- Bil B J = > 1010 encerkan 20 x
Maksud pengenceran ini supaya kita dapatkan hasil protein kira-kira mendekati 4 gr/L, sebab bila
didapatkan hasil > 4 gr/L maka pemeriksaan ini menjadi tidak teliti.
- Lakukan penetapan menurut Esbach seperti hal dalam urin, perhitungkan juga pengenceran yang kita buat.
Cara Kasar :
Rumus : (BJ – 1,007) x 343 = gr protein/ 100 ml cairan (dalam rumus ini, BJ air = 100 ml) dengan perhitungan ini,
maka :
- BJ 1,010 = 1 gr protein / 100 ml
- BJ 1,015 = 2,5 gr protein / 100 ml
- BJ 1,020 = 4,5 gr protein / 100 ml
- BJ 1,025 = 6 gr protein / 100 ml
GLUKOSA
Pemeriksaan glukosa pada transudat-eksudat sebagaimana pemeriksaan glukosa pada plasma darah. Transudat
mempunyai kadar glukosa sama dengan plasma darah, sedangkan eksudat mengandung sedikit glukosa, terutama
bila eksudat tersebut banyak mengandung leukosit.
LEMAK
Transudat biasanya tidak mengandung lemak kecuali bila tercampur dengan chylous. Eksudat karena proses
tuberculosis mungkin mengandung lemak karena dinding kapiler permeable dan dapat ditembus lemak.
Cairan yang berwarna putih seperti susu haru dibedakan apakah warna putih tersebut berasal dari chylous atau
bukan. Untuk membedakan chyolus bukan chylous (misalkan lecithin)
Cara :
- Caairan dibuat alkalis dengan pemberian NaOH 0,1 N
- Tambahkan ether lemak larut
- Penilaian :
o Bila cairan menjadi jernih lemak warna putih karena chylous
o Bila tidak menjadi jernih warna putih mungkin karena lecithin
Untuk meyakinkan adanya lecithin tsb, kita lakukan tes sbb :
- Encerkan cairan tsb 5 x dengan ethyl alcohol 95%
- Panasilah berhati – hati dalam air kalau menjadi jernih mungkin lecithin kita lanjutkan
- Saringlah cairan yang telah menjadi jernih itu dalam keadaan masih panas
- Filtratnya ditampung dan diuapkan dalam air panas sampai volume menjadi seperti semula (sebelum diberi
ethyl alcohol)
- Biarkan menjadi dingin lagi
- Penilaian : kalau menjadi keruh lagi adanya lecithin lebih terbukti, kekeruhan itu bertambah kalau sudah
diberi sedikit air.
Tambahan
Empyema : kumpulan pus dalam suatu rongga tubuh yang sejak semula sudah ada (misalnya dalam rongga plerura)
Abscess : kumpulan pus dalam suatu rongga tubuh yang semula belum ada.
TABEL BEDA ANTARA TRANSUDAT DAN EKSUDAT
Keterangan : seringkali sifat cairan tidak khas, sehingga sulit dibedakan.
Contoh soal
Plih salah satu jawaban yang paling benar :
Peningkatan kumpulan cairan dalam jumlah berlebihan dapat terjadi karena hal-hal berikut kecuali :
a. Penurunan tekanan osmotic koloid dalam darah
b. Penurunan tekanan hidrostatik intra kapiler
c. Kerusakan endotel kapiler
d. Peningkatan tekanan hidrostatik kapiler
e. Gangguan permeatbilitas kapiler
Soal sebab akibat
Permeriksaan glukosa merupakan pemeriksaan kimia yang paling penting
SEBAB
Kadar glukosa cairan eksudat hamper sama dengan kada glukosa plasma darah
Daftar pustaka
Ganasoebrata R. transudat dan eksudat. Dalam : penuntun laboratorium klinik Jakarta : penerbit dian rakyat, 1989 :
1 – 10
Kjeldserg CR, Krieg AF. Cerebrospinal Fluid and other body fluids. In : Clincal Diagnosis and Management by
Laboratory Methods. 17th ed. Todd-Stanford-Henry JB. , 1984 : 483-7
Lisyani S. Diktat Kuliah Transudat dan eksudat. Semarang : Bagian Patologi Klinik FK UNDIP, 1984 : 1 – 10
CAIRAN OTAK (dr. Nyoman Suci Widyastii
PENDAHULUAN
Cairan otak ialah cairan jernih, tak berwarna yang 70 % dibuat oleh plexus choroideus di dalam ruang atau ventrikel
otak melalui transport akitf dan ultrafiltrasi, sedangkan 30% dibentuk pada tempat lain, termasuk dpedim ventrikel
dan rongga subarachnoid. Cairan otak ini pada orang dewasa diproduksi 500 ml setiap hari (21 ml/jam), walaupun
hanya kurang lebih 120 – 150 mll saja yang bersirkulasi. Volume cairan otak pada neonates kurang lebih 10 – 60 ml.
seluruh cairan otak diganti secara lengkap kira-kira tiga kali sehari.
Cairan otak bersirkulasi lambat dari tempat produksi di ventrikel, keluar melalui foramina Lushka dan Magendie pada
ventrikel IV, bersirkulasi ke rongga-rongga yang mengelilingi hemisfer serebral dan medulla spinalis lalu direseorbsi
melalui villi pada sinus dural, masuk kembali ke vena. Laju produksi cairan otak tersebut tidak tergantung pada
gradient tekanan cairan otak vena, sedangkan resorbsi bergantung pada graien tekanan antara cairan otak dan
darah vena pada sinus dural (normal : 60 – 80 mm air).
Tekanan cairan otak normal dijaga dengan absorbs cairan otak dalam jumlah yang sama dengan produksinya.
Sumbatan akan menyebabkan peningkatan jumlah cairan otak, menyebabkan hidrosephalus pada bayi dan anak,
atau peningkatan tekanan cairan otak pada orang dewasa. Dari semua factor yang mengatur tingkat tekanan cairan
otak, tekanan vena adalah yang terpenting, karena cairan yang terabsorbsi pada akhirnaya akan mengalir ke system
vena.
Cairan otak dapat mendifusikan tekanan akibat hantaman keras pada tengkorak yang mungkin menyebabkan cedera
berat, sehingga cairan otak ini dapat berfungsi sebagai peredam kejut hidrolik (hydraulic shock absorber). Cairan
otak juga membantu regulasi tekanan intracranial sehingga tak mudah berfluktuasi terhadap aliran darah, dan
mengangkut nutrient dan produk sisa.
Hamper semua konstituen yang ada di plasma darah, juga ditemukan dalam kadar merah di cairan otak, kecuali
kadar chloride yang biasanya selalu tinggi. Akan tetapi, dalam susunannya cairan otak tidak boleh dipandang sama
dengan cairan yang terjadi karena proses ultrafiltrasi dari plasma darah saja, oleh karena disamping proses filtrasi,
juga terdapat factor sekresi dari plexus choroideus. Cairan otak bukanlah transudat semata.
Beberapa penyakit dapat membuat elemen-elemen yang seharusnya dihambat oleh sawar darah-otak dapat
menembus sawar tersebut. Erirosit dan lekosit dapat masuk ke cairan otak, bila terjadi rupture pembuluh darah atau
reaksi menigeal terhadap iritasi. Bilirubin, secara normal tidak ditemukan, tetapi dapat ditemukan pada cairan spinal
pasca perdarahan intra cranial. Sawar darah cairan otak jga dapat terbuka secara reversible pada hipertensi, kejang,
hiperkapnia, dan injeksi bahan kontras radiografik.
FUNGSI LUMBAL
Cairan otak biasanya didapatkan dengan pungsi ke dalam cavum subarachnoidale bagian lumbal. Selain ditempat
tsb. Juga pungsi suboccipital ke dalam cistern magna atau pungsi ventrikel, sesuai dengan indikasi kinik. Saccus
lumbalis antara L4-L5 merupakan lokasi pungsi yang palin sering dikerjakan, karena pada lokasi tersebut terdapat
pooling cairan otak dan hamper tidak mungkin menimbulkan cedera system saraf. Pada anak-anak spinal cord
berada lebih caudal dari orang dewasa, yaitu pada L3-L4 sampai usia 9 bulan, saat medulla spinalis pada posisi L1-
L2 dan harus dilakukan pungsi lumbal pada posisi lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Pengeluaran cairan
otak dapat menimbulkan nyeri kepala. Hal itu disebabkan saat cairan mengalir dari ventrikel atau rongga
subarachnoid, ujung saraf bebas di sekitar pembuluh utama furameter teregang-sebagai akibat otak yang kolaps
sebagian akan menarik meningen.
Pungsi lumbal dilakukan dengan maksud diagnostic atau untuk melakukan tindakan terapi, antara lain :
1. Untuk memeriksa cairan otak, untuk menyingkirkan diagnosis banding, dan menegakkan diagnosis
misalnya pada kasus suspek meningitis ataupun perdarahan intra cranial.
2. Untuk menentukan tekanan cairan otak, untuk mencatat gangguan aliran cairan otak, atau menurunkan
tekanan, dengan jalan mengurangi volume cairan otak
3. Untuk memasukkan obat-obat anestesi, obat tertentu (misalnya methotrecxate untuk leukemia meningeal,
ampthericin pada meningitis fungal) dan media kontras x-ray.
Pada hamper semua kasus, pungsi lumbal dilakukan secaraa elektif (terprogram). Pungsi lumbal elektif dilakukan
pada pagi hari, pada pasien yang telah puasa sepanjang malam. Hal ini disebabkan karena pada pagi hari seluruh
staf laboratorium dan konsltan berada di tempat sehingga dapat melakukan pemeriksaan secepatnya, serta karena
evaluasi kadar glukosa cairan emergency dilakukan pada pasien dengan suspek meningitis, perdarahan
subarachnoid atau leukemia yang mengenai susunan saraf pusat.
Kontraindikasi :
1. Peningkatan tekanan intracranial, pada beberapa kasus dengan pasien koma, perdarahan intracranial atau
suspek meningitis sangat perlu dilakukan pngsi lumbal untuk menegakkan diagnosis, sehingga boleh
dilakukan pungsi lumbal dengan sangat berhati-hati.
2. Suspek infeksi epidural
3. Infeksi atau penyakit kulit berat pada area lumbar, yang akan menyebabkan infiltrasi cairan otak dan
komplikasi infeksi.
4. Persoalan psikiatrik berat atau nyeri pinggang kronik pada pasien neurotic
Kompliasi pungsi lumbal :
1. Herniasi uncus melalui tentorium atau cerebellar tonsils melalui foramen magnum pada pasien dengan
tekanan intra cranial yang tinggi. Edema papil bukan kontraindikasi mutlak
2. Pata tumor medulla spinalis, dapat terjadi progresi paresis atau paralisis
3. Pada pasien dengan gangguan pembekuan darah atau mendapat terapi anti koagulan, pungi lumbal dapat
menyebabkan hematom ekstra dural atau subdural. Kondisi ini bukan kontraindikasi mutlak.
4. Pada pasien sepsis, perforasi meningen akan meningkatkan kemungkinana terjadinya meningitis. Bila
pasien diduga sepsis, maka sebelum dilakukan pungsi lumbal harus dilakukan kultur darah terlebih dahulu.
5. Pada bayi/balita pungsi lumbal dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena peregangan yang
ekseseif dan obstruksi tracheal karena penekanan kepala.
6. Bila tak digunakan stylet, maka dapat tumbuh tumor epidermoid setelah selang 2 – 10 tahun.
7. Infeksi
8. Nyeri kepala. Nyeri ini disebabkan kebocoran lubang penusukan pasca pungsi lumbal (13-32 % kasus).
Pencegahannya ialah dengan cara menggunakan jarum dengan stylet berukuran kecil (22gauge).
Tekanan Cairan Otak
Harga normal : 75 – 150 mm air pada posisi lateral decupitus
30 – 40 cm air pada posisi duduk
Tekanan cairan otak secara langsung berhubungan denan tekanan vena juguler dan vertebral yang berhubungan
dengan sinus-sinus dural intra cranial dan spinal. Implikasi klinis tekanan meningkat :
a. Massa intra cranial (tumor, abces, perdarahan intra cerebral)
b. Meningitis tuberculosa atau purulenta
c. Proses inflamasi ringan
d. Encephalitis
e. Gagal jantung kongestif
f. Obstruksi vena cava superior akut
g. Obstruksi sinus-sinus vena intracranial karena thrombosis
h. Hipoosmolalitas karena hemodialisis
i. Gangguan resorbsi cairan otak karena peningkatan kadar protein, misalnya karena perdarahan
subarachnoid
j. Edema serebral
Tekanan turun
a. Tumor yang obstruktif atau menekan rongga sbarachnoid spinal
b. Koma diabetic
c. Kolaps sirkulasi
d. Dehidrasi berat
e. Hiperosmolalitas akut
f. Kebocoran cairan otak(karena sobekan dra pasca cedera pinggang, rhinorrhea cairan otak, pungsi lumbal)
Perbedaan tekanan awal dan akhir pada pungsi lumbal
a. Sumbatan tumor atau spinal
Bila terdapat perbedaan penurunan tekanan yang besar meengindikasikan adanya pool cairan otak yang
sedikit.
b. Hidrosephalus
Bila terdapat perbedaan penurunan tekanan yang kecil, mengindikasikan pool cairan yang banyak.
c. Penurunan tekanan 25 – 50 % pasca pengeluaran 2 ml cairan otak, maka diduga terdapat herniasi
cerebellar atau kompresi di atas lokasi pungsi
Factor yang mempengaruhi penilaian hasil
1. Peningkatan tekanan ringan dapat terjadi pada pasien yang sadar, yang menahan nafas atau meregangkan
otot-ototnya.
2. Bila lutut pasien difleksikan terlalu rapat dengan abdomen, kompresi vena akan menyebabkan peningkatan
tekanan cairan otak. Hal ini dapat dijumpai pada pasien dengan berat badan normal dan obsese.
PEMERIKSAAN CAIRAN OTAK
Macam pemeriksaan cairan otak
1. Pemeriksaan makroskopis (warna, kekeruhan, sedimen, bekuan)
2. Pemeriksaan mikroskopis (hitung jumlah sel, hitung jenis sel, bakterioskopis)
3. Pemeriksaan kimia (protein, glukosa, chloride, calcium, LDH, asam laktat, pemeriksaan khusus untuk
meningitis tuberculosa, glutamine)
4. Pemeriksaan serologis
5. Pemeriksaan bakteriologis
Cara menampung bahan pemeriksaan
Disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan persangkaan macam penyakit. Untuk melakukan
berbagai macam pemeriksaan, jarang diperlukan lebih dari 15 ml. tabung pemeriksaan haru sanag bersih dan jernih,
karena hasil pemeriksaan makroskopis, mikroskopis dan kimia menjadi tak berarti karena tabung-tabung yang tidak
memenuhi syarat.
1. Bila tanpa pemeriksaan bakteriologis, disiapkan paling sedikit 3 tabung untuk menampung cairan otak
a. Tabung pertama : menampung beberapa tetes yang keluar pertama dari jarum pungsi. Jangan
dipakai untuk pemeriksaan karena mungkin sekali mengandung sedikit darah karena tindakan
pungsi.
b. Tabung kedua 2-4 ml (sama banyak dengan tabung ketiga)
c. Tabung ketiga : 2-4 ml tabung kedua dan ketiga digunakan untuk pemeriksaan non bakteriologis.
2. Jika hendak dilakukan pemeriksaan bakteriologis, maka tabung ketiga harus steril
3. Selalu sediakan tabung yang berisi larutan Natrium citrate 20 % (0,01 ml larutan Natrium Citrat untuk 1 ml
cairan otak). Tabung ini diunakan bila diperkirakan cairan otak akan membeku, misalnya cairan otak yang
mengalir keruh, xanthokromia atau bercampr darah.
PEMERIKSAAN MAKROSKOPIS
Untuk pemeriksaan makroskopis, tabung pemeriksaan berisi cairan otak harus selalu dibandingkan dengan tabung
control yang serupa dan berisi aquadest, agar kelainan ringan dapat terlihat.
Warna :
Normal : sejernih Kristal dan tak berwarna, seperti air / aquadest. Perubahan warna yang sangat minimal akan
menyulitkan untuk interpretasi. Cairan otak harus dibadingkan dengan tabung control yang berisi aquadest dengan
latar belakang berwarna putih. Implikasi klinis :
Warna abnormal :
a. Darah / merah : darah yang disebabkan oleh perdarahan subarachnoid dan serebral akan sama pada
ketiga tabung. Bila dalam cairan otak tersebut hanya terdapat < 400 eritrosit/ul cairan otak, maka darah dan
kekeruhan tak dapat dilihat denngan mata telanjang.
b. Keabu-abuan karena leukosit dalam jumlah bear, misalnya pada radang purulen
c. Coklat disebabkan perdarahan yang lama karena eritrosit hemolisis. Bila dipusingkan, maka supernatant
akan xanthokromia
d. Xanthokromia ialah warna pink pucat hingga oranye atau kuning pada supernatant cairan otak yang telah
dipusingkan. Xanthorkoia harus diamati sesegera mungkin (<1jam) pasca pungsi sebelum eritrosit lisis (1-4
jam) untuk menghindari hasil positif palsu.
Pigmen yang menyebabkan xanthokromia :
a. Oksihemoglobin
b. Methemoglobin
c. Bilirubin (>6 mg/dl) karena eritrosit dalam cairan otak yang mengalami lisis, karena plasma
d. Peningkatan kadar protein pada cairan otak (> 150 mg/dl) biasanya cairan otak yang berasal dari
melanosarcoma meningeal.
Xanthorkomia biasanya menandakan adanya perdarahan sebelumnya, misalnya pada perdarahan subarachnoid.
Pada perdarahan subarachnoid, xanthokromia karena oksihemoglobin berwarna pink pucat atau oranye pucat)
terlihat 2-4 jam setelah awal perdarahan, menapai puncak kurang lebih 24 – 36 jam dan berangsur-angsur
menghilang setelah 4-8 hari. Xanthorkomia karena bilirubin (berwarna kuning mulai terlihat di cairan otak kurang
lebih 12 jam setelah awal perdarahan mencapai pncak ±2-4 hari, dan berangsur-angsur menghilang setelah 2-4
minggu. Xantokromia dibagi atas 1+ hingga 4+. Xanthoromia secara normal dapat terjadi pada cairan otak bayi
premature. Hal ini disebabkan karena sawar darah-cairan otak belum matur, kadar bilirubin meningkat, atau
peningkatan kadar proein. Pemeriksaan xanthoromia lebih sensitive dan spesifik bila diperiksa dengan metode
spektofotometri dibandingkan dengan pemeriksaan aakroskopis (visual).
Factor yang mempengaruhi penilaian hasil
- Darah pada spesiman cairan otak bias disebabkan trauma karena pungsi lumbal dan harus dibedakan dari
darah yang disebabkan karena perdarahan subarachnoid. Eritrosit yang mengalami krenasi tak dapat
digunakan untuk membedakan asal darah dalam cairan otak.
a. Pada saat pungsi.
Pada trauma pungsi : darah tampak tidak homogeny dengan cairan otak dan aliran cairan otak semakin
lama semakin jernih. Pada perdarahan subarachnoid, darah tampakhomogen. Tekanan cairan otak pada
perdarahan subarachnoid biasanya meningkat. Pada trauma pungsi, tekanan cairan otak biasanya rendah
atau normal.
b. Pemeriksaan makroskopis
- Warna
Darah karena trauma pungsi : darah pada cairan otak biasanya secara gradual berkurang, sehingga pada
tabung ketiga darah lebih sedikit dan cairan otak lebih jernih (warna darah lebih muda). Bila dipusingkan
supernatant akan tampak jernih, tidak xanthokromia (kecuali bila pasien ikterik)
- Bekuan
Darah karena trauma pungsi akan membeku setelah cairan otak didiamkan beberapa saat atau mengendap
bila dipusingkan.
Kontaminasi cairan otak dengan cairan disinfektan akan mempengaruhi warna specimen cairan otak.
TUGAS
1. Osmolalitas plasma dan cairan otak sama, sehingga lisis eritrosit tidak disebabkan perbedaan osmolalitas
kedua cairan tersebut. Diskusikan kemungkinan-kemungkinan penyebab lisis eritrosit pada cairan otak
pasca perdarahan subarachnoid.
2. Bagaiman cara memperkirakan waktu awal terjadinya perdarahan subarachnoid dari pemeriksaan
makroskopis cairan otak?
Kekeruhan
Normal : jernih, sejernih aquadest, bila tidak ada kekeruhan maka surat kabar akan terbaca dengan jelas
melalui/menembus tabung.
Pertambahan jumlah sel-sel (pleisitosis) tidak eslalu disertai dengan kekeruhan, misalnya pada encephalitis,
meningitis tuberculosa, meningitis syhilitica, tabes dorsalis dan poliomyelitis. Kekeruhan biasanya berhubungan
dengan leukosit yang banyak, terutama netrofil. Selain itu juga disebabkan darah dan kuman-kuman, pada
meningitis kekeruhan bervariasi dari kekeruhan minimal hingga hamper penuh oleh pus. Pada infeksi cryptokokal,
kekeruhan disebabkan oleh sel-sel yeast. Pada umumnya :
a. < 200 sel / ul : kekeruhan tidak terlihat
b. 200 – 500 sel /ul sedikit keruh
c. > 500 sel / ul : keruh
Laporkan sebagai : jernih, agak keruh, keruh atau sangat keruh
Sedimen
Normal : tidak ada sedimen walaupun cairan otak telah dipusingkan. Adanya sedimen berarti abnormal. Jumlah
sedimen sebanding dengan kekeruhan cairan otak.
Bekuan
Normal : tidak ada bekuan, walaupun cairan otak didiamkan beberapa lama hal ini disebabkan cairan otak normal
tidak mengandung fibrinogen. Periksa cairan otak 10 menit setelah pungsi lumbal / penampungan. Bila didapatkan
bekuan, laporkan macam bekuan : halus sekali, berkeping-keping, menyerupai serat, menyerupai selaput, atau
bekuan kasar dan besar. Bekuan terbentuk bila terdapat fibrinogen dalam cairan otak. Keadaan ini biasanya disertai
bertambahnya protein albumin dan globulin (>1000 mg/dl atau kurang).
Pada meningitis tuberculosa terlihat terbentuknya bekuan yang sangat halus dan sangat renggang yang mulai
terbentuk pada permukaan cairan dan tumbuh sampai ke pertengahan cairan. Pembentukan bekuan ini memerlukan
waktu 12 jam atau lebih. Akan tetapi tidak semua meningitis tuberculosa membentuk bekuan yang halus dan
renggang. Pada peradangan yang menahun, juga mungkin terbentuk bekuan berupa selaput tipis di atas permukaan
cairan otak. Bekuan yang besar atau kasar mengarah pada meningitis purulenta. Bekuan en masse, yaitu cairan
otak membeku seluruhnya, terlihat pada sindroma Froin dan pada perdarahan besar. Keterangan :
Sindroma Froin : penyakit dengan kumpulan gejala dan tanda.
- Sumbatan subarachnoid
- Kadar protein cairan otak sangat meningkat
- Xanthokromia (karena peningkatan kadar protein)
- Pembentukan gel setelah cairan otak didiamkan.
Pemeriksaan Makroskopis
Pemeriksaan mikroskopis diarahkan jumlah dan jenis sel, dan adanya bakteri serta jenisnya secara bakterioskopik.
Secara essensial, tidak ada sel-sel dalam cairan otak. Bila terdapat sel-sel, maka sel tersebut harus diidentifikasi tipe
dan persentasenya dibandingkan dengan jumlah total leukosit yang ditemukan. Hanya terdapat dua jenis sel dalam
cairan otak, yaitu leukosit atau sel-sel tumor. Bila ditemukan leukosit, harus dihitung jumlahnya.
Hitung jumlah sel
Sama dengan konsentrasi lekosit (hitung jumlah) menggunakan bilik hitung. Harga normal (dewasa) : 0-5 / mm 3
(limfosit) = < 5x 106 leukosit per liter
Neonates 0 – 30 sel / mm3 (segmen)
Pemeriksaan dilakukan < ½ jam setelah penampungan, karena leukosit sangat cepat menjadi rusak dan penyebaran
tak merata, sehingga menjadi tak homogeny walaupun telah dikocok. Unakan tabung penampungan ketiga untuk
pemeriksaan hitung jumlah sel, karena merupakan sampel paling murni. Digunakan bilik hitung Fuch Rosenthal. Bilik
hitung Fuch Rosenthal lebih teliti, karena lebih luas dan lebih tinggi dari pada bilik hitung Neubauer Improve. Materi :
- Bilik hitung Fuch – Rosenthal (bila tak ada, dapat digunakan bilik hitung Neubauer Improve)
- Pipet Pasteur dengan penghisap karet / pipet leukosit
- Larutan turk
Metode :
1. Tutup bilik hitung dengan kaca penutup (coverglass)
2. Aduk/kocok cairan otak pelan-pelan
a. Bila cairan otak jernih, pemeriksaan tanpa pengeceran atau dengan pengenceran ringan. Buatlah
pengenceran 10/9 dengan cara menghisap larutan Turk pekat sampai garis bertanda 1 pada pipet
lekosit, lalu menghisap cairan otak sampai garis bertanda 1.
b. Bila cairan otak sangat keruh, lakukan pengenceran. Buatlah pengenceran 1 : 20 menggunakan
0,02 ml cairan otak (=garis bertanda 0,5 pada pipet leukosit) dan 0,95 ml larutan Turk (=garis
bertanda 11 pada pipet leukosit)
3. Kocok pipet, buanglah 3 tetes pertama dari pipet. Tetesi bilik hitung dengan cairan otak
4. Diamkan bilik hitung yang telah ditetesi cairan otak selama 5 menit agar sel-sel mengendap. Letakkan bilik
hitung pada mikroskop.
5. Hitunglah jumlah sel yang tampak per 1 mm3, menggunakan perbesaran obyektif 10x. bila pelaporan
menggunakan SI, harga tersebut tidak berubah missal (150 sel/mm3 – 150 x 106 /I). bila tanpa pengenceran,
gunakan perbesaran obyektif 40x untuk memastikan bahwa sel-sel yang terhitung ialah leukosit. Bila
dengan pengenceran, tetapi dijumpai sel eritrosit, gunakan perbesaran obyektif 40x eritrosit itu tidak ikut
dihitung.
6. Perhitungan :
a. Luas bilik hitung Fuch – Rosenthal 16 mm3. Tinggi bilik 0,2 mm
i. Bila tanpa pengenceran, tak dilakukan koreksi penghitungan hitung sel-sel dalam 5 mm3
menggunakan kotak 1,4,7, 13 dan 16.
ii. Bila dengan pengenceran ringan (10/9) jumlah sel = n x 5 x 10 = 50 kira-kira n(16 9 144 3)
Implikasi klinis :
1. Peningkatan jumlah sel-sel di cairan otak disebut :pleisitosis
a. 2-10 sel : borederlin atau pleiositosis ringan
b. > 10 sel / ul berarti abnormal
c. 25 – 50 sel : pleiositosis sedang
d. > 50 sel : pleiositosis berat pada anak <5 tahun jumlah <= 20 sel / ul masih dianggap normal
2. Penyakit tertentu dapat meningkatkan atau menggeser hitung sel yang normal
a. Lekosit >500 biasanya disebabkan infeksi purulen dan predominan sel granulosit / segmen
b. Lekosit 300 – 500 dengan sel predominan sel mononuclear (limfosit / monosit) :
i. Infeksi viral, misalnya poliomyelitis, dan meningitis aseptic
ii. Syphilis di cairan otak
iii. Meningitis tuberculosa
iv. Tumor atau abses (lekosit bias juga dalam batas normal)
v. Meningitis bacterial yang dalam pengobatan
vi. Multiple sklerosis (50% kasus)
vii. Encephalopati karena penyalahgunaan obat
viii. Sindrom Guillain-Barre
ix. Encephalomyelitis Disseminata akut
x. Sarcoidosis dari meningen
xi. Polyneuritis
xii. Periarteritis susunan saraf pusat
c. Lekosit dengan >40% monosit, diumpai pasca perdarahan sub arachnoid.
3. Peningkatan netrofil
a. Infeksi
i. Meningitis bacterial
ii. Meningoencephalitis viral awal
iii. Tuberculosis awal
iv. ‘meningitis mikotik
v. Encephalomyelitis amebic
vi. Stadium awal siphylis meningovascular
vii. Meningitis aseptic
viii. Emboli septic karena endokarditis bacterial
ix. Osteomielitis spinal atau tulang tengkorak
x. Empiema subdural
xi. Abses serebral
xii. Phlebitis sinus dural atau vena kortikal
b. Non infeksi
i. Reaksi karena perdarahan susunan saraf pusat
ii. Reaksi terhadap pungsi lumbal berulang
iii. Injeksi substansi asing pada rongga subarachnoid, misalnya medium kontras dan obat
kemoterapi.
iv. Pneumoencephalogram
v. Leukemia granulositik kronik yang metastasis ke susunan saraf pusat
vi. Pungsi lumbal yang terkontaminasi detergent
vii. Tumor yang mengalami metastasis
viii. Infark, reaksi neutrofilik biasanya disebabkan karena organism piogenik.
4. Sel-sel lain
a. Sel maligna (limfosit atau histosit) pada tumor otak primer atau metastasis, terutama dengan
ekstensi meningeal
b. Peningkatan jumlah sel plasma disebabkan :
i. Proses inflamasi sub akut dan kronis
ii. Multiple sclerosis
iii. Leukoencephalitis
iv. Respon hipersensitivitas lambat
v. Encephalitis viral sub akut
vi. Meningitis (tuberculosa atau fungal)
vii. Beberapa tumor otak
c. Makrofag pada traumatic dan iskemik infark cranial, meningitis tuberculosa atau mycotik reaksi
terhadap eritrosit, substansi asing atau lipid dalam cairan otak.
d. Sel glial, ependimal atau plexus : pasca prosedur bedah atau trauma susunan saraf pusat
e. Sel leukemix pada cairan otak : pasca remisi karena kemoterapi dan pasca penghentian
kemoterapi.
BAKTERIOSKOPI
Dengan pemeriksaan bakterioskopi, sering sudah dapat diperoleh petunjuk kea rah etiologi, sebaiknya disamping itu
perlu dilakukan biakan dan percobaan binatang. Dilakukan pulasan dari sedimen cairan otak.
Pemeriksaan Kimia
PROTEIN
Pemeriksaan protein merupakan pemeriksaan kimia cairan otak paling penting. Cairan tak normal pada pungsi
lumbal mengandung protein 10 mg % - 45 mg % (rata-rata 25 mg %) kadar tsb memberikan hasil negative terhadap
pemeriksaan secara kualitatif.
Kadar protein dipengaruhi tempat pengambilan cairan otak. Semakin cranial, kadar protein semakin berkurang.
- Pada cistenal kadar protein normal : 15 – 25 mg %
- Pada ventricular : 5 – 15 mg%
Kadar normal tersebut juga tergantung pada usia, misalnya protein cairan otak lumbar pada usia 65 ialah 65 mg %.
TABEL
Cairan otak secara normal mengandung sangat sedikit protein karena protein dalam darah dalam bentuk molekul
yang besar tidak mampu melintasi sawar darah otak. Proporsi albumin globulin pada cairan otak lebih tinggi dari
pada plasma darah, hal ini disebabkan molekul albumin secara signifikan jauh lebih kecil dari molekul globulin, dan
dapat lebih mudah menembus sawar darah otak.
Pada sebagain besar penyakit, perubahan hidung jumlah sel sebanding dengan kadar protein. Keadaan dimana
kenaikan kadar protein tidak sebanding dengan kenaikan jumlah sel disebut : A;buminocytologic dissociation
dijumpai pada beberapa keadaan antara lain : tumor medulla spinalis, poliomyelitis (sebagian kasus), sindroma
Guillain-Barre dan Sindrom Froin. Sebab kenaikan kadar protein dan alterasi rasio albumin-globulin dalam cairan
otak :
- Kerusakan sawar darah otak, misalnya karena infeksi
- Pendarahan / eksudasi serum
- Pembebasan protein dari sel-sel tumor / radang
- Obstruksi sirkulasi cairan otak
- Degenerasi jaringan, misalnya pada sindroma Guillain Barre
Variasi kenaikan kadar protein pada berbagai penyakit :
- Naik ringan : neurolues, poilomielitis (stadium permulaan), beberapa bentuk ensefalitis
- Naik sedang : meningitis tuberkulosa
- Naik sampai 200 mg % - 500 mg % meningitis purulenta, sindrom Froin, sindrom guillain Barre
Cara pemeriksan (kualitatif, semikuantitatif, kuantitatif)
Bila ada darah dalam cairan otak, hasil pemeriksaan protein (dengan cara apapun) menjadi tidak ada artinya lagi,
karena akan menjadi kurang akurat.
Kualitatif :
1. Percobaan busa
Merupakan tes kasar terhadap kadar protein.cairan otak normal hanya berbusa sedikit saja dan hilang
setelah 1-2 menit. Cara : dalam sebuah tabung reaksi, cairan dikocok kuat-kuat.
Penilaian : negative (timbul busa sedikit dan hilan setelah 1 meni/ 2 menit, positive : timbul busa banyak
yang belum hilang setelah didiamkan sampai 5 menit.
2. Modifikasi percobaan Nonne – Apelt
Tes ini terutama menguji kadar globulin. Tes ini sudah banyak ditinggalkan, digantikdan dengan metodi
yang lebih baik. Bahan yang digunakan lebih banyak daripada pemeriksaan pandy, tetapi lebih bermakna
dari tes Pandy, karena dalam keadaan normal hasil tes ini negative sama sekali tidak ada kekeruhan pada
batas cairan.
Reagen : larutan ammonium sulfat jenuh (Ammonium Sulfat 80 g + aquadest 100 ml, disaring)
Cara :
- Dalam sebuah tabung reaksi tuangkan larutan ammonium sulfat jenuh sebanyak 1 ml
- Tambahkan secara berhati-hati cairan otak sebanyak ml sehingga terbentuk 2 lapisan
- Diamkan selama 3 menit, amati perbatasan kedua lapisan
Penilaian :
- Negative tak ada cincin
- Positif : bila terbentuk cincin putih pada perbatasan kedua cairan
- 1+ cincin putih yang bila dikocok menghilang dan cairan jernih
- 2+ cincin putih yang bila dikocok menyebabkan cairan menjadi sedikit keruh
- 3+ cincin putih yang bila dikocok menyebabkan cairan tampak seperti awan
- +4 cincin putih yang bila dikocok menyebabkan cairan menjadi sangat keruh
3. Percobaan untuk albumin
- Reagen : larutan asam asetat 10%
- Cara :
o Kocok isi tabung percobaan untuk globulin di atas lalu disaring
o Filtratnya diasamkan kengan penambahan satu tetes asam asetat 10% kemudian didihkan
o Penilaian : Negatif : tidak timbul kekeruhan / keruh sedikit
o 1+ kekeruhan seperti awan dengan sedikit endapan
o 2+ Kekeruhan seperti awan dengan flokulasi
o 3+ kekeruhan seperti awan dengan flokulasi banyak
Ad. Semikuantitatif
Untuk menyatakan adanya globulin dan albumin
Percobaan Pandy :
Reagen : reagen pandy, yaitu larutan fenol jenuh dalam air (phenolum liquefactum 10ml aquadest 90ml)
Cara :
- Masukkan 1 ml reagen pandy pada tabung tes
- Tempatkan tabung di depan papan / kartu hitam
- Teteskan 3 tetes cairan otak perlahan-lahansetetes demi setetes menggunakan pipet tetes. Amati
perubahan reagen setiap penambahan satu tetes cairan otak.
- Baca hasil dengan cepat.
Penilaian :
Negative : tidak ada kekeruhan / keruh sedikit
Positif terbentuk kabut putih saat tetesan cairan otak tercampur reagen atau terdapat kekeruhan ringan yang
kemudian hilang
1+ kekeruhan jelas = kurang lebih 50 mg% - 100mg %
2+ kekeruhan seperti awan kurang lebih 100 mg % - 300 mg %
3+ kekeruhan seperti awan besar-besar kurang lebih 300 mg % - 500 mg %
4+ sangat keruh > 500 mg %
Ad. Kuantitatif ditetapkan dengan spektrofotometer
Cara ini mudah dikerjakan, dan hasilnya lebih bermakna/akurat. Cara ini yang saat ini banyak dikerjakan selain cara
pemeriksaan protein secara kasar seperti disebutkan di atas, saat ini pemeriksaan protein dalam cairan otak
diarahkan pada fraksi-fraksi protein dalam cairan otak untuk membantu menegakkan beberapa penyakit,
terutamaMultiple Sclerosis. Pemerisaan fraksi protein menggunakan metode elektroforesis dan imunoelektroforesis.
Factor-faktor yang mempengaruhi penilaian kadar protein cairan otak:
1. Obat-obatan yang dapat menyebabkan kenaikkan penilaian kadar protein
a. Kontaminan obat anestesi (local)
b. Chlorpromazine
c. Golongan salisilat
d. Streptomycin
e. Sulfanilamide
f. Tryptophan
2. Darah karena traua yang disertai campuran darah tepi pada cairan otak akan meningkatkan penilaian kadar
protein (koreksi dilakukan dengan mengurangi sebanyak 7 mg % untuk setiap 500 sel darah merah/mm3).
3. Obat-obatan yang menurunkan penilaian kadar protein (albumin, acetophenetidin)
Catatan
Neurosyphilis ditandai : peningkatan kadar protein, VDRL yang reaktif (+), peningkatan jumlah limfosit.
GLUKOSA
Harga normal : 2,5 – 4,2 mmol/l
45 – 85 mg / 100 ml
Atau kira-kira setengah kadar glukosa plasma pada saat cairan otak diambil. Indikasi utama penetapan kadar
glukosa cairan otak ialah persangkaan meningitis. Pada penderita meningitis yang diobati, penetapan kadar glukosa
cairan otak dapat untuk tindak lanjut / menilai prognosis.
Kadar glukosa cairan otak bervariasi tergantung pada kadar glukosa darah. Kadar glukosa cairan otak basanya 60-
70 % kadar glukosa darah. Pemeriksaan kadar gula darah harus dilakukan paling lambat 30 – 60 menit sebelum
dilakukan pungsi lumbal, untuk perbandingan kadarnya. Setiap perubahan pada kadar glukosa darah akan
direfleksikan pada cairan otak setelah 1-3 jam.
Pengukuran kadar glukosa cairan otak bermanfaat untuk mengetahui gangguan transport glukosa dari plasma
menuju cairan otak oleh system saraf pusat, lekosit dan mikroortanisme. Evaluasi akurat dari kadar glukosa cairan
otak memerlukan kadar glukosa plasma yang relative konstan.
Hal-hal yang menyebabkan penyimpangan dari keadaan normal :
- Kerusakan sawar darah otak
- Adanya sel-sel radang / sel-sel tumor yang menggunakan glukosa dalam metabolismenya
- Difusi yang berlangsung lambat
- Glikolisis, dapat terjadi cepat dalam temperature kamar
- Obat-obatan yang mempunyai reaksi reduksi misalnya streptomisin
Penetapan kadar glukosa cairan otak dilakukan dengan pemeriksaan secarapa spektrofotometrik glukosa dalam
cairan otak sangat cepat dirombak, oleh karena itu pemeriksaan kadar glukosa harus dilakukan sesegera mungkin.
Bila dilakukan penndaan, harus ditambahkan pengawet floride oxalate.
Prinsip : pada meningitis (terutama meningitis purulenta), glukosa dalam cairan otak sangat menurun.
Material : sama dengan pemeriksaan kadar glukosa darah
Metode ; sama dengan metode yang digunakan dengan pemeriksaan glukosa darah hanya digunakan volume cairan
otak 4 kali lebih banyak.
Implikasi Klinis
1. Penurunan kadar glukosa
2. Peningkatan kadar glukosa berasosiasi dengan diabetes
a. Infeksi piogenik, tuberkulosa jamur
b. Limfoma dengan penyebaran meningeal
c. Leukemia dengan penyebaran meningeal
d. Mumps meningoencephalitis (biasanya normal pada meningoencephalitis viral)
e. Hipoglikemia / kelaparan
Catatan : semua tipe organism mengkonsumsi glukosa, dan penurunan kadar glukosa merefleksikan
aktivitas bacterial.
3. Kadar glukosa cairan otak biasanya normal pada beberapa infeksi viral pada otak dan meningen, pada
meningitis aseptic, penyakit degernerasi kronis dan tumor jinak
CHLORIDA
Harga normal 118 – 132 mEq/liter
720 – 750 mg/dl
Semua kondisi yang mengubah kadar chloride dalam plasma darah akan dapat mengubah kadar cholorida dalam
cairan otak. Kadar chloride pad cairan otak lebih tinggi dari kdar chloride plasma darah. Pengukuran kadar chloride
sangat berguna untuk diagnosis meningitis tuberculosa. Hal – hal yang mempengaruhi kadar Chlorida cairan otak.
- Kadar chloride dalam darah (bila kadar Cl dalam darah naik, maka kadarnya dalam cairan otak juga akan
naik)
- Kenaikan kadar protein yang secara osmotic menggantikan Cl.
Contoh :
naik :
- Koma uremik
- Penyakit ginjal dengan retensi Natrium dan garam
Turun
- Meningitis tuberculosa
- Radang akut
- Diare dan muntah yang frekuen
- Banyak berkeringat
- Meningitis dengan sebab apapun (kecuali pada lues kadar Cl dapat normal atau hanya turun ringan)
Normal :
- Proses degenerasi
- Peradangan setempat
- Ensepalitis
- Poliomyelitis
- Neurolues
Pemeriksaan chloride dengan metode titrasi
Factor yang mempengaruhi penilaian hasil pemeriksaan :
1. Pemberian chloride bersamaan dengan pungsi akan mengacaukan hasil tes
2. Hasil tes akan tak berarti bila darah (misalnya dari trauma pungsi) tercampur specimen
Catatan : meningitis tuberulosa pada umunya : cairan otak jernih
Pleiositosis
Protein naik, glukosa dan chloride turun
CALCIUM
Cairan otak normal mengandung calfcium dalam kadar sebanyak setengah kadar Ca dalam darah. Kenaikan kadar
protein dalam cairan otak juga kaan diikuti kenaikan kadar Ca. penetapan kadar Ca dilakukan dengan pemeriksaan
secara spektrofotometrik.
ENZIM LACTATE DEHYDROGENASE (LD / LDH)
Harga normal : 5 – 10 % kadar LDH serum
Kenaikan kadar enzim dalam cairan otak disebabkan karena adanya kerusakan sel-sel otak dan tidak tergantung
dari adanya kenaikan kadar protein.
Meskipun banyak enzim berbeda telah diukur di cairan otak, hanya LDH yang bermanfaat secara klinik. Sumber LDh
dalam cairan otak normal berasal dari difsi melintasi sawar darah-cairan otak, difusi melintasi sawar otak-cairan otak
dan aktivitas LDH dari elemen seluler cairan otak, misalnya lekosit, bakteri dan sel tumor. Oleh karena jaringan otak
sangat kaya LDH. Maka kerusakan susunan saraf pusat akan menyebabkan peningkatan kadar LDH cairan otak.
Penguikuran LDH dalam cairan otak berguna untuk diagnosis banding antara meningitis bacterial dan meningitis
viral. Kadar LDH yang tinggi terdapat pada 90 % kasus meningitis bacterial, dan hanya 10 % kasus meningitis viral.
Bila peningkatan kadar LDH terjadi pada kasus meningitis viral, maka kondisi tersebut biasanya berhubungan
dengan encephalitis dan prognosis yang buruk.
Implikasi klinis
Peningkatan kadar LDH berhubungan dengan :
a. Meningitis bacterial
b. Meningitis viral (hanya 10% kasus)
c. Perdarahan subarachnoid
d. Leukemia
e. Limfoma
f. Metastasis carcinoma pada SSP
ASAM LAKTAT
Harga normal : 24 mg/dl (bervariasi)
Batas kadar tertinggi : 25 mg / dl (0,28 mmol/L)
Sumber asam laktat adalah metabolism anaerobic. Kadar asam laktat dalam cairan otak tak tergantung pada kadar
dalam darah.
Semua kondisi yang mengakibatkan penurunan aliran darah otak atau peningkatan tekanan intracranial akan
meningkatkan kadar asam laktat. Pengukuran asam laktat berguna untuk screening untuk mendeteksi penyakit
susunan saraf pusat dan member bantuan untuk diagnose banding antara meningitis bacterial dan meningitis viral
bila kondisi-kondisi lain telah disingkirkan. Bedasar pengalaman klinis, tampaknya pemeriksaan asam laktat pada
cairan otak akan menjadi prosedur pemeriksaan laboratorium rutin.
Implikasi klinis
Peningkatan kadar, berasosiasi dengan :
a. Meningitis bacterial (90% kasus)
b. Hipokapnia
c. Hydrocephalus
d. Abses otak
e. Iskemi serebral
f. Cedera otak traumatis
g. Kejang idiopatik
h. Alkalosis respitratorik
i. Tekanan darah rendah
j. PO2 arterial darah
k. Infark serebral
l. Multiple sclerosis kurang dari 50 % kasus)
m. Kanker susunan saraf pusat
TUGAS
Bagaimana cara membedakan meningitis bacterial dan viral dari hasil pemeriksaan mikroskopis dan kimia cairan
otak?
Bagaiman cara membedakan meningitis awal dan kronis dari hasil pemeriksaan mikroskopis cairan otak.
PERCOBAAN KHUSUS UNTUK MENINGITIS TUBERCULOSA
Percobaan LEVINSON (untuk membedakan meningitis T.B dengan meningitis purulenta0
Alat : 2 tabung reaksi sama besar dengan penampang 6 mm
Reagen : larutan mercurichlorife 2 % dan larutan asam sulfosalisilat 3 %
Dasar pemeriksaan
- Pada meningitis T.B terjadi kenaikan protein fraksi gamma globulin lebih banyak sedangkan pada
meningitis purulenta terjadi kenaikan protein lebih banyak
- Globulin akan mengendap dengan pemberian larutan HgCl2
- Protein akan mengendap dengan pemberian asam sulfosalisilat
Cara :
- Isilah masing-masing tabung reaksi dengan 1 ml cairan otak
- Pada tabung I ditambahkan 1 ml larutan HgCl2 2% pada tabung II ditambahkan 1 ml larutan asam
sulfosalisilat 3%
- Berilah sumbat pada masing-masing tabung tersebut dan biarkan pada temperature kamar selama 24 jam.
- Ukurlah tinggi sedimen yang terbentuk pada masing-masing tabung
Penilaian
- Cairan cetak normal tinggi sedimen pada masing-masing tabung <2mm
- Meningitis tuberculosa : tinggi sedimen pada tabung 1 >= 2 x tabung II
- Meningitis purulenta : tinggi sedimen pada tabung II > tabung I
Percobaan Triptofan
Alat : sebuah tabung reaksi biasa
Reagen HCl pekat, larutan formaldehid 2 %, larutan natrium nitrit 0,06 %
Dasar pemeriksaan : mycobacterium tuberculosa menghasilkan asam amino triptofan yang membentuk cincin ungu
pada reaksi ini.
Cara :
- Masukkan 3 ml cairan otak pada tabung reaksi
- Tambahkan HCl pekat sebanyak 15 ml dan 2 tetes / 3 tetes larutan formaldehid 2%
- Kocok dan diamkan selama 5 menit
- Tambahkan dengan hati-hati beberapa ml larutan Natrium Nitrit 0,06% sedemikian sehingga menyusun
lapisan atas.
Penilaian
Positif : bila terbentuk ungu terhadap pada perbatasan kedua cairan yang dapat bertahan sampai 15 menit atau
lebih.
Positif palsu : terjadi bila cairan otak mengandung banyak sel darah merah / sel darah putih atau berwarna
xanthokromia
GLUTAMIN
Harga normal : 20 mg/dl (sangat bervariasi)
Glutamine disintesis di jaringan otak dari ammonia dan asam glutamik. Produksi glutamine mengatur mekanisme
pembersihan ammonia dari susunan saraf pusat. Pengukuran glutamine berguna sebagai determnasi encephalopati
hepatic dan asidosis cairan otak.
Prosedur : dengan reaksi kolorimetrik
Implikasi klinis :
Peningkatan kadar berhubungan dengan :
a. Encephalopati hepatic
b. Sindrom reye
c. Koma hepatic
d. Cirrhosis hepatis
e. Hiperkapnia
PEMERIKSAAN SEROLOGI
1. Percobaan untuk lues : W.R/V.D.R.L / Kahn
Hasil percobaan ini penting sebagai petunjuk dalam memberikan pengobatan dan di dalam memperkirakan
keadaan penyakit (prognosis). Hasil yang positif dapat teradi bertahun-tahun sebelum gejala klinik dari
neurolues timbul.
2. Percobaan koloid emas menurut Lange (Colloid gold test)
Yaitu suatu cara tidak langsung untuk menilai ketidak normalan distribusi protein fraksi albumin dan globulin
pada beberapa penyakit
Alat : sebelas tabung reaksi (10 untuk tes dan 1 untuk control)
Reagen : larutan koloid emas (NaAuC14, larutan NaCl 0,4%)
Dasar pemeriksaan
Albumin tidak mengendap dengan pemberian larutan koloid emas (warna larutan emas tidak berubah).
Globulin diendapkan oleh larutan koloid emas
Cara :
- Dalam 10 tabung, encerkan cairan otak secara bertingkan dengan pemberian NaCl 0,4% (encerkan mulai
dari 1/10 – 1/20 – 1/40 – 1/80 … sampai 1/5120)
- Tabung ke 11 dipakai untk control
- Tambahkan 0,5 ml larutan koloid emas pada masing-masing tabung
- Campur baik-baik dan diamkan dalam keadaan tegak pada temperature kamar selama 12 hari.
- Catat perubahan warna yang terjadi pada masing-masing tabung.
Penilaian
Normal : tidak terjadi perubahan warna
Kurve tipe paretic (kurve “zone” I) menunjukkan keadaan fraksi globulin meninggi. Contoh : keadaan parese
pada umumnya a.l dimensia paralitika, multiple sklerosis.
Kurve tipe tiabetik (kurve “zone” II tengah) : menunjukkan keadaan fraksi albumin maupunglobulin meninggi.
Contoh : a.l tabes dorsalis, poliomyelitis
Kurve tipe meningitik (Kurve “zone” III/akhir) : menunjukkan keadaan fraksi albumin meninggi. Contoh : a.l
meningitis purulenta/ semua meningitis akut.
TABEL
Daftar acuan
1. Kjeldsberg CR, Krieg AF. Cerebrospinal Fluid and Other Body Fluids. In : Clinical Diagnosis and
Management by Laboratory Methods. 17th ed. Odd-Stanford-Henry JB, 1984 : 459 – 74
2. Fischbach FT. Cerebrospinal Fluid Studies. In : A Manual Laboratory Diagnostic Test.Philadelphia : J.B.
Lippincott Co. , 1989 : 206 – 21.
3. Gandasoebrata R. Penuntun Laboratorium Klinik. Jakarta : Dian Rakyat, 1989 ; 159 – 69
4. NN. Manual of Basic Techniques for a Health Laboratory. Geneva : World Health Organization, 1980 : 339 –
46
5. Lisyani S. Diktat Kuliah Analisa Cairan Otak. Semarang : Bagian Patologi Klinik FK UNDIP, 1984 : 1 – 10
6. Caplan LR. Stroke In : Clinical Symposia. Vol 40 No. 4, 1988 : 13
7. Ravel R. Cerebrospinal Fluid Examination In : Clinical Laboratory Medicine – Clinical Application
of :Laboratory Data. 4th ed. Chicago, 1984 ; 203 – 10
8. Wallach J. Central and Peripheral Nervous System Diseases Laboratory Tests for Disordes of the Nervous
System. In : Interpretation of Diagnostic Tests – A Synopsis of Laboratory Medicine. 5th ed. 1992 : 217 – 21.
KESEIMBANGAN AIR DAN ELEKTROLIT, ASAM DAN BASA (dr. Purwanto AP, SpPK
Keseimbangan air dan elektrolit
Dalam keseimbangan air dan elektrolit ini terdapatr pengaturan yang kompleks dari berbagai mekanisme, antara lain
- System hormonal : ADH, paratiroid, tiroid, suprarenal
- System enim
- Susunan saraf pusat
- Kejiwaan
Keseimbangan air dan elektrolit berkaitan erat dengan keseimbangan asam basa. Keduanya terikat pada hokum
fisiko kimia :
1. Hukum netralitas muatan listrik. Dalam satu larutan, jumlah muatan + (kation) harus sama dengan jumlah
muatan – (anion).
2. Hokum iso-osmolaritas. Osmolaritas suatu cairan harus sama dengan osmolaritas berbagai ruangan tubuh
yang dibatasi oleh dinding yang permeable terhadap air.
3. Hukum Faali. Bahwa pH tubuh harus dipertahankan agar fungsi tubuh berjalan normal dan enzim dapat
berkerja normal.
KESEIMBANGAN AIR
Adalah penting untuk mengetahui susunan cairan tubuh, yaitu untuk mengetahui adanya gangguan :
- Volume, meningkat atau menurun
- Pergeseran dari cairan intra ke ekstrasel dalam jumlah atau bahan terlarut.
Pada keadaan patologis akan terjadi gangguan gangguan yang berbeda sehingga penting untuk tujuan pengobatan.
Jumlah cairan tubuh
- Pada laki-laki berkisar 60% dari berat badan atau kurang lebih 45 liter / 70 kg
- Pada wanita : 50 % BB
Cairan tersebut tersebar di berbagai jaringan tubuh dengan perbandingan sbb :
1. Cairan intraseluler : 35 – 50 % terbanyak dalam sel otot
2. Cairan ekstraseluler : 15 – 20 % yang terbagi dalam :
a. Kompartmen fungsional dimana ¼ c.ekstra sel dalam plasma dan cairan intertisiel
b. Kompartmen non fungsional, dalam cavum pleura, peritoneum, tulang, tulang rawan
Pada bayi cairan ekstraselulernya lebih besar proporsinya disbanding pada dewasa :
- Bayi baru lahir : 50 – 43 %
- Anak 1 -2 tahun : 25 %
- Anak 10 tahun : 22 %
Distribusi air dan bahan padat orang dewasa berdaasr proporsinya …
TABEL
Rute keseimbangan air
TABEL
Jumlah air yang masuk melalui makanan, minuman, hasil kosidasi harus sama dengan jumlah pengeluaran melalui
keringat, paru-paru, ginjal dan tinja.
Pemasukan air ditimbulkan oleh adanya : rasa haus, penyerapan usus
Rasa haus akan timbul bila terjadi keadaan : hipertonik, kekurangan cairan. Keadaan tersebut akan merangsang
pusat haus dan osmoreseptor di : hypothalamus, pancreas, vena porta, hepar, atria dan vascular bed (baroreseptor).
Air akan keluar dari tubuh secara penguapan dipengaruhi oleh :
- Luas permukaan tubuh
- Suhu tubuh
- Suhu lingkungan
- Kelembapan udara
- Frekwensi pernapasan
Hormon yang mempengaruhi keseimbangan air : ADH dan aldosteron
ADH akan diproduksi bila terdapat rangsang osmotic pressure receptor di arteria carotis interna. ADH yang berasal
dari pars anterior hypophyse akan mempengaruhi permeabilitas tubulus distal dan akan menaikkan reabsorbsi air.
Aksi ADH :
- Menaikkan mukopolisacharida yang mengikat air
- Mengaktifkan vasopressin, merangsang reseptor jaringan sehingga peremeabilitas air naik oleh karena
mekanik
- Meningkatkan aktifitas sel dengan membentuk seluler intermediate (siklus AMP)
Hormon aldosteron (steroid hormone) berasal dari Cortex adrenal. Aksi aldosteron :
- Tak langsung : Na
- Langung : mempengaruhi filtrasi glomerulus atau menaikkan reabsorbsi air
Penilaian jumlah cairan
Penilaian jumlah cairan dalam tubuh sangat penting dalam kaitan dengan pengobatan. Penilaian ini dilakukan
dengan berbagai cara antara lain:
a. Klinis sederhana
a. Melihat penderita
Dehidrasi : kulit layu, turgor berkurang, mata cekung ubun-ubun bayi cekung, jari “washer woman
hand”
Overhidrasi : udem, ronchi basah basal, sesak nafas
b. Melihat berat badan
Dehidrasi : berat badan kurang dari 5 % ringan
bBB kurang dari 10 % atau lebih berat
b. Penentuan laboratorium sederhana
Dengan melihat Berat jenis plasma. Plasma diteteskan pada jarak 1 cm di atas cairan CuSO4. Cairan sudah
diketahui berat jenisnya.
Yang dinilai adalah : dilihat jatuhnya plasma dari permukaan cairan sampai dasar tabung. BJ plasma normal
: bila tetesan melayang antara 10 – 15 detik.
Normal : laki laki : 1,025 – 1,033 wanita : 1,025 – 1,031
DENGAN MENILAI BEBERAPA PARAMETER :
- Hematokrit (Ht), Hemoglobin (Hb)
- Kreatinin, protein
- Jumlah urine 24 jam
- Berat jenis urine
Pemeriksaan secara teliti.
Dilakukan pada keadan kedaruratan : di ICU, pada operasi / bedah jantung. Cara :
Dengan penentuan kembali suatu bahan yang disuntikkan dalam vena. Dasarnya adalah : dilusi dari bahan tsb
sesuai dengan jumlah caairan tubuh dalam tubuh penderita.
Syarat bahan untuk penilaian :
- Bahan tidak mengalami metabolism
- Didistribusi dalam tubuh secara uniform (merata)
- Dapat / mudah diteliti kembali.
Bahan yang serin dipakai adalah:
- Thiosulfat
- Deuterium oksida
- Evans blue 131
- I
KESEIMBANGAN ELEKTROLIT
Keseimbangan elektrolit ini diregulasi dengan bebagai cara yaitu :
1. Osmose : elektrolit tidak hanya menjaga keseimbangan asam basa tetapi juga didistribusi cairan tubuh
dengan cara tekanan osmose.
2. Balans sodium :
- Konsentrasi Na+ di regulasi oleh neurohypophyse dan ginjal.
- Pusat haus di hypothalamus dirangsang oleh hipertonis cairan serum.
- Na + disekresi melalui urine, faeces dan kulit.
3. Keseimbangan K : sebagian besar potassium terdapat dalam cairan intrasel. Komposisi elektrolit dalam
kompartmen tubuh TABEL
POTASIUM
Merupakan katon penting dalam cairan intraseluler, oleh karena 90 % terdapat dalam sel. Penentuan K sangat sulit
oleh karena intrasel. Kemudian dipergunakan K plasma untuk memperkirakan jumlah K dalam tubuh.
Nilai normal : 3,5 – 5 mEq / L (11 – 20 mg) fungsi utama : menjaga keseimbangan iritabilitas neuromuskuler. Kadar K
naik sebanyak 0,5 mEq/L (11 – 20 mg%)
Fungsi utama : menjaga keseimbangan iritabilitas neuromuskuler. Kadar K naik sebanyak 0,5 mEq/L (11-20 mg%)
Fungsi utama : menjaga keseimbangan iritabilitas neuromuskuler. Kadar K naik sebanyak 0,5 mEq/L menurunkan
pH sebanyak 0,1. Kadar K naik lebih dari 6,5 mEq/L menyebabkan cardiotoksik. K cairan ekstraseluler menurun,
menyebabkan asidosis intrasel kemudian memacu SSP sehingga frekwensi nafas naik (PCO)2. Ginjal akan
meretensi Na+ dan mengganti H+ untuk dibuang melalui urine. Urine akan menjadi asam. Eksresi dalam urine : 40 –
80 mEq/L
Rasio ekskresi Na : K normal 2 : 1, pada aldosteronisme =1 : 2, pada penyakit adison 10 : 1
Regulasi K dipengarui oleh :
1. Giinjal glomerulus memfiltrasi kompleks, reabsorbasi di tubulus proksimal, tubulus distal sekresi aktif,
dipengaruhi Na+ dan H+
2. Hormonal aldosteron : menurunkan K, ADH : menaikkan K
3. pH naik (respirasi/metabolic) akan menurunkan K
4. Ion lain : Cl, HCO3, CO2, NH3, ureum, kreatinin (keseimbangan dalam dinding eritrosit)
5. Diuretika
Klinis :
Meninggi pada :
- Renal insufisiensi
- Adrenal insufisiensi
- Aldacton tablet
Menurun pada :
- Puasa
- Vomitus, diare
- Terapi dengan corticosteroid
- Alkalosis
- Testoteron
CHLORIDA
Merupakan anion penting dalam cairan ekstraseluler. Fungsi chloride : osmolality plasma, keseimbangan asam basa
Kehilangan HCl, NHCl alkalosis
Pemakaian Cl berlebihan asidosis
Cl berpengaruh pada koreksi hipokalium, karena Cl. Merangsang retensi Na dan K oleh ginjal.
Nilai normal : 97 – 106 mEq / L (340 – 375 mg %).
Klinis :
- Meninggi pada :
o Renal insufisiensi
o Dehidrasi
- Menurun pada
o Gastroenteritis
o Obat diuretika
o Asidosis
o Adrenal insufisiensi
KALSIUM
Normal : 2,1 – 2,6 mmol / L
Hamper 50% kadar plasma merupakan Ca yang dapat di ultrafiltrasi dan bebas, sisanya terikat albumin.
Penurunan Ca (akibat metabolic alkalosis) menyebabkan :
- Iritabilitas neuromuskuler
- Gangguan fungsi kardiovaskuler
Eksresi Ca melalui urine
Kalsium meningkat banya asidosis kronik
MAGNESIUM
Kadar normal : 0,7 – 1,0 mmol/L
80 % dapat berdifusi / bebas
20 % terikat albumin
Keseimbangan Mg pada orang sehat dan sakit, kurang luas dipelajari dibandingkan kalium.
Perubahan Mg+ dapat mempengaruhi iritabilitas neuromuskuler seperti kalsium tetapi jarang timbul perubahan klinis
bermakna.
Kadar Mg : meningkat pada CRF (chronic renal failure), menurun pada aldosteronisme I dan alkoholoisme.
Pemeriksaan Laboratorium
Penentuan potassium dilakukan secara : titrimetri, fotometri, flamefotometri, flameless.
SODIUM
Merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler (bersama Cl-) peninggian Na pada :
- Hemokonsentrasi / intake cairan yang kurang
- Kehilangan air perubahan / pergeseran komposisi, missal :
o Aldosteronisme
o Pelepasan dari tempat penyimpanan, osteoporosis, paget disease (Na tulang : 60 % Na tubuh)
o Gangguan faal ginjal, reabsorbsi Na pada tubulus proksimal 80 – 90 %
Nilai normal : 136 – 145 mEq / L (310 – 335 mg %)
Jumlah ekskresi 80 – 180 mEq/L
Na deficit 60/80 x BB x (135 – Na+ serum)
Hipnatremia :
Terjadi gangguan mental, lethargi, confuse bila berat : stupor, convulasi, coma
Regulasi Na dipengaruhi oleh :
- Aldosteron : meminah Na masuk sel
- Angiotensi II : menaikkan aldosteron, retensi Na
Klinik
- Meninggi pada
o Dehidrasi
o Hiperadrenalisme
o Obat corticosteroid, ADH
- Menurun pada
o Adrenal insufisiensi
o Pituitary insufisiensi
o Renal tubuler acidosis
o Kehilangan cairan : combustion, gastroenteritis, perdarahan
Pemeriksaan laboratorium :
Sederhana : cara fantus untuk menilai Cl secara tidak langsung
Flamefotometri
KESEIMBANGAN ASAM BASA
Tujuan :
a. Mengetahui seluk beluk asam basa yang terdiri dari buffer, respiratori, metabolic, asidosis dan alkalosis
status suatu penyakit
b. Mengenali alat dan jenis pemeriksaan yang digunakan
c. Mengumpulkan data laboratorium dan mengadakan evaluasi serta membuat diagnose sederhana.
Pengetahuna dasar yang dibutuhkan ialah faal dan biokimia.
Masalah utama ;
Anusia untuk energy hidupnya mengeluarkan 13.000 mEq CO2 dan 300 mEq H+ tiap harinya untuk mempertahankan
pH optimal (7,25 – 7,55 H patologis 6,7 – 7,9, dan pH diluar ini dapat menyebabkan kematian.
Adi pengendalian ion H oleh tubuh dilakukan oleh asam (donor H+) dan basa (akseptor H+)
Buffer atau penyangga berfungsi untuk menjaga agar kadar ion H+ tetap. Misalnya ditambah asam (ion H) akan
ditangkap oleh HCO3 dan jika ditambah basa(kurangi ion H) akan dikembalikan oleh H2CO3 bentuk penyangga bias
berupa :
1. Asam dan garam-garamnya (H2CO3 dan HCO3)
2. Senyawa hemoglobin
3. Protein
Pada manusia yang berpengaruh dalah no 1 dan 2, sedangkan yang bias secara praktis diperiksa secara laboratorik
hanya no. 1.
Pemeriksaan laboratorium
Ph dengan menggunakan pH meter
Bicarbonate (HCO3) dengan metoda van slyk
Cara ini sudah lama tidak dipergunakan, prinsip pemeriksaannya adalah dengan menambah asam pada serum
sehingga HCO3 diubah menjadi CO2. Volume CO2 dapat diihat dengan indicator tendon air raksa kemudian hasilnya
dilihat pada table.
Total HCO3
Pengukuran hamper sama dengan bikarbonat tetapi dilakukan dengan cara anaerob, untuk mencegah menguapnya
CO2 yang larut dan HCO2.
PCO2dicari dengan normogram sigard Andersen setelah pH dan total bikarbonat diketahui. Dengan cara astrup
dapat dilakukan pemeriksaan langsung.
Standart bikarbonat.
Jumlah HCO3- dalam keadaan normal atau sakit yaitu pada PCO2 adalah 40 mmHg dan suhu 370C (paru-paru
normal).
Base excess
Menunjukkan kelebihan mEz basa, termasuk bikarbonat dihitung dengan normogram siard Andersen
Buffer basa
Total basa dari seluruh buffer, terdiri dari :
- Bikarbonat
- PO4
- Hemoglobin
- Protein dll
Normal : 45 – 50 mEq / L diukur dengan astrup
Total CO2
Terdiri dari :
- CO2 sendiri yang larut
- Asam karbonat
- Bikarbonat
- Senyawa karbamino
Total CO2 = (actual Bic. + 0,0306) actual PCO3
Keseimbangan asam basa berdasarkan rumus Handersen Hasselbach :
pH = 6,1 + log HCO3/H2CO3
pH = 6,1 + log HCO3 / 0,03 x P CO2
Macam – macam gangguan
Asidosis : keadaan dimana ion H+ dalam tubuh tinggi (pH rendah).
Alkalosis : keadaan dimana ion H+ dalam tubuh rendah (pH tinggi). Setiap perubaha pH oleh karena keadan diluar
respiratory asidosis / alkalosis. Perubahan pH oleh karena keadaan diluar respirasi disebut dengan metabolic
asidosis / alkalosis.
Metabolic asidosis :
Terjadi asidosis karena adanya :
- Kekurangan basa (bse excess < 3 mEq / L)
- Kelebihan asam
Tanda :
- HCO3 plasma rendah
- Base excess rendah
- pH bias mencapai 6,9
Metabolic alkalosis :
Terjadinya alkalosis karena :
- kelebihan basa
- kekurangan asam
tanda :
- HCO3
- Cl rendah
- Na tinggi
- pH mencapai 7,8
Respiratory asidosis
Asidosis oleh karena PCO2 tinggi
Tanda
- PCO2 tinggi
- H2CO3 tinggi
- Bikarbonat tinggi
- Buffer basa normal
Respiratori alkalosis :
Alkalosis oleh karena PCO2 rendah
H2O + CO2 H2CO3 H+ + HCO3-
Keseimbangan bergeser kekiri pH bisa mencapai 7,8
Tanda :
- PCO2 tinggi
- H2CO3 rendah
- Base excess normal
- HCO3-
PEMERIKSAAN ASAM BASA (BGA = Blood Gas Analysis)
Tahun 1961 astrup mengemukakan tentang standart bikarbonat yang merupakan jumlah HCO3 darah dalam
keadaan respirasi normal yaitu PCO2 40 mmHg
Sekarang analisa gas darah telah dilakukan secara computerized dengan satu sampel darah maka hasil sudah
lengkap diperoleh.
TABEL
Cara memperoleh sampel darah :
- Untuk pemeriksaan asam basa : dengan darah arteri
- Pemeriksaan elektrolit : vena. Bila pemeriksaan gas darah dengan sampel vena maka perlu dilakukan
koreksi, kadang-kadang pada alat computerized sudah dilengkapi dengan factor koreksi.
- Antikoagulan yang dipergunakan : heparin. (a.k. yang mengandung mineral tidak dipakai sebab akan
menaikkan kadar elektrolit).
Yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan gas darah
1. Exercise jangan berlebihan (cairan keluar dari sel merubah kadar elektrolit.
2. Jangan melepas bendngan mendadak saat aspirasi, karena dapat merubah komposisi darah, aliran menjadi
berkurang
3. Alat harus kering (bila hemolisa ekeltrolit ICF ke ECF)
4. Tabung harus bersih, bila kotor asam akan menguapkan CO2
5. Sampel segera diserahkan ke laboratorium setelah diambil (pada suhu 250C hanya bertahan 20 menit, pada
ksus leukemia hanya 5 menit).
6. Sampel harus diserahkan ke laboratorium dalam keadaan anaerob.
Grafik hubungan antara pH, CO2 dan HCO3. GRAFIK
TABEL
Kompensasi
Untuk kompensasi dalam tubuh adalah sbb :
Respirasi asidosis metabolic alkalosis
Respirasi alkalosis metabolic asidosis
Daftar pustaka :
Gradwohl : Clinical Laboratory Methods and Diagnosis. WB Saunders Co, 1989
Dennis A. Noe dan Robert C Rock : Dyslipidemias, dalam Laboratory Medicine, The Selection and Interpretation of
Clinical Laboratory Studies, William and Wilkins 1994.
Jacques Wallach, Interpretation of Diagnostic Tests, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, 1986.
John C. Vannata, Morris J. Vogelman. Keseimbangan Cairan dan Elektrolit, Dengan Aplikasi Klinik, Aliha bahasa : M.
Sadikin, Binarupa Aksara, 1990.
PEMERIKSAAN KELAINAN GINJAL DAN SALURAN KEMIH (Dr. Lisyani Suromo SpPK (K)
Pendahuluan
Penyakit ginjal dan saluran kemih dibawah ginjal dapat berjalan tanpa disertai keluhan klinik sampai kerusakan
mencapai 70 – 80 % sehingga diperlukan a.l. pemeriksaan laboratorium yang dapat mendeteksi mungkin kelainan
ginjal-saluran kemih tersebut dalam upaya untuk mencegah penyakit berjalan lebih lanjut.
Peradangan saluran kemih bagian bawah misalnya yang tidak diatasi dengan baik dapat mengakibatkan infeksi
menaik (asenderen) sehingga mengenai ginjal sampai terjadinya kegagalan fungsi ginjal tersebut yaitu apabila
kerusakan telah mencapai lebih dari 50 %. Hal ini berarti telah terjadi kelainan morfologik/anatomic sebelum terjadi
kelainan fungsi.
Salah satu pemeriksaan sederhana yang dapat dikerjakan secara rutin dan dapat member informasi diagnostic yang
penting untuk kelainan morfologik adalah urinalisis, sedangkan untuk menilai gangguan fungsi ginjal sampai dengan
dewasa ini dapat dipakai cara-cara sederhana yang relative mudah dikerjakan.
GINJAL
Fisiologi dasar
Secara umum fungsi ginjal adalah untuk :
- Mempertahankan keseimbangan asam-basa
- Mempertahankan keseimbangan air-elektrolit
- Mengeluarkan sisa-sisa metabolism yang tidak berguna dan membahayakan tubuh
- Produksi, sekresi, degradasi hormone (a.l. degradasi insulin)
Hal ini dipenuhi a.l. melalui fungsi filtrasi-reabsorpsi-sekresi-eksresi ginjal yang saling berhubungan satu dengan
yang lain.
Setiap ginjal memiliki sejumlah kira-kira satu sampai satu setengah juta nefron. Bila terjadi kerusakan pada sejumlah
nefron maka sisa nefron yang masih utuh akan mengalami hipertrofi dan hiperplasi untuk mengatasi tugas dari
nefron yang rusak, oleh karena itu manusia dengan satu ginjal masih mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
Dibedakan 2 macam nefron yaitu nefron kortikalis dan nefron juksta medularis dan setiap nefron terdiri dari 2 bagian
yaitu glomerulus dan tubulus yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Glomerulus :berfungsi untuk filtrasi
- Tubulus : berfungsi untuk reabsopsi, sekresi. Tubulus dibedakan lagi menjadi :
o tubulus proksimalis. Aktif mereabsopsi air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya a.l. natrium,
glukosa, protein dengan berat molekul kecil, asam amino, asam urat, bikarbonat, fosfat anorganik
dan lain-lain.
o lengkung /ansa henle, bagian menurun dan menaik dimana terjadi mekanisme berlawanan arah
(filtrate yang dating dari tubulus proksimalis dipekatkan dengan mereabsorbsi air dan kemudian
diencerkan dengan mereabsorpbi garam-garam)
o tubulus distalis (the diluting segmen dan the late distal tubule) dimana a.l. terjadi :
reabsorpsi air dengan adanya hormone ADH
reabsorpsi ion Na dengan adanya hormone aldosteron
pengontrolan ekskresi fosfat oleh hormone paratiroid
sekresi ion H
- kemudian nefron-nefron tersebut akan bertemu pada tubules pengumpul.
MACAM PEMERIKSAAN UNTUK KELAINAN GINJAL :
Kelainan morfologik
Kerusakan anatomic ginjal dapat diperkirakan berdasaarkan hasil pemeriksaan urin :
1. proteinuria
normal, dalam sehari protein dieksresi ke dalam urin sebanyak lebih kecil dari atau sama dengan 150 mgr
(kira-kira mgr / 100 ml) pada dewasa, pada anak kira-kira 100 mgr, terutama terdiri dari protein dengan
berat molekul kecil (terdeteksi negative dengan metode konvensional). Bila terjadi proteinuria menetap
walaupun asimtomatik, perlu diwaspadai akan kemungkinan kelainan pada ginjal.
Jenis proteinuria :
a. albumin : merupakan protein dengan berat molekul kira-kira 70.000 yang keluar lebih dulu pada
kerusakan glomerulus, disebut proteinuria selektif (perlu disingkirkan kemungkinan adanya proteinuria
fisiologis / fungsional)
b. globulin dengan berat molekul besar : dieksresi ke dalam urin bila kerusakan glomerulus lebih lanjut,
disebut sebagai proteinuria non selektif.
2. penemuan sel darah merah/putih dalam jumlah melebihi nilai rujukan perlu diperhatikan dan diperkirakan
kemungkinan kelainan yang berlokasi pada ginjal, bahan dasar disertai dengan silindruria patologik (silinder
terbentuk dalam tubulus dari bahan dasar utama protein Tamm Horsfall yang hanya bisa disekresi oleh
tubulus), atau disertai penemuan banyak sel epitis tubulus atau “oval fat bodies”. Catatan : silinder
berukuran lebar (broad cast) menunjukkan sudah terjadi kegagalan fungsi.
3. NAG (N-Asetil-beta-D-glukosamidase) : adalah enzim yang berfungsi mempercepat reaksi (katalisis)
degradasi mukopolisakarida dan glikoprotein yang dapat dijumpai di dalam lisosom sel-sel tubuh,
mempunyai berat molekul besar sehingga tidak dapat melewati membrane glomerutus yang sehat. Pada
keadaan normal dapat dijumpai sejumlah kecil NAG sebagai akibat adanya proses pembaruan sel. Diginjal
NAG dijumpai pada sel epitel tubulus proksimal dan dalam jumlah sedikit juga terdapat pada tubulus distal
sedangkan pada kandung kemih tidak dijumpai NAG.
4. RTA (renal tubuler antigen) adalah antigen yang berasal dari “brush border” mikrovili tubulus proksimal yang
dapat dideteksi di dalam serum dan urin bila terjadi kerusakan. Catatan : pemeriksaan NAG dan RTA belum
banyak dikerjakan di laboratorium.
Contoh keadaan dengan kerusakan morfologik
- Kerusakan glomerulus a.l. karena penyakit imun, hipertensi lama, diabetes mellitus, bermacam-macam
toksin
- Kerusakan tubulus a.l. disebabkan karena adanya peningkatan filtrasi glomerulus sehingga memperberat
kerja reabsorpsi tubulus yang berakibat kerusakan sel-sel tubulus, peradangan, penyumbatan lumen
tubulus misalnya oleh protein, hemoglobin mioglobin, obat-obatan dan lain-lain.
PEMERIKSAAN GANGGUAN FUNGSI :
a. Untuk gangguan fungsi glomerulus
a. Penetapan kadar ureum, kreatinin dalam darah
b. Penetapan laju filtrasi glomerulus
b. Untuk gangguan fungsi tubulus :
a. Berat jenis urin
b. Kadar natrium dalam urin
c. Glukosuri
c. Untuk gangguan fungsi glomerulus maupun tubulus
a. Volume urin
b. Beta 2 mikroglobulin
Pemeriksaan untuk gangguan fungsi glomerulus:
Penetapan kadar ureum, kreatinin dalam darah :
Zat –zat tersebut akan meningkat kadarnya did alma serum, apabila kegagalan fungsi ginjal telah mencapai lebih
dari 50 .
Kenaikan kadar ureum dalam darah terjadi lebih dulu dari pada kreatinin, karena pembentukan kreatinin dari keratin
otot serta pelepasannya ke dalam plasma relative konstan dan juga karena sebanyak kurang lebih 20 % keratin
darah secara normal dapat disekresi oleh tubulus ke dalam urin pada keadaan kreatinin darah meningkat oleh sebab
apapun.
Kadar kreatinin darah baru naik dengan cepat jika sampai 2/3 bagian dari seluruh jumlah nefron rusak dan juga pada
keadaan kerusakan glomerulus yang akut. (kadar asam urat dalam darah / serum dapat dipakai sebagai parameter
tambahan untuk lebih memperkuat diagnosis gagal ginjal).
Penetapan kadar zat-zat ini dalam darah dapat dipakai untuk uji saring dan pemantauan penyakit.
Penetapan laju filtrasi glomerutus (klirens)
Definisi : klirens adalah volume darah yang dibersihkan dari suatu zat dengan ekskresi dalam urin dalam waktu 1
menit. Sifat zat yang baik untuk pemeriksaan klirens adalah :
- Bebas difiltrasi
- Tidak direabsorbsi ataupun disekresi oleh tubulus
- Tidak di metabolisir
- Tidak disimpan dalam ginjal
- Tidak mengikat protein
- Tidak bersifat toksik
- Tidak berefek terhadap kecepatan filtrasi
- Mudah diukkur kadarnya baik dalam serum maupun urin
Dikenal 3 macam pemeriksaan klirens yang umum dipakai :
Yaitu klirens inulin, kreatinin, ureum
Inulin mempunyai sifat :
- Difiltrasi oleh glomerulus
- Tidak direabsorpsi maupun disekresi oleh tubulus
- Tidak dimetabolisir oleh ginjal
- Kadar dalam darah dapat dibuat stabil
Oleh karena itu inulin sangat tepat untuk penetapan laju filtrasi glomerulus.
Kelemahan :
- Bahan eksogen
- Harus diberikan lewat suntikan (i.v.)
- Disusul pemberian lewat infuse untuk membuat kadar dalam darah stabil
- Belum banyak laboratorium yang mengerjakan
Kreatinin :
- Difiltrasi oleh glomerulus
- Tidak direabsorbsi oleh ginjal
- Tidak tergantung dieresis
- Kadar dalam darah stabil
- Tidak / hamper tidak dipengaruhi oleh protein makanan ataupun keadaan metabolism tubuh.
Oleh karena itu kreatinin cukup dapat dipercaya untuk penetapan laju filtrasi glomerulus.
Kelemahan :
Dalam keadaan kadar kreatinin darah meninggi baik karena penyakit ginjal ataupun sebab lain, sebagian dari
kelebihan ini (10-20%) disekresi oleh tubulus. Kadar kreatinin dalam darah akan nailk perlahan-lahan bila kegagalan
ginjal telah mencapai kurang lebih 50 % dan naik cepat bila telah mencapai kurang lebih 70%. Pada usia lanjut lebih
dari 40 tahun, ekskresi kreatinin berkurang, dan pada umur 60-90 tahun ekskresi hanya 50% dari nilai normal
dewasa muda tanpa adanya kelainan ginjal.
Ureum :
- Difiltrasi oleh glomerulus
- Direabsorpsi oleh tubulus secara pasif dengan variasi reabsorpsi 25 – 75 % tergantung dieresis
- Dipengaruhi oleh a.l.:
o Difiltrasi oleh glomerulus
o Direabsorbsi oleh tubulus secara pasif dengan variasi reabsorpsi 25 – 75 % tergantung dieresis
o Dipengaruhi a.l.
Protein makanan
Katabolisme protein berlebihan, misalnya karena trauma, perdarahan gastrointestinal
Obat-obatan seperti kortikosteroid, antibiotic tertrasiklin dan lain-lain
Penyakit / keadaan lain di luar ginjal yang mempengaruhi dieresis misalnya payah
jantung, dehidrasi, syok dan lain-lain.
Oleh karena itu ureum kurang tepat untuk penetapan laju filtrasi glomerulus
Perhitungan klirens :
Rumus yang umum dipakai ialah : C zzat = U zat / P zat x V
(berlaku untuk orang dengan luas permukaan badan 1,73 m2)
Keterangan C = klirens, V = dieresis/menit, Zat = insulin/kreatinin, ureum dalam urin/darah
(untuk ureum rumus tersebut berlaku bila dieresis lebih besar dari 2 ml /menit, bila dieresis kurang dari 2 ml/menit
maka hasilnya tidak lagi handal).
Beberapa peneliti mengetengahkan rumus jabaran untuk klirens kreatinin a.l. oleh Gault dan Cockcroft sebagai
berikut :
C Cr = (140 – umur) x BB (Kg)/72xserum kreatinin (mg/100ml) ml/menit
Berlaku untuk pria sedangkan untuk wanita dikalikan 90 %
Rumus jabaran ini sebenarnya hanya dapat dipakai bila fungsi ginjal stabil.
Aplikasi klinik nilai klirens :
- Pada glomerulonefritis akut, nilai klirens dapat normal atau rendah, dan nilai ini tidak dapat dipakai untuk
memberi gambaran prognosis penyakitk, sebab pada glomerulonefritis akut, dapat terjadi kesembuhan.
- Pada glomerulonefritis kronik, nilai klirens yang rendah mempunyai arti prognosisi jelek.
Ad. B. Pemeriksaan untuk gangguan fungsi tubulus :
Berat jenis urin
- Penetapan berat jenis urin dengan cermat cukup dapat memberikan gambaran tentang kemampuan ginjal
dalam memekatkan urin. Kemampuan pemekatan ginjal adalah terbatas, B.J. Maksimal = 1,035. Berat jenis
yang lebih tinggi dapat disebabkan karena obat, cairan konttas yang digunakan untuk pemeriksaan sinar X
yang mempunyai berat molekul tinggi, glukosuri, proteinuri, sehingga perlu diperhatikan / dilakukan koreksi
pada keadaan-keadaan tersebut.
- Berat jenis urin rendah / lebih kecil dari 1,018 menunjukkan kerusakan ginjal yang berat atau gagal ginjal
kronik dengan gangguan fungsi pemekatan dan pengenceran.
Penetapan kadar natrium dalam urin
- Dapat ditetapkan dengan metode Fantus (cara konvensional) atau metode spektrofotometris. Penetapan
ekskresi natrium ini berguna untuk menilai fungsi reabsorbsi tubulus dan dapat dipakai untuk membedakan
kegagalan ginjal intrinsic (ekskresi natrium bertambah) atau kegagalan ginjal karena pengurangan volume
efektif (ekskresi natrium berkurang).
- Catatan : kadar natrium maupun kalium dalam darah dapat bervarisai tergantung dieresis, dalam keadaan
poliuri dapat terjadi penurunan, sedangkan dalam keadaan anuri dapat terjadi kenaikan.
Glujosuri
Keadaan glukosuri dapat disebabkan karena :
Daya glukosuri dapat disebabkan karena:
- Daya reabsorpsi tubulus rendah (gangguan reabsorpsi)
- Nilai ambang ginjal terlampaui
PEMERIKSAAN YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MENILAI GANGGUAN FUNGSI GLOMERULUS MAUPUN
TUBULUS
Volume urin :
Normal : 720 – 2000 ml/24 jam (rata-rata 1200-1500 ml/hari) atau dengan pembatasan minum, ekskresi urin tidak
kurang dari 30 ml / jam
Jumlah urin siang 2-4 x urin malam produksi urin dipengaruhi oleh keadaan a.l.
- Luas permukaan badan
- Pemakaian (intake) cairan
- Kelembapan udara
- Aktivitas fisik/psikik
- Obat—obatan a.l. salisilat, antipretika, analgetika, diuretika
Abnormal : kurang dari 720 ml/lebih dari 2000 ml / hari
Dikenal istilah untuk keadaan tidak normal sebagai berikut :
- Poliuri : keadaan dimana produksi urin meningkat sampai lebih dari 2000 ml / hari atau dengan pembatasan
minum eksresi urin lebih dari 55 ml / jam. Contoh :
o Penyakit ginjal dengan gangguan fungsi pemekatan yaitu nefritis kronik
o Diabetes mellitus, diabetes insipidus, udem stadium penyembuhan
- Oliguri : keadaan dimana produksi urin kurang dari 720 ml/hari atau keadaan di mana dengan pembatasan
minum eksresi urin kurang dari 30 ml/jam.
o Penyakit ginjal dengan gangguan fungsi filtrasi yaitu gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik stadium
akhir.
o Penyakit dari luar ginjal/ yang bukan primer pada ginjal misalnya dehidrasi, syok, demam (febris),
udem sebab lain.
- Anuri : keadaan dimana urin tidak diproduksi. Contoh :
o Gagal ginjal akut karena penyakit ataupun akibat pemakaian obat / bahan nefrotoksik
- Nokturi
Keadaan dimana volume urin malam meningkat lebih dari 500 ml dengan berat jenis rendah (kurang dair
1.018) keadaan nokturi ini merupakan tanda dini akan adanya kerusakan ginjal.
Catatan : dikenal istilah lain sehubungan dengan kelainan volume urin yang bukan karena sebab pada ginjal :
- Poakisuri : keadaan dimana frekuensi miksi bertambah, tetapi volume normal Contoh : karena iritasi /
radang kandung kemih
- Retensi urin : keadaan di mana urin tidak keluar karena tertahan kandung kemih. Contoh : batu kandung
kemih/ saluran kemih bagian bawah, radang uretra, tumor prostat
Beta – 2 mikroglobulin
Merupakan unsure normal dari sel / membrane sel berinti mempunyai berat molekuk 11.800, setelah difiltrasi, 99,9%
akan direabsorpsi leh tubulus proksimalis dan dipecah.
- Gangguan filtrasi glomerulus : kadar dalam darah naik (kenaikan kadar dalam darah juga dapat disebabkan
karena keganasan, sepsis penyakit imun)
- Gangguan reabsorbsi tubulus : kadar dalam urin naik (gangguan fungsi ginjal dapat disebabkan oleh
hipoperfusi ginjal, kerusakan parenkim ginjal atau obstruksi saluran ginjal).
SALURAN KEMIH DI BAWAH GINJAL
Dibedakan :
- Bagian atas (atas kandung kemih)
- Bagan baawah (kandung kemih, ke bawah)
Urinalisis rutin maupun berdasarkan indikasi khusus memberi informasi yang sangat bernilai untuk kelainan ginjal
dan saluran kemih serta membedakan antara keduanya/bagian-bagiannya dengan memperhatikan gabungan
interpetasi hasil a.l. seperti proteinuria, glukosuria, leukosituria/piuria, hematuria, silindruria, jenis sel epitel, eksresi
natrium, NAG, urin 2-3 porsi dan lain-lain.
RUjukan yang dianjurkan :
- Kuliah urinalisis semester IV
- Wilson lm, patofisiologi ginjal In : patofisiologi konsep klinik proses-proses penyakit bag 2 . price sa , Wilson
lm alih bahasa Ajdi Dharma
- Murphy JE, preuss HG. Henry JB. Evaluation of Renal, Function and Water Electrolyte, and acie- base
balance in : henry j bed. Todd Sanford davidsohn clinical diagnosis and management by laboratory
methods.
- Ravel R. Clinical Aplication of Laboratory Data
- Lampiran cara pemeriksaan klirens kreatinin dan ureum.
LAMPIRAN
Pemeriksaan klirens kreatinin :
Cara : (percobaan berlangsung minimum 8 jam sebaiknya 24 jam)
- Ukur tinggi basan dan berat badan penderita
- Penderita diberi minum air sedemikian sehingga dieresis minimum 1 ml/menit
- Saat mula percobaan penderita disuruh mengosongkan kandtung kemih sehabis-habisnya, buang urin ini
dan catat waktunya dengan tepat sebagai permulaan percobaan
- Tamping urin 8 jam dan tetapkan kadar kreatinin dalam urin
- Ambil darah vena pada jam ke 8/24 dan tetapkan kadar kreatinin darah.
Perhitungan :
Cc1 = Uc1/Pc1 x V
C c1 = klirens kreatinin
U c1 = mgr kreatinin / 100 ml urin
P c1 = mgr kreatinin / 100 ml darah
V : dieresis / menit
Klirens ureum :
Cara : (percobaan berlansung 2 jam)
- Ukur tinggi badan dan berat badan penderita
- Penderita diberi minum 2 gelas air (kurang lebih 400-500 ml) dan harus habis sebelum percobaan dimulai.
- Saat mulai percobaan penderita disuruh berkemih sehabis-habisnya, buang urin ini dan catat waktunya
dengan tepat.
- 1 jam kemudian penderita disuruh berkemih, tamping urin sebagai porsi pertama, ukur volume dan kadar
ureum dalam darah
- 1 jam lagi (dua jam dari permulaan percobaan) penderita disuruh berkemih lagi, tamping urin sebagai porsi
ke dua, ukur volue dan kadar ureum dalam urin.
Perhitungan :
a. . jika dieresis lebih besar/ sama dengan 2 ml / menit : perhitungan Cmax = U u1/Pu1 x V
Cmax = klirens maksimum
b. Jika dieresis <2 ml/menit
Cst = Uul/Pul x akar V
Cst = lirens standar
Nilai rujukan rata : Cmax : 75 ml/menit, Cst = 54 ml/menit
Berlaku untuk orang dengan luas permukaan tubuh 1,73 m2.
Catatan : hasil pemeriksaan tidak dapat dipercaya apabila dieresis lebih kecil dari 0,5 ml/menit.
KOAGULASI (dr.Purwanto AP SpPK
Pendahuluan
Salah satu fungsi darah yang utama adalah menjaga stabilitas jaringan, sehingga akan dipertahankan keadaan faali
tubuh normal. Agar stabilitas terjaga dan darah tetap dalam keadaan lancer mengalir dalam pembuluh darah maka
dibutuhkan mekanisme yang mengatur keadaan tersebut. Demikian juga bila terjadi kelainan pada pembuluh darah
maka akan terjadi juga reaksi untuk menghentikan perdarahan yang terjadi. Proses faali yang berlangsung tersebut
kita kenal sebagai hemostasis.
Respon Hemostatik
Proses Koagulasi : mekanisme positif
Respon hemostatik normal terhadap adanya kerusakan pembuluh darah merupakan kerja sama dari beberapa factor
yang terkait yaitu pembuluh darah, trombosit yang beredar dan factor –faktor koagulasi.
Pembuluh darah
Reaksi disini timbul akibat adanya trauma pembuluh darah, dan merupakan respon yang pertama kali timbul.
Reaksinya berupa:
- Vasokonstriksi dan ekstravasasi
Terjadi pada pembuluh darah besar dimana terjadi kontraksi dinding pembuluh darah
- Vasokonstriksi
Pada pembuluh darah kecil, yang berkontraksi karena mekanisme humoral yaitu terlepasnya serotonin dan
amine yang aktif yang berasal dari kerusakan dari trombosit. Akibat vasokonstriksi pembuluh darah ini akan
menyebabkan penurunan aliran darah sehingga memudahkan pembentukan jenalan trombosit (platelet
plug).
Sel Beku darah (trombosit)
Adanya jaringan yang rusak akan menyebabkan SBO akan menempel pada jaringan yang terbuka tersebut. Proses
yang dikenal dengan nama adhesi ini diperkuat oleh bagian factor VIII/ von wilebrand. Setelah mengalami proses
tersebut maka SBD ini akan melepaskan granulanya yang berisikan ADP, serotonin, fibrinogen, ensim lisosom dan
factor penetral heparin (heparin neutralizing factor). Jaringan kolagen dan thrombin juga memacu SBD mensintesa
prostaglandin dan membentuk tromboxan A2. Zat tersebut akan menimbulkan stimulasi terhadap proses agregrasi
SBD dan aktivasi vasokonstrikis.
Sumbat primer hemostatik oleh SBD ini masih kurang stabil dan terjadi pada menit-menit pertama, bisasanya ini
cukup untuk mengontrol sementara perdarahan yang terjadi.
Faktor Koagulasi
Oleh adanya jaringan kolagen yang terluka maka akan terjadi aktifasi jalur intrinsic melalui factor XII. Demikan juga
adanya kebocoran factor jaringan akan mengaktifasi jalur estrinsik melalui factor VII. Aktifasi dari factor-faktor
koagulasi akhirnya akan membentuk fibrin. Agregasi trombosit ditempat tersebut akan menyebabkan perubahan
fibrinogen plasma menjadi fibrin. Anyaman fibrin yang terjadi akan memperbesar sumbat primer sehingga menjadi
kuat. SBD yang mengalami agregasi lama kelamaan akan mati sendiri (autolysis) dan diganti oleh komponan fibrin
dalam sumbat hemostatik. Akhirnya setelah 24-48 jam seluruh sumbat hemostatik sudah berubah bentuk menjadi
masa fibrin yang padat. Factor koagulasi sendiri berjumlah 13 yang sudah mempunyai angka romawi dan dua factor
yang belum mempunyai. Untuk nama-namanya lihat pada kuliah yang lalu.yang perlu mendapat perhatian adalah
adanya 4 faktor yang dibuat dalam hepar dan termasuk dependent vitamin K yaitu :
- Factor II : protrombin
- Faktor VII : proconvertin
- Factor IX : Christmas factor
- Factor X : stuart power factor
Mekanisme pembekuan berlansung dalam tiga tingkat yaitu sbb :
SKEMA
Proses Fibrinolitik : mekanisme negative
Mekanisme negative dari hemostatik adalah memecah fibrin hyang terjadi dengan tujuan tertentu. Mekanisme ini
berjalan melalui proses sebagai berikut :
SKEMA
Mekanisme Inhibitor
Disamping mekanisme positif dan negative yang membentuk bekuan hemostatik dan menghilangkannya bila
diperlukan, maka ternyata terdapat pula mekanisme inhibitor dari hemostatik, yaitu terdiri dari :
1. Antitrombin III (AT III)
Merupakan inhibitor thrombin yang fisiologis dan terdapat dalam sirkulasi darah
Cara kerja:
a. Absorbs dari thrombin
b. Aktivitas fibrinogen dan FDP
c. Sebagai heparin kofaktor (fasilitasi plasma protein heparin)
2. Anti tromboplastin
3. Antifibrinolisin : keduanya bekerja menetralisir tromboplastin dan fibrinolisin
Indikasi pemeriksaan koagulasi
Indikasi pemeriksaan koagulasi adalah sebagai berikut
1. Persiapan operasi
Jenis pemeriksaannya tergantung pada besar kecilnya operasi, makin besar jenis operasinya semakin
banyak pula jenis pemeriksaan koagulasi yang harus dilakukan. Operasi besar tersebut misalnya jantung,
paru, otak dan sebagainya. Untuk operasi biasa minimal harus dilakukan pemeriksaan skrining koagulasi
yaitu :
- Pemeriksaaan SBD
- Waktu perdarahan
- Waktu pembekuan
- PPT dan PTTK
2. Untuk mendiagnosa penyakit-penyakit perdarahan, anamnesa perdarahan perlu dilakukan sebelumnya.
Obat-obatan golongan heparin dan coumarin sering dipergunakan untuk penderita trombosit. Karena
dosisnya harus tepat maka perlu monitoring yang ketat dari terapi tersebut dengan melakukan test
koagulasi.
Akhirnya pembekuan darah merupakan hasil dari 3 fase vaskuler, SBD dan factor koagulasi yang berakhir
dengan pembentukan jendalan fibrin. Kecpatan dan banyaknya jendalan diregulasi oleh mekanisme
inhibitor dan oleh proses resolusi jendalam nelalui system fibrinolitik. Kekurangan atau kelebihan dari
beberapa komponen system tersebut akan membawa seseorang pada keadaan perdarahan atau
thrombosis.
PATOLOGI HEMOSTASIS
Terdapat keadaan-keadaan dimana terjadi gangguan hemostasis di dalam tubuh yang penting diketahui etiologinya
sehingga terapinya dapat diberikan.
Keadaan-keadaan tersebut yaitu :
Vaskulopati : Contoh penyakig :
a. Penyakit Von Willebrand (Angiohemofili/Pseudohemofili/Vasculer Hemofilia) merupakan kelainan
perdarahan yang diturunkan (herediter) yang ditandai dengan waktu perdarahan yang memanjang dan
defisiensi factor VIII yang sifatnya ringan sampai sedang.
b. Henoch Schonlein Purpura (Alergic/Anaphylactoid Purpura) merupakan vaskulitis akut atau kronik yang
mengenai kulit, sendi, traktus gastrointestinal dan ginjal.
c. Rendu-Osler-Weber Sindrom (teleangiectasi Hemorhagi herediter) kelainan vaskuler yang ditandai dengan
lesi teleangiekstasis dari kulit selaput lender. Diturunkan secara autosom dominan.
Kelainan SBD
Meliputi kelainan terhadap kuantitas dan kualitas SBD
Kuantitas:
Trombositopeni, yaitu penurunan jumlah trombosit yang terjadi karena beberapa keadaan yaitu :
1. Penurunan produksi (megakariositopeni)
Terjadi bila fungsi sumsum tulang terganggu, berupa hipoplasi, displasi dan disversi/dispoiesis missal pada
- Pemakaian obat-obatan
- Radiasi
- Penyakit keganasan
- Anemia megaloblastik
Contoh
- Akibat sensitifitas obat
- Lupus eritrematosus
- Trombositopeni neonates
- Alkoholisme
- Gigitan ular
- Penyakit gaucher’s
2. Akibat pemakaian yang berlebihan (megakariositosis) misalnya :
- DIC (Disseminated Intravasculer Coagulation) sehingga kuantitasnya menurun
- Giant hemangioma
- Purpura trombositopeni trombotik
- Neoplasma
- Kebakaran
- trauma
3. Pengenceran SBD
Oleh karena transfuse yang dibiarkan dalam waktu yang singkat dengan memakai curah darah murni yang
disimpan, dapat mengakibatkan kegagalan hemostatik pada pasien.
Pada transfuse plasma ekspander yang banyak seperti : dextrans gelatin dan lain-lain, dapat menyebabkan
trombositopeni karena pengenceran
Trombositosis
Terjadi oleh karena proses yang benigna, missal pada perdarahan yang akut. Contoh : trauma waktu
pembedahan/melahirkan
Trombositemi
Yaitu peningkatan jumlah trombosit oleh proses yang “ganas” missal pada leukemia mielositik kronik
Kualitas :
Suatu keadaan dimana kualitas SBD menurun disebut : trombositopati. Penggunaan beberapa jenis obat dapat
menghambat fungsi SBD, sehingga waktu perdarahan memanjang.
- Tromboasteni : merupakan kelainan yang jarang, ditandai dengan :
o Retraksi jendalan abnormal
o SBD tak dapat agregasi o.k. konsentrasi ADP tak sesuai
Sehingga waktu perdarahan memanjang, tetapi ringan. Pada pemeriksaan darah tepi tanpa antikoagulan
Nampak SBD terisolasi dan tidak didapatkan agregasi. Tromboasteni dimana faal SBD menurun sedang
jumlah normal didapatkan pada penyakit Gianzmann.
- Penyakit Von Willebrand’s
Soulier sindrom bentuk besar SBD ini dengan abnormalitas fungsi, berhubungan dengan anomaly may
heggelin = trombositopeni dan lekosit abnormal serta sindroma Chediak higashi.
KOAGULOPATI
Terdapat beberapa tahap kelainian dari factor-faktor pembekuan , a.l :
1. Kelainan pda pembekuan prothrombin aktifator contoh :
a. Sindrom hemofili
Hemofili A karena defisiensi factor VII
Hemofili B karena defisiensi factor IX
Hemofili C karena defisiensi factor XI
Yang paling sering didapatkan adalah defisiensi factor VII dan IX.
b. Penyakit von willebrand’s
Penyakit yang diturunkan secara dominan berupa kelainan hemostasis yang klinis menyerupai
hemophilia ringan. Bias mengenai baik pria maupun wanita. Tendensi perdarahan menunjukkan
gejala ringan, epistaksis yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas bagian atas dan
kesulitan berhentinya perdarahan lebih dari 36 jam walau luka ringan. Tanda khas penyakit :
- Abnormalitas vaskuler dan funbgsi SBD sehingga menyebabkan waktu perdarahan memanjang
- Defek koagulasi berhubunan dengan defisiensi factor VIII
c. Karena kelainan pembentukan prothrombin komplek missal : pada penyakit hati yang menahun,
untuk mengetahui hal ini perlu pemeriksaan PPT
d. Gangguan pada fibrinogen dapat berupa : A/Hypofibrinogenemia, fibrinolisis, fibrinogenolisis
contoh yang sering ditemui adanya fibrinolisis dan fibrinogenolisis adalah penyakit DIC.
D.I.C – Desseminated Intravasculer Coagulation = Consumption Coatulopathy = Defibrinasi Sindrom
DIC terjadi oleh karena masuknya / terdapatnya substansi tromboplastin ke dalam sirkulasi darah. Seringkali ini
berupa emboli amnion yang bersifat sebagai tromboplastin. Bila masuk ke dalam pembuluh darah maka akan terjadi
pembekuan darah yang sifatnya intravaskuler. Sehingga di dalam plasma akan terjadi defisiensi factor pembekuan
karena telah dikonsumsi oleh cairan amnion tersebut. Masuknya substans tromboplastin kedalam sirkulasi ini
dimungkinkan oleh karena :
1. Produk jaringan dari abruption placenta, placenta previa, metastase karsinoma, jaringan iskemia dari luka
yang akut, shoc
2. Endotoksin bakteri gram negative yang menyebabkan sepsis dan meningococcemia
3. Pelepasan substansi lipid dari sdm pada penyakit hemollitik akut atau dari SBD pada penderita
trombositosis atau trombositemia
4. Kelainan imunologik dimana kompleks antigen antibody akan mengaktifkan factor XII yang kemudian
merangsang system pembekuan.
DIC ini sering ditemukan pada kasus obstetric.
Tes laboratorium
Syarat-syarat untuk pengambilan darah pada pemeriksaan hemostasis yaitu ;
1. Cara pengambilan darah manset tidak boleh terlalu lama dipasaang
2. Waktu memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah vena, tidak boleh diungkit-ungkit
3. Cara mengaspirasi harus baik oleh karena bila terjadi anoksia maka akan terjadi peningkatan proses
fibrinolitik
4. Zat antikoagulan yang dipergunakan adalah citras natricus 3,8 % dengan perbandingan 1 : 9
5. Spuit harus bersih dan kering
6. Temperature tempat kerja harus sesuai karena mempengaruhi kecepatan reaksi pembekuan. Missal : pada
suhu 370C reaksi kecepatan pembekuan 2 x lipat disbanding pada suhu 200C.
7. Khusus untuk pemeriksaan PTTk dan PPT yaitu untuk menilai factor intrinsic dan ekstrinsik digunakan
water bath untuk mengatur suhu.
Adapun macam-macam test yang dipergunakan untuk keperluan hemostasis :
1. Test resistensi kapiler/rumple leed
2. Waktu perdarahan
3. Waktu pembekuan
4. PPT = plasma Prothrombin time
5. PTTK = partial thromboplastin time with kaolin
6. SPT = serum prothrombin time
7. TGT = thromboplastin generation tie
8. Pemeriksaan trombosit
Penutup
Untuk pemeriksaan koagulasi darah ini, baik metoda dan penilaiannya dapat dilihat pada buku petunuk
praktikum/kuliah assistensi yang diberikan.