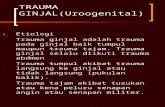Trauma Tajam
description
Transcript of Trauma Tajam
1. Teknik Anestesi pada Trauma Tajam KepalaTrauma kepala merupakan salah satu penyebab kematian akibat trauma, dimana angka mortalitasnya dapat mencapai 50%. Glasgow Coma Scale (GCS) penting dinilai pada pasien trauma untuk mengetahui prognosis pasien, dimana angka kematian pada pasien dengan GCS dibawah 9 sekitar 35%. Trauma intraabdominal, trauma toraks, fraktur tulang panjang, dan kerusakan spinal juga harus diperhatikan karena dapat terjadi bersamaan pada pasien dengan trauma kepala. Tujuan pembedahan dan tatalaksana anestesi pada trauma kepala adalah untuk mencegah kerusakan neuronal dan kerusakan sekunder. Kerusakan sekunder meliputi:1. Faktor sistemik, seperti hipoksemia, hiperkapnia atau hipotensi2. Timbulnya hematoma epidural, subdural, dan intraserebral3. Peninggian tekanan intrakranial1 Tatalaksana pada trauma tajam kepala yang dapat dilakukan adalah kraniektomi diikuti dengan debridemen. Debridemen adalah pengangkatan jaringan yang rusak dan mati sehingga luka menjadi bersih. Debridemen pada trauma tajam kepala biasanya dapat dilakukan secara elektif.1Teknik anestesi yang digunakan adalah anestesi umum, dimana anestesi umum biasanya dimanfaatkan untuk tindakan operasi besar yang memerlukan ketenangan pasien dan waktu pengerjaan yang panjang. Anestesi umum adalah menghilangkan rasa sakit seluruh tubuh secara sentral disertai hilangnya kesadaran yang bersifat reversibel. Kedalaman anestesi harus dimonitor terus menerus oleh pemberi anestesi agar tidak terlalu dalam sehingga membahayakan jiwa penderita, tetapi cukup adekuat untuk melakukan operasi.2Guedel membagi kedalaman anestesi dalam 4 stadium seperti berikut:1. Stadium I (stadium analgesi atau stadium disorientasi)Stadium ini dimulai sejak diberikan anestesi sampai hilangnya kesadaran. Pada stadium ini operasi kecil bisa dilakukan.22. Stadium II (stadium delirium atau stadium eksitasi)Stadium ini dimulai sejak hilangnya kesadaran sampai nafas teratur. Dalam stadium ini penderita bisa meronta-ronta, pernafasan ireguler, pupil melebar, refleks cahaya positif, gerakan bola mata tidak teratur, lakrimasi, tonus otot meninggi, refleks fisiologi masih ada, dapat terjadi batuk atau muntah, kadang-kadang keluar urin dan defekasi. Stadium ini diakhiri dengan hilangnya refleks menelan dan kelopak mata dan selanjutnya nafas menjadi teratur. Keadaan ini dapat dikurangi dengan memberikan premedikasi yang adekuat, persiapan psikologi penderita, dan induksi yang halus dan tepat. 23. Stadium III (stadium operasi)Stadium ini dimulai dari nafas teratur sampai paralise otot nafas. Stadium ini dibagi menjadi 4 plane: Plana I: Dari nafas teratur sampai berhentinya gerakan bola mata. Ditandai dengan nafas teratur, nafas torakal sama dengan abdominal. Gerakan bola mata berhenti, pupil mengecil, refleks cahaya dijumpai, lakrimasi meningkat, refleks faring dan muntah menghilang, tonus otot menurun.2 Plana II: Dari berhentinya gerakan bola mata sampai permulaan paralisa otot interkostal. Ditandai dengan pernafasan teratur, volume tidal menurun, frekuensi nafas meningkat, mulai terjadi depresi nafas torakal, pupil mulai melebar dan refleks cahaya menurun, refleks kornea menghilang, dan tonus otot makin menurun.2 Plana III: Dari permulaan paralise otot interkostal sampai paralise seluruh otot interkostal. Ditandai dengan pernafasan abdominal lebih dominan dari torakal karena terjadi paralisis otot interkostal, pupil makin melebar, refleks cahaya menghilang, tonus otot makin menurun.2 Plana IV: Dari paralise semua otot interkostal sampai paralise diafragma. Ditandai dengan paralise otot interkostal, pernafasan lambat dan ireguler serta tidak adekuat, terjadi jerky karena terjadi paralise diafragma, tonus otot makin menurun hingga terjadi flaccid, refleks spinkter ani negatif.24. Stadium IV (stadium overdosis atau stadium paralisis)Stadium ini dimulai dari paralisis diafragma sampai apneu dan kematian. Stadium ini ditandai dengan hilangnya semua refleks, pupil dilatasi, terjadi respiratory failure diikuti dengan circulatory failure.2
2. PremedikasiPremedikasi merujuk kepada pemberian obat-obatan pada periode 1-2 jam sebelum induksi anestesi dilakukan. Tujuan premedikasi secara umum adalah: Menghilangkan kecemasan dan ketakutanHal ini dapat diatasi dengan psikoterapi, yaitu dengan menjelaskan tindakan pembedahan pada pasien. Apabila ketakutan tetap terjadi setelah penjelasan diberikan, maka perlu diberikan obat ansiolitik seperti benzodiasepin.2 Mengurangi sekresiUntuk mengurangi produksi sekresi dari glandula yang ada di faringeal dan bronkial dapat diberikan obat antikolinergik. Pemberian obat antikolinergik disarankan pada pasien yang akan dilakukan intubasi fiberoptik secara sadar atau sebelum penggunaan ketamin.2 Memperkuat efek hipnotik dari agen anestesia umum (sedasi)Obat-obatan seperti barbiturat atau beberapa opioid menghasilkan sedasi namun tidak mempunyai efek ansiolisis. Pada umumnya tindakan ini dilakukan pada pasien pediatrik.2 Mengurangi mual dan muntah pasca operasiHal ini sering diakibatkan karena pemberian obat-obatan opioid selama dan setelah tindakan bedah. Biasanya obat antiemetik diberikan sebagai premedikasi. Tetapi sebenarnya lebih efektif jika diberikan intravena selama penderita dalam keadaan teranestesi.2 Menimbulkan amnesiaPada beberapa keadaan, terutama pada pasien anak-anak, perlu dibuat suatu keadaan amnesia selama periode perioperasi oleh karena pengalaman yang tidak menyenangkan selama tindakan pembedahan. Anterograde amnesia (hilangnya ingatan dari segala tindakan setelah pemberian obat) dapat dihasilkan oleh obat golongan benzodiasepin seperti midazolam, lorazepam, atau diazepam.2 Mengurangi volume dan meningkatkan keasaman isi lambungPada pasien dengan risiko terjadinya muntah dan regurgitasi (misalnya pasien darurat dengan lambung penuh), perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pengosongan lambung dan meningkatkan pH dari sisa isi lambung. Pengosongan lambung dapat diperkuat dengan pemberian metoklopramid, sedangkan untuk meningkatkan pH dapat digunakan sodium sitrat.2 Menghindari terjadinya refleks vagalPremedikasi dengan antikolinergik pada situasi yang menyebabkan terjadinya vagal bradikardi, seperti pada pasien dengan denyut jantung lambat yang diberikan propofol.2 Membatasi respon simpatoadrenalInduksi anestesi dan tindakan laringoskopi intubasi dapat mengakibatkan rangsangan aktivitas simpatoadrenal, yang ditandai dengan takikardi, hipertensi, dan peningkatan konsentrasi katekolamin plasma. Pada penderita hipertensi atau penyakit jantung iskemik perlu diberikan premedikasi dengan -bloker atau klonidin.2
Tabel 1. Obat-obatan yang sering digunakan untuk premedikasi2GolonganNama obatDosis (mg)Rute
BenzodiasepinEfek: Ansiolisis, sedasi, dan amnesiaDiazepam5-20Oral
Flurazepam15-30Oral
Lorazepam2-4Oral, IM
Midazolam2-5IM/IV
Triazolam0,125-0,250Oral
TransquilizerEfek: AntiemetikDroperidol0,626-2,5IM/IV
AntihistaminDifenhidramin25-75Oral, IM/IV
Hidrokzisin50-100IM
OpioidEfek: Anti nyeri, sedasi Fentanil0,05-0,2IM/IV
Hidromorfon1-2IM/IV
Morfin5-15IM/IV
Meperidin50-100IM/IV
AntikolinergikEfek: Antisialagogue (mengurangi sekresi), sedasi, amnesia, pencegahan bradikardiaAtropin0,2-0,6IM/IV
Glikopirolat0,2-0,6IM/IV
Skopolamin/hyosin0,2-0,4IM/IV
GastrokinetikMetoklopramid10-20Oral, IM/IV
H2-agonisSimetidin300Oral, IM/IV
2-agonisEfek: menurunkan aktivitas notadrenergik sentralKlonidin0,2-0,4Oral
5-HT agonisEfek: antiemetikOndansentron4-8IM/IV
Sumber: Soenarjo dkk. 2013. Anestesiologi. Semarang: Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
Premedikasi khusus untuk kraniotomi pada trauma kepala biasanya tidak ada, namun premedikasi dapat diberikan apabila diperlukan untuk mencapai tujuan premedikasi secara umum.3
Tabel 2. Penanganan preoperatif pada pasien dengan trauma kepala3
Sumber: Jaffe, R.A. et al. 2009. Anesthesiologist's Manual of Surgical Procedures, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
3. InduksiPemberian anestesi dimulai dengan induksi, yaitu memberikan obat sehingga penderita tidur. Induksi secara umum dapat dilakukan dengan cara inhalasi, intravena, intramuskuler atau perrektal. Pada operasi yang waktunya pendek, cukup dengan induksi saja. Tetapi untuk operasi jangka lama, kedalaman anestesi perlu dipertahankan dengan memberikan obat terus menerus dengan dosis tertentu. Hal ini disebut dengan maintenance atau pemeliharaan.2
Tabel 3. Induksi dan maintenance selama operasi pada trauma kepala3
Sumber: Jaffe, R.A. et al. 2009. Anesthesiologist's Manual of Surgical Procedures, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
Tabel 4. Pemantauan saat operasi3
Sumber: Jaffe, R.A. et al. 2009. Anesthesiologist's Manual of Surgical Procedures, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
Obat-obatan yang dapat digunakan selama induksi dan maintenance adalah sebagai berikut: Sedasi1. IsofluranIsofluran adalah obat anestesi isomer dari enfluran yang merupakan cairan tak berwarrna dan berbau tajam, menimbulkan iritasi jalan nafas jika dipakai dengan konsentrasi tinggi menggunakan sungkup muka. Isofluran tidak mudah terbakar, tidak terpengaruh cahaya, dan tidak merusak logam. Konsentrasi alveolar minimal isofluran (minimal alveolar concentration/MAC) pada usia 20-30 tahun adalah 1,28, usia 30-55 tahun 1,15, dan usia di atas 55 tahun 1,05. MAC adalah konsentrasi obat anestesi inhalasi minimal pada tekanan udara 1 atm yang dapat mencegah gerakan otot skelet sebagai respon rangsang sakit supra maksimal pada 50% pasien atau dapat diartikan sebagai konsentrasi obat inhalasi dalam alveoli yang dapat mencegah respon terhadap insisi pembedahan pada 50% individu. Induksi inhalasi dengan 5% isofluran menyebabkan pasien akan tertidur dalam waktu 40 detik pada pasien yang mendapat premedikasi 5 g/kgBB fentanil. Induksi anestesi sebaiknya dimulai dengan 0,5% dan dinaikkan bertahap dengan konsentrasi 1,3-3%. Dalam waktu 7-10 menit biasanya sudah mencapai stadium pembedahan anestesi. Pemeliharaan anestesi antara 1-2,5% dengan kombinasi N2O dan O2, apabila tidak menggunakan N2O (hanya O2) diperlukan dosis 1,5-3%. Pada pasien yang mendapat anestesi isofluran kurang dari 1 jam akan sadar kembali sekitar 7 menit setelah obat dihentikan, sedangkan jika 5-6 jam pasien akan sadar sekitar 11 menit setelah isofluran dihentikan.2Efek terhadap sistem tubuh: Kardiovaskular: Depresi ringan pada jantung. Curah jantung dipertahankan dengan meningkatnya frekuensi jantung. Stimulasi -adrenergik meningkatkan aliran darah pada otot rangka, menurunkan tahanan vaskular sistemik dan menurunnya tekanan darah. Peningkatan konsentrasi isofluran yang cepat menyebabkan peningkatan sementara pada laju jantung, tekanan darah arteri dan kadar norepinefrin plasma, serta dilatasi arteri koroner dan stenosis arteri jantung lainnya (coronary steal syndrome) sehingga dapat menimbulkan iskemia miokard.2 Respirasi: Iritasi jalan nafas atas, bronkodilator, dan depresi nafas. Pada dosis 0,1 MAC, isofluran sudah dapat mengurangi respon ventilasi pada hipoksia dan hiperkarbi.2 Susunan saraf pusat: meningkatkan aliran darah otak dan tekanan intrakranial, mengurangi kebutuhan oksigen otak, serta meningkatkan aktivitas listrik pada EEG sehingga diduga bermanfaat untuk brain protection pada iskemia serebral.2 Otot rangka: menimbulkan efek relaksasi pada otot rangka, berpotensiasi dengan pelumpuh otot.2 Hati: menurunkan aliran darah hati, namun saturasi oksigen vena hepatika masih normal. Hanya sedikit perubahan pada tes faal hati sesudah anestesi dengan isofluran.2 Ginjal: laju filtrasi glomerulus dan produksi urin menurun karena isofluran menurunkan aliran darah.2
2. Sevofluran Sevofluran merupakan fluorokarbon dengan bau yang tidak begitu menyengat, jernih, tidak berwarna, dan tidak begitu mengiritasi saluran napas. MAC sevofluran 1,7, namun bila dikombinasikan dengan N2O menjadi 0,66. Sevofluran nyaman dipakai untuk induksi anak-anak karena baunya enak dan tidak iritatif pada jalan nafas. Waktu pulih sadar antara 7-15 menit setelah anestesi menggunkan 2-3 MAC selama 1 jam.2Efek terhadap sistem tubuh: Kardiovaskular: depresi ringan kontraksi otot jantung, terjadi penurunan tekanan vaskular sistemik dan tekanan arteri yang ringan. Sevofluran juga dapat menyebabkan coronary steal syndrome.2 Respirasi: depresi nafas dan bronkospasme.2 Susunan saraf pusat: menaikkan aliran darah otak, menaikkan tekanan intrakranial, dan menurunkan kebutuhan oksigen otak.2 Otot rangka: relaksasi otot, berpotensiasi dengan pelumpuh otot.2 Ginjal: penurunan aliran darah ginjal.2 Hati: menurunkan aliran darah portal, tetapi meningkatkan aliran darah arteri hepatika sehingga dapat mempertahankan total aliran darah dan kebutuhan oksigen hepar.2
3. PropofolPropofol (2,6-diisopropylophenol) adalah suatu obat anestesi umum yang berupa cairan emulsi isotonik yang berwarna putih. Emulsi ini terdiri dari gliserol, phospatid dari telur, sodium hidroksida, minyak kedelai dan air. Obat ini onsetnya cepat dan durasinya singkat, sehingga pasien dapat pulang berobat jalan lebih cepat setelah pemberian propofol. Kelebihan lainnya pasien merasa lebih nyaman pada periode paska bedah dibanding anestesi intravena lainnya. Mual dan muntah paska bedah lebih jarang karena propofol mempunyai efek anti muntah. Propofol menimbulkan rasa nyeri di tempat suntikan, untuk mengurangi nyeri maka dapat disuntikkan bersama anestesi lokal atau memilih vena besar. Bila anestesi lokal yang dipakai lidokain 1%, maka volume lidokain yang digunakan adalah satu per dua puluh volume propofol.2Mekanisme aksinya belum diketahui, kemungkinan menyebabkan peningkatan aktivitas gamma amino butiric acid (GABA) dalam menghambat neurotransmitter di SSP. GABA adalah neurotransmiter penghambat utama dalam susunan saraf pusat.2Efek terhadap sistem tubuh: Kardiovaskular: turunnya tekanan darah, dimana pada keadaan tidak ada gangguan kardiovaskuler, dosis induksi 2-2,5 mg/kg BB menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik sebesar 25-40%. Penurunan tekanan darah ini mengikuti penurunan curah jantung sebesar 15% dan penurunan resistensi vaskular sistemik sebesar 15-25%. Vasodilatasi yang dihasilkan oleh propofol disebabkan hambatan aktivitas saraf simpatik dan lepasnya nitric oxide. Refleks baroreseptor yang mengontrol denyut jantung juga didepresi oleh propofol sehingga mengurangi refleks takikardia yang selalu mengikuti hipotensi. Propofol tidak mempunyai efek vagolitik, sehingga dapat terjadi bradikardia sampai asistol, sehingga pada keadaan dimana tonus vagal dominan atau penggunaan bersama dengan obat-obatan penyebab bradikardia dianjurkan untuk memberikan antikolinergik sebelum pemakaian propofol.2 Respirasi: depresi nafas sampai apnea, mengurangi volume tidal dan laju nafas, serta mengurangi refleks jalan nafas atas. Pemberian opioid pada pengobatan preoperatif dapat meningkatkan efek depresi ventilasi. Propofol dapat mengakibatkan bronkodilatasi dan menurunkan insidensi sesak pada pasien asma. Propofol mengurangi respon ventilasi pada karbon dioksida dan juga hipoksemia. Propofol akan menekan respon ventilasi terhadap hiperkapnia, disebabkan efek pada kemoreseptor sentral. Berbeda dengan anestesi inhalasi dosis rendah, respon kemorefleks perifer terhadap karbon dioksida masih ada pada pemberian propofol.2 Susunan saraf pusat: menurunkan aliran darah otak, tekanan intrakranial, dan metabolisme otak. Propofol tidak menghambat sekresi hormon adreno kortikal sehingga pemberian obat ini mempunyai risiko terjadinya kejang pada penderita epilepsi.2 Gastrointestinal: Efek mual muntah lebih sedikit dibandingkan obat inhalasi.2 Hati dan ginjal: Propofol dimetabolisme di hati dan diekskresi melalui ginjal, namun tidak bersifat toksik pada hati dan ginjal.2 Mata: menurunkan tekanan intraokuli sehingga propofol ideal digunakan pada operasi mata.2 Pada ibu hamil, propofol dapat menembus plasenta dan dengan cepat masuk ke dalam janin dan menyebabkan depresi janin.2 Propofol menyebabkan pelepasan histamin.2
Kontraindikasi: Penderita yang alergi pada propofol.2Dosis:- Induksi pada pasien dewasa usia kurang dari 55 tahun antara 2-2,5 mg/kg BB. Pada pasien di atas 55 tahun diberikan dosis induksi yang rendah (diturunkan 25% hingga 50) akibat penurunan volume distribusi propofol dan juga penurunan klirens propofol.- Maintenance 4-12 mg/kg BB/jam.- Sedasi di ICU 0,3-4 mg/kg BB/jam, dimulai dengan bolus 1-2 mg/kg BB.2Onset: 30-60 detik.2Preparat:- Tersedia dalam ampul berisi 20 cc, tiap cc mengandung 10 mg propofol. Obat ini harus disimpan dengan suhu 2-250C dan tidak boleh dibekukan, sebelum dipakai harus dikocok dahulu.- Bila sudah dibuka harus segera dipakai, karena emulsi propofol merupakan media yang baik untuk berkembangnya bakteri.2
4. Sodium Tiopental (STP)Sodium tiopental adalah obat hipnotik sedatif dari golongan barbiturat dengan lama kerja ultra short acting. Dosis sodium tiopental adalah 4-5 mg/kg BB. Metabolisme terutama di hepar dan ekskresi melalui ginjal. Mekanisme kerja kemungkinan menghambat konduksi ascenden dalam formatio retikularis thalamus sehingga menghambat transmisi impuls ke korteks. Dalam waktu 30-40 detik penderita akan tertidur setelah disuntik intravena dan kesadaran pulih setelah 20-30 menit.2Efek terhadap sistem tubuh: Kardiovaskular: depresi otot jantung, vasodilatasi perifer, dan turunnya curah jantung. Dapat terjadi takikardia sebagai kompensasi turunnya tekanan darah dan curah jantung. Respirasi: depresi nafas sampai apnoe, serta bronkospasme. Susunan saraf pusat: menurunkan metabolisme otak, menurunkan konsumsi oksigen dan menurunkan tekanan intrakranial. Hepar: mengurangi aliran darah hepar. Pada pemberian dosis 18,5 mg/kg BB menimbulkan perubahan pada fungsi hepar. Ginjal: penurunan fungsi ginjal, diduga karena meningkatnya sekresi ADH sehingga vasokonstriksi arteri renalis, serta akibat turunnya tekanan darah dan curah jantung.2
5. EtomidatEtomidat adalah suatu imidazol karboksilat yang larut dalam air pada pH asam dan larut dalam lipid pada pH fisiologis. Etomidat dikemas dalam larutan 0,2% dengan 35% propilen glikol yang menimbulkan nyeri pada penyuntikan dan kadang menimbulkan iritasi vena. Onsetnya cepat dan durasinya singkat. Dosis induksi dapat dikurangi dengan premedikasi benzodiasepin, opiat, atau barbiturat. Mekanisme kerja kemungkinan berpengaruh pada GABA. Metabolisme terjadi di hepar dan disekresi lewat ginjal dan empedu. Biasanya pasien bangun 10 menit setelah pemberian dihentikan.2Dosis:Induksi anestesi: 0,2-0,6 mg/kg BB/ivMaintenance anestesi: 10 g/kg BB/iv dengan N2O dan opiatSedasi: 5-8 g/kg BB/menit2Efek terhadap sistem tubuh: Kardiovaskular: efek minimal, dimana dengan dosis 0,3 mg/kg BB pada penderita penyakit jantung hampir tidak menimbulkan perubahan. Respirasi: depresi nafas minimal, dapat juga terjadi hiperventilasi, apnoe, batuk atau cegukan. Susunan saraf pusat: mengurangi cerebral blood flow dan menurunkan metabolisme otak. Gastrointestinal: menimbulkan mual muntah Tidak menyebabkan pelepasan histamin.2
Analgesik1. FentanilFentanil merupakan analgesi opioid agonis dimana potensi analgesinya 75-125 kali lebih kuat dibandingkan morfin. Mekanisme kerjanya adalah dengan blokade pada mesensefalon, sehingga rangsang sakit tidak mencapai kortikal. Pada pemberian intravena, mula kerja 30 detik dan mencapai puncak dalam waktu 5 menit, kemudian menurun cepat dalam 5 menit pertama (kadarnya berkurang 20%), selanjutnya menurun lambat selama 10-20 menit. Fentanil dimetabolisme di hepar dan dieksresi melalui ginjal dan empedu.2Dosis: Loading dose 2-8 g/kg BB dilanjutkan infus kontinu 0,5-3 g/kg BB/jam. Sebagai obat tunggal diperlukan dosis 50-150 g/kg BB. Untuk laringoskopi intubasi dosis fentanil 2-10 g.2Efek terhadap sistem tubuh: Kardiovaskular: depresi otot jantung minimal. Pemberian atropin sulfat dapat menurunkan kejadian bradikardia. Respirasi: umumnya dengan dosis 1-3 g/kg BB tidak menimbulkan depresi nafas. Depresi nafas sering terjadi pada periode pasca bedah dimana diduga terjadi akibat sequesterasi fentanil dalam asam lambung (ion trapping). Sequesterasi fentanil ini kemudian diabsorpsi di usus halus dan masuk dalam darah sehingga menyebabkan depresi nafas. Otot: kekakuan otot rangka, khususnya otot toraks, abdomen, dan ekstremitas. Hal ini diduga karena aktivitas sentral agonis pada reseptor . Fentanil tidak menyebabkan pelepasan histamin.2
RelaksasiRelaksan otot adalah obat yang mengurangi ketegangan otot dengan bekerja pada saraf yang menuju otot. Berdasarkan perbedaan mekanisme kerja dan durasi kerjanya, obat-obat pelumpuh otot dapat dibagi menjadi obat pelumpuh otot depolarisasi (meniru aksi asetilkolin) dan obat pelumpuh otot nondepolarisasi (mengganggu kerja asetilkolin).2,4Pelumpuh otot depolarisasi bekerja seperti asetilkolin, tetapi di celah sinaps tidak dirusak dengan asetilkolinesterase sehingga bertahan cukup lama menyebabkan terjadinya depolarisasi yang ditandai dengan fasikulasi yang diikuti relaksasi otot lurik. Termasuk golongan ini adalah suksinilkolin. Pelumpuh otot golongan nondepolarisasi bekerja berikatan dengan reseptor kolinergik nikotinik tanpa menyebabkan depolarisasi, hanya menghalangi asetilkolin menempatinya, sehingga asetilkolin tidak dapat bekerja.2,4Contoh obat pelumpuh otot golongan nondepolarisasi adalah:1. RocuroniumDosis:0,6 mg/kg BBOnset:Untuk intubasi paralise otot laring terjadi dalam waktu 1 menit, namun untuk operasi diperlukan waktu 2 menitEkskresi:Hepar dan ginjalEfek:- Pelumpuh otot- Sedikit perubahan kardiovaskular karena efek vagolitik- Tidak menimbulkan pelepasan histamin2
2. VecuroniumDosis:0,1-0,2 mg/kg BB untuk intubasi (durasi 45-90 menit)0,03-0,04 mg/kg BB untuk relaksasi (durasi 25-40 menit)0,01-0,02 mg untuk maintenanceOnset:1,5-3 menitMetabolisme:HeparEkskresi:Empedu dan ginjalEfek:- Pelumpuh otot- Tidak menyebabkan perubahan kardiovaskular- Tidak menimbulkan pelepasan histamin2
Tabel 5. Perbedaan antara pelumpuh otot depolarisasi dan nondepolarisasi4Ciri kelumpuhan ototDepolarisasiNondepolarisasi
Fasikulasi ototAdaTidak ada
Berpotensiasi denganAntikolinesteraseHipokalemia, hipotermia, obat anestesi inhalasi
Kelumpuhan bertahapTidakYa
ReversalTidak adaAda: Antikolinesterase, contoh prostigmin/ neostigmin dengan dosis 0,06 mg/kg BB
Sumber: Firman. 2014. Prevalensi Mual dan Muntah Pasca Anestesi Umum pada Bedah Elektif di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2013. Dikutip dari: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/41148 [Diakses tanggal 3 September 2014]
4. Terapi cairan pre-operatif dan intraoperatifTerapi cairan intraoperatif meliputi penyediaan kebutuhan cairan dasar dan penggantian sisa defisit pre-operatif serta kehilangan cairan intraoperatif. Idealnya, darah yang hilang harus digantikan dengan cairan kristaloid atau koloid untuk mempertahankan volum intravaskular tetap normovolemia hingga saat dimana diperkirakan risiko anemia lebih berat daripada risiko transfusi. Pada batas tersebut, kehilangan darah selanjutnya diganti dengan transfusi darah.5
Jumlah cairan yang harus diberikan dapat dihitung sebagai berikut:1. Tentukan derajat perdarahan preoperatifTabel 6. Derajat perdarahan berdasarkan American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support Program for Physicians tahun 20126VariabelKelas IKelas IIKelas IIIKelas IV
Kehilangan darah40% EBV
Nadi (x/menit)140
Tekanan darahNormalNormalMenurunMenurun
Tekanan nadiNormal atau meningkatMenurunMenurunMenurun
Nafas (x/menit)14-2020-3030-40>35
UOP (cc/jam)>3020-305-15Dapat diabaikan
Status mentalSlightly anxiousMidly anxiousAnxious, confusedConfused, lethargic
*EBV: Estimated blood volumeSumber: David dkk. 2014. Initial Evaluation of the Trauma Patient. Dikutip dari: http://emedicine.medscape.com/article/434707-overview [Diakses tanggal 3 September 2014]
2. Menentukan estimated blood volume (EBV)Tabel 7. EBV menurut umur5UmurEBV (Estimated Blood Volume)
Neonatus
Prematur95 ml/kg BB
Cukup bulan85 ml/kg BB
Bayi80 ml/kg BB
Dewasa
Laki-laki75 ml/kg BB
Perempuan65 ml/kg BB
Sumber: Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia. 2009. Panduan Tatalaksana Terapi Cairan Perioperatif. Jakarta: PP IDSAI
Penggantian cairan:- Kristaloid: 3 kali volume darah yang hilang- Koloid: sesuai volum darah yang hilang- Transfusi darah : whole blood = Hb x BB x 5 untuk PRC setengah dari whole bloodJika preoperasi Hb cukup (Hb >8 g%), maka pertimbangan transfusi durante operasi dilakukan jika mencapai maximal allowable blood loss.5Cara menghitung maximal allowable blood loss:5 Hitung EBV Hitung volum sel darah merah (RBCV) berdasarkan Ht preoperatif Hitung RBCV pada kadar Ht 30% (RBCV30%) Hitung RBCV yang hilang (RBCV lost = RBCV preop RBCV30%) Maximal allowable blood loss = RBCV lost x 3
Perkiraan jumlah kehilangan darah dan cairan selama pembedahan: Jumlah darah di tabung penghisap Perkiraan jumlah darah yang terserap pada kain kasa bedah dan duk:Kasa 4x4 cm dapat menampung 10 ml darah, sedangkan duk alas operasi yang basah dapat menampung 100-150 ml darah. Untuk lebih akurat, kasa dan duk alas operasi dapat ditimbang sebelum dan sesudah penggunaan. Kehilangan cairan karena redistribusi internal dan evaporasi5
Tabel 8. Kebutuhan cairan tambahan karena redistribusi internal dan evaporasi5Derajat keparahan trauma operasiKebutuhan cairan tambahan
Minimal (misal: hernioraphy)0-2 ml/kg BB
Sedang (misal: kolesistektomi)2-4 ml/kg BB
Berat (misal: reseksi usus)4-8 ml/kg BB
Sumber: Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia. 2009. Panduan Tatalaksana Terapi Cairan Perioperatif. Jakarta: PP IDSAI
5. Penilaian Post AnestesiaSetelah pasien dilakukan anestesi dan masuk ruang pemulihan, dokter harus menilai patensi jalan nafas, saturasi oksigen, vital sign, kecukupan cairan, kesadaran, nyeri, pergerakan, serta fungsi organ (hepar dan ginjal). Lama tinggal di ruang pemulihan tergantung dari teknik anestesi yang digunakan. Pasien dikirim ke ICU (Intensive Care Unit) apabila hemodinamik tidak stabil dan perlu support inotropik, serta membutuhkan ventilator. Pasien yang stabil dapat keluar dari ruang pemulihan. Salah satu penilaian yang dapat dilakukan adalah dengan Aldrete Score, dimana skor 9 berarti dapat keluar dari ruang pemulihan.2
Tabel 9. Aldrete Score2
Sumber: Soenarjo dkk. 2013. Anestesiologi. Semarang: Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
19
Daftar Pustaka
1. Morgan & Mikhail. 2013. Clinical Anesthesiology, 5th ed. US: Mc Graw Hill Education2. Soenarjo dkk. 2013. Anestesiologi, 2nd ed. Semarang: Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro3. Jaffe, R.A. et al. 2009. Anesthesiologist's Manual of Surgical Procedures, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins4. Firman. 2014. Prevalensi Mual dan Muntah Pasca Anestesi Umum pada Bedah Elektif di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2013. Dikutip dari: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/41148 [Diakses tanggal 3 September 2014]5. Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia. 2009. Panduan Tatalaksana Terapi Cairan Perioperatif. Jakarta: PP IDSAI6. David dkk. 2014. Initial Evaluation of the Trauma Patient. Dikutip dari: http://emedicine.medscape.com/article/434707-overview [Diakses tanggal 3 September 2014]