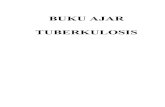Rangkuman Buku Ajar i
-
Upload
richa-nurselviana-damrah -
Category
Documents
-
view
219 -
download
3
description
Transcript of Rangkuman Buku Ajar i
RINGKASAN BUKU AJAR IOleh Richa Nurselviana, 1406640000
I. KEKUATAN DAN KEUTAMAAN KARAKTERPembentukan karakter memang menjadi salah satu kunci dari kemajuan dan pembangunan bangsa. Bung Hatta (1988) sudah menekankan pentingnya pembentukan karakter bersama dengan pembangunan rasa kebangsaan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan, Manusia yang merdeka adalah manusia dengan karakter yang kuat (Dewantara, 1988). Tujuan pendidikan adalah pembentukan watak atau karakter (Santoso, 1979). Pendidikan karakter juga merupaka usaha untuk membantu peserta didik mencapai kebahagiaan.18 Nilai Karakter dalam pendidikan karakter, yakni 1) religious, 2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 13) bersahabat/komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, dan 18) tanggungjawab.Kekuatan karakter bersumber pada keberadaan manusia sebagai makhluk spiritual. Spritualitas merupakan dasar dari kekuatan karakter. Kemampuan manusia untuk memperbaiki diri dan dunianya dari waktu ke waktu bersumber pada daya-daya spritualitasnya. Dengan spritualitasnya, manusia mengatasi dan melampaui keterbatasannya sebagai makhluk ilmiah.Karakter bukan kepribadian. Allport (1937) mendefinisikan kepribadian sebagai the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. Dari definisi tersebut dibapahmi bahwa kepribadian manusia terorganisasi dan unsur-unsurnya tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Kepribadian juga bersifat dinamis. Artinya, kepribadian manusia terus bergerak dan berkembang.Allport (1937) mendefinisikan karakter sebagai kepribadian yang dievaluasi. Karakter adalah kumpulan sifat mental dan etis yang menandai seseorang. Untuk membentuk karakter yang kuat, orang perlu menjalani serangkaian proses pemelajaran, pelatihan, dan peneladanan. Pendidikan pada intinta merupakan proses pembentukan karakter. Karakter yang kuat adalah karakter yang bercirikan keutamaan-keutamaan yang merupakan keunggulan manusia.Peterson dan Selingman (2004) mengemukakan tiga level konseptual dari karakter, yaitu keutamaan, kekuatan dan tema situasional dari karakter. Ini berguna untuk kepentingan pengenalan, pengukuran dan pendidikan karakter. Hubungan antara keutamaan, kekuatan, dan tema situasional karakter bersifat hierarkis. Keutamaan merupakan karekteristik utama dari karakter. Keutamaan sebagai nilai moral oleh karena itu keutamaan dianggap sebagai tindakan uang baik. Kekuatan karakter adalah unsur psikologis, lebih tepatnya proses mendefinisikan keutamaan. Tema situasional dari karakter adalah kebiasaan khusus yang mengarahkan orang untuk mewujudkan kekuatan karakter dalam situasi tertentu.Peterson dan Seligman (2004) mengemukakan kriteria dari karakter yang kuat.1. Karakter yang ciri-cirinya (kekuatan yang dikandungnya) memberikan sumbangan terhadap pembentukan kehidupan yang baik untuk diri-sendiri dan sekaligus untuk orang lain.2. Ciri-ciri atau kekuatan yang dikandungnya secara moral bernilai sesuatau yang baik bagi diri sendiri dan orang lain, bahkan walaupun tak ada keuntuknag langsung yang dihasilkan.3. Penampilan cirri-ciri itu tidak mengganggu, membatasi atau menghambat orang-orang di sekitar.4. Kekuatan karakter tampil dalam rentang tingkah laku individu yang mencangkup pikiran, perasaan, dan tindakan, serta dapat dikenali, dievaluasi dan diperbandingkan derajat kuat-lemahnya.5. Karakter yang kuat dapat dibedakan dari cirri-ciri yang berlawananan dengannya.6. Kekuatan karakter diawadahi oleh model atau kerangka piker yang ideal.7. Kekuatan karakter dapat dibedakan dari cirri-ciri yang berlawanan dengannya.8. Dalam konteks dan ruang lingkup tertentu, kekuatan karakter tertentu menjadi cirri yang mengagumkan bagi orang-orang yeng mempersepsinya.9. Boleh jadi tidak semua cirri karakter yang kuat muncul pada seseorang, tetapi kebanyakan dari cirri-ciri karakter yang kuat tampil pada orang itu.10. Kekuatan karakter memiliki akar psiko-sosisal; potensinya ada dalam diri sendiri, dan aktualisasinya dipengaruhi oleh lingkungan sosial.Ada enam kategori keutamaan dan 24 kekuatan karakter yang membentuknya.Kebijaksanaan dan PengetahuanAda enam kekuatan yang tercakup dalam keutamaan ini, yaitu (1) kreativitas, orisinilitas dan kecerdasan praktis, (2) rasa ingin tahu dan minat terhadap dunia, (3) cinta akan pembelajaran, (4) pikiran kritis dn terbuka, dan (5) perspektif atau kemampuan memahami beragam perspektif yang berbeda dan memadukannya secara sinergis untuk pencapaian hidup yang baik.Kemanusiaan dan CintaTerdiri atas kekuatan (1) baik hati dan murah hati, (2) selalu memiliki waktu dan tenaga untuk membantu orang lain, mencintai dan membolehkan diri sendiri untuk dicintai, serta (3) kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional.Kesatriaan (Courage)Mencakup empat kekuatan, yaitu (1) untuk menyatakan kebenaran dan mengakui kesalahan, (2) ketabahan dan kegigihan, tegus dan keras hati, (3) integritas, kejujuran, dan penampilan diri dengan wajar, serta (4) vitalitas, bersemangat dan antusias.Keadilan Kekuatan yang tercakup, yakni (1) kewarganegaraan atau kemampuan mengemban tugas, dedikasi dan kesetiaan demi keberhasilan bersama, (2) kesetaraan perlakuan terhadap orang lain atau tidak membeda-bedakan perlakuan yang diberikan kepada satu orang dengan yang diberikan kepada orang lain, dan (3) kepemimpinan.Pengelolaan DiriKekuatannya ialah (1) pemaaf dan pengampun, (2) pengendalian diri, (3) kerendahan hati, dan (4) kehati-hatian.TransendensiTercakup kekuatan (1) penghargaan terhadap keindahan dan kesempurnaan, (2) kebersyukuran atas segala hal yang baik, (3) oenuh harapan, optimis, dan berorientasi ke masa depan, semangat dan gairah besar untuk mneyongsong hari demi hari; (4) spritualitas: memiliki tujuan yang menuntun kepada kebersatuan dengan alam semesta, serta (5) menikmati hidup dan selera humor yang memadai.Orang dengan watak atau karakter yang kuat adalah orang yang berbahagia, mandiri dan member sumbangan positif kepada masyarakatnya.
II. DASAR-DASAR FILSAFATKata filsafat pertama kali ditemukan dalam tulisan sejarawan Yunani Kuno, Herodotus (484-424 SM) yang dimaksudkan dengan mencari pengetahuan semata. Cicero (106-43 SM) menduga bahwa kata filsafat dapat dilacak lebih jauh lagi asalnya pada Phytagoras (sekitar 582-500 SM). Dalam arti sempitnya, filsuf adalah orang yang menyelidiki dan mendiskusikan sebab-sebab benda dan kebaikan tertinggi (Thayer, 2011). Orang-orang yang gagasan dan pemikirannya didasari oleh pengetahuan tentang kebenaran dan dapat mempertahankannya dengan argumentasi yang kuat patut disebut filsuf. Mereka adalah pencinta kebijaksanaan. Apa yang dilakukan oleh filsuf disebut filsafat. Filsafat adalah usaha yang merupakan proses, bukan semata produk. Filsafat sebagai sebuah upaya adalah sebuah proses yang terus menerus berlangsung hingga kini. Proses tersebut berisi aktivitas-aktivitas untuk memahami segala perwujudan kenyataan.Berfisafat berarti memilih-milih obyek yang dikaji dan memberi penilaian terhadap obyek tersebut untuk dibandingkan. Hasil perbandingan kemudian dinilai guna mengetahui hubungan antara hal. Pemahaman yang ingin diperoleh dari kegiatan filsafat adalah pemahaman yang mendalam. Berfilsafat dilakukan secara sistematis yang berasal dari kata systema yang berarti keteraturan, tatanan dan saling keterkaitan. Dapat disimpulkan bahwa berpikir filosofis berarti berarti merenung yang bukan menghayal atau melamun. Merenung yang dimaksudkan adalah berkontemplasi, yaitu berpikir mendalam, kritis, dan universal dengan konsentrasi tinggi yang terfokus pada segi usaha mengetahui sesuatu.Objek filsafat harus menyangkut sesuatu yang jelas. Pada dasarnya filsafat menelaah segala masalah yang dapat dipikirkan oleh manusia. Namun, masalah yang dipikirkan itu harus jelas, bukan yang misterius. (Kattsoff, 2004: 1-5).Cabang dan Aliran FilsafatFilsafat dibagi menjadi cabang-cabang yang memiliki obyek kajian khusus dengan berbagai cara. Namun di sini hanya akan dibahas pembagian filsafat berdasarakn sistematika permasalahannya. Secara sistematis, filsafat dibagi menjadi 3 bagian besar:a. OntologiMerupakan bagian filsafat yang mengkaji tentang ada (being) atau tentang apa yang nyata. Ontologi berasal dari kata Latin, Onta yang berarti ada dan logia yang berarti ilmu, kajian, prinsip atau aturan. Secara umum didefinisikan sebagai studi filosofis tentang hakikat ada (being), eksistensi, atau realitas, serta kategori keberadaan dan hubungan mereka. Dalam arti umum ontology dibagi dua menjadi dua subbidang. Ontologi (dalam arti khusus) mengkaji ada yang keberadaannya tidak disangsikan lagi. Filsafat tentang sesuatu yang keberadaannya dipersepsi secara fisik dan tertangkap oleh indra. Metafisika adalah cabang filsafat yang mengkaji hal-hal (being) yang masih disangsinkan kehadirannya. Secara fisik hal; itu tidak tampak namun oleh sebagian orang dianggap ada, misalnya jiwa, ilusi, eksistensi Tuhan, dan sebagainya.b. EpistemologiMerupakan cabang filsafat yang mengkaji teori-teori tentang sumber hakikat, dan batas-batas pengetahuan, yaitu tentang bagaimana proses perolehan pengetahuan pada diri manusia dan sejauh mana ia dapat mengetahui. Epistemologi dibagi menjadi empat cabang:Epistemologi dalam arti sempit merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan yang ditelusuri melalui 4 pokok, yaitu : 1) Sumber pengetahuan, 2) Struktur pengetahuan, 3) Keabsahan pengetahuan, 4) Batas-batas pengetahuan.Filsafat ilmu pengetahuan merupakan cabang filsafat yang mengkaji ciri-ciri dan cara-cara memperoleh ilmu pengetahuan (science). Dalam filsafat ini, yang menjadi obyek adalah pengetahuan-pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan (science) yang merupakan pengetahuan yang sistematis, diperoleh dengan menggunakan metode-metode tertentu, logis dan teruji kebenarannya.Metodologi adalah cabang filsafat yang mengkaji cara-cara dan metode-metode ilmu pengetahuan memperoleh ilmu pengetahaun secara sistematis, logis, sahih (valid), dan terujiLogika adalah kajian filsafat yang mempelajari teknik-teknik dan kaidah-kaidah penalaran yang tepat. Argument menjadi satuan penalaran dalam dalam logika yang merupakan ungkapan dari putusan. Secara umum, ada dua jenis argument: 1) induktif dan 2) deduktif.c. AxiologyYang dibicarakan di axiologi adalah nilai-nilai (kata axiology dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang menjadi sumbu perilaku penghayatan dan pengalaman manusia). Dibagi menjadi:1. EtikaMengkaji tentang nilai apa yang berkaitan dengan kebaikan dan apakah itu perilaku baik. 2. EstetikaMengkaji pengalaman dan penghayatan manusia dalam menanggapi apakah sesuatu itu indah atau tidak. Jadi estetika membahas soal-soal keindahan yang dipersepsi oleh manusia.Aliran FilsafatBeberapa aliran yang cukup mempengaruhi sejarah dan perkembangan filsafat: 1) Rasionalisme, 2) Empirisme, 3) Kritisisme, 3) Idealism, 4) Vitalisme, 5) FenomenologiAlternatif Langkah Belajar FilsafatSecara umum, filsuf berusaha memperoleh makna istilah-istilah dengan cara melakukan analisis terhadap istilah-istilah itu berdasarkan pengenalan obyeknya dalam kenyataan. Analisis didefinisikan sebagai pemilahan bagian-bagian satu satu hal berdasarkan kategori yang relevan. Analisis terhadap istilah dilakukan dengan memilah-milah bagian makna atau isi pikiran dari istilah berdasarkan kategori tertentu. Meski pada dasarnya para filsuf memulai filsafat dari benda-benda dan bukan dari kata atau istilah, pemakaian istilah yang tepat harus dilakukan.Setelah analisis istilah, filsuf berusaha untuk memadukan hasil-hasil penyelidikannya melalui aktivitas sintesis. Dalam aktivitas sintesis, filsuf membanding-bandingkan bagian-bagian dari makna istilah yang dihasilkan dari aktivitas analisis. Lalu ia mencari benang merah antar-bagian untuk kemudian menemukan kesamaan makna di antara mereka. Dari situ diperoleh satu makna istilah yang komprehensif yang memayungi semua bagian sekaligus menjelaskan hubungan antar-bagian istilah.
III. DASAR-DASAR LOGIKALogika dapat diartikan sebagai kajian tentang prinsip, hukum, metode, dan cara berpikir yang benar untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Jika ditempatkan sebagai cabang filsafat, logika dapat diartikan sebagai cabang dari filsafat yang mengkaji prinsip, hukum dan metode berpikir yang benar, tepat dan lurusLogika, di samping etika, dapat dipahami sebagai asas pengaturan alam dan isinya yang dikembangkan manusia. Secara filosofis, logika adalah kajian tentang berpikir atau penalaran yang benar. Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan alasan yang relevan. Logika menggunakan pemahaman tentang standar kebenaran yang diperoleh dari epistemologi yang merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan. Sebagai bagian dari epistemologi dalam arti luas, logika juga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang mencakup segi-segi sumber pengetahuan, batas pengetahuan, struktur pengetahuan, dan keabsahan pengetahuan. Sebagai kajian tentang penalaran, logika juga berhubungan erat dengan bahasa alamiah yang sehari-hari dipakai oleh manusia yang juga berkaitan dengan matematikaUntuk menyamakan pengertian dan menghindari kesalahan penafsiran terhadap term diperlukan definisi. Definisi adalah pernyataan yang menerangkan hakikat suatu hal. Ada dua jenis definisi, yakni definisi nominal (definisi sinonim) dan definisi real (definisi analitik). Definisi real dibedakan atas dua, yakni definisi esensial dan definisi deskriptif. Definisi deskriptif dibedakan atas empat, yakni definisi distingtif (menunjukkan properti), definisi genetik (proses terjadinya suatu hal), definisi kausal (penyebab atau akibat), dan definisi aksidental (tidak mengandung hal-hal yang esensial).Selain dapat dijelaskan apa artinya, term juga dapat diuraikan dengan kriteria tertentu menjadi bagian-bagian. Penguraian term itu biasa disebut divisi. Divisi adalah uraian suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian berdasarkan satu kesamaan karakteristik tertentu.Pembagian dalam bentuk divisi merupakan upaya lain untuk menjelaskan term.Tiga jenis hubungan antar-pernyataan adalah implikasi, ekuivalensi dan independensi logis. Ketiga jenis hubungan ini sering muncul dalam keseharian kita dan sering pula dipertukarkan pengertiannya; tidak jarang orang memperlakukan hubungan yang satu sebagai hubungan yang lain.Deduksi adalah bentuk argumen yang kesimpulannya niscaya mengikuti premis-premisnya. Dalam deduksi kesimpulan diturunkan dari premis-premisnya. Bentuk deduksi yang paling umum digunakan adalah silogisme yangterdiri atas premis mayor, premis minor, dankesimpulan.Silogisme adalah jenis argumen logis yang kesimpulannya diturunkan dari dua proposisi umum (premis) yang berbentuk prosisi kategoris. Dilihat dari bentuknya, penilaian terhadap silogisme adalah sahih (valid) atau tidak sahih (invalid). Silogisme sahih jika kesimpulannya dibuat berdasarkan premis-premisnya dengan bentuk-bentuk yang tepat. Sedangkan penilaian benar (true) diberikan jika silogisme valid dan klaimnya akurat (informasinya sesuai dengan fakta). Istilah argumen induktif atau induksi biasanya mencakup proses-proses inferensial dalam mendukung atau memperluas keyakinan kita pada kondisi yang mengandung risiko atau ketidakpastian. Argumen induktif dapat dipahami sebagai hipotesis yang mengandung risiko dan ketidakpastianSesat pikir menurut logika tradisional adalah kekeliruan dalam penalaran berupa penarikan kesimpulan-kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah, yang disebabkan oleh dilanggarnya kaidah-kaidah logika. Dalam deduksi, penalaran ditentukan oleh bentuknya. Jika sebuah penalaran bentuknya tidak sesuai dengan bentuk deduksi yang baku, maka penalaran itu tidak sahih dan tergolong sesat pikir.Berikut ini adalah beberapa jenis sesat pikir formal. Empat Term, sesat pikir jenis empat term terjadi jika ada empat term yang diikutsertakan dalam silogisme padahal silogisme yang sahih hanya mempunyai tiga term. Term tengah yang tidak terdistribusikan, silogisme kategoris yang term tengahnya tidak memadai menghubungkan term mayor dan term minor. Proses ilisit adalah perubahan tidak sahih dari term mayor atau term minor. Premis-premis afirmatif tetapi kesimpulannya negatif terjadi jika dalam premis digunakan proposisi afirmatif (pernyataan yang menyatakan sesuatu secara positif) tetapi dalam kesimpulan digunakan proposisi negatif (pernyataan yang menegasi sesuatu). Dua premis negatif terjadi jika dalam silogisme kedua premis yang digunakan adalah proposisi negatif. Mengafirmasi konsekuensi adalah pembuatan kesimpulan yang diturunkan dari pernyataan yang hubungan antara anteseden dan konsekuensinya tidak niscaya tetapi diperlakukan seolah-olah hubungan itu suatu keniscayaan. Menolak anteseden juga merupakan pembuatan kesimpulan yang diturunkan dari pernyataan yang hubungan antara anteseden dan konsekuensinya tidak niscaya tetapi diperlakukan seolah-olah hubungan itu suatu keniscayaan. Mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan argumentasi disjungsi subkontrer (atau) terjadi jika hubungan atau di antara dua hal diperlakukan sebagai pengingkaran oleh hal yang satu terhadap hal yang lain. Atau belum tentu menunjukkan suatu pengingkaran. Mengingkari suatu pilihan dalam suatu disjungsi yang kontrer (dan) terjadi jika dua hal yang dihubungkan dengan kata dan diperlakukan seolah-olah nilai kebenaran (benar atau tidak benar) dari gabungan keduanya sama dengan nilai kebenaran dari setiap hal yang digabungkan, atau nilai tidak benar dari gabungan dari dua hal itu seolah-olah disebabkan oleh salah satunya.Kesalahan Umum Dalam Penalaran Induktif , kesalahan itu sering disebut dengan nama yang cukup umum dalam percakapan sehari-hari mengenai argumen induktif dan statistik. Dari semua pengetahuan yang kita miliki, sebagian besar kita peroleh dari pengalaman dan dokumentasi mengenai pengalaman orang lain. Tanpa pengetahuan empiris, kita tidak mungkin bertahan hidup. Pada akhirnya, kita mendasarkan pengetahuan empiris kita pada penalaran induktif. Deduksi memungkinkan kita memastikan kebenaran pengetahuan kita hanya jika kita yakin akan kebenaran premis-premisnya. Ada lima kesalahan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu 1. Kesalahan Generalisasi yang Terburu-buru2. Kesalahan Kecelakaan3. Kesimpulan Yang Tidak Relevan 4. Kesalahan Bukti yang Ditahan5. Kesalahan statistikalIV. DASAR-DASAR ETIKAEtika mengacu kepada seperangkat aturan-aturan, prinsip-prinsip atau cara berpikir yang menuntun tindakan dari suatu kelompok tertentu. Etika fokus tentang bagaimana kita mendefinisikan sesuatu itu baik atau tidak. Secara terminologis, moralitas sering kali dirujuk sebagai diferensiasi dari keputusan dan tindakan antara yang baik atau yang tidak baik. Moralitas mengacu pada nilai baik atau tidak baik yang diadopsi dalam suatu lingkungan tertentu (Borchert, 2006).Moralitas sangat berhubungan dengan etika karena hal itu adalah objek kajiannya. etika adalah suatu abstraksi dalam memahami atau mendefinisikan moral dengan melakukan refleksi atasnya.Etika diklasifikasikan manjadi empat, yaitu:Etika Normatif merupakan cabang etika yang penyelidikannyaterkait dengan pertimbangan pertimbangan tentang bagaimana seharusnya seseorang beritndak secara etis. Etika normatif adalah sebuah studi tindakan atau keputusan etis.Etika Terapan merupakan sebuah penerapan teori-teori etika secara spesifik kepada topik-topik kontroversial baik pada dominan atau publik seperti perang, hak-hak binatang, hukuman mati, dan lain-lain.Etika Deskriptif merupakan sebuah studi tentang apa yang dianggap etis oleh individu atau masyarakat. Etika deskripyif bukan sebuah etika yang mempunyai hubungan langsung dengan filsafat tetapi merupakan sebuah bentuk studi empiris terkait dengan perilaku-perilaku individual atau kelompok.Metaetika berhubungan dengan sifat penilaian moral. Fokus dari metaetika adalah arti atau makna dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam etika. Merupaka kajian tingkat kedua dari etika.Ada satu persoalan penting dalam etika, yaitu penyataan etika itu objektif atau hal itu bergantung kepada subjek etika itu sendiri.Realisme EtisBerpusat pada manusia menemukan kebenaran etis yang memiliki eksistensi independen di luar dirinya. Kosekuensinya, realisme etis ini mengajarkan bahwa kualitas etis atau tidak ada secara independen dari manusia dan pernyataan etis memberikan pengetahuan tentang dunia objektif.Nonrealisme EtisGagasan utamnya adalah manusia yang menciptakan kebenaran etis (Callcut, 2009,46). Nonrealisme etis sangat berkaitan dengan relativisme etis. Relativisme etis yang menagatakan bahwa jika Anda melihat budaya yang berbeda atau melihat periode yang berbeda dalam sejarah, Anda akan menemukan bahwa hal itu memiliki aturan etis yang berbeda pula.Pengkajian terhadap permasalahan etis pada dasarnya bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Ketika seseorang mengatakan "pembunuhan itu tidak baik" apa yang dimaksudkannya sesungguhnya? Kita dapat menunjukkan beberapa hal yang berbeda ketika Anda mengatakan 'pembunuhan adalah tidak baik' dengan menulis ulang pernyataan tersebut untuk menunjukkan apa yang benar-benar dimaksud. Pernyataan "pembunuhan itu adalah salah" adalah realisme moral yang didasarkan pada gagasan bahwa ada fakta-fakta nyata dan objektif terkait masalah etis di alam semesta.Pernyataan "saya tidak menyetujui pembunuhan" adalah subjektivisme yang mengajarkan bahwa penilaian etis tidak lebih dari pernyataan perasaan atau sikap seseorang.Pernyataan "tidak ada kompromi dengan pembunuhan" adalah emotivisme yang merupakan pandangan bahwa klaim moral adalah tidak lebih dari ekspresi persetujuan atau ketidaksetujuan.Pernyataan "jangan melakukan pembunuhan adalah preskriptivisme yang berfokus pada pernyataan etis adalah petunjuk atau rekomendasi.Prinsip moral dapat muncul dari berbagai sumber, diserap dari nilai-nilai agama, kaidah norma masyarakat, maupun dari hukum yang dibuat oleh negara. Hal-hal ini dapat menjadi referensi bagaimana seseorang bertingkah laku dan membedakan manakah baik dan buruk. Kant mempopulerkan filsafatnya, ia selalu berkata Sapere Aude! (beranilah berpikir secara mandiri. Pengertian Kant mendorong individu bahkan dalam urusan bersikap etis, individu harus dapat memikirkan dan bertindak atas kehendaknya sendiriTeori moral dalam filsafat dapat dipahami menjadi dua aliran besar, yang pertama adalah deontologis, seperti yang telah dibahas pada bagian Immanuel Kant, yang kedua adalah kaum konsekuensialis. Pandangan konsekuensialis menyatakan bahwa segala tindakan dianggap bernilai secara moral bila mempertimbangkan hasil akhir dari tindakan tersebut. Adapula tokoh yang mengembangkan paham etis utilitarian adalah John Stuart Mill. Utilitarianisme, dari akar kata utility, yang berarti kegunaan, menganggap bahwa dorongan utama bagi seseorang untuk bersikap etis adalah untuk mencapai kebahagiaan.Pandangan moral intuitif dari seorang etikus bernama W.D Ross, ia menggunakan penjelasan intuisi. Ross berargumen bahwa seseorang mengetahui secara intuitif perbuatan apa yang bernilai baik maupun buruk. Ia mengkritik pandangan utilitarian yang terlalu menekankan pada konsep kebahagiaan, bahkan mensejajarkan kebahagiaan sebagai kebaikan. Bagi Ross, kebahagiaan tidak dapat secara mudah disamakan dengan kebaikan, justru kebaikan adalah bentuk nilai moral yang lebih tinggi. Jadi tujuan moral adalah mencapai kebaikan bukan kebahagiaan.Ross menyebutkan tentang berbagai macam kewajiban yang membutuhkan pertimbangan individu dalam kejadian-kejadian aktual, ia menyusunya sebagai berikut; 1) Fidelitas atau yang menyangkut perihal bagaimana seseorang memegang janji atau komitmennya, 2) Kewajiban atas rasa terimakasih, ketika kita berkewajiban atas jasa yang sudah ditunjukan oleh orang lain, 3) Kewajiban berdasarkan keadilan, hal ini menyangkut perihal pembagian yang merata yang berhubungan dengan kebaikan orang banyak, 4) Kewajiban beneficence, atau bersikap dermawan, dan menolong orang lain sebagai tanggung jawab sosial, 5) Kewajiban untuk merawat dan menjaga diri sendiri, 6) Kewajiban untuk tidak menyakiti orang lain.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Pendidikan Karakter. http://perpustakaan.kemdiknas.go.id/download/Pendidikan%20Karakter.pdf (15 Maret 2015)Ibrahim, Slamet. Filsafat Ilmu Pengetahuan. https://www.academia.edu/5455916/Filsafat_ilmu_filsafat_ilmu_pengetahuan_pengetahuan. (15 Maret 2015)Takwin, Bagus., Fristian Hadinata., dan Saraswati Putri. (2013). Buku Ajar I: Kekuatan dan Keutaman Karakter, Filsafat, dan Etika. Depok: Universitas IndonesiaTeichman, Jenny. (1998). Pustaka Filsafat Etika Sosial. Jakarta: Kanisius