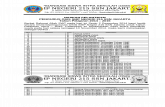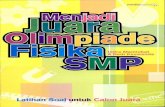PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP … · Pengurus OSIS dan Pramuka, selain itu penulis...
Transcript of PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP … · Pengurus OSIS dan Pramuka, selain itu penulis...
PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP KEBERDAYAAN
DAN PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA
(Kasus: Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur)
Oleh:
DEVIALINA PUSPITA
A14204019
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
RINGKASAN
DEVIALINA PUSPITA. PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP KEBERDAYAAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA. Kasus Program Urban Masyarakat Mandiri Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Di bawah bimbingan SAID RUSLI).
Salah satu isu penting pada negara-negara berkembang adalah kemiskinan,
kemiskinan merupakan fenomena yang sering dijumpai, baik di perkotaan
maupun perdesaan. Berbagai upaya telah ditempuh negara-negara berkembang
untuk mengatasi isu ini. Di Indonesia, dewasa ini tidak hanya pemerintah yang
peduli untuk mengentaskannya, instansi swasta, LSM dan lain-lain menaruh
perhatian yang sama. Salah satu lembaga yang peduli adalah lembaga pengelola
zakat, baik milik pemerintah, swasta, maupun swadaya masyarakat. Lembaga
tersebut memanfaatkan dana zakat yag dibayarkan orang-orang yang wajib untuk
mengeluarkannya (muzakki) untuk kemudian disalurkan kepada orang-orang yang
berhak menerimanya (mustahik), salah satu diantaranya kepada fakir miskin .
Dompet Dhuafa Republika melalui Program Masyarakat Mandiri (MM)
sudah bertahun-tahun melakukan proses pembinaan bagi kaum dhuafa (miskin)
dengan memberikan pinjaman modal usaha agar mereka mampu untuk bertahan
hidup bahkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Daerah yang dijadikan
lokasi penelitian adalah daerah Bidaracina yang merupakan salah satu daerah
binaan MM.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi karakteristik rumah
tangga penerima zakat dan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, 2)
Menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat terhadap keberdayaan rumah tangga
miskin penerima bantuan zakat di Kelurahan Bidaracina, 3) Menganalisis
pengaruh pendayagunaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan pada
rumah tangga miskin penerima bantuan zakat di Kelurahan Bidaracina.
Penelitian ini menggunakan perpaduan dua pendekatan penelitian, yaitu
pendekatan kuantitatif (metode survei) dan pendekatan kualitatif. Respoden yang
diwawancarai terdiri dari 24 orang, yang terdiri dari 20 orang mitra, seorang
ketua RT, 2 orang tokoh masyarakat, dan seorang pendamping. Selain data primer
(kuesioner dan panduan pertanyaan), penelitian ini juga menggunakan data
sekunder (data-data dari MM dan Kelurahan Bidaracina).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga
penerima zakat terdiri dari: 1) karakteristik bangunan rumah; 2) kepemilikan aset
pribadi; dan 3) penghasilan usaha pokok (laba usaha). Karakteristik tersebut
merupakan parameter yang digunakan MM untuk menyatakan layak tidaknya
seseorang untuk menjadi mitra. Seseorang layak menjadi mitra apabila sekurang-
kurangnya dua karakteristik tersebut dinyatakan memenuhi kriteria. Seluruh
responden peneliti dinyatakan memenuhi kriteria, sehingga layak mendapatkan
pinjaman MM, sedangkan menurut Garis Kemiskinan Sajogjo (dalam Rusli, dkk,
1995), dapat disimpulkan bahwa sebanyak 75 persen responden berada di bawah
Batas Garis Kemiskinan, sedangkan sisanya sebanyak 25 persen berada di atas
Batas Garis Kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa responden yang berada
di bawah Batas Garis Kemiskinan merupakan responden yang layak mendapatkan
pinjaman.
Faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah faktor eksternal, yaitu
kebijakan pemerintah berupa kenaikkan harga BBM, bencana alam (banjir), dan
sempitnya lapangan pekerjaan. Kenaikan harga BBM dan bencana banjir yang
melanda Jakarta tahun 1996 adalah faktor penyebab langsung yang menyebabkan
mitra menjadi miskin/tambah miskin. Sempitnya lapangan pekerjaan adalah faktor
yang tidak langsung mempengaruhi mereka.
Bantuan MM hanya sampai pada memberdayakan mitra untuk dapat
melanjutkan usahanya, belum sampai pada peningkatan kesejahteraan. Hal
tersebut dapat dilihat dari pendayagunaan bantuan hanya sampai bagaimana mitra
harus memutar modal mereka setiap harinya, belum sampai pada tahap bagaimana
mitra harus mengembangkan usaha dan mensejahterakan mereka dengan
menaikkan pendapatannya.
Secara umum omzet usaha mitra mengalami kenaikkan. Namun jika
dilihat dari segi laba dan pendapatan usaha sebagian besar mitra mengalami
penurunan. Dapat dikatakan bantuan MM belum berpengaruh nyata terhadap
upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pendapatan
mitra yang berimplikasi kepada belum tercapainya mitra yang sejahtera.
PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP KEBERDAYAAN
DAN PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA
(Kasus Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur)
Oleh:
Devialina Puspita
A14204019
SKRIPSI
Sebagai Bagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian
pada
Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh:
Nama : Devialina Puspita
NRP : A14204051
Program Studi : Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Judul : Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan
Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga
Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana
Pertanian pada Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Ir. Said Rusli, MA
NIP. 130 345 011
Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian
Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr. NIP. 131 124 019
Tanggal Kelulusan:
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL
“PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP KEBERDAYAAN
DAN PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA” BELUM PERNAH
DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN
MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK
TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-
BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG
BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH
PIHAK LAIN, KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG
DINYATAKAN DALAM NASKAH. DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA
BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN SAYA BERSEDIA
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERNYATAAN INI.
Bogor, September 2008
Devialina Puspita
A14204019
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 21 Desember 1986, dari
pasangan H. Umardani dan Hj. Nasroh. Penulis dibesarkan di sebuah daerah di
Tangerang, tepatnya di Jl. Ketimun, RT 05/09 No. 7 Pondok Cabe Ilir, Pamulang.
Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dengan Widya Sari dan
Idha Farida sebagai kakak, dan Ade Zulharmain sebagai adik, selama 21 tahun
penulis telah menjalani pendidikan formal pada Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Miftahul Huda Cipayung Ciputat (1992-1998), SLTP PGRI 1 Ciputat (1998-
2001), SMAN 1 Ciputat, (2001-2004), Institut Pertanian Bogor, Tahun 2004-
sekarang.
Sejak SLTP penulis aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, diantaranya
Pengurus OSIS dan Pramuka, selain itu penulis merupakan juara umum berturut-
turut selama tiga tahun, dan mendapatkan beasiswa prestasi. Pada tingkat SMA
penulis juga aktif di berbagai organisasi, baik dalam lingkup sekolah seperti
Pengurus OSIS dan Rohis SMAN 1 Ciputat selama tiga kepengurusan, maupun
dalam lingkup daerah, seperti pengurus Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia
(KAPMI) pada tahun 2001-2002. Penulis juga pernah mendapatkan prestasi di
luar sekolah, diantaranya Juara 1 Lomba Debat Pelajar Muslimah se-DKI Jakarta
tahun 2002-2003, Juara 1 Lomba Debat Pelajar se-Jakarta Selatan, dan Peserta
Terbaik Pesantren Kilat Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2002-2003.
Tahun 2004, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor
melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada program studi
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM), Jurusan Ilmu-ilmu Sosial
Ekonomi, Fakultas Pertanian. Pada Tingkat Persiapan Bersama (TPB) penulis
aktif di kelembagaan mahasiswa TPB, yaitu pada Dewan Perwakilan Mahasiswa
(DPM) TPB IPB 2004-2005, selanjutnya pada tingkat dua penulis kembali aktif
di organisasi legislatif, yaitu dengan menjadi pengurus DPM Fakultas Pertanian
2005-2006 dan tergabung ke dalam Tim Wakil Mahasiswa Unsur Mahasiswa,
tahun ketiga penulis aktif di MPM/DPM KM 2006-2007, dan tingkat akhir
penulis masih tercatat sebagai pengurus MPM/DPM KM 2007-2008.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas
rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul ”Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan
Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus Program Urban Masyarakat
Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)”.
Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penulis
berupaya untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan pada rumah tangga dan
faktor-faktor penyebabnya, menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat terhadap
keberdayaan dan pengentasan kemiskinan rumah tangga.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran
yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan
dijadikan referensi penulisan selanjutnya.
Bogor, Agustus 2008
Penulis
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang
tiada henti memberikan rahmat, nikmat dan petunjuknya kepada penulis sehingga
dapat menyelesaikan karya kecil ini. Tak lupa, salam dan shalawat penulis
sampaikan kepada pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW.
Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini izinkanlah
penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Ir. Said Rusli, MA sebagai dosen pembimbing yang telah dengan tulus dan
sabar memberikan arahan, bimbingan, perhatian, masukan, motivasi, dan
nasehat serta meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik.
2. Ir. Nurani W. Prasodjo M.S. sebagai Dosen penguji utama atas kritik dan
masukannya dalam penulisan skripsi ini.
3. Ratri Virianita, S. Sos. M.Si. sebagai Dosen Komisi Pendidikan atas kritik dan
masukannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Keluarga tercinta, mama dan bapak yang senantiasa memberikan sokongan
doa, materi dan kasih sayang.
5. Ka Idha yang sudah bersedia menjadi dosen pembimbing di rumah, Bang
Achmad yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Dek
Fawwaz yang menjadi inspirasi penulis.
6. Masyarakat Mandiri Crew, Ibu Wasiah yang telah memberikan izin penulis
untuk melakukan penelitian di daerah binaan MM Bidaracina, Mba Leni dan
Mas Dede sebagai pendamping mitra yang selalu bersedia untuk membantu
penulis.
7. Mitra MM yang selalu bersedia bekerjasama dengan penulis dengan
memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, Ibu
Mus yang bersedia mengantarkan penulis untuk menyusuri gang-gang sempit.
8. Keluarga kedua penulis di Bogor, Fitri, Nyit-nyit, RisQ, dan Novita. Terima
kasih atas kebersamaannya di DPM TPB. Semoga ukhuwah yang terjalin tetap
terjaga.
9. Teman-teman sepermainan baik di dalam kelas kuliah maupun di luar kelas,
Qoi, Princess Nau, Dinceu, Tongki, Uchay, Mamachi. Terima kasih atas
kebersamaannya selama ini.
10. Teman seperjuanganku Leo dan Bang Ilham, terima kasih kesediaannya untuk
konsultasi bareng.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran
yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan
dijadikan referensi penulisan selanjutnya.
xi
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2. Perumusan Masalah .................................................................. 4
1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................... 5
1.4. Kegunaan Penelitian .................................................................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Kemiskinan .................................................................. 7
2.1.1. Pengertian Kemiskinan .................................................. 7
2.1.2. Ukuran Kemiskinan ........................................................ 9
2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan ............ 15
2.1.4. Upaya-upaya Mengentaskan Kemiskinan ....................... 16
2.2. Konsep Zakat ............................................................................. 18
2.2.1. Pengertian dan Golongan Penerima Zakat ...................... 18
2.2.2. Peran dan Hikmah Zakat ................................................ 19
2.2.3. Lembaga Pengelola Zakat ............................................... 21
2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .......................................... 23
2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .......................... 23
2.3.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ............................. 23
2.4. Kerangka Pemikiran .................................................................. 25
xii
2.5. Hipotesis Pengarah ..................................................................... 28
2.5.1. Hipotesis Umum ............................................................ 28
2.3.1. Hipotesis Khusus ........................................................... 28
2.6. Definisi Operasional ................................................................. 28
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Strategi Penelitian .................................................................... 31
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................... 31
3.3. Penentuan Responden dan Informan ........................................ 32
3.4. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 32
3.5. Teknik Analisis Data ................................................................ 32
BAB IV GAMBARAN UMUM KELURAHAN BIDARACINA
4.1. Sejarah ....................................................................................... 34
4.2. Kondisi Geografis ..................................................................... 35
4.3. Kondisi Kependudukan ............................................................. 35
4.3.1. Jumlah Penduduk .......................................................... 35
4.3.2. Penduduk BerdasarkanMata Pencaharian .................... 36
4.3.3. Penduduk BerdasarkanTingkat Pendidikan ................. 36
4.3.4. Penduduk BerdasarkanAgama ..................................... 37
4.4. Sarana dan Prasarana................................................................ 37
4.4.1. Kesehatan ...................................................................... 37
4.4.2. Pendidikan .................................................................... 38
4.4.3. Fasilitas Peribadahan ..................................................... 39
4.5. Kelembagaan Ekonomi ............................................................. 39
4.6. Zakat dan Kemiskinan di Bidaracina ........................................ 41
4.7. Ikhtisar ..................................................................................... 42
xiii
BAB V PELAKSANAAN PROGRAM URBAN MASYARAKAT MANDIRI
5.1. Profil dan Pelaksanaan Program Urban Masyarakat
Mandiri ...................................................................................... 44
5.1.1. Profil Program Urban Masyarakat Mandiri ................. 44
5.1.2. Rancangan Pelaksanaan Program Urban Masyarakat
Mandiri .......................................................................... 46
5.2. Pelaksanaan Program Urban Masyarakat Mandiri .................... 49
5.3. Ikhtisar ...................................................................................... 52
BAB VI KARAKTERISTIK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DAN FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
6.1. Karakteristik Masyarakat Penerima Bantuan ............................. 54
6.1.1. Karakteristik Bangunan Rumah ..................................... 54
6.1.2. Kepemilikan Aset Pribadi ............................................. 61
6.1.3. Tingkat Penghasilan Usaha Pokok (Laba Usaha) ........ 64
6.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan ......................................... 65
6.2.1. Faktor-faktor Internal ...................................................... 65
6.2.2. Faktor-faktor Eksternal ................................................... 70
6.3. Ikhtisar ...................................................................................... 73
BAB VII PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP
KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN
7.1. Ekonomi Produktif (Modal Usaha dan Tabungan) .................. 75
7.2. Investasi SDM (Pendidikan dan Kesehatan) ............................ 76
7.3. Kebutuhan Non-produktif (Konsumsi Rumah Tangga) ........... 78
7.4. Ikhtisar ..................................................................................... 80
xiv
BAB VIII PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA
MISKIN
8.1. Omset Usaha Responden Sebelum dan Setelah
Mendapatkan Pinjaman ........................................................... 82
8.2. Laba Usaha Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan
Pinjaman .................................................................................. 84
8.3. Pendapatan Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan
Pinjaman .................................................................................. 86
8.4. Ikhtisar ..................................................................................... 92
BAB IX PENUTUP
9.1. Kesimpulan ............................................................................. 95
9.2. Saran ........................................................................................ 97
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 98
LAMPIRAN ...................................................................................................... 98
xv
DAFTAR TABEL
Nomor Teks Halaman
Tabel 1. Batas Garis Kemiskinan (Sajogjo, dalam Rusdi, dkk, 1995) ............ 10
Tabel 2. Ukuran dan Kriteria Kemiskinan BerdasarkanBeberapa
Lembaga Pemerintahan, Bogor, 2008 .............................................. 12
Tabel 3. Indikator Karakteristik Bangunan Rumah (Indikator
Masyarakat Mandiri), Jakarta, 2008 ................................................ 14
Tabel 4. Kepemilikan Aset Pribadi (Indikator Masyarakat Mandiri),
Jakarta, 2008 .................................................................................... 15
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Bidaracina Berdasarkan
Jenis Kelamin, Mei 2008 ................................................................. 35
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kelurahan Bidaracina Berdasarkan
Mata Pencaharian, Mei 2008............................................................. 36
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kelurahan Bidaracina Berdasarkan
Tingkat Pendidikan, Mei 2008 ........................................................ 37
Tabel 8. Jumlah Penduduk Kelurahan Bidaracina Berdasarkan Agama,
Mei 2008 .......................................................................................... 37
Tabel 9. Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Bidaracina,
Mei 2008 ......................................................................................... 38
Tabel 10. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelurahan Bidaracina,
Mei 2008 ......................................................................................... 39
Tabel 11. Sarana dan Prasarana Peribadahan Kelurahan Bidaracina,
xvi
Mei 2008 ......................................................................................... 39
Tabel 12. Kelembagaan Ekonomi Informal Kelurahan Bidaracina,
Mei 2008 ......................................................................................... 40
Tabel 13. Kelembagaan Ekonomi Nonformal Kelurahan Bidaracina,
Mei 2008 .......................................................................................... 40
Tabel 14. Lembaga Lokal (IMW/ISM) dan Usaha Bersama yang telah
Terbentuk, Jakarta, 2008 .................................................................. 46
Tabel 15. Tahapan Pendampingan Program Perkotaan (Urban),
Jakarta, 2008 .................................................................................... 50
Tabel 16. Input, Aktivitas dan Output Program Perkotaan (Urban),
Jakarta 2008 ...................................................................................... 51
Tabel 17. Daftar Skim Pembiayaan Program Komunitas Urban,
Jakarta, 2008 .................................................................................... 52
Tabel 18. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Rumah,
Kelurahan Bidaracina, 2008 .............................................................. 54
Tabel 19. Jumlah Responden Berdasarkan Ukuran Rumah,
Kelurahan Bidaracina, 2008 ............................................................. 57
Tabel 20. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Dinding Rumah,
Kelurahan Bidaracina, 2008 .............................................................. 58
Tabel 21. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Lantai Rumah, Kelurahan
Bidaracina, 2008 .............................................................................. 58
Tabel 22. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Atap Rumah, Kelurahan
Bidaracina, 2008 .............................................................................. 59
Tabel 23. Jumlah Responden Berdasarkan Dapur Rumah, Kelurahan
Bidaracina, 2008 ............................................................................... 60
Tabel 24. Jumlah Responden Berdasarkan Kursi Rumah, Kelurahan
Bidaracina, 2008 .............................................................................. 60
xvii
Tabel 25. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Kebun/Sawah,
Kelurahan Bidaracina, 2008 ............................................................. 61
Tabel 26. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Barang/barang
Elektronik, Kelurahan Bidaracina, 2008 .......................................... 62
Tabel 27. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Jenis Kendaraan,
Kelurahan Bidaracina, 2008 .............................................................. 63
Tabel 28. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Binatang Ternak,
Kelurahan Bidaracina, 2008 .............................................................. 63
Tabel 29. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Simpanan Uang,
Kelurahan Bidaracina, 2008 .............................................................. 64
Tabel 30. Faktor-faktor Internal yang Menyebabkan Kemiskinan, Kelurahan
Bidaracina, 2008 .............................................................................. 67
Tabel 31. Faktor-faktor Eksternal yang Menyebabkan Kemiskinan,
Kelurahan Bidaracina, 2008 ............................................................. 70
Tabel 32. Pengeluaran Responden untuk Pendidikan, Kelurahan
Bidaracina, 2008 ............................................................................... 77
Tabel 33. Omset Usaha Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan
Pinjaman, Kelurahan Bidaracina, 2008 ............................................. 82
Tabel 34. Laba Usaha Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan
Pinjaman, Kelurahan Bidaracina, 2008 ............................................. 84
Tabel 35. Pendapatan Usaha Responden Sebelum dan
Setelah Mendapatkan Pinjaman, Kelurahan Bidaracina, 2008 ......... 87
Tabel 36. Pendapatan Perkapita Responden Berdasarkan Batas Garis
Kemiskinan Sajogjo (dalam Rusli, dkk, 1995), Kelurahan
Bidaracina, 2008 ............................................................................... 91
xviii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Teks Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 27
xix
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. Peta Lokasi Kelurahan Bidaracina ...............................................
2. Kuesioner Penelitian .................................................................... 152
3. Hasil Uji t Antara Siswa SMAN 5 dan MAN 2 Bogor
Mengenai Pemilihan Lokasi Menonton Film dan Jenis Film
Yang Ditonton .............................................................................. 153
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di negara
berkembang dan telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian pemerintah dan
masyarakat dunia. Hal ini disebabkan kemiskinan memiliki implikasi luas
terhadap kehidupan masyarakat di suatu kawasan dan global, khususnya jika
dikaitkan dengan implikasi ekonomi, sosial dan keamanan secara keseluruhan.
Kemiskinan merupakan ekses dari tidak meratanya kepemilikan/alokasi sumber
daya yang jumlahnya terbatas di dalam suatu masyarakat/negara. Dalam
hubungan ini, terdapat suatu kondisi dimana satu orang/sekelompok orang/
golongan menguasai lebih banyak sumber daya yang ada (surplus) dibanding satu
orang/sekelompok orang lainnya yang menguasai sumber daya yang ada dalam
jumlah yang relatif sangat kecil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2006) pada periode 2000-
2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun
2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan
persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97
persen pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah
penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 %) pada
bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 %) pada bulan Maret 2006.
Penduduk miskin di daerah perdesaanan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah
perkotaan bertambah 2,09 juta orang. Sedangkan data terbaru BPS (2007)
menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17
2
juta (16,58 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2006
yang berjumlah 39,30 juta (17,75 %), berarti jumlah penduduk miskin turun
sebesar 2,13 juta. Selama periode Maret 2006-Maret 2007, penduduk miskin di
daerah perdesaanan berkurang 1,20 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang
0,93 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan
perdesaanan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52
%) penduduk miskin berada di daerah perdesaanan.
Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menunjukkan adanya tren
positif untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk di bawah garis
kemiskinan nasional pada tahun 2015 menjadi sebesar 7,2 persen (BPS, 2007).
Hal ini harus diupayakan dengan usaha, kerjasama seluruh stakeholders dan
keberpihakan terhadap kaum miskin dalam pelaksanaan pembangunan di
Indonesia. Seluruh stakeholders, baik pemerintah, swasta, lembaga independen
maupun masyarakat harus sama-sama menaruh perhatian yang besar terhadap
pengentasan kemiskinan melalui berbagai macam program.
Stakeholders yang saat ini sedang menjamur dalam masyarakat antara lain
adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah (LAZIS), Badan Amil Zakat
(BAZ), baik yang berasal dari pemerintah maupun lembaga yang berdiri secara
independen. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang bergerak dalam
peningkatan sosial ekonomi masyarakat miskin dengan memanfaatkan zakat,
infak dan shadaqah dari para donatur. Dalam kaitannya dengan masalah
kemiskinan, zakat berpotensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang
terjadi. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, zakat dapat dipandang sebagai
energi sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi,
3
zakat dapat dipandang sebagai alat/rangsangan yang mendorong kemajuan
perekonomian nasional (Inayah, 2005).
Pengelolaan zakat harus diupayakan dengan optimal. Apabila dikelola
dengan optimal, maka potensinya pun akan besar. Berdasarkan data SUSENAS
(1999), jumlah nilai dana zakat yang dapat dihimpun dari sektor maal dapat
mencapai sekitar Rp 3,825 trilyun. Jika ditambah dengan zakat perniagaan,
pertanian, peternakan, emas, perak, infak, shadaqah, kafarat, fidyah, wakaf dan
lain-lain, maka umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana yang sangat besar.
Melalui bantuan dana zakat, diharapkan para mustahik (penerima zakat)
mampu mendayagunakannya untuk kegiatan usaha-usaha yang produktif agar
dapat terus bermanfaat bagi kehidupan keluarganya, yang sesuai dengan ketentuan
UU No. 38 tahun 1999 pasal 16 tentang pendayagunaan zakat. Dalam pasal
tersebut dijelaskan bahwa pendayagunaan hasil zakat berdasarkan skala prioritas
kebutuhan mustahik untuk kemudian dimanfaatkan untuk usaha produktif.
Pendayagunaan zakat produktif dimaksudkan untuk membantu permodalan dalam
berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha
golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya menganggur
atau tidak dapat berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.
Kendatipun potensi zakat sangat besar, pengaruh pendayaguaan zakat
sangat ditentukan oleh kemampuan (keberdayaan) rumah tangga-rumah tangga
penerima zakat (rumah tangga miskin) menggunakannya untuk usaha-usaha
ekonomi produktif. Dengan kemampuan rumah tangga miskin menggunakan
zakat untuk usaha-usaha ekonomi produktif dapat diharapkan tertanggulanginya
keadaan kemiskinan yang mereka alami yang pada gilirannya akan memberikan
4
kontribusi kepada penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Oleh karena itu,
pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan rumah tangga perlu
ditelaah melalui penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai daerah. Dalam
hubungan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh
Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan
Rumah Tangga (Kasus: Rumah Tangga Penerima Zakat Program Urban
Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur).
1.2. Perumusan Masalah
Sebagaimana dapat dilihat pada data-data jumlah penduduk miskin yang
telah dikemukakan, masalah kemiskinan di Indonesia belum dapat ditanggulangi
secara memuaskan. Sebagian besar jumlah penduduk miskin ada di
peKelurahanan. Hal ini juga terlihat di Jakarta Timur seperti di Kelurahan
Bidaracina. Di Kelurahan ini cukup banyak penduduk atau rumah tangga miskin.
Diantara rumah tangga miskin tersebut terdapat rumah tangga yang menerima
zakat dari Lembaga Amil Zakat dan dijadikan sebagai Kelurahan binaan.
Pendayagunaan dana zakat dapat optimal apabila digunakan untuk kegiatan/usaha
produktif yang dilakukan oleh rumah tangga penerima zakat.
Kenyataan belum dapat ditanggulanginya masalah kemiskinan terakait
dengan berbagai faktor, seperti karakteristik rumah tangga, potensi sumberdaya
alam pada Kelurahan tersebut, program-program pengentasan kemiskinan yang
belum tepat sasaran, budaya dan etos kerja yang rendah, dan lain-lain.
5
Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai
berikut.
1 Bagaimanakah karakteristik rumah tangga penerima zakat dan faktor-faktor
yang menyebabkan kemiskinan?
2 Bagaimanakah pengaruh pendayagunaan zakat terhadap keberdayaan rumah
tangga miskin penerima bantuan zakat di Kelurahan Bidaracina?
3 Bagaimanakah pengaruh pendayagunaan zakat terhadap upaya pengentasan
kemiskinan pada rumah tangga miskin penerima bantuan zakat di Kelurahan
Bidaracina?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasi karakteristik rumah tangga penerima zakat dan faktor-faktor
yang menyebabkan kemiskinan.
2. Menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat terhadap keberdayaan rumah
tangga miskin penerima bantuan zakat di Kelurahan Bidaracina.
3. Menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat terhadap upaya pengentasan
kemiskinan pada rumah tangga miskin penerima bantuan zakat di Kelurahan
Bidaracina.
6
1.4. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:
1. Bagi penulis, berguna sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman ilmiah
dan juga merupakan sarana untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh
yaitu dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan yang kemudian
dikaitkan dengan teori-teori yang sesuai.
2. Bagi kalangan masyarakat Kelurahan Bidaracina, penelitian ini diharapkan
menjadi sarana untuk berpartisipasi dalam membangun kesadaran untuk
bangkit dari kemiskinan.
3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih
lanjut, baik dari segi teoritis maupun praktis.
4. Bagi penentu kebijakan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk
kegiatan perencanaan dan rancangan program selanjutnya dalam kegiatan
pengentasan kemiskinan.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kemiskinan
2.1.1. Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah yang dapat dilihat dari berbagai aspek.
Berikut ini adalah berbagai pandangan menganai kemiskinan menurut Nasoetion
(1996):
1. Ditinjau dari titik pandang ekonomi, kemiskinan dianggap merupakan
masalah dengan beberapa alasan, antara lain: (1) kemiskinan merupakan
cermin dari rendahnya permintaan agregat. Lebih lanjut permintaan agregat
yang rendah mengurangi insentif untuk mengembangkan sistem produksi, (2)
kemiskinan berkaitan dengan rasio kapital/tenaga kerja yang rendah yang
selanjutnya mengakibatkan produktivitas tenaga kerja yang rendah pula, dan
(3) kemiskinan seringkali mengakibatkan kesalahan dalam mengalokasikan
sumberdaya terutama tenaga kerja.
2. Ditinjau dari sudut pandang sosial, kemiskinan merupakan ciri lemahnya
potensi suatu masyarakat untuk berkembang. Di samping itu, kemiskinan
berhubungan dengan aspirasi yang sempit dan pendeknya horizon waktu
wawasan ke depan suatu masyarakat.
3. Ditinjau dari sudut pandang politik, kemiskinan merupakan masalah
ketergantungan dan eksploitasi suatu kelompok masyarakat oleh kelompok
masyarakat lainnya.
Pada dasarnya kemiskinan dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu
(1) kemiskinan alamiah dan (2) kemiskinan struktural. Menurut Nasoetion (1996)
8
kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh rensahnya kualitas
sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga peluang produksi yang
dapat dilakukan pada umumnya dengan tingkat efisiensi yang relatif rendah.
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak
langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan.
Menurut Soemardjan (1997), ditinjau dari sudut pandang sosiologi,
kemiskinan dapat dilihat dari pola-polanya, yaitu:
1. Kemiskinan Individual.
Kemiskinan ini terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang disandang
oleh seorang individu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk
mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan.
2. Kemiskinan Relatif.
Untuk mengetahui kemiskinan relatif ini perlu diadakan perbandingan antara
taraf kekayaan material dari keluarga/rumah tangga di dalam suatu komunitas
tertentu. Dengan perbandingan tersebut dapat disusun pandangan masyarakat
mengenai mereka yang tergolong kaya dan relatif miskin di dalam komunitas
tersebut. Ukuran yang dipakai adalah ukuran yang ada pada masyarakat tersebut
(lokal). Dengan demikian suatu keluarga yang di suatu komunitas dianggap relatif
miskin dapat saja termasuk golongan kaya apabila diukur dengan kriteria di
tempat lain yang secara keseluruhan merupakan komunitas lebih miskin.
3. Kemiskinan Stuktural.
Kemiskinan ini dinamakan struktural karena disandang oleh suatu golongan
yang buit in (menjadi bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu
masyarakat). Di dalam konsep kemiskinan struktural, ada suatu golongan sosial
9
yang menderita kekurangan fasilitas, modal, sikap mental/jiwa usaha yang
diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan.
4. Kemiskinan Budaya.
Kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan
alam yang mengandung cukup banyak sumberdaya yang dapat dimanfaatkan
untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kemiskinan ini disebabkan kebudayaan
masyarakat tidak memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, teknologi, jiwa usaha
dan dorongan sosial yang diperlukan untuk menggali kekayaan alam di
lingkungannya dan menggunakannya untuk kebutuhan masyarakat.
2.1.2. Ukuran Kemiskinan
Upaya pengentasan kemiskinan harus mencapai kepada langkah-langkah
yang nyata, para perencana dan pengelola pembangunan perlu kesepakatan
tentang pengertian dan ukuran-ukuran yang dipakai untuk menetukan sasaran
yang dianggap sebagai penduduk miskin. Pengertian dan ukuran-ukuran tersebut
harus diterima dan dipakai oleh semua pihak (Soemardjan, 1993).
Kemiskinan memiliki dimensi dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung
dari sudut pandang melihatnya. Setiap tokoh atau lembaga/instansi memiliki sudut
padang yang tidak sama dalam menerjemahkan hal tersebut. Menurut Sajogjo
(dalam Rusli, dkk, 1995), identifikasi tingkat kemiskinan dapat difokuskan pada
dua aspek, yaitu golongan dan daerah miskin. Penentuan besarnya golongan
miskin dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini
ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan/pengeluaran per bulan/per tahun.
Konsep garis kemiskinan Sajogjo (dalam Rusli, dkk, 1995) ditentukan
10
berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga setara dengan konsumsi beras per
kapita per tahun dan dat perbedaan antara kota dan desa (Tabel 1).
Tabel 1. Batas Garis Kemiskinan (Sajogjo, dalam Rusdi, dkk, 1995)
No Kategori Batas Tingkat Pendapatan (setara beras per kapita
per tahun) Perkotaan (dalam kg) Perdesaan (dalam kg)
1. Miskin 480 320 2. Miskin Sekali 360 240 3. Paling Miskin 270 180
Sumber : Dikutip oleh Rusli, dkk. (1995)
Menurut Soemardjan (1993), sebuah keluarga dikatakan miskin apabila
tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Hal tersebut tampak
dari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar
spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Untuk itulah adanya Indikator
Keluarga Sejahtera yang pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan
kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai
dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan diri dari keluarga.
Ukuran taraf pemenuhan kebutuhan tersebut dibagi dalam tiga kelompok dan
masing-masing kelompok dibagi dalam variabel yang masing-masing ditetapkan
rincian variabel sebagai kumpulan dari indikator keluarga sejahtera yaitu sebagai
berikut:
1. Kebutuhan Dasar atau (Basic Needs), yang terdiri dari variabel: pangan,
sandang, papan, dan kesehatan.
2. Kebutuhan Sosial Psikologis (Social Psychological Needs), yang terdiri dari
variabel: pendidikan, rekreasi, transportasi, dan interaksi sosial internal dan
eksternal
11
3. Kebutuhan Pengembangan (Developmnet Needs), yang terdiri dari variabel:
tabungan, pendidikan khusus/kejuruan, dan akses terhadap informasi.
Atas dasar pemenuhan kebutuhan keluarga yang digunakan, maka
keluarga-keluarga di Indonesia dapat diketegorikan dalam lima tahap, yaitu
Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera
II (KS II) Keluarga Sejahtera III (KS III) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III +).
Merujuk pada pendapat Soemardjan (1993), keluarga yang dikatakan miskin
adalah Keluarga Pra Sejahtera, yakni keluarga yang belum memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal. Hal tersebut tampak dari ketidakmampuan mereka
dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar spiritual, pangan, sandang, papan,
dan kesehatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam
sehari.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda pada saat di rumah,
bekerja, sekolah dan bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB, maka dibawa ke
sarana kesehatan.
Selain pengertian kemiskinan di atas, pengertian dan kriteria kemiskinan
yang lebih baru dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga
pemerintahan. Pengertian dan kriteria kemiskinan yang dikeluarkan oleh lembaga-
lembaga pemerintah sangat beragam seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.
12
Tabel 2. Ukuran dan Kriteria Kemiskinan Menurut Beberapa Lembaga Pemerintahan, Bogor, 2008.
Lembaga Ukuran/kriteria kemiskinan
Bappenas (2005)
Kemiskinan mencakup unsur-unsur : (1) ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, transportasi dan sanitasi) (2) kerentanan (3) ketidakberdayaan (4) ketidakmampuan menyalurkan aspirasi.
KPK (2003) Secara umum masyarakat miskin ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakmampuan, antara lain: (1) tidak mempunyai daya/kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan
dan kesehatan (basic need deprivation) (2) tidak mempunyai daya/kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha
produktif. (3) tidak mempunyai daya/kemampuan untuk menjangkau akses
sumberdaya sosial dan ekonomi (innaccessibility) (4) tidak mempunyai daya/kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri,
senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (vurnerability)
(5) tidak mempunyai daya/kemampuan untuk membebaskan diri dari budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.
BPS (2006) 14 kriteria rumah tangga miskin, yaitu: (1) luas lantai bangunan tempat tinggal yang dimanfaatkan untuk aktivitas
sehari-hari. (2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas terbuat dari
tanah/bambu/kayu yang berkualitas rendah. (3) Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas terbuat dari
tanah/bambu/kayu yang berkualitas rendah. (4) Fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus) digunakan secara
bersama-sama/untuk umum. (5) Sumber air minum adalah mata air yang tidak terlindungi/sungai/air
hujan. (6) Sumber penerangan utama bukan listrik. (7) Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari dari kayu/arang/minyak
tanah. (8) Jarang/tidak pernah membeli daging/ayam/susu setiap minggunya. (9) Anggota rumah tangga hanya mampu menyediakan makan dua kali
dalam sehari. (10) Tidak mampu membeli pakaian baru minimal satu stel dalam setahun. (11) Bila jatuh sakit tidak berobat karena tidak ada yang biasa berobat. (12) Pekerjaan utama kepala keluarga sebagai buruh kasar/tidak bekerja. (13) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga maksimal SD. (14) Ada tidaknya barang dalam keluarga yang dapat dijual dengan nilai Rp
500.000 Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2008)
Selain dari lembaga pemerintahan, lembaga pengelola zakat Dompet
Dhuafa Republika melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (MM)
juga memiliki kriteria tersendiri untuk mengukur kemiskinan yang kemudian
13
dijadikan standar kelayakan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan
dana zakat. Karakteristik masyarakat miskin (dhuafa) yang dilihat berdasarkan
program MM terdiri dari tiga indikator, yaitu: 1) karakteristik bangunan rumah, 2)
kepemilikan aset pribadi dan 3) penghasilan usaha pokok (laba usaha). Dari ketiga
indikator tersebut ditentukan kelayakan menjadi mitra, apabila minimal dua dari
tiga indikator tersebut dinyatakan layak, maka masyarakat yang mengajukan
bantuan layak menjadi mitra. Berikut ini adalah ketiga indikator tersebut:
1. Indikator Karakteristik Bangunan Rumah
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa karakteristik bangunan rumah terdiri
dari ukuran rumah yang terdiri dari sangat kecil (<4m2), kecil (4-6m2), sedang (6-
8m2), dan besar (8m2); jenis dinding yang terbuat dari bilik bambu/kayu, semi,
dan tembok/beton; jenis lantai terdiri dari tanah, panggung, semen, dan keramik;
jenis atap terdiri kirai/ijuk, genteng/seng, dan asbes/berglazur; kepemilikan
rumah, terdiri dari rumah menumpang, kontrak, milik keluarga, dan sendiri; dapur
(alat masak) terdiri dari tungku, kompor minyak, kompor gas/listrik; dan jenis
kursi yang terdiri dari lesehan, balai bambu, kayu, dan sofa.
Warga yang dianggap miskin dan dikatakan layak menjadi mitra adalah
yang memiliki indikator karakteristik bangunan rumah dengan indeks rumah dua
teratas (berdasarkan Tabel 3), artinya yang memiliki ukuran minimal dari sebuah
bangunan/rumah.
14
Tabel 3. Indikator Karakteristik Bangunan Rumah (Indikator Masyarakat Mandiri), Jakarta, 2008.
KARAKTERISTIK
BANGUNAN RUMAH Indeks Rumah
KARAKTERISTIK BANGUNAN RUMAH
Indeks Rumah
Ukuran Rumah
Sangat kecil (<4m2)
Kepemilikan Rumah Menumpang
Kecil (4-6m2) Kontrak Sedang (6-8m2) Keluarga Besar (8m2) Sendiri
Dinding Bilik bambu/kayu Dapur Tungku
Semi Kompor Minyak
Tembok/beton Kompor Gas/Listrik
Lantai Tanah Kursi Lesehan Panggung Balai Bambu Semen Kayu Keramik Sofa Atap Kirai/Ijuk Genteng/Seng Asbes/Berglazur
Sumber : Laporan Perkembangan Program Urban Msyarakat Mandiri (2008)
2. Kepemilikan aset pribadi terdiri dari: kepemilikan kebun/sawah, elektronik,
kendaraan, ternak, dan simpanan.
Tabel 4 menunjukkan bahwa kepemilikan aset pribadi merupakan aset
harta yang dimiliki warga, yaitu terdiri dari kepemilikan kebun/sawah, barang-
barang elektronik, kendaraan, ternak, simpanan serta aset produkstif yang dapat
dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan. Seperti halnya dengan indikator
karakteristik bangunan rumah, warga yang dianggap miskin adalah yang memiliki
indikator kepemilikan aset pribadi dua teratas (berdasarkan Tabel 4) yang
merupakan kepemilikan aset pribadi minimal.
15
Tabel 4. Indikator Kepemilikan Aset Pribadi (Indikator Masyarakat Mandiri), Jakarta, 2008.
KEPEMILIKAN ASET PRIBADI KEPEMILIKAN ASET PRIBADI
Kebun/Sawah Tidak Ada Ternak Unggas (.....ekor)
<1000m2 Kambing/Domba (.....ekor)
1000-5000m2 Sapi/Kerbau (.....ekor) >5000m2 Simpanan Ada (Rp...................) Tidak Ada Elektronik Radio Tape ASET PRODUKTIF
Televisi Sebutkan Jenisnya: 1.
CD Player 2. 3.
Kendaraan Tidak Ada Penggunaan: Bertambahnya aset produktif
Sepeda Investasi usaha lain
Sepeda Motor Investasi usaha turunan
Mobil Lainnya.................... Sumber: Laporan Perkembangan Program Urban Msyarakat Mandiri (2008)
3. Pendapatan adalah besarnya penghasilan yang didapatkan perhari.
Warga yang dikatakan miskin adalah yang memiliki penghasilan pokok
usaha/keuntungan dibawah Rp 30.000 perhari, standar ini merupakan kriteria
pendapatan yang digunakan MM untuk warga miskin perkotaan yang akan
menjadi mitranya. Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan
MM dalam menentukan kriteria kemiskinan sekaligus menentukan kelayakan
warga untuk menjadi mitra.
2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
Secara garis besar, penyebab terjadinya kemiskinan di suatu wilayah
disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor alamiah dan faktor non alamiah. Faktor
alamiah bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan
yang kurang memadai, dan adanya bencana alam. Faktor non alamiah disebabkan
16
oleh faktor kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak
stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain (Tarumingkeng,
2001).
Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Tansey dan Ziegley dalam
Suharto, dkk (2003), faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan terdiri dari
faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam keluarga, seperti:
(1) tingkat karakteristik usaha, termasuk di dalamnya sumberdaya manusia, jenis
usaha yang dilakukan, sumber modal dan pemasaran, (2) tingkat motivasi,
terutama berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan
keterampilan berusaha, (3) tingkat dukungan anggota keluarga, (4) pola produksi
dan konsumsi keluarga. Faktor eksternal merupakan unsur-unsur penyebab yang
berasal dari luar yang mempengaruhi keberdayaan keluarga miskin, yang
meliputi: (1) perbedaan peluang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, (2)
sempitnya mendapatkan peluang pekerjaan, (3) perbedaan aksesibilitas terhadap
sumberdaya.
2.1.4. Upaya-upaya Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah yang harus dientaskan oleh semua pihak,
terutama pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan
pemerintah sangat beragam. Pada awal April tahun 2001 telah muncul Badan
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK), yang menunjukkan parahnya
kondisi kemiskinan dan seriusnya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
Tugas utama dari BKPK adalah mengkoordinasikan program-program
penangulangan kemiskinan secara efektif dan terpadu dengan empat peran utama,
yaitu sebagai koordinator, katalisator, mediator dan fasilitator. Sebagai
17
koordinator, BKPK bertugas mengkoordinasikan perumusan standar-standar dasar
mengenai konsep kemiskinan yang digunakan oleh berbagai instansi di pusat dan
daerah. Sebagai katalisator, BKPK berupaya memecahkam kendala-kendala
utama dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan
kemiskinan. Sebagai mediator, badan ini diharapkan menjadi wahana unutk
menampung beragam aspirasi. Sedangkan sebagai fasilitator, BKPK mampu
menjadi penghubung antara para donor dengan pelaku utama (SMERU, 2000).
Selain itu, beberapa program telah dilaksanakan melalui Instruksi Presiden
(Inpres) diantaranya (Tarumingkeng, 2001) adalah:
1. Inpres Kelurahan Tertinggal (IDT), dengan tujuan menciptakan kesetaraan
Kelurahan dan menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Inpres Kesehatan, dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang
mudah dan murah untuk penduduk peKelurahanan.
3. Inpres Pendidikan, dengan tujuan memberikan layanan pendidikan yang gratis
untuk pendidikan dasar smpai menengah.
4. Inpres Obat-obatan, dengan tujuan memberikan obat-obatan yang murah
kepada masyarakat miskin.
Di samping Inpres, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan
yang tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk
Kelurahan melalui:
1. Ketentuan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk memudahkan petani mendapatkan
modal.
18
2. Ketentuan mengenai kredit perbankan (Kredit Candak Kulak) untuk
memberikan kemudahan kepada rakyat dalam mendapatkan modal di luar
sektor pertanian.
3. Pembebasan pajak untuk hasil pertanian.
4. Subsidi atas pupuk dan obat-obatan pertanian.
5. Operasi beras murah dan beberapa program lainnya.
2.2. Zakat
2.2.1. Pengertian dan Golongan Penerima Zakat
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat menurut Majma (dalam Bariadi,
2003) mempunyai beberapa pengertian, yaitu al-barakatu atau keberkahan, an-
namaa’, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu, yaitu kesucian,
dan ash-shalahu, yaitu keberesan. Secara istilah, meskipun para ulama
mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang
lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian
dari harta dengan prasyarat tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada
pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.
Menurut Abdurrahim dalam Inayah (2005), secara istilah zakat adalah
sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan
berbagai syarat. Sedangkan menurut Hukum Islam (Syara’), zakat adalah nama
bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat
tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan firman Allah
SWT dalam QS. At-Taubah:60 bahwa zakat diberikan kepada delapan ashnaf
(golongan), yaitu golongan fakir, miskin, amil (pengumpul/pengelola) zakat,
19
muallaf (orang yang baru masuk Islam), riqab, gharimiin (orang yang memiliki
hutang), sabilillaah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan ibnu sabil (orang
yang sedang dalam perjalanan). Namun kaitannya dalam penelitian ini yaitu
dengan upaya pengentasan kemiskinan, golongan yang dikaji hanya terbatas pada
golongan fakir dan miskin.
Menurut Taqyuddin dalam Bariadi, dkk (2003), fakir adalah golongan
yang memiliki harta namum kebutuhan hidupnya lebih banyak dibandingkan harta
yang mereka miliki, atau orang-orang yang sehat dan jujur, tetapi tidak memiliki
pekerjaan, sehingga tidak memiliki penghasilan. Miskin adalah golongan orang
yang memiliki pekerjaan (mempunyai harta) untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya namun tidak memenuhi standar. Selaras dengan pendapat tersebut,
Afzalurrahman (dalam Bariadi, dkk, 2003) mengemukakan fakir adalah orang
yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi
penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari
kebutuhannya. Miskin adalah orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) karena
telah lanjut usia, sakit, atau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja
maupun tidak, tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk
menjamin kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya.
2.2.2. Peran dan Hikmah Zakat
Qardhawi (1991) membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu tujuan untuk
kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan
pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka
berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak yang baik, mengobati hati dari
20
cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan
rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua
tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia
dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia
melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat matrealisme dalam diri
manusia. Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara
luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem
jaminan sosial dalam Islam.
Tujuan dari hikmah lain dari zakat dikemukakan oleh Hafiduddin (2002),
yaitu:
1. Merupakan perwujudan ketundukan, ketaatan dan rasa syukur atas karunia
Tuhan (QS. At-Taubah:103; Ar-Rum:39; dan Ibrahim:7).
2. Zakat merupakan hak mustahik (orang yang menerima zakat) yang berfungsi
untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang
lebih baik dan lebih sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
dengan layak dan dapat beribadah kepada-Nya.
3. Merupakan pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan
hidupnya dengan para orang yang membutuhkan.
4. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus
dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial
maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya
manusia.
21
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah
membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak
orang lain atas harta yang dimiliki.
6. Merupakan salah satu instrumen/sarana bagi pembangunan kesejahteraan
umat, pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.
7. Mendorong umat untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk
dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya serta dapat
berzakat/berinfak.
2.2.3. Lembaga Pengelola Zakat
Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki
kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan (Qadir, 1998), yaitu:
1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan
langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan
pemerintahan yang Islami.
Masyarakat Mandiri (MM) adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak
dalam pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan, yang
merupakan salah satu program dari Dompet Dhuafa Republika yang didirikan
pada tahun 2000. Sejak bulan Juli 2005, MM resmi menjadi lembaga otonom
dengan memperkuat visi dan misi sebagai wahana pemberdayaan berbagai
22
komunitas dhuafa atau yang terpinggirkan, sehingga mereka mencapai
kemandirian. Program pemberdayaan MM menjangkau komunitas perdesanaan,
perkotaan, wilayah pasca bencana, serta komunitas berdasar tingkat ekonomi.
Untuk wilayah perdesaan, MM menjangkau beberapa Kelurahan di wilayah
Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang, Tasikmalaya dan Garut. Komunitas
perkotaan yang sudah dijangkau di wilayah Cilandak Jakarta Selatan dan Ciputat
Tangerang. Poso adalah pilihan komunitas dampingan untuk wilayah pasca
konflik (Kurniawan, 2007).
Tujuan program MM adalah tercapainya kemandirian material komunitas
sasaran dengan tercapainya kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan
hidup dasar (basic needs), serta cadangan dan mekanisme untuk bertahan dalam
kondisi krisis, tercapainya kemandirian intelektual komunitas sasaran
(terbentuknya kemandirian berpikir, bersikap serta berkesadaran kritis),
tercapainya kemandirian manajemen komunitas sasaran, yaitu kemampuan
komunitas dalam mengelola aksi kolektif untuk mewujudkan kelembagaan lokal
yang berkelanjutan, sehingga mampu menjalin kemitraan yang setara lintas pelaku
(stakeholders).
Kegiatan yang ada pada MM meliputi pembinaan usaha mikro berbasis
kelompok, dengan aturan disiplin pinjaman dan disiplin kelompok, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, yang dilakukan dengan berbagai pelatihan
ketrampilan, pengembangan kelembagaan komunitas, meliputi mekanisme
organisasi, kepengurusan dan administrasi, pemupukan modal swadaya.
Pembinaan juga dilakukan dengan membangun sistem tabungan, dana bergulir
serta menghubungkan lembaga komunitas dengan lembaga keuangan,
23
pembangunan jaringan dan sinergi, dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga
keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakar (LSM), Perseroan Terbatas (PT),
Asosiasi Profesi, serta pengembangan informasi dan teknologi tepat guna.
2.3. Pemberdayaan Masyarakat
2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu
empowerment. Empowerment berasal dari kata power yang berarti kemampuan
untuk berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal dari
bahasa latin dan yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat
berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya
pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.
(Badudu dan Zein, 2001).
Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan
bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang
sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat
diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya,
dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan
mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan (Syafei dalam Inayah
2005). Selain itu, pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan
kondisi hingga semua orang (yang lemah) dapat menyumbang kemampuannya
secara maksimal untuk mencapai tujuannya.
24
2.3.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Menurut Halim (dalam Inayah, 2005), dalam membangun kekuatan
perekonomian masyarakat, perlu diperhatikan hak, nilai dan keyakinan, antara lain
yaitu:
1. Hak menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan
mereka. Hak ini, muncul karena adanya keyakinan bahwa masyarakat
memiliki realibilitas (kemampuan) memecahkan masalahnya sendiri dalam
ekonomi.
2. Masyarakat mempunyai hak untuk berusaha menciptakan lingkungan dan
menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar. Penciptaan lingkungan
sesuai keinginan tetap didasari ketenangan dan ketenteraman, mengingat
dalam diri masyarakat telah terjadi interaksi sosial aktif dan adaptif. Proses
pembelajaran itu selalu lahir dari proses interaksi sosial.
3. Masyarakat harus diyakini mampu bekerjasama rasional dalam bertindak
untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitasnya, serta bertindak
dalam menggapai tujuannya secara bersama. Hal itu menjadi penting dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan karakteristik
komunitas masyarakat pada umumnya, sebagai pengusaha, terutama dalam
kaitannya dengan penentuan dan distribusi bantuan modal usaha.
Menurut Suryana (2003) penanggulangan kemiskinan pada tingkat rumah
tangga dapat berpusat pada:
1. Peningkatan produktivitas usaha (lahan dan teknologi).
2. Peningkatan akses terhadap pelayanan kapital.
3. Peningkatan sumberdaya tenaga kerja.
25
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemberdayaan keluarga merupakan bagian upaya strategi pada program
pengembangan masyarakat, karena tidak saja mengandung nilai partisipasi, tetapi
juga memperlihatkan kebijakan pembangunan yang pro masyarakat miskin.
Menurut Darwanto (2004), diperlukan strategi dasar dalam memberdayakan
masyarakat lokal (termasuk di dalamnya unit sosial keluarga) yang ditujukan pada
(1) pola kerja yang fleksibel, yang tidak terhambat oleh sistem administrasi
penganggaran yang ketat, (2) pemberian peluang, (3) pengembangan kapasistas,
dan modal manusia, dan (4) perlindungan.
Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat berarti upaya meningkatkan
pendapatan kelompok-kelompok masyarakat melalui usaha pembangunan
ekonomi lokal. Menurut Syaukat dan Sutara (2004), upaya pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development), fokus utama pengembangan ekonomi
lokal ditujukan untuk: (1) peningkatan daya saing (competitiveness), (2)
penciptaan kesempatan (lapangan) kerja bagi masyarakat (job creation), (3)
pengembangan aspek pemerataan (equity), (4) mencakup berbagai disiplin:
perencanaan dan manajemen, ekonomi dan pemasaran.
2.4. Kerangka Pemikiran
Program Urban Masyarakat Mandiri diperuntukan bagi masyarakat/rumah
tangga dhuafa/miskin yang mau untuk memberdayakan diri mereka sendiri
dengan berbagai program yang tersedia. Salah satu daerah binaan adalah
Kelurahan Bidaracina. Pada Kelurahan Bidaracina terdapat rumah tangga miskin
yang harus mendapatkan bantuan secara ekonomi. Untuk melihat gejala
26
kemiskinan yang ada pada rumah tangga tersebut, digunakan karakteristik rumah
tangga miskin menurut MM dan batas garis kemiskinan Sajogjo (dalam Rusli,
dkk, 1995) sebagai pembahasan pelengkap. Munculnya rumah tangga miskin
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri sendiri
(internal), maupun faktor yang berasal dari lingkungan (eksternal).
Selanjutnya dilihat dan dianalisis sejauh mana dana zakat yang diberikan
kepada rumah tangga miskin dapat mempengaruhi tingkat keberdayaan dan
tingkat kemiskinan. Tingkat keberdayaan dapat dilihat dengan menganalisis
bagaimana rumah tangga miskin menggunakan dana bantuan tersebut, yaitu
dengan melihat pengalokasian dana bantuan zakat tersebut, apakah digunakan
untuk kegiatan produktif untuk jangka waktu yang panjang seperti pendidikan,
investasi, tabungan, wirausaha, atau digunakan untuk kegiatan yang hanya bersifat
konsumtif, sedangkan tingkat kemiskinan dianalisis dengan melihat perubahan
pendapatan sebelum mendapatkan bantuan zakat dengan setelah menerima
bantuan.
Rumah tangga yang dikatakan berdaya adalah rumah tangga yang
mengalokasikan dana pinjamannya untuk kebutuhan ekonomi produktif seperti
kebutuhan usaha, tabungan dan investasi, serta kebutuhan investasi sumberdaya
manusia seperti untuk alokasi dana pendidikan dan kesehatan keluarga.
Sedangkan rumah tangga yang dikatakan tidak berdaya apabila dana pinjamannya
digunakan untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga, sedangkan rumah tangga
yang dikatakan mampu mengentaskan kemiskinan keluarganya adalah rumah
tangga yang dapat meningkatkan pendapatannya setelah mendapatkan pinjaman.
Kerangka pemikiran tersebut terangkum dalam Gambar 1.
27
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Konseptual
Keterangan:
: Mempengaruhi
: Menghasilkan
: Terdiri atas
Karakteristik Rumah Tangga (RT) Miskin sebelum mendapatkan bantuan
Faktor-faktor yang Menyebabkan Kemiskinan
Internal : - Tingkat Karakteristik
Usaha - Tingkat Motivasi - Tingkat Dukungan
Anggota Keluarga - Pola Produksi dan
Konsumsi Keluarga Eksternal : - Sumberdaya alam - Sosial Budaya
Non-produktif: - Konsumsi
rumah tangga
Pendayagunaan
Ekonomi Produktif:
- Investasi - Tabungan - Wirausaha
Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (MM)
Karakteristik Rumah Tangga (RT) Miskin setelah
mendapatkan bantuan
Pengentasan Kemiskinan
Investasi SDM: - Pendidikan - Kesehatan
Keberdayaaan RT
28
2.5. Hipotesis Pengarah
2.5.1. Hipotesis Umum
Hipotesis umum dari penelitian ini adalah zakat berpengaruh positif
terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.
2.5.2. Hipotesis Khusus
1. Karakteristik Rumah Tangga Miskin terdiri dari karakteristik bangunan
rumah, kepemilikan aset pribadi, dan pendapatan.
2. Faktor-faktor menyebabkan kemiskinan adalah faktor internal dan eksternal.
3. Pendayagunaan zakat berpengaruh positif terhadap keberdayan rumah tangga
miskin.
2. Pendayagunaan zakat berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan
rumah tangga miskin
2.6. Definisi Operasional
1. Muzakki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat.
2. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
3. Masyarakat Mandiri (MM) adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak
dalam pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan.
4. Zakat adalah sejumlah harta tertentu harus yang diberikan seseorang kepada
orang-orang yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat.
4. Karakteristik Rumah Tangga Miskin Penerima Pinjaman dicirikan dengan
tinggal di kontrakan/menumpang, rumah dengan ukuran bangunan rumah
29
sangat kecil (<4m2) atau kecil (4-6m2), dinding rumah terbuat dari
bilik/kayu/semi, lantai terbuat dari tanah dan panggung/kayu, atap terbuat dari
kirai/ijuk/genteng/seng, alat masak dari tungku/kompor minyak, kursi
bambu/kayu/tidak memiliki keduanya; tidak memiliki aset pribadi
(kebun/sawah, barang elektornik, kendaraan dan ternak) serta aset produktif
(simpanan atau tabungan); serta penghasilan usaha pokok/keuntungannya
dibawah Rp 30.000.
3. Penerimaan adalah jumlah pemasukan uang yang didapatkan baik dari hasil
usaha maupun non usaha.
4. Hasil usaha adalah jumlah uang yang didapatkan dari kegiatan ekonomi yang
modalnya mendapatkan bantuan dari MM.
5. Hasil non usaha adalah jumlah uang yang didapatkan selain dari kegiatan
ekonomi yang modalnya mendapatkan bantuan dari MM, seperti gaji.
6. Pengeluaran adalah jumlah uang yang digunakan untuk membiayai aktivitas
sehari-hari baik untuk usaha maupun non usaha.
7. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dikurangi pengeluaran.
8. Pendayagunaan adalah penggunaan pendapatan untuk berbagai kebutuhan
sehari-hari baik kebutuhan rumah tangga maupun usaha.
9. Rumah Tangga Miskin yang berdaya adalah rumah tangga yang
mendayagunakan dana pinjamannya untuk kebutuhan ekonomi produktif
(usaha, tabungan dan simpanan) serta untuk kebutuhan investasi sumberdaya
manusia (pendidikan dan kesehatan).
30
10. Faktor kemiskinan internal adalah faktor yang mempengaruhi kemiskinan dari
dalam rumah tangga itu sendiri, seperti karakteristik kepala RT, ukuran besar
RT, aset yang dimiliki RT, jumlah anggota RT usia produktif.
11. Faktor kemiskinan eksternal adalah faktor yang mempengaruhi kemiskinan
pada tingkat yang lebih makro seperti kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi,
kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam,
sosial budaya dan lain-lain.
12. Omset Usaha adalah jumlah pemasukan uang yang didapatkan dari penjualan
hasil usaha.
13. Modal usaha adalah sejumlah materi yang digunakan untuk memulai usaha
per satuan waktu (perhari/perminggu)
14. Laba adalah selisih antara Omset usaha dan modal usaha.
31
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Strategi Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif
deskriptif dengan menggunakan teknik survei yang dikombinasikan dengan
metode kualitatif. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data dari
sejumlah responden rumah tangga miskin penerima zakat dengan instrumen
kuesioner. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari para
informan terpilih dengan instrumen panduan pertanyaan. Unit anaslisis dari
penelitian ini adalah tingkat rumah tangga. Penelitian ini menggunakan strategi
kasus, yaitu dengan memilih sebuah lokasi/daerah untuk melihat gejala kasus
pengaruh pendayagunaan zakat terhadap keberdayaan dan pengentasan
kemiskinan bagi rumah tangga miskin yang ada pada daerah tertentu yang sesuai
dengan masalah yang akan dianalisis.
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bidaracina, Jakarta Timur.
Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) karena lokasi tersebut
merupakan salah satu Kelurahan binaan dari Masyarakat Mandiri. Di Kelurahan
tersebut terdapat program pemberian modal kepada pedagang mie ayam, bakso
dan sayur-sayuran. Sedangkan proses penelitiannya berlangsung selama empat
bulan, yaitu dari Mei hingga Agustus 2008 (Lampiran 2).
32
3.3. Penentuan Responden dan Informan
Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja
(purposive), yaitu rumah tangga yang menjadi peserta program MM. Jumlah
rumah tangga yang mendapatkan bantuan MM adalah sebanyak 39, rumah tangga
yang menjadi responden, yaitu sebanyak 20 rumah tangga yang terdiri dari
penjual mie ayam, bakso, bubur, rujak, jajanan anak-anak. Rumah tangga yang
dijadikan responden dipilih secara sengaja, berdasarkan keaktifan selama proses
pendampingan, sedangkan informan adalah orang yang mengetahui program
tersebut, seperti pendamping MM, tokoh masyarakat Bidaracina.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner dan
wawancara mendalam kepada responden dan informan. Data sekunder diperoleh
dari studi literatur yang dilakukan peneliti, baik pada saat sebelum maupun setelah
pangambilan data di lapangan, serta data sekunder yang berasal dari arsip MM
dan Kelurahan Bidaracina.
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data kuantitatif yang diperoleh dari lapangan diolah dengan menggunakan
tabel frekuensi yang digunakan untuk menganalisis karakteristik rumah tangga
miskin, faktor-faktor yang mempengaruhi, tingkat pendapatan dan tingkat
kemiskinan. Untuk data kualitatif disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara
33
yang dilengkapi dengan matriks analisis data yang akan mempermudah pembaca
dalam melihat dan membaca hasil dari penelitian ini.
Peneliti menggunakan indikator pendapatan dalam melihat pengaruh
pendayagunaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut
dilakukan karena indikator pendapatan merupakan indikator kuantitatif yang
mudah diukur terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Dari tingkat
pendapatan dapat dilihat apakah suatu program dapat menyejahterakan
masyarakat dengan meningkatkan pendapatannya atau sebaliknya.
Dalam memberikan bantuannya, MM menggunakan tiga
karakteristik/indikator, yaitu karakteristik bangunan rumah, kepemilikan aset
pribadi/produktif dan karaktersitik penghasilan usaha pokok (laba usaha).
Karakteristik bangunan rumah dan kepemilikan aset pribadi/produktif diolah
dengan menghitung jumlah responden yang memilikinya, yang kemudian
disajikan dengan tabel. Pendapatan responden, maka terlebih dahulu peneliti harus
mengetahui besarnya omset usaha (A); pengeluaran usaha (B); laba usaha (C)
diperoleh dari selisih antara omset usaha dan pengeluaran usaha (A-B); dan
penerimaan keluarga (D); dan pengeluaran keluarga (E). Pendapatan keluarga (F)
diperoleh dari selisih antara penerimaan keluarga dan pengeluaran keluarga (D-E).
34
BAB IV
GAMBARAN UMUM KELURAHAN BIDARACINA
4.1. Sejarah
Bidaracina dewasa ini menjadi nama sebuah kelurahan, kelurahan
Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur. Menurut beberapa
informasi, kawasan tersebut dikenal dengan nama Bidaracina, karena pada waktu
terjadi pemberontakan orang-orang Cina di Batavia dan sekitarnya terhadap
Kompeni pada tahun 1740, dan dari mereka terbunuh mati, bermandi darah. Di
antaranya di tempat yang kemudian disebut Bidaracina itu.
Perkiraan lainnya, asal nama kawasan tersebut dari bidara yang ditanam
oleh orang Cina di situ. Bidara, atau bahasa ilmiahnya Zizyphus jujube Lam,
famili Rhanneae, adalah pohon yang kayunya cukup baik untuk bahan bangunan,
akar dan kulitnya yang rasanya pahit, mengandung obat penyembuh beberapa
macam penyakit, termasuk sesak nafas. Di ketiak dahannya biasa timbul
gumpalan getah. Buahnya dapat dimakan (Fillet 1888:52) Ada kaitannya dengan
perkiraan tersebut, yaitu keterangan tentang adanya seorang Cina yang mengikat
kontrak yang aktanya dibuat oleh Notaris Reguleth tertanggal 9 Oktober 1684,
untuk menanami kawasan sekitar benteng NoorDw (35 tahun) dengan pohon
buah-buahan, termasuk pohon Bidara (De Haan 1911, (11):613). Walaupun di luar
kontrak tersebut, mungkin saja seorang Cina menanam bidara di tempat yang kini
dikenal dengan sebutan Bidaracina itu (http://www.budayajakarta)
35
4.2. Kondisi Geografis
Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1251 tahun 1986
tentang pemecahan, penggabungan dan perubahan batas-batas kelurahan, serta
pembentukan Kelurahan baru di wilayah Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur
ditetapkan luas wilayah Kelurahan Bidaracina seluas 126,10 ha. Dengan batas-
batas sebagai berikut:
1. Utara : Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Balimester
2. Selatan : Kelurahan Cawang dan Jalan MT. Haryono
3. Barat : Kali Ciliwung dan Kelurahan Kebon Baru
4. Timur : Kali Baru dan Kelurahan Cipinang Cempedak
4.3. Kondisi Kependudukan
4.3.1. Jumlah Penduduk
Kelurahan Bidaracina merupakan kelurahan dengan luas wilayah dan
jumlah penduduk yang cukup besar. Kelurahan Bidaracina terdiri dari 16 Rukun
Warga (RW), yang kemudian dibagi ke dalam 188 Rukun Tetangga (188) dengan
jumlah penduduk sebesar 43.175 jiwa dengan perbandingan penduduk Laki-laki
dan Perempuan yang relatif seimbang (Tabel 5).
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Bidaracina Berdasarkan Jenis Kelamin, Mei 2008.
Kategori Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Penduduk 22.967 20.203 43.170 Jumlah Kepala Keluarga 8.095 2.698 10.793
Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 2008.
36
4.3.2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa mata pencaharian yang paling
dominan di Kelurahan Bidaracina adalah sebagai Karyawan
Swasta/Pemerintah/ABRI yakni sebanyak 11.224 jiwa, sedangkan di posisi kedua
adalah sebagai pedagang sebanyak 7.771 jiwa, kemudian disusul pertukangan
sebanyak 6.476 jiwa, pensiunan 4.317 jiwa, kemudian terdapat juga golongan
masyarakat yang tidak bekerja (pengangguran) sebanyak 5.180 jiwa, fakir miskin
sebanyak 1.295 jiwa dan sebanyak 6.907 jiwa lainnya yang mata pencahariannya
tidak jelas (serabutan).
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kelurahan Bidaracina Berdasarkan Mata Pencaharian, Mei 2008.
No. Pekerjaan Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan Jiwa %
1. Karyawan Swasta/Pemerintah/ABRI 5.971 5.253 11.224 26
2. Pedagang 4.134 3.637 7.771 18 3. Pensiunan 2.297 2.020 4.317 10 4. Pertukangan 3.445 3.030 6.476 15
5. Pengangguran 2.756 2.424 5.180 12 6. Fakir Miskin 689 606 1.295 3 7. Lain-lain 3.675 3.232 6.907 16
Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 2008.
4.3.3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikannya, hingga Mei 2008 mayoritas penduduk
berpendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Berdasarkan
Tabel 7 diketahui bahwa sebanyak 12.951 jiwa tamat SLTP, kemudian diikuti
oleh penduduk yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA) sebanyak
12.519 jiwa, tamat Sekolah Dasar (SD) 8.634 jiwa, tamat Perguruan Tinggi (PT)
37
sebanyak 6.043 jiwa, tidak tamat SD sebanyak 2.590, dan sebanyak 432 yang
tidak mengenyam bangku sekolah.
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kelurahan Bidaracina Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Mei 2008
No. Jenjang Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan Jiwa %
1. Tidak Sekolah 230 202 432 1 2. Tidak Tamat SD 1.378 1.212 2.590 6 3. Tamat SD 4.593 4.041 8.634 20 4. Tamat SLTP 6.890 6.061 12.951 30 5. Tamat SLTA 6.660 5.859 12.519 29 6. Tamat PT 3.215 2.828 6.043 14
Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 2008.
4.3.4. Penduduk Menurut Agama
Berdasarkan Tabel 8, mayoritas penduduk Kelurahan Bidaracina adalah
muslim sebanyak 41.423 jiwa, Kristen Katolik sebanyak 1.577 jiwa, kemudian
Kristen Protestan sebanyak 105 jiwa dan sisanya beragama Hindu dan Budha
yaitu sebanyak 592 jiwa.
Tabel 8. Jumlah Penduduk Kelurahan Bidaracina Berdasarkan Agama, Mei 2008.
No. Agama Jumlah Jiwa %
1. Islam 41.423 94,80 2. Kristen Protestan 105 0,24 3. Kristen Katolik 1.577 3,61 4. Hindu dan Budha 592 1,35
Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 2008.
4.4. Sarana dan Prasarana
4.4.1. Kesehatan
Sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Bidaracina tergolong cukup
baik. Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa dari 39 jumlah sarana kesehatan yang
38
tersedia, 20 diantaranya berupa posyandu, 6 buah balai posyandu, 5 buah apotik, 4
buah poliklinik, 3 buah puskesmas, dan sebuah rumah sakit.
Tabel 9. Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Bidaracina, Mei 2008.
No. Sarana Kesehatan Jumlah 1. Rumah Sakit 1 2. Puskesmas 3 3. Poliklinik 4 4. Apotik 5 5. Posyandu 20 6. Balai Posyandu 6
Jumlah 39 Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, 2008. Posyandu tersebar di seluruh RW dan RT, sedangkan balai posyandu
hanya berada pada lokasi-lokasi tertentu. Fungsi dari balai posyandu adalah
sebagai pusat kegiatan dari kegiatan posyandu, tempat para bidan untuk
berkoordinasi, dan tempat pemyimpanan obat-obatan, sarana kesehatan lainnya
tersedia menyebar di beberapa titik sehingga untuk mengaksesnya penduduk
Bidaracina tidak terlalu mengalami kesulitan.
4.4.2. Pendidikan
Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang ada di
Kelurahan Bidaracina cukup banyak dan memadai. Dari 27 jumlah sekolah, 10
diantaranya adalah berupa Sekolah Dasar (SD), 8 buah Taman Kanak-kanak (TK),
5 buah Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP), 1 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta 2 buah Perguruan
Tinggi (PT).
39
Tabel 10. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelurahan Bidaracina, Mei 2008
No. Tingkat Jumlah Gedung Sekolah
1. TK 8 8 2. SD 10 10 3. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 5 5 4. SLTP 1 1 5. SLTA 1 1 6. Perguruan Tinggi 2 2
Jumlah 27 27 Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, 2008. 4.4.3. Fasilitas Peribadatan
Jumlah sarana peribadatan sesuai dengan jumlah pemeluk agama,
mayoritas penduduk beragama Islam, maka fasilitas peribadahannyapun paling
banyak. Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa dari 88 sarana peribadahan, 83
diantaranya adalah sarana peribadahan umat Islam, yang terdiri dari 12 buah
masjid, 31 buah musholla, dan 40 buah majlis ta’lim yang tersebar di seluruh RW
dan RT, 5 diantaranya adalah sarana peribadahan umat Nasrani yaitu berupa
gereja, sedangkan kuil/vihara tidak dijumpai di Kelurahan Bidaracina.
Tabel 11. Sarana dan Prasarana Peribadahan Kelurahan Bidaracina, Mei 2008
No. Fasilitas Peribadahan Jumlah 1. Masjid 12 2. Musholla 31 3. Gereja 5 4. Kuil/Vihara - 5. Majlis Ta’lim 40
Jumlah 88 Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, 2008. 4.5. Kelembagaan Ekonomi
Di Kelurahan Bidaracina terdapat beberapa jenis usaha yang bergerak di
sektor produksi yaitu usaha pada sektor informal, usaha mikro, kecil dan
40
menengah dengan komoditas yang berbeda-beda. Pembedaan keempat jenis usaha
tersebut berdasarkan atas besarnya modal yang dimiliki. Sektor informal adalah
jenis usaha yang memiliki modal Rp 100.000-Rp 5.000.000, usaha mikro
memiliki modal Rp 5.000.000-Rp 50.000.000, usaha kecil memiliki modal Rp
50.000.000-Rp200.000.000 dan menengah Rp 200.000.000-1 M. Berikut ini
adalah jenis-jenis keempat usaha tersebut yang terdapat di Kelurahan Bidaracina.
Tabel 12. Kelembagaan Ekonomi Informal Kelurahan Bidaracina, Mei 2008.
No. Jenis Usaha Komoditi Jumlah 1. Sektor Informal Pabrik Tahu 1 2. Sektor Informal Pabrik Tempe 1 3. Sektor Informal Logam 7 4. Sektor Informal Sablon 1 5. Sektor Informal Tas 1 6. Mikro Pabrik Kerupuk 1 7. Mikro Aksesoris 1 8. Mikro Pabrik Roti 2 9. Mikro Logam 12 10. Kecil Minuman Ringan 1 11. Menengah Rambu-rambu Lalu lintas 1
Jumlah 29 Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, 2008. Selain usaha-usaha tersebut di atas, di Kelurahan Bidaracina juga terdapat
usaha-usaha lainnya yang dijalankan oleh penduduk.
Tabel 13. Kelembagaan Ekonomi Nonformal Kelurahan Bidaracina, Mei 2008.
No. Jenis Usaha Jumlah 1. Pangkalan Minyak Tanah 1 2. Depot Isi Ulang Air Minum Mineral 5 3. Mini Market/Swalayan 5 4. Rumah Makan 27 5. Hotel/Penginapan 3 6. Bengkel 15 7. Koperasi 2 Jumlah 58
Sumber : Data Monografi Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 2008.
41
4.6. Zakat dan Kemiskinan di Kelurahan Bidaracina
Untuk melihat jumlah warga miskin yang berada di wilayah Bidaracina,
peneliti menggunakan data dari penerima bantuan Raskin (Beras Untuk Keluarga
Miskin) Tahun 2005 yang tersebar di 16 Kelurahan, jumlah Kepala Keluarga yang
mendapatkan bantuan Raskin adalah 648, yang terdiri dari 2.185 jiwa. Meskipun
tersebar di seluruh RW, namun pembagian proporsi Raskin masing-masing RW
berbeda-beda, jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan Raskin di RW
001 adalah 24 KK, RW 002 sejumlah 49 KK, RW 003 sejumlah 75 KK, RW 004
sejumlah 34 KK, RW 005 sejumlah 29 KK, RW 006 sejumlah 29 KK, RW 007
sejumlah 88 KK, RW 008 sejumlah 41 KK, RW 009 sejumlah 19 KK, RW 010
sejumlah 35 KK, RW 011 sejumlah 35 KK, RW 012 sejumlah 28 KK, RW 013
sejumlah 27 KK, RW 014 sejumlah 42 KK, RW 015 sejumlah 42 KK, dan RW
016 sejumlah 36 KK.
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan Raskin di
RW 007 merupakan yang paling besar jika dibandingkan dengan jumlah penerima
bantuan Raskin di RW yang lainnya. Hal tersebut berarti bahwa jumlah warga
miskin di RW 007 lebih banyak dibandingkan dengan RW lainnya, sehingga
program Urban MM telah tepat dalam memilih lokasi program.
Data yang digunakan adalah data yang sama pada tahun yang berbeda,
yaitu data penerima bantuan Raskin (beras untuk keluarga miskin) pada tahun
2005 dan 2008. Tahun 2005 jumlah KK yang mendapatkan bantuan Raskin adalah
88, sedangkan di tahun 2008 naik cukup drastis menjadi 155 KK, dengan total
beras yang dibagikan sebanyak 930 liter. Hal tersebut menunjukkan bahwa
42
sebenarnya kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu dinamis berubah
dan cenderung terus meningkat pad setiap tahunnya.
4.7. Ikhtisar
Kelurahan Bidaracina merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kondisi geografis Kelurahan Bidaracina
sangat strategis, karena berada diantara ruas jalan yang ramai, dan daerah yang
padat seperti Kampung Melayu, Jalan MT. Haryono, dan Cawang yang
merupakan kawasan perkotaan, dimana banyak terdapat fasilitas umum, seperti
terminal Kampung Melayu, pasar Jatinegara dan fasilitas lainnya.
Tidak hanya memiliki kawasan yang letaknya strategis, Kelurahan
Bidaracina juga terbilang maju secara kependudukan, misalnya dapat dilihat dari
tingkat pendidikan, dan mata pencaharian, serta dari sarana dan prasarana umum
seperti jumlah fasilitas peribadahan, pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan
ekonomi, serta fasilitas penunjang lainnya seperti jalanan dan alat transportasi.
Terkait dengan masalah kemiskinan, jumlah penduduk fakir miskin dan
pengangguran jika dibandingkan dengan penduduk yang bermatapencaharian
cukup besar, jumlah penduduk fakir dan miskin di Kelurahan Bidaracina
tergolong sedikit. Meskipun jumlah fakir miskin tidak terlalu banyak, tetapi
kesenjangan sosial yang terjadi cukup besar, diantara jajaran rumah besar dan
mewah terdapat rumah kontrakan kecil yang kumuh, dengan kata lain kekayaan
yang ada tidak didistribusikan kepada yang lain. Selain itu, meskipun jumlah
kelembagaan ekonomi di Kelurahan Bidaracina cukup banyak, namun hanya
orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya, dan biasanya orang-orang yang
43
memiliki usaha di Bidaracina merekrut pegawai/pekerja tidak selalu dari dalam
Kelurahan, banyak diantaranya yang tinggal di luar Kelurahan Bidaracina.
Dapat disimpulkan bahwa jumlah warga miskin (fakir) di Kelurahan
Bidaracina tidak begitu tinggi. Namun kesenjangan sosial yang terjadi cukup
tinggi, sehingga diperlukan usaha-usaha untuk membangkitkan warga dari
kemiskinan, meskipun Kelurahan Bidaracina tergolong maju, namun usaha-usaha
untuk menolong warga yang miskin tetap saja dibutuhkan.
44
BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM URBAN
MASYARAKAT MANDIRI
5.1. Profil dan Pelaksanaan Program Urban Masyarakat Mandiri
5.1.1. Profil Program Urban Masyarakat Mandiri
Program Urban dilatarbelakangi oleh kemunculan isu-isu makanan yang
mengandung formalin dan bakso tikus. Isu-isu tersebut secara tridak langsung
menurunkan citra makanan jajanan yang banyak dijual oleh para pelaku
usaha/pedagang di sekolah-sekolah, perkantoran, pasar-pasar tradisional dan
pusat-pusat keramaian lainnya. Dalam kenyataannya, isu-isu itu berkembang
menjadi fakta. Berita di televisi, radio dan media lainnya seringkali menunjukkan
bahwa makanan jajanan yang biasanya dijual banyak mengandung bahan
pengawet dan Bahan Tambahan Makanan (BTM), seperti formalin, boraks,
pewarna tekstil, penggunaan bahan baku seperti daging dengan kualitas rendah,
dan sebagainya. Dihadapkan oleh kondisi seperti di atas, serta faktor kebijakan
pemerintah, seperti kenaikan harga, maka posisi para pedagang menjadi semakin
lemah dalam meningkatkan kesejahteraanya mereka, seperti semakin menurunnya
pendapatan mereka, serta dalam hal mendapatkan akses publik (permodalan,
kesehatan dan pendidikan).
Program Urban adalah salah satu program dari Masyarakat Mandiri
jejaring Dompet Dhuafa yang merupakan lembaga nirlaba yang memiliki
kepedulian untuk meningkatkan taraf hidup para pelaku usaha mikro makanan
jajanan yang terkena imbas isu formalin dan bahan pengawet bahaya lainnya di
lingkar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Program ini
45
diharapkan mampu membangkitkan daya ekonomi komunitas sasaran dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran. Pelaksanaan program ini
terdiri dari pendampingan usaha, penguatan modal, pembinaan kelompok serta
menumbuhkan pola jaminan keamanan pangan yang berbasis komunitas, sehingga
diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha makanan
kecil baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.
Program pemberdayaan pelaku usaha mikro makanan jajanan yang rentan
penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya di Bidaracina, Pancoran,
Manggarai, Cipinang, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Program yang telah berlangsung dari 2006 dan akan berakhir 2008 ini memiliki
520 anggota dan total penerima manfaat 2.034 orang yang tersebar di Bidaracina,
Pancoran, Manggarai, Cipinang, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Total dana
yang telah disalurkan sejak Maret 2006 adalah sebesar Rp. 769.622.000, dimana
Rp. 375.244.000 diantaranya adalah dana yang berhasil digulirkan dari angsuran
pembiayaan mitra.
Selama awal berdiri, Program Urban Masyarakat Mandiri telah berada di
seluruh wilayah Jabodetabek, khususnya pada kawasan kemiskinan di perkotaan,
khususnya pada wilayah dimana banyak terdapat para pedagang makanan jajanan
yang rentan terhadap pengunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM). Pada
kawasan-kawasan tersebut, program MM tidak selalu memiliki kesamaan usaha,
tergantung dari potensi wilayah dan potensi masyarakat (mitra). Kemudian usaha-
usaha yang dijalankan mitra tersebut berkembang menjadi berbagai macam jenis,
yaitu Ikatan Mitra Wilayah (IMW) dan Ikhtiar Swadaya Mitra (ISM) yang
46
tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Berikut ini adalah Tabel 14 yang
memuat informasi tersebut.
Tabel 14. Lembaga Lokal (IMW/ISM) dan Usaha Bersama yang telah Terbentuk, Jakarta, 2008.
No. Wilayah IMW/ISW Usaha Bersama 1. Bidaracina,
Jakarta Timur ISM Bidaracina (dalam proses badan hukum)
Grosir Sembako Mandiri
2. Cipinang, Jakarta Timur
Koperasi Serba Usaha ISM Bidaracina (dalam proses badan hukum)
Gerai BasoCip
3. Pancoran dan Manggarai, Jakarta Selatan
Koperasi Serba Usaha Grosir Sembako Mandiri
4. Bogor Koperasi Serba Usaha ISM Pasir Jaya
KSU Pasir Jaya dan Mie Kalam
5. Depok ISM Depok 3 Unit Devok Fried Chicken
6. Tangerang ISM Tangerang Usaha Plastik Mandiri
7. Bekasi ISM Bekasi Gerai Siomay Sehat
Sumber : Laporan Perkembangan Program Urban Msyarakat Mandiri (2008)
5.1.2. Rancangan Pelaksanaan Program Urban Masyratakat Mandiri
Tujuan umum dari program ini adalah peningkatan pendapatan keluarga
para pelaku usaha makanan jajanan di sekitar wilayah Jabodetabek melalui
kegiatan pendampingan, pembiayaan, dan pembinaan usaha yang berkolaborasi
dengan dinas/lembaga terkait, sedangkan tujuan akhir dan tujuan antara adalah
sebagai berikut:
1. Tujuan Akhir (Goals) : Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro.
2. Tujuan antara (Purpose) : Peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro
makanan jajanan dengan indikator keuntungan
harian rata-rata meningkat minimal Rp. 50.000.
47
Rancangan program Urban Masyarakat Mandiri, dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Sasaran/Pemetik Manfaat (Target Group)
Pemetik manfaat program adalah para pelaku usaha mikro makanan jajanan yang
rentan penggunaan bahan kimia berbahaya (seperti boraks, formalin, dll) yang
berpenghasilan dari usaha rata-rata maksimal Rp. 30.000 perhari dengan target
spesifik:
1. Sudah memiliki usaha makanan jajanan skala mikro,
2. Usaha yang dilakukan independen,
3. Skala modal kerja perhari di bawah Rp. 500.000,
4. Rentan terhadap penggunaan bahan aditif berbahaya,
5. Tinggal dalam satu domisili di tempat kumuh,
6. Tidak memperoleh pembiayaan dari pihak lain.
7. Jumlah penerima manfaat program diperkirakan sebanyak 1000 orang mitra.
2. Wilayah (Target Area)
Wilayah program meliputi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi.
3. Waktu (Time Frame)
Pelaksanaan kegiatan program berjangka waktu 2 tahun yang terdiri dari 3
tahapan, yaitu: perintisan, penguatan dan pelepasan.
48
4. Nama Program (Programe Name)
Pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro makanan jajanan yang rentan
penggunaan bahan kimia berbahaya di lingkar wilayah Jabodetabek.
5. Output (Expected Outcome)
Keluaran (output) yang dibangun dilandasi oleh permasalahan, potensi yang
dimiliki serta peluang yang ada bagi pemenuhan kebutuhan para pelaku usaha
mikro makanan jajanan. Output yang diharapkan adalah:
1. Meningkatnya jumlah pembeli dengan omset penjualan pelaku usaha mikro
makanan jajanan pasca isu meningkat minimal 50 persen.
2. Mutu produk pelaku usaha mikro makanan jajanan meningkat dengan
ditandainya produk yang dihasilkan tidak menggunakan bahan-bahan kimia
berbahaya.
3. Meningkatnya posisi tawar para pelaku usaha mikro makanan jajanan dengan
terbentuknya wadah berbasis komunitas yang memperhatikan mutu produk.
4. Keberlanjutan program dengan terbentuknya kader lokal minimal 2 orang
untuk masing-masing wilayah pendampingan dan terkumpulnya modal
swadaya sebesar Rp 1.000.000 untuk setiap wilayah pendampingan.
6. Kebijakan dan Strategi Program
Langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam program pemberdayaan
komunitas perkotaan/urban melalui kegiatan pendampingan sebagai berikut:
1. Pembentukan Kelompok secara Partisipatif
2. Penguatan Kapasitas SDM Komunitas
49
3. Menciptakan dan Mengembangkan Usaha Produktif
4. Pengembangan Kelembagaan Komunitas
5.2. Pelaksanaan Program Urban Masyarakat Mandiri
1. Pra Persiapan
a. Kajian Kebutuhan (Need Assesment)
Pada tahap ini, yang penting adalah bagaimana
mentransformasikan kebutuhan-kebutuhan individu menjadi kebutuhan
bersama/kelompok dan selanjutnya menjadi tujuan akhir kelompok yang
diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
a. Kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan pada saat tertentu (field needs).
b. Kebutuhan-kebutuhan nyata (actual needs)
c. Kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan di waktu mendatang
(anticipated needs).
b. Perencanaan Program
Hasil kajian kebutuhan ini akan memberikan gambaran sekaligus
pijakan tentang orientasi sasaran pembangunan di komuniats program
urban. Dengan demikian dapat dibuat Matrik Perencanaan Program (MPP)
pemberdayaan dan pengembangan usaha yang selaras dengan kebutuhan
kelompok sasaran, termasuk 1) perencanaan anggaran operasional; 2)
rencana pembiayaan; 3) sumber-sumber pendanaan; 4) langkah-langkah
strategis; 5) tahapan pekerjaan teknis; 6) pembagian peran, dan 7) tugas
serta kemungkinan sumberdaya serta hambatannya. Dalam tahapan ini
pula dibuat perencanaan penyerapan dana sesuai skim pembiayaan dengan
mekanisme, prosedur dan administrasi yang dibutuhkan.
50
2. Persiapan
Pada tahap ini, pelaksana program mempersiapkan segala sesuatu yang
terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan di wilayah sasaran. Hal-hal
yang harus dipersiapkan adalah: cetak biru program, pedoman teknis peleksanaan,
sumberdaya manusia, biaya operasional, dana pembiayaan dan lain-lain.
3. Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan di lapangan, perubahan atau pergeseran semua
rencana program sangat mungkin terjadi. Selama perubahan yang terjadi dalam
jumlah dan frekuensi yang wajar, maka tidak perlu dikhawatirkan. Peran tenaga
pendamping yang bertugas selaku fasilitator dan motivator program sangat
dibutuhkan pada tahapan ini. Pendampingan yang dilakukan kepada komunitas
perkotaan (urban) di setiap wilayah sasaran berlangsung selama 2 tahun. Periode
setiap tahapan pendampingan.
Tabel 15. Tahapan Pendampingan Program Perkotaan (Urban), Jakarta, 2008.
No. FASE PROGRAM TAHUN 2006 2007 2008
1. Perintisan dan Penumbuhan KM 6 bln 2. Penguatan kapasitas individu dan lembaga lokal 6 bln 3. Pelepasan (kemandirian material dan wadah
kelompok) 6 bln
Sumber : Laporan Perkembangan Program Urban Msyarakat Mandiri (2008)
Untuk mencapai tujuan, maka tahapan program perkotaan (Urban) didasarkan
pada unsur-unsur input, proses aktivitas tertentu dan output, yang diharapkan
mampu mendukung pencapaian keberhasilan program. Secara garis besar, unsur-
unsur input dan aktivitas yang direncanakan pada program ini adalah sebagai
berikut.
51
Tabel 16. Input, Aktivitas dan Output Program Perkotaan (Urban), Jakarta, 2008.
INPUT PROSES OUTPUT
Aktivitas Usaha a. Pelatihan manajemen dan pengembangan
usaha, b. Pengembangan usaha turunan/aset produktif. Peningkatan
pendapatan Kemitraan dalam masyarakat
a. Fasilitas dalam mengupayakan pasar, b. Fasilitas dengan sumber permodalan.
Teknologi a. Fasilitas dengan sumber-sumber permodalan, b. Fasilitas penerapan teknologi tepat guna.
SDM
a. Penumbuhan dan penguatan kelompok/kelembagaan,
b. Pelatihan manajemen keorganisasian dan leadership,
c. Fasilitas dengan Dinas terkait.
Kemandirian kelompok/kelembagaan
Sumber : Laporan Perkembangan Program Urban Msyarakat Mandiri (2008)
Pembiayaan kepada responden adalah salah satu bentuk aktivitas
penguatan kepada responden yang diikuti oleh aktivitas program lainnya.
Pembiayaan ini hanya akan diberikan kepada mitra yang memenuhi kriteria
dhuafa dan secara ekonomi cukup layak untuk mendapatkan pembiayaan.
Selanjutnya bagi mitra yang tidak memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan,
dapat bergabung menjadi mitra untuk mendapatkan fasilitas penyuluhan,
pembinaan, dan pendampingan, serta memperoleh kesempatan dalam proses
sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sertifikasi dari Dinas
Kesehatan.
Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk dana bergulir dengan akad jual
beli secara angsuran/cicilan antara MM dengan mitra melalui tiga tahap
pembiayaan (skim) berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Tabel 17. Daftar Skim Pembiayaan Program Komunitas Urban, Jakarta, 2008.
SKIM JUMLAH MAKSIMUM PEMBIAYAAN AKAD
WAKTU MAKSIMUM
CICILAN 1 Rp. 750.000 Cicilan jual beli 10 bulan 2 Rp. 1.250.000 Cicilan jual beli 6-8 bulan 3 Rp. 2.000.000 Cicilan jual beli 6 bulan
52
Sumber : Laporan Perkembangan Program Urban Msyarakat Mandiri (2008)
Cicilan jual beli merupakan pembiayaan dengan cara akad jual beli,
dimana pihak pembeli/responden akan membayar dengan cara
mencicil/mengangsur. Margin/keuntungan jual beli dan jangka waktu cicilan
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara MM (penjual) dan responden
(pembeli) sesuai dengan jangka waktu maksimum pembiayaan.
5.3. Ikhtisar
Program Urban MM bertujuan untuk membangkitkan daya ekonomi
komunitas sasaran dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan
kesadaran. Pelaksanaan program ini terdiri dari pendampingan usaha, penguatan
modal, pembinaan kelompok dan menumbuhkan pola jaminan keamanan pangan
yang berbasis komunitas, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan
kesejahteraan para pelaku usaha makanan kecil baik dalam aspek ekonomi
maupun sosial.
Sejak awal, Program Urban Masyarakat Mandiri telah berada di seluruh
wilayah Jabodetabek, khususnya pada kawasan miskin di perkotaan. Pada
kawasan tersebut, peserta program MM tidak selalu memiliki kesamaan usaha,
tergantung dari potensi wilayah dan potensi masyarakat (mitra). Seiring dengan
perkembangan kondisi mitra di masing-masing wilayah, program ini berkembang
menjadi organisasi yang lebih formal seperti Koperasi. Pembentukan koperasi
dimaksudkan agar setelah proses pendampingan selesai, para mitra tidak begitu
saja membubarkan diri, melainkan meneruskan program tersebut dengan bentuk
yang lain meskipun dengan tujuan yang sama.
53
Seperti halnya di daerah Bidaracina, program MM yang pada awalnya
hanya sebagai perkumpulan mitra, kini telah berkembang menjadi Koperasi agar
statusnya lebih formal, para pengurus dan anggota mitra adalah orang-orang yang
pada awalnya sudah terlibat, bahkan semakin banyak yang menjadi mitra baru.
Pemetik manfaat program adalah para pelaku usaha mikro makanan
jajanan yang rentan penggunaan bahan kimia berbahaya (seperti boraks, formalin,
dll) yang berpenghasilan dari usaha rata-rata maksimal Rp. 30.000 perhari dan
dinyatakan layak sebagai kriteria dhuafa. Kemudian orang-orang tersebut
dinyatakan sebagai mitra, selanjutnya mereka diberikan pinjaman modal usaha.
Pemberian pinjaman yang diberikan dalam bentuk dana bergulir dengan akad jual
beli secara angsuran/cicilan antara MM dengan mitra melalui tiga tahap
pembiayaan (skim) berdasarkan waktu yang telah ditentukan
54
BAB VI
KARAKTERISTIK MASYARAKAT PENERIMA PINJAMAN
DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
6.1. Karakteristik Masyarakat Penerima Bantuan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, karakteristik masyarakat
penerima bantuan terdiri dari tiga indikator. Berikut ini akan diuraikan
selangkapnya mengenai ketiga karakteristik tersebut.
6.1.1. Karakteristik Bangunan Rumah
a. Kepemilikan Rumah
Tabel 18 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah yang ditinggali oleh
responden saat ini adalah rumah kontrakan (sewa) yakni sebesar 70 persen,
kemudian diikuti oleh rumah milik sendiri dan milik keluarga masing-masing 15
persen dan 10 persen, serta menumpang lima persen. Seluruh responden yang
tinggal di rumah kontrakan sebenarnya memiliki rumah sendiri di daerahnya
masing-masing, mereka tidak mau membangun rumah sendiri di Jakarta karena
tidak ada biaya dan pada suatu saat mereka ingin kembali ke daerah asal mereka
kesulitan untuk menjualnya.
Tabel 18. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Rumah, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Kepemilikan Rumah Jumlah Responden Jiwa %
1. Menumpang 1 5 2. Kontrak 14 70 3. Keluarga 2 10 4. Sendiri 3 15
Total 20 100
55
Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sebagian besar
responden adalah warga pendatang yang berasal dari daerah, yang kemudian
datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, mereka lebih suka
untuk mengontrak rumah dibandingkan membangun rumah sendiri, karena
sebenarnya mereka mempunyai rumah di daerahnya masing-masing.
“Warga Bidaracina banyak yang pendatang, termasuk mitra. Kalau di sini mereka ngontrak rumah, tapi kalau di kampung rumahnya besar-besar” (Ln, 27 tahun, pendamping).
Responden yang tinggal di rumah keluarganya hanya ada sebesar 10
persen atau dua orang (rumah tangga), yakni keluarga Dw (35 tahun) dan Edg
(40 tahun). Dw (35 tahun) adalah warga pendatang, namun ia menikah dengan
warga setempat, sehingga ia tinggal bersama keluarganya pada satu rumah yang
sama, masing-masing keluarga beriuran untuk membayar kebutuhan bersama
seperti listrik, telepon, dll. Sedangkan Edg (40 tahun) adalah warga asli
Bidaracina yang sudah sejak lama tinggal di sana. Namun demikian, rumah yang
ia dan kelurganya tempati masih berstatus rumah keluarganya belum sepenuhnya
menjadi hak milik ia dan suaminya.
Responden yang tinggal di rumah sendiri sebesar 15 persen, atau sebanyak
tiga orang (RT), yakni Snt (45 tahun), Smn (48 tahun), dan Snr (41 tahun). Snt (45
tahun) sudah lama tinggal di Bidaracina, sehingga ia dan keluarga sudah bisa
membangun rumah sendiri, meskipun ia dan istrinya bukan warga asli. Menurut
Snt (45 tahun) rumah milik sendiri lebih enak jika dibandingkan menumpang.
“Enakan rumah sendiri mba, walaupun sepetak rasanya beda, kita bisa bebas mau ngapain aja. Padahal ini rumahnya ga jelas bentuknya, soalnya ngebangunnya sedikit-sedikit, kalo ada uang tambahin, ada dikit lagi tambahin” (Snt, 45 tahun, mitra MM).
56
Smn (48 tahun) telah lama tinggal di Bidaracina dan sudah lama membeli
rumah, walaupun sebenarnya ia telah mempunyai rumah di daerah asalnya, namun
rumah tersebut bukan rumahnya sendiri, melainkan rumah keluarganya.
b. Ukuran Rumah
Data pada Tabel 19 menunjukkan bahwa sebagian besar responden
memiliki ukuran rumah yang kecil yakni sebanyak 45 persen, diikuti oleh sangat
kecil yakni 25 persen serta sedang dan besar yakni sama-sama sebesar 15 persen.
Data tersebut sesuai dengan data kepemilikan rumah pada Tabel 18, bahwa
sebagian besar responden tinggal di rumah kontrakan. Jika dihubungkan dengan
ukuran rumah yang ditinggali oleh responden dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar responden tinggal di rumah kontrakan yang ukurannya kecil. Dari
wawancara yang dilakukan kepada responden, diperoleh informasi bahwa rata-
rata rumah kontrakan di Jakarta berukuran kecil yaitu rumah kontrakan dengan
luas 4-6m2. Rumah kontrakan dengan ukuran tersebut biasanya ditempati oleh
warga pendatang yang mengadu nasib di Jakarta untuk berdagang/wirausaha.
Responden yang tinggal di rumah yang berukuran sangat kecil (<4m2)
sebanyak 25 persen atau sebanyak 5 orang (RT), rumah yang mereka tempati
adalah rumah kontrakan yang sangat sederhana. Pan (40 tahun), salah satu
responden yang tinggal di rumah yang berukuran sangat kecil memberikan alasan
bahwa ia tinggal di Jakarta hanya sendiri, istri dan anak-anaknya tinggal di
Wonogiri, jadi ia lebih memilih untuk mencari kontrakan yang sederhana.
“Saya tinggal Cuma sendiri mba, anak istri di kampung, buat apa saya ngontrak di rumah yang gede, sayang-sayang duit, mending saya kirimin ke kampung buat anak istri makan.” (Pan, 40 tahun, mitra).
57
Responden yang tinggal di rumah yang berukuran besar dan sedang adalah
responden yang tinggal bersama keluarga dan tinggal di rumah sendiri. Responden
yang tinggal di rumah yang berukuran besar adalah responden yang tinggal di
rumah bersama keluarga, yakni Dw (35 tahun) dan Edg (40 tahun). Ukuran
rumah mereka besar karena mereka tinggal bersama-sama anggota keluarga yang
lain (lebih dari 1 keluarga). Responden yang tinggal di rumah berukuran sedang
adalah responden yang tinggal di rumah sendiri, yakni Snt (45 tahun) dan Smn
(48 tahun).
Tabel 19. Jumlah Responden Berdasarkan Ukuran Rumah, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Ukuran Rumah Jumlah Responden Jiwa %
1. Sangat kecil (<4m2) 5 25 2. Kecil (4-6m2) 9 45 3. Sedang (6-8m2) 3 15 4. Besar (8m2) 3 15
Total 20 100
c. Jenis Dinding
Berdasarkan Tabel 20, mayoritas jenis dinding rumah responden terbuat
dari tembok/beton, yaitu sebesar 85 persen atau sebanyak 17 RT. Dari ke-17 RT,
14 diantaranya adalah yang tinggal di kontrakan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa rumah kontrakan yang ada di Jakarta adalah berdindingkan tembok. Jarang
dijumpai di Jakarta rumah yang memiliki dinding yang terbuat selain dari tembok,
seperti yang diutarakan Pan (40 tahun).
“Kalo rumah di sini mah mba emang dindingnya tembok, ga ada yang lain, walaupun kontrakan, emangnya di kampung pake bambu atau kayu.” (Pan, 40 tahun, mitra).
58
Tabel 20. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Dinding Rumah, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Jenis Dinding Jumlah Responden Jiwa %
1. Bilik bambu/kayu 2 10 2. Semi 1 5 3. Tembok/beton 17 85
Total 20 100 d. Lantai
Data pada Tabel 21 menunjukkan bahwa sebagian besar responden tinggal
di rumah yang berlantai semen yaitu sebanyak 65 persen, kemudian diikuti
dengan lantai keramik sebesar 30 persen, dan panggung lima persen, sedangkan
tidak satupun rumah responden yang berlantai tanah. Seluruh responden yang
lantai semen adalah responden yang tinggal di rumah kontrakan, sehingga mereka
harus menerima kondisi tersebut. Namun ada responden yang walaupun tinggal di
rumah sendiri tetapi lebih memilih untuk membuat lantainya dari semen, yaitu Snt
(45 tahun). Kondisi tersebut menurutnya ia putuskan karena tetidaktersediaan
dana pada saat membangun rumah, sehingga ia memilih untuk hanya berlantaikan
semen.
“Ga apa-apa mba Cuma disemen, yang penting angga kotor, ntar kalo ada duit sedikit-sedikit lantainya dat pake keramik, sekarang mah yang ada aja.” (Snt, 45 tahun, mitra).
Tabel 21. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Lantai Rumah, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Lantai Jumlah Responden Jiwa %
1. Tanah - - 2. Panggung 1 5 3. Semen 13 65 4. Keramik 6 30
Total 20 100
59
e. Atap
Tabel 22 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki jenis
atap yang terbuat dari genteng/seng yaitu sebesar 80 persen, dan diikuti oleh
Asbes sebesar 20 persen. Jenis atap genteng/seng merupakan jenis atap yang pada
umumnya digunakan di perkotaan baik pada rumah sendiri maupun rumah
kontrakan. Salah satu responden yang memiliki atap rumah terbuat dari genteng
adalah Dw (35 tahun), dengan alasan genteng merupakan bahan yang umumnya
dipakai, kuat dan sulit terbawa angin.
“.........Biasanya emang pake genteng mba, walaupun dia punya rumah sendiri atau ngontrak, abisnya udah biasa sih, mau rumah punya sendiri, rumah kontrakan, sama aja pake genteng. Ya...emang yang beda kualitasnya, kalo orang yang berada gentengnya juga yang mahal, yang warna-warni.” (Dw (35 tahun), 35 tahun, mitra).
Tabel 22. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Atap Rumah, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Jenis Atap Jumlah Responden Jiwa %
1. Kirai/Ijuk - - 2. Genteng/Seng 16 80 3. Asbes/Berglazur 4 20
Total 20 100
f. Dapur
Berdasarkan Tabel 23, sebanyak 40 persen responden menggunakan
kompor minyak untuk memasak, diikuti oleh kompor gas/listrik dan kompor
minyak dan kompor gas yaitu sama-sama sebanyak 20 persen kemudian tungku
dan kompor minyak sebesar 15 persen dan tungku sebesar lima persen. Penyebab
dari banyaknya penduduk yang masih menggunakan kompor minyak/tungku
adalah terkait dengan program pemerintah yaitu konversi bahan bakar minyak
menjadi bahan bakar gas yang belum merata. Sebagian besar penduduk
60
Bidaracina masih menggunakan tungku/kompor minyak, seperti yang diuatarkan
Pan (40 tahun).
“....... Wah, di sini mah mba pembagian kompor gas belum merata, kalo daerah laen udah pada dapet, tapi di sini belum tuh. Ngga tau ya kenapa, padahal kan lumayan kalo kita dapet kompor gas gratis, bisa ngirit juga sih” (Pan, 40 tahun, mitra).
Tabel 23. Jumlah Responden Berdasarkan Dapur Rumah, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Dapur Jumlah Responden Jiwa %
1. Tungku 1 5 2. Kompor Minyak 8 40 3. Kompor Gas/Listrik 4 20 4. Tungku dan Kompor Minyak 3 15 5. Kompor Minyak dan Kompor Gas 4 20
Total 20 100
g. Kursi
Berdasarkan Tabel 24, sebagian besar responden (65%) tidak
menggunakan kursi (lesehan) di rumahnya, 25 persen menggunakan kursi kayu,
dan balai bambu serta sofa yaitu sama-sama sebesar 5 persen. Pada umumnya
responden lebih memilih lesehan karena ketidaktersediaan dana untuk membeli
kursi dan juga berhubungan dengan luas rumah yang mereka tinggali, dengan
ukuran rumah yang kecil bahkan sangat kecil, tidak memungkinkan untuk
memiliki kursi.
Tabel 24. Jumlah Responden Berdasarkan Kursi Rumah, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Lantai Jumlah Responden Jiwa %
1. Lesehan 13 65 2. Balai Bambu 1 5 3. Kayu 5 25 4. Sofa 1 5
Total 20 100
61
6.1.2. Kepemilikan Aset Pribadi
a. Kebun/Sawah
Untuk kepemilikan aset pribadi seperti kebun/sawah, sebagian besar
responden tidak memiliki aset kebun/sawah yaitu sebesar 45 persen, selebihnya
responden memiliki kebun/sawah dengan ukuran yang berbeda-beda, yaitu
responden yang memiliki kebun/sawah seluas <1000m2 sebesar 40 persen, 1000-
5000m2 sebesar 10 persen, dan >5000m2 sebesar 5 persen. Pada umumnya
responden yang tidak memiliki aset kebun/sawah mengatakan bahwa jangankan
memiliki kebun/sawah, untuk usaha saja susah, salah satu diantaranya adalah Edg
(40 tahun).
“Kalo dulu sih punya mba, tapi udah pada dijual. Kalo sekarang jangankan punya kebon/sawah mba, buat makan sama usaha aja susah, ntar yang ada dijualin mulu buat makan ama modal usaha.”
Sedangkan bagi responden yang mempunyai aset kebun/sawah
mengatakan kalau aset tersebut tidak ada di Jakarta, melainkan di kampung
mereka masing-masing. Salah satu responden yang mengatakan hal tersebut
adalah Pan (40 tahun).
“Ya...kalo tanahnya di sini sih mba engga mungkin, di Jakarta sekarang ga ada tanah nganggur yang luas. Kalo tanah saya sih di kampung, itu juga tanah warisan orang tua.”
Tabel 25. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Kebun/Sawah, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Kebun/Sawah (meter2) Jumlah Responden
Jiwa % 1. Tidak Ada 9 45 2. <1000m2 8 40 3. 1000-5000m2 2 10 4. >5000m2 1 5
Total 20 100
62
b. Barang-barang Elektronik
Berdasarkan Tabel 26, responden yang memiliki satu jenis dan dua jenis
barang elektronik sama-sama sebesar 25 persen, diikuti dengan yang memiliki tiga
dan empat jenis barang elektronik yaitu sebesar 15 persen, dan tidak memiliki
barang elektronik sebesar 20 persen.
Tabel 26. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Barang/barang Elektronik, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Barang-barang Elektronik (buah) Jumlah Responden Jiwa %
1. 1 5 25 2. 2 5 25 3. 3 3 15 4. 4 3 15 5. Tidak punya 4 20
Total 20 100
c. Kendaraan
Pada Tabel 27, dapat dilihat bahwa 50 persen responden memiliki
kendaraan berupa sepeda motor, kemudian diikuti oleh sepeda motor dan tidak
memiliki kendaraan yaitu sama-sama sebesar 25 persen. Responden yang
memiliki sepeda motor mengatakan bahwa sepeda motor yang mereka miliki
digunakan untuk menunjang usaha mereka, seperti yang dikatakan Pan (40 tahun)
berikut ini.
“Punya motor itu penting mba, bisa bantu saya, bukan cuma usaha aja tapi juga buat saya jalan kemana-mana, kalo buat usaha misalnya buat ngangkut beli bahan dagangan, kalo buat jalan biasanya maen ke rumah temen atau sodara, kan kalo pake angkot atau bis, ongksonya mahal, mending punya motor walaupun kredit.” (Pan, 40 tahun, mitra).
63
Tabel 27. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Jenis Kendaraan, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Jenis Kendaraan Jumlah Responden Jiwa %
1. Tidak Ada 5 25 2. Sepeda 5 25 3. Sepeda Motor 10 50
Total 20 100 d. Binatang Ternak
Tabel 28 menunjukkan bahwa sebagian besar mitra tidak memiliki
binatang ternak, yaitu sebesar 90 persen, sedangkan responden yang memiliki
binatang ternak sebesar 10 persen, lima persen diantaranya memiliki unggas, dan
5 persen lainnya memiliki kerbau. Sebagian besar mitra yang tidak memiliki
binatang ternak mengatakan tidak tertarik memelihara binatang, sehingga mereka
tidak mau memeliharanya. Responden yang memiliki unggas mengatakan
sebenarnya hanya sekedar iseng, kemudian responden yang memiliki kerbau,
yaitu Pan (40 tahun) mengatakan bahwa binatang ternak yang ia miliki tidak
dimaksud untuk diternak.
“Ah...kerbau itu mah mba cuma peliharaan aja, bukan sengaja buat diternak, lagian itu adanya di kampung, engga mungkin saya pelihara di sini.” (Pan, 40 tahun, mitra).
Tabel 28. Jumlah Responden Berdasarkan Kepemilikan Binatang Ternak,
Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Jenis Binatang Ternak Jumlah Responden Jiwa %
1. Unggas 1 5 2. Sapi/Kerbau 1 5 3. Tidak punya 18 90
Total 20 100
64
d. Simpanan
Berdasarkan Tabel 29, sebagian besar responden yaitu sebanyak 90 persen
tidak memiliki simpanan dalam bentuk apapun, sedangkan sisanya sebanyak 10
persen memiliki simpanan dalam bentuk uang. Sebagian besar responden yang
tidak memiliki simpanan mengatakan pendapatan yang mereka miliki tidak cukup,
sehingga tidak dapat menyimpan. Sedangkan salah satu responden yang memiliki
simpanan adalah Dw (35 tahun). Menurutnya simpanan yang ia miliki digunakan
untuk pendidikan anaknya, yaitu pada saat masuk SMP.
“Sebenernya sih biasanya ga punya simpenan, yang ini mah ada buat anak aja, besok mau masuk SMP, itu juga engga gede, Cuma 2 juta.” (Dw , 35 tahun, mitra).
Tabel 29. Jumlah Responden Berdasarkan Simpanan Uang, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Simpanan Jumlah Responden Jiwa %
1. Ada 2 10 2. Tidak Ada 18 90
Total 20 100
6.1.3. Tingkat Penghasilan Usaha Pokok (Laba Usaha)
Indikator penghasilan usaha pokok (laba usaha) merupakan indikator
ketiga yang menjadi parameter/karakteristik masyarakat penerima bantuan.
Rumah tangga yang layak dibiayai adalah rumah tangga yang memiliki
penghasilan usaha pokok (laba usaha) ≤Rp 30.000, apabila di atas angka tersebut,
maka mitra tidak layak. Namun demikian tidak dapat dikatakan ia tidak layak
menerima bantuan, karena masih ada dua indikator lainnya seperti yang telah
disebutkan. Sebanyak tiga mitra (15%) yang tidak layak mendapatkan bantuan
berdasarkan penghasilan usaha pokok (laba usaha) dikarenakan melebihi Rp
65
30.000, sedangkan sisanya sebanyak 17 mitra (85%) merupakan mitra yang layak
mendapatkan pinjaman dikarenakan penghasilan usaha pokok (laba usaha) ≤Rp
30.000.
6.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan
Menurut Tansey dan Ziegley (dalam Suharto, dkk, 2003), faktor-faktor
yang menyebabkan kemiskinan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor
internal yaitu yang berasal dari dalam keluarga, seperti: 1) tingkat karakteristik
usaha; 2) tingkat motivasi; 3) tingkat dukungan anggota keluarga, serta 4) pola
produksi dan konsumsi keluarga, sedangkan faktor eksternal merupakan unsur-
unsur penyebab yang berasal dari luar yang mempengaruhi keberdayaan keluarga
miskin, yang meliputi: 1) perbedaan peluang meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan; 2) sempitnya mendapatkan peluang pekerjaan; 3) perbedaan
aksesibilitas terhadap sumberdaya; 4) bencana alam, 5) dan kebijakan pemerintah.
6.2.1. Faktor Internal
Tingkat karakteristik usaha berkaitan dengan ciri-ciri usaha responden
yang bisa/memiliki kemungkinan/peluang untuk menjadikan usahanya bertambah
sukses atau sebaliknya, seperti ketertarikan pembeli terhadap produk usahanya,
lokasi usaha yang cukup strategis, dan modal yang digunakan. Kemungkinan
usahanya menjadi sukses karena produk usaha yang diminati, lokasi yang
strategis, dan modal yang cukup, sehingga usaha yang dijalankan layak menurut
tingkat karakteristik usahanya. Begitupula sebaliknya, kemungkinan usahanya
dapat menjadi tidak sukses karena produk usaha yang kurang diminati, lokasi
yang kurang strategis, dan modal yang kurang.
66
Tingkat motivasi adalah yang berkaitan dengan semangat, etos kerja dan
tujuan hidup yang ada di dalam diri seseorang, yang kemudian diturunkan
menjadi beberapa indikator, yaitu etos kerja yang berkaitan dengan rasa malas
yang ada dalam diri responden, apakah responden termasuk orang yang giat
bekerja, serta keinginan responden untuk hidup yang layak. Seseorang menjadi
kaya atau miskin kemungkinan disebabkan dari dalam dirinya sendiri, rasa malas,
tidak giat bekerja serta tidak memiliki keinginan untuk hidup layak bisa jadi
merupakan penyebab mengapa selama ini seseorang menjai miskin, seseorang
yang memiliki tujuan hidup yang baik dan usaha yang keras kemungkinan akan
membawanya untuk meraih hidup yang lebih baik. Sebaliknya seseorang yang
tidak memiliki tujuan hidup yang usaha yang keras kemungkinan besar akan
membawanya kepada kehidupan yang tidak layak.
Tingkat dukungan keluarga merupakan salah satu hal yang penting apabila
seseorang akan melakukan usaha, dukungan tersebut dapat berupa tenaga, materi
maupun support yang dapat mendukung usaha keluarga, seperti yang terkait
dengan bantuan anggota keluarga dalam menjalankan usahanya, seperti yang
terkait dengan proses produksi, pemasaran dan dukungan lainnya yang juga
berupa membantu dalam mencarikan modal, dll.
Pola produksi dan konsumsi keluarga juga merupakan hal yang penting
yang harus diperhatikan sebagai penyebab kemiskinan. Hal tersebut terkait
dengan pola hidup seseorang/keluarga setiap harinya, bagaimana seseorang dapat
menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung/disimpan, pola hidup
seseorang yang hemat atau sebaliknya, apakah seseorang sering membeli barang-
barang yang sebenarnya tidak diperlukan, serta bagaimana cara seseorang untuk
67
menghadapi situasi dimana ia tidak memiliki uang/materi. Keempat karakteristik
tersebut ditanyakan kepada responden dapat dilihat pada Tabel 30.
Tabel 30. Faktor-faktor Internal yang Menyebabkan Kemiskinan, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Karakteristik Jawaban
Ya Tidak Jiwa % Jiwa %
1. Tingkat Karakteristik Usaha a. Ketertarikan pembeli terhadap jenis
dagangan 16 80 4 20
b. Lokasi jualan yang strategis 17 85 3 15 c. Ketersediaan modal 5 25 15 75
2. Tingkat Motivasi a. Sering merasakan malas bekerja 7 35 13 65
b. Merasakan selalu giat bekerja 15 75 5 25 c. Keinginan unutk hidup layak 20 100 - -
3. Tingkat Dukungan Anggota Keluarga a. Bantuan keluarga dalam proses produksi 15 75 5 25
b. Bantuan keluarga dalam pemasaran 4 20 16 80 c. Seluruh keluarga mendukung 20 100 - -
4. Pola produksi dan Konsumsi Keluarga a. Selalu menyisihkan uang untuk ditabung
setiap hari/ bulan. 4 20 16 80
b.Termasuk keluarga yang hemat. 17 85 3 15 c. Sering membeli barang yang tidak terlalu diperlukan
- - 20 100
d. Sering meminjam uang kepada orang lain 5 25 15 75 Berdasarkan Tabel 30, untuk tingkat karakteristik usahanya, usaha
sebagian besar responden (80%) banyak diminati oleh pembeli, sedangkan sisanya
sebanyak 20 persen tidak diminati oleh pembeli. Responden yang produk
usahanya banyak diminati oleh pembeli memberikan alasan bahwa meskipun
produk usaha sudah banyak dilakukan oleh pedagang lainnya. Namun mereka
mempunyai ciri khas, diantaranya Edg (40 tahun), barang dagangannya adalah
mie rebus dan mie goreng untuk anak-anak di SDN V, harga jajanannya tergolong
dapat dijangkau oleh anak-anak SD dan memiliki ciri khas, yakni memakai
piring/mangkok kecil sebagai wadah mie dan sumpit sebagai alat makannya. Jenis
68
dagangan tersebut sangat disukai anak-anak SD, karena sebagian besar berangkat
sekolah tanpa sarapan pagi, selain itu juga mie bersifat mengenyangkan perut,
sehingga dengan harga yang terjangkau perut bisa menjadi kenyang.
Tidak hanya produk usaha yang disukai, sebagian besar responden (85%)
juga mengatakan lokasi tempat mereka berdagang adalah lokasi yang strategis.
Lokasi-lokasi tempat mereka berdagang adalah lokasi yang banyak dilalui banyak
orang. Seperti lokasi dagang Krz (45 tahun) penjual rujak dan Pan (40 tahun)
penjual bakso. Lokasi jualan mereka berada di pinggir jalan perkampungan yang
sering dilewati orang baik yang berkendaraan maupun pejalan kaki, selain itu juga
tempat mangkal mereka berdekatan dengan pangkalan ojek dan warung
kelontong. Responden lainnya adalah Dw (35 tahun), Edg (40 tahun), Ahm (50
tahun), dan Snt (45 tahun). Lokasi jualan mereka terletak di SDN V dan sebuah
sekolah Madrasah Ibtidaiyah, pembeli mereka pada umumnya adalah anak-anak
SD yang bersekolah pada pagi dan siang hari.
Berbeda halnya dengan kedua karakteristik di atas, sebagian besar
responden mengatakan bahwa modal yang mereka peroleh selama ini belum
mencukupi dalam menjalankan usaha. Dengan kondisi seperti sekarang ini dimana
harga barang-barang melambung tinggi, merekapun harus menyesuaikan dengan
kondisi tersebut. Kondisi tersebut diakui Snt (45 tahun).
“......Dibilang cukup sih ya engga mba, tapi ya dicukup-cukupin. Kalo cukup itu kan duit yang ada cukup buat biayain kebutuhan kita, tapi sekarang kan duitnya sedikit kebutuhannya banyak. Jadi duitnya dicukup-cukupin, walaupun banyak yang engga kebeli. Modal engga cukup, buat makan apalagi, yaa,, seadanya mba.....” (Snt, 45 tahun, mitra).
Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan etos kerja responden, sebagian
besar responden (65%) tidak termasuk ke dalam orang yang malas dan giat
69
bekerja (75%), serta seluruh responden menginginkan hidup yang layak.
Informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara mendalam, adakalanya
mereka memiliki rasa bosan/jenuh dalam menjalankan usahanya. Namun hal
tersebut masih dalam batas kewajaran, tidak sampai membuat mereka menjadi
orang yang malas bekerja apalagi tidak bekerja, karena pada dasarnya mereka
menyadari apabila mereka malas/tidak bekerja maka mereka tidak dapat
meneruskan kehidupannya, dan apabila mereka berada pada kondisi tersebut,
biasanya mereka termotivasi dengan melihat kesuksesan teman, seperti yang
dikatakan Pan (40 tahun).
“... Ya malu mba kalo ngga kerja, masa temen-temen pada sukses kita sendiri malah ngoyo, kan kalo ngeliat temen maju kita juga pengen mba. Lagian kalo kita engga kerja, ntar anak bini mau dikasih makan apa?.. yang ada aja dijalanin, kalo kitanya tekun ntar juga maju, sedikit-demi sedikit, orang kan ngga langsung kaya mba, usaha dulu kan??...” (Pan, 40 tahun, mitra).
Berkaitan dengan tingkat dukungan keluarga, usaha seluruh responden
didukung oleh anggota keluarga lainnya, sebesar 75 persen anggota keluarganya
membantu dalam proses produksi dan hanya 20 persen yang anggota keluarganya
membantu dalam proses pemasaran. Pada umumnya proses produksi berkaitan
dengan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan pada saat berjualan, menyiapkan
bahan baku, dan mengolah bahan baku menjadi bahan yang sudah jadi/matang.
Proses pemasaran dengan membantu dalam memasarkan barang dagangannya.
Pola produksi dan konsumsi keluarga adalah yang berkaitan dengan pola
hidup keluarga. Sebanyak 20 persen responden mereka tidak bisa
menabung/menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disimpan, 80 persen
tergolong memiliki pola hidup hemat, seluruh responden tidak pernah membeli
barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan, dan 25 persen sering meminjam
70
uang kepada orang lain. Alasan mereka tidak bisa menabung adalah karena antara
penghasilan dan pendapatan tidak sesuai sehingga mereka tidak bisa menyisihkan
uang, dengan uang yang sedikit, mereka harus mampu untuk menghemat
pengeluaran mereka yang berkaitan dengan konsumsi keluarga.
6.2.2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan kemiskinan
yang bukan berasal dari dalam diri seseorang, melainkan yang berasal dari
lingkungan, baik yang terkait dengan alam (bencana), akses terhadap sesuatu
(tertutup/terbuka), kebijakan-kebijakan maupun yang berkaitan dengan manusia
lainnya. Berikut Tabel 31 yang menyajikan faktor-faktor eksternal yang
menyebabkan seseorang menjadi miskin.
Tabel 31. Faktor-faktor Eksternal yang Menyebabkan Kemiskinan, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Karakteristik Jawaban
Ya Tidak Jiwa % Jiwa %
1. Kesulitan mendapatkan pekerjaan 17 85 3 15 2. Kesulitan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan 18 90 2 10
3. Kesulitan memperoleh akses pendidikan - - 20 100 4. Kesulitan memperoleh akses kesehatan - - 20 100 5. Sering terjadi bencana alam (seperti banjir,
kebakaran, dll) 20 100 - -
6. Kondisi tersebut merugikan usaha Anda 20 100 - - 7. Kesulitan memperoleh bahan baku dagangan 11 55 9 45 8. Keterjangkauan harga - - 20 100 9. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM
berpengaruh terhadap usaha 20 100 - -
10. Kondisi tersebut merugikan usaha 20 100 - -
Sebanyak 85 persen responden merasa kesulitan dalam mendapatkan
pekerjaan di Jakarta, khususnya di Bidaracina dan 90 persen kesulitan dalam
71
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kondisi tersebut menunjukkan
kondisi yang cukup ironis, dimana ketika pada gambaran umum kelurahan
dijelaskan potensi Kelurahan yang cukup besar, baik dari segi lapangan pekerjaan
maupun banyaknya lembaga pendidikan. Namun melalui wawancara mendalam
ternyata peneliti memperoleh informasi tambahan, bahwa lembaga ekonomi yang
ada di wilayah kelurahan Bidaracina tidak hanya memperkerjakan warga setempat
saja, melainkan juga orang-orang luar Bidaracina, dan pada umumnya orang-
orang yang bekerja di lembaga-lembaga ekonomi tersebut sudah lama bekerja.
Untuk masalah banyaknya lembaga pendidikan namun responden merasa
kesulitan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dikarenakan lembaga
pendidikan yang ada adalah lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA, dan
PT), sedangkan responden tidak mungkin mengenyam pendidikan tersebut.
Hal di atas berbeda dengan jawaban responden mengenai akses terhadap
pendidikan dan kesehatan. Seluruh responden memiliki akses terhadap pendidikan
dan kesehatan. Hal tersebut dilihat dari mudahnya mereka menyekolahkan anak-
anak mereka karena biaya SPP gratis, dan mudahnya mereka jika mengurus
administrasi jika mereka pergi ke rumah sakit, karena sudah ada kartu Gakin
(Keluarga Miskin).
Terkait dengan masaah bencana alam yang melanda, seluruh responden
sering terjadi bencana alam berupa banjir di Jakarta, khususnya di Bidaracina.
Biasanya banjir terjadi setiap awal tahun sekitar bulan Februari-Maret, banjir
tersebut merupakan rutinan yang terjadi setiap kali musim hujan, dan yang paling
parah adalah banjir rutinan yang terjadi setiap lima tahun sekali. Banjir tahunan
tidak begitu parah, biasa hanya semata kaki sampai selutut orang dewasa. Namun
72
banjir yang terjadi lima tahun sekali terjadi sangat besar, terakhir terjadi pada
tahun 2006, dimana hampir seluruh rumah responden dan warga Jakarta lainnya
hanyut terbawa luapan aliran sungai Ciliwung yang begitu deras. Banjir tahun
2006 menyebabkan kerugian yang sangat besar, hampir seluruh harta benda
responden habis terbawa arus air, termasuk barang dagangan, gerobak, dan
perlengkapan jualan mereka lainnya. Pasca banjir 2006, mereka benar-benar harus
memulai lagi dari awal. Bahkan sebagian besar responden tidak bisa
mengembalikan pinjaman ke MM.
Berkaitan dengan stok bahan baku dan keterjangkauan harganya, 55
persen responden kesulitan memperoleh bahan baku, dan seluruh responden
menyatakan harga bahan baku saat ini tidak dapat dijangkau. Menurut mereka
harga bahan baku saat ini sudah sangat melambung tinggi. Hal tersebut berkaitan
dengan kebijakan pemerintah yang telah dua kali menaikkan harga BBM sejak
tahun 2006 hingga kini. Seluruh responden menganggap kebijakan tersebut sangat
mempengaruhi usaha mereka, dan seluruhnya sepakat jika pengaruh yang
ditimbulkan adalah pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan usaha bahkan
hidup mereka. Sebelum harga BBM naik, mereka masih bisa mendapatkan
keuntungan yang lebih besar, karena biaya produksinya lebih sedikit, tetapi
sekarang mereka tidak bisa menekan biaya produksi, seperti yang diutarakan Ahm
(50 tahun).
“Sekarang mah mau dagang apa-apa juga susah, harga barang-barang ngga kaya dulu, sekarang mah susah. Kalo mau usaha harus modalnya gede sekalian, kalo kecil mah nanggung, malah bikin rugi. Rakyat makin kecekek. Beli ini mahal, beli itu mahal, saingan banyak, yang beli makin sedikit.. susah mba sekarang mah, dagangan abis aja sekarang mah udah untung, apalagi kalo untung....” (Ahm, 50 tahun, mitra).
73
Hal senada juga diutarakan Snt (45 tahun) dan istrinya, mereka
mengatakan bahwa beban hidup semakin berat, dengan harga barang-barang yang
melambung tinggi. Pedagang kecil semakin terjepit, dengan kondisi seperti ini,
penghasilan kecil. Dengan naiknya harga BBM maka berimplikasi terhadap
kenaikan harga-harga/biaya hidup lainnya, seperti biaya transportasi, listrik,
sembako, dll.
“......Sebenernya hasil usahanya gedean sekarang dibanding dulu, misalnya dulu dapet 50.000, sekarang 60.000, tapi keuntungannya sekarang jauh lebih kecil, karena modalnya sekarang mah gede banget. Dulu untungnya bisa 25.000-30.000, sekarang mah 10.000 aja udah untung. Jadi kalo diitung-itung sih sekarang malah tambah buntung, udah ga sesuai antara penghasilan sama pengeluaran....” (Snt, 45 tahun, mitra)
6.3. Ikhtisar
Karakteristik rumah tangga penerima zakat terdiri dari: karakteristik
bangunan rumah; kepemilikan aset pribadi; dan pendapatan. Karakteristik tersebut
merupakan parameter yang digunakan MM untuk menyatakan layak tidaknya
seseorang untuk menjadi mitra. Seseorang layak menjadi mitra apabila sekurang-
kurangnya dua karakteristik tersebut dinyatakan layak. Seluruh responden peneliti
dinyatakan layak mendapatkan bantuan MM.
Karakteristik bangunan rumah terdiri dari ukuran rumah yang terdiri dari
sangat kecil (<4m2), kecil (4-6m2), sedang (6-8m2), dan besar (8m2); jenis dinding
yang terbuat dari bilik bambu/kayu, semi, dan tembok/beton; jenis lantai terdiri
dari tanah, panggung, semen, dan keramik; jenis atap terdiri kirai/ijuk,
genteng/seng, dan asbes/berglazur; kepemilikan rumah, terdiri dari rumah
menumpang, kontrak, milik keluarga, dan sendiri; dapur (alat masak) terdiri dari
tungku, kompor minyak, kompor gas/listrik; dan jenis kursi yang terdiri dari
74
lesehan, balai bambu, kayu, dan sofa. Warga yang dianggap miskin dan dikatakan
kayak menjadi mitra adalah yang memiliki indikator karakteristik bangunan
rumah dengan indeks rumah yang memiliki ukuran minimal.
Karakteristik kepemilikan aset pribadi terdiri dari kepemilikan
kebun/sawah, elektronik, kendaraan, ternak, dan simpanan. Seperti halnya dengan
indikator karakteristik bangunan rumah, warga yang dianggap miskin adalah yang
memiliki indikator kepemilikan aset pribadi yang merupakan kepemilikan aset
pribadi minimal.
Karakteristik pendapatan adalah calon mitra yang memiliki pendapatan
usaha pokok/keuntungan usaha dibawah Rp 30.000 perhari, standar ini merupakan
kriteria pendapatan yang digunakan MM untuk warga miskin perkotaan yang akan
menjadi mitranya. Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan
MM dalam menentukan kriteria kemiskinan sekaligus menentukan kelayakan
warga untuk menjadi mitra.
Faktor-faktor penyebab kemiskinan terdiri dari dua, yaitu faktor internal
dan eksternal, faktor internal yang paling dominan adalah rendahnya modal yang
mereka peroleh dan tidak bisanya mereka menyisihkan uang (menabung). Faktor
eksternal, yaitu kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM, bencana
alam (banjir), dan sempitnya lapangan pekerjaan. Kenaikan harga BBM dan
bencana banjir yang melanda Jakarta tahun 1996 adalah faktor penyebab langsung
yang menyebabkan mitra menjadi miskin/tambah miskin. Kenaikan harga BBM
berimplikasi pada kenaikan harga bahan sembilan pokok (sembako) dan harga-
harga lainnya seperti ongkos (trasnportasi), sedangkan sempitnya lapangan
pekerjaan adalah faktor yang tidak langsung mempengaruhi mereka.
75
BAB VII
PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP
KEBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN
Pengaruh pendayagunaan zakat terhadap keberdayaan rumah tangga
miskin dilihat dari apakah dana yang diberikan MM digunakan untuk kebutuhan-
kebutuhan sebagai berikut: kebutuhan non-produktif (konsumsi rumah tangga),
investasi SDM (pendidikan dan kesehatan), ekonomi produktif (wirausaha,
tabungan, investasi). Mitra dikatakan berdaya apabila dana bantuan MM
digunakan untuk dua kebutuhan terakhir. Berikut ini adalah data yang dapat
disajikan peneliti.
7.1. Ekonomi Produktif (Modal Usaha, dan Tabungan)
Pinjaman dana MM digunakan untuk kebutuhan ekonomi produktif agar
usaha yang dijalankan mitra dapat berjalan dengan kontinyu, dan agar mitra dapat
menjadikan dana tersebut sebagai simpanan apabila dikemudian hari dana tersebut
dibutuhkan. Peneliti membagi kebutuhan ekonomi produktif tersebut ke dalam
dua kategori.
a. Modal Usaha
Modal usaha yang dimaksud adalah modal yang digunakan untuk
melanjutkan usaha yang selama ini dilakukan, modal usaha tersebut dimaksudkan
agar para mitra dapat melanjutkan usahanya setiap hari, modal usaha digunakan
untuk membeli bahan baku dagangan mitra. Seluruh responden menggunakan
bantuan dana MM untuk modal usaha digunakan kembali untuk melanjutkan
usaha setiap harinya. Namun dalam kenyataannya tidak selamanya modal usaha
76
tersebut sama besar setiap harinya. Seperti yang diungkapkan Pan (40 tahun)
berikut.
“.....Kalo masalah modal mah mba tergantung rejeki, kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil, tergantung dapetnya berapa sehari itu. Tapi emang duitnya harus muter lagi buat modal, kalo engga entar saya modalnya darimana lagi. Pinter-pinternya kita aja buat ngelola duit....” (Pan, 40 tahun, mitra).
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Dw (35 tahun), ia juga
mengatakan bahwa modal harus tetap berputar, walaupun tidak besar, tetapi harus
tetap dikelola dengan baik. Kalau hari ini jualan, maka esokpun harus kembali
berjualan, meskipun dengan modal usaha yang berbeda.
b. Tabungan
Selain modal usaha, kebutuhan ekonomi produktif juga terdiri dari
tabungan. Tabungan ditujukan agar mitra dapat menjadikan dana tersebut sebagai
simpanan apabila dikemudian hari dana tersebut dtuhkan untuk modal usaha atau
kebutuhan lainnya. Dari seluruh responden, hanya 20 persen yang dapat
menyisihkan pendapatannya untuk disimpan/ditabung, yaitu sebesar Rp.1000-
Rp.5.000 perhari. Sedangkan sisanya mengatakan tidak dapat menyisihkan
pendapatannya untuk ditabung karena terlalu banyak pengeluaran. Responden
yang dapat menyisihkan pendapatannya diantaranya adalah El (36 tahun) yang
merupakan istri dari Snt (45 tahun).
“........ Ya, cukup ngga cukup kalo saya mah prinsipnya harus ada yang disimpen, mau seribu ke, dua ribu ke, yang penting nyimpen. Biasanya saya nyimpen sama tetangga yang emang suka megang tabungan, atau kalo engga di sekolah anak, setiap harinya nabung seribu, seribu, kan ntar lumayan juga hasilnya”. (El, 36 tahun, mitra).
7.2. Investasi SDM (Pendidikan dan Kesehatan)
Keberdayaan selanjutnya adalah dalam hal bagaimana responden
menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk kebutuhan pendidikan anak-
77
anaknya dan kesehatan keluarga. Dari data yang diperoleh seluruh responden
mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga tetapi
dengan jumlah yang berbeda-beda. Tabel 32 yang menyajikan kondisi tersebut.
Tabel 32. Pengeluaran Responden untuk Pendidikan, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Kategori (Rupiah/hari) Jumlah Responden
Jiwa % 1. Rp. 10.000-Rp. 15.000 11 55 2. Rp. 15.100-Rp. 20.000 6 30 3. Rp. 20.100-Rp. 25.000 3 15
Berdasarkan data pada Tabel 32, responden yang pengeluarannya untuk
pendidikan keluarga sebesar Rp. 10.000-Rp. 15.000 sebanyak 55 persen, Rp.
15.100-Rp. 20.000 sebanyak 30 persen, dan Rp. 20.100-Rp. 25.000 sebanyak 15
persen. Perbedaan tersebut disebabkan oleh jumlah anak masing-masing
responden usia sekolah, jenjang pendidikan, dan jarak antara rumah dan sekolah.
Responden pada kategori pertama pada umumnya adalah responden yang
memiliki anak usia sekolah sekitar 1-3 orang dan jarak antara rumah dan sekolah
yang relatif dekat, bahkan ada yang tidak menggunakan ongkos transportasi,
seperti halnya dengan keluarga Snt (45 tahun), jarak sekolah ketiga anaknya
dengan rumah relatif dekat, tidak perlu ongkos transport, hanya dibutuhkan uang
jajan saja.
Responden pada kategori kedua pada umumnya responden yang memiliki
anak usia sekolah lebih dari tiga, dan responden pada kategori ketiga adalah
responden yang memiliki anak usia sekolah yang jenjangnya lebih tinggi (SMP-
SMA), dan jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh sehingga membutuhkan
transport yang cukup besar.
78
Seluruh responden mengeluarkan biaya untuk pendidikan anaknya
meskipun dengan jumlah yang berbeda-beda. Namun hal tersebut menunjukkan
adanya kepedulian responden tentang pendidikan bagi anak-anak mereka.
Walaupun dengan kehidupan yang sederhana, mereka masih mempunyai harapan
yang tinggi untuk anak-anak mereka, seperti yang diungkapkan Snt (45 tahun) dan
istri (El, 36 tahun).
“.....Anak saya yang paling besar mau masuk SMP. Sebenernya saya ga punya duit, tapi karena anaknya mau sekolah, nilai-nilainya juga bagus, saya nekat aja nyekolahin biar dia engga kaya saya. Saya juga bingung mba belum ada uang masuknya, beli baju, buku-buku. Ya.. walaupun SPP gratis, kan tetep aja harus beli ini, itu, tetek bengek, kan pake duit mba.....” (Snt, 45 tahun, mitra). Terkait dengan lokasi kesehatan, responden tidak mengalokasikan secara
khusus, karena bersifat insidental, tidak direncanakan dan tidak dapat diprediksi.
Pada umumnya apabila mereka sakit, biasanya hanya menggunakan obat-obatan
yang dijual di warung-warung. Namun apabila sakit yang diderita cukup parah,
sehingga harus dirawat di rumah sakit, umumnya mereka menggunakan Surat
Keterangan Keluarga Miskin yang dikeluarkan RT/RW/Kelurahan setempat,
sehingga mereka diringankan secara pembiayaan, seperti yang diutarakan Ahm
(50 tahun).
“Ya kalo sakitnya Cuma puyeng-puyeng sedikit mah minum aja obat warung. Tapi kalo sakitnya parah, ya ke dokter/rumah sakit, tinggal bawa surat keterangan keluarga miskin dari RT/RW/Kelurahan, nanti ada keringanan dari pihak rumah sakit. Jadi intinya untuk biaya kesehatan di sini mah ngga ada yang dianggarin khusus. Masa sakit direncanain mba....” (Ahm, 50 tahun, mitra).
7.3. Kebutuhan Non-produktif (Konsumsi Rumah Tangga)
Idealnya usaha yang dilakukan responden adalah untuk menyejahterakan
kehidupan responden, apabila kebutuhan usahanya telah terpenuhi maka akan
79
sangat baik sekali jika penghasilan dari usahanya dapat ditabung dan digunakan
untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Tetapi sebaliknya, akan menjadi sangat
tidak produktif apabila dana bantuan yang diberikan sebagian besar digunakan
hanya untuk konsumsi keluarga, bahkan untuk usahanya sendiri tidak terpenuhi.
Hal inilah yang dilihat lebih jauh lagi, bagaimana responden menggunakan
bantuan dana yang diberikan dengan produktif.
Sebagian besar responden tidak sepenuhnya menggunakan bantuan dana
untuk kebutuhan usahanya, beberapa diantaranya yang menggunakannya untuk
kebutuhan rumah tangga. Namun tidak ada yang sampai tidak mempunyai modal
untuk usaha berikutnya, jika mereka menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan
rumah tangga, biasanya mereka harus mengurangi modal yang digunakan usaha
selanjutnya, misalnya yang seharusnya modal untuk hari esok Rp. 70.000, karena
kebutuhan mendesak mereka menguranginya menjadi Rp.50.000 untuk
pengeluaran kebutuhan rumah tangga.
Namun kondisi tersebut berlangsung terus menerus, sehingga modal yang
digunakan sebagian besar responden (70%) relatif semakin berkurang setiap
harinya, 20 persen mengatakan tetap, dan 10 persen mengatakan naik. Responden
yang modal usahanya berkurang setiap harinya mengatakan bahwa modal tersebut
dapat berkurang karena sebagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
seperti yang diutarakan Pan (40 tahun).
“...... Secara umum sih modal semakin berkurang mba. Ya.. engga setiap hari menurun sih, tapi rata-rata kalo saya itung-itung lama-lama ya makin berkurang, yang paling sering sih dipake buat kebutuhan makan keluarga sama sekolahnya. Ya.. kalo lagi ga ada duit, modalnya diputer dulu. Ntar ditambahin lagi, ya.. gali lobang tutup lobanglah mba, apallagi sekarang apa-apa makin mahal, selalu aja ada yang kurang” (Pan, 40 tahun, mitra).
80
Hal serupa juga dikatakan Sprn (35 tahun) selaku sebagai Ketua RT 005
sekaligus Ketua dari Gerai Sembako Murah (GSM) bahwa terkadang dana
pinjaman tersebut digunakan para mitra untuk kebutuhan pokok rumah tangga
sehari-hari karena terpaksa.
“......... Kalau sudah terpaksa, biasanya uang pinjaman MM digunakan mitra untuk kebutuhan dapurnya mba, mereka tahu kalau itu sebenarnya ga boleh, tapi mau gimana lagi, kalau udah kepepet mah susah lagi mau cari uang dari mana, ya kalau gitu saya mau gimana lagi, mau ngelarang juga susah, ntar anak istrinya ga makan.” (Sprn, 35 tahun, ketua RT).
7.4. Ikhtisar
Pengaruh pendayagunaan dana pinjaman dapat menjadikan para mitra
berdaya apabila dana tersebut digunakan untuk kebutuhan usaha ekonomi
produktif, yakni dapat digunakan untuk modal usaha, dan tabungan, serta untuk
investasi SDM, yakni untuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan yang dikatakan
tidak memberdayakan apabila dana tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi
rumah tangga. Usaha mitra dapat dikatakn berhasil apabila pendapatannya dapat
digunakan untuk kesejahteraan keluarga, tetapi apabila pinjaman yang dijadikan
sebagai modal usaha digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga, maka
kondisi tersebut tidak menunjukkan keberdayaan, melainkan sebaliknya.
Dana pinjaman MM digunakan sebagian besar responden sebagai modal
usaha, jumlahnya disesuaikan dengan skala usaha mereka masing-masing,
sedangkan untuk menabung, hanya 20 persen mitra yang melakukannya. Bagi
mitra yang tidak dapat menyisihkan uang mereka mengatakan bahwa tidak ada
alokasi dana untuk ditabung, pada umumnya dana tersebut selalu ada alokasinya
untuk hal-hal yang mereka anggap lebih penting daripada menabung. Bagi
responden yang bisa menyisihkan pendapatannya mengatakan jumlah uang yang
81
mereka sisihkan tidak besar, tetapi kontinyu dilakukan, tujuannya adalah untuk
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di kemudian hari.
Investasi SDM dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk
kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga. Sebagian besar responden (55%)
mengeluarkan biaya Rp 10.000-15.000 perhari untuk pendidikan, pada umumnya
mereka memiliki anak usia sekolah sekitar 1-3 orang dan jarak antara rumah dan
sekolah yang relatif dekat, bahkan ada yang tidak menggunakan ongkos transport,
sedangkan untuk alokasi kesehatan, mereka tidak mengalokasikan secara khusus,
karena bersifat insidental, tidak direncanakan dan tidak dapat diprediksi.
Sebagian besar responden tidak sepenuhnya menggunakan bantuan dana
untuk kebutuhan usahanya, ada beberapa diantaranya yang menggunakannya
untuk kebutuhan rumah tangga. Namun tidak ada yang sampai tidak mempunyai
modal untuk usaha berikutnya, jika mereka menggunakan dana tersebut untuk
kebutuhan rumah tangga, biasanya mereka harus mengurangi modal yang
digunakan usaha selanjutnya, misalnya yang seharusnya modal untuk hari esok
Rp. 70.000, karena kebutuhan mendesak mereka menguranginya menjadi
Rp.50.000 untuk pengeluaran kebutuhan rumah tangga.
Namun kondisi tersebut berlangsung terus menerus, sehingga modal yang
digunakan sebagian besar responden (70%) relatif semakin berkurang setiap
harinya, 20 persen mengatakan tetap, dan 10 persen mengatakan naik. Responden
yang modal usahanya berkurang setiap harinya mengatakan bahwa modal tersebut
dapat berkurang karena sebagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
Kondisi tersebut dipicu dengan naiknya seluruh komoditi sembako, sehingga
dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini responden belum berdaya.
82
BAB VIII
PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA
MISKIN
8.1. Omset Usaha Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan Pinjaman
Sebelum mendapatkan bantuan, pada umumnya responden telah
melakukan usaha yang sama. Mereka sudah lama berdagang, dan omset
hariannyapun tidak menentu setiap harinya, ada diantara mereka yang mengalami
kenaikan omset usaha, namun ada juga yang sebaliknya. Tabel 33 menunjukkan
peruabahan omset usaha responden sebelum dan setelah mendapatkan pinjaman
MM.
Tabel 33. Omset Usaha Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan Pinjaman, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Nama Omset Usaha (per hari) Keterangan Sebelum Setelah 1. Irs 120.000 130.000 Naik 2. Edg 130.000 100.000 Turun 3. Msl 90.000 100.000 Naik 4. Pan 500.000 460.000 Turun 5. Snr 250.000 300.000 Naik 6. Kmt 260.000 300.000 Naik 7. Ahm 150.000 170.000 Naik 8. Snt 100.000 120.000 Naik 9. Sbr 180.000 220.000 Naik 10. Dtm 140.000 170.000 Naik 11. Krz 230.000 200.000 Turun 12. Nrz 240.000 200.000 Turun 13. Tkn 330.000 350.000 Naik 14. Lgk 230.000 260.000 Naik 15. Stm 237.000 250.000 Naik 16. Smn 100.000 150.000 Naik 17. Mar 120.000 150.000 Naik 18. Dw 210.000 150.000 Turun 19. Muj 165.000 150.000 Turun 20. Bjr 70.000 100.000 Naik
83
Berdasarkan Tabel 33, dari total responden, 70 persen diantaranya
menyatakan bahwa omset usaha setelah mendapatkan bantuan lebih tinggi
dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan, Dengan kata lain, bantuan tersebut
menaikkan omset usaha mereka. Sedangkan sisanya sebanyak 30 persen
menyatakan bahwa omset usaha setelah mendapatkan bantuan lebih rendah
dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan.
Responden yang omsetnya meningkat setelah mendapatkan bantuan dari
MM, mengatakan bahwa dengan bantuan MM, mereka memiliki modal yang lebih
dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan. Modal tersebut biasanya digunakan
untuk menambah komoditi dagangan, membeli gerobak agar barang dagangan
mereka terlihat lebih menarik perhatian, seperti yang diutarakan Ahm (50 tahun)
berikut.
“.. Ya sebenernya ngebantu juga sih mba, yang tadinya kita modalnya sedikit, setelah dapet bantuan jadi nambah lagi walaupun ga banyak. Ya..pinter-pinter kita aja gunainnya buat apa, kalo saya sih buat nambahin barang dagangan sama benerin gerobak yang rusak...” (Ahm, 50 tahun, mitra).
Sedangkan bagi responden yang omset usahanya menurun setelah
mandapatkan bantuan mengatakan bahwa salah satu penyebab menurunnya omset
usaha mereka adalah karena persaingan yang semakin kuat, dan daya beli
masyarakat yang semakin rendah. Salah satu yang mengatakan demikian adalah
Dw (35 tahun).
“Sekarang ini banyak orang yang nyoba untuk usaha berdagang, apalagi usaha kaya saya ini banyak dilakukan juga sama orang lain, gampang kok cuma jualan makanan anak sekolah, juice buah dan juice minuman ringan. Udah gitu anak-anak mah kan suka cari jajanan yang paling murah. Walaupun jauh dibela-belain, makanya saya harus bersaing harga, biar untung sedikit tapi lancar....” (Dw, 35 tahun, mitra).
84
8.2. Laba Usaha Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan Pinjaman
Setelah mendapatkan pinjaman modal dari MM, para mitra berharap usaha
mereka akan mengalami perubahan yang lebih baik, yaitu berupa peningkatan,
baik dari segi omset usaha, laba, dan lebih jauh lagi dapat meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Namun pada kenyataannya,
kondisi tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka, sebagian kecil responden
merasakan peningkatan tersebut, sebagian kecil lainnya tetap dan sebagian besar
lainnya justru merasakan sebaliknya. Berikut ini disajikan Tabel 34 yang
menunjukkan perubahan laba usaha mitra sebelum dan setelah mendapatkan
pinjaman modal dari MM.
Tabel 34. Laba Usaha Mitra Sebelum dan Setelah Mendapatkan Pinjaman, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Nama Laba Usaha (per hari) Keterangan Sebelum Setelah1. Irs 20.000 20.000 Tetap 2. Edg 30.000 10.000 Turun 3. Msl 30.000 25.000 Turun 4. Pan 30.000 15.000 Turun 5. Snr 50.000 30.000 Turun 6. Kmt 50.000 25.000 Turun 7. Ahm 30.000 20.000 Turun 8. Snt 20.000 10.000 Turun 9. Sbr 40.000 60.000 Naik 10. Dtm 30.000 30.000 Tetap 11. Krz 30.000 10.000 Turun 12. Nrz 30.000 15.000 Turun 13. Tkn 25.000 10.000 Turun 14. Lgk 25.000 25.000 Tetap 15. Stm 30.000 25.000 Turun 16. Smn 30.000 35.000 Naik 17. Mar 30.000 30.000 Tetap 18. Dw 30.000 30.000 Tetap 19. Muj 35.000 20.000 Turun 20. Bjr 20.000 25.000 Naik
85
Data pada Tabel 34 menunjukkan bahwa pada umumnya laba yang
diperoleh responden setelah mendapatkan bantuan adalah menurun (60%), diikuti
tetap (25%) dan naik (15%). Sebagian besar Omset usaha responden naik setelah
mendapatkan bantuan, namun laba yang diperoleh tidak otomatis naik mengikuti
Omset usaha. Penyebabnya adalah semakin mahalnya bahan baku yang mereka
gunakan sehari-hari sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. Hal tersebut
diutarakan oleh Ahm (50 tahun) berikut ini.
“...Sekarang mah neng jaman serba susah, kita Cuma punya modal aja belum tentu untung, pengahsilan usaha kita naek juga belum tentu untungnya juga naek. Sekarang apa-apa serba mahal, naek penghasilan usaha sedikit, harga bahan bakunya naek banyak, gimana mau untung gede, mending dulu walaupun untung sedikit, tapi harga-harga masih murah.....” (Ahm, 50 tahun, mitra)
Ahm (50 tahun) juga kemudian menambahkan bahwa kondisi yang sulit
ini bukan disebabkan karena pemberian pinjaman MM.
“...... Wah kalo angga ada pinjaman MM malah lebih susah lagi mba, keguriannya lebih besar barang kali. Modal usaha bukan satu-satunya faktor bagi pedagang mba, tapi juga perlu diperhatikan kondisi ekonomi, harga sembako, harga minyak, dan hagra-harga yang laennya. Kalo modalnya gede, tapi keadaannya gini-gini aja, ya agak susah mba buat bertahan.” (Ahm, 50 tahun, mitra).
Kondisi tersebut juga terjadi pada usaha Pan (40 tahun). Menurutnya
usaha yang dilakukannya selama ini tidak mengalami peningkatan, justru
sebaliknya. Alasan yang sama juga disampaikan seperti yang diutarakan Ahm (50
tahun). Namun ia menambahkan alasan lainnya yaitu banyaknya saingan usaha
yang memiliki usaha sejenis. Menurutnya, sempitnya lapangan pekerjaan dan
susahnya tinggal di Jakarta yang menyebabkan hal tersebut, orang-orang lebih
tertarik untuk berjualan karena berjualan dianggap usaha yang paling mudah dan
tidak membutuhkan keahlian khusus.
“.... Sekarang sih mba harga bahan-bahan pada mahal, minyak tanah, minyak goreng, tepung terigu, pokoknya semuanya mahal, jadi susah kalo mau meningkat, trus kalo sekarang banyak banget saingan yang juga
86
jualan bakso, dulu mah masih sepi. Ya...tapi saya juga ga bisa nyalahin, orang sama-sama usaha, abisnya jualan mah paling gampang sih mba, ngga perlu pake keahlian, Cuma modal duit ama nekat.” (Pan, 40 tahun, mitra). Menurut Sekretaris Pengelola Program MM di Bidaracina, Abd (47 tahun)
kondisi tersebut merata di seluruh wilayah Binaan MM, karena kebijakan
kenaikan BBM adalah kebijakan nasional, yang berdampak pada peningkatan
harga-harga bahan-bahan lainnya dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,
terutama yang berada di dalam kemiskinan.
Memang kondisi kaya sekarang ini dialami oleh seluruh rakyat termasuk saya, walaupun pekerjaan saya bukan dagang seperti mitra, tapi mau bagaimana lagi. Kalau orang besar sudah ngomong A, ya orang kecil harus ngikutin.....” (Abd, 47 tahun, Pengelola). Berbeda dengan pendapat Ahm (50 tahun), Dw (35 tahun) mengatakan
bahwa keuntungan usaha ia sebelum dan setelah mendapatkan bantuan cenderung
relatif tetap. Dw (35 tahun) memberikan alasan yang sama dengan pada saat
omset ia menurun. Pada intinya omset yang besar tidak secara otomatis
keuntungannya juga besar, bisa saja tetap atau bahkan turun.
“....Mau dulu apa sekarang, saya ngerasanya sama aja mba, abisnya saya bukan orang yang suka ngitung-ngitung banget, trus harus dirinci kaya gini kaya gitu. Ya...emang gitu-gitu aja” (Dw, 35 tahun, mitra).
8.3. Pendapatan Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan Pinjaman Seperti halnya dengan Omset dan laba usaha, pendapatan mitra setelah dan
sebelum mendapatkan bantuan mengalami perubahan, yaitu peningkatan dan
penurunan. Namun ada juga mitra yang pendapatannya tetap. Berikut ini Tabel 35
yang menunjukkan kondisi tersebut.
87
Tabel 35. Pendapatan Usaha Responden Sebelum dan Setelah Mendapatkan Pinjaman, Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Nama Jumlah Pendapatan (per hari) Keterangan Sebelum Setelah 1. Irs 10.000 15.000 Naik 2. Edg -95.000 -135.000 Turun 3. Msl 30.000 20.000 Turun 4. Pan -200.000 20.000 Naik 5. Snr 30.000 20.000 Turun 6. Kmt 25.000 10.000 Turun 7. Ahm 35.000 20.000 Turun 8. Snt -150.000 -160.000 Turun 9. Sbr -115.000 -50.000 Naik 10. Dtm -83.000 10.000 Naik 11. Krz 30.000 10.000 Turun 12. Nrz 30.000 20.000 Turun 13. Tkn 30.000 10.000 Turun 14. Lgk 25.000 20.000 Turun 15. Stm 30.000 10.000 Turun 16. Smn 30.000 30.000 Tetap 17. Mar 30.000 20.000 Turun 18. Dw 30.000 15.000 Turun 19. Muj 35.000 30.000 Turun 20. Bjr 20.000 25.000 Naik
Tabel 35 menunjukkan bahwa ternyata pendapatan yang diperoleh oleh
sebagian besar responden (70%) setelah mendapatkan bantuan mengalami
penurunan, kenaikan dialami oleh 25 persen responden, dan sisanya sebanyak
lima persen tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan (tetap). Hal tersebut
merupakan sebuah kondisi yang tidak diharapkan, karena idealnya ketika mitra
diberikannya bantuan modal usaha, maka idealnya pendapatan merekapun terus
meningkat. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, kondisi tersebut berlaku
sebaliknya, setelah mendapatkan bantuan sebagian besar mitra menyatakan
pendapatannya malah berkurang. Tentu saja kondisi tersebut harus kita lihat lebih
dalam lagi, dengan melihat apakah penyebabnya dan bagaimanakah hal tersebut
bisa terjadi.
88
Menurut sebagian besar responden kondisi usaha mereka saat ini semakin
sulit karena kenaikan bahan-bahan dasar. Menurut Ahm (50 tahun) pendapatannya
mengalami penurunan karena mahalnya sembako (sembilan bahan pokok) sebagai
bahan bakunya untuk menjual bubur ayam seperti beras, minyak tanah, minyak
goreng, sayur-sayuran dan berimbas pada kenaikan barang-barang kebutuhan
lainnya termasuk juga kenaikan ongkos (transportasi). Meskipun omset usahanya
mengalami kenaikan, namun laba usaha dan pendapatannya menurun.
Keluarganya tidak memiliki pemasukan lain selain dari hasil usaha, sehingga
usaha yang saat ini mereka lakukan adalah satu-satunya usaha yang menghasilkan
uang.
“Kalo harga-harga sembako pada naik, pendapatan kita turun, tapi sebaliknya mba, kalo harga-harga pada turun, pendapatan kita yang naik. Sekarang kankeadaanya harga barang-barang pada naik, ya pasti pendapatan kita yang turun, tinggal pilih aja. Apalagi keluarga saya cuma ngandelin dari jualan, ngga ada lagi usaha lain, ya gini-gini aja dah. Ini aja udah bersyukur masih bisa makan sehari-hari...” (Ahm, 50 tahun, mitra). Namun demikian ada lima responden yang pendapatannya naik setelah
mendapatkan dana pinjaman MM, diantaranya adalah Irs (39 tahun). Irs (39
tahun) memiliki strategi untuk bisa tetap bertahan (survive) dalam menjalankan
usahanya. Hal ini tampaknya ada hubungan dengan perilaku kewiraswastaan
(enterpreneural behaviour) yang dimiliki oleh Irs (39 tahun). Hal tersebut
diindikasikan dengan perilaku inovational dalam hal perubahan strategi usaha
untuk menghadapi perubahan kondisi, diantaranya perubahan-perubahan
kebijakan pemerintah. Kondisi kenaikan harga-harga sembako tentu saja sangat
mempengaruhi, namun harus dapat disiasati, yaitu dengan mengurangi
kuantitas/jumlah produk usahanya.
89
“....Dulu mah saya jualan nasi uduk bisa-bisa sampai 10-15 liter, tapi sekarang mah cuma sekitar 6-7 liter, karena dulu saya jualannya dibantu orang tua, ditambah dulu saingan usaha masih sedikit. Kalo sekarang mah hampir setiap orang jualan, apalagi jualan nasi uduk kalo pagi-pagi, kalo saya tetep jualan kaya dulu bisa bangkrut ga ada yang beli..... Ya, gitu dah cara saya biar bisa bertahan” (Irs, 39 tahun, mitra). Pada umumnya para responden mengeluhkan kondisi usaha yang semakin
sulit, keadaan tersebut ternyata akar permasalannya adalah bukan terletak dari
bantuan itu sendiri. Namun, ada faktor eksternal lain yang muncul seperti yang
sudah dijelaskan dalam bab VI, bahwa faktor yang paling dominan yang
menyebabkan kondisi tersebut adalah adalah faktor kebijakan pemerintah yaitu
dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimplikasi terhadap
kenaikan biaya hidup lainnya seperti kenaikan Sembilan Bahan Pokok (Sembako)
yang merupakan bahan dasar jualan mereka, biaya transportasi (angkot, ojek, dll),
sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian bantuan modal usaha hanya dapat
membuat mitra untuk memutar modalnya saja, belum sampai tahap
menyejahterakan apalagi mengentaskan kemiskinan.
Namun sebaiknya responden lebih kreatif dalam memilih dan
memodifikasi produk jualan serta strategi-strategi usaha agar usaha yang
dilakukan dapat bertahan atau bahkan meningkat, walaupun dihadapkan pada
kondisi perekonomian yang sulit, seperti strategi usaha yang dilakukan oleh Irs
(39 tahun). Strategi usaha tersebut bisa dilakukan oleh semua responden yang
memiliki keinginan yang tinggi untuk tetap menjalankan usahanya.
Selain menggunakan karakteristik/kriteria penghasilan usaha pokok (laba
usaha) dari Program Urban Masyarakat Mandiri, peneliti juga melihat pendapatan
responden yang dibandingkan dengan Batas Garis Kemiskinan Sajogjo (dalam
Rusli, dkk, 1995), yaitu dengan melihat batas tingkat pendapatan (setara dengan
90
beras per kapita per tahun), dimana terdapat tiga kategori yaitu: 1) Miskin; 2)
Miskin Sekali; dan 3) Paling Miskin yang kemudian dibedakan menjadi wilayah
perkotaan dan pedesaan. Program Urban Masyarakat Mandiri berada di wilayah
perkotaan. Oleh karena itu, ukuran yang digunakan adalah ukuran untuk wilayah
perkotaan. Untuk wilayah perkotaan, rumah tangga yang dikatakan Miskin apabila
pendapatan perkapitanya per tahun setara dengan 480 kg beras, Miskin Sekali
setara dengan 360 kg, dan Paling Miskin setara dengan 270 kg. Jika disesuaikan
dengan kondisi perekonomian saat ini dimana harga beras berkisar antara Rp.
4.500-Rp. 6.000/kg. Untuk mendapatkan harga beras yang digunakan sebagai
acuan, maka peneliti menggunakan nilai tengah dari kisaran harga tersebut, yaitu
senilai Rp. 5.250/kg.
Selanjutnya untuk mendapatkan pendapatan per kapita per tahun, maka
jumlah beras pada masing-masing kategori dikalikan dengan harga beras saat ini,
sehingga diperoleh hasil pendapatan per kapita per tahun rumah tangga Miskin
adalah sebesar Rp. 2.520.000, Miskin Sekali sebesar Rp. 1.890.000, dan Paling
Miskin sebesar Rp. 1.417.500. Setelah mengetahui nilai tersebut, maka diperlukan
informasi mengenai pendapat responden sebelum mendapatkan pinjaman, dan
jumlah anggota keluarga. Untuk mengetahui besarnya pendapatan responden per
kapita per tahun, maka jumlah pendapatan dikalikan dengan 364 hari (satu tahun)
kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Untuk mengetahui kategori
responden, berikut disajikan informasi tersebut dalam Tabel 36.
91
Tabel 36. Pendapatan Perkapita Responden Berdasarkan Batas Garis Kemiskinan Sajogjo (dalam Rusli, dkk, 1995), Kelurahan Bidaracina, 2008.
No. Nama
Pendapatan Sebelum
Mendapatkan Pinjaman (Rp.)
Jumlah Anggota Keluarga
Pendapatan per kapita per tahun
(Rp.) Kategori
1. Irs 10.000 4 910.000 Paling Miskin
2. Edg -95.000 4 -8.645.000 Paling Miskin
3. Msl 30.000 2 5.460.000 Tidak Miskin
4. Pan -200.000 4 -18.200.000 Paling Miskin
5. Snr 30.000 5 2.184.000 Miskin Sekali
6. Kmt 25.000 4 2.275.000 Miskin 7. Ahm 35.000 6 2.123.333 Miskin
Sekali 8. Snt -150.000 6 -9.100.000 Paling
Miskin 9. Sbr -115.000 5 -8.372.000 Paling
Miskin 10. Dtm -83.000 7 -4.316.000 Paling
Miskin 11. Krz 30.000 3 3.640.000 Miskin
Sekali 12. Nrz 30.000 4 2.730.000 Tidak
Miskin 13. Tkn 30.000 5 2.184.000 Miskin 14. Lgk 25.000 5 1.820.000 Miskin
Sekali 15. Stm 30.000 5 2.184.000 Miskin 16. Smn 30.000 5 2.184.000 Miskin 17. Mar 30.000 4 2.730.000 Tidak
Miskin 18. Dw 30.000 4 2.730.000 Tidak
Miskin 19. Muj 35.000 3 4.246.666 Tidak
Miskin 20. Bjr 20.000 4 1.820.000 Miskin
Sekali
Penentuan kategori didasarkan pada pendapatan per kapita yang mendekati
pada setiap kategori. Beberapa pendapatan per kapita berada diantara dua
92
kategori, maka penetuan kategorinya adalah dengan melihat nilai antara
pendapatan per kapita dan kategori yang selisihnya lebih kecil. Tabel 36
menunjukkan bahwa responden yang berada pada kategori Miskin adalah
sebanyak 20 persen, Miskin Sekali 25 persen, Paling Miskin 30 persen, serta
responden yang tidak masuk ke dalam ketiga kategori karena pendapatan per
kapitanya di atas garis kemiskinan. Oleh karena itu, digunakan kategori Tidak
Miskin bagi para responden, yakni sebanyak 25 persen. Dengan kata lain dapat
disimpulkan bahwa sebanyak 75 persen responden berada di bawah Batas Garis
Kemiskinan Sajogjo (dalam Rusli, dkk, 1995), sedangkan sisanya sebanyak 25
persen berada di atas Batas Garis Kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa
responden yang berada di bawah Batas Garis Kemiskinan merupakan responden
yang layak mendapatkan pinjaman.
8.4. Ikhtisar
Secara umum omset usaha mitra mengalami kenaikkan. Dari total
responden, 70 persen diantaranya menyatakan bahwa omset usaha setelah
mendapatkan bantuan lebih tinggi dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan,
Dengan kata lain, bantuan tersebut menaikkan omset usaha mereka. Sedangkan
sisanya sebanyak 30 persen mitra menyatakan bahwa omset usaha setelah
mendapatkan bantuan lebih rendah dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan.
Responden yang omsetnya meningkat setelah mendapatkan bantuan dari
MM, mengatakan bahwa dengan bantuan MM, mereka memiliki modal yang lebih
dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan. Modal tersebut biasanya digunakan
untuk menambah komoditi dagangan, membeli gerobak agar barang dagangan
93
mereka terlihat lebih menarik perhatian. Sedangkan bagi responden yang omset
usahanya menurun setelah mandapatkan bantuan mengatakan bahwa salah satu
penyebab menurunnya omset usaha mereka adalah karena persaingan yang
semakin kuat, dan daya beli masyarakat yang semakin rendah.
Berbeda dengan omset usaha, sebagian besar mitra justru mengalami
penurunan pada laba/keuntungan usaha setelah mendapatkan pinjaman. Sebanyak
60 persen mitra mengalami penurunan laba, 25 persen tidak berubah baik sebelum
maupun setelah mendapatkan pinjaman, dan 15 persen mengalami kenaikan.
Kenaikan omset usaha tidak selalu berkorelasi positif terhadap peningkatan laba,
kondisi tersebut disebab semakin mahalnya bahan baku yang mereka gunakan
sehari-hari sebagai imbas dari kenaikan harga BBM.
Sama halnya dengan laba usaha, pendapatan sebagian besar mitra
mengalami penurunan setelah mendapatkan pinjaman, sebanyak 70 persen
mengalami penurunan, 25 persen mitra mengalami peningkatan, dan sisanya
sebanyak 5 persen tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan (tetap). Hal
tersebut disebabkan karena mahalnya sembako (sembilan bahan pokok) sebagai
bahan baku seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, sayur-sayuran dan
berimbas pada kenaikan barang-barang kebutuhan lainnya termasuk juga kenaikan
ongkos (transportasi).
Jika dilihat pendapatan responden menurut Garis Kemiskinan Sajogjo
(dalam Rusli, dkk, 1995), dapat disimpulkan bahwa sebanyak 75 persen
responden berada di bawah Batas Garis Kemiskinan, sedangkan sisanya sebanyak
25 persen berada di atas Batas Garis Kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa
94
responden yang berada di bawah Batas Garis Kemiskinan merupakan responden
yang layak mendapatkan pinjaman.
Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
pendayagunaan zakat yang disalurkan MM kepada masyarakat dhuafa/miskin
yang membutuhkan belum dapat mengentaskan kemiskinan. Karena bantuan yang
diberikan belum dapat mengeluarkan responden dari kemiskinannya. Pada
umumnya mereka hanya dapat memutar modalnya yang dalam kurun waktu
tertentu menjadi berkurang. Responden belum dapat meningkatkan kesejahteraan
keluarganya karena pendapatan yang mereka hasilkan saat ini masih minim.
Kondisi tersebut terkait juga oleh beberapa faktor seperti yang talah diuraikan
pada bab sebelumnya. Oleh karena itu perlu upaya-upaya yang lebih
komprehensif di kemudian hari untuk program pengentasan kemiskinan
selanjutnya.
95
BAB IX
PENUTUP
9.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Karakteristik rumah tangga penerima zakat terdiri dari: karakteristik bangunan
rumah; kepemilikan aset pribadi; dan pendapatan. Karakteristik bangunan
rumah dicirikan dengan tinggal di kontrakan/menumpang, rumah dengan
ukuran bangunan rumah sangat kecil (<4m2) atau kecil (4-6m2), dinding
rumah terbuat dari bilik/kayu/semi, lantai terbuat dari tanah dan
panggung/kayu, atap terbuat dari kirai/ijuk/genteng/seng, alat masak dari
tungku/kompor minyak, kursi bambu/kayu/tidak memiliki keduanya; tidak
memiliki aset pribadi (kebun/sawah, barang elektornik, kendaraan dan ternak)
serta aset produktif (simpanan atau tabungan); serta penghasilan usaha
pokok/keuntungannya dibawah Rp 30.000. Karakteristik tersebut merupakan
parameter yang digunakan MM untuk menyatakan layak tidaknya seseorang
untuk menjadi mitra. Seseorang layak menjadi mitra apabila sekurang-
kurangnya dua karakteristik tersebut dinyatakan layak. Seluruh responden
peneliti dinyatakan layak mendapatkan bantuan MM. Jika dilihat dari
pendapatan responden menurut Garis Kemiskinan Sajogjo (dalam Rusli, dkk,
1995), dapat disimpulkan bahwa sebanyak 75 persen responden berada di
bawah Batas Garis Kemiskinan, sedangkan sisanya sebanyak 25 persen berada
di atas Batas Garis Kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa responden
96
yang berada di bawah Batas Garis Kemiskinan merupakan responden yang
layak mendapatkan pinjaman.
2. Faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah faktor eksternal, yaitu kebijakan
pemerintah dengan menaikkan harga BBM, bencana alam (banjir), dan
sempitnya lapangan pekerjaan. Kenaikan harga BBM dan bencana banjir yang
melanda Jakarta tahun 1996 adalah faktor penyebab langsung yang
menyebabkan mitra menjadi miskin/tambah miskin. Kenaikan harga BBM
berimplikasi pada kenaikan harga bahan sembilan pokok (sembako) yang
merupakan bahan dasar/baku dari komoditi yang mereka jual, kenaikan BBM
juga berimplikasi pada kenaikan harga barang-barang lainnya termasuk
ongkos transportasi, sehingga kondisi tersebut semakin menyulitkan mitra.
Sedangkan sempitnya lapangan pekerjaan adalah faktor yang tidak langsung
mempengaruhi mereka.
3. Dana zakat melalui Program Urban Masyarakat Mandiri belum dapat
memberdayakan rumah tangga miskin untuk menjadi sejahtera, melainkan
hanya sampai pada memberdayakan rumah tangga untuk dapat melanjutkan
usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pendayagunaan bantuan hanya
sampai bagaimana responden harus memutar modal mereka setiap harinya,
belum sampai pada tahap bagaimana responden harus mengembangkan usaha
dan mensejahterakan mereka dengan menaikkan pendapatannya.
4. Dana zakat melalui Program Urban Masyarakat Mandiri Bantuan MM belum
berpengaruh nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat
dari masih rendahnya pendapatan mitra yang berimplikasi kepada belum
tercapainya mitra yang sejahtera.
97
9.2. Saran
Penulis mengajukan beberapa saran kepada berbagai pihak, yaitu:
1. Bagi Pemerintah agar lebih arif dalam menentukan kebijakan, terutama yang
terkait langsung dengan masyarakat, dan melihat implikasi dari kebijakan
tersebut dengan lebih bijaksana.
2. Bagi Pengelola Program Urban Masyarakat Mandiri:
a. Dalam penentuan kriteria peserta program selain menggunakan kriteria
yang sudah ada, sebaiknya juga menambahkan kriteria pendapatan per
kapita.
b. Mempertimbangkan kembali jumlah bantuan modal yang diberikan kepada
mitra mengingat besarnya bantuan yang diberikan sudah kurang relevan
dengan kondisi saat ini.
c. Agar memberikan perhatian kepada para mitra agar mereka memiliki etos
kerja yang tinggi dan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaannya
melalui pelatihan-pelatihan.
3. Bagi Aparat Pemerintah Kelurahan Bidaracina agar lebih mengoptimalkan
dana zakat yang berasal dari warga setempat, agar dapat dinikmati orang-
orang yang berhak.
4. Bagi Mitra Program Urban Masyarakat Mandiri:
a. Agar dapat menyisihkan sebagian penghasilan usahanya untuk ditabung
yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila dibutuhkan.
b. Agar lebih kreatif dalam memilih dan memodifikasi produk jualan serta
strategi-strategi usaha agar usaha yang dilakukan dapat bertahan atau
bahkan meningkat.
98
DAFTAR PUSTAKA
Bappenas. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
Bariadi, Lili. et.al. 2003. Zakat dan Wirausaha. Centre of Interpreneurship
Development. Hikmah Utama. Jakarta. BPS. 2006. Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2005-2006. Berita Resmi
Statistik no. 47/IX / 1 September 2006. BPS. 2007. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007. Berita Resmi Statistik
no.38/07/th. x, 2 Juli 2007. Darwanto, Herry. 2004. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis
Masyarakat Terpencil dalam Majalah Triwulan Perencanaan Pembangunan, Edisi 04/IX, Bappenas. Jakarta.
Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani
Press. Jakarta. http://www.budayajakarta.com/idx.php?pg=dload&n_id=354. Diakses tanggal 15
Juli 2008. Inayah, Gazi. 2005. Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak. Tiara Wacana.
Jakarta. Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2003. Informasi Dasar Penyusunan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Badan Perencanaan Pembanguanan Nasional. Jakarta.
Kurniawan, Hery. 2006. Tentang Kami Masyarakat Mandiri.
www.masyarakatmandiri.org. Diakses tanggal 23 Maret 2007. Laporan Perkembangan Program Urban Masyarakat Mandiri. 2008. Masyarakat
Mandiri. Tidak diterbitkan. Jakarta. Monografi Kelurahan Bidaracina. 2008. Tidak diterbitkan. Qardhawi, Yusuf. 1991. Fiqih Zakat. Gema Insani Press. Jakarta. Rusli, S. dkk. 1995. Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin.
Gramedia Widiasarana. Jakarta.
99
SMERU. 2000. Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia. Jakarta.
Soemardjan, Selo. 1993. Kemiskinan: Suatu Pandangan Sosiologis. Makalah.
Tidak diterbitkan. Jakarta. Soemardjan, Selo. 1997. Jurnal Sosiologi Indonesia. Ikatan Sosiolog Indonesia.
Jakarta. Suharto. 2003. Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial dalam Menangani
Kemiskinan. Suryana, Achmad. 2003. Evaluasi Pemikiran Kebijakan Ketahan Pangan,
kumpulan artikel. BPFE Ekonomi UGM. Yogyakarta. Syaukat, Yusman dan Sutara. 2004. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal.
Jurusan Ilmu-ilmu Sosial. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Tarumingkeng, Rudi C, et.al. 2001. Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif
Ekonomi. Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.
101
Lampiran 2. Kuisioner Penelitian Kepada Yth. Responden Penelitian Kuisioner ini digunakan untuk meneliti Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan serta Penggunaannya oleh Rumah Tangga Miskin. Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk mengisi dengan sebenar-benarnya. No. Responden : A. DATA DIRI RESPONDEN
1. Nama Lengkap : 2. Alamat : 3. Jenis Kelamin : 4. Status : 5. Pendidikan : 6. Pekerjaan : 7. Lama Menjadi Mitra : 8. Jumlah anggota keluarga.
No. Anggota Keluarga Pekerjaan Penghasilan/bulan Keterangan 1. Istri/suami 2. Anak/tanggungan:
1. 2. 3. 4. 5.
B. KARAKTERISTIK KEMISKINAN
KARAKTERISTIK BANGUNAN RUMAH
Indeks Rumah KEPEMILIKAN ASET PRIBADI
Ukuran Rumah (m2/orang)
Sangat kecil (<4m2) Kebun/Sawah Tidak Ada
Kecil (4-6m2) <1000m2 Sedang (6-8m2) 1000-5000m2 Besar (8m2) >5000m2
Dinding Bilik bambu/kayu Elektronik Radio Semi Tape Tembok/beton Televisi CD Player Lantai Tanah Panggung Kendaraan Tidak Ada Semen Sepeda Keramik Sepeda Motor Mobil Atap Kirai/Ijuk
Genteng/Seng Ternak Unggas (.........ekor)
Asbes/Berglazur Kambing/Domba (.........ekor)
Sapi/Kerbau (.........ekor)
102
Kepemili- kan Rumah Menumpang Simpanan
Ada (Rp......................)
Kontrak Tidak Ada Keluarga Sendiri ASET PRODUKTIF Dapur Tungku Sebutkan Jenisnya: 1. Kompor Minyak 2.
Kompor Gas/Listrik 3.
Kursi Lesehan Penggunaan: Bertambahnya aset produktif
Balai Bambu Investasi usaha lain
Kayu Investasi usaha turunan
Sofa Lainnya.........................
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN Faktor Internal
No. Karakteristik Jawaban Ya Tidak
1. Tingkat Karakteristik Usaha a. Apakah jenis usaha yang dilakukan banyak diminati
pembeli?
b. Apakah lokasi jualan Anda strategis? c.Apakah modal yang digunakan mencukupi?
2. Tingkat Motivasi a. Apakah Anda sering merasakan malas bekerja?
b. Apakah Anda termasuk orang yang giat bekerja? c. Apakah Anda dan keluarga menginginkan hidup yang layak?
3. Tingkat Dukungan Anggota Keluarga a. Apakah ada anggota keluarga yang membantu
melakukan proses produksi?
b. Apakah ada anggota keluarga yang membantu melakukan proses pemasaran?
c. Apakah seluruh anggota mendukung usaha Anda? 4. Pola produksi dan Konsumsi Keluarga a. Apakah keluarga Anda dapat menyisihkan uang untuk
ditabung setiap hari/ bulan?
b. Apakah keluarga Anda tergolong hemat? c. Apakah keluarga Anda sering membeli barang yang tidak terlalu diperlukan?
d. Apakah Anda/keluarga sering meminjam uang kepada orang lain?
103
Faktor Eksternal
No. Karakteristik Jawaban Ya Tidak
1. Apakah Anda merasa sulit mendapatkan pekerjaan? 2. Apakah Anda merasa sulit meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan?
3. Apakah Anda kesulitan memperoleh akses pendidikan? 4. Apakah Anda kesulitan memperoleh akses kesehatan? 5. Apakah sering terjadi bencana alam (seperti banjir,
kebakaran, dll)?
6. Apakah kondisi tersebut merugikan usaha Anda? 7. Apakah Anda kesulitan memperoleh bahan baku dagangan
Anda?
8. Apakah bahan baku tersebut tersedia dengan harga yang terjangkau?
9. Apakah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berpengaruh terhadap usaha Anda?
10. Apakah kondisi tersebut merugikan usaha Anda? D. TINGKAT PENDAPATAN Analisa Pembiayaan Usaha
No. Keterangan Setelah
Mendapatkan Pinjaman
Sebelum Mendapatkan
Pinjaman 1. Omzet Usaha (A) - Perhari - Perbulan 2. Pengeluaran (B) - Pembelian bahan baku - Biaya operasional usaha - Pengeluaran lain 3. Keuntungan Usaha (C=A-B)
Keuangan Keluarga Sebelum Mendapatkan Pinjaman
Penerimaan Keluarga (D) Jumlah (Rp/bulan) Pengeluaran Rutin (E)
Jumlah (Rp/bula
n) 1. Penghasilan Usaha
Pokok/Keuntungan (C) 1. Kebutuhan Dapur
2. Penghasilan Usaha Sampingan
2. Pendidikan
3. Penghasilan Suami/Istri 3. Kesehatan 4. Penghasilan
Anak/Menantu 4. Transportasi
5. Lainnya……………… 5. Iuran Rutin (Listrik, PAM, Siskamling,
104
Kontrakan ) 6. Lainnya………. 7. ……………….. TOTAL TOTAL Pendapatan (F=D-E) :
Setelah Mendapatkan Pinjaman
Penerimaan Keluarga (D) Jumlah (Rp/bulan) Pengeluaran Rutin (E)
Jumlah (Rp/bula
n) 1. Penghasilan Usaha
Pokok/Keuntungan (C) 1. Kebutuhan Dapur
2. Penghasilan Usaha Sampingan
2. Pendidikan
3. Penghasilan Suami/Istri 3. Kesehatan 4. Penghasilan
Anak/Menantu 4. Transportasi
5. Lainnya…………………..
5. Iuran Rutin (Listrik, PAM, Siskamling, Kontrakan )
6. Lainnya………. 7. ……………….. TOTAL TOTAL Pendapatan (F=D-E) :
105
Lampiran 3. Panduan Pertanyaan Penelitian Kepada Yth. Informan Penelitian Panduan Pertanyaan ini digunakan untuk meneliti Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga Miskin. PENDAMPING PROGRAM A. DATA DIRI INFORMAN
1. Nama Lengkap : 2. Alamat : 3. Jenis Kelamin : 4. Status : 5. Pendidikan : 6. Pekerjaan :
B. PROGRAM MASYARAKAT MANDIRI 1. Bagaimana pertama kali program MM dapt masuk ke daerah Bidara Cina? 2. Sudah berapa tahun program MM di daerah Bidara Cina? 3. Sudah berapa lama Anda menjadi pendamping? 4. Bagaimana pendampingan yang Anda lakukan? 5. Bagaimana teknis pendampingan program? 6. Berapa lama proses pendampingan yang dilakukan? 7. Apakah karakteristik RMT yang mendapatkan bantuan? 8. Apakah syarat-syarat administrasi menerima bantuan? 9. Apakah tujuan pemberian bantuan? 10. Apakah bantuan yang diberikan harus dikembalikan? 11. Jika ya, berapa lama setelah mendapatkan bantuan? 12. Menurut Anda, apakah program telah tepat sasaran? 13. Apakah seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi
sasaran program? 14. Apakah permasalahan yang dihadapi selama proses pendampingan? 15. Bagaimana cara mengatasi permasalah tersebut? 16. Apakah hak dan kewajiban sasaran? 17. Digunakan untuk apakah bantuan yang diberikan? 18. Apakah pendapatan rata-rata penerima bantuan mengalami kenaikan? 19. Apakah pemberian bantuan dapat meningkatkan angka kemiskinan? 20. Apakah pemberian bantuan dapat meningkatkan keberdayaan sasaran?
106
APARAT PEMERINTAH DAN TOKOH MASYARAKAT A. DATA DIRI INFORMAN
1. Nama Lengkap : 2. Alamat : 3. Jenis Kelamin : 4. Status : 5. Pendidikan : 6. Pekerjaan :
B. PROGRAM MASYARAKAT MANDIRI 1. Program-program pengentasan kemiskinan apa saja yang ada di Kelurahan
Bidaracina? 2. Bagaimana pertama kali program MM dapt masuk ke daerah Bidara Cina? 3. Sudah berapa tahun program MM di daerah Bidara Cina? 4. Bagaimana tata cara sosialisasi program? 5. Apakah tokoh diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi program? 6. Apakah karakteristik RMT yang mendapatkan bantuan? 7. Menurut Anda, apakah program telah tepat sasaran? 8. Apakah seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi
sasraan program? 9. Digunakan untuk apakah bantuan yang diberikan? 10. Apakah pendapatan rata-rata penerima bantuan mengalami kenaikan? 11. Apakah pemberian bantuan dapat meningkatkan angka kemiskinan? 12. Apakah pemberian bantuan dapat meningkatkan keberdayaan sasaran?
107
Lampiran 4. Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan
Nama : Leni Usia : 24 tahun Jenis Kelamin : Perempuan Lama menjadi pendamping : 3 tahun Tempat : Sekretariat GSM Waktu : 19.30 WIB
Wawancara mendalam dilakukan bertepatan dengan pertemuan kelompok mitra, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2008, wawancara berlangsung beberapa saat sebelum pertemuan mitra dimulai, sambil menunggu para mitra yang datang, peneliti bersama pendamping melakukan proses wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut ini hasil wawancara mendalam tersebut:
Sekitar tahun 2006, isu bahan makanan/jajanan terbuat dengan formalin dan boraks dan bahan-bahan lainnya yang membahayakan muncul, kebanyakan pedagang yang menggunakan bahan-bahan tersebut adalah pedagang kecil yang menjajakan dagangannya di sekolah-sekolah terutama di SD dan tempat-tempat lainnya yang dengan mudah dijangkau anak kecil. Salah satu daerah yang banyak ditemukan pedagang menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut adalah daerah Bidara Cina. Oleh karena itu MM masuk di kawasan tersebut dengan memberikan bantuan usaha dan pendampingan kepada para pedagang untuk bisa mandiri dan mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut. Program MM masuk pada tahun yang sama, program tersebut didampingi oleh seorang pendamping, untuk daerah Bidara Cina, didampingi oleh Mba Leni, ia mendampingi program tersebut kurang lebih sudah tiga tahun, tahun pertama di daerah Cipinang, dan tahun kedua hinggi sekarang mendampingi kawasan Bidara Cina.
Pada awal tahun 2008, program ini berkembang menjadi sebuah Koperasi, dimana para mitra tidak hanya mendapatkan bantuan lalu mengembalikan, tetapi juga diharapkan membeli bahan dasar dagangannya dari koperasi. Di masing-masing daerah unit kerjanya berbeda-beda, seperti penggilingan ikan di Bekasi, Kalam Mie di Bogor, dll.
Pendampingan tidak melakukan pendampingan setiap, apabila mitra membutuhkan sesuatu maka bisa langsung menghubungi pengelola yang tidak lain adalah warga yang tinggal di daerah yang sama dengan mitra, susunan pengelola adalah: Bapak Suparno sebagai Ketua, Bapak Abdul Malik sebagai Sekretaris, dan Bapak Mardiono sebagai Bendahara. Setiap dua pekan sekali diadakan pertemuan mitra, yakni setiap Rabu malam dari pukul 19.30-21.00 WIB, serta beberapa kali dilakukan survey oleh donatur.
Pada setiap pertemuan pendamping selalu berusaha untuk memberdayakan mitra dengan menjadi pengisi acara pada pertemuan tersebut, seperti MC, pembaca do’a, pemimpin pembacaan ikrar mitra, serta sambutan, pendamping hanya memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada mitra akan bahayanya bahan-bahan pengawet, memberikan masukan-masukan mengenai cara-cara/kiat-kiat melayani pembeli, bagaimana berakhlakul karimah kepada pelanggan/pembeli, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas mereka.
108
Selain itu, pendamping juga biasanya mengunjungi kios-kios/ tempat mangkalnya mitra dalam waktu yang tidak ditentukan.
Proses pendampingan biasanya dilakukan selama dua tahun, tetapi biasanya juga disesuaikan dengan kesiapan mitra. Syarat-syarat untuk menjadi mitra adalah pedagang kecil yang rentan terhadap penggunaan bahan-bahan berbahaya serta kaum dhuafa yang pendapatannya dibawah 30.000 per hari. Selain itu juga dilihat karakteristik rumah dan aset yang mereka miliki, seperti bangunan rumah, kepemilikan barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, serta aset produktif lainnya (terlampir di dalam kuesioner). Adapun persyaratan administratif untuk menjadi mitra adalah dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Tujuan dari program MM adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya, meningkatkan pendapatan mitra dan menciptakan akhlakul karimah (budi perkerti yang baik) pada diri mitra, selain itu menjadikan mitra untuk dapat bertanggung jawab dengan mengembalikan bantuan yang diberikan pada waktu yang telah ditentukan, yakni selama sepuluh bulan dengan cara menyicil yang dibayarkan pada saat pertemuan mitra (sebulan dua kali). Namun demikian, para mitra dapat secara fleksibel mengembalikan pinjamannya kapan saja selama dalam kurun waktu tersebut.
Awalnya, bantuan diberikan secara berkelompok, mitra yang terdaftar dikelompok-kelompokkan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kelompok dinilai lebih efektif karena sebagai jaminan bagi MM serta memudahkan dalam proses monitoring serta menjadikan mitra bertanggung jawab kepada kelompoknya. Namun sejak tahun 2008, bantuan diberikan secara perorangan karena jenis dagangan para mitra semakin beragam.
Bantuan MM sudah tepat sasaran ”bantuan tersebut sudah tepat sasaran, mitra yang mendapatkan bantuan MM adalah
orang yang tepat, yaitu masyarakat yang mempunyai usaha makanan jajanan dalam skala kecil yang kesulitan dalam hal modal (kurang mampu). Namun demikian, memang tidak semua pedagang kecil yang membutuhkan modal menjadi mitra MM, karena mereka tidak mengajukan.”
Setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan
bantuan, dengan syarat mempunyai usaha makanan jajanan dalam skala kecil serta memiliki kesulitan dalam hal permodalan, dalam sebuah rumah tangga hanya boleh mangajukan satu kali permohonan, bisa yang mengajukan istri atau suami
Masalah klasik yang sering dihadapi adalah masalah kehadiran dan
kedisiplinan, serta masalah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kehadiran yaitu pada saat pertemuan mitra, kedisiplinan yang berkaitan dengan pengembalian, sedangkan masalah yang tidak pernah diduga adalah bencana banjir yang datang pada awal 2006. Banjir tersebut membawa pengaruh yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, dan kitra pada khususnya.
”....Banyak mitra yang sering tidak hadir dalam pertemuan mitra, sehingga mengakibatkan macet dalam pengembalian. Selain itu bencana banjir pada awal 2006 juga sangat mempengaruhi, banyak rumah dan dagangan mitra yang hanyut terbawa air, dan sebagian besar tidak bisa diselamatkan”
109
Untuk mengatasi masalah kehadiran, biasanya pendamping mendatangi kios-kios/tempat mangkalnya mitra dalam berdagang untuk mengajak mereka hadir dlam pertemuan mitra dan cara lainnya adalah dengan menitipkan pesan keapda mitra yang hadir dalam pertemuan. Sedangkan untuk mengatasi masalah kedisplinan pembayaran pihak pengelola menunjuk satu orang yang juga seorang mitra untuk menarik uang setoran dengan waktu dua minggu sekali. Kemudian untuk masalah bencan banjir, pihak MM mengembalikan bantuan lagi kepada para mitra yang rumah dan barang dagangannya hanyut tersapu banjir.
Setiap mitra berhak untuk mendapatkan pinjaman bantuan, mendapatkan materi serta berkesempatan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan MM. Sedangkan kewajiban yang harus ditunaikan mitra adalah menghadiri pertemuan melunasi pinjaman dalam waktu sepuluh bulan, dan membeli bahan-bahan dagangannya ke koperasi. Bantuan yang didapatkan mitra biasanya digunakan untuk menambah modal usaha, tetapi ada juga mitra yang menggunakannya untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari, misalnya dalam keadaan kepepet atau dagangannya merugi.
Apabila dalam perjalanannya mitra tidak dapat mengembalikan dengan
tidak bertanggung jawab, maka tidak ada sanksi bagi mereka ”Kalo ada yang tidak mengembalikan tidak ada sanksi, karena sebenarnya uang itu adalah
hak/milik mereka, tetapi dari awal kita tidak menekankan itu agar mereka termotivasi untuk terus berusaha”
Jika dilihat dari peningkatan pendapatan mitra, sebagian besar meningkat,
namun tidak signifikan, dan kenaikannya tidak terlalu berarti, karena diikuti juga dengan kenaikan harga-harga bahan dasar dagangan mereka (harga sembako), dapat dikatakan juga pendapatan naik, namun modal jauh lebih naik. Dalam tingkat rumah tangga, pemberian bantuan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kenaikan harga sembako. Sehingga dapat dikatakan pemberian bantuan belum bisa mengurangi angka kemiskinan, hanya pada taraf membantu mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan dalam tingkat masyarakat, pemberian juga belum mengurangi angka kemiskinan, karena penerima bantuan hanya sebagian kecil dari masyarakat miskin di daerah Bidaracina. Jika dilihat dari aspek keberdayaannya, secara mendapatkan modal usaha, sudah dapat dikatakan berdaya, namun secara kesejahteraan masih belum dan sedang mengarah ke sana.
110
Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan (Pengelola)
Nama : Suparno Usia : 35 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Jabatan : Ketua Tempat : Sekretariat GSM Waktu : 19.30 WIB
Wawancara mendalam dilakukan bertepatan dengan pertemuan kelompok mitra, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2008, wawancara berlangsung beberapa saat setelah pertemuan mitra selesai, sambil menunggu para mitra yang menyelesaikan pembayaran, peneliti bersama pengelola melakukan proses wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut ini hasil wawancara mendalam tersebut:
Sekitar tahun 2006 MM masuk ke daerah Bidaracina untuk memberikan bantuan kepada pedagang kecil yang kesulitan modal, MM mendata masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, lalu kemudian secara formal, orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut mendaftarkan diri. Sampai saat ini usia dari program bantuan MM di Bidaracina adalah kurang lebih dua tahun. Sejak awal pak Parno sudah ditunjuk menjadi ketua oleh para mitra. Namun demikian beliau tidak setiap hari ada di kantor/sekretariat.
”.........Setiap hari kan saya kerja, sehingga tidak bisa selalu stand by di kantor, yang biasa
stand by itu pak Mardiono selaku sebagai bendahara, karena kantor sekaligus tempat tinggal dia, tetapi kalo ada pertemuan mitra saya selalu usahain datang........”
Pengelolaan dilakukan secara bersama-sama, ketua bertugas melakukan
koordinasi ke MM melalui pendamping, serta mencari pihak-pihak yang mau bekerjasama. Jika ada masyarakat yang menginginkan bantuan, dapat secara langsung mendaftarkan diri ke sekretariat atau langsung datang ke pertemuan mitra setiap Rabu malam (dua minggu sekali) dengan melengkapi persyaratan, yaitu fotokopi KTP dan KK.
Program ini sudah berlangsung kurang lebih selama dua tahun, program ini tidak membeda-bedakan golongan, siapa saja boleh ikut, asalkan punya usaha kecil, kesulitan modal dan berkomitmen. Tujuan akhir dari program ini adalah mengurangi angka kemiskinan.
”Melalui program ini mitra diharapkan dapat menaikkan modal usaha, memperbaiki
kualitas makanan, membagusin gerobak, meningkatkan pandapatan yang tadinya seumpama Rp 2.000 naek jadi Rp5.000.”
Pinjaman harus dikembalikan dalam tempo sepuluh bulan yang dibayarkan
dua minggu sekali pada saat pertemuan mitra. Bantuan ini telah tepat sasaran, karena benar-benar dimanfaatkan oleh pedagang kecil. Namun demikian, setiap suatu program tentunya terdapat beberapa kendala/masalah, masalah yang dijumpai dalam program ini adalah masalah penunggakan. Banyak mitra yang nunggak pembayaran dengan alasan belum ada uang, masalah tersebut diantisipasi
111
oleh pengelola dengan menunjuk satu orang sebagai penarik setoran, yang waktunya juga dua minggu sekali.
Hak dari mitra adalah mendapatkan bantuan/pinjaman, sedangkan kewajibannya adalah mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Selain itu, karena program ini telah berkembang menjadi sebuah koperasi, maka kewajiban mitrapun bertambah, yaitu mitra diharapkan dpat membeli bahan dagangannya di koperasi, serta membayar berbagai iuran, yaitu simpanan pokok sebesar Rp 2.000, iuran wajib sebesar Rp 10.000/bulan (kedua iuran ini akan dikembalikan), iuran sukarela (tabungan) yang jumlahnya ditentukan sebesar Rp. 5.000, serta dana sosial Rp. 5.000/bulan, iuran digunakan apabila ada mitra atau anggota keluarganya yang terkena musibah. Pinjaman yang diberikan sebagian besar digunakan untuk modal usaha, seperti membuat gerobak, dan menambah komoditas barang dagangan. Namun ada juga yang menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangganya, seperti untuk makan sehari-hari dan jajan anak-anak.
Pendapatan rata-rata mitra mengalami kenaikan, namun kenaikan itu tidak sesuai dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sembako. Sehingga kenaikan pendapatan tidak dirasakan secara nyata. Jika dilihat dari aspek mengurangi tingkat kemiskinan, program ini belum dapat dikatakan seperti itu, karena biasanya mitra hanya bisa untuk memutar modal saja, dengan kata lain untuk dapat bertahan hidup. Sedangkan jika dilihat dari pemberdayaan, mitra belum sepenuhnya berdaya, tetapi dari mulai usaha yang kecil kemudian bida berkembang menjadi usaha yang besar.
112
Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan (Pengelola)
Nama : Abdul Malik Usia : 40 tahun Jenis Kelamin : Laki-laki Jabatan : Sekretaris Tempat : Sekretariat GSM Waktu : 19.30 WIB
Wawancara mendalam dilakukan bertepatan dengan pertemuan kelompok mitra, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2008, wawancara berlangsung beberapa saat setelah pertemuan mitra selesai, sambil menunggu para mitra yang menyelesaikan pembayaran, peneliti bersama pengelola melakukan proses wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut ini hasil wawancara mendalam tersebut:
Sebelum masuk program MM, terdapat program KPDR (Kelompok Pemberdayaan Dhuafa dan Remaja), bapak Abdul Malik tergabung ke dalamnya sebagai pengurus, yaitu tepatnya sebagai Seksi Kerohanian. Kemudian, pada tahun 2006 masuklah program MM yang memberikan bantuan kepada para pedagang kecil yang kurang mampu. Proses perekrutannya yaitu dengan mendata orang-orang yang masuk ke dalam kriteria tersebut. Dalam kesehariannya beliau bekerja sebagai pegawai pada tabloid Sinar Tani bagian pemasaran. Selain sebagai pengelola porgram MM, beliau juga dianggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungan RW 007.
Dari mulai berdirinya program MM beliau sedah ditunjuk sebagai pengelola, yaitu sebagai sektreatis, dimana tugasnya adalah mengelola maslah administrasi dan bertanggungjawab juga dengan hadir pada pertemuan mitra. Namun pada kesehariannya beliau tidak selalu stand by di kantor/sekretariat.
”Saya jarang ada di kantor, karena saya kerja di kantor. Paling engga saya hadir di
pertemuan mitra dan rapat pengelola dengan pendamping.” Pengelola MM terdiri dari tiga orang, yaitu Ketua, Sekretaris, dan
Bendahara, yang pda intinya tugasnya adalah mengkoordinasikan mitra dan berhubungan dengan pendamping. Proses pendampingan dilakukan sampai dengan mitra bisa mandiri, biasanya waktu yang dibutuhkan adalah dua tahun.
Masyarakat yang bisa menjadi mitra adalah pedagang kecil yang kurang pembiayaan, besarnya pembiayaan tergantung kebutuhan mitra, namun sebelumnya ada survey terlebih dahulu dari pihak MM atau dari donatur. Calon mitra mendaftarkan diri ke sekretariat MM, kemudian mengisi formulir dan melengkapinya dengan fotokopi KTP dan KK.
Tujuan dari program ini adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan makanan berbahaya, karena pada awal tahun 2006 banyak pedagang di daerah Bidaracina yang menggunakan bahan makanan berbahaya, mengurangi pengaruh rentenir (bank keliling), karena sebelumnya banyak rentenir yang memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil dengan bunga yang sangat tinggi, setelah MM masuk maka secara otomatis jumlah rentenir menjadi berkurang, membuat produk yang berkualitas dengan tidak menggunakan bahan-bahan makanan
113
berbahaya, meningkatkan pendapatan mitra dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan/pembeli.
Bantuan yang diberikan oleh MM adalah berupa pinjaman, sehingga harus dikembalikan. Waktu yang diberikan kepada para mitra unutk melunasinya adalah selama sepuluh bulan. Program ini telah tepat sasaran, karena mitra yang mendapatkan bantuan adalah orang-orang dhuafa yang membutuhkan. Persayaratannya sangat sederhana, asalkan mitra adalah pedagang kecil yang kesulitan modal dan memiliki kemauan yang tinggi untuk berusaha.
Dalam berdagang, tentunya banyak kendala/masalah yang dihadapi oleh para mitra, seperti razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mitra yang dirazia adalah mitra yang berdagang di jalan-jalan raya (protokol), apabila mitra ditertibkan oleh Satpol PP, paling tidak gerobaknya ditahan dan mitra dpat menebusnya dengan harga yang mahal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekarang ini mitra berdagang di dalam gang, sekolah-sekolah, lapangan, pasar dan berkeliling di rumah-rumah warga.
Hak dan kewajiban setiap mitra adalah sama, tidak ada yang memiliki hak atau kewajiban yang lebih dari yang lain. Hak setiap mitra adalah mendapatkan bantuan pinjaman, sedangkan kewajibannya adalah mengembalikannya sampai batas waktu yang ditentukan, membeli bahan-bahan untuk berdagang di Gerai Sembako Murah (GSM) atau sekarang telah menjadi Koperasi.
Bantuan pinjaman yang diberikan kepada mitra digunakan untuk memperbesar usaha, menambah modal dengan membeli gerobak, peralatan yang dibutuhkan serta membeli bahan baku produksi. Namun tidak sedikit juga yang menggunakannnya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk makan keluarga dan untuk jajan anak. Kondisi tersebut biasanya terpaksa dilakukan oleh mitra apabila mereka tidak mendapatkan pengahasilan yang mencukupi setiap harinya.
Setelah mendapatkan bantuan MM, pendapatan mitra rata-rata mengalami kenaikan, namun kenaikan itu biasanya tidak terlalu besar, ditambah lagi dengan naiknya harga BBM yang berimbas pada naiknya bahan-bahan sembako. Sehingga kenaikan pendapatan tidak dirasakan secara nyata. Banyak yang mengaku pada zaman susah seperti sekarang, modal usaha harus besar, jika modalnya tanggung, maka usahanya cepat rugi. Program ini belum dapat dikatakan mengurangi angka kemiskinan, tetapi dengan usaha yang keras cita-cita itu dapat terwujud. Namun untuk kondisi sekarang ini belum, karena biasanya mitra hanya bisa untuk memutar modal saja. Sedangkan jika dilihat dari pemberdayaan, secara modal mitra bisa lebih akses, karena bisa mendapatkan bantuan dari MM. Namun pada kenyataannya tidak sedikit mitra yang mengalami kerugian dan apda akhirnya bingung untuk mengembalikan pinjaman.
114
Lampiran 5 . Foto Dokumentasi
Gambar 3. Rumah Kontrakan Responden Gambar 4. Sungai yang Sering
Berukuran Kecil Meluap pada Musim Hujan
Gambar 5. Alat Masak Responden Gambar 6. Dinding Rumah Responden Berupa Kompor Minyak Terbuat dari Tembok