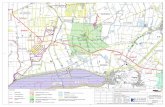p
-
Upload
aninda-wulan-pradani -
Category
Documents
-
view
65 -
download
3
description
Transcript of p

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Banyak kasus kematian yang terjadi akibat keadaan emergency/gawat
darurat. Penderita gawat darurat adalah penderita yang oleh karena suatu
penyebab (penyakit, trauma, kecelakaan, tindakan anestesi) yang bila tidak
segera ditolong akan mengalami cacat, kehilangan organ tubuh atau
meninggal (Sudjito, 2003). Berdasarkan KODEKI pasal 13, setiap dokter
wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan,
kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu
memberikan (MKEK, 2002). Dalam penanganan penderita gawat darurat
yang terpenting bagi tenaga kesehatan adalah mempertahankan jiwa
penderita, mengurangi penyulit yang mungkin timbul, meringankan
penderitaan korban, dan melindungi diri dari kemungkinan penularan
penyakit menular dari penderita (Sudjito, 2003).
Pertolongan Pertama Pada Gawat Darurat (PPGD) adalah serangkaian
usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam
rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Prinsip Utama PPGD adalah
menyelamatkan pasien dari kematian pada kondisi gawat darurat, kemudian
filosofi dalam PPGD adalah “Time Saving is Life Saving”, dalam artian
bahwa seluruh tindakan yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat
haruslah benar-benar efektif dan efisien, karena pada kondisi tersebut pasien
dapat kehilangan nyawa dalam hitungan menit saja ( henti nafas selama 2-3
menit dapat mengakibatkan kematian). Pertolongan ini harus diberikan secara
tepat, sebab penanganan yang salah justru dapat berakibat kematian atau
kecacatan bagi penderita (Purwadianto dan Sampurna, 2000). Oleh karena itu,
sebagai dokter gigi kita harus mengetahui cara-cara pertolongan pertama pada
kegawatdaruratan sebab kasus emergency dapat terjadi di ruang praktik
ataupun saat menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan tersebut
dimanapun kita berada.
1

.
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka laporan ini akan membahas
mengenai contoh kasus kegawatdaruratan, hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam kasus kegawatdaruratan, pengkajian pasien dalam kondisi kegawat
daruratan, langkah-langkah penanganannya, serta kasus kegawatdaruratan
dental.
C. Tujuan
Tujuan dari Problem Based Learning (PBL) kali ini adalah mengetahui
contoh kasus kegawatdaruratan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
penyelamatan kasus kegawatdaruratan, langkah-langkah penanganannya,
serta kasus kegawatdaruratan dental.
D. Manfaat
Sebagai sarana belajar bagi mahasiswa untuk menggali pengetahuan
lebih dalam tentang kasus kegawatdaruratan secara umum dan
kegawatdaruratan dental, serta mampu memberikan pertolongan pertama
pada kasus kegawatdaruratan tersebut.
2

BAB II
PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
1. Gawat Darurat
Kasus Gawat Darurat adalah keadaan yang menimpa seseorang yang dapat
menyebabkan sesuatu yang mengancam jiwanya dalam arti memerlukan
pertolongan tepat, cermat dan cepat bila tidak maka seseorang tersebut
dapat mati atau menderita cacat. Situasi gawat darurat disebabkan oleh
banyak hal dan dapat berakibat kematian atau cacat dalam waktu singkat,
baik sebab bidang medik ataupun trauma (Adam, 2010).
Yang mengakibatkan kegawatan menyangkut:
a. Jalan napas dan fungsi napas
b. Fungsi peredaran darah
c. Fungsi otak dan kesadaran
2. Initial Assestment
Initial assessment adalah untuk memprioritaskan pasien dan menberikan
penanganan segera. Informasi digunakan untuk membuat keputusan
tentang intervensi kritis dan waktu yang dicapai. Saat melakukan
pengkajian, pasien harus aman dan dilakukan secara cepat dan tepat
dengan mengkaji tingkat kesadaran (Level Of Consciousness) dan
pengkajian ABC (Airway, Breathing, Circulation), pengkajian ini
dilakukan pada pasien memerlukan tindakan penanganan segera dan pada
pasien yang terancam nyawanya (Campbell, 2004).
Penilaian awal ini intinya adalah :
a. Primery survey, yaitu penanganan ABCDE dan resusitasi. Disini
digolongkan keadaan yang mengancam nyawa, dan apabila menemukan
harus dilakukan resusitasi.
b. Secondary survey, yaitu head to toe / pemeriksaan yang teliti dari ujung
kepala sampai kaki
c. Penanganan definitive atau menetap
3

3. Basic Life Support
Usaha yang dilakukakan untuk mempertahankan kehidupan pada saat
pasien atau korban mengalami keadaan yang mengancam jiwa dikenal
dengan Bantuan Hidup Dasar (BHD) / Basic Life Support (BLS).
Sedangkan bantuan yang diberikan pada pasien /korban yang dilakukan
dirumah sakit sebagai kelanjutan dari BHD disebut Bantuan Hidup
Lanjut/Advance Cardiac Life Support (ACLS) (Lasprita, 2012).
BHD sangat bermanfaat bagi penyelamatan kehidupan mengingat dengan
pemberian sirkulasi dan napas buatan secara sederhana, BHD memberikan
asupan oksigen dan sirkulasi darah ke sistem tubuh terutama organ yang
sangat vital dan sensitif terhadap kekurangan oksigen seperti otak dan
jantung. Berhentinya sirkulasi beberapa detik sampai beberapa menit,
asupan oksigen ke dalam otak terhenti, terjadi hipoksia otak yang yang
mengakibatkan kemampuan koordinasi otak untuk menggerakkan organ
otonom menjadi terganggu, seperti gerakan denyut jantung dan pernapasan
(Adam, 2010).
Tujuan dilakukan BHD dengan segera adalah (Adam, 2010):
a. Mencegah berhentinya sirkulasi darah atau berhentinya pernapasan
b. Memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi (melalui kompresi
dada) dan ventilasi (melalui bantuan napas penolong) dari pasien yang
mengalami henti jantung atau henti napas melalui rangkaian kegiatan
Resusitasi Jantung Paru (RJP).
4

B. Pembahasan
1. Skenario
Gambar 2.1 Medical Emergency
2. Metode Seven Jumps
a. Step 1 Klarifikasi Istilah
1) Emergensi
Suatu keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan yang cepat
dan tepat untuk menghindari kecacatan dan kematian.
2) Kegawatan
Keadaan yang menimpa seseorang yang dapat menyebabkan jiwanya
terancam sehingga memerlukan pertolongan secara cepat, tepat dan
cermat (Dinkes, 2004).
3) Kedaruratan
5

Keadaan yang memerlukan tindakan mendesak dan tepat untuk
menyelamatkan nyawa, menjamin perlindungan dan memulihkan
kesehatan individu atau masyarakat (Dinkes, 2004).
4) Kegawatdaruratan
Suatu keadaaan dimana seseorang mengalami ancaman kehidupan
dan apabila tidak dilakukan pertolongan/ tindakan dgn cepat dan
tepat dapat menyebabkan cacat atau meninggal (Dinkes, 2004).
5) Urgensi / Akut
Serangan mendadak yang tiba-tiba yang dapat berakibat fatal apabila
tidak ditangani dengan benar.
b. Step 2 Perumusan Masalah
1) Basic life support
2) Kondisi emergensi secara umum, tanda dan gejala pasien, serta
penanganan pasien
3) Kondisi emergensi kedokteran gigi, tanda dan gejala pasien, serta
penanganan pasien
c. Step 3 Brain Storm
1) Basic life support
Basic life support (BLS) adalah pertolongan dasar untuk menunjang
kehidupan yang terdiri dari Airway, Breathing, Circulation (ABC).
Airway yaitu usaha untuk membebaskan jalan nafas dengan cara dahi
ditarik ke belakan dan dagu ditarik ke depan untuk menghindari
tertutupnya jalan nafas. Breathing diawali dengan melihat kondisi
nafas pasien, apabila nafas tidak adekuat maka dapat diberikan nafas
buatan secara langsung mouth to mouth, atau tidak langsung mouth
to mask. Circulation diawali dengan melihat ada tidaknya detak
jantung, apabila jantung berhenti berdetak maka dilakukan tindakan
kompresi untuk memicu detak jatung kembali. Cara untuk
melakukan kompresi yaitu dengan meletakkan dua jari diatas ulu hati
lalu menekan telapak tangan pada bagian tersebut.
6

Sebelum melakukan tindakan BLS, perlu dipastikan situasi dan
kondisi aman bagi penolong untuk melakukan tindakan ABC.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan
pertolongan adalah:
1. Jauhkan pasien dari hal bahaya lainnya.
2. Posisikan pasien di tempat kering, keras, aman
3. Perhatikan keselamatan diri dan gunakan alat proteksi diri (APD)
4. Pasien jangan digerakkan terlalu banyak, untuk menghindari
adanya fraktur
5. Kontrol breathing dan circulation
2) Kondisi emergensi secara umum, tanda dan gejala pasien, serta
penanganan pasien
1. Syok
Syok merupakan suatu kegagalan hemodinamik pada tubuh yang
mengakibatkan kegagalan perfusi pada organ vital. Syok
dibedakan menjadi syok neurogenik (suhu tubuh hangat), syok
anafilaktik (pucat, suhu tubuh dingin, penurunan denyut nadi),
syok hipovolemik (pucat, suhu tubuh dingin, penurunan denyut
nadi).
2. Sinkop
Adanya penurunan ventilasi yang ditandai dengan muka pucat,
untuk penanganannya sebaiknya diberikan bau-bauan yang
merangsang kesadaran misalnya alkohol atau minyak angin
3. Asma
Asma ditandai dengan bunyi mengi atau wheezing, pucat
berkeringat, telapak tangan dan kaki dingin, serta bagian tubuh
yang lainnya hangat. Penanganan asma sebaiknya diberikan
inhaler, oksigen aliran tinggi, suntuik adrenalin intramuskular.
4. Gagal nafas
Kondisi gagal nafas dapat terjadi akibat tenggelam, maupun
kebakaran. Pertolongan pertama yang dapat diberikan pada
7

korban tenggelam adalah mengeluarkan air dari jalan nafas dan
diberikan oksigen aliran tinggi, begitu juga halnya dengan korban
kebakaran yaitu dengan memberikan oksigen aliran tinggi pada
pasien.
5. Luka bakar
Pasien yang menderita luka bakar dapat diberikan pertolongan
dengan membersihkan luka bakar, dan pemberian air sebanyak
mungkin jika pasien telah sadar, atau infus jika pasien tidak sadar.
6. Trauma kepala
Trauma kepala dapat dicurigai dengan melihat adanya tanda-tanda
luka lebam maupun perdarahan pada wajah dan kepala pasien.
Pertolongan pertama yang dapat diberikan yaitu diberi penyangga
kepala dan leher, serta selalu meminimalkan guncangan pada
daerah leher ke atas.
7. Overdosis obat
Keracunan akibat overdosis obat dapat ditandai dengan adanya
busa dari mulut, mual muntah, dan kemerahan pada mukosa
mulut. Hal yang dapat dilakukan pada pasien tersebut yaitu
dengan memosisikan kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang
lain. Pasien juga dapat diberikan air kelapa, susu, maupun
antidotum dan adrenalin, lalu pastikan jalan nafas pasien normal.
8. Patah tulang
Adanya fraktur pada tulang dapat terjadi secara open fraktur
maupun close fraktur. Pertolongan pada pasien yang fraktur yaitu
harus memperhatikan cara mengangkat pasien dengan
mengangkat bagian yang sehat atau tidak dicurigai ada patah
tulang. Saat pasien dipindahkan memerlukan 2-3 orang penolong.
Diperlukan adanya imobilisasi dan fiksasi diatas bagian yang
dicurigai fraktur.
9. Keracunan bisa binatang (ular/kalajengking)
Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan
membebat bagian yang terkena gigitan binatang tersebut.
8

Pemberian obat antibisa dapat menjadi terapi awal pada pasien.
Pasien yang telah digigit binatang berbisa memiliki critical time
selama 15 menit.
10. Kesetrum
Pasien yang kesetrum memiliki tanda luka bakar pada bagian
tubuhnya, apabila tegangan listrik tinggi maka jantung dapat
berhenti berdetak.pertolongan yang pertama adalah hentikan
aliran listrik yang masih menyala, jauhkan pasien dari air karena
kemungkinan aliran listrik masih terdapat dalam tubuh.
Posisikan pasien dengan benar dan perawatan luka bakar.
11. Serangan jantung
Adanya serangan jantung biasanya mengakibatkan kesulitan
bernafas sampai dengan pingsan. Apabila pasien mulai sulit
bernafas dapat berikan aliran oksigen maupun pasien disuruh
untuk batuk kuat-kuat. Apabila serangan mengakibatkan detak
jantung berhenti maka perlu dilakukan kompresi.
12. Persalinan
Pada kondisi persalinan terdapat kondisi emergensi apabila
ketuban telah pecah selama <24 jam, maka perlu dibawa ke
rumah sakit untuk menghindari keracunan pada bayi.
13. Epilepsi
Pasien epilepsi ditandai dengan kejang, dengan rahang atas dan
rahang bawah mengatup. Pertolongan yang dapat diberikan pada
pasien yaitu memberi penahan diantara rahang untuk mencegah
tergigitnya lidah, dan juga obat antikonvulsan seperti
carbamazepine dan phenytoin. Posisi pasien ditegakkan, dan
pembebasan jalan nafas apabilan tersumbat oleh air liur.
3) Kondisi emergensi kedokteran gigi, tanda dan gejala pasien, serta
penanganan pasien
1. Syok anafilaktik
2. Fraktur
9

3. Avulsi
4. Tertelannya benda-benda kecil
5. Perdarahan dan luka karena intrumen dan pencabutan
6. Dislokasi TMJ
7. Dry soket
8. Abses akut
9. Iatrogenik dalam endodontik (file patah saat PSA)
10. Pulpitis akut
d. Step 4 Analisis masalah
1) Bagian manakah yang mengalami kematian sel dahulu, otak atau
jantung?
Jantung merupakan organ vital yang berfungsi memompa darah yang
mengandung oksigen dan makanan untuk seluruh sel dalam tubuh
termasuk sel-sel otak. Sehingga dalam proses kematiannya dalam
dunia kedokteran dikenal dengan istilah mati klinis yaitu tidak
ditemukan adanya pernafasan dan denyut nadi. Mati klinis dapat
reversible. Pasien mempunyai kesempatan waktu selama 4-6 menit
untuk dilakukan resusitasi, sehingga memberikan kesempatan kedua
sistem tersebut berfungsi kembali. Sedangkan istilah lainnya yaitu
mati biologis yaitu terjadi kematian sel dalam tubuh, dimana
kematian sel dimulai terutama sel otak dan bersifat irreversible, biasa
terjadi dalam waktu 8 – 10 menit dari henti jantung. Dari penjelasan
tersebut dapat disimpulkan bahwa sel jantung akan mengalami
kematian terlebih dahulu baru setelahnya sel tubuh lain tidak dapat
mengkompensasi kekurangan oksigen akibat jantung berhenti
memompa sehingga organ vital lainnya juga akan mengalami
kerusakan. Otak adalah organ yang paling cepat mengalami
kerusakan, karena otak hanya akan mampu bertahan jika ada asupan
glukosa dan oksigen. Jika dalam waktu lebih dari 10 menit otak tidak
mendapat asupan oksigen dan glukosa maka otak akan mengalami
kematian secara permanen (Ashar, 2011).
10

e. Step 5 Sasaran belajar
1) BLS dan RJP terbaru
2) Kondisi emergensi kedokteran gigi, tanda dan gejala pasien, serta
penanganan pasien
f. Step 6 Belajar Mandiri
Tidak ada
g. Step 7 Reporting
1) BLS dan RJP terbaru
Resusitasi jantung paru (RJP) adalah usaha untuk mengembalikan
fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada henti nafas (respiratory
arrest) dan atau henti jantung (cardiac arrest). Resusitasi jantung paru
otak dibagi dalam tiga fase : bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut,
bantuan hidup jangka lama. Namun pembahasan kali ini lebih
difokuskan pada Bantuan Hidup Dasar (Lasprita, 2012).
American Heart Assocation (AHA) menetapkan pedoman resusitasi
yang pertama kali pada tahun 1966, resusitasi jantung paru (RJP)
awalnya ABC yaitu membuka jalan nafas korban (Airway),
memberikan bantuan napas (Breathing) dan kemudian memberikan
kompresi dinding dada (Circulation). Namun, konsekuensinya
berdampak pada penundaan bermakna (kira-kira 30 detik) untuk
memberikan kompresi dinding dada yang dibutuhkan untuk
mempertahankan sirkulasi darah yang kaya oksigen. Sehingga pada
tahun 2010 tindakan BLS diubah menjadi CAB (circulation,
breathing, airway). Tujuan utama dari BLS adalah untuk melindungi
otak dari kerusakan yang irreversibel akibat hipoksia, karena
peredaran darah akan berhenti selama 3-4 menit (Adam, 2010).
Tata laksana RJP (Ashar, 2010):
11

1. Memeriksa keadaan pasien, respon pasien, termasuk mengkaji
ada / tidak adanya nafas secara visual tanpa teknik Look Listen and
Feel.
2. Melakukan panggilan darurat.
3. Circulation
· Meraba dan menetukan denyut nadi karotis. Jika ada denyut nadi
maka dilanjutkan dengan memberikan bantuan pernafasan, tetapi
jika tidak ditemukan denyut nadi, maka dilanjutkan dengan
melakukan kompresi dada. Untuk penolong non petugas kesehatan
tidak dianjurkan untuk memeriksa denyut nadi korban.
· Pemeriksaan denyut nadi ini tidak boleh lebih dari 10 detik.
· Lokasi kompresi berada pada tengah dada korban (setengah bawah
sternum). Penentuan lokasi ini dapat dilakukan dengan cara tumit
dari tangan yang pertama diletakkan di atas sternum, kemudian
tangan yang satunya diletakkan di atas tangan yang sudah berada di
tengah sternum. Jari-jari tangan dirapatkan dan diangkat pada
waktu penolong melakukan tiupan nafas agar tidak menekan dada.
· Petugas berlutut jika korban terbaring di bawah, atau berdiri
disamping korban jika korban berada di tempat tidur
Gambar 2.2 Chest compression
· Kompresi dada dilakukan sebanyak satu siklus (30 kompresi,
sekitar 18 detik)
· AHA Guideline 2010 merekomendasikan (Adam, 2010) :
12

Kompresi dada dilakukan cepat dan dalam (push and hard)
Kecepatan adekuat setidaknya 100 kali/menit
Kedalaman adekuat
Dewasa : 2 inchi (5 cm), rasio 30 : 2 (1 atau 2 penolong)
Anak : 1/3 AP (± 5 cm), rasio 30 : 2 (1 penolong) dan 15 : 2
(2 penolong)
Bayi : 1/3 AP (± 4 cm), rasio 30 : 2 (1 penolong) dan 15 : 2
(2 penolong)
Memungkinkan terjadinya complete chest recoil atau
pengembangan dada seperti semula setelah kompresi,
sehingga chest compression time sama dengan waktu
relaxation/recoil time.
4. Airway.
Korban dengan tidak ada/tidak dicurgai cedera tulang belakang
maka bebaskan jalan nafas melalui head tilt– chin lift. Caranya
dengan meletakkan satu tangan pada dahi korban, lalu mendorong
dahi korban ke belakang agar kepala menengadah dan mulut sedikit
terbuka (Head Tilt) Pertolongan ini dapat ditambah dengan
mengangkat dagu (Chin Lift). Namun jika korban dicurigai cedera
tulang belakang maka bebaskan jalan nafas melalui jaw thrust yaitu
dengan mengangkat dagu sehingga deretan gigi rahang bawah
berada lebih ke depan daripada deretan gigi rahang atas.
Gambar 2.3 Head Tilt & Chin Lift
13

Gambar 2.4 Jaw Thrust
AHA Guideline 2010 merekomendasikan langkah-langkah (Adam,
2010):
1) Gunakan head tilt-chin lift untuk membuka jalan napas pada
pasien tanpa ada trauma kepala dan leher. Sekitar 0,12-3,7%
mengalami cedera spinal dan risiko cedera spinal meningkat
jika pasien mengalami cedera kraniofasial dan/atau GCS <8
2) Gunakan jaw thrust jika suspek cedera servikal
3) Pasien suspek cedera spinal lebih diutamakan dilakukan
restriksi manual (menempatkan 1 tangan di ditiap sisi kepala
pasien) daripada menggunakan spinal immobilization devices
karena dapat mengganggu jalan napas tapi alat ini bermanfaat
mempertahankan kesejajaran spinal selama transportasi
5. Breathing.
Berikan ventilasi sebanyak 2 kali. Pemberian ventilasi dengan jarak
1 detik diantara ventilasi. Perhatikan kenaikan dada korban untuk
memastikan volume tidal yang masuk adekuat.
Pemberian nafan dapat dilakukan pada mulut ke mulut, mulut ke
hidung, dan mulut dari big valve mask.
1) Untuk pemberian mulut ke mulut langkahnya sebagai berikut :
· Pastikan hidung korban terpencet rapat
· Ambil nafas seperti biasa (jangan terelalu dalam)
14

· Buat keadaan mulut ke mulut yang serapat mungkin
· Berikan satu ventilasi tiap satu detik
· Kembali ke langkah ambil nafas hingga berikan nafas kedua
selama satu detik.
Gambar 2.5 Pernafasan mulut ke mulut
· Jika tidak memungkinkan untuk memberikan pernafasan melalui
mulut korban dapat dilakukan pernafasan mulut ke hidung korban.
2) Untuk pemberian oksigen melalui bag mask langkahnya
sebagai berikut :
1. Pastikan menggunakan bag mask dewasa dengan volume
1-2L agar dapat memberikan ventilasi yang memenuhi
volume tidal sekitar 600 ml.
2. Menghubungkan bag dengan mask, jika belum tersambung
3. Meletakkan bagian yang menyempit (apeks) dari masker di
atas batang hidung pasien dan bagian yang melebar (basis)
diantara bibir bawah dan dagu
4. Menstabilkan masker pada tempatnya dengan ibu jari dan
jari teluntuk membentuk huruf “C”. Menggunakan jari yang
lainnya pada tangan yang sama untuk mempertahankan
ketepatan posisi kepala dengan mengangkat dagu sepanjang
mandibula dengan jari membentuk huruf “E”
5. Memberikan ventilasi dengan mengempiskan bag dengan
menggunakan tangan lainnya
15

6.Mengobservasi pengembangan dada pasien selama
melakukan ventilasi
Gambar 2.6 Bag valve mask
AHA Guideline 2010 merekomendasikan untuk pemberian rescue
breathing sama dengan rekomendasi AHA 2005, yaitu (Adam,
2010) :
a. Pemberian dilakukan sesuai tidal volume
b. Rasio kompresi dan ventilasi 30:2
c. Setelah alat intubasi terpasang pada 2 orang penolong : selama
pemberian RJP, ventilasi diberikan tiap 8-10 x/menit tanpa usaha
sinkronisasi antara kompresi dan ventilasi. Kompresi dada tidak
dihentikan untuk pemberian ventilasi
Menurut AHA, kondisi yang mungkin terjadi pada pasien yang
telah dilakukan pertolongan breathing adalah (Adam, 2010):
· Tidak menekankan pemeriksaan breathing karena penolong baik
profesional maupun awam mungkin tidak dapat menentukan
secara akurat ada atau tidaknya napas pada pasien tidak sadar
karena jalan napas tidak terbuka atau karena pasien occasional
gasping dapat terjadi pada beberapa menit pertama setelah henti
jantung.
· Kembali tangan dan jari secapatnya ke tengah dada dan beri
kompresi dan ventilasi berikutnya, lanjutkan 30 kompresi dan 2
16

siklus napas .
· Sesudah 5 siklus kompresi dan ventilasi kemudian pasien
dievaluasi kembali. Jika tidak ada nadi karotis, dilakukan kembali
kompresi dan bantuan nafas dengan rasio 30 : 2.
· Jika ada nafas dan denyut nadi teraba letakkan pasien pada posisi
mantap (recovery position).
· Jika tidak ada nafas tetapi nadi teraba, berikan bantuan nafas
sebanyak 10- 12 x/menit dan monitor nadi setiap 2 menit.
· Jika sudah terdapat pernafasan spontan dan adekuat serta nadi
teraba, jaga agar alan nafas tetap terbuka.
· Jika mengalami kesulitan untuk memberikan nafas buatan yang
efektif, periksa apakah masih ada sumbatan di mulut pasien serta
perbaiki posisi tengadah kepala dan angkat dagu yang belum
adekuat.
· Bila pasien kembali bernafas spontan dan normal tetapi tetap
belum sadar, ubah posisi pasien ke recovery position, bila pasien
muntah tidak terjadi aspirasi.
· Waspada terhadap kemungkinan pasien mengalami henti nafas
kembali, jika terjadi segera terlentangkan pasien dan lakukan
nafas buatan kembali.
6. RJP terus dilakukan hingga alat defibrilasi otomatis datang, pasien
bangun, atau petugas ahli datang. Bila harus terjadi interupsi,
petugas kesehatan sebaiknya tidak memakan lebih dari 10 detik,
kecuali untuk pemasangan alat defirbilasi otomatis atau
pemasangan advance airway.
7. Alat defibrilasi otomatis (Automatic External Defibrilation).
Penggunaanya sebaiknya segera dilakukan setelah alat
tersedia/datang ke tempat kejadian. Pergunakan program/panduan
yang telah ada, kenali apakah ritme tersebut dapat diterapi kejut
atau tidak, jika iya lakukan terapi kejut sebanyak 1 kali dan
lanjutkan RJP selama 2 menit dan periksa ritme kembali. Namun
17

jika ritme tidak dapat diterapi kejut lanjutkan RJP selama 2 menit
dan periksa kembali ritme. Lakukan terus langkah tersebut hingga
petugas ACLS (Advanced Cardiac Life Support ) datang, atau
korban mulai bergerak.
Perbedaaan Langkah BLS Sistem ABC dan CAB (Lasprita, 2012):No ABC CAB1 Memeriksa respon pasien Memeriksa respon pasien termasuk
ada/tidaknya nafas secara visual.2 Melakukan panggilan darurat
dan mengambil AEDMelakukan panggilan darurat
3 Airway (Head Tilt, Chin Lift) Circulation (Kompresi dada dilakukan sebanyak satu siklus 30
kompresi, sekitar 18 detik)4 Breathing (Look, Listen, Feel,
dilanjutkan memberi 2x ventilasi dalam-dalam)
Airway (Head Tilt, Chin Lift)
5 Circulation (Kompresi jantung + nafas buatan (30 : 2))
Breathing ( memberikan ventilasi sebanyak 2 kali, Kompresi jantung
+ nafas buatan (30 : 2))6 Defribilasi
2) Kondisi emergensi kedokteran gigi
Kegawatdaruratan di kedokteran gigi adalah suatu keadaan dimana terdapat trauma terhadap mulut yang melibatkan gigi yang tercabut, rahang yang bergeser dan trauma wajah atau fraktur. Kegawatdaruratan ini menyangkut rasa sakit, perdarahan, infeksi dan estetika dimana ada keadaan-keadan tertentu yang irreversible bila tidak ditangani dengan cepat.
Berikut merupakan contoh kasus kegawadaruratan dalam bidang
kedokteran gigi:
a) Nyeri pada gigi
1. Abses dentoalveolar
Tanda dan Gejala klinis:
18

Nyeri yang spontan dan hebat, berlangsung selama beberapa jam terlokalisir dengan baik dan ditimbulkan oleh proses pengunyahan. Gusi dari gigi yang bersangkutan sering teraba lunak dan terdapat fluktuasi cairan. Absesnya dapat berbentuk (“gumboil” atau abses subperiosteal pada gusi) kadang dengan pembengkakan wajah, demam dan sakit. Pada kondisi akut umumnya belum terbentuk jalan keluar untuk pusTreatment:
Terapi utama adalah untuk mengeluarkan abses dari gigi yang bersangkutan, dengan cara insisi dan drainase pus, open bur pada gigi. Situasi yang akut ini biasanya menyembuh tetapi absesnya dapat timbul lagi apabila pulpa yang nekrotik tersebut terinfeksi kembali, kecuali dilakukan perawatan endodontik atau pencabutan gigi.Untuk obat yang dapat diberikan adalah antibiotik (metronidazol/amoksisilin) dan analgesik (ibuprofen).
2. Pulpitis akut
Tanda dan Gejala klinis:
Nyeri spontan, intermiten, tajam, dan sensitif terhadap
perubahan suhu panas dan dingin. Terdapat pada gigi yang
bermasalah yaitu berupa karies, fraktur, tumpatan yang besar.
Treatment:
Terapi segera yang dapat dilakukan yaitu dengan memberi
Zoe pada gigi bermasalah yang telah dipreparasi, lalu ditutup
sementara menggunakan GIC. Pasien diberikan obat
analgesik. Untuk terapi lanjutan dapat dilakukan pilihan
perawatan saluran akar seperti pulpcapping, pulpotomi,
pulpektomi
b) Trauma
1. Avulsi
19

Tanda dan Gejala klinis:
Lepasnya gigi dari soketnya, umunya dapat disertai dengan
adanya trauma
Treatment:
Gigi yang avulsi harus langsung di replantasi dalam soket. Gigi yang kotor dibersihkan tanpa menghilangkan serabut periodontal pada bagian servik gigi. Rendam dengan larutan air garam steril, dan apabila soket terisi bekuan darah, hilangkan dengan irigasi larutan garam. Tanam kembali gigi dengan benar sesuai permukaannya secara manual tekan soketnya dan balut giginya. Jika penanaman kembali tidak dapat dilakukan segera, taruh gigi pada larutan isotonik seperti susu segar dingin yang terpasteurisasi, larutan garam Nacl atau larutan lensa kontak (Weine, 2002). Tindakan yang harus dilakukan dokter gigi adalah mengirigasi soket dengan larutan saline, dan memeriksa soket apakah terdapat sisa akar atau tulang yang fraktur. Gigi direplantasi dalam soket secepatnya saat golden time yaitu selama 2 jam paska avulsi dengan harapan prognosisnya akan baik menggunakan soft arch wiring. Teknik splinting yangdirekomendasikan adalah fiksasi semi rigid selama 7-10 hari (Trope, 2002). Setelahnya pasien diberi obat analgesik. Satu minggu setelah replantasi, pasien diharap datang untuk melakukan perawatan lanjutan yaitu perawatan endodontik
2. Dislokasi mandibula
Tanda dan Gejala klinis:
Pembukaan rahang yang terlalu lebar dapat
menyebabkan condylus bergeser ke depan atas,
anterior dari eminensia sehingga mulut pasien
terbuka terus tidak dapat menutup.
Treatment:
Proses pengembalian posisi dapat dilakukan dengan menghadap wajah pasien dan meletakkan ibu jari tangan kanan dan kiri yang sudah dibalut perban pada gigi molar
20

bawah dan lakukan tekanan ke arah bawah secara bersaman dengan jari lainnya dibawah dagu, dorong dari bawah ke atas. Apabila otot-otot mengalami spasme, dapat diberikan midazolam i.v. Apabila posisi rahang sudah kembali, hindari pembukaan rahang yang lebar.
3. Fraktur gigi
Tanda dan Gejala klinis:
Treatment:
4. Fraktur Mandibula
Tanda dan Gejala klinis:
Fraktur yang berat pada sympysis yang mengalami remuk, lidah dapat terdorong ke belakang dan menyumbat jalan nafas, dan ini perlu dicegah. Fraktur sederhana yang tidak bergeser dapat dirawat secarakonservatif dengan diet lunak apabila gigi tidak rusak. Jika fragmen bergeser, nyeri cenderung terjadi
Klasifikasi dan Treatment:
a. Berdasarkan lokasi terjadinya fraktur
Gambar 2.6 Regio trauma mandibula
b. Berdasarkan ada tidaknya gigi menurut Kazanjian dan Converse, lasifikasi berdasarkan gigi pasien penting diketahui karena akan menentukan jenis terapi yang akan kita ambil. Dengan adanya gigi, penyatuan fraktur dapat
21

dilakukan dengan jalan pengikatan gigi dengan menggunakan kawat:Fraktur kelas 1: gigi terdapat di 2 sisi fraktur,
penanganan pada fraktur kelas 1 ini dapat melalui interdental wiring (memasang kawat pada gigi)
Fraktur kelas 2: gigi hanya terdapat di salah satu fraktur
Fraktur kelas 3: tidak terdapat gigi di kedua sisi fraktur, pada keadaan ini dilakukan melalui open reduction, kemudian dipasangkan plate and screw, atau bisa juga dengan cara intermaxillary fixation.
5. Fraktur rahang
Tanda dan Gejala klinis:
Diagnosa frakturnya dari anamnesa yaitu nyeri, bengkak, memar, pendarahan (biasanya dalam mulut), adanya fragmen yang bergeser (adanya krepitasi), oklusi yang tidak rata, paresthesia dan anesthesia dari saraf yang bersangkutan dan tanda-tanda fraktur pada radiografi.Treatment:
Penatalaksanaan fraktur, walaupun terjadi kerusakan wajah yang parah, bukan merupakan prioritas yang utama. Namun serpihan seperti gigi yang patah, darah, atau air liur harus dibersihkan dari mulut. Dan diperlukan pembebasan jalan nafas orofaringeal. Tindakan yang terutama adalah membebaskan jalan nafas. Bebaskan semua trauma pada pasien sepanjang jalan nafas dengan pedoman ATLS. Pendarahan dari pecahnya arteri inferior gigi biasanya berhenti dengan sendirinya. Tetapi timbul kembali pada traksi mandibula. Pendarahan maxillofacial yang hebat dapat ditamponade dengan fiksasi craniofacial,. Pendarahan dapat timbul dari fraktur tulanghidung, dimana dibutuhkan fiksasi pada hidung. Jika pendarahan berulang, pembuluh darah yang rusak harus dijahit.Masalah lain yang mengancam kehidupan seperti pendarahan intracranial, pendarahan hebat dari organ lain dan kerusakan tulang leher harus segera ditangani.
22

6. Fraktur midfacialKlasifikasi dan Tanda Gejala klinis:
Klasifikasi Fraktur Le Fort :
Gambar 2.7 fraktur Le Fort
Le Fort I : bagian bawah dasar hidung segmentasi / horizontal dari processus alveolaris (pembengkakan bibir bagian bawah)
Le Fort II : unilateral atau bilateral maksila (subzygomaticus),menyebabkan bengkak pada wajah yang masif (ballooning) dan (Panda Facies)
Le Fort III : Seluruh maksila (suprazygomatic) dan satu atau lebih tulang wajah terpisah dari kerangka craniofacial (terjadi pembengkakan wajah masif dan kebocoran cairan serebrospinal melalui hidung). Mungkin terdapat pula penyumbatan jalan nafas, cedera kepala, cedera dada, robekan organ visceralis, fraktur tulang belakang dan tulang panjang.
Treatment:Sebagian besar fraktur sepertiga tengah dirawat dengan pembedahan dan fiksasi dengan mini plate.
b) Inflamasi
1. Dry socket
Tanda dan Gejala klinis:
Alveolar osteitis atau dry socket terjadi akibat soket bekas pencabutan kehilangan pembentukan bekuan darah. Kondisi ini terjadi setelah 2 - 4 hari
23

post ekstraksi, dapat terjadi nyeri yang meningkat, halitosis,rasa tidak enak, rongga gigi yang kosong (empty socket), dan terasa lunak.Treatment:
Irigasi dengan air garam hangat (50°C) atau cairan chlorhexidine, kemudian menutup socket dengan sedative dressing seperti eugenol atau alvolgyl. Berikan analgesik dan antibiotik (amoksisilin atau metronidazol). Perawatan ini tidak dapat dilakukan bila ada akar yang tertinggal, benda asing, fraktur rahang, osteomielitis, atau penyebab lain khususnya bila ada demam, nyeri yang menetap atau gangguan neurologis lain seperti rasa baal pada bibir.
2. Periodontal Abses
Tanda dan Gejala klinis:
Treatment:
3. Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis (ANUG)
Tanda dan Gejala klinis:
Treatment:
c) Komplikasi pasca pencabutan
1. Terbukanya sinus maksilaris
Tanda dan Gejala klinis:
Masuknya gigi ke dalam antrum, sehingga
menyebabkan
sinus robek. Terdapat gelembung udara pada
bekas soket
pencabutan
Treatment:
Pasien dapat diberi terapi antimikroba dan dekongestan hidung dan cari gigi tersebut dengan radiografi. Terapi selanjutnya memerlukan tindakan bedah
24

2. Perdarahan
Tanda dan Gejala klinis:
Treatment:
d) Kondisi lainnya
1. Overdosis anestesi
Tanda dan Gejala klinis:
Treatment:
2. Synkop
Tanda dan Gejala klinis:
Treatment:
3. Tertelan instrumen kedokteran gigi
Tanda dan Gejala klinis:
Treatment:
25

BAB III
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Dinkes, 2004, Definisi OperasionalStandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Propinsi Jawa Timur
Andrew H, Travers. Thomas D, Rea. Bentley J, Bobrow et al. CPR Overview: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122;S676-S684
26

Diana M, Cave. Raul J, Gazmuri. Charles W, Otto et al. CPR Techniques and Devices: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122;S720-S728
Robert A, Berg. Robin, Hemphill. Benjamin S, Abella. Tom et al. Adult Basic Life Support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010;122;S685-S705
Muhammad Ashar. Maret 2011. Planning cardiac emergency medical service with Mobile
application in aceh rural. http://www.acehpublication.com/adic2011/ADIC2011-039.pdf.
diakses Kamis, 20 September 2012 pukul 08:30 WIB.
Lasprita, L., 2012, Bantuan Hidup Dasar (BLS). http://www.scribd.com/doc/84871056/Bantuan-
Hidup-Dasar. diakses Kamis, 20 September 2012 pukul 08:30 WIB.
Adam, M., 2010, Resusitasi Jantung Paru Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia, dalam http://www.scribd.com/doc/95942220/Resusitasi-Jantung-dan-Paru-Bahasa-Indonesia-Versi-AHA-2010, diakses 01 Mei 2013
27