Makalah Tradisi Sariga Yang Kini Terlupakan - Muhamad Arzan-libre
-
Upload
g-danu-pratomo -
Category
Documents
-
view
87 -
download
21
description
Transcript of Makalah Tradisi Sariga Yang Kini Terlupakan - Muhamad Arzan-libre
-
MAKALAH BAHASA INDONESIA
TRADISI SARIGA YANG KINI TERLUPAKAN
Disusun oleh :
Nama : Muhamad Arzan
NIM : F1B113021
Program Studi : Fisika
Jurusan : Fisika
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Halu Oleo
Kendari
2013
-
1
KATA PENGANTAR
Puji sukur penyusun panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
limpahan rahmat hidayah dan kerunia-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan.
Disamping itu, penyelesaian karya ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian
karya tulis ini.
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu
saran dan kritik yang membangun selalu penyusun harapkan demi perbaikan-
perbaikan selanjutnya. Akhirnya penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca.
Kendari, 27 November 2013
Penyusun
-
2
Daftar Isi
Halaman Sampul ........................................................................................................ 0
Kata Pengantar .......................................................................................................... 1
Daftar Isi ..................................................................................................................... 2
Bab I Pendahuluan ..................................................................................................... 3
1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 3 1.2. Rumusan Masalah ..................................................................................... 4
1.3. Tujuan........................................................................................................ 4 1.4. Manfaat...................................................................................................... 4
Bab II Tinjauan Pustaka ............................................................................................. 5
Bab III Pembahasan ..................................................................................................... 8
Bab IV Penutup .......................................................................................................... 13
4.1. Kesimpulan.............................................................................................. 13
4.2. Saran ........................................................................................................ 13
Daftar Pustaka ............................................................................................................ 14
-
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah kecil di ujung tenggara pulau Sulawesi dengan keajaiban alam, keindahan dan sumber-sumber alam yang menakjubkan. Ditambah dengan budaya dan sejarah didaerah ini yang sangat banyak.
Dewasa ini Muna adalah tempat yang menarik. Muna adalah suku yang jumlahnya paling besar diantara orang-orang Buton, dengan jumlah jiwa 300.000. Orang Muna yang tinggal dalam Kabupaten Muna merasa bangga menjadi orang muna dan mengidentifikasi diri dengan kota Raha, khususnya mereka yang tinggal di utara pulau ini (Coppenger, 2012).
Dalam masyarakat Muna terdapat falsafah daerah yang memiliki makna sangat mendalam. Dalam Muharto (2012) falsafah ini menggambarkan strukturisasi nilai yang ,menjadi prioritas dalam memilih landasan hidup. Bunyi falsafah tersebut adalah Hansuru-hansuru mbadha kono hansuru liwu. Hansuru-hansuru liwu kono hansuru adhati. Hansuru-hansuru adhati kono hansuru (tangka) agama.
Kabupaten Muna merupakan daerah yang cukup banyak memiliki cerita, tradisi dan realitas soisal budaya yang ada namun tidak terekam dengan baik atau tidak bnayak diketahui oleh masyarakat luas. Seiring dengan perjalanan waktu pada akhirnya cerita, tradisi dan realitas itu menjadi kabur, jauh dan tenggelam secara perlahan-lahan, tanpa meninggalkan jejak. Hal itu patut dimaklumi karena pada saat ini sudah banyak masyrakat khususnya suku Muna yang tak mengetahui atau tidak pernah lagi menjalankan tradisi nenek moyang yang telah berkembang sejak zaman dahulu kala itu . Misalnya tradisi kasambu, kaago-ago, kafematai, kaalano wulu, kasampu, katoba, sariga, karia dan sebagainya, tradisi tradisi itu sekarang sebagian sedikit demi sedikit telah ditinggalkan atau dicampur adukkan dengan budaya barat. Selain hal itu, tradisi-tradisi tersebut termasuk bahasa daerah muna sendiri pun saat
-
4
ini dikategorikan sudah terancam punah, sebab banyak masyarakat mulai meninggalkan tradisi-tradisi tersebut dalam kehidupan sehari harinya, bahkan masyarakat yang tinggal dikampung-kampungpun sudah sedikit demi sedikit mulai meninggalkannya.
Oleh karena itu, muncul keinginan penulis untuk menghidupkan kembali cerita tradisi dan realitas kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Muna Pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya, khususnya yang menyangkut kehidupan masyarakat muna, melalui karya tulis ini. Adapun materi yang penulis angkat adalah salah satu tradisi yang kini mulai terlupakan yaitu tradisi sariga.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diuraikan sebagai berikut.
a. Apakah yang dimaksud dengan tradisi sariga?
b. Bagaimana pelaksanaan tradisi sariga ?
c. Bagaimana eksistensi tradisi sariga di Kabupaten Muna saat ini ?
1.3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis ini adalah dapat
mengetahui bagaimana pelaksanaan dan eksistensi tradisi sariga di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
1.4. Manfaat
Manfaat dari karya tulis ini adalah tidak lain agar para pembaca dapat menghidupkan kembali kebudayaan daerah muna yang saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan dan bahkan banyak yang mendekati ambang kepunahan.
-
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Koentjaraningrat (2010) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.
Menurut Selo Soemardjan (1993) kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karya masyarakat yang dimanfaatkan menurut karsa masyarakat itu.
Budaya menurut Taylor (1871) merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Keesing, 1981).
Dalam Muharto (2012) Kroeber dan Kluckhohn memberikan definisi kebudayaan dari sisi historis sebagai warisan yang dialih-turunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (seringkali) lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah (Wikipedia, 2013).
Dalam masyarakat Muna terdapat falsafah budaya daerah yang memiliki makna sangat mendalam. Dalam Muharto (2012) falsafah ini menggambarkan strukturisasi nilai yang ,menjadi prioritas dalam memilih landasan hidup. Agama merupakan nilai tertinggi yang harus diprioritaskan. Dalam falsafah tersebut mengharuskan agar agama dapat menjadi fondasi yang harus dipertaruhkan dalam totalitaspotensi yang dimiliki oleh seseorang . Bunyi falsafah tersebut adalah
-
6
Hansuru-hansuru mbadha kono hansuru liwu. Hansuru-hansuru liwu kono hansuru adhati. Hansuru-hansuru adhati kono hansuru (tangka) agama.
Pesta katoba adalah pesta pada waktu anak-anak diislamkan pada umur kira-kira sebelas tahun atau hampir mencapai umur kedewasaan. Para anak laki-laki termasuk golongan maradika, dihiasi dengan pakaian yang paling bagus memakai pengikat kepala sama dengan yang dipakai oleh lakina agama, serta memakai sebuah keris. Para anak perempuan berpakaian lengkap dengan perhiasan keluarga (apabila keluarga tidak memiliki perhiasan maka dipinjam dari orang lain), wajah mereka dihiasi dengan bedak berwarna putih atau kuning muda, alis digunting rapi sehingga berbentuk sabit, rambut kepala dekat telinga dicukur sedikit, sedangkan rambut kepala bagian depan diselipkan sebuah pena rambut terbuat dari emas atau perak lengkap dengan perhiasan kecil-kecil yang melambai-lambai seperti daun-daun pohon yang tertiup angin bila mereka berjalan. Pendek kata, mereka ini dihiasi secantik mungkin.
Kemudian para anak laki-laki dan perempuan dari golongan La Ode yang telah didandani itu, dipikul diatas bahu oleh beberapa anggota keluarganya dan diantar kepada pejabat agama, dalam hal ini lakina agama, imam atau khatib. Pada golongan wesembali dan maradika anak-anak ini harus berjalan, pejabat agama mereka adalah modhi bhalano (Couvreur, 2001).
Tradisi sariga merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi sakral yang
biasa dilakukan oleh masyarakat suku Muna, di Sulawesi Tenggara. Tradisi ini wajib dilakukan oleh orang tua yang telah memiliki sepasang anak laki-laki dan perempuan. Tradisi ini dilakukan dengan harapan agar anak nantinya menjadi anak yang shaleh dan tidak durhaka kepada kedua orang tuanya (Wikipedia, 2013).
Apabila anak telah dapat mengenal atau membedakan ibu dan bapaknya dengan orang lain, maka dia diwajibkan mengikuti pendidikan yang dalam bahasa muna dikenal dengan sebutan sariga (Fariki, 2010).
Pendekatan pengajaran materi toba pada sariga berbeda dengan pendekatan pada mangkilo/kangkilo. Toba pada sariga diberikan dalam bentuk perbuatan yaitu membanting-banting kepala anak sebanyak 7 kali dipapan setiap pagi dan sore
-
7
selama 4 hari. Makna membanting-banting kepala, yaitu agar anak selalu taat pada perintah orang tua atau tidak durhaka kepada orang tua (Fariki, 2009).
Sariga dilakukan pada saat seorang anak berumur antara 1-10 tahun. Makna prosesi ini adalah supaya anak kelak tidak menjadi manusia durhaka, tetapi dapat menghormati kedua orang tuanya. Anak dilatih sejak dini agar mereka patuh terhadap orang tua.
Cara prosesi ini, yaitu gendang dipukul menurut irama Muna dan anak dimandikan sambil disandar sandarkan kepala si anak di lantai yang telah dipersiapkan sebanyak 7 kali mengikuti irama gendang. Acara ini berlangsung setiap pagi dan sore hari selama 4 hari. Acara ini ditutup dengan doa selamat (Fariki, 2009).
Menurut Caleb Coppenger (2012) di Kabupaten Muna terdapat banyak ritual dan upacara tradisional yang dilakukan dimasa silam, namun ada beberapa ritual dan upacara tradisional yang sudah tidak dilakukan lagi.
-
8
BAB III
PEMBAHASAN
Kabupaten Muna merupakan daerah kecil di ujung pulau Sulawesi. Daerah ini beribukotakan kota Raha dengan jumlah penduduk 248.461 jiwa (Survei Sosial Ekonomi Nasional - BPS 2010). Pada daerah ini kita dapat melihat cukup banyak keindahan alam, sumber-sumber sejarah yang masih terjaga, budaya, cerita-cerita tradisional (folklore, mitos, dan legenda), tradisi serta realitas soisal budaya yang menarik. Di daerah ini kita masih dapat menjumpai berbagai tradisi-tradisi yang merupakan warisan budaya dalam masyarakatnya. Tradisi-tardisi ini telah berjalan sejak masa lampau dan dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satunya adalah tradisi sariga.
Sariga merupakan salah satu bentuk tradisi pada masyarakat suku Muna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang kini mulai terlupakan. Sariga biasa dilakukan oleh masyarakat suku Muna pada anak yang baru mulai tumbuh gigi atau pada anak yang akan memasuki usia balig/dewasa (berusia antara 1-10 tahun). Tradisi ini dilakukan dengan harapan agar anak yang disariga tidak menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya serta agar sang anak cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Selain hal itu tradisi ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengobati anak-anak suku Muna yang terkena penyakit kulit, seperti kudis agar cepat sembuh dari penyakitnya. Tradisi ini dilakukan pada hari yang dianggap baik oleh suku Muna, berdasarkan perhitungan/penanggalan yang masih menggunakan cara yang sangat tradisional berdasarkan penampakan bulan dilangit.
Tradisi sariga dahulu merupakan tradisi sakral dikalangan suku Muna, pelaksanaannya memiliki makna agar anak kelak tidak menjadi manusia durhaka, yang melupakan orang tua dan Tuhannya, namun menjadi anak-anak shaleh dan tetap berbakti serta menghormati kedua orang tuanya. Para orang tua berharap anak yang disariga nantinya akan menyadari bahwa semua perbuatan yang akan dilakukannya kelak ketika memasuki usia balig/dewasa akan mendapat balasan dari
-
9
Allah SWT, Sang Pencipta Alam Semesta. Kebaikan akan dibalas dengan pahala, sebaliknya keburukan akan dibalas dengan dosa. Yang nantinya hasil perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Berbeda dengan katoba yang menerapkan pemberitahuan dan pengingatan kepada sang anak agar patuh dan taat terhadap orang tuanya serta tidak melupakan Allah SWT selaku Tuhan yang menciptakannya , tradisi ini lebih menekankan pengingatan terlebih dahulu dalam bentuk perbuatan kepada sang anak.
Dalam budaya muna, apabila suatu keluarga telah memiliki sepasang anak laki-laki dan anak perempuan, maka keluarga tersebut telah diwajibkan untuk melaksanakan tradisi sariga.
Syarat-syarat dalam Tradisi Sariga Syarat untuk melakukan tradisi ini tidak terlalu sulit. Syarat ini merupakan
syarat utama untuk melaksanakan tradisi sariga . Adapun syarat untuk melaksanakan tradisi sariga adalah sebagai berikut:
a. Keluarga yang akan melaksanakannya telah memiliki sepasanang anak laki-
laki dan anak perempuan.
b. Keluarga wajib menyediakan bahan-bahan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan tradisi sariga.
c. Tradisi ini dilakukan pada hari yang dianggap baik berdasarkan perhitungan penanggalan para pemuka suku muna.
Dalam pelaksanaanya pihak keluarga diwajibkan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosesi sariga. Bahan-bahan mudah ditemukan dilingkungan sekitar masyarakat muna. Bahan-bahan yang wajib disediakan oleh keluarga yang akan melaksanakan tradisi ini adalah sebagai berikut:
1. Selembar papan
2. Pucuk bunga kelapa (bansa)
-
10
3. Pelepah kulit batang pinang (kulubhea)
4. Umbi-umbian yang dalam suku muna dikenal sebagai mafu.
5. Sebatang pohon pisang
6. Sebatang Tebu yang masih berdaun
7. Pelepah kelapa
8. Gerabah tanah (nuhua wite)
9. Keranjang buah
Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Sariga Tata cara pelaksanaan tradisi ini memiliki cara yang beragam disetiap kampung
atau kecamatan di Kabupaten Muna. Tata cara yang akan penulis uraikan disini adalah tata pelaksanaan tradisi sariga yang umum digunakan. Tradisi ini biasa dimulai dari malam hari dan dilanjutkan pada pagi harinya.
Adapun tata cara pelaksanaan tradisi ini pada malam hari adalah anak yang akan disariga terlebih dahulu dimandikan oleh orang tua/sesepuh kampung, dan diiringi dengan pukulan gong dan gendang sesuai dengan irama muna. Setelah dimandikan, anak tersebut dibaringkan sejenak diatas papan yang telah dipersiapkan, sebelumnya pepan tersebut dilapisi dahulu dengan pelepah pohon pinang (kulubhea). Kemudian kepala sang anak disandar-sandarkan secara perlahan (dibanting-banting secara halus) oleh orang tua/sesepuh kampung pada papan yang telah dilapisi pelepah batang pinang tadi sesuai irama pukulan gong dan gendang sebanyak 7 (tujuh) kali ke kanan dan 7 (tujuh) kali ke kiri .
Pada Pagi harinya, dilaksanakan kegiatan yang sama seperti pada malam harinya, yaitu anak yang akan disariga terlebih dahulu dimandikan oleh orang tua/sesepuh kampung, dan diiringi dengan pukulan gong dan gendang sesuai dengan irama muna. Setelah dimandikan, anak tersebut dibaringkan sejenak diatas papan yang telah dipersiapkan, sebelumnya papan tersebut dilapisi dahulu dengan pelepah pohon pinang (kulubhea). Kemudian kepala sang anak disandar-sandarkan secara
-
11
perlahan (dibanting-banting secara halus) oleh orang tua/sesepuh kampung pada papan yang telah dilapisi pelepah batang pinang tadi sesuai irama pukulan gong dan gendang sebanyak 7 (tujuh) kali ke kanan dan 7 (tujuh) kali ke kiri . Setelah itu, anak-anak yang disariga diberi pakaian muna yang dilengkapi dengan pengikat kepala bagi laki-laki serta mereka didandani seelok/secantik mungkin. Bagi batita cukup diberi pakaian yang menarik. Apabila sang anak telah didandani sedemikian
rupa maka ia dibawa ketempat keluarga sang anak berkumpul untuk didoakan bersama dengan imam (modhi) kampung. Pada saat sang anak didoakan oleh imam (modhi) kampung biasanya keluarga/orang tua anak tersebut menyediakan dupa/menyan* (saat ini agar lebih praktis banyak yang menggunakan lilin) serta sesajen berupa bahan makanan yang diletakkan diatas nampan dan ditutup dengan penutup berupa kain putih.
Pada saat sang anak telah selesai didoakan, seseorang dari kelurganya (ayah/paman/sepupu) menunggunya diluar untuk memikulnya dibahu kemudian diarak keliling kampung. Biasanya sang anak dibawa menuju kearah timur sampai ketempat yang telah ditentukan diiringi dengan pukulan gendang dan gong serta tari-tarian suku Muna. Pada saat mulai mengarak biasanya didahului dengan para pesilat muna yang menunjukan kebolehannya dalam adu silat bersenjata tajam menggunakan parang (ewa wuna). Setelah tiba ditempat tujuan yang telah ditetapkan, sang anak diarak kembali kerumah.
Sambil menunggu arakan selesai, keluarga sang anak yang disariga menyiapkan sebatang pohon pisang yang telah ditancapkan di halaman rumah. Dibawah pohon pisang disiapkan pula keranjang buah untuk diletakkan mafu dan pucuk bunga kelapa (bansa). Disamping keranjang tersebut disusun rapih gerabah tanah (nuhua wite), pelepah kelapa, dan sebatang tebu yang masih berdaun.
Setelah tiba di rumah, satu dari para pesilat yang terdiri dari 4 orang memisahkan diri dari kelompoknya. Salah satu pesilat ingin menjaga pohon pisang dihalaman rumah sang anak dan yang lainnya ingin mencuri dan momotong pohon pisang tersebut. Akhirnya, satu dari ketiga pesilat yang ingin memotong pohon pisang yang dimaksud bertarung dengan yang menjaganya menggunakan senjata
-
12
tajam berupa parang/golok. Pertarungan mereka mengikuti irama pukulan gong. Irama pukulan gong yang dilakukan oleh pemukul gong tidak sembarang, apabila pemukul gong memukul dengan irama yang salah maka salah satu dari pesilat yang bertarung akan terluka parah terkena sabetan senjata tajam/parang. Sebelum memukul gong untuk pertarungan pesilat tersebut pemukul gong membaca mantra-mantra. Pertarungan akan berhenti apabila ada dua pesilat lainnya berhasil memotong
batang pisang tersebut. Pertarungan silat tersebut dapat pula menjadi hiburan bagi anak yang disariga ataupun para penonton dari keluarga besar orang tua anak yang disariga. Biasanya para penonton akan bersorak ketika batang pohon pisang berhasil dipotong/ditebas dengan menggunakan parang oleh salah seorang pesilat
Setelah batang pisang berhasil dipotong/ditebas oleh pesilat, anak yang akan disariga, dibanting-bantingkan pantatnya sebanyak tiga kali diujung potongan tersebut. Tiap bantingan mengikuti irama pukulan gong Tujuan membanting banting pantat anak pada ujung potongan tersebut adalah untuk menghilangkan katutura atau penyakit yang tidak dinginkan pada anak, biasanya untuk menghindarkan atau mengobati anak dari penyakit kulit seperti kudis.
Setelah rangkaian prosesi tersebut anak-anak yang disariga dilemparkan uang atau hadiah tertentu oleh keluarga sebagai tanda berakhirnya prosesi sariga.
Saat ini tradisi sariga banyak ditinggalkan oleh masyarakat muna . Salah satu penyebab ditinggalkannya tradisi ini adalah kurangnya perhatian masyarakat dan
pemerintah untuk menjaga budayanya akibat pengaruh moderenisasi dan globalisasi. Selain itu, dari tinjauan bahwa tradisi ini dapat mengobati/mencegah penyakit kulit hanya dianggap sebagai sebuah mitos belaka yang tidak terbukti secara medis. Namun bagi para orang tua yang rata-rata kelahiran tahun 50 an tradisi ini masih dianggap merupakan tradisi sakral dan apabila ada anak atau cucu mereka yang terkena penyakit kulit cara yang efektif untuk menyembuhkan penyakit kulit anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka adalah tradisi sariga. Tradisi ini masih dapat kita jumpai di daerah Tongkuno atau Wakuru, Kabupaten Muna.
-
13
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Tradisi sariga merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh suku Muna yang memiliki makna agar anak kelak tidak menjadi manusia durhaka, yang melupakan orang tua dan Tuhannya, namun menjadi anak-anak shaleh dan tetap berbakti serta menghormati kedua orang tuanya. Pelaksanaan tradisi ini melalui tahapan membentur-benturkan kepala anak yang akan disariga pada selembar papan yang telah dilapisi pelepah pohon pinang sebanyak 7 kali, pada malam dan pagi hari. Makna membanting-banting kepala, yaitu agar anak selalu taat pada perintah orang tua atau tidak durhaka kepada orang tua. Namun saat ini tradisi sariga mulai ditinggalkan, akibat tergerus arus arus moderenisasi dan globalisasi.
4.2. Saran
Penyusun berharap agar para pembaca dapat mengetahui tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Muna. Selain itu penyusun berharap masyarakat Muna paling tidak dapat menjaga atau menjalankannya, agar tradisi tersebut tidak ditinggalkan atau tidak akan punah dengan sendirinya. Oleh karena itu mari kita jaga tradisi ini sebagai salah satu unsur kebudayaan Indonesia.
-
14
Daftar Pustaka
BPS. 2010. Kebupaten Muna dalam Angka. Kendari: Badan Pusat Statistik Sulawesi
Tenggara.
Coppenger, Caleb. 2012. Misteri Kepulauan Buton: Menurut Sesepuh dan Saya
(dalam terjemahan Doreen Widjayana). Jakarta: Adonai
Couvreur, J. 2001. Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna (dalam terjemahan
Rene van den Berg). Kupang: Artha Wacana Press.
Fariki, La. 2009. Mengapa Perempuan Buton dan Muna dipingit. Kendari:
Komunika.
______.2009. Pusaka Moral dari Pulau Muna. Kendari: Komunika.
______.2010. Sistem Pendidikan Toba pada Masyarakat Buton dan Muna. Kendari:
Komunika.
Keesing, Roger M. 1981. Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer
(dalam terjemahan Gunawan Samuel). Jakarta: Erlangga.
Koentjaraningrat. 2010. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Muharto. 2012. Wuna Barakati: Antara Falsafah dan Realitas. Jogjakarta: Indie
Book Corner.
Soemardjan, Selo. 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
Wikipedia. 2013. Tradisi. http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi.
Wikipedia. 2013. Tradisi Sariga. http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi_Sariga.


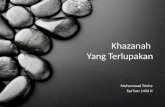

![Tuaian yang terlupakan [ok]](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5a64d7697f8b9ac21c8b6c07/tuaian-yang-terlupakan-ok.jpg)














