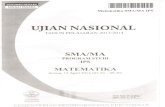Lembar Kerja Tutorial Ruang 11
-
Upload
ayoe-mutiah-dukomalamo -
Category
Documents
-
view
241 -
download
11
Transcript of Lembar Kerja Tutorial Ruang 11

TUGAS TUTORIAL
“ Modul Gangguan Endokrin”
Disusun Oleh :
Ruang Tutorial 11
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2014

Anggota Kelompok Tutorial 11
2
1 Lantu Gabrila Melinda 120111205
2 Dwi Yogyantara F.Isa 120111162
3 Semuel Johan Eman 120111265
4 Megi Lilingan 120111271
5 Yafet Tandayu 120111033
6 Lidiasani Perez Mosesa 120111045
7 Maria Estevina Siwi 120111245
8 Rionaldy Walasendow 120111125
9 Aqueline Nelly Faidiban 120111314
10 Naftalia T.S.Goni 120111233
11 Christine Meilani 120111291
12 Ayu Mutiah Dukomalamo 120111266
13 Ireine Soelingan 120111060
14 Lesley Zisilia Wangean 120111252
15 Miranda A.J.Makalew 120111049
16 Henry Crosby 120111101
17 Lisa Elsera Ritto 120111017
18 Billy Johanes Lombogia 120111051
19 Feibyg Th. Lumandung 100111049
20 Janet Walangitan 100111098
21 Junior Senkej 100111201
22 Gratia A. Tangkuman 100111040
23 Reinaldo Maramis 100111042
24 Yunita M. Umboh 100111178
25 Irene M.Sumayku 100111109
26 Indah S.Mampa
27 Marthalisa S. Sosir
28 Brigitha A. Situmorang

KASUS I
Trigger 1 Seorang pria 60 tahun, datang dengan keluhan kesemutan, rasa kebas
dan panas di ujung- ujung jari ke dua tangan sejak 2 minggu terakhir. Pasien juga mengeluh kedua tangan dan kaki membesar sejak beberapa tahun terakhir dan 2 tahun terakhir pasien tak dapat menggunakan cincin kawinnya. Ukuran sepatu membesar, dari no. 40 menjadi 43. Lidah terasa tebal sehingga agak sulit berbicara cepat.
Pada anamnesis lanjut, didapatkan riwayat tidur menggorok sejak 2 tahu terakhir, dan sering mengeluh nyeri kepala saat bangun tidur pagi hari. Tidak terdapat riwayat DM, hipertensi, nyeri sendi dan perubahan penglihatan. Libido berkurang, Tidak dijumpai riwayat tumor dan keganasan pada keluarga.
Trigger 2 Pemeriksaan klinis: Keadaan umum, compos mentis, cukup. Prognatisme + , penebalan hidung +, makroglosi +,Vital signs: T 37°C, RR - 18, pulse-80x/mnt, reg, BP- 150/100 Anemis: - ; Ikterik: - ; Sianosis : - ; Clubbing : - Edema : - ; kelenjar limfe: tak teraba, Teraba penebalan kulit serta diaporesis pada lengan dan tungkai. Kulit teraba berminyak.
MRITrigger 3 Pemeriksaan laboratorium: IGF-1 Puasa - 963ng/ml Random GH - 19.3ng/mL Gula darah puasa - 120mg/dlUji toleransi glukosa oral - 144mg/dl Trigliserida puasa - 170 mg/dl (53 - 150mg/dl) Serum prolaktin - normal
3

Scan MRI tampak gambaran makroadenoma hipofisis yang menginvasi sinus cavernosus, optic chiasma tidak terdorong.
I. Kata Sulit: 1. Prognatisme: pembengkakan rahang 2. Makroglosi: lidah yang membengkak3. Clubbing: jari tabuh 4. Compos mentis: Sadar penuh, GCS 155. Diaporesis: mengeluarkan keringat 6. Makroadenoma: tumor jinak.
II. Kata kunci 1. Laki-laki 2. 60 tahun 3. Rasa kebas dan panas ujung-ujung ke-2 jari tangan 4. Kedua tangan dan kaki membesar 5. Lidah terasa tebal 6. Agak sulit berbicara cepatt .
III. Masalah dasar:Kesemutan,rasa kebas dan panas di ujung-ujung jari kedua tangan.
IV. Pertanyaan
1. Langkah-langkah Anamnesis !
Anamnesis ini adalah tindakan yang sangat penting, dimana dengan
anamnesis yang baik dan benar ini kita dapat mendiagnosa sebuah kasus.
1.1 Identitas pasien
a) Nama
b) Jenis kelamin : Laki-laki
c) Umur : 60 tahun
d) Suku
e) Agama
4

1.2 Keluhan utama: kesemutan, rasa kebas dan panas di ujung-
ujung jari kedua tangan, serta kedua tangan dan kaki membesar.
1.3 Riwayat penyakit sekarang
Riwayat penyakit sekarang merupakan deskripsi keluhan utama dan gejala
penting secara detil
a) Lokasi keluhan
b) Waktu dan lamanya keluhan berlangsung :
- Kesemutan, rasa kebas dan panas di ujung-ujung jari kedua
tangan sudah sejak 2 minggu terakhir.
- Tangan dan kaki membesar sudah sejak beberapa tahun.
c) Sifat dan gejala yang menyertai
- Apakah tampilan wajah pasien berubah ? (mintalah melihat
foto sebelumnya)
- Apakah ada perubahan ukuran sepatu (kaki membesar) ? dan
apakah cicin tidak muat lagi (tangan membesar) ?
- Apakah pandangan kabur, penglihatan perifer berkurang ?
- Apakah pasien mengalami nyeri kepala, kelelahan, dan berat
badan bertambah ?
- Apakah pasien mengalami hiperglikemia, seperti poliuria dan
polidipsia ?
(hiperglikemia adalah peningkatan glukosa secara abnormal
dalam darah, seperti pada diabetes melitus. Poliuria adalah
pasase volume urin yang besar dalam periode tertentu.
Polidibsia adalah rasa haus dan intake cairan kronik yang
berlebihan)
- Apakah pasien mengalami galaktorea ?
(galaktorea adalah air susu yang berlebihan atau aliran spontan
air susu tanpa tujuan untuk menyusui)
- Apakah menstruasi pasien tidak teratur ?
- Apakah pasien mengalami impotensi ereksi ?
- Apakah pasien berkeringat berlebihan ?
- Apakah pasien mengalami carpal tunnel syndrome ?
(carpal tunnel syndrome adalah kompleks gejala yang
disebabkan oleh penekanan nervus medianus di terowongan
5

karpal, dengan nyeri dan rasa terbakar atau paraestesia yang
menggelitik di jari-jari tangan, terkadang meluas ke siku)
d) Frequensi, faktor yang memberatkan dan yang meringankan
e) Perkembangan penyakit, apakah sudah ada komplikasi
f) Riwayat pengobatan dan riwayat orang yang menderita keluhan
yang sama
1.4 Riwayat penyakit dahulu
a) Riwayat penyakit yang pernah diderita dan pengobatannya
- Apakah pasien mengetahui ada riwayat akromegali ?
- Pernahkah pasien menjalani terapi dengan radioterapi, obat-
obatan dan pembedahan ?
b) Riwayat operasi/kecelakaan
c) Alergi
d) Riwayat skrining penyakit keganasan
1.5 Anamnesis sistem
Anamnesis sistem merupakan deskripsi keluhan/masalah ulai dari
kepala hingga anggota gerak, saraf dan otot, status kejiwaan dan masalah
emosional
a) Rerata berat badan, adakah riwayat kenaikan atau penurunan berat
badan.
b) Problem khusus pasien usia lanjut : riwayat jatuh,dan kehilangan
keseimbangan, mobilisasi, polifarmasi, skrining osteoporosis serta
gangguan fungsi berbagai organ.
1.6 Riwayat kesehatan keluarga
Riwayat penyakit keluarga merupakan riwayat penyakit yang pernah
diderita dalam keluarga atau riwayat penyakit herediter.
1.7 Riwayat pribadi, sosial-ekonomi, budaya
a) Aktivitas sebeum sakit, hobi
b) Pola makan dan komposisi makan
c) Kebiasaan merokok, minum teh, kopi, obat, jamu atau narkoba
d) Pola tidur
e) Riwayat perjalanan ke luar kota, imunisasi
6

2. Pada anamnesis mengapa ditanyakan riwayat tidur mengorok dan mengeluh nyeri kepala saat bangun?
2.1 Riwayat tidur menggorok
Lebih dari 50% pasien akromegali mengalami obstruktive dan central
sleep apnea (apnea = henti napas). central sleep apnea adalah sleep
apneaakibat kegagalan pusat pernapasan di medulla. Obstruktive sleep apnea
adalah sleep apnea akibat obstruksi atau kolaps jalan napas dengan hambatan
pada tonus otot yang terjadi selama tidur. Pada pasien akromegali, obtruksi
pada saluran pernapasan atas ini dapat disebabkan oleh pelebaran lidah dan
penebalan jaringan di laring. Akibatnya saluran napas saat tidur mengalami
penyempitan. Penyempitan itulah yang menyebabkan getaran pada bagian
lunak saluran napas sehingga menghasilkan suara dengkuran.
2.2.2 Nyeri kepala
Tekanan intrakranial juga dapat terjadi pada tumor yang tumbuh.
Gejalanya meliputi sakit kepala, muntah, dan papiledema (pembengkakan di
saraf optikus masuk ke rongga mata).
3. Etiologi
3.1. Adenoma pituitari, berasal dari tipe sel somatotrof (tersering)3.2. Peningkatan GHRH (GH releasing hormone) yang dihasilkan oleh
tumor hipotalamus 3.3.Ektopik GHRH / GH ektopik dari tumor non endokrin : karsinoid,
sel-islet tumor pankreas, dan neoplasma bronkial.
4. Epidemiologi
Akromegali adalah lebih umum daripada gigantisme, dengan kejadian 3-4 kasus per juta orang per tahun dan prevalensi 40-70 kasus per juta penduduk. Usia rata-rata untuk terjadinya acromegali adalah pada dekade ketiga kehidupan, penundaan dari onset berbahaya gejala untuk diagnosis adalah 5-15 tahun, dengan penundaan rata-rata 8,7 tahun. Usia rata-rata saat diagnosis untuk acromegali adalah 40 tahun pada pria dan 45 tahun pada wanita.
7

5. Uraikan pemeriksaan lanjutan apa yang diperlukan untuk
menegakkan diagnosis kelainan ini. Hubungkanlah pemeriksaan lab
yang abnormal dan gejala-gejala klinis yang ada pada kasus!
5.1 Pemeriksaan radiografik tengkorak
Berguna untuk mlihat adanya prubhan khas disrtai pmbsaran sinus
paranasalis, pebalan kalvarium, deformitas mandibula, serta penebalan
dan destruksi sela tursika yang menimbulkan dugaan adanya tumor
hipofisis.
5.2 CT scan
Berguna untuk memperlihatkan mikroadenoma hipofisis, srta
makroadenoma yang meluas ke luar sela mencakup juga sistem di atas
sela, dan daerah sekitar sela, atau sinus sfenoid.
6. Diagnosis
Alur Diagnosa Akromegali
Diagnosis kasus ini adalah Akromegali. Diagnosa akromegali
ditegakkan atas dasar gambaran klinis yang cukup jelas dan ditunjang
dengan pemeriksaan laboratorium dan ditemukannya :
1. Kadar GH tidak bisa ditekan sampai < 2ng/ml dalam 2 jam
8

2. Peningkatan kadar IGF-1 berdasarkan nilai normal untuk
usiannya.
3. Peningkatan kadar IGFBP-3
4. Tumor hipofisis atau tumor-tumor lain (hipotalamus , paru ,
pankreas , dll) pada pemeriksaan CT-Scan atau lebih baik pada
pemeriksaan MRI
7. Terangkan patologi dasar pada tingkat selular dan molecular pada kelainan ini.
Patologi seluler terjadinya sekresi dari GH yang berlebihan bisa
disebabkan oleh beberapa faktor dari segi molekuler antara lain terjadinya
mutasi pada protein G, MEN (multiple endocrin neoplasma) yakni terjadinya
mutasi pada garis germinal gen MEN 1 pada kromosom 11q 13, aktivasi
mutasi pada onkogen RAS dan ekspresi berlebihan dari onkogen c -
MYC.GH diaktivasi melalui respon yg diberikan GHRH (Growth Hormon
Releasing Hormon). Pada hormon hormon yang termasuk golongan
kelompok hidrofilik menggunakan perantaraan protein pengikat GTP.
Reseptor ini memiliki 7 domain hidrofilik yang dpt menembus membran
plasma. Reseptor ini menghasilkan sinyal melalui perantaraan protein terikat
nukleotida guanin, yang dikenal sebagai GPCR (G - protein coupled
receptor). Mutasi dpt terjadi pada protein G di tingkat gen tergantung pada
tahap transkipsi atau translasi protein. Dalam hal ini terjadi mutasi pada gugus
Pi pada protein GTP.Menyebabkan terjadinya perubahan pada tahap adenyl
cycalase dengan menggunakan second messenger cAMP.cAMP ini dihasilkan
9

dari penguraian ATP. PKA (protein kinase) terdapat dalam bentuk inaktif
sebagai heterotetramer R2C2 yang terdiri dari 2 subunit regulatorik dan 2
subunit katalitik.cAMP yang dihasilkan dari kerja adenil siklase mengikat
subunit R PKA. Hal ini menyebabkan terlepasnya subunit regulatorik dari
katalitik dan mengaktivasi subunit katalitik. Subunit katalitik kemudian
memfosforilase sejumlah protein target pada residu serin dan treonin.
Fosfatase mengeluarkan fosfat dari residu residu ini sehingga menghentikan
respon fisiologis, Fosfodiesterase juga dapat menghentikan respon dengan
mengubah cAMP menjadi 5 - AMP.
8. Uraikan manifestasi klinis yang dapat timbul pada kelainan ini !
Tangan dan kaki membesar akibat pertumbuhan jaringan lunak Raut wajah menjadi kasar akibat pembesaran sinus paranasalis dan
frontalis Tonjolan supraorbital Deformitas mandibula disertai prognatisme (rahang yang menonjol ke
depan) dan gigi geligi tidak dapat menggigit Gigi-gigi menjadi renggang akibat pembesaran mandibula Lidah membesar sehingg sulit bicara Suara menjadi lebih dalam akibat penebalan pita suara Dapat menimbulkan gangguan penglihatan jika tumor menekan optic
chiasma.
9. Ada hormon apa yang menyebabkan kelainan prognatisme, makroglosi, makroadenoma? serta kelenjar apa yang terganggu?
Yang menyebabkan kelainan prognatisme dan makroglosi adalah peningkatan hormon GH karena adanya ganggian kelenjar hipofisis yang berperan mengatur hormon pertumbuhan ini. Berdasarkan hasil MRI kepala dapat dilihat adanya makroadenoma hipofisis, gangguan inilah yang menyebabkan gangguan dan ketidakseimbangan metabolisme dari sebuah hormon.
10. Prognosis
Tanpa diobati, akromegali akan berakibat penyakit kardiovaskuler prematur dengan gejala-gejala yang progresif. Apabila pengobatan dapat menurunkan kadar GH sampai normal (< 2 – 2,5 ng/ml), angka kematian akan kembali normal. Pembedahan transsphenoid berhasil pada 80 – 90% pasien dengan tumor berdiameter < 2 cm dan kadar GH < 50 ng / ml. Pasca
10

pembedahan, biasanya faal hipofisis tetap baik, pembengkakan jaringan lunak menyusut, namun pembesaran tulang menetap.Kadar GH > 5 ng / ml yang makin meningkat setelah pengobatan menunjukkan rekurensi.Prognosis pada kasus akromegali tergantung penanganan.
V. Kesimpulan
Diagnosa kasus ini adalah akromegali yang merupakan
penyakit akibat tumor hipofisis
yang mensekresi hormon pertumbuhan berlebihan. Diagno- sis akromegali ditegakkan atas dasar temuan klinis, evaluasi laboratorium, dan pencitraan hipofisis. Tata laksana akro- megali yang ada saat ini meliputi terapi pembedahan, medikamentosa dan radioterapi.
11

DAFTAR PUSTAKA
o Guyton, A.C., John E. Hall, 2007. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta: EGC.
o Setiati, Siti. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik Komprehensif.
Jakarta : Interna Publishing. 2013.
o Gleadle Jonathan. At a Glance Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik.
Jakarta : Penerbit Erlangga. 2007.
o Dorland, Newman WA. Kamus Kedokteran Dorland Edisi 31.
Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2012.
o Corwin, Elizabeth J. Buku Saku Patofisiologi Edisi 3. Jakarta :
Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2009.
o Melmed S. Acromegaly pathogenesis and treatment.J. Clin Invest.2009:119(11):3189-202.
12

KASUS II
I. Kata Sulit
- Struma tiroid
- TRAb
- TgAb
- TPOAb
- Immunoassay
II. Kata Kunci
- Wanita 34 tahun
- Keluhan palpitasi dan sesak napas
- BB turun 42 kg
- Tremor halus di jari
- TSH rendah
- FT3 dan FT4 tinggi
- Eksoftalmus
III. Masalah Dasar
Seorang wanita 34 thn dengan keluhan palpitasi dan sesak napas pada aktivitas
13

IV. Pertanyaan
1. Pemeriksaan lanjutan apa yang harus dilakukan?
Pemeriksaan yang harus dilakukan antara lain:
1.1. TFT (Thyroid Function Tests)
Pada kecurigaan adanya kelainan tiroid maka dilakukan uji fungsi tiroid (thyroid function tests = TFT). Pada awal era pemeriksaan hormon tiroid, parameter yang tersedia adalah T4 total,T3 total, T3 uptake dan TSH. Penetapan T4 total tidak tepat menggambarkan fungsi tiroid sebab dipengaruhi oleh Thyroid binding globulin (TBG) sehingga hasil dapat tinggi atau rendah palsu, juga dipengaruhi oleh obat-obatan tertentu. Oleh karena itu ada parameter hitungan yaitu Free thyroxin index (FTI) yang didapatkan dari nilai T4 total x T3 uptake sebagai perkiraan kadar T4 bebas. FTI ini lebih baik daripada hanya kadar T4 total. Hasil yang tinggi sesuai dengan hipertiroidisme dan yang rendah sesuai dengan hipotiroidisme. TSH lama kurang peka, hanya dapat mendeteksi kadar tinggi sehingga hanya dapat mendiagnosis hipotiroid.
Dengan perkembangan teknik pengukuran yang makin peka maka dimungkinkan untuk mengukur kadar T4 bebas (FT4), T3 bebas (fT3) dan TSH sensitive (TSHs). Dengan adanya fT4 dan fT3 maka FTI tidak diperlukan lagi. TSHs dapat mengukur kadar TSH baik yang tinggi maupun rendah sehingga juga dapat mendiagnosis hipertiroid atau tirotoksikosis. Sekarang dengan TSH yang dimaksud adalah TSHs.
Pada sangkaan adanya kelainan tiroid baik gangguan fungsi maupun morfologi maka TFT dimulai dengan TSH, diteruskan dengan fT4 atau fT3. Di bawah ini ada 2 algoritme / bagan alir. Gambar 1 membedakan pasien rawat jalan dan rawat inap dan sudah menggunakan fT4 dan fT3, gambar 2 masih dengan T4 total dan T3 total.1,2
14

Gambar 1. Bagan alir diagnosis laboratorium gangguan fungsi tiroid pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.1
1.2 RAI (Tes ambilan yodium)
Digunakan untuk mengukur kemampuan kelenjar tiroid dalam menangkap dan mengubah yodida. Pasien menerima dosis yang akan ditangkap oleh tiroid dan di pekatkan setelah melewati 24 jam. Kemudian radioaktivitas yang ada dalam kelenjar tiroid tersebut dihutung. Normalnya, jumlah radioaktif yang diambil berkisar dari 10% hungga 35% dari dosis pemberian. Pada hipertiroidisme nilainya tinggi dan akan rendah bila kelenjar tiroid di tekan.
1.3. Ultrasonografi
Teknik ultrasonografi digunakan untuk menentukan apakah nodul tiroid yang teraba pada palpasi adalah nodul tunggal atau multipel, dan berkonsistensi padat atau kistik. Pemeriksaan ultrasonografi ini terbatas nilainya dalam menyingkirkan kemungkinan keganasan dan hanya dapat mengenal kelainan di atas penampang setengah sentimeter.
1.4. Pemeriksaan sitologi
Pemeriksaan sitologi nodul tiroid diperoleh dengan aspirasi jarum halus. Cara pemeriksaan ini berguna untuk menetapkan diagnosis karsinoma tiroid, tiroiditis, atau limfoma. Cara ini cara baik untuk menduga kemungkinan keganasan dalam nodul tiroid, dan mulai menggeser kegunaan pemeriksaan radioaktif atau ultrasonografi
15

sebagai pemeriksaan penunjang diagnosis.
1.5. Test darah hormon tiroid Tes darah yang disebutkan di atas bisa mengkonfirmasi adanya kekurangan atau kelebihan hormon tiroid dan, oleh karena itu, bisa digunakan untuk mendiagnosa hipotiroidisme atau hipertiroidisme. Mereka tidak menunjuk pada suatu penyebab spesifik.
1.6. X-ray scan, CAT scan, MRI scan (untuk mendeteksi adanya tumor).
1.7. Antibodi Tiroglobulin (Tg) Merupakan salah satu protein utama tiroid yang berperan dalam sintesis dan penyimpanan hormon tiroid. Tujuan tes : terutama diperlukan sebagai petanda tumor dalam pengelolaan karsinoma tiroid berdiferensiasi baik (well differentiated thyroid carcinoma). Kadar Tg akan meningkat pada karsinoma tiroid berdiferensiasi baik dan akan kembali menjadi normal setelah tiroidektomi total, kecuali bila ada metastasis. Kadar Tg rendah menunjukkan tidak ada jaringan karsinoma atau metastasis lagi. Kadarnya akan meningkat kembali jika terjadi metastasis setelah terapi.
2. Apakah dasar patologik kelainan endokrin ini di tingkat selular dan
molecular?
Penyakit graves adalah penyakit autoimun; pada gangguan tersebut terdapat beragam autoantibody dalam serum. Reseptor TSH adalah autoantigen terpenting yang menyebabkan terbentuyknya antibody. Meskipun peran antibody sebagai penyebab penyakit Graves tampaknya sudah dipastikan, apa yang men yebabkan sel B menghasilkan autoantibody tersebut masih belum jelas. Sekresi antibody oleh sel antibody oleh sel B dipicu oleh sel T penolong CD4+, yang banyak diantaranya terdapat di dalam kelenjar tiroid. Sel T penolong intratiroid juga tersensitisasi ke reseptor tirotropin, dan sel ini mengeluarkan faktor larut, seperti interferon- dan faktor nekrosis tumor. Faktor ini pada gilirannya memicu ekspresi molekul HLA kelas II dan molekul kostimulatorik sel T pada sel epitel tiroid, yang memungkinkan antigen tiroid tersaji ke sel T lain. Hal inilah yang mempertahankan pengaktifan sel spesifik-reseptor TSH di dalam tiroid. Sesuai dengan sifat utama pengaktifan tiroid, penyakit graves memperlihatkan keterkaitan dengan alel HLA-DR tertentu polimorfisme antigen 4 limfosit T sitotoksik (CTLA-4). Pengaktifan CLTA-4 dalam keadaan normal meredam respon sel T, dan mungkin sebagian alel mengizinkan pengaktifan sel T yang tak terkendali terhadap autoantigen.
Respons seluler dan humoral bekerja bersamaan dengan sasaran kelenjar tiroid. Kerusakan seluler terjadi karena limfosit T tersensitisasi (sensitized T-lymphocyte) dan/atau antibodi antitiroid berikatan dengan membran sel tiroid, mengakibatkan lisis sel dan reaksi inflamasi.
16

Sedangkan gangguan fungsi terjadi karena interaksi antara antibodi antitiroid yang bersifat stimulator atau blocking dengan reseptor di membran sel tiroid yang bertindak sebagai autoantigen (Tomer et al, 2003).
G e n y g t e r l i b a t d a l a m p a t o g e n e s i s P e n y a k i t T i r o u d A u t o I m u n ( P T A I )
adalah gen yang mengatur respons imun seperti major histocompatibility complex (MHC), reseptor sel T, serta antibodi, dan gen yang mengkode (encoding) autoantigen sasaran seperti tiroglobulin, TPO = thyroid peroxidase, transporter iodium, TSHR = TSH Receptor. CD40, anggotaTNF-R receptor berperan penting dalam aktivasi sel B, menginduksi proliferasi sel B dan sekresi antibodi. Pada penyakit Graves terjadi up-regulation ekspresi CD40 di kelenjar tiroid; CD40 merupakan gen yang suseptibel untuk penyakit Graves, yang diekspresikan dan fungsional di tirosit (Ridgway et al, 2007).
Cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) merupakan molekul kostimulator yang terlibat dalam interaksi sel T dengan Antigen Presenting Cells (APC). APC akan mengaktivasi sel T dengan mempresentasikan peptida antigen yang terikat protein HLA kelas II pada permukaan reseptor sel T. Sinyal kostimulator berasal dari beberapa protein yang diekspresikan pada APC (seperti B7-1, B7-2, B7h, CD40), dan berinteraksi dengan reseptor (CD28, CTLA-4, dan CD40L) pada permukaan limfosit T CD4+ pada waktu presentasi antigen. CTLA-4 dan CD40 merupakan molekul kostimulator non-spesifik, yang dapat meningkatkan suseptibilitas terhadap PTAI dan proses autoimun lain, tidak hanya pada penyakit Graves. CTLA-4 berasosiasi dan terkait dengan berbagai bentuk PTAI (penyakit Graves, tiroiditis Hashimoto,
17

dan pembentukan antibodi antitiroid), dan dengan penyakit autoimun lain seperti diabetes tipe 1, penyakit Addison, dan myasthenia gravis (Tomer et al, 2003).
Pada ras Kaukasus penyakit Graves berasosiasi dengan HLA-B8. Kemudian diketahui bahwa asosiasinya lebih kuat dengan HLA-DR3 yang mempunyailinkage disequilibrium dengan HLA-B8. Pada bangsa Jepang terdapat asosiasi dengan HLA-B35, pada bangsa Cina dengan HLA-Bw46, dan pada keturunan Afrika-Amerika dengan HLA DRB3*0202 (Tomer et al, 2003).
Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa apoptosis berperan dalam PTAI – tiroiditis Hashimoto dan penyakit Graves. Defek pada CD4(+) CD25(+) Tregulatory cells akan merusak (breaks) toleransi host dan menginduksi produksi abnormal sitokin yang akan menfasilitasi apoptosis. Terdapat perbedaan mekanisme yang memediasi proses apoptosis pada HT dan GD, yaitu pada HT akan terjadi destruksi tirosit sedangkan apoptosis pada GD akan mengakibatkan kerusakan thyroid infiltrating lymphocytes. Perbedaan mekanisme apoptotik tersebut akan mengakibatkan dua bentuk respons autotimun berbeda yang akhirnya akan menimbulkan manfifestasi tiroiditis Hashimoto dan penyakit Graves (Baker et al, 2007).
Sitokin berperan penting dalam mengkoordinasikan reaksi imun; sitokin dapat bersumber dari sistem imun maupun non-imun. Limfosit CD4+ Thelper terdiri dari sel Th1, terutama memproduksi interferon-γ (IFNγ) dan interleukin-2 (IL-2), yang menimbulkan respons imun langsung pada sel (cellmediated immunity). Sebaliknya, sel Th2 menghasilkan terutama
18

IL-4, IL-5, dan IL-13 yang akan mempromosikan respons imun humoral. Sel Th3 menghasilkan terutama TGFβ yang mempunyai peranan protektif dan pemulihan dari penyakit autoimun (Weetman et al, 2002).
Sitokin dapat meningkatkan reaksi inflamasi melalui stimulasi sel T dan B intratiroid dan menginduksi perubahan pada sel folikel tiroid termasuk upregulasi MHC kelas I dan II, serta ekspresi molekul adhesi. Sitokin juga merangsang sel folikel tiroid untuk menghasilkan sitokin, Nitric Oxide (NO) dan Prostaglandin (PO), yang selanjutnya akan meningkatkan reaksi inflamasi dan destruksi jaringan. Molekul ini juga memodulasi pertumbuhan dan fungsi sel folikel tiroid, yang secara langsung akan berimplikasi terhadap disfungsi tiroid (Weetman et al, 2002).
Sitokin mempunyai peranan pula dalam penyulit ekstratiroid, terutama thyroid-associated ophthlamopathy (TAO). Sel T terkumpul di jaringan retrobulbar pada penderita dengan TAO; sel T tersebut akan diaktivasi dan menghasilkan sitokin, yang akan memperluas proses inflamasi melalui beberapa mekanisme termasuk peningkatan MHC kelas II, Heat Shock Protein (HSP), molekul adhesi, dan ekspresi TSH-R di jaringan retrobulbar. Sitokin akan meningkatkan proliferasi fibroblast secara lokal dan membantu pembentukan sel-sel radang baru, meningkatkan reaksi inflamasi, serta juga meningkatkan akumulasi matriks ekstraseluler di jaringan orbita melalui efek stimulatorik pada glycosaminoglycan (GAG) dan produksi inhibitor metalloproteinase oleh fibroblast retrobulbar. Berdasarkan hal-hal di atas, memodulasi produksi sitokin atau menghambat kerja sitokin di jaringan retrobulbar dapat dipertimbangkan untuk menangani oftalmopati yang sampai saat ini sukar diobati (Weetman et al, 2001).
3. Uraikan dasar fisiologi dari rentang perbedaan nilai FT4, FT3 dan
TSH. (Mengapa nilai TSH rendah bersamaan dengan FT4 dan FT3
tinggi?) !
19

Kelenjar thyroid menghasilkan 2 jenis hormon yang memiliki fungsi
yang sama, hanya saja jumlahnya yang berbeda. 93% dari hormon
yang dihasilkan adalah hormon tiroksin (T4), sedangkan 7%-nya
adalah triiodotironin (T3). Akan tetapi hampir semua hormon tiroksin
(T4) diubah menjadi hormon triiodotironin (T3). Pelepasan T3 dan T4
ke dalam darah distimulasi oleh TSH (Thyroid Stimulating Hormon)
dari kelenjar hipofisis yang dipacu oleh TRH (Thyroid Releasing
Factor) dari hipotalamus (Guyton and Hall, 2007).
Untuk membentuk hormon thyroid dalam jumlah yang normal, setiap tahunnya dibutuhkan kira-kira 50 mg yodium yang ditelan dalam bentuk iodida. Iodida tersebut akan diabsorbsi dari saluran pencernaan ke dalam darah. Seperlimanya akan diangkut ke kelenjar thyroid untuk sintesis hormon dan sisanya dibuang melalui ginjal. Iodida ini dihantarkan ke dalam sel-sel dan folikel kelenjar thyroid. Membran basal sel thyroid akan menjerat iodida (Iodise Trapping) diamana kecepatan penjeratannya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor yang terpenting adalah konsentrasi TSH (Guyton and Hall, 2007).
Iodida akan mengalami oksidasi menjadi bentuk yodium yang
teroksidasi. Selanjutnya akan berikatan dengan asam amino tirosin
yang berada dalam tiroglobulin. Yodium akan bereaksi dengan enzim
iodinase untuk mengiodisasi tirosin menjadi monoiodotirosin lalu
menjadi diiodotirosin. Semakin lama dengan bergandengan satu sama
lain terbentuk triiodotironin (T3) dan tiroksin (T4). Hormon-hormon
20

tersebut disimpan di dalam tiroglobulin sampai tubuh membutuhkan
hormon tersebut (Guyton and Hall, 2007).
Untuk melepaskan hormon-hormon tersebut, permukaan sel apikal
tiroid menjulurkan pseudopodia mengelilingi sebagian kecil koloid
sehingga terbentuk vesikel pinositik yang masuk ke bagian apeks sel-
sel thyroid. Lisosom dari sitoplasma sel bergabung dengan vesikel
tersebut untuk membentuk vesikel digestif yang mengandung enzim
pencernaan (salah satunya adalah protease). Enzim tersebut akan
mencerna molekul tiroglobulin menyebabkan T3, T4,
monoiodotironin, dan diiodotironin lepas. T3 dan T4 lepas ke dalam
darah, sedangkan monoiodotironin dan diiodotironin tetap di kelenjar
thyroid dan dengan bantuan enzim deiodinase, yodium dilepas dari
tirosin. Yodium tersebut dipakai kembali untuk membuat hormon
selanjutnya (Guyton and Hall, 2007).
T3 dan T4 dalam plasma diikiat oleh TBG (Globulin pengikat
Tiroksin), TBPA (Prealbumin pengikat Tiroksin), dan TBA (Albumin
pengikat Tiroksin) sehingga disebut hormon terikat, sedangkan yang tidak
terikat disebut hormon bebas (FT3 dan FT4). FT3 dan FT4 lah yang aktif
karena langsung melakukan reaksi terhadap tubuh (Price and Lorraine,
2005). Hormon tersebut memiliki banyak efek pada tubuh, yaitu efek pada
metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, pada plasma dan lemak hati,
meningkatnya kebutuhan vitamin, meningkatnya laju metabolisme basal,
menurunkan berat badan, meningkatkan aliran darah dan curah jantung,
meningkatkan frekuensi denyut jantung, meningkatkan kekuatan jantung,
tekanan arteri normal, meningkatkan pernapasan, meningkatkan motilitas
saluran cerna, merangsang pada SSP, efek pada otot, tremor otot, efek
pada tidur, efek pada kelenjar endokrin lain, dan fungsi seksual (Guyton
and Hall, 2007).
21

4. Keadaan/penyakit-penyakit apa saja yang dapat menunjukkan
gambaran hasil laboratorium seperti tersebut diatas?
Data laboratorium
Normal Data PasienfT3 2,8-7,7 17,7 pmol/lfT4 11-24 49,3 pmol/lTSH 0,27-4,2 <0,01 mIU/l
dari data dapat dilihat bahwa nilai TSH menurun disertai dengan peningktan fT3 dan fT4, kemungkinan penyakit yang sesuai dengan data tersebut diantaranya:
o Hipertiroid o Grave’s diseaseo Tirotoksikosiso Tiroiditis
Thyroiditis bias disebut juga sebagai radang kelenjar Thyroid (Dorland, 2006). Penyakit ini mencakup segolongan kelainan yang ditandai dengan adanya inflamasi tiroid. Termasuk di dalamnya keadaan yang timbul mendadak disertai rasa sakit yang hebat pada tiroid (misalnya: subacute granolumatous thyroiditis dan infectious thyroiditis), dan keadaan dimana secara klinis tidak ada inflamasi dan manifestasi penyakitnya terutama dengan adanya disfungsi tiroid atau pembesaran kelenjar tiroid (misalnya: subacute lymphocytic painless thyroiditis) dan tiroiditis fibrosa (Riedels thyroiditis) (Wiyono, 2007).
Pada Tiroiditis subakut, pola perubahan fungsi tiroid biasanya dimulai dengan hipertiroid (akibat kerusakan sel-sel folikel dan pemecahan tiroglubulin, menyebabkan pelepasan tidak terkendali dari hormone T3 dan T4. TSH menurun karena T3 dan T4 meningkat. Hal ini berlangsung hingga T3 dan T4 habis dan sel
22

folikel rusak), diikuti hipotiroid (karena T3 dan T4 habis), dan akhirnya kembali eutiroid (bila inflamasi mereda, sel-sel folikel tiroid akan regenerasi, sintesis, dan sekresi hormone akan pulih kembali) (Wiyono, 2007).
Gambar 2. Penafsiran uji fungsi tiroid laboratorium untuk dokter layanan primer.6
5. Uraikan tanda dan keluhan klinis terkait dengan kelainan ini!
5.1. Nadi meningkat dgn irama tdk teratur
5.2. Lelah
5.3. Gemetar
5.4. Tidak tahan panas
5.5. Teraba struma tiroid, kenyal, tdk nyeri, kesan difus.
23

6. Apa makna gambaran laboratorium tersebut di atas terhadap dasar
pathogenesis penyakit ini?
Seperti yang diketahui, Hasil lab immunoassay terhadap autoantibodi serum dijumpai TRAb (thyrotropin reseptor antibody) 9,3 IU/ml, TgAb (thyroglobulin antibody) 845 IU/ml, dan TPOAb (thyroid peroxidase antibody) 968 IU/ml, dimana hasil lab itu terjadi peningkatan.
Antibodi-antibodi tersebut meningkat, karena antibodi membaca TSH (thyrotropin stimulating hormon) sebagai antigen, jadi antibodi-antibodi (TRAb, TgAb, TPOAb) berikatan dengan TSH di tiroid, sehingga menstimulasi hormon secara berlebihan, dan menghasilkan jumlah hormon tiroid yang lebih dari normal.
7. Apakah diagnosis penyakit ini?
Penyakit graves merupakan bentuk tirotoksikosis(hipertiroid) yang
paling sering dijumpai. Penyakit gaves memiliki tanda gejala yang paling
mudah dikenali,yaitu adanya struma(hipertrofi dan hiperplasia difus),
tirotoksikosis(hipersekresi kelenjar tiroid/hipertiroidisme),dan sering
disertai oftalmopati,dan jarang adanya dermopati. Pada gambaran klinis ,
pasien mengalami oftalmopati.
Oftalmopati adalah gangguan yang disebabkan oleh kombinasi
aktifitas berlebihan saraf simpati yang menyertai tirotoksikosis, dan
adanya pengendapan komponen matriks dibelakang bola mata . hal ini
ditandai oleh kelopak mata melebar,membesar, dan bola mata menonjol
secara abnormal (proptosis). Keadaan ini disebut
eksoptalmos(penonjolan).
Pada oftalmopati graves, volume jaringan ikat retro-orbital dan
otot ekstraokuler meningkat karena beberapa sebab: Adanya infiltrasi sel2
mononuklear terutama limfosit dalam rongga retro-orbital, edema radang
dan pembengkakanotot ekstraokuler, penimbunan komponen matriks
ekstraseluler ,khas adalah hydrophilic glycosaminoglycans(GAGs) seperti
hyaluronic acid dan chondroitin sulfate,serta penigkatan jumlah sel2
lemak (infiltrasi lemak).
24

8. Uraikan gambaran patologi anatomi jaringan tiroid pada penyakit
ini!
Kelenjar tiroid membesar secara difus akibat hipertrofi dan hyperplasia difus sel epitel folikel tiroid. Kelenjar biasanya lunak dan licin, dan kapsulnya utuh. Secara mikroskopis, sel epitel folikel pada kasus yang tidak diobati tampak tinggi dan kolumnar serta lebih ramai daripada biasa. Meningkatnya jumlah sel ini menyebabkan terbentuknya papilla kecil, yang menonjol ke dalam lumen folikular. Papila ini tidak memiliki inti fibrovaskular, berbeda dengan yang ditemukan pada karsinoma papilar. Koloid di dalam lumen folikel tampak pucat, dengan tepi berlekuk-lekuk. Infiltrat limfoid, terutama terdiri atas sel T dengan sedikit sel B dan sel plasma matang, terdapat di seluruh interstisium; pusat germinatum sering ditemukan. Terapi praoperasi mengubah morfologi tiroid pada penyakit Graves. Sebagai contoh, pemberian yodium praoperasi menyebabkan involusi epitel dan akumulasi koloid akibat terhambatnya sekresi tiroglobulin; jika terapi dilanjutkan, kelenjar mengalami fibrosis.
Kelainan di jaringan ekstatiroid adalah hyperplasia limfoid generalisata. Pada pasien dengan oftalmopati , jaringan orbita tampak adematosa akibat adanya glikosaminoglikan hidrofilik. Selain itu, terjadi infiltrasi oleh limfosit, terutama sel T. Otot orbita mengalami edema pada awalnya tetapi kemudian mengalami fibrosis pada perjalanan penyakit tahap lanjut. Dermopati, jika ada, ditandai dengan menebalnya dermis akibat pengendapan glikosaminoglikan dan infiltrate limfosit.3
25

9. Uraikan penatalaksanaan non farmakologis dan farmakologis dari
penyakit ini. Dan edukasi serta penatalaksanaan dokter layanan
primer!
9.1. Dasar pengobatanBeberapa faktor hams dipertimbangkan, ialah :
Faktor penyebab hipertiroidi
Umur penderita
Berat ringannya penyakit
Ada tidaknya penyakit lain yang menyertai
Tanggapan penderita terhadap pengobatannya
Sarana diagnostik dan pengobatan serta pengalaman dokter dan
klinik yang bersangkutan.
Pada dasarnya pengobatan penderita hipertiroidi meliputi :
Pengobatan Umum Pengobatan Khusus Pengobatan dengan Penyulit
o Pengobatan umum
IstirahatHal ini diperlukan agar hipermetabolisme pada penderita tidak makin meningkat. Penderita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan yang melelahkan/mengganggu pikiran balk di rumah atau di tempat bekerja. Dalam keadaan berat dianjurkan bed rest total di Rumah Sakit.
26

DietDiet harus tinggi kalori, protein, multivitamin serta mineral. Hal ini
antara lain karena : terjadinya peningkatan metabolisme, keseimbangan
nitrogen yang negatif dan keseimbangan kalsium yang negatif.
Obat penenang
Mengingat pada PG sering terjadi kegelisahan, maka obat penenang
dapat diberikan. Di samping itu perlu juga pemberian psikoterapi.
o Pengobatan khusus
Obat antitiroid
Obat-obat yang termasuk golongan ini adalah thionamide, yodium,
lithium, perchlorat dan thiocyanat.
Obat yang sering dipakai dari golongan thionamide adalah
propylthiouracyl (PTU), 1 - methyl - 2 mercaptoimidazole (methimazole,
tapazole, MMI), carbimazole. Obat ini bekerja menghambat sintesis
hormon tetapi tidak menghambat sekresinya, yaitu dengan menghambat
terbentuknya monoiodotyrosine (MIT) dan diiodotyrosine (DIT), serta
menghambat coupling diiodotyrosine sehingga menjadi hormon yang
aktif. PTU juga menghambat perubahan T4 menjadi T3 di jaringan tepi,
serta harganya lebih murah sehingga pada saat ini PTU dianggap sebagai
obat pilihan.
Obat antitiroid diakumulasi dan dimetabolisme di kelenjar gondok
sehingga pengaruh pengobatan lebih tergantung pada konsentrasi obat
dalam kelenjar dari pada di plasma. MMI dan carbimazole sepuluh kali
lebih kuat daripada PTU sehingga dosis yang diperlukan hanya satu
persepuluhnya.
Dosis obat antitiroid dimulai dengan 300 - 600 mg perhari untuk PTU
atau 30 - 60 mg per hari untuk MMI/carbimazole, terbagi setiap 8 atau 12
jam atau sebagai dosis tunggal setiap 24 jam. Dalam satu penelitian
dilaporkan bahwa pemberian PTU atau carbimazole dosis tinggi akan
memberi remisi yang lebih besar.
Secara farmakologi terdapat perbedaan antara PTU dengan MMI/CBZ,
antara lain adalah:
27

a. MMI mempunyai waktu paruh dan akumulasi obat yang lebih lama
dibanding PTU di clalam kelenjar tiroid. Waktu paruh MMI ± 6 jam
sedangkan PTU + 11/2 jam.
b. Penelitian lain menunjukkan MMI lebih efektif dan kurang toksik
dibanding PTU.
c. . MMI tidak terikat albumin serum sedangkan PTU hampir 80%
terikat pada albumin serum, sehingga MMI lebih bebas menembus
barier plasenta dan air susu, sehingga untuk ibu hamil dan menyusui
PTU lebih dianjurkan.
Jangka waktu pemberian tergantung masing-masing penderita (6 - 24
bulan) dan dikatakan sepertiga sampai setengahnya (50 - 70%) akan
mengalami perbaikan yang bertahan cukup lama. Apabila dalam waktu 3
bulan tidak atau hanya sedikit memberikan perbaikan, maka harus
dipikirkan beberapa kemungkinan yang dapat menggagalkan pengobatan
(tidak teratur minum obat, struma yang besar, pernah mendapat
pengobatan yodium sebelumnya atau dosis kurang)
Efek samping ringan berupa kelainan kulit misalnya gatal-gatal, skin rash
dapat ditanggulangi dengan pemberian anti histamin tanpa perlu
penghentian pengobatan. Dosis yang sangat tinggi dapat menyebabkan
hilangnya indera pengecap, cholestatic jaundice dan kadang-kadang
agranulositosis (0,2 - 0,7%), kemungkinan ini lebih besar pada penderita
umur di atas 40 tahun yang menggunakan dosis besar. Efek samping lain
yang jarang terjadi. a.l. berupa : arthralgia, demam rhinitis, conjunctivitis,
alopecia, sakit kepala, edema, limfadenopati, hipoprotombinemia,
trombositopenia, gangguan gastrointestinal
Yodium
Pemberian yodium akan menghambat sintesa hormon secara akut tetapi
dalam masa 3 minggu efeknya akan menghilang karena adanya escape
mechanism dari kelenjar yang bersangkutan, sehingga meski sekresi
terhambat sintesa tetap ada. Akibatnya terjadi penimbunan hormon dan
pada saat yodium dihentikan timbul sekresi berlebihan dan gejala
hipertiroidi menghebat
Pengobatan dengan yodium (MJ) digunakan untuk memperoleh efek
yang cepat seperti pada krisis tiroid atau untuk persiapan operasi. Sebagai
28

persiapan operasi, biasanya digunakan dalam bentuk kombinasi. Dosis
yang diberikan biasanya 15 mg per hari dengan dosis terbagi yang
diberikan 2 minggu sebelum dilakukan pembedahan. Marigold dalam
penelitiannya menggunakan cairan Lugol dengan dosis 1/2 ml (10 tetes)
3 kali perhari yang diberikan '10 hari sebelum dan sesudah operasi.
Penyekat Beta (Beta Blocker)
Terjadinya keluhan dan gejala hipertiroidi diakibatkan oleh adanya
hipersensitivitas pada sistim simpatis. Meningkatnya rangsangan sistem
simpatis ini diduga akibat meningkatnya kepekaan reseptor terhadap
katekolamin.
Penggunaan obat-obatan golongan simpatolitik diperkirakan akan
menghambat pengaruh hati.Reserpin, guanetidin dan penyekat beta
(propranolol) merupakan obat yang masih digunakan. Berbeda dengan
reserpin/guanetidin, propranolol lebih efektif terutama dalam kasus-kasus
yang berat. Biasanya dalam 24 - 36 jam setelah pemberian akan tampak
penurunan gejala.
Khasiat propranolol:
a. penurunan denyut jantung permenit
b. penurunan cardiac output
c. perpanjangan waktu refleks Achilles
d. pengurangan nervositas
e. pengurangan produksi keringat
f. pengurangan tremor
Di samping pengaruh pada reseptor beta, propranolol dapat menghambat
konversi T4 ke T3 di perifer. Bila obat tersebut dihentikan, maka dalam
waktu ± 4 - 6 jam hipertiroid dapat kembali lagi. Hal ini penting
diperhatikan, karena penggunaan dosis tunggal propranolol sebagai
persiapan operasi dapat menimbulkan krisis tiroid sewaktu operasi.
Penggunaan propranolol a.l. sebagai : persiapan tindakan pembedahan
atau pemberian yodium radioaktif, mengatasi kasus yang berat dan krisis
tiroid.
Ablasi kelenjar gondok
Pelaksanaan ablasi dengan pembedahan atau pemberian I131
Tindakan pembedahan:
29

a. Indikasi utaina untuk melakukan tindakan pembedahan adalah mereka
yang berusia muda dan gagal atau alergi terhadap obat-obat antitiroid.
Tindakan pembedahan berupa tiroidektomi subtotal juga dianjurkan pada
penderita dengan keadaan yang tidak mungkin diberi pengobatan dengan
I131(wanita hamil atau yang merencanakan kehamilan dalam waktu
dekat).
b. Indikasi lain adalah mereka yang sulit dievaluasi pengobatannya,
penderita yang keteraturannya minum obat tidak teijamin atau mereka
dengan struma yang sangat besar dan mereka yang ingin cepat eutiroid
atau bila strumanya diduga mengalami keganasan, dan alasan kosmetik.
c. Untuk persiapan pembedahan dapat diberikan kombinasi antara
thionamid, yodium atau propanolol guna mencapai keadaan eutiroid.
Thionamid biasanya diberikan 6 - 8 minggu sebelum operasi, kemudian
dilanjutkan dengan pemberian larutan Lugol selama 10 - 14 hari sebelum
operasi. Propranolol dapat diberikan beberapa minggu sebelum operasi,
kombinasi obat ini dengan Yodium dapat diberikan 10 hari sebelum
operasi.
d. Tujuan pembedahan yaitu untuk mencapai keadaan eutiroid yang
permanen. Dengan penanganan yang baik, maka angka kematian dapat
diturunkan sampai 0.
Ablasi dengan I131
a. Sejak ditemukannya I131 terjadi perubahan dalam bidang pengobatan
hipertiroidi. Walaupun dijumpai banyak komplikasi yang timbul setelah
pengobatan, namun karena harganya murah dan pemberiannya mudah,
cara ini banyak digunakan.
b. Tujuan pemberian I131 adalah untuk merusak sel-sel kelenjar yang
hiperfungsi. Sayangnya I131 ini temyata menaikan angka kejadian
hipofungsi kelenjar gondok (30 — 70% dalam jollow up 10 — 20 tahun)
tanpa ada kaitannya dengan besarnya dosis obat yang diberikan. Di
samping itu terdapat pula peningkatan gejala pada mata sebanyak 1 —
5% dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perubahan gen dan
keganasan akibat pengobatan cara ini, walaupun belum terbukti.
30

c. Penetapan dosis I131 didasarkan atas derajat hiperfungsi serta besar dan
beratnya kelenjar gondok. Dosis yang dianjurkan ± 140 — 160 micro
Ci/gram atau dengan dosis rendah ± 80 micro Ci/gram.
d. Dalam pelaksanaannya perlu dipertimbangkan antara lain : dosis
optimum yang diperlukan kelenjar tiroid, besar/ukuran dari kelenjar yang
akan diradiasi, efektivitas I131 di dalam jaringan dan sensitivitas jaringan
tiroid terhadap I131
Pengobatan dengan penyulit
Eksoftalamus
Pengobatan hipertiroidi diduga mempengaruhi derajat pengembangan
eksoflmus. Selain itu pada eksoftalmus dapat diberikan terapi a.l. :
istirahat dengan berbaring terlentang, kepala lebih tinggi; mencegah mata
tidak kering dengan salep mata atau larutan metil selulose 5%;
menghindari iritasi mata dengan kacamata hitam; dan tindakan operasi;
dalam keadaan yang berat bisa diberikan prednison peroral tiap hari.
10. Uraikan kesan anda terhadap gambaran klinis MATA yang tampak
pada potongan wajah di atas.
Dapat dilihat di kedua mata terjadi pembesaran, terlihat juga bahwa
optic nerve sudah tertutup oleh benda asing. Juga mata terlihat melotot.
11. Uraikan kesan anda terhadap hasil gambar orbit pada kasus ini,
dibandingkan gambar orbit orang normal!
Terjadi pembesaran pada kedua bola mata serta bola mata yang sebelah kiri terdorong ke luar karena jaringan orbita dan otot-otot mata diinfiltrasi oleh limfosit, sel mast, dan sel-sel plasma yang mengakibatkan eksoftalmoa (proptosis bola mata), okulopati kongestif dan kelemahan gerakan ekstraokular.
12. Apakah diagnosis klinis dari keadaan ini?
Imaging orbit pada kasus ini menunjukkan keadaan eksoftalmus yang disebabkan karena hipertiroidisme. Eksoftalmus adalah penonjolan abnormal pada salah satu atau kedua bola mata. Eksoftalmus terjadi akibat kombinasi infiltrasi limfosit, pengendapan glikosaminoglikan, adipogenesis dalam jaringan ikat orbita sehingga terjadi eksofltalmus
31

13. Terangkan dasar pathogenesis kelainan ini?
Eksoftalmus terjadi akibat kombinasi infiltrasi limfosit,
pengendapan glikosaminoglikan, adipogenesis dalam jaringan ikat orbita
sehingga eksofltalmus. Jaringan tertentu diluar tiroid seperti fibroblas
orbita secara aberan mengekpresikan reseptor TSH di permukaannya.
Sebagai respons terhadap antibodi anti-reseptor TSH di darah dan sitokin
lain milieu lokal, fibroblas mengalami diferensiasi menuju adiposit
matang dan mengeluarkan glikosaminoglikan hidrofilik ke interstisium
sehingga terjadi eksoftalmus. Mekanisme ini hampir sama terjadi pada
dermopati penyakit Graves. Setelah terjadi ekoftalmus maka akan terjadi
juga retraksi palpepra dan pembengkakan otot-otot palpepra.
14. Terangkan keterkaitan antara kelainan mata ini dengan diagnosis
yang ditegakkan pada pertanyaan no 7!
Penyebab protrusi bola mata adalah adanya pembengkakan pada jaringan retroorbita dan timbulnya perubahan degeneratif pada otot-otot ektraokular. Pada kebanyakan pasien, dapat ditemukan immunoglobulin dengan otot-otot mata. Lebih lanjut, konsentrasi immunoglobulin ini biasanya paling tinggi pada pasien yang mempunyai konsentrasi TSI yang tinggi. Oleh karena itu, sebenarnya ada banyak alasan untuk mempercayai bahwa eksoftalmus, seperti halnya hipertiroidisme sendiri, merupakan suatu proses autoimun. Biasanya eksoftamus ini hilang atau membaik dengan pengobatan hipertiroidismenya.
15. Uraikan penatalaksanaan dari kelainan mata pada kasus ini!
Pada penyakit Grave, oftalmopati dapat menyertai hipertiroidisme. Pada oftalmopati, ada pembesaran jaringan ikat retrobulbar dan otot ekstraokular. Peningkatan volume jaringan retrobulbar dan otot ekstraokular disebabkan oleh retensi cairan. Volume jaringan dan otot yang meningkat mendorong bola mata ke depan (eksoftalmus). Ada pula edema periorbital dan kelopak mata.
a. Tanda dan Gejala oftalmopati,antaralain:- Bright-eyed stare, yang terjadi akibat retraksi kelopak mata atas.- Lid lag. Bila melihat ke bawah, kelopak mata atas lambat
mengikuti bola mata.- Mata setengah terbuka ketika tidur.- Edema periorbital
32

- Merasa ada iritasi pada mata dan mengeluarkan banyak air mata.- Merasa ada tekanan pada bagian belakang mata.- Penglihatan kabur, penglihatan ganda, dan mata merasa cepat
lelah.Pada banyak pasien, oftalmiopati dapat sembuh sendiri dan
tidak memerlukan pengobatan selanjutnya. Tetapi pada kasus yang berat hingga ada bahaya kehilangan penglihatan, perlu diberi pengobatan dengan glukokortikoid dosis tinggi disertai tindakan dekompresi orbita untuk menyelamatkan mata tersebut.
b. Terapi oftalmopati akibat tiroid,diantaranya:- Suportif : posisi kepala lebih tinggi daripada kaki (tidur dengan
posisi kepala ditinggikan untuk mengurangi edema periorbita), air buatan, kacamata prisma untuk mengatasi diplopia.
- Definitif : terapi dengan steroid dosis tinggi, imunosupresan lain (untuk dekrompesi bola mata), dekompresi bola mata dengan bedah, atau radioterapi bola mata.
16. Etiologi dan faktor resiko
Penyakit Graves merupakan suatu penyakit otoimun yaitu saat
tubuh menghasilkan antibodi yang menyerang komponen spesifik dari
jaringan itu sendiri, maka penyakit ini dapat timbul secara tiba-tiba dan
penyebabnya masih belum diketahui. Hal ini disebabkan oleh
autoantibodi tiroid (TSHR-Ab) yang mengaktifkan reseptor TSH (TSHR),
sehingga merangsang tiroid sintesis dan sekresi hormon, dan pertumbuhan
tiroid (menyebabkan gondok membesar difus).
Terdapat beberapa faktor risiko, antaralain:1. Genetik
Riwayat keluarga dikatakan 15 kali lebih besar dibandingkan populasi umum untuk terkena Graves. Gen HLA yang berada pada rangkaian kromosom ke-6 (6p21.3) ekspresinya mempengaruhi perkembangan penyakit autoimun ini. Molekul HLA terutama klas II yang berada pada sel T di timus memodulasi respons imun sel T terhadap reseptor limfosit T (T lymphocyte receptor/TcR) selama terdapat antigen. Interaksi ini merangsang aktivasi T helper limfosit untuk membentuk antibodi. T supresor limfosit atau faktor supresi yang tidak spesifik (IL-10 dan TGF-β) mempunyai aktifitas yang rendah pada penyakit autoimun kadang tidak dapat membedakan mana T helper mana yang disupresi sehingga T helper yang membentuk antibodi yang
33

melawan sel induk akan eksis dan meningkatkan proses autoimun. 2
2. Wanita lebih sering terkena penyakit ini karena modulasi respons
imun oleh estrogen. Hal ini disebabkan karena epitope
ekstraseluler TSHR homolog dengan fragmen pada reseptor LH
(7€85%) dan homolog dengan fragmen pada reseptor FSH
(20€85%)
3. Status gizi dan berat badan lahir rendah sering dikaitkan dengan
prevalensi timbulnya penyakit autoantibodi tiroid.
4. Stress juga dapat sebagai faktor inisiasi untuk timbulnya penyakit
lewat jalur neuroendokrin.
5. Merokok dan hidup di daerah dengan defisiensi iodium.
6. Toxin, infeksi bakteri dan virus. Bakteri Yersinia enterocolitica
yang mempunyai protein antigen pada membran selnya yang sama
dengan TSHR pada sel folikuler kelenjar tiroid diduga dapat
mempromosi timbulnya penyakit Graves’ terutama pada penderita
yang mempunyai faktor genetik. Kesamaan antigen bakteri atau
virus dengan TSHR atau perubahan struktur reseptor terutama
TSHR pada folikel kelenjar tiroid karena mutasi atau
biomodifikasi oleh obat, zat kimia atau mediator inflamasi
menjadi penyebab timbulnya autoantibodi terhadap tiroid dan
perkembangan penyakit ini.
7. Periode post partum dapat memicu timbulnya gejala hipertiroid.
8. Pada sindroma defisiensi imun (HIV), penggunaan terapi antivirus
dosis tinggi highly active antiretroviral theraphy (HAART)
berhubungan dengan penyakit ini dengan meningkatnya jumlah
dan fungsi CD4 sel T.
9. Multipel sklerosis yang mendapat terapi Campath-1H monoclonal
antibodi secara langsung, mempengaruhi sel T yang sering disertai
kejadian hipertiroid.
10. Terapi dengan interferon α
17. Komplikasi
34

Komplikasi Graves’ disease adalah krisis tiroid (thyroid storm). Krisis
tiroid adalah kondisi hipermetabolik yang mengancam jiwa dan ditandai
oleh demam tinggi dan disfungsi sistem kardiovaskular, sistem saraf, dan
sistem saluran cerna. Awalnya, timbul hipertiroidisme yang merupakan
kumpulan gejala akibat peningkatan kadar hormon tiroid yang beredar
dengan atau tanpa kelainan fungsi kelenjar tiroid. Ketika jumlahnya
menjadi sangat berlebihan, terjadi kumpulan gejala yang lebih berat, yaitu
tirotoksikosis. Krisis tiroid merupakan keadaan dimana terjadi
dekompensasi tubuh terhadap tirotoksikosis tersebut. Tipikalnya terjadi
pada pasien dengan tirotoksikosis yang tidak terobati atau tidak tuntas
terobati yang dicetuskan oleh tindakan operatif, infeksi, atau trauma.
Gambaran klinisnya ialah distress berat, sesak napas, takikardia,
hiperpireksia, lemah, bingung, delirium,muntah, diare.
18. Prognosis
Prognosis pada kenyakit Graves biasanya baik, apabila kita
melakukan penanganan dengan baik serta mendiagnosa dengan cepat.
V. Kesimpulan
Wanita 34 thn, sesuai dgn gmbaran klinis dan pmeriksaan lab srta penunjang lainnya, di diagnosis Penyakit Graves.
35

DAFTAR PUSTAKA
o Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Buku Ajar Patologi Robbins Edisi 7 Volume 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2012. Halaman 813-814.
o Davey, Patric. Medicine at a Glance. Jakarta : Penerbit Erlangga. 2006.
o Demers LM, Spencer CA. Laboratory medicine practice guidelines: Laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Washington, DC: The National Academy of Clinical Biochemistry; 2000. Free download: http://www.nacb.org/lmpg/thyroid_LMPG_Word.stm diunduh 1 November 2008.
o Stockigt J. Assessment of thyroid function: Towards an integrated laboratory – clinical approach. Clin Biochem Rev 2003; 24:110-23.
o “Physiology of thyroid”, Sherwood’s Fundamental of Physiology, A Human Perspektif (2nd ed. West Publishing company,1995),500-504.
o “ Fisiologi Thyroid”, Guyton & Hall Buku Ajar Fisiologi Kedokteran, alih bahasa dr. Irawati Setiawan, dkk ( cetakan I, Penerbit buku Kedokteran EGC,1997),1187-1199.
o Supit EJ, Peiris AN. Interpretation of laboratory thyroid function tests for the primary care physician. South Med J 95(5):481-85, 2002. © 2002 Southern Medical Association.
o Djokomoeljanto. 2007. Kelenjar Tiroid, Hipotiroidisme, dan Hipertiroidisme. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid III. Jakarta: EGC.
o Dorland, W.A. Newman. 2006. Kamus Kedokteran Dorland-Edisi 29. Jakarta: EGC.
o Ganong. 2008. Fisiologi Kedokteran. Jakarta: EGC.o Guyton, A.C., John E. Hall, 2007. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran.
Jakarta: EGC.o Price, Sylvia A and Lorraine M Wilson. 2005. Patofisologi Volume 2.
Jakarta: EGC.o Wiyono, Paulus. 2007. Tiroiditis. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam
Jilid III. Jakarta: EGC.o Konthen, Putu Gede.et al. Pedoman Diagnostik Dan Terapi SMF Ilmu
Penyakit Dalam : Hipertiroid dan Tirotoksikosis. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga; 2010. p.105-109
36