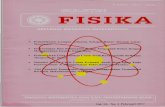Jurnal ilmiah m kn unud edisi 10 oktober 2014
-
Upload
magister-kenotariatan-univ-udayana -
Category
Law
-
view
703 -
download
8
Transcript of Jurnal ilmiah m kn unud edisi 10 oktober 2014

VVV ooo lll uuu mmm eee 111 000
EEE ddd iii sss iii KKK hhh uuu sss uuu sss HHH aaa lll aaa mmm aaa nnn 111 ––– 777 777
DDD eee nnn ppp aaa sss aaa rrr
OOO kkk ttt ooo bbb eee rrr 222 000 111 444 III SSS SSS NNN
222 222 555 222 --- 333 888 000 XXX
KKEERRTTHHAA PPEERRTTIIWWII JJJ UUU RRR NNN AAA LLL III LLL MMM III AAA HHH MMM AAA GGG III SSS TTT EEE RRR KKK EEE NNN OOO TTT AAA RRR III AAA TTT AAA NNN UUU NNN III VVV EEE RRR SSS III TTT AAA SSS UUU DDD AAA YYY AAA NNN AAA
PPPRRROOO GGGRRRAAA MMM SSS TTTUUUDDD III MMMAAAGGG IIISSS TTTEEERRR KKKEEE NNNOOO TTTAAARRRIIIAAA TTTAAA NNN
UUUNNN IIIVVVEEERRR SSSIII TTTAAASSS UUU DDDAAAYYYAAANNNAAA
222000111444


i
KERTHA PERTIWI Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan
(Scientific Journals of The Master of Notary) ISSN 2252 – 380 X
Volume 10 (Edisi Khusus) Periode Oktober 2014
Susunan Organisasi Pengelola
Penanggung Jawab
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum.
Pimpinan Redaksi
I Made Tjatrayasa, SH.,MH.
Mitra Bestari
Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH.,MS.,CN.
Dewan Redaksi
Prof. R.A. Retno Murni, SH.,MH.,Ph.D.
Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum.
Dr. I Gede Yusa, SH.,MH.
Dr. Ketut Westra, SH.,MH.
Penyunting Pelaksana
Drs. Yuwono, SH.,M.Si.
Dr. I Ketut Sudantra, SH.,MH
Kadek Sarna.,SH.,M.Kn.
I Made Walesa Putra, SH.,M.Kn.
Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn.
Petugas Administrasi dan Keuangan
Ni Putu Purwanti, SH.,M.Hum.
Wiwik Priswiyanti, A.Md.
I Putu Artha Kesumajaya
I Gde Chandra Astawa Widhiasa
Luh Komang Srihappy Widyarthini, SH.
I Made Suparsa
I Ketut Wirasa
I Gusti Bagus Mardi Sukmawan, Amd. Kom.
Alamat Redaksi
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah Denpasar
Telp. : (0361)264812. Fax (0361)264812
E-mail : [email protected]
Website : http://www.fl.unud.ac.id/notariat/
Gambar Co ver : Keind ahan Alam Indonesi a
Ker tha Per t iwi merup akan ju rnal i lmiah yan g d i t erb i tkan dua kal i se tahun ( Apr i l
dan Oktober ) yan g memu at in formasi t en t ang b erb agai asp ek huku m Kenotar i a tan
dar i : (1 ) h as i l pene l i t i an , (2 ) naskah konseptu al /op in i , (3 ) resen si buku , d an in fo
Kenotar i a t an actual la inn ya

i i
PENGANTAR REDAKSI
Om, Swastyastu,
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Esa oleh karena atas perkenan dan rahkmat-Nyalah Jurnal Ilmiah Program Studi
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana periode Oktober Tahun
2014 (Edisi Khusus) dapat diselesaikan. Disusunnya Jurnal Ilmiah Prodi M.Kn. Unud. ini
dimaksudkan untuk dapat sebagai referensi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan
dalam bidang Hukum Kenotariatan bagi mahasiswa, dosen serta masyarakat pembaca.
Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari mahasiswa maupun dosen
Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan
Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan
Akta Jual Beli Tanah, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Covernote Sebagai
Salah Satu Produk Hukum Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,
Analisis Keabsahan Akta Notaris Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Bukti Kepemilikan
Dalam Bentuk Pipil dan artikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian
tesis mahasiswa yang sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang
ujian dihadapan dewan penguji dan Guru Besar.
Dengan diterbitkannya Jurnal Ilmiah periode Oktober Tahun 2014 (Edisi Khusus) ini
diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan didalam mewujudkan
visi dan misi serta tujuan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Udayana. Kami juga memberikan kesempatan kepada semua pihak yang kompeten dan
pemerhati bidang Hukum Kenotariatan baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas
Udayana untuk berpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah dengan tetap mentaati semua
aturan atau ketentuan yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah ini. Akhirnya, semoga Jurnal
Ilmiah ini bermanfaat untuk semua pihak.
Om, Santih, Santih, Santih, Om.
Denpasar, Oktober 2014
Redaksi

i i i
DAFTAR ISI
Hlm
Susunan Organisasi Pengelola ………………………………………………………………….. i
Pengantar Redaksi ………………………………………………………………………………. ii
Daftar isi ………………………………………………………………..................................... iii
Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam
Pembuatan Akta Jual Beli Tanah
Pande Putu Doron Swardika ……………………………………………………………………… 1
Status Hukum Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Warga Negara Asing
Melalui Perjanjian Nominee
Ni Nyoman Carina Pariska Pribadi… .…………… .………………… . .…………….. 24
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Covernote Sebagai Salah Satu Produk
Hukum Yang Tidak Diatur Dalam Undang - Undang Jabatan Notaris
Putu Ayu Lestari Dewi,SH ………………………………………………………………… 34
Analisis Keabsahan Akta Notaris Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan
Bukti Kepemilikan Dalam Bentuk Pipil
Anak Agung Ade Jaya Wibawa ……. . . .………………………………… . .………… . 44
Pengaturan Hubungan Hukum Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Deposan
Robert Wiradinata ……....…………….……………………………………………..…………. 54
Pengaturan Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi
Perusahaan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra ……....…………….……………………………. 65

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 1
TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH
Oleh
Pande Putu Doron Swardika
NIM : 1092461010
Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Email : [email protected]
Pembimbing I : Prof. Dr. Ibrahim R. SH., MH.
Pembimbing II : J.S. Wibisono, SH., MH., MKn.
Abstract
Along with the growth and development of such a large population, while the land area are
relatively not increased, obviously this causes the increasing demand for land, thereby it results in
various problems of land. To prevent or at least reduce the potential for conflict or dispute, then the
mechanism of transfer of land to be registered must be proven under the notarial deed of the Land Deed
Official (PPAT). In practice, often a deed which is not in accordance with the procedures of making the
deed of the Land Deed Official which could pose a risk to the security of rights to land. The legal
consequences of such deviations will put Land Deed Official held a judicial accountability with regard to
authentic act made, if it has legal flaws. In this case, the aspects of legal protection of the PPAT are not
expressly regulated by the Regulation for Position of PPAT, PPAT as an honorable position, should be
given special treatment than the general population because of PPAT is a representation of the state
government to implement some of the tasks in the areas of land associated with data maintenance of the
land registration (Bijhouding or Maintenance).
The problems under discussion in this study is what the responsibility of the Land Deed Official
over the deed of sale of land that they made if it has legal flaws and whether the Job Regulations of the
Land Deed Official has provided legal protection to the Land Deed Officials in performing their duties?
This study is classified as a normative legal research which is due to the lack of its governing law
by using the legislative and the conceptual approach. The legal research material used is derived from the
research literature in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through the
techniques of document studies and library research. The supporting legal materials and information that
has been collected were analyzed by the techniques of description, systematization and construction, then
it was analyzed qualitatively to obtain conclusions on the two issues under studied.
The research results showed that as a result of legal deviations from the law-making procedures
of the PPAT deed, therefore, the PPAT can be subject to sanctions as their consequences both
administrative, civil, or criminal sanctions. While the aspects of legal protection in the law enforcement
process against PPAT who violates the law is not regulated by the Job Regulations of the PPAT.
Keywords: Procedure for Making PPAT deed, Responsibility, Legal Protection, Land Deed Official
(PPAT).
I. Pendahuluan
Tanah dalam pengertian geografis adalah
lapisan permukaan bumi yang digunakan untuk
dipakai sebagai usaha. Dewasa ini tanah tidak
hanya dibutuhkan secara sederhana untuk tempat
tinggal ataupun sebagai modal alami utama dalam
kegiatan pertanian dan peternakan. Seiring dengan
laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk
yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relatif
tidak bertambah, secara nyata hal ini
menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin
meningkat, sehingga menyebabkan tanah dan
berbagai masalah agraria muncul dipermukaan.
Dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap pemilik tanah dan mengatur
kepemilikan, peralihan dan peruntukan tanah
secara adil dan menyeluruh serta untuk dapat
mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia,
sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD
NRI 1945 dan untuk dapat mengejawantahkan
amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, maka
diciptakan suatu Hukum Agraria Nasional yakni
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang
lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang
Pokok Agraria. (selanjutnya disingkat UUPA).

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 2
Pejabat Pembuat Akta Tanah
(selanjutnya disingkat PPAT) mempunyai peran
yang penting dalam pendaftaran tanah, yaitu
membantu Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (selanjutnya disingkat PJPPAT),
merupakan pelaksanaan dari ketentuan PP No. 24
Tahun 1997. Kemudian PP No. 37 Tahun 1998
dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4
Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP
No. 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT, (PMNA/Ka
BPN 4/1999). PMNA/Ka BPN 4/1999 dinyatakan
tidak berlaku lagi oleh Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP
No. 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT, (Perka BPN
1/2006).1 Kemudian Perka BPN 1/2006 diubah
dengan beberapa perubahan pasal, yang diatur
dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 23 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
BPN RI No. 1 tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang
PJPPAT, (Perka BPN 23/2009). Pendaftaran
peralihan hak atas tanah, dilaksanakan oleh
PPAT, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2
PJPPAT, dengan demikian dalam rangka
pendaftaran pemindahan hak, maka jual beli hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun harus dibuktikan dengan akta yang dibuat
di hadapan PPAT. Selain itu syarat jual beli harus
dibuktikan dengan akta PPAT ditegaskan pula
dalam Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.
Menurut Wawan Setiawan, setiap
pemberian atau adanya suatu kewenangan
senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau
1 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan
Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada
Media Grup, Jakarta, hal. 316-317.
tanggung jawab dari padanya.2 Dengan demikian
PPAT diberi kewenangan membuat akta otentik
khususnya bidang pertanahan, maka PPAT yang
bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi
segala persyaratan yang telah ditentukan,
khususnya dalam pembuatannya agar akta yang
dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik
yang sah. Sebagai konsekuensinya PPAT sebagai
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun, harus bertanggung jawab
apabila terjadi penyimpangan dan/atau
pelanggaran persyaratan pembuatan akta yang
dilakukannya, yang akan membawa akibat
terhadap tidak sahnya akta yang dibuat PPAT
tersebut.
Meskipun peralihan hak atas tanah
tersebut sudah dilaksanakan melalui akta PPAT,
tetapi terbuka kemungkinan akan dapat
menimbulkan sengketa pertanahan. Pembatalan
kepemilikan hak atas tanah, sedikit banyaknya
juga berkaitan dengan pembuatan akta jual beli
tanah dihadapan PPAT yang tidak sesuai dengan
prosedur pembuatan akta PPAT. Hal ini
disebabkan dalam prakteknya ada situasi-situasi
dan kondisi-kondisi dalam jual beli yang
menyebabkan ketidak-sesuaian tersebut sepertinya
harus dilakukan agar transaksi atau proses jual
beli tanah bisa dilangsungkan.
Adanya penyimpangan maupun kelalaian
dalam pembuatan akta jual beli oleh PPAT yang
pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yang
telah ditentukan dalam perundang-undangan
dalam praktek yang seringkali terjadi misalnya,
penandatanganan akta jual beli telah dilakukan
tapi PPAT belum mengecek atau memeriksa
kesesuaian sertifikat terlebih dahulu ke Kantor
Pertanahan; penandatanganan akta jual beli
2 Wawan Setiawan, 1991, “Tanggung Jawab
Notaris Dalam Pembuatan Akta”, Makalah dalam
seminar nasional sehari Ikatan Mahasiswa
Notariat Universitas Diponegoro, 9 Maret 1991,
Semarang, tanpa halaman.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 3
dilakukan di luar kantor PPAT dan tanpa dihadiri
oleh saksi-saksi; nilai harga transaksi yang dimuat
dalam akta jual beli berbeda dengan nilai transaksi
yang sebenarnya; dan praktek lainnya yang dapat
memberikan akibat hukum berupa akta yang
dibatalkan dimuka pengadilan atau yang hanya
dianggap sebagai akta di bawah tangan, yang
semua itu diantaranya disebabkan kelalaian dari
seorang PPAT yang membuat akta yang tidak
didasarkan pada persyaratan bentuk yang harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan
terkait.
Prinsip equality before the law adalah
pilar utama dari bangunan Negara Hukum yang
mengutamakan hukum di atas segalanya (supreme
of law). Pengakuan kedudukan tiap individu di
muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang
sama tanpa memandang status sosial.
Keberlakuan prinsip equality before the law
dalam praktek penegakan negara hukum yang
berdasarkan kedaulatan hukum terkadang
mengalami “penghalusan” atau “exception”
(pengecualian).
Perbedaan perlakuan hukum atau
pengecualian ini hanya berlaku jika ada alasan
yang khusus, misalnya pengecualian berlaku bagi
orang-orang/kelompok orang-orang tertentu yaitu
mereka yang oleh karena melaksanakan suatu
perbuatan yang ditugaskan oleh Undang-undang
tidak dapat dihukum/dipidana. Terhadap orang-
orang ini tidak berlaku kekebalan hukum, karena
apabila mereka terbukti melakukan tindak pidana
dengan menggunakan kekuasaan dan
kewenangannya, maka hukuman terhadap mereka
lebih berat daripada hukuman yang seharusnya
diterima oleh orang biasa.
Sehingga terhadap orang-orang ini jika
melakukan suatu perbuatan guna melaksanakan
ketentuan Undang-Undang tidak dapat dihukum
(bukan kebal hukum), sebaliknya apabila yang
bersangkutan melakukan suatu perbuatan yang
melanggar hukum dengan menggunakan
kekuasaan dan/atau kewenangannya, maka
hukumannya diperberat. Untuk menjadi orang
yang dikecualikan dari prinsip equality before the
law, tentu saja harus memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu yang dibuat sesuai standart
pemenuhan nilai-nilai sebagai orang yang
terhormat (nobile person) maupun jabatan
terhormat (nobile officium).
Seorang PPAT dalam melaksanakan
fungsi jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip
equality before the law, sepanjang dalam
melaksanakan jabatannya telah mengikuti
prosedur yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Namun dengan
“disetujuinya” PPAT diperiksa oleh penyidik,
penuntut umum dan/atau hakim, maka sudah
terdapat unsur pengkondisian bagi PPAT tersebut
untuk ditempatkan dalam posisi tidak berada
dalam golongan “nobile person” atau “nobile
officium”, melainkan seperti seorang yang tunduk
pada prinsip equality before the law seperti yang
terjadi pada orang pada umumnya. Selanjutnya
yang menjadi pertanyaan mendasar apakah PPAT
yang merupakan jabatan tertentu yang
menjalankan sebagian dari tugas pemerintah
khususnya di bidang pertanahan di dalam sistem
hukum Indonesia telah mendapatkan perlindungan
hukum secara layak?
Ketentuan dalam PP No. 37 Tahun 1998
tentang PJPPAT, maupun dalam Perka BPN
1/2006 sebagaimana telah diubah dengan Perka
BPN 23/2009 tentang Perubahan Atas Perka BPN
No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
PP No. 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT, sebagai
ketentuan bagi PPAT, tidak ada pengaturan
tentang perlindungan hukum bagi PPAT itu
sendiri, dalam peraturan terkait ke-PPAT-an
lainnya pun tidak diatur, maka perlu adanya dasar
hukum mengenai hal itu, karena PPAT
mempunyai peranan yang cukup besar dalam
membantu tugas pemerintah khususnya dibidang
pertanahan.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 4
Jadi dalam hal seorang PPAT juga ikut
terpanggil dalam suatu kasus tertentu, di mana ia
dijadikan sebagai saksi atau tersangka maupun
terdakwa, maka sampai di mana perlindungan
yang ia peroleh sebagai Pejabat Umum yang
menjalankan jabatannya, adalah dia diproses
dengan cara pada umumnya sesuai dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
dan tidak ada suatu mekanisme atau prosedur
yang bersifat khusus. Padahal PPAT
dikategorikan sebagai seorang Pejabat Umum,
dan oleh undang-undang diberikan suatu imunitas
hukum bagi jabatan-jabatan tertentu salah satunya
PPAT berupa hak ingkar atau hak mengundurkan
diri (verschoningrecht) dalam pelaksanaan
kewajiban memberi keterangan sebagai saksi di
Pengadilan, hal ini berkaitan dengan rahasia
jabatan.
Berdasarkan uraian di atas terdapat
kekosongan norma mengenai ketentuan
perlindungan hukum bagi PPAT dalam
menjalankan tugas jabatannya, dimana konsep
perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan
aspek pertanggungjawaban, sehingga Penulis
tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai
aspek pertanggungjawaban PPAT terhadap akta
jual beli tanah yang mengandung cacat hukum
kemudian mengkaji mengenai sejauh mana
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
mengatur mengenai perlindungan hukum bagi
PPAT dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Tujuan yang ingin dicapai dengan
adanya penelitian ini adalah meliputi tujuan
umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis
mengenai aspek tanggung jawab dan perlindungan
hukum PPAT dalam pembuatan akta jual beli
tanah. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis mengenai
aspek pertanggungjawaban PPAT terhadap akta
jual beli tanah yang di buat dihadapannya
mengandung cacat hukum, dan untuk mengetahui
sejauh mana pengaturan perlindungan hukum
kepada PPAT dalam melaksanakan tugas
jabatannya.
II. Metode Penelitian
2.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini
adalah yuridis normatif, dimana dilakukan
penelusuran terhadap permasalahan yang telah
dirumuskan dengan mempelajari ketentuan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.3
2.2 Jenis Pendekatan
Jenis pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan (the statute approach) dan pendekatan
analisis konsep hukum (analitical & conceptual
approach).
2.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum berupa:
a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini
adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945);
2. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata);
3. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
(UUJN);
3 Ronny Hamit i jo
Soemitro, 1990, Metodologi
Peneli t ian Hukum dan
Jurumetr i , Ghalia Indonesia,
Jakarta , hal . 14.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 5
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun
2009);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (PP No. 24 Tahun 1997);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PP No. 37 Tahun 1998/PJPPAT);
10. Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (PMNA/Ka BPN 3/1997);
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Perka
BPN 8/2012);
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006
tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Perka BPN 1/2006);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor 23 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (Perka BPN
23/2009);
14. Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Indonesia (Kode Etik
IPPAT).
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam penelitian ada yang berupa buku-
buku teks, artikel dalam berbagai
majalah ilmiah atau jurnal hukum,
dan makalah-makalah. Selain itu,
digunakan bahan hukum dari internet
dengan menyebutkan nama situsnya.
c. Bahan hukum tersier, yang memberikan
informasi lebih lanjut mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum
sekunder antara lain berupa kamus
hukum.
2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum
dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem
kartu.4 Sistem kartu yang digunakan kemudian
diterapkan dengan menggunakan teknik bola salju
dengan menemukan bahan hukum sebanyak
mungkin yang diawali dengan penentuan bahan
hukum yang mula-mula berjumlah kecil,
kemudian dari bahan hukum ini dipilih bahan-
bahan hukum untuk dijadikan bahan hukum
berikutnya, begitu selanjutnya, sehingga jumlah
bahan hukum semakin banyak.
2.5 Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang digunakan
dalam penilitian ini adalah teknik analisis isi.
Teknik analisis isi dalam penelitian ini diawali
dengan mengambil bahan hukum yang tepat
dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum
yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan
deskripsi dengan menguraikan proposisi-proposisi
4 Sistem kartu yaitu dilakukan dengan cara
mencatat dan memahami isi dari masing-masing
informasi yang diperoleh dari bahan hukum
primer, sekunder maupun bahan hukum tersier.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 6
hukum sesuai pokok permasalahan yang dikaji,
untuk selanjutnya dilakukan sistematisasi
/pengklasifikasian terhadap bahan-bahan hukum
tertulis melalui proses analisis tentang isi-isinya.
Berdasarkan atas hasil sistematisasi tersebut,
kemudian dilakukan konstruksi hukum dan
interpretasi atau penafsiran secara normatif
terhadap proposisi-proposisi yang ada sehingga
dapat diberikan argumentasi untuk mendapat
kesimpulan atas pokok permasalahan yang akan
diteliti dalam penulisan penelitian ini.
III. Tinjauan Umum
3.1 Tinjauan Umum tentang PPAT Sebagai
Pejabat Umum
Menurut Soegondo Notodisoejo, Pejabat
Umum adalah seorang yang diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah dan diberi
wewenang dan kewajiban untuk melayani publik
dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta
melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber
pada kewibawaan (gezag) dari pemerintah. Dalam
jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang
membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya
dalam masyarakat.5 Sedangkan menurut Wawan
Setiawan, Pejabat Umum adalah organ negara
yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum (met
openbaar gezag bekleed), berwenang
menjalankan (sebagian dari) kekuasaan negara
untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik
dalam bidang hukum perdata.6
Berkenaan dengan diperlukannya akta
PPAT sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat
menurut tatanan hukum yang berlaku, maka
diperlukan adanya pejabat umum yang ditugaskan
oleh undang-undang untuk melaksanakan
5 R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum
Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44.
6 Wawan Setiawan, 1996, “Kedudukan dan
Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT
dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata
Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional”,
Media Notariat Nomor 38-41, Jan-Apr-Jul-Okt
1996, hal. 264.
pembuatan akta otentik itu. Perwujudan tentang
perlunya kehadiran pejabat umum untuk lahirnya
akta otentik, maka keberadaan PPAT sebagai
pejabat umum tidak dapat dihindarkan. Agar suatu
tulisan mempunyai nilai bobot akta otentik yang
bentuknya ditentukan oleh undang-undang
membawa konsekuensi logis, bahwa pejabat
umum yang melaksanakan pembuatan akta otentik
itupun harus pula diatur dalam Undang-Undang,
dan tidak dalam peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah, misalnya Peraturan
Pemerintah.
Embrio institusi PPAT telah ada sejak
tahun 1961 berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah dengan istilah
Penjabat saja. Bahwa yang dimaksud pejabat
adalah PPAT disebutkan dalam Peraturan Menteri
Agraria No. 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta
(PMA 11/1961).7 Pada awal kelahirannya PPAT
tidak dikategorikan atau disebut sebagai Pejabat
Umum, perkembangan kemudian berdasarkan
Pasal 1 angka 4 UU No. 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-
Benda yang Berkaitan dengan Tanah bahwa :
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat
Umum yang diberi wewenang untuk membuat
akta pemindahan hak atas tanah, akta
pembebanan hak atas tanah, dan akta
pemberian kuasa membebankan Hak
Tanggungan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”
Selanjutnya keberadaan PPAT ditegaskan
dalam Pasal 1 angka 24 PP No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah bahwa :
7 Habib Adjie, 2009, Meneropong Khazanah
Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal. 253.
Catatan Penulis : Dalam ketentuan Pasal 19 PP
No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,
menggunakan istilah “Penjabat”, sedangkan
penyebutan secara lengkap istilah “Pejabat
Pembuat Akta Tanah” ditemukan pada Pasal 1
PMA No. 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 7
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana
disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
tertentu.”
Secara khusus keberadaan PPAT diatur
dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 37 Tahun 1998
tentang PJPPAT, yang menegaskan bahwa :
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya
disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun.”
Pengertian yang sama diatur juga didalam
peraturan pelaksana PJPPAT yakni pada Pasal 1
angka 1 Perka BPN 1/2006, yang menegaskan :
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya
disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun.”
Sedangkan pada Pasal 1 angka 3 Kode Etik
IPPAT, menentukan bahwa :
“PPAT adalah setiap orang yang
menjalankan tugas jabatannya yang
menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum.”
Dari definisi-definisi PPAT yang disebut di
atas maka dapat disimpulkan bahwa PPAT adalah
“Pejabat Umum” yang berwenang membuat akta
otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum
tertentu berkaitan dengan hak-hak atas tanah atau
hak milik atas satuan rumah susun. Dimana
kewenangan ini diberikan kepada pejabat tersebut
oleh peraturan perundang-undangan.
3.2 Tinjauan Umum tentang Tata Cara
Pembuatan Akta PPAT
Berkaitan dengan jual beli tanah,
terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi
berkaitan dengan tata cara pembuatan akta PPAT,
yakni syarat formil dan syarat materil. Adapun
syarat formil dari tata cara pembuatan akta PPAT
tersebar dalam berbagai peraturan yang terkait ke-
PPAT-an. Mengenai bentuk dan tata cara
pembuatan akta PPAT didasari oleh Pasal 24 PP
No. 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT yang
menentukan “Ketentuan-ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pembuatan akta PPAT diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai
pendaftaran tanah.” Ketentuan dalam PP No. 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
mengatur mengenai hal ini ditegaskan pada Pasal
38 ayat (2) yang menentukan “Bentuk, isi dan
cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh
Menteri”. Peraturan yang dimaksud adalah
PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, yang diatur pada Pasal
95-102. Ketentuan formil lainnya dapat juga
ditemui pada Pasal 21-24 PP No. 37 Tahun 1998
tentang PJPPAT, Pasal 51-55 Perka BPN No. 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP
No. 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT, dan
peraturan yang berkaitan dengan perpajakan.8
1. Syarat Formil
Dalam hal pembuatan akta PPAT, terdapat
tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh
PPAT yaitu:
a. Sebelum melaksanakan pembuatan akta
jual beli hak atas tanah, terlebih dahulu
PPAT wajib melakukan pemeriksaan ke
Kantor Pertanahan setempat untuk
mengetahui kesesuaian sertifikat hak atas
tanah yang bersangkutan dengan daftar-
daftar yang ada di Kantor Pertanahan
dengan memperlihatkan sertifikat asli
kepada petugas Kantor Pertanahan.
(Pasal 97 ayat (1) PMNA/Ka BPN
3/1997).
b. Penyiapan dan pembuatan akta dilakukan
oleh PPAT sendiri dan harus dilakukan
8 Ketentuan formil mengenai tata cara
pembuatan akta PPAT ini pada substansinya
adalah sama, dan Penulis lebih menitikberatkan
pada pengaturan yang diatur pada PMNA/Ka
BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, karena lebih memiliki
relevansi secara yuridis.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 8
dalam bentuk yang sesuai dengan
ketentuan yang telah ditentukan. (Pasal
96 Perka BPN 8/2012 tentang Perubahan
Atas PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
Ketentuan mengenai bentuk akta
telah mengalami perubahan dengan
disahkannya Perka BPN 8/2012, dimana
pada peraturan yang lama pembuatan
akta harus dilakukan dengan
menggunakan formulir (blanko) akta
yang dikeluarkan oleh BPN. Artinya
PPAT tinggal mengisi blanko yang
bentuk dan formatnya telah ditentukan
oleh BPN. Sedangkan ketentuan pada
Perka BPN 8/2012, PPAT diberi
keleluasaan untuk menyiapkan dan
membuat akta PPAT sendiri. Akan tetapi
bentuk dan formatnya harus mengikuti
ketentuan yang diatur oleh BPN
sebagaimana terlampir pada lampiran 16-
23 Perka BPN 3/1997.
Penulis berpendapat bahwa
perubahan yang diatur dalam peraturan
yang baru tersebut bertujuan untuk
mengatasi terjadinya kelangkaan blanko.
Sehingga PPAT diberi kewenangan
untuk membuat akta sendiri akan tetapi
bentuk dan formulasinya harus sama
seperti yang ditentukan oleh BPN.
Sebagaimana di atur pada Pasal 96 ayat
(5) Perka BPN 8/2012 “Kepala Kantor
Pertanahan menolak pendaftaran akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur pada ayat (1)”. Artinya adalah
BPN akan menolak akta PPAT yang
bentuk dan formatnya tidak sesuai
dengan ketentuan dari BPN.
Sebelum Perka BPN 8/2012 berlaku
apabila terjadi kelangkaan blanko, PPAT
tidak diberikan kewenangan untuk
membuat aktanya sendiri. BPN melalui
suratnya Nomor 640/1884 tertanggal 31
Juli 2003 telah memberikan kewenangan
kepada Kanwil BPN dalam menghadapi
keadaan mendesak seperti dalam
menghadapi kelangkaan dan kekurangan
blanko akta PPAT dengan membuat
fotocopy blanko akta sebagai ganti
blanko akta yang dicetak, dengan syarat
pada halaman pertama setiap fotocopy
blanko akta itu dilegalisasi oleh Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Propinsi atau pejabat yang ditunjuk serta
dibubuhi paraf dan cap dinas pada setiap
halaman.9
c. Dalam hal izin pemindahan hak
diperlukan maka izin tersebut harus
sudah diperoleh sebelum akta
pemindahan atau pembebanan hak yang
bersangkutan dibuat. (Pasal 98 ayat (2)
PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
d. Sebelum dibuat akta mengenai
pemindahan hak atas tanah, calon
penerima hak harus membuat pernyataan
yang menyatakan:
a. bahwa yang bersangkutan dengan
pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas tanah
yang melebihi ketentuan maksimum
penguasaan tanah menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. bahwa yang bersangkutan dengan
pemindahan hak tersebut tidak
menjadi pemegang hak atas tanah
absentee (guntai) menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. bahwa yang bersangkutan
menyadari bahwa apabila
pernyataan sebagaimana dimaksud
pada a dan b tersebut tidak benar
maka tanah kelebihan atau tanah
9 Bambang S. Oyong, 2013, “Peraturan
KBPN Nomor 8 Tahun 2012 Dalam Kajian Tugas
Pekerjaan PPAT”, diakses pada tanggal 18
Februari 2013, URL :
http://bambangoyong.blogspot.com/2013/01/norm
al-0-false-false-false-en-us-x-none.html

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 9
absentee tersebut menjadi obyek
landreform;
d. bahwa yang bersangkutan bersedia
menanggung semua akibat
hukumnya, apabila pernyataan
sebagaimana dimaksud pada a dan b
tidak benar.
(Pasal 99 ayat (1) PMNA/Ka BPN
3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
PP No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah).
e. Pembuatan akta PPAT harus dihadiri
oleh para pihak yang melakukan
perbuatan hukum atau orang yang
dikuasakan olehnya dengan surat kuasa
tertulis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(Pasal 101 ayat (1) PMNA/Ka BPN
3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
PP No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah).
f. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
memenuhi syarat untuk bertindak
sebagai saksi dalam suatu perbuatan
hukum, yang memberi kesaksian antara
lain mengenai kehadiran para pihak atau
kuasanya, keberadaan dokumen-
dokumen yang ditunjukkan dalam
pembuatan akta, dan telah
dilaksanakannya perbuatan hukum
tersebut oleh para pihak yang
bersangkutan. (Pasal 101 ayat (2)
PMNA/Ka BPN 3/1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
g. PPAT wajib membacakan akta kepada
para pihak yang bersangkutan dan
memberi penjelasan mengenai isi dan
maksud pembuatan akta dan prosedur
pendaftaran yang harus dilaksanakan
selanjutnya sesuai ketentuan yang
berlaku. (Pasal 101 ayat (3) PMNA/Ka
BPN 3/1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah).
h. PPAT dilarang membuat akta, apabila
PPAT sendiri, suami atau istrinya,
keluarganya sedarah atau semenda,
dalam garis lurus tanpa pembatasan
derajat dan dalam garis ke samping
sampai derajat kedua, menjadi pihak
dalam perbuatan hukum yang
bersangkutan, baik dengan cara bertindak
sendiri maupun melalui kuasa, atau
menjadi kuasa dari pihak lain. (Pasal 23
ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang
PJPPAT).
i. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal ditandatanganinya akta
yang bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatkannya
berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan
untuk didaftar. (Pasal 40 ayat (1) PP No.
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah).
j. Terhadap perbuatan hukum pengalihan
hak tersebut, maka PPAT wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis
mengenai telah disampaikannya akta
sebagai mana dimaksud di atas kepada
para pihak yang bersangkutan. (Pasal 40
ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah).
k. Sebelum dilakukannya penandatanganan
akta jual beli, PPAT harus terlebih
dahulu meminta bukti pembayaran pajak,
ketentuan ini menyatakan: “Pejabat
Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya
dapat menandatangani akta pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak”. (Pasal 91 ayat (1)
UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah).
Ketentuan mengenai tugas PPAT
untuk meminta bukti pembayaran pajak
dari pembeli diatur pada Pasal 24 ayat
(1) UU No. 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
(UU BPHTB), yang menyatakan:
“PPAT/Notaris hanya dapat
menandatangani akta pemindahan hak
atas tanah dan atau bangunan pada saat
Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak berupa Surat Setoran
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 10
Bangunan.” Sedangkan bagi penjual
diatur pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 71
Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga
Atas PP No. 48 Tahun 1994 Tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas
Tanah Dan/Atau Bangunan, yang
menyatakan: “Pejabat yang berwenang
hanya menandatangani akta, keputusan,
perjanjian, kesepakatan atau risalah
lelang atas pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan apabila kepadanya
dibuktikan oleh orang pribadi atau
badan dimaksud bahwa kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
telah dipenuhi dengan menyerahkan
fotokopi Surat Setoran Pajak yang
bersangkutan dengan menunjukkan
aslinya.”
2. Syarat Materil.
Selain tahapan-tahapan syarat formil
tersebut di atas, Adrian Sutedi mengemukakan
bahwa syarat materil sangat menentukan sahnya
jual beli tanah, antara lain sebagai berikut :10
a. Pembeli berhak membeli tanah yang
bersangkutan.
Maksudnya adalah pembeli sebagai
penerima hak harus memenuhi syarat
untuk memiliki tanah yang dibelinya atau
memenuhi syarat sebagai subyek hak
milik.
b. Penjual berhak untuk menjual tanah yang
bersangkutan
Yang berhak menjual suatu bidang tanah
tentu saja pemegang hak yang sah atas
tanah tersebut yang disebut pemilik.
Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu
orang, maka ia berhak untuk menjual
sendiri tanah itu. Akan tetapi, apabila
pemilik tanah adalah dua orang maka
10
Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas
Tanah dan Pendaftarannya, Cet. ke-4, Sinar
Grafika, Jakarta, hal. 77-78.
yang berhak menjual tanah itu ialah
kedua orang itu bersama-sama. Tidak
boleh seorang saja yang bertindak
sebagai penjual.
c. Tanah hak yang bersangkutan boleh
diperjualbelikan dan tidak sedang dalam
keadaan sengketa. Jika salah satu syarat
materil ini tidak dipenuhi dalam arti
penjual bukan merupakan orang yang
berhak atas tanah yang dijualnya atau
pembeli tidak memenuhi syarat untuk
menjadi pemilik hak atas tanah, atau
tanah yang diperjualbelikan sedang
dalam sengketa atau merupakan tanah
yang tidak boleh diperjualbelikan, maka
jual beli tanah tersebut adalah tidak sah.
Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang
tidak berhak adalah batal demi hukum.
Artinya, sejak semula hukum
menganggap tidak pernah terjadi jual
beli.
Ketentuan mengenai syarat materil diatas,
secara yuridis adalah berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 39 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, yakni PPAT
berwenang menolak untuk membuat akta jual
beli jika:11
a. Mengenai bidang tanah yang sudah
terdaftar, kepadanya tidak disampaikan
sertifikat asli hak yang bersangkutan atau
sertifikat yang diserahkan tidak sesuai
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota;
b. Salah satu atau para pihak yang akan
melakukan jual beli atau saksinya tidak
berhak atau memenuhi syarat untuk
bertindak dalam jual beli;
c. Salah satu atau para pihak bertindak atas
dasar surat kuasa mutlak yang pada
hakikatnya berisikan perbuatan hukum
pemindahan hak;
d. Untuk jual beli yang akan dilakukan
belum diperoleh izin pejabat atau instansi
yang berwenang, apabila izin tersebut
11
Urip Santoso, Op.cit, hal. 375.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 11
diperlukan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Obyek jual beli yang bersangkutan
sedang dalam sengketa mengenai data
fisik dan/atau data yuridis; dan
f. Tidak dipenuhinya syarat lain atau
dilanggar larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.12
IV. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta
Tanah Atas Akta Jual Beli Tanah Yang
Dibuatnya Mengandung Cacat Hukum
4.1 Sebab Degradasi Kekuatan Pembuktian
dan Batalnya Akta PPAT
1. Sebab Pasal 1868 KUHPerdata.
Dalam kaitannya dengan akta PPAT,
ketentuan tersebut tercantum dalam ketentuan
Pasal 95-102 PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.
a. PPAT belum melakukan cek bersih atau
pemeriksaan kesesuaian data ke Kantor
Pertanahan, akan tetapi penandatanganan
akta jual beli telah dilakukan.
b. Penandatanganan akta jual beli oleh para
pihak (penjual dan pembeli) tidak dilakukan
dalam waktu yang bersamaan di hadapan
PPAT dan atau di hadapan PPAT yang
menandatangani akta jual beli.
12
Dalam penje lasan
pada Pasa l 39 ayat (1) PP No.
24 Tahun 1997, menyebutkan
contoh syarat atau larangan
yang d itentukan o leh peraturan
perundang-undangan yang
ber laku sebagaimana ketentuan
huruf f d i a tas, adalah larangan
yang diadakan o leh PP No. 48
Tahun 1994 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dar i Pengalihan
Hak Atas Tanah dan Bangunan
Jo. PP No. 27 Tahun 1996
tentang perubahan Atas PP No.
48 Tahun 1994 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dar i
Pengalihan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan untuk membuat akta,
j ika kepadanya t idak diserahkan
fo tocopy sura t se toran pajak
penghasilan yang bersangkutan.
c. Pembuatan dan penandatanganan akta jual
beli dilakukan diluar daerah kerja PPAT dan
atau diluar Kantor PPAT dan tanpa dihadiri
oleh saksi-saksi.
d. PPAT tidak membacakan isi dari akta jual
beli dihadapan para pihak secara terperinci,
hanya menjelaskan mengenai maksud dari
pembuatan akta.
e. Nilai harga transaksi yang dimuat di akta
jual beli tidak sesuai dengan nilai harga
transaksi sebenarnya.
f. Penandatanganan akta jual beli telah
dilakukan akan tetapi para pihak belum
melakukan pembayaran pajak, yakni Pajak
Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
bagi Penjual, dan Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi
Pembeli.
Ketentuan dalam pasal-pasal itu
merupakan syarat formil dari prosedur pembuatan
akta PPAT, yang apabila dilanggar oleh PPAT,
maka akta PPAT itu hanya memiliki kekuatan
pembuktian sebagai akta dibawah tangan
sepanjang para pihak menandatanganinya, dan
degradasi kekuatan bukti akta PPAT tersebut
menjadi akta dibawah tangan sejak adanya
putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap. Sepanjang berubahnya atau
terjadinya degradasi dari akta otentik menjadi akta
dibawah tangan tidak menimbulkan kerugian,
maka PPAT bersangkutan tidak dapat dimintakan
tanggung jawab hukumnya melalui Pasal 1365
KUHPerdata. Namun apabila karena degradasi
kekuatan bukti menjadi akta dibawah tangan
tersebut menimbulkan kerugian, dimana adanya
pihak ketiga yang memanfaatkan keadaan ini
sehingga salah satu pihak mendapatkan kerugian
maka PPAT bersangkutan dapat digugat dengan
perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur
didalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Jadi kesimpulannya adalah apabila
terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal
95-102 PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal
1868 dan 1869 KUHPerdata, maka akta otentik

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 12
dapat turun atau terdegradasi kekuatan
pembuktiannya dari mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna menjadi hanya mempunyai
kekuatan pembuktian selayaknya akta dibawah
tangan, jika pejabat umum yang membuat akta itu
tidak berwenang untuk membuat akta tersebut
atau jika akta tersebut cacat dalam bentuknya,
karena dalam perjalanan proses pembuatan akta
tersebut terdapat salah satu atau lebih
penyimpangan terhadap syarat formil dari
prosedur atau tata cara pembuatan akta PPAT,
baik disengaja maupun karena kealpaan dan/atau
kelalaian dari PPAT bersangkutan.
2. Sebab Pasal 1320 KUHPerdata.
Penyimpangan terhadap syarat materil
(subyektif) menyebabkan akta jual beli yang
dibuat oleh PPAT bersangkutan dapat dimintai
pembatalan oleh pihak yang tidak cakap dan/atau
wakilnya yang sah. Sehingga salah satu pihak
dalam perjanjian maupun pihak ketiga, dapat
mengajukan pembatalan atas perjanjian baik
sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu
dilaksanakan maupun setelahnya. Pasal 1451 dan
Pasal 1452 KUHPerdata menentukan bahwa
setiap kebatalan membawa akibat bahwa
kebendaan dan orang-orang yang dipulihkannya
sama seperti keadaan sebelum perjanjian itu
dibuat. Jadi perjanjian yang telah di buat akan
tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan
(oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak
meminta pembatalan tersebut. Sedangkan
penyimpangan terhadap syarat materil (obyektif)
menyebabkan akta jual beli yang dibuat oleh
PPAT bersangkutan dapat dinyatakan batal demi
hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak
semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.
1. Akta PPAT tersebut dapat dibatalkan.
Dalam kaitannya dengan syarat materil
prosedur atau tata cara pembuatan akta PPAT
adalah ketidakcakapan seseorang untuk
melakukan tindakan hukum (handeling-
sonbekwaamheid).
a. Salah satu atau para penghadap dalam
perjanjian tersebut tidak cakap untuk bertindak
dalam hukum, dan/atau tidak memiliki
kewenangan untuk melakukan tindakan atau
perbuatan hukum tertentu. Misalnya anak
berumur 17 tahun tidak berwenang melakukan
jual beli, walaupun ia yang berhak atas tanah
itu. Jual beli terlaksana jika yang bertindak
adalah ayah dari anak itu sebagai orang yang
melakukan kekuasaan orang tua. Mengenai
yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330
KUHPerdata, yang menentukan: 1). Telah
berusia 21 tahun, 2). Atau belum 21 tahun
tetap sudah atau pernah kawin sebelumnya.
(Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g PP No. 24
Tahun 1997 Jo. Pasal 330 Jo. 1330
KUHPerdata).
b. Salah satu atau para penghadap bertindak
berdasarkan kuasa, namun pemberi kuasa yang
disebutkan dalam akta kuasa telah meninggal
dunia. Berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata,
berakhirnya pemberian kuasa dapat
disebabkan karena penarikan kembali kuasa
oleh pemberi kuasa; penghentian kuasa oleh
penerima kuasa; meninggalnya atau
diampunya atau pailitnya pemberi kuasa atau
penerima kuasa; dan karena perkawinan
perempuan sebagai pihak pemberi atau
penerima kuasa. (Pasal 39 ayat (1) huruf c dan
g PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 1813
KUHPerdata).
c. Salah satu atau para penghadap bertindak
berdasarkan kuasa substitusi, namun pada
surat kuasa semula tidak dicantumkan klausula
atau ketentuan tentang hal itu. Berdasarkan
Pasal 1803 KUHPerdata mengatur bahwa
pemberian kuasa substitusi harus dengan jelas
disebutkan dalam surat kuasa, dan apabila
jelas disebutkan maka pemberian kuasa
substitusi harus diikuti dengan penyebutan
nama penerima kuasa substitusi. Kuasa
Substitusi adalah penggantian penerima kuasa
melalui pengalihan, atau dengan kata lain
bahwa Kuasa Substitusi adalah Kuasa yang
dapat dikuasakan kembali kepada orang lain.
Surat kuasa bisa dialihkan kepada pihak lain
dengan persetujuan pemberi kuasa awal,
dengan ketentuan dalam surat kuasa yang
pertama harus dinyatakan bahwa surat kuasa
tersebut dapat dialihkan dengan hak substitusi.
Jika tidak dinyatakan demikian, maka surat
kuasa tersebut dapat dinyatakan tidak
sah. (Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g PP No. 24
Tahun 1997 Jo. Pasal 1803 KUHPerdata).

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 13
Penyimpangan terhadap syarat materil
(subyektif) ini menyebabkan akta jual beli yang
dibuat oleh PPAT bersangkutan dapat dimintai
pembatalan oleh pihak yang tidak cakap dan/atau
wakilnya yang sah. Sehingga salah satu pihak
dalam perjanjian maupun pihak ketiga, dapat
mengajukan pembatalan atas perjanjian baik
sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu
dilaksanakan maupun setelahnya. Pasal 1451 dan
Pasal 1452 KUHPerdata menentukan bahwa
setiap kebatalan membawa akibat bahwa
kebendaan dan orang-orang yang dipulihkannya
sama seperti keadaan sebelum perjanjian itu
dibuat. Jadi perjanjian yang telah di buat akan
tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan
(oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak
meminta pembatalan tersebut.
2. Akta PPAT tersebut batal demi hukum
Dalam kaitannya dengan syarat materil
prosedur atau tata cara pembuatan akta PPAT
adalah ketidakwenangan seseorang untuk
melakukan tindakan hukum (handeling-
sonbevoegdheid).
a. Pihak penjual dalam akta PPAT tidak disertai
dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak
yang berhak memberi persetujuan terhadap
perbuatan hukum dalam suatu akta, artinya
tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu, misalnya :
- Sebidang tanah dalam sertifikat atas nama
istrinya, sedangkan tanah tersebut adalah
harta bersama dengan suaminya, akan
tetapi istri tidak atau belum mendapat
persetujuan menjual sendiri tanah tersebut
dari suami, atau suaminya belum
memberikan persetujuan tertulis kepada
istri. Demikian juga sebaliknya, istri belum
memberi persetujuan kepada suami untuk
menjual suatu tanah sebagai harta bersama
walaupun tertulis atas nama suami. (Pasal
39 ayat (1) huruf c dan g PP No. 24 Tahun
1997 Jo. Pasal 119 KUHPerdata).
- Terhadap pengurus perseroan melakukan
perbuatan untuk mengalihkan atau
menjaminkan hak atas tanah yang
merupakan harta kekayaan perseroan tanpa
adanya persetujuan dari pesero yang
ditetapkan dalam anggaran dasar
perseroan. Demikian juga terhadap salah
seorang atau beberapa orang pengurus
yayasan atau koperasi dalam melakukan
perbuatan hukum mengalihkan atau
menjaminkan hak atas tanah tanpa
persetujuan dari pengurus yayasan dan
koperasi yang ditetapkan dalam anggaran
dasar. (Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g PP
No. 24 Tahun 1997).
- Sebidang tanah dalam sertifikat atas nama,
misalnya X, tetapi Tuan X ini tunduk
kepada KUHPerdata yakni sedang berada
dibawah pengampuan, dan Y sebagai
pengampu atau curator dari X hendak
menjual tanah tersebut dengan alasan
untuk kepentingan X, akan tetapi Y belum
mendapat persetujuan atau ijin dari Ketua
Pengadilan Negeri. (Pasal 39 ayat (1) huruf
e dan g PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal
452 Jo. 393 KUHPerdata).
b. Penghadap yang hendak menjual tanah
belum/tidak mendapat persetujuan dari para
ahli waris. (Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g PP
No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 833 ayat (1) Jo.
Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata).
c. Salah satu penghadap bertindak berdasarkan
surat kuasa mutlak, surat kuasa mutlak pada
saat ini tidak diperbolehkan lagi khususnya
dalam hubungannya dengan Tanah
(benda tidak bergerak) yaitu berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun
1982 tentang larangan penggunaan kuasa
mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah,
tanggal 6 Maret 1982, jual-beli tanah dengan
menggunakan surat kuasa mutlak tidak sah,
sehingga batal demi hukum.
Jadi kesimpulannya adalah apabila
terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 39
ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah juncto Pasal 1320
KUHPerdata, maka akta PPAT yang dibuatnya
akan berkonsekuensi logis dapat ditolak
pendaftarannya, dimana berkas permohonan
pendaftaran peralihan haknya sudah diproses
secara administratif, namun ketika diteliti
substansi perbuatan hukumnya, terdapat
permasalahan yang menyebabkan akta ditolak
pendaftarannya. Selanjutnya berkaitan dengan
tugas dan wewenang dari PPAT dalam pembuatan
akta jual beli tanah yang mengandung unsur
penyimpangan terhadap syarat materil dari
prosedur pembuatan akta PPAT, yang terdiri dari

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 14
syarat subyek (subyek hak atau orang-orang yang
menghadap atau komparan) dan syarat obyek
(obyek hak yang dialihkan), baik disengaja
maupun karena kealpaan dan/atau kelalaian dari
PPAT bersangkutan, maka akta PPAT itu akan
memiliki konsekuensi yuridis yaitu dapat
dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
4.2 Bentuk Pertanggungjawaban PPAT Atas
Akta Yang Mengandung Cacat Hukum
1. Tanggung Jawab Secara Administratif.
Pertanggungjawaban PPAT terkait
kesengajaan, kealpaan dan/atau kelalaiannya
dalam pembuatan akta jual beli yang menyimpang
dari syarat formil dan syarat materil tata cara
pembuatan akta PPAT, maka PPAT dapat
dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Perka
BPN 1/2006, penyimpangan terhadap syarat
formil dan materil tersebut adalah termasuk
pelanggaran berat oleh PPAT yang dapat
dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak
hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan
Pertanahaan Nasional Indonesia.
Tanggung jawab PPAT secara
administratif ini, termasuk didalamnya adalah
tanggung jawab perpajakan yang merupakan
kewenangan tambahan PPAT yang diberikan oleh
undang-undang perpajakan. Berkaitan dengan hal
itu PPAT dapat dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- terhadap
pelanggaran Pasal 91 ayat (1) UU No. 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah. Jadi, sanksi yang dapat mengancam
PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan
syarat formil dan syarat materil dari prosedur atau
tata cara pembuatan akta PPAT adalah sanksi
pemberhentian dengan tidak hormat dari
jabatannya dan pengenaan denda administratif.
2. Tanggung Jawab Secara Keperdataan.
Pertanggungjawaban PPAT secara
keperdataan sebagai akibat dari adanya kesalahan
karena kesengajaan maupun kelalaian berupa
kekurang-hati-hatian, ketidakcermatan dan
ketidaktelitian dalam pelaksanaan kewajiban
hukum bagi PPAT dalam pembuatan akta jual beli
tanah, sehingga menyebabkan pelaksanaan hak
subyektif seseorang menjadi terganggu, apabila
menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak,
maka PPAT bersangkutan harus bertanggung
jawab untuk mengganti kerugian yang diderita
oleh para pihak tersebut dalam bentuk
penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.
Penentuan bahwa akta tersebut terdegradasi
menjadi akta dibawah tangan maupun dinyatakan
batal dan/atau batal demi hukum, dan menjadi
suatu delik perbuatan melanggar hukum yang
menimbulkan kerugian, harus didasari dengan
adanya suatu putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila
ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai,
bahwa akta PPAT tersebut palsu atau tidak benar
karena telah terjadi penyimpangan terhadap syarat
materil dan formil dari prosedur pembuatan akta
PPAT (aspek formal), maka pihak tersebut harus
membuktikan tuduhan atau penilaian sendiri
melalui proses hukum gugatan perdata bukan
dengan cara mengadukan PPAT kepada pihak
kepolisian.
3. Tanggung Jawab Secara Pidana.
Penjatuhan sanksi pidana terhadap PPAT
dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan
sebagaimana tersebut dilanggar, artinya
disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang
tersebut dalam peraturan perundang-undangan
terkait ke-PPAT-an, Kode Etik IPPAT juga harus
memenuhi rumusan yang tersebut dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menurut Habib Adjie, adapun perkara
pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta
Notaris/PPAT dalam pembuatan akta otentik
adalah sebagai berikut:13
a. Membuat surat palsu/yang dipalsukan
dan menggunakan surat palsu/yang
13
Habib Adjie, Op. cit, hal. 76.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 15
dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2)
KUHP);
b. Melakukan pemalsuan terhadap akta
otentik (Pasal 264 KUHP);
c. Menyuruh mencantumkan keterangan
palsu dalam akta otentik (Pasal 266
KUHP);
d. Melakukan, menyuruh melakukan, turut
serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263
ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264
atau Pasal 266 KUHP);
e. Membantu membuat surat palsu/atau
yang dipalsukan dan menggunakan surat
palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1)
dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2)
KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266
KUHP).
Penulis berpendapat bahwa seorang
PPAT tidak dapat dikenakan Pasal 266 ayat (1)
KUHP. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 266 ayat
(1) tersebut, terdapat unsur menyuruh. PPAT
dalam pembuatan akta jual beli hanya merupakan
media (alat) untuk lahirnya suatu akta otentik,
sedangkan inisiatif timbul dari para penghadap,
sehingga dalam hal ini PPAT adalah pihak yang
disuruh dan bukan pihak yang menyuruh. Namun,
apabila seorang PPAT telah dengan sengaja dan
diinsyafi atau disadari bekerja sama dengan
penghadap, maka PPAT dapat dikenakan Pasal
263 ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan Pasal
55 (1) KUHP, yaitu turut serta melakukan tindak
pidana. Selain itu, karena produk yang dihasilkan
oleh PPAT adalah berupa akta otentik, maka
PPAT dikenakan pemberatan yaitu sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) huruf a
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
V. Perlindungan Hukum Bagi Pejabat
Pembuat Akta Tanah Dalam
Melaksanakan Tugas Jabatannya
5.1 Perlindungan Hukum Terhadap PPAT
Berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT
1. Pengawasan Terhadap Tugas Jabatan PPAT.
Institusi yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap PPAT dalam melaksanakan
jabatannya adalah Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(IPPAT). Adapun peranan BPN dalam hal ini
adalah memberikan pembinaan dan pengawasan
terhadap PPAT agar dalam melaksanakan
jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan peranan
IPPAT dalam hal ini adalah memberikan
bimbingan dan pengawasan terhadap PPAT agar
dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan
Kode Etik IPPAT.
Penulis berpendapat bahwa pengawasan
oleh BPN dan IPPAT tersebut pada dasarnya
adalah merupakan wujud dari perlindungan
hukum (bersifat intern) terhadap PPAT itu sendiri
oleh karena dengan adanya suatu pengawasan,
maka setiap PPAT dalam berperilaku dan
tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya
maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor
hukum, sehubungan dalam menjalankan tugasnya,
seorang PPAT dituntut untuk selalu berpijak pada
hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia,
dan juga berkewajiban untuk menjalankan tugas
sesuai dengan etika yang sudah disepakati
bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik ini
membatasi tindak tanduk PPAT agar dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak bertindak
sewenang-wenang.
2. Prosedur Khusus Dalam Penegakan Hukum
Terhadap PPAT
Berdasarkan MoU atau Nota
Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, No. Pol. : B/1055/V/2006 dan Nomor :
05/PP-IPPAT/V/2006 tentang Pembinaan dan
Peningkatan Profesionalisme Di Bidang
Penegakan Hukum. Dalam lampiran nota
kesepahaman (MoU) ini pada Pasal 1 ayat (2),
mengatur bahwa ketentuan Pasal 66 UUJN
diberlakukan juga bagi PPAT dalam lingkup
proses peradilan pidana, sedangkan dalam proses
peradilan perdata tidak ada perangkat hukum yang
mengaturnya, karena MoU diatas adalah nota

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 16
kesepahaman antara POLRI dengan IPPAT,
sedangkan MoU antara Badan Peradilan dengan
IPPAT tidak ada atau tidak diatur. Namun yang
menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah
kekuatan hukum dari suatu nota kesepahaman
atau MoU ini? Menurut Sjaifurrachman, MoU
atau Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan IPPAT bukan
merupakan produk hukum, dan hanya
kesepakatan antara organisasi IPPAT dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak
mengikat Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal
ini PPAT yang dipanggil sebagai saksi atau
tersangka diberlakukan ketentuan Pasal 112
KUHAP sedangkan penyitaan terhadap akta asli
PPAT (minuta) dan warkahnya hanya dapat
dilakukan dengan izin khusus Ketua Pengadilan
Negeri setempat berdasarkan ketentuan Pasal 43
KUHAP.14
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat kekosongan norma berkaitan
dengan prosedur khusus dalam penegakan hukum
bagi seorang PPAT apabila ditinjau dari sudut
peraturan perundang-undangan terkait ke-PPAT-
an. Walaupun telah diatur dalam MoU dan
memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi
MoU tidak termasuk dalam tata urutan
perundang-undangan di Indonesia. Salah satu
konsekuensi logis dari prinsip negara hukum
adalah penerapan asas legalitas, dengan kata lain,
dalam unsur negara hukum Pancasila, asas
legalitas menjadi hal yang penting terutama
kaitannya dengan aspek perlindungan hukum bagi
PPAT yang sampai saat ini belum ada ketentuan
yang mengatur, karena perlindungan hukum harus
dimaknai sebagai perlindungan dengan
menggunakan sarana hukum atau perlindungan
yang diberikan oleh hukum, artinya pengaturan
mengenai dasar hukumnya harus jelas tertuang
dalam hukum positif.
14
Sjaifurrachman, 2011, Aspek
Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan
Akta, Mandar Maju, Bandung, hal. 236.
Perkembangan terkini telah menghentak
dunia Notaris, yakni Majelis Mahkamah
Konstitusi (MK), dengan Putusan MK No.
49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, telah
mengabulkan permohonan uji materiil (judicial
review) terhadap Pasal 66 ayat (1) UU No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan
dibatalkannya frasa “dengan persetujuan Majelis
Pengawas Daerah” Pasal 66 ayat (1) UUJN
berubah bunyi menjadi : Untuk kepentingan
proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim berwenang (tanpa izin MPD):
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta
dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol
Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir
dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya atau
Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.
Sehingga dengan dikeluarkannya putusan
MK tersebut otomatis ketentuan perlindungan
hukum bagi Notaris khususnya dalam proses
pidana dan perdata kembali seperti sebelum
berlakunya UUJN atau pada saat berlakunya
Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.
1860:3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN).
Dimana dalam proses peradilan guna mengambil
dokumen dalam penyimpanan Notaris dan
memanggil Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-
dokumen yang dibuatnya dalam kedudukan
sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa, tidak
perlu meminta persetujuan MPD.
Putusan MK ini jelas berimplikasi pula
kepada jabatan PPAT, karena dengan dicabutnya
beberapa frasa dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN
otomatis MoU atau nota kesepahaman antara
POLRI-INI-IPPAT menjadi berubah juga.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 17
Selanjutnya sampai sejauh mana peraturan
perundang-undangan terkait ke-PPAT-an
mengatur mengenai perlindungan hukum bagi
PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya,
disamping ketentuan yang telah otomatis berubah
sebagaimana penjelasan diatas.
Penulis berpendapat walaupun frasa
tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat maka dalam rangka pemanggilan
terhadap Notaris maupun PPAT dalam suatu
perkara, walaupun tidak diperlukan adanya
persetujuan dari MPD (karena frasa ini sudah
dihapus) akan tetapi secara prosedur etik,
pemanggilan tersebut minimal atau tetap harus
diberitahukan kepada MPD sebagai pengawas
Notaris dan Majelis Kehormatan Daerah sebagai
pengawas PPAT, dan/atau apabila pihak
kepolisian dalam hal ini penyidik hendak meminta
keterangan dari Notaris/PPAT, akan lebih bijak
pihak penyidik yang datang ke kantor. Di sisi lain
menjadi kewajiban formal dan terstruktur dari INI
dan/atau IPPAT untuk mendampingi atau
melakukan pendampingan kepada Notaris/PPAT
yang dipanggil untuk memenuhi panggilan
penyidik, kejaksaan dan hakim. Berkaitan dengan
hal tersebut hendaknya segera dikeluarkan
Peraturan Menteri Hukum dan Ham perihal
pemanggilan Notaris dan/atau Peraturan Kepala
BPN RI perihal pemanggilan PPAT sehubungan
dengan adanya Putusan MK tersebut agar tidak
terjadi kesemena-menaan dalam pemanggilan
Notaris/PPAT.
5.2 Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar PPAT
Berdasarkan uraian di atas Penulis
berpendapat bahwa, walaupun “hak istimewa”
yang pertama yakni perlindungan hukum berupa
keharusan bagi penyidik, penuntut umum dan
hakim memperoleh persetujuan Majelis Pengawas
Daerah untuk memanggil PPAT dalam rangka
proses peradilan telah dicabut berdasarkan
Putusan MK RI Nomor 49/PUU-X/201215
,
tidaklah menghilangkan hak istimewa lainnya
yakni “Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar”,
sehingga Jabatan PPAT sebagai Pajabat Umum
dalam menjalankan jabatannya tetap terlindungi.
Secara implisit hak istimewa PPAT
diatur karena berkaitan dengan rahasia jabatannya
sebagai pejabat umum. Apabila dikaitkan dengan
hukum, maka tindakan membocorkan rahasia,
secara materil didasarkan pada Pasal 322 ayat (1)
KUHP dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata dan
bahkan apabila terdapat unsur pencemaran nama
baik dapat dilihat pada pasal-pasal perbuatan
melanggar hukum dalam KUHPerdata.
Pasal 322 ayat (1) KUHP :
“Barangsiapa dengan sengaja membuka suatu
rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan
atau pekerjaannya yang sekarang maupun yang
dahulu, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau denda paling banyak
sembilan ribu rupiah.”
Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata :
“Segala siapa yang karena kedudukannya,
pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-
undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu,
namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal
yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya
sebagai demikian.”
Sedangkan secara formil atau hukum
acara, didasarkan pada Pasal 170 KUHAP untuk
proses acara pidana, dan dalam Pasal 277 ayat (1)
HIR Jo. 146 ayat (1) angka 3 HIR untuk proses
acara perdata.
Pasal 170 KUHAP :
(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat
martabat atau jabatannya diwajibkan
menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan
dari kewajiban untuk memberi keterangan
sebagai saksi, yaitu tentang hal yang
dipercayakan kepada mereka.
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala
alasan untuk permintaan tersebut.
Pasal 277 ayat (1) HIR :
“Orang yang karena martabatnya, pekerjaan
atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan
rahasia, boleh minta dibebaskan daripada
15
Berdasarkan Putusan MK ini otomatis
MoU antara POLRI dengan IPPAT, yang
memberlakukan ketentuan Pasal 66 ayat (1)
UUJN bagi Jabatan PPAT juga berubah.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 18
memberi penyaksian; akan tetapi hanya tentang
hal itu saja, yang diberitahukan kepadanya
karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya
itu.”
Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR :
“Sekalian orang yang karena martabatnya,
pekerjaan atau jabatan syah diwajibkan
menyimpan rahasia akan tetapi hanya semata-
mata mengenai pengetahuan yang diserahkan
kepadanya karena martabat, pekerjaan atau
jabatannya itu.”
Sebagaimana uraian di atas, PPAT
sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga
rahasia yang dipercayakan orang yang
menggunakan jasa PPAT kepadanya. Sama
halnya dengan profesi Notaris maupun Advokat,
rahasia jabatan tidak sekedar merupakan
ketentuan etik, melainkan pula menjadi asas
hukum yang memberikan Kewajiban Ingkar
(Verschoningsplicht) dan Hak Ingkar
(Verschoningsrecht). Hal ini bermakna disamping
berkewajiban untuk merahasiakan isi akta baik
karena hukum formal (Pasal 170 KUHAP dan
Pasal 277 ayat (1) HIR Jo. 146 ayat (1) angka 3
HIR) maupun hukum materil (Pasal 322 ayat (1)
KUHP dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata),
juga untuk menjaga martabatnya sebagai seorang
Notaris/PPAT yang tentunya menjadi tidak
dipercaya, apabila Notaris/PPAT tersebut tidak
bisa menjaga rahasia kliennya.
Hak untuk tidak membuka rahasia
didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh
klien untuk kepentingan suatu jabatan. Menjadi
kewajiban untuk tidak membuka rahasia
didasarkan pada sumpah jabatan dan Kode Etik
IPPAT yang memberikan sanksi bagi PPAT yang
membuka rahasia. Dalam hukum pidana Pasal 322
ayat (1) KUHP memberikan ancaman pemidanaan
bagi wajib penyimpan rahasia yang membuka
rahasia pekerjaan atau jabatannya. Sedangkan
dalam kedudukan sebagai saksi pada perkara
perdata PPAT dapat minta dibebaskan dari
kewajibannya untuk memberikan kesaksian,
karena jabatannya menurut undang-undang
diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909
ayat (3) KUHPerdata).
1. Pelaksanaan Kewajiban Ingkar
(Verschoningsplicht) oleh PPAT.
Telah menjadi suatu asas hukum publik,
bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat
menjalankan jabatannya dengan sah, harus
terlebih dahulu mengangkat sumpah atau diambil
sumpahnya, selama hal ini belum dilakukan, maka
jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan
dengan sah. Untuk jabatan PPAT asas ini tertuang
dalam Pasal 15 ayat (1) PJPPAT, yang
menentukan, bahwa: “Sebelum menjalankan
jabatannya PPAT dan PPAT Sementara wajib
mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya di daerah kerja PPAT yang
bersangkutan”. Selanjutnya mengenai isi sumpah
jabatan PPAT dan PPAT Sementara, berdasarkan
ketentuan Pasal 17 ayat (2) PJPPAT, diatur
didalam peraturan pelaksana PJPPAT yakni pada
Pasal 34 ayat (1) Perka BPN 1/2006.
Pengaturan mengenai sumpah jabatan
tersebut merupakan instrumen Kewajiban Ingkar
(Verschoningsplicht) bagi PPAT, hal ini
ditegaskan pula dalam Kode Etik IPPAT, dimana
seorang PPAT dalam rangka melaksanakan tugas
jabatan ataupun dalam kehidupan sehari-hari
diwajibkan “senantiasa menjunjung tinggi dasar
negara dan hukum yang berlaku serta bertindak
sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik
dan berbahasa Indonesia secara baik dan benar”
(Pasal 3 huruf b Kode Etik IPPAT).
Jadi ketika PPAT dipanggil atau diminta
oleh Penyidik untuk bersaksi atau memberikan
keterangan berkaitan dengan akta yang dibuat
dihadapannya, adalah menjadi kewajiban hukum
PPAT untuk memenuhi hal tersebut. Kemudian
Kewajiban Ingkar (Verschoningsplicht) dapat
dipergunakan oleh PPAT pada saat memenuhi
panggilan penyidik, PPAT dapat menyatakan
akan mengunakan Kewajiban Ingkarnya

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 19
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1)
PJPPAT Jo. Pasal 34 ayat (1) Perka BPN 1/2006.
Pernyataan menggunakan Kewajiban Ingkar
tersebut akan dicatat dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP). Pernyataan menggunakan
kewajiban ingkar tersebut semata-mata
menjalankan perintah PJPPAT, sehingga tidak
perlu disertai alasan apapun.
2. Pelaksanaan Hak Ingkar
(Verschoningsrecht) oleh PPAT
Kewajiban untuk memenuhi panggilan
sebagai saksi ditegaskan dalam Pasal 244 KUHP
Jo. 522 KUHP, dimana terdapat ancaman pidana
apabila tidak dipenuhi sehingga PPAT wajib
memenuhi panggilan tersebut. Berkaitan dengan
hal tersebut, Penulis berpendapat ketika PPAT
dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan
dengan akta yang dibuat dihadapannya atau
berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan PPAT
berdasarkan peraturan perundang-undangan
terkait ke-PPAT-an, maka PPAT wajib memenuhi
panggilan tersebut, dan ketika panggilan tersebut
dipenuhi, seorang PPAT bisa mempergunakan
Hak Ingkar (Verschoningsrecht)-nya dengan
terlebih dahulu membuat surat permohonan
kepada hakim yang mengadili/memeriksa perkara
tersebut, bahwa PPAT akan menggunakan Hak
Ingkarnya. Hakim yang memeriksa perkara yang
bersangkutan akan menetapkan apakah
mengabulkan atau menolak permohonan PPAT
tersebut. Jika hakim mengabulkan permohonan
PPAT tersebut, maka PPAT tidak perlu bersaksi.
Tapi jika hakim menolak permohonan PPAT
tersebut, maka PPAT perlu bersaksi, dan atas
keterangan PPAT sebagai saksi di Pengadilan,
jika ada yang dirugikan atas keterangan PPAT,
maka PPAT tidak dapat dituntut berdasarkan
Pasal 322 ayat (1) KUHP karena PPAT
melakukannya atas perintah hakim.
Berpijak pada uraian diatas keberadaan
PPAT selama ini dimata hukum seolah-olah tidak
ada bedanya dengan masyarakat umum.
Seringkali terjadi persamaan perlakuan terhadap
pemeriksaan PPAT sebagai saksi baik dalam
tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan,
PPAT diposisikan seolah-olah sebagai warga
negara masyarakat umumnya yang tidak memiliki
rahasia jabatan yang wajib dirahasiakannya.
Menurut Johan Rabe “in the constitutional sense
equality does not mean that the law must treat
everyone equally and justice require differential
treatment when there are relevant or justified
grounds for that treatment. Equality in
constitutional sense therefore means that those
who are similarly situated, or which reasons are
just reasons.”16
Artinya dalam konstitusi
kesetaraan tidak berarti bahwa hukum harus
memperlakukan semua orang sama dan keadilan
memerlukan perlakuan yang berbeda ketika ada
alasan yang relevan atau dibenarkan untuk
perlakuan itu.
Di sisi lain, Notaris/PPAT merupakan
profesi hukum dan dengan demikian profesi
Notaris/PPAT adalah suatu profesi mulia (nobile
officium), disebut nobile officium dikarenakan
profesi notaris sangat erat kaitannya dengan
kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh dan/atau
dihadapan Notaris/PPAT dapat menjadi alas
hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban
seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris/PPAT
dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang
atau terbebaninya seseorang atas suatu
kewajiban.17
(garis bawah dari Penulis)
Berpijak pada pandangan tersebut,
Penulis berpendapat bahwa Notaris maupun
PPAT yang dalam pasal 1868 KUHPerdata,
dikenal sebagai Pejabat Umum (Openbare
16
Johan Rabe, 2001, Equality, Affirmative
Action and Justice, Hamburg Univ, Germany, p.
21.
17
Anshori , Abdul
Ghofur , 2009, Lembaga
Kenotar iatan Indonesia
(Perspekti f Hukum dan Etika) ,
UII Press , Yogyakar ta , ha l . 25.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 20
Ambtenaren) dan telah dijabarkan dalam UUJN
dan PJPPAT adalah orang yang dikecualikan dari
prinsip equality before the law, dan memenuhi
persyaratan-persyaratan tertentu yang dibuat
sesuai standart pemenuhan nilai-nilai sebagai
orang yang terhormat (nobile person) atau profesi
terhormat dan luhur (officium nobile), sebaliknya
seorang Notaris/PPAT yang tidak sedang dalam
kapasitas sebagai Notaris/PPAT adalah sama
dengan orang pada umumnya, yang tunduk pada
prinsip equality before the law.
Dengan demikian berpijak pada
diakuinya suatu imunitas hukum berupa Hak
Ingkar (Verschoningsrecht) dan Kewajiban Ingkar
(Verschoningsplicht), serta PPAT dikualifikasikan
sebagai Pejabat Umum yang juga termasuk dalam
kategori orang yang terhormat, jabatan terhormat
(nobile person, nobile officium), maka sudah
sepantasnya urgensi pengaturan secara normatif
mengenai prosedur khusus dalam penegakan
hukum (pemanggilan dan pemeriksaan pada
proses penyidikan, penuntutan dan persidangan)
terhadap seorang PPAT segera diatur kembali
dengan masukan pengaturan tersebut di atur
bukan dalam suatu MoU tapi dalam suatu
ketentuan normatif.
VI. Simpulan dan Saran
6.1 Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual
beli tanah yang dibuatnya mengandung cacat
hukum yang dikarenakan adanya kesengajaan
maupun kelalaian dalam proses pembuatan
akta PPAT akan berakibat hukum terhadap
akta jual beli sekaligus terhadap PPAT
bersangkutan berupa:
- Penyimpangan terhadap Syarat Formil
Dengan berpijak pada syarat-syarat
terpenuhinya akta otentik yang diatur pada
Pasal 1868 KUHPerdata dikaitkan dengan
ketentuan Pasal 95-102 Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, maka apabila
ketentuan formil tersebut dilanggar, akan
menyebabkan terdegradasinya kekuatan
bukti sempurna dari akta jual beli tersebut
menjadi kekuatan bukti akta dibawah
tangan apabila berdasarkan putusan
Pengadilan menyatakan adanya salah satu
atau lebih pelanggaran yang dilakukan.
- Penyimpangan terhadap Syarat Materil
Dengan berpijak pada syarat-syarat
perjanjian yang diatur pada Pasal 1320
KUHPerdata dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, maka syarat materil dari tata cara
pembuatan akta PPAT harus memenuhi
syarat-syarat subyektif (subyek hak atau
para pihak yang menghadap atau
komparan) dan syarat obyektif (obyek hak
yang dialihkan) dalam pembuatan akta
PPAT. Apabila syarat subyektif dan
obyektif dilanggar, maka akta PPAT
tersebut dapat dimintai pembatalan
dan/atau dinyatakan batal demi hukum.
Pertanggungjawaban PPAT terhadap akta jual
beli tanah yang dibuatnya mengandung cacat
hukum yang didasari adanya penyimpangan
terhadap syarat formil dan syarat materil dari
prosedur atau tata cara pembuatan akta PPAT
dapat dikenai sanksi :
- Sanksi Administratif : PPAT yang
bersangkutan dapat dikenai sanksi
pemberhentian dengan tidak hormat dari
jabatannya dan pengenaan denda
administratif karena telah melanggar
larangan atau melalaikan kewajibannya.
- Sanksi Perdata : Apabila akta PPAT yang
terdegradasi menjadi akta dibawah tangan,

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 21
atau dinyatakan batal dan/atau batal demi
hukum berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
dikategorikan sebagai perbuatan
melanggar hukum yang menimbulkan
suatu kerugian bagi para pihak, maka
PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban
dalam bentuk penggantian biaya, ganti
rugi dan bunga.
- Sanksi Pidana : Sepanjang tindakan PPAT
bersangkutan terbukti secara sengaja dan
direncanakan baik sendiri maupun secara
bersama-sama dengan salah satu atau para
pihak melakukan pembuatan akta yang
dibuatnya dijadikan suatu alat melakukan
suatu tindak pidana, maka terhadap PPAT
bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana
sesuai peraturan yang berlaku.
2. Secara normatif Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta
peraturan perundang-undangan terkait ke-
PPAT-an lainnya tidak mengatur
perlindungan hukum kepada PPAT dalam
melaksanakan tugas jabatannya. Secara
eksplisit pengaturan mengenai perlindungan
hukum bagi PPAT diatur pada Nota
Kesepahaman antara POLRI dengan IPPAT
No. Pol. : B/1055/V/2006 dan Nomor :
05/PP-IPPAT/V/2006, yang menentukan
bahwa Pasal 66 UUJN diberlakukan pula
terhadap PPAT. Namun berdasarkan Putusan
MK RI Nomor 49/PUU-X/2012 prosedur
khusus dalam mekanisme pemanggilan dan
penyitaan protokol akta Notaris/PPAT tidak
perlu meminta persetujuan Majelis Pengawas
Daerah, artinya hak istimewa tersebut telah
dicabut. Secara implisit hak istimewa lainnya
yang dimiliki oleh PPAT adalah Kewajiban
Ingkar (Verschoningsplicht) dan Hak Ingkar
(Verschoningrecht) yang diakui sebagai suatu
imunitas hukum untuk kewajiban memberi
keterangan sebagai saksi di tingkat
penyidikan, penuntutan dan persidangan baik
perkara perdata maupun pidana bagi jabatan-
jabatan tertentu, salah satunya PPAT,
berdasarkan :
Secara Materil :
- Pasal 17 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Juncto Pasal 34
ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998;
- Pasal 322 ayat (1) KUHP;
- Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata.
Secara Formil :
- Pasal 170 KUHAP dalam proses acara
pidana;
- Pasal 277 ayat (1) HIR Jo. 146 ayat (1)
angka 3 HIR dalam proses acara perdata.
6.2 Saran
1. Untuk PPAT
Sebagai PPAT dalam melakukan pembuatan
akta jual beli hendaknya berpijak pada
ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait ke-PPAT-an yang ada, karena akta
otentik yang dibuatnya akan mempengaruhi
kepastian hukum peralihan hak atas tanah
sehingga dapat mengurangi timbulnya
permasalahan dan konflik pertanahan yang
disebabkan dari alat bukti hak atas tanah yang
cacat hukum, baik secara yuridis maupun
teknis dan administratif. PPAT hendaknya
lebih memperhatikan dan memahami
ketentuan-ketentuan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas jabatannya agar terhindar
dari sanksi pemberhentian, denda
administratif, dan gugatan ganti rugi dari para
pihak maupun tuntutan pidana. Disamping itu
PPAT dalam menjalankan tugasnya harus
selalu berlandaskan pada moralitas dan
integritas yang tinggi terhadap profesi dan
jabatannya selaku PPAT.
Untuk Pemerintah dan DPR

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 22
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan akta
PPAT lebih menitikberatkan pada unsur
kepastian hukum, akan tetapi perkembangan
dalam praktek terkadang menerobos aturan-
aturan tersebut yang apabila tidak dipenuhi
maka akan banyak kepentingan klien yang
tidak bisa dilayani. Sehingga perlu kiranya
dinamika-dinamika yang berkembang dalam
proses pembuatan akta PPAT diperhatikan
dan ditampung untuk dijadikan pertimbangan
dalam pengaturan secara normatif
kedepannya. Sehingga unsur kepastian
hukum dalam pembuatan akta PPAT dapat
terpenuhi dan sebaliknya unsur pelayanan
terhadap masyarakat pengguna jasa PPAT
juga dapat terakomodasi dengan baik.
2. Diharapkan peraturan perundang-undangan
yang akan berlaku kemudian (ius
constituendum) dibentuk suatu unifikasi
hukum mengenai pengaturan PPAT di
Indonesia dalam bentuk Undang-Undang
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, baik itu
yang berkaitan dengan tata cara pembuatan
akta PPAT dan pengaturan mengenai
perlindungan hukum bagi PPAT dalam
melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat
Umum. Berpijak pada diakuinya hak ingkar
sebagai suatu kewajiban hukum sekaligus
imunitas hukum, menunjukkan PPAT selaku
Pejabat Umum memiliki hak istimewa
dibanding masyarakat biasa, maka perlu
dipertimbangkan pengaturan mekanisme
khusus dalam penegakan hukum terhadap
PPAT. Untuk tindakan jangka pendek demi
menjaga harkat dan martabat Jabatan PPAT
(juga Notaris) diharapkan prosedur
pemanggilan terhadap PPAT (juga Notaris)
minimal ada pemberitahuan kepada Majelis
Kehormatan Daerah (MPD bagi Jabatan
Notaris) melalui suatu peraturan organis.
Sedangkan prosedur pengambilan atau
penyitaan protokol PPAT kembali pada
aturan Pasal 43 KUHAP, yakni harus dengan
izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
terlebih dahulu.
VII. Daftar Bacaan
A. Buku-buku
Adjie, Habib, 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika), UII Press,
Yogyakarta.
Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Rabe, Johan, 2001, Equality, Affirmative Action and Justice, Hamburg Univ, Germany.
Santoso, Urip, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju,
Bandung.
Soemitro, Ronny Hamitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sutedi, Adrian, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet. ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Artikel Majalah

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 23
Setiawan, Wawan, 1996, “Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan
Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional”, Media Notariat Nomor 38-
41, Jan-Apr-Jul-Okt 1996.
C. Makalah
Setiawan, Wawan, 1991, ”Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta”, Makalah dalam seminar
nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro, Semarang.
D. Internet
Oyong, Bambang S., 2013, “Peraturan KBPN Nomor 8 Tahun 2012 Dalam Kajian Tugas Pekerjaan
PPAT”, diakses pada tanggal 18 Februari 2013, URL :
http://bambangoyong.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
Tjahjono, Jusuf Patrianto, 2008, “Apakah Notaris Tunduk Pada Prinsip Equality Before The Law?”,
diakses pada tanggal 15 November 2012, URL : http://notarissby.blogspot.com/2008/03/apakah-
notaris-tunduk-pada-prinsip.html
E. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) (Staatsblad Tahun
1941 Nomor 44).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
1017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746).
Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta.
*****

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 24
STUDY OF LEGAL OWNERSHIP OF LAND juridical PROPERTY BY FOREIGN
CITIZENS THROUGH THE "NOMINEE AGREEMENT"WHICH WAS MADE BEFORE
THE NOTARY
Oleh:
Carina Pariska Pribadi*,I Ketut Rai Setiabudhi **, Ida Bagus Wyasa Putra***
Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
e-mail: [email protected]
ABSTRACT
Bali as a world tourism center not only draw attention to foreign tourists , but also for foreign who
want to own land and reside in bali. National land laws recognize the various kinds of land rights can be
held by legal subjects. ownership of land rights is determined by the legal subject whether he is qualified
to have a certain right to land or not. Freehold rights are the rights to the fullest and strongest owned by
the subjects of law, only Indonesian people can have freehold rights as set in Article 26, paragraph 2 of
Law No. 5 of 1960 concerning agrarian subjects, for foreign given rights in the form of land use rights. in
practice, foreign desire to own property is very high, therefore they make some sort of agreement with
Indonesian citizen by the name of a nominee agreement which aims to foreigners can borrow the
Indonesian name for the certificate included in the property purchased by foreign.
This thesis aims to determine how the free hold rights of land owner ship arrangements by foreign
through a nominee agreement and fulfillment of achievements like Which nominee agreements if one party
(in particular theIndonesianparty) died. methods used in this study is a normative juridical method, which
is done in-depthstudyof Article 26, paragraph 2 of Law No. 5 of 1960 concern in agrarian subjects. And
discuss the nominee agreement looked from its validity of the terms in the agreement asset in Article 1320
of the Civil Code, as well as case studies are also presented concerning the fulfillment of the achievements
in the nominee agreement.
Nominee agreement ineligible validity agreement asset in Article 1320 of the Civil Codein
particular causesa lawful requirement, because the actual causes of the nominee agreement is to violate
Article 26, paragraph 2 of Law No. 5 of 1960 concern ing agrarian subjects, but in the agrarian law not
expressly on nominee ownership therefore the judge to cancel the agreement should be doing first
interpretation. Nominee agreement is basically a natural agreement, in the sense of achievement
fulfillment by the parties based on the moral attitude and good faith of each party. Achievement in terms
of the fulfillment of an Indonesian citizen died can be done by negotiation with the heirs of the Indonesia
if foreigners want to keep the land if he appointed heir of the dead as a nominee or a nominee to replace
with others, or foreigners sell the land to act as the power of the dead to sell the land.
Key Words : Nominee Agreement, Free hold, Foreigner
*Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2011/2012
**Pembimbing I
***Pembimbing II
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada masa sebelum Kemerdekaan
Indonesia penduduk Indonesia dibagi menjadi 3
(tiga) golongan penduduk berdasarkan Pasal 131
(seratus tiga puluh satu) Indische Staatsregerling
(Is) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
1926 yakni Eropa, Bumi Putera dan Timur Asing.
Setelah kemerdekaan Indonesia maka
penggolongan penduduk sebagaimana diuraikan
di atas tidak berlaku lagi. Dengan
diundangkannya Undang-Undang nomor 12 tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, maka penggolongan penduduk dibagi
menjadi 2 (dua) yakni warga negara Indonesia
dan warga negara asing. Konsekuensi dari
pembagian ini salah satunya ada pada hak dan
kewajiban serta hukum yang berlaku bagi warga
Negara Indonesia dan warga negara asing.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 25
Hukum yang berlaku bagi warga negara
asing tidaklah berbeda dengan hukum yang
berlaku bagi warga Negara Indonesia, Namun
terdapat beberapa ketentuan dimana hak dan
kewajiban warga negara asing berbeda dengan
warga Negara Indonesia yakni dalam bidang
hukum tanah / agraria. Perbedaan hak yang paling
jelas terlihat adalah dalam hal penguasaan tanah,
dimana Warga negara asing hanya diperbolehkan
mempunyai Hak Pakai atas tanah, karena prinsip
yang dianut oleh Undang Undang Pokok Agraria
adalah prinsip Nasionalitas. Hanya warga Negara
Indonesia yang dapat mempunyai hubungan
sepenuhnya dengan tanah sebagai bagian dari
Bumi dalam Frasa yang termuat dalam Pasal 33
Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Hubungan
sepenuhnya sebagaimana dimaksud di atas adalah
dalam wujud Hak Milik.
Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1)
Undang Undang Pokok Agraria
“hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Hanya
Warga Negara Indonesia dan badan hukum
tertentu saja yang dapat memiliki Hak Milik atas
tanah sedangkan bagi Warga negara asing dan
Badan Hukum Asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak
Pakai.1 Sebagaimana diatur dalam Undang
Undang Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1) “Hanya
warga negara Indonesia dapat mempunyai hak
milik atas tanah” dan diperkuat juga dengan Pasal
26 ayat (2) UUPA, yakni :
Setiap jual beli, penukaran, penghibahan,
pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsung
memindahkan hak milik kepada orang
asing, kepada seorang warga negara
yang disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing atau kepada
suatu badan hukum, kecuali yang
1Maria S.W. Sumardjono, 2007, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan, Kompas, hal.1.
ditetapkan oleh Pemerintah termaksud
dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal
Bali sebagai salah satu destinasi wisata
dunia tidak hanya memiliki daya tarik dari segi
pariwisata saja melainkan dari segi bisnis dan
investasi. Banyak warga negara asing yang
membangun usaha di Bali bahkan bertempat
tinggal di Bali, namun tidak sedikit pula yang
melakukan investasi dalam bentuk tanah
mengingat peningkatan harga tanah di Bali yang
mencapai 50% (lima puluh persen) pertahunnya.
Oleh karena itulah banyak warga negara asing
yang menggunakan perjanjian nominee untuk
mensiasati larangan kepemilikan hak atas tanah
oleh orang asing.
Nominee yang dimaksud dalam
penulisan tesis ini adalah warga Negara Indonesia
yang namanya dipergunakan atau dipinjam pada
Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh
warga negara asing juga memberi kuasa penuh
(mutlak) kepada warga negara asing untuk
melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan
baik tindakan pengurusan maupun pemilikan atas
tanah tersebut. Perjanjian Perjanjian nominee
dituangkan dalam perjanjian yang sepintas lalu
keliatan tidak menyalahi peraturan perundang
undangan, tetapi isinya secara tidak langsung
memindahkan kepemilikan tanah tersebut kepada
warga negara asing yang bertentangan dengan
undang undang. Adapun macam perjanjiannya
adalah sebagai berikut :
1. Perjanjian Induk yang terdiri dari
Perjanjian Tanah (Land Agreement) dan
Surat Kuasa;
2. Perjanjian Opsi;
3. Perjanjian Sewa Menyewa (Lease
Agreement);
4. Kuasa Menjual (Power of Attorney to
sell);
5. Hibah Wasiat; dan

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 26
6. Surat Pernyataan ahli Waris2
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah
diuraikan di atas dapat dirumuskan
Masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan kepemilikan
tanah oleh orang asing yang dibuat
melalui Perjanjian Nominee dihadapan
Notaris?
2. Bagaimanakah status hukum
“perjanjian nominee” apabila salah satu
pihak meninggal dunia?
1.3. Landasan Teori
1. Konsep Hak
Dalam hukum seseorang yang
mempunyai hak milik atas sesuatu benda
kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari
benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual,
digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan. Izin
atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut
“Hak” atau “Wewenang”. Jadi pemilik benda itu
berhak untuk mengasingkan benda tersebut.3
2. Konsep Kepemilikan
Berbeda dengan penguasaan, maka
pemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih
jelas dan pasti. Konsep pemilikan juga
menunjukkan hubungan antara seseorang dengan
obyek yang menjadi sasaran pemilikan. Namun
berbeda dengan penguasaan yang lebih bersifat
faktual, maka pemilikan terdiri dari suatu
kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat
digolongkan ke dalam ius in rem, karena berlaku
terhadap semua orang, berbeda dengan ius
personam yang hanya berlaku terhadap orang-
orang tertentu.
3. Konsep Penguasaan Hak Atas Tanah
2Salim , 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdata, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 25. 3C.S.T. Kansil, 1979, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. Kedua, hal. 119.
Menurut Budi Harsono dalam bukunya
Hukum Agraria Indonesia bahwa pengertian
“Penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga
dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan
beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak
yang dilindungi oleh hukum dan umumnya
memberi kewenangan kepada pemegang hak
untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.
Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun
memberi kewenangan untuk menguasai tanah
yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya
penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.
Konsep hak, konsep kepemilikan dan
konsep penguasaan hak atas tanah digunakan
sebagai pisau analisis untuk membahas
permasalahan pertama khususnya untuk
membahas kepemilikan tanah oleh warga negara
Indonesia yang diikat dengan perjanjian nominee
oleh warga asing
4. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas Kebebasan Berkontrak adalah suatu
asas hukum penting dengan berlakunya kontrak
yang mengandung pengertian bahwa para pihak
bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang
sudah ada pengaturannya dan bebas menetukan isi
kontrak Namun kebebasan tersebut tidak mutlak
karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh
bertentangan dengan Undang Undang dan
Ketertiban Umum dan kesusilaan.4
5. Asas Konsesualitas
Konsensuil secara sederhana diartikan
sebagai kesepakatan, dengan tercapainya
kesepakatan antara para pihak lahirlah kontrak
meskipun kontrak pada saat itu belum
dilaksanakan. Hal ini berarti juga bahwa dengan
tercapinya kesepakatan oleh para pihak
4PT. Asiamaya Dotcom, Kontrak, Indonesia Menara Imperium, Jl.HR.Rasuna Said, Kav 1A, Jakarta selatan, Email:[email protected], terakhir diakses tanggal 2 April 2007, hal 1.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 27
melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang
membuatnya (atau dengan kata lain perjanjian itu
bersifat obligatoir). Asas kebebasan berkontrak
dan Asas konsensualitas digunakan sebagai pisau
analisa untuk permasalahan pertama dan kedua
yakni untuk membahas keabsahan perjanjian
nominee dan perikatan alamiah pada pemenuhan
prestasi dalam perjanjian nominee.
6. Teori Kedudukan
Penegak hukum mempunyai kedudukan
(status) dan peranan (role). Kedudukan (status)
merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-
hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua
unsur tersebut merupakan peranan (role). Suatu
hak merupakan wewenang untuk berbuat atau
tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban
atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin
dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya
dari penegak hukum yang berasal dari dirinya
sendiri atau dari lingkungan, yaitu:
a) Keterdaulatan batasan kemampuan untuk
menempatkan diri dalam peranan pihak
lain dengan siapa dia berinteraksi;
b) tingkat aspiaasi yang relatif belum tinggi;
c) kegairahan yang sangat terbatas untuk
memikirkan masa depan, sehingga sulit
sekali untuk membuat suatu proyeksi;
d) belum adanya kemampuan untuk menunda
pemuasan suatu kebutuhan tertentu,
terutama kebutuhan material;
e) kurangnya daya inovatif yang sebenarnya
merupakan pasangan konservatisme. 5
5Soerjono Soekanto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada,Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I), hal. 30.
7. Teori Kedaulatan Negara
Negara adalah suatu organisasi
kekuasaan. Organisasi tersebut merupakan tata
kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang
menggambarkan hubungan, pembagian tugas, dan
kewajiban alat-alat perlengkapan negara sebagai
suatu kesatuan untuk mencapai tujuan negara.
Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan lancar
maka negara harus memiliki kekuasaan.6 Dengan
adanya kekuasaaan negara memiliki kekuatan
(power) untuk mengatur masyarakat serta alat-alat
perlengkapan negara demi tercapainya tujuan
negara. Teori kedaulatan negara dan teori
kedudukan merupakan norma dasar yang
digunakan sebagai acuan penggunaan undang-
undang sebagai dasar pembahasan masalah
pertama dan kedua.
1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan penulisan ini adalah untuk
mengetahui secara yuridis mengenai status warga
negara asing yang memiliki tanah di Indonesia
dengan menggunakan perjanjian nominee.
1.4.2 Tujuan khusus.
1 Untuk mengetahui Status Hukum dari
“Perjanjian Nomine” itu sendiri apabila
si Warga Negara Indonesia meninggal
dunia.
2 Untuk mengetahui kekuatan mengikat
dari Perjanjian Nominee terhadap ahli
waris dari Warga Negara Indonesia yang
meninggal dunia.
II. METODE PENELITIAN
2.1 Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah
penelitian Hukum Normatif yakni membahas
mengenai Pasal 1320 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata yang dikaitkan dengan perjanjian
nominee itu sendiri, membahas mengenai
6Max Bolisabon et.al, 1992, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.111.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 28
ketentuan dalam Undang Undang Pokok Agraria
serta membandingkan pelaksanaan perjanjian
nominee dalam praktek.
2.2. Jenis Pendekatan
Pendekatan yang dipergunakan untuk
membahasan permasalahan dalam tulisan ini ini
adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan analisis konsep hukum
(analytical and conceptual approach) dan
dipergunakan pendekatan kasus (case approach).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Umum
3.1.1 Tinjauan umum tentang Perjanjian
Perjanjian merupakan Suatu peristiwa
dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua orang itu berjanji untuk
melaksanakan suatu hal.7 Pitlo menjelaskan
pengertian perikatan ”Perikatan adalah suatu
hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan
antara dua atau lebih atas dasar pihak yang satu
(kreditur) berhak atas suatu prestasi (debitur) dan
pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu
prestasi”8.
Pasal 1320 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata menguraikan” tentang syarat
syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu
perjanjian; Sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan, Suatu hal tertentu, suatu sebab yang
halal”
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya Jadi
sepakat dengan sendirinya mengandung
pemahaman bahwa kedua belah pihak
melakukan perjanjian dengan penuh
kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari
siapapun.
7Soebekti, 1989, Hukum Perjanjian, Cet.CV.IV.Pen.Internusa Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Soebekti II) hal 1 8R.Setiawan,1986, Pokok–pokok Hukum Perikatan, pen. Bina Cipta, Bandung,hal 2
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Dalam melakukan suatu perjanjian kedua
belah pihak harus cakap untuk itu, sedangkan
orang yang berada dibawah pengapuan,
dibawah umur, orang sakit jiwa tidak cakap
untuk membuat suatu perjanjian. Jadi jelas
diantara persyaratan tersebut harus dipenuhi
oleh para pihak, karena ada kondisi
seseorang menurut hukum dinyatakan tidak
cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum.
3. Suatu hal tertentu Suatu perjanjian yang
dibuat berdasarkan kesepakatan dengan
saling menguntungkan dan dalam perjanjian
keduabelah pihak menganggap baik
sehinggga tidak ada yang dirugikan.
4. Suatu sebab yang halal maksudnya yaitu apa
yang diperjanjikan itu harus bebas dari
unsur-unsur yang dianggap tidak benar bila
dipandang menurut hukum, agama maupun
norma-norma lainnya.
3.1.2 Tinjauan tentang hak atas tanah
Hak milik di atur dalam Pasal 20-27,
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (1)
dan Pasal 56 Undang Undang pokok Agraria.
Nama Hak Milik bukan nama asli Indonesia.
Tetapi sifat sifat hak menguasai tanah yang diberi
nama sebutan hak milik itu sudah dikenal dalam
hukum adat, yaitu sebagai hasil perkembangan
penguasaan dan pengusahaan atau penggunaan
sebagian tanah ulayat secara intensif dan terus
menerus oleh perseorangan warga masyarakat
hukum adalah pemegang hak ulayat9. Hak Milik
pada dasarnya hak yang hanya boleh dimiliki oleh
warga Negara Indonesia baik untuk tanah maupun
bangunan yang ada di atasnya. Kepemilikan Hak
Milik dengan jangka waktu tidak terbatas, dapat
beralih karena pewarisan dan dapat juga
dipindahkan kepada pihak lain. Menurut Pasal 20
Undang Undang Pokok Agraria “Hak Milik
adalah Hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh
9 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, hal. 286

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 29
yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 6, Hak milik
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”
Dari uraian pasal tersebut dapat penulis
simpulkan bahwa bunyi Pasal 20 berhubungan
dengan Pasal 6 dikatakan bahwa Hak Milik
adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan
mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi
social.
Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 - 43
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang
Undang Pokok Agraria hal-hal yang ditentukan di
dalam Undang Undang Pokok Agraria tersebut
kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.
Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria
menyebutkan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk
menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah
milik orang lain yang memberi wewenang dan
kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
3.2 Keabsahan dan Kekuatan Mengikat dari
Perjanjian Nominee
Menurut Pasal 1320 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata, sahnya suatu perjanjian
jika memenuhi 4 syarat, yakni tercapainya kata
sepakat antara para pihak, para pihak cakap untuk
melakukan / membuat perjanjian, adanya
obyek/sesuatu yang diperjanjikan dan kausa yang
halal. Berikut akan dibahas mengenai keabsahan
perjanjian nominee.
a. Sepakat antara para pihak.
b. Kecakapan dalam bertindak
c. Suatu hal tertentu
d. Sebab yang halal / Kausa yang halal.
Pada perjanjian nominee seolah-olah
obyek perjanjian itu memiliki kausa yang halal,
namun perjanjian ini sebenarnya digunakan untuk
menutupi kausa yang sebenarnya yakni
memindahkan penguasaan tanah secara materiil
dari tangan warga Negara Indonesia yang
namanya akan dicantumkan di sertifikat yang
menjadi obyek jual beli ke tangan warga negara
asing. Secara sepintas memang praktek nominee
ini tidak menyalahi peraturan namun lebih lanjut
dalam Undang Undang Pokok Agraria Pasal 26
ayat (2) menyatakan secara tegas bahwa :
Setiap jual beli, penukaran, penghibahan,
pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsungmemindahkan hak
milik kepada orang asing, kepada seorang
warganegara yang disamping kewarganegaraan
Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali
yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud
dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena
hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara,
dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung serta
semua pembayaran yang telah diterima oleh
pemilik tidak dapat dituntut kembali. (garis
bawah dari penulis).
Dari rumusan tersebut terlihat bahwa
orang asing dilarang keras untuk memiliki Hak
Milik atas tanah, namun dalam perjanjian
nominee nama yang tercantum hanyalah nama
warga Negara Indonesia dan karena tanah
termasuk benda tak bergerak maka peralihannya
harus dilakukan dengan balik nama dan dalam
kasus perjanjian nominee nama yang masuk
kedalam sertifikat tanah adalah warga Negara
Indonesia yang telah diikat dengan nominee, hal
ini lah yang menjadi kelemahan Pasal 26 ayat (2)
Undang Undang Pokok Agraria karena UUPA
tidak secara tegas mencantumkan larangan
kepemilikan secara nominee.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 30
Berdasarkan analisa pada Pasal 1320
Kitab Undang Undang hukum Perdata
sebagaimana diuraikan di atas, maka didapatkan
hasil bahwa perjanjian nominee batal demi
hukum, karena tidak memenuhi ketentuan “kausa
yang halal”. Karena dianggap melanggar
ketentuan mengenai subyek yang dapat memiliki
hak milik sebagaimana di atur dalam Undang
Undang Pokok Agraria. Namun apakah Pasal 26
Undang Undang Pokok Agraria memang
dilanggar oleh perjanjian Nominee tersebut.
Memang dalam hukum agraria, belum
dikeluarkan aturan yang secara tegas menyatakan
larangan untuk melakukan pembelian tanah
dengan cara semacam ini (melalui perjanjian
Nominee). Namun dalam hukum penanaman
modal, telah dikeluarkan larangan secara tegas
yakni terdapat dalam Undang-Undang No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU
25/07“).
UU 25/07 ini mengatur dalam Pasal 33
ayat (1) bahwa penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing yang melakukan
penanaman modal dalam bentuk perseroan
terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau
pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan
saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas
nama orang lain. Alasan dari adanya pelarangan
ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan
yang secara normatif dimiliki seseorang tetapi
secara materi atau substansi pemilik perseroan
tersebut adalah orang lain. Tujuan dibuatnya
perjanjian nominee adalah untuk menyiasati
ketentuan dalam peraturan perundang undangan
yang membatasi adanya bidang usaha yang
tertutup ataupun terbuka bagi asing dengan
persyaratan tertentu di bidang penanaman modal.
Berbicara mengenai aspek-aspek yang
mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian, maka
struktur nominee khusus dalam kepemilikan
saham ini menjadi struktur yang dilarang dengan
demikian segala bentuk perjanjian atau
pernyataan yang demikian adalah bertentangan
dengan hukum yang berlaku. Pasal 33 ayat (2)
UU 25/07 mengatur sanksi bahwa perjanjian
dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi
hukum. Dalam Pasal 26 maupun pasal lain dalam
Undang Undang Pokok Agraria tidak mengatur
larangan untuk memiliki tanah secara nominee
seperti yang di atur dalam Pasal 33 ayat (2) UU
25/07 sehingga disini terjadi kekosongan hukum.
Untuk dapatnya suatu perjanjian
nominee dibatalkan oleh hakim jika terjadi
sengketa maka perlu dilakukan penafsiran secara
acontrario oleh hakim karena terdapat
kekosongan hukum dalam Undang Undang Pokok
Agraria mengenai kepemilikan secara nominee.
Perjanjian nominee atas saham memiliki struktur
yang sama dengan perjanjian nominee untuk
tanah sehingga hakim memiliki dasar yang kuat
untuk menyatakan bahwa perjanjian ini batal
demi hukum.
3.3 Perbandingan kasus pemenuhan
prestasi dalam perjanjian nominee
Pemenuhan prestasi pada perjanjian
nominee tergantung pada itikad baik para pihak
yang terlibat. Sekuat dan serapi apapun perjanjian
nominee tersebut masih menyimpan potensi
wanprestasi yang tinggi karena sampai saat ini
belum diatur secara tegas mengenai pemilikan
tanah secara nominee. Dalam hukum perdata
dikenal suatu doktrin mengenai perikatan yang
bersifat alamiah, Perikatan alamiah adalah
perikatan yang tidak dapat dipaksakan
pemenuhannya melalui sarana hukum, namun
demikian apabila perikatan tersebut dipenuhi
secara sukarela, maka perikatan tersebut tetap
secara alamiah lahir dan mengikat tanpa
memerlukan sarana pemaksa (hukum).10
10http://strategihukum.net/ketika-perjanjian-nominee-berujung-pada-sengketa (tanggal akses 1 november 2013)

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 31
Perikatan alamiah dikenal juga dengan
perikatan moral, dari pengertian luas bahwa yang
dianggap perikatan alamiah ada 3, yaitu:
- Perikatan yang berdasarkan ketentuan
undang-undang atau kehendak para pihak
sejak semula tidak mempunyai hak
penuntutan, contoh pasal 1788 Kitab Undang
Undang Hukum Perdata seperti utang yang
timbul karena perjudian.
- Perikatan yang berasal dari moral yang
sifatnya mendesak, contoh orang yang
menemukan dompet seseorang kemudian
mengembalikan- nya, tidak bisa menuntut si
pemilik dompet untuk membayar kepadanya
sejumlah uang.
- Perikatan yang semula perikatan perdata
kemudian karena verjaring menjadi perikatan
moral. Contoh: pasal 1967 sampai dengan
1975 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata11
Penulis memiliki pendapat bahwa
penegakan hak dan kewajiban yang dibangun
dalam perjanjian nominee tidaklah bisa
dipaksakan melalui hukum. Suatu hal yang
bertentangan dengan hukum pastilah telah
menciderai syarat perjanjian yang sah secara
obyektif. Namun kesukarelaan para pihak untuk
mengikatkan diri dalam perjanijan nominee-lah
yang melahirkan suatu perikatan alamiah tersebut.
Pertanyaan yang patut untuk dibahas adalah,
bisakah perjanjian nominee yang secara hukum
batal demi hukum dapat dilaksanakan. Terdapat
dua pandangan mengenai hal tersebut. Pertama
11Riduan Syahrani, 2004,Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, hal 203.
secara hukum perjanjian tersebut tidak dapat
dipaksakan atau ditegakkan keberlakuannya,
karena bertentangan dengan ketertiban umum
yang tertulis dan tertuang di dalam hukum positif.
Kedua perjanjian yang cacat hukum tadi tetap
dapat mengikat kedua belah pihak, dalam hal
kedua belah pihak sukarela berkomitmen dengan
ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam
perjanjian nominee tersebut.12
Sebagai contoh singkat mengenai konsep
perikatan alamiah ini adalah dalam hal penagihan
utang dalam perjudian. Pasal 1359 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata “Tiap tiap pembayaran
memperkirakan adanya suatu utang; apa yang
telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat
dituntut kembali. Terhadap perikatan perikatan
bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak
dapat dilakukan penuntutan kembali.” Dari uraian
pasal di atas mengatur bahwa pembayaran lahir
dari adanya suatu utang. Perjanjian nominee
hanya bisa terus hidup sebagai perikatan alamiah
apabila kedua belah pihak terus menerus beritikad
baik dan memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak secara sukarela. Dalam hal salah
satu pihak ingkar janji terhadap kewajibannya
tersebut, perjanjian nominee tidak memiliki
kekuatan keberlakuan di hadapan hukum, dan
oleh karenanya tidak ada sanksi pemaksa pihak
yang ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya
kecuali sanksi moral.
3.4 Status hukum perjanjian nominee dalam
hal salah satu pihak meninggal dunia.
Dalam hal salah satu pihak meninggal
dunia (dalam hal ini pihak nominee / Warga
Negara Indonesia) maka terjadi peristiwa turun
waris yakni hak atas tanah si mati beralih menjadi
milik dari para ahli waris dari si meninggal
(nominee). Pada perjanjian nominee pada
umumnya terdapat klausula bahwa ”dia beserta
ahli warisnya turut serta dan mengikatkan diri
12 Op.cit. Hal 165.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 32
secara sukarela dalam perjanjian (perjanjian
nominee)”. Dalam hukum perjanjian, suatu
perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang
membuatnya dalam hal ini pihak warga negara
asing dan nomineenya, sehingga sejatinya pihak
lain tidak terikat oleh perjanjian ini begitu juga
ahli waris dari nominee dalam hal ia meninggal.
Namun dalam pewarisan menurut KUH Perdata,
yang dimaksud dengan harta warisan adalah hak
dan kewajiban dari si meninggal, jadi yang
diwariskan kepada ahli waris tidak hanya hak saja
namun juga kewajiban. Dalam kasus perjanjian
nominee tanah yang menjadi obyek perjanjian
tersebut telah diikat atau dibebani dengan suatu
kewajiban yang tertera dalam perjanjian maka
disini timbul kewajiban moral dari para ahli waris
nominee untuk menyelesaikan kewajiban
almarhum. Disinilah ikatan antara pihak warga
negara asing dengan ahli waris nominee tersebut
terbentuk.
Dalam Perjanjian nominee dalam prakteknya
dibuat berbagai perjanjian yakni :
1. Perjanjian Induk yang terdiri dari dari
Perjanjian PemilikanTanah (land agreement)
dan Surat Kuasa;
2. Perjanjian Opsi
3. Perjanjian sewa-menyewa (lease agreement)
4. Kuasa Menjual (power of attorney to sell)
5. Hibah Wasiat; dan
6. Surat Pernyataan Ahli Waris.
7. Akta Pengakuan Hutang.
8. Akta Pemberian Hak Tanggungan.
Dengan adanya perjanjian-perjanjian di atas,
pada umumnya pihak Warga Negara Asing
melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan
para ahli waris jika pihak asing ingin menunjuk
ahli waris dari Warga Negara Indonesia tersebut
sebagai nominee pengganti atau pihak asing
tersebut dapat bertindak selaku kuasa dari
nominee yang meninggal dunia dengan
menggunakan Kuasa Menjual yang sudah
dibuatnya. Namun terkadang pelaksanaan
penjualan dengan menggunakan kuasa menjual
tersebut menemui hambatan, hambatan terjadi
jika terdapat persyaratan yang mengharuskan
pihak Warga Indonesia untuk hadir (selaku
pemilik tanah yang tercantum didalam sertipikat)
khususnya dalam hal pengukuran.
IV.SIMPULAN DAN SARAN
4.1 Simpulan
1. Pengaturan kepemilikan tanah oleh orang
asing yang dibuat melalui Perjanjian nominee
dihadapan Notaris menurut Hukum
pertanahan Indonesia adalah dengan
memberikan hak atas tanah kepada warga
negara asing berupa hak pakai atas tanah
namun Warga negara asing dan lebih
memilih untuk menggunakan perjanjian
nominee untuk dapat memiliki hak milik atas
tanah. Perjanjian nominee yang sering
disebut sebagai bentuk penyelundupan
hukum dikatakan sah apabila ia tidak
melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku, ketertiban umum dan
kesusilaan. Berdasarkan paparan di atas
perjanjian nominee tidak memenuhi satu dari
empat syarat sebagaimana yang ditetapkan
oleh Pasal 1320 Kitab Undang undang
Hukum Perdata khususnya syarat „kausa
yang halal”, sehingga dapat dikatakan bahwa
perjanjian nominee tidak sah karena
melanggar ketentuan pasal 26 ayat 2 UUPA,
namun ternyata Pasal-pasal dalam UUPA
tidak mengatur mengenai larangan
kepemilikan secara nominee secara tegas
sehingga perjanjian nominee yang tidak
memenuhi klausula yang halal perlu untuk
dilakukan penafsiran terlebih dahulu oleh
hakim.
2. Status hukum “perjanjian nominee” apabila
salah satu pihak meninggal dunia adalah
dengan penjelasan sebagai berikut untuk satu
kasus perjanjian nominee perlu dibuat lebih

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 33
dari satu macam perjanjian, guna menutupi
kelemahan dari satu perjanjian dengan
perjanjian lainnya. Selain itu perjanjian
nominee termasuk dalam perikatan alamiah
jika berbicara mengenai pemenuhan prestasi
dalam arti suatu perjanjian yang
mengkedepankan itikad baik dari masing-
masing pihak untuk memenuhi prestasi
tersebut. Hal ini berbeda dengan perjanjian
pada umumnya yang pemenuhan prestasinya
bisa dipaksakan jika perjanjian nominee
dipaksakan pemenuhannya tanpa ada itikad
baik dari para pihak maka prestasi akan sulit
untuk dilaksanakan. Dalam hal pihak warga
Indonesia meninggal maka terjadi peristiwa
turun waris dan pihak asing dapat menunjuk
ahli waris si nominee untuk menggantikan
pihak yang meninggal atau menjual tanah
tersebut dengan bertindak sebagai kuasa dari
pihak yang meninggal .
4.2 Saran
Bahwa pemerintah harusnya membuat
suatu peraturan yang tegas mengenai perjanjian
nominee dalam bidang pertanahan. Karena selain
tidak memberi perlindungan bagi Warga negara
asing, juga dapat merusak iklim investasi di
Indonesia khususnya di bali karena membuka
peluang bagi Warga Negara Indonesia untuk
melakukan penipuan terhadap Warga negara
asing yang menggunakan namanya untuk
memiliki tanah hak milik. Selain itu pemerintah
harus mempermudah dan memperjelas prosedur
penurunan hak milik menjadi hak pakai, karena
dengan pengurusan yang mudah maka Warga
negara asing tidak akan lagi menggunakan
perjanjian nominee. Bahwa perjanjian nominee
bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini, jika
Warga negara asing ingin memiliki tanah untuk
tempat tinggal, maka dapat menggunakan
lembaga hak pakai di atas hak milik.
DAFTAR PUSTAKA
I. BUKU :
Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Hal. 286
Kansil, C.S.T., 1979, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.
Kedua
Salim., 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdata, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,
hlm. 25.
Syahrani, Riduan, 2004, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, hlm.203.
Max Bolisabon et.al, 1992, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, h.111.
Soebekti, 1989, Hukum Perjanjian, Cet.CV.IV.Pen.Internusa Jakarta
Setiawan,1986, Pokok–pokok Hukum Perikatan, pen. Bina Cipta, Bandung,hal 2
Soekanto, Soerjono, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada,Jakarta
II. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009,
Cetakan XXXX, Pradnya Paramita, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria(Lembaran Negara 1960-104)

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 34
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
58)
III. JURNAL :
Sumardjono, Maria S.W., 2007, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan,
Kompas, hal.1.
IV. INTERNET :
http://strategihukum.net/ketika-perjanjian-nominee-berujung-pada-sengketa, tanggal akses 1 november
2013
PT. Asiamaya Dotcom, Kontrak, Indonesia Menara Imperium, Jl.HR.Rasuna Said, Kav 1A, Jakarta
selatan, Email:[email protected], terakhir diakses tanggal 2 Agustus 2013
*****
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN COVERNOTE SEBAGAI SALAH
SATU PRODUK HUKUM YANG TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS
Oleh
Putu Ayu Lestari Dewi*, Prof. R.A. Retno Murni, SH.MH.,Ph.D **, Dr. Ni Nyoman Sukeni,
SH.,Msi.**
Magister Kenotariatan Universitas Udayana
E-mail : [email protected]
ABSTRACT
RESPONSIBILITIES OF A NOTARY TOWARDS THE MAKING OF A COVERNOTE AS A LAW
PRODUCT NOT REGULATED UNDER THE REGULATION OF A NOTARY’S POSITION
This thesis is motivated by the existence of a legal product that is issued or made by Notary
beyond its authority and not provided for in Law No. 30 Year 2004 on Notary . The legal product known
as covernote .Covernoteis a statement or frequently termed as a cover note made by a notary .Covernote
isissued by the notary for a notary has not finished its work in relation to the duty and authority to issue an
authentic deed . When examined in the duties and authority of the notary Notary Act is not a single article
that confirms that the notary may issue covernote . Based on the background above , the problems arise :
first , Is a Notary has the power to make Covernote according to Law Number 30 Year 2004 concerning
Notary and secondly , How Notary responsible in terms of events or actions in covernote law can not be
fulfilled .
To answer the issues above , the research methods used in this thesis are normative legal research
methods which imply the existence of a vacancy norm in Article 15 UUJN namely the lack of regulation
on the issuing authority covernote Notary . Sources of legal materials used is the primary legal materials ,
secondary , and tertiary , which is also supported by the field data . After all the data has beencollected ,
both field data and literature data are then classified qualitatively according to the problem .
The results of this thesis is first, a notary is not authorized to make covernote because they are
not set in UUJN , so that the product or Notary legal act is not legally binding . And second, in issuing a
covernote,Notary solely responsible for the content of such covernote , which is about facts or the truth
about what is done by him and obliged to finish what has been described in the covernote . If covernote
Notary proved to result in losses for the party , then the Notary personally responsible and can be sued
civilly in the form of compensation . Criminal sanctions may be imposed if the contents covernote issued
by the Notary is proven to describe a false statement .
Key words :covernote , Notary authority , responsibility Notary

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 35
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar belakang masalah
Keberadaan Notaris di tengah-tengah
kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan, dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan
alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna. Alat bukti yang mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna tersebut, lazimnya disebut
dengan akta notariil atau akta otentik. Namun
selain akta-akta yang bersifat otentik tersebut, ada
satu produk hukum yang dikeluarkan/ dibuat oleh
Notaris yang tidak diatur dalam Pasal 15 UUJN
tersebut, namun di dalam praktek kenotarisan
sering dilakukan dan dikerjakan oleh Notaris
sebagai produk hukum, yang disebut dengan
covernote. Hampir semua Notaris mengenal
covernote yang lahir, besar, dan tumbuh dari
kebiasaan Notaris yang sudah berjalan sekian
lama, bahkan sering dipraktekan dalam
menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam praktek
ditemukan pula covernote tersebut dibuat dalam
bentuk surat keterangan yang dibuat oleh Notaris
sendiri atas suatu tindakan hukum para pihak
yang dilakukan oleh para pihak dihadapan
Notaris.
Covernote sebagai surat keterangan atau
sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang
dibuat oleh notaris, dikeluarkan karena notaris
belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya
dengan tugas dan kewenangan untuk menerbitkan
akta otentik. Jika dicermati tugas dan kewenangan
notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
tidak ada satu pasal pun yang menegaskan bahwa
notaris dapat mengeluarkan covernote untuk
menerangkan bahwa akta yang akan dikeluarkan
masih dalam proses berjalan.
Dengan telah berlakunya UUJN sebagai
unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di
Indonesia (ius constitutum),maka hanya UUJNlah
yang berlaku, termasuk kewenangan Notaris yang
tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2),
sedangkan Pasal 15 ayat (3) akan berlaku dan
mengacu kepada peraturan perundang-undangan
yang akan berlaku kemudian (ius constituendum).
Dengan demikian jika Notaris melakukan suatu
tindakan diluar wewenang, maka Notaris telah
melakukan perbuatan melawan hukum atau
berbuat diluar wewenang. Jika Notaris telah
melakukan seperti itu, maka produk atau tindakan
hukum Notaris tidak mengikat secara hukum
(nonexecutable),dan pihak atau mereka yang
merasa dirugikan oleh tindakan hukum Notaris
diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat
digugat perdata ke pengadilan negeri.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil pengamatan tentang
permasalahan yang berlatar belakang hal tersebut
diatas, maka timbul masalah antara lain :
1. Apakah Notaris mempunyai kewenangan
membuat Covernote menurut Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris
dalam hal peristiwa atau perbuatan
hukum dalam covernote tidak dapat
terpenuhi?
I.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dari penulisan
tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Tujuan umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah
Untuk mengetahui secara umum
mengenai kedudukan covernote di dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris serta
untuk membangun wawasan ilmu hukum
khususnya tentang kewenangan dari
pada Notaris.
b. Tujuan khusus
Mengenai tujuan khusus penelitian ini,
sesuai permasalahan yang dikaji dalam
tesis ini adalah :

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 36
1. Untuk mengetahui dan
menganalisis mengenai
kewenangan Notaris dalam
mengeluarkan covernote
menurut Undang-Undang
Jabatan Notaris
2. Untuk mengetahui dan
menganalisis mengenai
tanggung jawab notaris
terhadap covernote yang dibuat
.
I.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dari penulisan
tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menambah khasanah ilmu hukum
perdata pada umumnya, khususnya
tentang ilmu hukum kenotariatan
terutama mengenai permasalahan
kewenangan Notaris dalam menerbitkan
covernote menurut Undang-Undang
Jabatan Notaris.
1.4.2 Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan informasi kepada
pihak-pihak yang terlibat dalam
penerbitan covernote yaitu bagi Notaris,
dan pihak-pihak yang memerlukan
covenote notaris . Bagi peneliti sendiri,
disamping untuk menyelesaikan studi
juga untuk menambah wawasan dibidang
hukum Kenotariatan khususnya dalam
hal penerbitan covernote oleh Notaris.
I.5 Landasan Teoritis
Adapun teorinya yang digunakan adalah
sebagai berikut :
1. Teori Kewenangan
Ateng Syafrudin berpendapat
ada perbedaan antara pengertian
kewenangan dan wewenang.
Kewenangan adalah apa yang disebut
kekuasaan formal, kekuasaan yang
berasal dari kekuasaan yang diberikan
oleh undang-undang, sedangkan
wewenang hanya mengenai suatu
“onderdeel” (bagian) tertentu saja dari
kewenangan. Dalam kewenangan
terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe
voegdheden). 1
Max Weber mengemukakan
beberapa bentuk wewenang dalam
hubungan manusia yang juga
menyangkut hubungan dengan
kekuasaan. Menurut Weber, wewenang
adalah kemampuan untuk mencapai
tujuan – tujuan tertentu yang diterima
secara formal oleh anggota – anggota
masyarakat. Sedangkan kekuasaan
dikonsepsikan sebagai suatu kemampuan
yang dimiliki seseorang untuk
mempengaruhi orang lain tanpa
menghubungkannya dengan penerimaan
sosialnya yang formal. Dengan kata lain,
kekuasaan adalah kemampuan untuk
mempengaruhi atau menentukan sikap
orang lain sesuai dengan keinginan si
pemilik kekuasaan.
Istilah wewenang atau
kewenangan disejajarkan dengan
“authority” dalam bahasa Inggris dan
“bevoegdheid” dalam bahasa Belanda.
Authority dalam Black S Law Dictionary
diartikan sebagai “Legal power; a right
to command or to act; the right and
power of public officers to require
obedience to their orders lawfully issued
in scope of their public duties.”2
(Terjemahan bebas; Kewenangan atau
1 Ateng Syafrudin, 2000, Menuju
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang
Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro
Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan,
Bandung, hal. 22 2Henry Campbell Black, 2009, Black‟S
Law Dictionary, West Publishing, hal. 133.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 37
wewenang adalah kekuasaan hukum, hak
untuk memerintah atau bertindak; hak
atau kekuasaan pejabat publik untuk
mematuhi aturan hukum dalam lingkup
melaksanakan kewajiban publik).
2. Teori Tanggung Jawab
Mengenai persoalan
pertanggung jawaban pejabat menurut
Kranenburg dan Vegtig ada dua teori
yang melandasinya yaitu:
a. teori fautes personalles, yaitu
teori yang menyatakan bahwa
kerugian terhadap pihak ketiga
dibebankan kepada pejabat
yang karena tindakannya itu
telah menimbulkan kerugian.
Dalam teori ini beban tanggung
jawab ditujukan pada manusia
selaku pribadi.
b. teori fautes de services, yaitu
teori yang menyatakan bahwa
kerugian terhadap pihak ketiga
dibebankan pada instansi dari
pejabat yang bersangkutan.
Menurut teori ini tanggung
jawab dibebankan kepada
jabatan. Dalam penerapannya,
kerugian yang timbul itu
disesuaikan pula apakah
kesalahan yang dilakukan itu
merupakan kesalahan berat atau
kesalahan ringan, dimana berat
dan ringannya suatu kesalahan
berimplikasi pada tanggung
jawab yang harus ditanggung.3
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam tesis
ini merupakan penelitian hukum normatif.
Penelitian ini beranjak pada kekosongan norma
dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor
3Phillipus M. Hadjon, 1997, Tentang
Wewenang, Yuridika, hal. 365
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai
kewenangan dan kewajiban Notaris dalam
mengeluarkan covernote yang tidak diatur dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris.
1.6.2 Jenis Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam tesis
ini adalah:
1. Pendekatan Perundang-undangan
(Statute Approach) dilakukan
dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani.4
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach) beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang di dalam ilmu
hukum.5
3. Pendekatan Sejarah (Historical
Approach) dilakukan dengan
menelaah latar belakang apa yang
dipelajari dan perkembangan
pengaturan mengenai isu yang
dihadapi.6
1.6.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian
ini berasal dari penelitian kepustakan (library
research) artinya terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tertier Adapun bahan hukum primer yang
dimaksud dalam tesis ini adalah bahan hukum
yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu:
a. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata;
b. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
4
Peter Mahmud Marzuki, 2005,
Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, (selanjutnya
disingkat Peter Mahmud Marzuki II), hal. 93. 5 Ibid, hal. 95.
6 Ibid, hal. 94.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 38
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Bneda
yang Berkaitan dengan Tanah;
e. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan;
f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris;
g. Kode Etik Notaris
Adapun bahan hukum sekunder yang
dimaksud dalam penulisan tesis ini adalah bahan
hukum yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
dalam penulisan tesis ini meliputi : buku – buku
literature, jurnal, makalah dan bahan – bahan
hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.
Adapun bahan hukum tertier yang
dimaksud dalam penulisan tesis ini yaitu bahan
hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier
dalam penulisan tesis ini meliputi kamus hukum
dan kamus bahasa Indonesia.
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum
dalam penelitian tesis ini yaitu dilakukan dengan
teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka ini
dilakukan melalui tahap-tahap indentifikasi dan
inventarisasi. Bahan hukum yang sudah
terkumpul kemudian diolah sesuai dengan
kebutuhan penelitian, melalui beberapa tahap
pemeriksaan (editing), penandaan (coding),
penyusunan (reconstructing), sistimatisasi
berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok
bahasan yang di indentifikasi dari rumusan
masalah (systematizing). 7
1.6.5 Teknik Pengolahan Analisis Bahan
Hukum
Setelah semua bahan hukum terkumpul
kemudian diklasifikasikan secara kualitatif sesuai
dengan rumusan masalah. Bahan hukum tersebut
dianalisa dengan teori-teori yang relevan
kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab
masalah. Akhirnya bahan hukum tersebut
disajikan secara deskriptif anatis.
BAB II
PEMBAHASAN
Kewenangan Notaris dalam Membuat
Covernote Menurut Undang- Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Akta otentik merupakan produk hukum
dari Notaris, namun di dalam praktek tidak hanya
sebuah akta otentik yang dibuat oleh Notaris,
melainkan ada produk hukum lain yang dibuat
oleh Notaris namun tidak diatur dalam Pasal 15
UUJN, yaitu Covernote. Dalam praktek Notaris
Covernote merupakan surat keterangan yang
dibuat oleh Notaris sendiri atas suatu tindakan
hukum para pihak dan dilakukan dihadapan
Notaris, yang dapat dipercaya oleh para pihak dan
dapat diandalkan karena terdapat tanda tangan,
cap serta segel dari Notaris yang digunakan
sebagai jaminan dan alat bukti yang kuat. Ada
beberapa contoh kegunaan dari surat
keterangan/Covernote Notaris :
1. Bila debitur hendak mengambil kredit di Bank
dan barang yang akan dijaminkan itu masih
dalam proses roya fidusia sedangkan bank
baru akan mencairkan kredit bila barang yang
dijaminkan telah selesai di-roya fidusia
terlebih dahulu, maka salah satu solusi agar
kredit itu dapat dicairkan oleh bank, yaitu
Notaris akan mengeluarkan covernote yang
berisi keterangan bahwa surat-surat
kepemilikan atas barang itu sedang dalam
proses roya dan apabila telah selesai di-roya
maka akan diserahkan kepada bank nantinya.
7Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal. 192

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 39
2. Bila suatu Perseroan Terbatas (PT) sedang
menunggu surat keputusan pengesahan
sebagai badan hukum dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI dan proses
pengurusannya dilimpahkan ke kantor Notaris,
maka Notaris akan mengeluarkan covernote
yang menerangkan bahwa surat-surat tersebut
sedang dalam proses di Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI, apabila telah
selesai pengurusannya akan diserahkan kepada
pihak yang berkepentingan8.
Sebagai seorang pejabat, Notaris
memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan
tugasnya. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris
dapat dilihat di dalam Pasal 15 UUJN, yaitu :
1. Kewenangan Umum Notaris
Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa
salah satu kewenangan notaris yaitu membuat
akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai
Kewenangan Umum Notaris dengan batasan
sepanjang :
a. Tidak dikecualikan kepada pejabat
lain yang telah ditetapkan oleh
undang-undang.
b. Menyangkut akta yang harus dibuat
adalah akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan ketetapan
yang diharuskan oleh aturan hukum
untuk dibuat atau dikehendaki oleh
yang bersangkutan
c. Mengenai kepentingan subjek
hukumnya yaitu harus jelas untuk
kepentingan siapa suatu akta itu
dibuat.
2. Kewenangan Khusus Notaris
Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam
Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai
kewenangan khusus notaris untuk melakukan
tindakan hukum tertentu, seperti:
1. Mengesahkan tanda tangan dan
menetapkan kepastian tanggal surat di
8
Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja,
Panduan Teori Dan Praktek Notaris, 2011,
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.86.
bawah tangan dengan mendaftarkannya
di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah
tangan dengan mendaftarkannya dalam
suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-
surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis
dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan
antara fotokopi dengan surat aslinya
5. Memberikan penyuluhan hukum
sehubungan dengan pembuatan akta
6. Membuat akta yang berkaitan dengan
pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang
3. Kewenangan Notaris yang ditentukan
kemudian
Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN
dengan kewenangan yang akan ditentukan
kemudian adalah wewenang yang berdasarkan
aturan hukum lain yang akan datang kemudian
(ius constituendum). Wewenang notaris yang
akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang
yang akan ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan
bahwa covernote bukan termasuk kewenangan
Notaris karena tidak diatur dalam Pasal 15 UUJN,
karena kewenangan merupakan kekuasaan formal
yang berasal dari undang-undang. Setiap jabatan
apapun di negara kita ini mempunyai kewenangan
tersendiri. Setiap kewenangan harus ada dasar
hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai
kewenangan , maka kewenangan seorang Pejabat
apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
Pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika
seorang Pejabat melakukan suatu tindakan diluar
kewenangan disebut sebagai perbuatan melanggar
hukum. Oleh karena itu, suatu kewenangan tidak

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 40
muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu
diskusi atau pembicaraan di belakang meja
ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun
pendapat-perdapat di lembaga legislatif, tapi
wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam
peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS
TERHADAP COVERNOTE YANG DIBUAT
Mengenai tanggung jawab notaris
terhadap covernote yang dibuatnya dapat
dikategorikan sebagai tanggung jawab secara
personal. Menurut Kranenburg dan Vegtig, ada
dua teori yang melandasi persoalan pertanggung
jawaban pejabat yaitu teori fautes personalles dan
teori fautes de service dari kedua teori tersebut.
Teori fautes personalles akan digunakan untuk
menjawab permasalahan tanggung jawab notaris
terhadap covernote yang dikeluarkannya, karena
beban tanggung jawab terhadap covernote yang
dikeluarkan oleh notaris ditujukan kepada
manusia selaku pribadi bukan tanggung jawab
jabatan. Sehingga jika seorang pejabat melakukan
suatu tindakan di luar kewenangan disebut
sebagai perbuatan melanggar hukum.
Perbuatan melanggar hukum merupakan
perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan
secara normative perbuatan tersebut tunduk pada
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365
KUH Perdata menyatakan “tiap perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut.” Bentuk tanggung jawab yang
dianut oleh Pasal 1365 KUH Perdata adalah
tanggung jawab berdasarkan kesalahan.
Perbuatan melanggar hukum yang
dimaksud dalam perbuatan melanggar hukum
oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung
melanggar hukum, melainkan juga perbuatan
yang secara langsung melanggar peraturan lain,
yang dimaksud dengan peraturan lain adalah
peraturan yang berada dalam lapangan kesusilaan,
keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat
dilanggar.9
Notaris dalam mengeluarkan covernote
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi dari
covernote tersebut, yaitu tentang fakta atau
kebenaran mengenai apa yang dikerjakan olehnya
dan berkewajiban menyelesaikan apa yang sudah
diterangkan di dalam covernote. Jika dilihat
bahwa notaris dalam mengeluarkan covernote
yang bukan merupakan kewenangannya menurut
UUJN, apabila covernote tersebut mengakibatkan
kerugian bagi para pihak maka notaris dapat
dituntut secara perdata dalam bentuk ganti rugi
dengan ketentuan bahwa covernote tersebut
ternyata tidak benar. Notaris sebagai pihak yang
mengeluarkan covernote harus bertanggung jawab
sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya.
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan
yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya
terhadap permasalahan yang dikaji dalam tesis
ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
a. Notaris dapat dikatakan tidak berwenang
membuat Covernote menurut UUJN,
karena tidak diatur dalam Pasal 15
UUJN tentang kewenangan Notaris.
kewenangan merupakan kekuasaan
formal yang berasal dari undang-undang.
Namun covernote tidak juga dilarang
menurut Pasal 17 UUJN terutama pada
huruf i yaitu Notaris dilarang melakukan
pekerjaan lain yang bertentangan dengan
norma agama, kesusilaan, atau kepatutan
yang dapat mempengaruhi kehormatan
9R. Wirjono Prodjodikoro, 2000,
Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari
Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung,
hal. 6

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 41
dan martabat jabatan Notaris. Hanya saja
Notaris tetap harus memiliki batasan-
batasan dalam pembuatan covernote
tersebut, seperti batasan terhadap isi atau
materi yang diterangkan didalamnya
harus berdasarkan fakta yang terjadi atau
dilakukan dihadapan Notaris tersebut,
bukan covernote pesanan atau
permintaan para pihak yang
membutuhkan, serta tidak melebih-
lebihkan isinya.
b. Notaris dalam mengeluarkan covernote
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
isi dari covernote tersebut, yaitu tentang
fakta atau kebenaran mengenai apa yang
dikerjakan olehnya dan berkewajiban
menyelesaikan apa yang sudah
diterangkan di dalam covernote. Jika
dilihat bahwa notaris dalam
mengeluarkan covernote yang bukan
merupakan kewenangannya menurut
UUJN, apabila covernote tersebut
mengakibatkan kerugian bagi para pihak
maka notaris dapat dituntut secara
perdata dalam bentuk ganti rugi dengan
ketentuan bahwa covernote tersebut
ternyata tidak benar. Sedangkan
tanggung jawab secara pidana dapat
dikenakan terhadap notaris apabila
terbukti turut serta memberikan
keterangan palsu mengenai isi covernote
yang dibuatnya. Notaris sebagai pihak
yang mengeluarkan covernote harus
bertanggung jawab sepenuhnya dengan
segala akibat hukumnya.
2. Saran
1. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang
telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya
terhadap permasalahan yang dikaji dalam
tesis ini, maka dapat diberikan saran;
Mengingat covernote yang dikeluarkan oleh
notaris memiliki peranan yang sangat penting
di dalam praktek kenotariatan, maka
diharapkan agar undang-undang Jabatan
Notaris memberikan pengaturan yang jelas
mengenai bentuk dan isi dari covernote.
Sehingga terdapat kejelasan mengenai
kewenangan notaris dalam mengeluarkan
covernote dan covernote memiliki dasar
hukum yang jelas.
DAFTAR PUSTAKA
I. BUKU
Adjie, Habib, 2006, Tidak Ada Sengketa Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan
Notaris dalam Bidang Pertanahan, Renvoi 1.37.IV, 3 Juni 2006
, 2009, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan), CV. Mandar Maju,
Bandung.
, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT.
Refika Aditama, Bandung.
Andasasmita, Komar, 1981, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung.
Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika), 2009, UII
Press, Yogyakarta.
Bertens, K, 1997, Etika, cetakan ke 3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Budiono, Herlien, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Black, Henry Campbell, 2009, Black‟S Law Dictionary, West Publishing.
Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Burhan, Ashsofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 42
Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja, Panduan Teori Dan Praktek Notaris, 2011, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta.
Efendi, Lutfi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang.
Efendi, Masyhur, 1994, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan
Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.
, 2005, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Garner , Bryan A., 2009, Black‟s Law Dictionary 2nd
Pocket Edition, ST. Paul, Minn West Group.
Hadjon, Phillipus M., 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, Surabaya.
, dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta.
H.R., Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
HS, Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Indroharto, 1994, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti ,
Bandung.
Indonesia Legal Center Publishing, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris
dan PPAT, CV Karya Gemilang, Jakarta.
Kansil, C.S.T, 2006, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.
Kantaprawira, Rusadi, 1998, MakalahHukum dan Kekuasaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Kie, Tan Thong, 2000, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta.
Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta.
Lubis, Suhrawardi K., Etika Profesi Hukum, 2000, Sinar Grafika, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
Mertokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta
Muhamad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, 1992, Citra Aditya, Bandung.
, 2001, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
,2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu
Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas
Airlangga, Surabaya.
Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of
Business Law
Notodisoerjo, Soegondo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Perasada,
Jakarta

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 43
Prodjodikoro, Wiryono, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata,
Mandar Maju, Bandung
, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama,
Bandung
Setiardja, Gunawan, 1990, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia,
Kanisius, Yogyakarta.
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta.
Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju,
Bandung.
Soegondo, R., 1991, Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
dan Sri Mamudji, 2010, Penelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerojo, Irwan, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya.
Soesilo dan Pramudjir, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, WIPRESS.
Suherman, E, 1979, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah
Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung.
Supriadi, 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 1977, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syarifudin, Ateng, 2000, Jurnal Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab, Universitas Parahyangan, Bandung.
Tedjosaputro, Liliana, 2003, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing,
Yogyakarta.
Thamrin, Husni, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
Tobing, G.H.S. Lumbun, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
Yudara , Nyoman Gede, dkk, 2006, Kapitaselekta Penegakan Hukum di Indonesia, Prestasi Pustaka
Publisher, Jakarta.
, 2006, Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta
akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Renvoi, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret.
II UNDANG-UNDANG :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, Cetakan
XXXX, Pradnya Paramita, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terjemahan Moeljatno, 2006, Bumi Aksara, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan;

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 44
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4432).
Kode Etik Notaris
III MAKALAH :
Adjie,
Habib, 2011, Kumpulan Makalah “Memaknai Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan dalam
Kerangka Mendukung Pelaksanaan Jabatan Notaris/PPAT”
Hadjon, Philipus M., Makalah Tentang Wewenang, Universitas Airlangga, Surabaya
, Eksistensi dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Figur Hukum
Akta PPAT, Makalah Ceramah Fakultas Hukum UNAIR tanggal 22 Pebruari 1996, hal.
Setiawan, Wawan, Kedudukan dan Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum dan PPAT dibandikan
dengan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, Makalah diskusi Ilmiah,
FH Unair dan INI Pengda Jatim, Surabaya, hal. 24
, 1994, Ciri-ciri Notaris yang Ideal, Makalah Refreshing Up Grading Course INI,
Jakarta, hal.
IV INTERNET
Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum, www.wawasanhukum.blogspot.com, diakses tanggal 1 Agustus
2013
Damang, Covernote, http://Psycho-legal.blogspot.com/2011/07/cover-note-oleh-notaris.html
*****
ANALISIS KEABSAHAN AKTA NOTARIS TENTANG SEWA MENYEWA TANAH
DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN DALAM BENTUK PIPIL
Oleh
Anak Agung Ade Jaya Wibawa*, Prof. Dr. I Wayan Windia, SH.,M.Si , **, I Made Pria Dharsana,
SH.,M.Kn**
Magister Kenotariatan Universitas Udayana
E-mail : [email protected]
ABSTRACT
VALIDITY ANALYSIS OF NOTARY DEED LAND OF LEASE RENT IN PIPIL
Land has an important meaning for society, both in terms of economic, social. Each person will try
to meet the need for land, each person will be trying to acquire the land as much as possible. One effort
that is often made is to lease the land.
Lease is a form of reciprocal agreement, lease agreement should not be loose rather than legal
provisions applicable in Indonesia, namely the draft Civil Code (hereinafter referred to as the Code
Civil). Regarding the legitimacy of agreements governed by Article 1320 of the Civil Code, among others:
the agreement of the parties, the skill of the parties who made it, a certain object and a lawful reason.
Lease agreement will give rise to the rights and obligations of the parties who made it. Agreements made
legally valid as the law for those who make it, it is stipulated in Article 1338 of the Civil Code.
This thesis uses empirical legal research methods to approach legislation, which was associated
with the approach of the case and facts approach. Regulatory approach is done by reviewing and
analyzing legislation relating to the regulation of land namely Law No. 5 of 1960 Concerning Basic
Principles of Agricultural and Government Regulation No. 24 of 1997 on registration of land, and a case

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 45
approach is used to assess how the lease agreement with the object of ownership in the form of finely
made in a notarial deed, as well as the fact approach to the fact that occur in the field of the ground lease
with the object of ownership in the form of finely.
The results showed that it is legitimate rental agreement with the finely object. When referring to
one of the principles is the principle of konsensualisme agreement, in which agreement has been born if it
has the agreement of the parties. So also with the object of the agreement is not something that is
prohibited by the Act. As for the possible problems arising from the agreement is to be done with the effort
both preventive and repressive laws of the realm of civil and criminal law
*Penulis
**Pembimbing I
*** Pembimbing II
Keywords: Agreement, Lease, Pipil, Deed
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Tanah bagi kehidupan manusia
mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal
ini disebabkan hampir seluruh aspek
kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia
tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang
sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari
aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala
kehidupan dan penghidupannya.
Kebutuhan ekonomi dalam kehidupan
manusia akan tanah mengakibatkan lalu lintas
hukum dalam jual beli dan sewa-menyewa
terhadap tanah meningkat.
Namun tidak semua orang yang memiliki tanah
memiliki bukti kepemilikan berupa sertipikat Hak
Milik, namun ada juga yang hanya memiliki pipil.
Di Indonesia, secara konstitusional
pengaturan hukum tanah (sebagai bagian dari
sumber daya alam) ditegaskan dalam Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Dalam Pasal tersebut terkandung 2 unsur
yang berarti penting, yaitu “dikuasai” dan
“dipergunakan”. Unsur dikuasai adalah dasar
wewenang Negara dalam mengatur , negara
adalah badan hukum publik yang dapat
mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia
biasa. Sedangkah unsur “dipergunakan”
mengandung suatu perintah kepada Negara untuk
mempergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat.
Bukti kepemilikan tanah di Indonesia
saat ini adalah sertipikat sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria yang lebih
dikenal dengan UUPA (selanjutnya disebut
UUPA). Lalu bagaimana dengan proses
pendaftaran tanah yang merupakan bukti
kepemilikan seseorang terhadap tanah sebelum
berlakunya UUPA dan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah. Sebelum berlakunya UUPA dan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah, bahwa tanda bukti
kepemilikan tanah itu adalah pipil. Pipil adalah
bukti kepemilikan tanah seseorang yang
digunakan pada saat sebelum berlakunya UUPA.
Pada saat setelah berlakunya UUPA,
bukti kepemilikan terhadap tanah adalah berupa
sertipikat , jadi apabila di suatu tanah yang sama
terdapat pipil dan ada sertipikatnya, maka pemilik
sertipikatlah yang akan memiliki hak kebendaan
(hak milik atas tanah) yang lebih kuat, karena
sertipikat hak milik atas tanah adalah tanda bukti
yang lebih kuat daripada pipil.
Pengadaan tanah sudah menjadi
kebutuhan bagi masyarakat yang ingin
meningkatkan taraf perekonomiannya, kebutuhan
tersebut menimbulkan keinginan dari subjek

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 46
hukum untuk menguasai sebanyak-banyaknya
tanah di Indonesia, dan salah satu cara yang
dipergunakan oleh mereka adalah dengan sewa-
menyewa tanah. Perjanjian sewa-menyewa diatur
di dalam babVII Buku III KUH Perdata yang
berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang
meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600
KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa
menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan
bahwa: “Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada
pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang,
selama waktu tertentu dan dengan pembayaran
suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan
telah disanggupi pembayaranya.”
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata
mengandung pengertian bahwa perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku mengikat bagi yang
membuat perjanjian tersebut. Itu artinya sejak
lahirnya perjanjian sewa menyewa tanah tersebut
yang dikatakan sah secara undang-undang
otomatis mengikat para pihak yang membuat
perjanjian sewa menyewa itu. Selain asas tersebut
yang patut diperhatikan adalah syarat sahnya
perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata.
Setelah kebutuhan manusia akan tanah
terpenuhi dengan upaya sewa-menyewa tersebut,
sekarang munculah kembali bagaimana cara
menuangkan perbuatan hukum sewa menyewa
tersebut agar menjadi alat bukti yang kuat, maka
disinilah letak peran notaris dalam membuat akta
notaris yang berisi perbuatan hukum yang mereka
lakukan tersebut. Dalam hal mencari kepastian
hukum terhadap perbuatan hukum sewa menyewa
tersebut dibuatlah akta notariil.
Walaupun segala informasi mengenai
tanah tersebut belum jelas, baik itu kepemilikan
maupun luasnya, tetap saja dilakukan perjanjian
sewa-menyewa dengan menggunakan objek
berupa pipil, bahkan dengan menggunakan akta
otentik atau akta yang dibuat oleh notaris.Yang
menjadi permasalahan adalah bagaimana
keabsahan akta notaris tersebut, terutama bila
ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata terutama
dalam hal objek tertentu.
Pipil sebagai yang merupakan
representasi pengakuan Negara terhadap hak
kepemilikan oleh warga Negara Indonesia
sebelum berlakunya UUPA memang bisa diubah
menjadi sertipikat dengan proses konversi yang
dilakukan di Badan Pertanahan Nasional. Secara
garis besar proses konversi ada 4 yaitu,
pendaftaran, pengukuran, sidang dan penerbitan
sertipikat. Proses ini sangat panjang, belum lagi
apabila pemilik tanah ini sudah meninggal tentu
harus ada surat pernyataan silsilah keluarga dan
surat pernyataan waris yang benar-benar valid,
lalu bagaimana dengan perjanjian sewa-menyewa
yang sudah terjadi sebelum proses konversi itu ,
bagaimana bila malah status kepemilikan
terhadap tanah itu bukanlah jatuh kepada pemilik
semula yang menyewakan tanah tersebut padahal
perjanjian itu telah berlangsung selama beberapa
waktu.
1.2 Rumusan Masalah.
Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan
beberapa masalah antara lain :
a) Bagaimanakah keabsahan akta notaris
tentang sewa menyewa tanah dengan bukti
kepemilikan dalam bentuk pipil bila ditinjau
dari hukum perjanjian?
b) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan
untuk mengantisipasi akibat hukum yang
ditimbulkan dari sewa menyewa tanah
dengan bukti kepemilikan dalam bentuk
pipil?
1.3 Tujuan Penelitian.
1.3.1 Tujuan Umum
a) Tujuan umum dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 47
bagaimana keabsahan akta notaris
tentang sewa menyewa tanah dengan
bukti kepemilikan dalam bentuk pipil
dalam hukum perjanjian.
1.3.2 Tujuan Khusus
b) Tujuan khusus untuk menganalisa
apakah upaya hukum yang dapat
dilakukan untuk mengantisipasi akibat
hukum yang ditimbulkan dari sewa
menyewa tanah dengan bukti
kepemilikan dalam bentuk pipil.
1.4 Manfaat Penelitian.
a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan hukum,
khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan
bidang pertanahan.
b. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini bagi
Pemerintah dalam hal ini adalah kantor
pertanahan setempat, masyarakat khususnya
pihak-pihak yang melangsungkan perjanjian sewa
menyewa dengan objek sebidang tanah dengan
bukti kepemilikan berupa pipil dan bagi Notaris.
1.5 Landasan Teoritis.
Untuk memperjelas dalam memberikan
suatu gambaran mengenai pembahasan
permasalahan diatas, maka dalam penulisan
tesis ini digunakan teori dan asas, yaitu :
1. Teori Negara Hukum
Teori ini digunkana untuk melihat
hubungan antara Badan atau Pejabat tata
Usaha Negara dengan seseorang atau
badan hukum perdata, contohnya adalah
bagaimana pemerintah sebagai regulator
dalam membuat suatuperaturan hukum
yang mengatur seseorang atau badan
hukum perdata.
2. Teori Perjanjian
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, dalam teori
perjanjian meliputi asas-asas yang berlaku
umum dalam perjanjian, antara lain asas
kebebasan berkontrak, asas
konsensualisme, asas itikad baik, asas
kepastian dan asas kepribadian.
3. Teori Keadilan.
Keadilan distributif, yaitu keseimbangan
antara apa yang didapati oleh seseorang
dengan apa yang patut didapatkan dan
keadilan korektif, yaitu keadilan yang
bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang
tidak adil.1
4. Asas Pembuktian.
Untuk menemukan kepastian hukum
diupayakan dengan pembuktian,
membuktikan dibedakan menjadi 2, yaitu
membuktikan dalam arti logis dan dalam
arti konvensional.2
1.6 Metode Penelitian.
a. Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris, yaitu dengan melihat
permasalahan dari kenyataan yang ada
dalam masyarakat dan dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku saat ini. Penelitian hukum empiris
adalah penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normatif (kodifikasi
undang-undang atau kontrak) secara in
actio pada setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyarakat.3
.
1 Faudy Munir, 2007, Dinamika Teori
Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal. 109. 2 Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum
Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
h.134 3 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum
dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal.134

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 48
b. Jenis Pendekatan.
1) Pendekatan Perundang-undangan
(Statue Aprroach).
2) Pendekatan Kasus (Case Aprroach).
c. Sumber Data.
a. Data primer yaitu data yang diperoleh
melalui penelitian di lapangan yaitu
wawancara yang berasal dari para
informan, Notaris yang berkedudukan
di Kabupaten Badung dan Kabupaten
Tabanan.
b. Data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan
yang meliputi data yang sudah
terdokumentasikan dalam bentuk
bahan-bahan hukum yang dikumpulkan
dengan studi–studi dokumen.
d. Teknik Pengumpulan Data.
Data sekunder, dilakukan dengan studi
dokumen dan untuk data primer, dilakukan
dengan mengadakan wawancara langsung
dengan para informan untuk memperoleh
jawaban yang relevan.
e. Teknik Analisis Data.
Sesudah semua data terkumpul baik itu
data lapangan yang diperoleh dengan
teknik wawancara ataupun data
kepustakaan yang diperoleh dari studi
dokumen kemudian diklasifikasikan secara
kualitatif yang disesuaikan dengan
permasalahan yang dibahas
BAB II
PEMBAHASAN
Keabsahan Akta Notaris Tentang Sewa
Menyewa Tanah Dengan Bukti Kepemilikan
Dalam Bentuk Pipil Bila Ditinjau Dari Hukum
Perjanjian.
Sewa menyewa bukanlah perbuatan
hukum pengalihan hak dari satu orang ke orang
lain yang menuntut pengalihan itu harus
didasarkan atas sertifikat. Itu artinya sewa
menyewa bisa dilakukan dengan menggunakan
pipil atas tanah sebagai objeknya. Atas terjadinya
sewa menyewa yang menggunakan pipil atas
tanah sebagai objeknya dituntut kejelian dari
seorang Notaris menempatkan pipil itu sebagai
objek atas perjanjian sewa menyewa dalam akta
Notariil yang dibuatnya.
Bukan berarti seseorang yang memiliki
tanah tanpa bersertifikat tidak mungkin
melakukan sewa menyewa terhadap tanah yang
dimilikinya tersebut. Ini sejalan dengan teori
kemanfaatan oleh Jeremy Bentham. Berikut
adalah kutipan pendapat dari Jeremy Bentham
mengenai kemanfatan yang terdapat dalam
bukunya “Introduction to the morals and
legislation”, bahwa hukum bertujuan semata-
mata apa yang berfaedah bagi orang.4 Dari
pendapat tersebut dapat penulis analisa bahwa
hukum dapat dinilai baik buruknya di mata
masyarakat adalah bagaimana hukum itu sendiri
memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum itu
dinilai baik apabila ia memberikan faedah yang
berguna bagi masyarakat, dan sebaliknya dinilai
buruk apabila hukum itu malah menimbulkan
kerugian bagi masyarakat. Kemanfaatan adalah
salah satu tujuan hukum disamping kepastian dan
keadilan. Seringkali kemanfaatan digunakan
4 R.Soeroso, 2000, Pengantar Ilmu Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta, h.58

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 49
sebagai tolak ukur apakah suatu peraturan itu
benar-benar berlaku dan bermanfaat bagi
masyarakat.Teori yang berhubungan dengan
kemanfaatan ini adalah Teori utilitarianisme, inti
dari teori ini adalah bahwa hukum pada dasarnya
bertujuan untuk memberikan faedah yang
sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.
Dalam kaitannya dengan sewa menyewa
atas tanah yang masih berpipil adalah tetap
dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan
dengan hukum, kesopanan dan kesusilaan, di
mana objek tanah berpipil itu dilengkapi dengan
data-data yang lengkap yang menunjang bahwa
objek tanah itu adalah yang dimaksud
sebagaimana tertera dalam pipil tersebut.
Perjanjian sewa menyewa dapat
dilaksanakan sejak adanya persetujuan dari para
pihak, jadi entah itu sewa menyewa dengan objek
pipil atau sertifikat tetap dapat terjadi dengan
syarat ada persetujuan dari para pihak yang
membuatnya. Hal ini sejalan dengan teori
perjanjian, khususnya asas perjanjian yaitu asas
konsensualisme. Perjanjian dianggap telah lahir
sejak adanya tanda persetujuan dari para pihak.
Subekti mendefinisikan pengertian
perjanjian sebagai berikut bahwa suatu perjanjian
adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji
kepada seorang yang lain atau di mana dua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.5
Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi
5R. Soebekt i , 2001,
Hukum Perjanj ian , PT.
Intermasa, Jakar ta , hal . 45
bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan
hukum mengenai harta benda kekayaan antara
dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau
tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain
berhak menuntut pelaksanaan janji itu.6 Dari
beberapa definisi atas perjanjian tersebut dapat
dikatakan bahwa asalkan para pihak telah setuju
terhadap isi dari perjanjian tersebut maka
perjanjian itu berlaku dan sah bagi mereka
sebagai Undang-Undang (asas kebebasan
berkontrak). Dalam definisi tersebut tidak
dijelaskan mengenai Objek perjanjian entah itu
berpipil atau bersertifikat, jadi walaupun
perjanjian didasarkan atas pipil maka perjanjian
itu adalah sah dan berlaku mengikat bagi para
pihak.
Pipil adalah sebuah bentuk pengakuan
negara terhadap penguasaan hak atas tanah
sebelum berlakunya UUPA, dapat dikatakan
bahwa pipil adalah didasarkan atas hukum yang
saat itu berlaku di Indonesia, adapun setelah
berlakunya UUPA adanya sertifikat atas tanah
sebagai bentuk kepemilikan suatu hak atas tanah,
bukan berarti pipil tidak berlaku lagi, pipil tetap
berlaku. Oleh karena itu dari segi norma hukum,
kesusilaan dan ketertiban umum pipil tidak
melanggar, dari segi objek perjanjian yang
dianggap sah sesuai pasal 1320 KUHPerdata
6 Wirjono Prodjodikoro,1985, Hukum
Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet VIII,
Sumur, Bandung , hal 11.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 50
perjanjian sewa menyewa dengan objek pipil atas
tanah adalah sah dan bisa dilaksanakan.
Perjanjian sewa menyewa terhadap pipil dapat
menimbulkan permasalahan yang lebih ketimbang
perjanjian sewa menyewa atas sertifikat, ini
karena data-data yang termuat dalam pipil
tidaklah selengkap dan akurat sebagaimana dalam
sertifikat. Dalam memasukan objek perjanjian
sewa dengan objek pipil ke akta notariil haruslah
mendapat perhatian yang lebih agar jangan
sampai objek yang dimaksud sampai salah yang
mengakibatkan akta notariil yang dibuat oleh
Notaris menjadi salah.
Dalam melakukan perjanjian sewa
menyewa tanah yang masih dalam bentuk pipil
tidaklah sama dengan perjanjian sewa menyewa
dengan objek tanah yang telah bersertipikat. Hal
ini dikarenakan ada beberapa informasi dalam
pipil yang belum sesuai dengan kenyataan pada
saat ini, harus diperhatikan data yuridis dan data
sporadik yang berkaitan dengan tanah tersebut.
Apabila ingin melakukan perjanjian sewa
menyewa tanah yang masih dalam bentuk pipil
sebagaiknya didahului dengan pembuatan Akta
Perikatan Pendahuluan Sewa Menyewa Tanah
yang mana isinya sebagaimana hasil wawancara
yang dilakukan oleh peneliti dan kemudia baru
kemudian dibuat Akta Perjanjian Sewa Menyewa
Tanah sebagai tindak lanjut dari Akta
Pendahuluan tersebut.
Perjanjian sewa menyewa baik dengan
objek sertifikat ataupun masih dalam bentuk pipil
adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang
sebagaimana bila ditinjau dari teori perjanjian.
Adapun yang dilihat dari perjanjian ini bukanlah
karena objek sewa sudah dalam bentuk sertifikat
atau masih dalam bentuk pipil tetapi lebih kepada
manfaat yang diberikan sebagai akibat dari
perjanjian sewa menyewa tersebut. Bila ditinjau
dari teori kemanfaatan maka perjanjian sewa
menyewa dengan objek sewa masih dalam bentuk
pipil adalah memberi manfaat bagi para pihak,
baik itu yang menyewakan tanah atau penyewa
tanah, kemanfaatan adalah salah satu tujuan
hukum disamping kepastian hukum dan keadilan.
Akta Notaris tentang sewa menyewa tanah
dengan bukti kepemilikan dalam bentuk pipil bila
ditinjau dari hukum perjanjian adalah sah dan
mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan
ketentuan bahwa Akta Notaris tersebut dibuat
berdasarkan tata cara dan syarat yang telah
ditentukan oleh UUJN dengan tidak
mengenyampingkan asas-asas umum yang
berlaku dalam perjanjian, sehingga Akta Notaris
itu memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna, dan merupakan murni hasil
kesepakatan para pihak saat itu.
Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk
Mengantisipasi Akibat Hukum yang
Ditimbulkan Dari Sewa Menyewa Tanah
Dengan Bukti Kepemilikan Dalam Bentuk
Pipil
Upaya hukum adalah dilakukan untuk
mencari suatu kebenaran materiil, yaitu kebenaran

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 51
yang sebenar-benarnya terjadi. Upaya hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya disebut KUHAP), adalah hak
terdakwa atau penuntut umum untuk tidak
menerima putusan pengadilan yang berupa
perlawanan atau banding atau kasasi atau hak
terpidana untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).
Secara singkat eksistensi upaya hukum tersebut
adalah upaya untuk mendapatkan keadilan dan
kebenaran materiil (materieele waarheid) bagi
terdakwa/terpidana maupun jaksa/penuntut umum
dari pengadilan yang lebih tinggi.
Upaya Hukum adalah cerminan secara
nyata salah satu asas hukum yang penting yaitu
asas persamaan dimata hukum (equality before
the law) yang mana asas ini menentukan bahwa
bahwa setiap orang yang disangka, ditahan,
dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Setiap orang pasti berusaha sebisa
mungkin untuk menghindar dari masalah, dan
mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya.
Begitu juga bagi mereka yang melakukan
perjanjian sewa menyewa dengan objek tanah
yang bukti kepemilikannya masih berbentuk pipil,
mereka berusaha memetik keuntungan
semaksimal mungkin dari perjanjian tersebut dan
menghindar dari sengketa atau permasalahan
yang mungkin timbul.
Akta Perikatan Sewa Menyewa Tanah
dibuat sebelum dibuatkan Akta Perjanjian Sewa
Menyewa Tanah terhadap tanah yang masih ber-
pipil. Akta Pendahuluan ini berisi mengenai
kehendak para pihak yang ingin memberi sewa
dan menerima sewa terhadap tanah yang pada
saat itu masih dalam berbentuk pipil, dan apabila
pipil tersebut telah dikonversikan menjadi
sertipikat maka para penghadap sepakat tidak
akan mempemasalahkannya, baik itu apabila
terjadi perubahan luas terhadap bidang tanah yang
menjadi objek sewa tersebut.
Selain merupakan kehendak dari para
pihak, akta pendahuluan tersebut juga sebagai alat
untuk meminimalisir potensi sengketa yang
timbul dari perjanjian sewa menyewa tanah yang
masih ber-pipil, karena dalam akta tersebut juga
dituangkan persetujuan dari para pihak bahwa
mereka telah setuju apabila nanti ada perubahan
setelah proses konversi dari pipil ke sertipikat.
Persetujuan kehendak dari para pihak
yang membuat persetujuan adalah termasuk salah
satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat
persetujuan kehendak itu adalah bersifat subjektif.
Yang artinya apabila dilanggar akan
menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan.
Dapat dikatakan bahwa untuk mencegah ataupun
meminimalisir akibat hukum yang diduga muncul

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 52
dari perjanjian sewa menyewa tanah dalam
bentuk pipil adalah dengan menggunakan Akta
Perjanjian Perikatan Pendahuluan Sewa
Menyewa, yang terpokok harus ada dalam akta ini
adalah harus berisi kedudukan dari pipil saat
perjanjian tersebut dibuat, apakah sedang proses
konversi atau akan dilakukan proses konversi dari
pipil ke sertipikat. Tidak lupa juga dalam Akta ini
harus dituangkan bahwa para pihak yang terlibat
dalam perjanjian ini telah mufakat dan sepakat
akan isi akta ini dan setuju untuk menuangkannya
dalam bentuk akta notariil.
Walaupun telah dilakukan upaya dengan
membuat Akta Perjanjian perikatan Sewa
Menyewa terlebih dahulu bisa juga berpotensi
menimbulkan masalah, entah itu menyangkut
objek perjanjian ataupun unsur-unsur lain dalam
perjanjian tersebut yang dapat dipermasalahkan.
Dalam Akta Notaris biasanya tercantum
mengenai pilihan domisili hukum bagi para
penghadap, yang artinya bila akhirnya mereka
bermasalah terhadap akta tersebut, atau terjadi
wanprestasi dalam perjanjian yang tertuang dalam
Akta tersebut maka para penghadap sepakat untuk
menyelesaikannya di Pengadilan Negeri setempat.
Adapun Akta Notaris yang bermasalah
sehingga terdegradasi menjadi Akta dibawah
tangan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna, artinya hakim tidak lagi hanya
membaca akta itu sebagaimana yang tertera saja.
Hakim di pengadilan dalam memberikan
putusannya harus berpedoman kepada alat-alat
bukti yang telah disebutkan sebelumnya, apabila
permasalahan yang timbul mengarah ke ranah
pidana ataupun ke arah ranah perdata. Selama
Akta Notaris memenuhi unsur-unsur sebagai akta
otentik dan dibuat berdasarkan tata cara yang
telah ditentukan UUJN maka Akta Notaris itu
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di
mata pengadilan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam
bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Akta Notaris tentang sewa menyewa
tanah dengan bukti kepemilikan dalam
bentuk pipil bila ditinjau dari hukum
perjanjian adalah sah dan mengikat para
pihak yang membuatnya. Dengan
ketentuan bahwa Akta Notaris tersebut
dibuat berdasarkan tata cara dan syarat
yang telah ditentukan oleh UUJN dengan
tidak mengenyampingkan asas-asas
umum yang berlaku dalam perjanjian,
sehingga Akta Notaris itu memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna,
dan merupakan murni hasil kesepakatan
para pihak saat itu.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan
untuk mengantisipasi akibat hukum yang
diduga timbul terhadap sewa menyewa
dengan objek berupa tanah yang berpipil
adalah dengan dua cara, yaitu dengan

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 53
cara upaya hukum sebelum timbulnya
akibat hukum dan sesudah timbulnya
akibat hukum. Adapun upaya hukum
sebagai pencegahan akan timbulnya
akibat hukum yang mungkin terjadi
adalah dengan membuat Akta Perikatan
Pendahuluan Sewa Menyewa tanah
sedangkan upaya hukum yang dapat
dilakukan sesudah timbulnya akibat
hukum adalah dengan jalur litigasi atau
pengadilan baik dalam ranah hukum
pidana ataupun perdata.
Saran.
Sebaiknya membuat Akta Pendahuluan
Perikatan Sewa Menyewa Tanah terlebih
dahulu sebelum membuat Akta Sewa
Menyewa tanah dengan objek sewa yang
masih dalam bentuk pipil, yang mana
inti dari Akta Pendahuluan tersebut
adalah bahwa berisi kesepakatan dari
para pihak bahwa saat itu yang menjadi
objek dalam perjanjian itu adalah tanah
dalam bentuk pipil dengan menerima
baik ataupun pemegang pipil sesuai yang
tercantum dalam pipil tersebut,
disebutkan juga mengenai data yuridis
dan sporadik dari tanah tersebut, dan
kedudukan dari pipil itu saat
diperjanjikan apakah sedang dalam
proses konversi atau akan dilakukan
proses konversi ke bentuk sertipikat,
setelah sertipikat selesai maka
dibuatkanlah Akta Sewa Menyewa oleh
Notaris.
Dalam membuat Akta Notaris sebaiknya tetap
berpedoman kepada tata cara dan syarat yang
telah ditentukan oleh undang-Undang baik itu
UUJN ataupun KUHPerdata tentu saja dengan
tidak mengenyampingkan syarat sahnya
perjanjian dan asas-asas yang berlaku umum
dalam hukum perjanjian. Pembuatan Akta Notaris
diharapkan dengan teliti jangan sampai Akta yang
dibuat malah salah dan terdegradasi menjadi Akta
dibawah tangan yang jelas kekuatan
pembuktiannya tidak sempurna lagi, hal ini
bukannya memberikan kepastian hukum bagi para
pihak malah memunculkan sengketa dari para
pihak baik dalam ranah hukum pidana ataupun
perdata.
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Abdul Kadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni, Badung.
, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung
Adi Rianto, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 54
Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Peneletian Hukum, Cetakan ke IV, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.
Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan,
Alumni, Bandung.
Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah,
Republika, Jakarta
Muljadi, Kartini, 2004, Perikatan Pada Umumnya, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
*****
HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN DEPOSAN
Oleh
Robert Wiradinata*, Prof. R A. Retno Murni, SH.,MH., Ph.D**, Dr. Iketut Westra SH., MH**
Magister Kenotariatan Universitas Udayana
E-mail : [email protected]
ABSTRACT
ARRANGEMENT OF LAW RELATIONSHIP OF CREDIT AGREEMENT BETWEEN BANK WITH
DEPOSITOR
In modern era, business world cannot be separated with the bank as the financial institution.
Bank as credit giver always broaden its credit distribution as long as in bank‟s own point of view there
was a conviction that the credit distributed will be able to be returned by the debtor according to its
expectation. Thus, in credit giving the bank always ask for an assurance. Initially, the bank only accept
the rights upon the land or other moving property as an assurance but in next development the bank is
also able to accept deposit as an assurance. Practice of deposit as an assurance of debt in an assurance
legal system has not been arranged clearly and certainly.
Deposit as an assurance is important to be learned to find out about how is the arrangement of
legal relation between the bank and the depositor and how is the legal protection for the bank as credit
giver to the depositor in Bankruptcy Decision. Research about “The arrangement of Legal Relation of
Credit Agreement between the bank and the Depositor” use the research method of normative law with
legislation approach, which is related to the analysis of agreement law concept, and assurance law. The
legal material include the Law No.10 Year 1998 about the Banking of the Republic of Indonesia State
Sheet Year 1998 No.182, Additional of Sheet of the Republic of Indonesia State No.3790, the Law No.37
Year 2004 about Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Duty of the Republic of Indonesia State
Sheet Year 2004 No.131, Additional of Sheet of the Republic of Indonesia State No.4443, Civil Code.
This research shows that there are two legal relations between the depositor and the bank that is
the relation of capital lease and loan. So in the implementation of Bankruptcy Decision, the law
protection for the bank is very weak because the bank only has position as a congruent creditor.
Key words: Deposit, Legal relation, Credit Agreement, Bankruptcy.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pemilik deposito disebut deposan,
kepada setiap deposan akan diberikan imbalan
bunga atas depositonya. Bagi, bunga yang
diberikan kepada para deposan merupakan bunga
yang tertinggi, jika dibandingkan dengan
simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito
sebagian dianggap sebagai dana amal.1
1Kasmir, 2001, Dasar-dasar Perbankan,
PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,h.93.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 55
Pinjam meminjam uang yang
diselanggarakan oleh bank pada dasarnya disebut
dengan kredit, di Indonesia lembaga penyalur
kredit identik dengan bank.
Pemberian kredit yang diberikan oleh bank
kepada deposan mempunyai karakteristik yang
sangat khusus, terutama deposan sebagai debitur
dalam kredit yang diberikan oleh bank sebagai
pemegang deposito, tetapi sekaligus sebagai
kreditur dalam hubungannya sebagai pemilik
simpanan dana dalam bentuk deposito. Dalam
praktek pemberian kredit oleh bank kepada
deposan dilakukan dengan sistem back to back
yang pada hakekatnya bank memberikan
pinjaman sekaligus deposan menyerahkan
depositonya dengan surat kuasa. Dari perspektif
hukum jaminan kedudukan bank sebagai
pemegang kuasa atas deposito deposan,
mempunyai kedudukan yang sangat lemah
bilamana terjadi kepailitan, kepailitan adalah
ketiadamampuan untuk membayar dari seorang
(debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh
tempo2, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tetang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443 (untuk
selanjutnya disebut UU Kepailitan), Syarat
ketiadamampuan itu, harus disertai dengan
tindakan nyata untuk mengajukan, yang dilakukan
oleh debitur sendiri secara sukarela, maupun
permintaan dari pihak ketiga, suatu permohonan
pailit kepada pengadilan. Oleh karena itu perlu
adanya perlindungan hukum agar bank
mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap
deposito yang dipegangnya. Baik di dalam hukum
jaminan atau hukum perbankan, tidak ada
lembaga jaminan yang hanya diikat dengan surat
kuasa.
2Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999,
Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.11
Mengingat hak dan kewajiban debitur
adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban
kreditur maka selama proses itu tidak menghadapi
masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan yang
diperjanjiakan maka persoalan tidak akan muncul.
Namun biasanya persoalan baru muncul jika
debitur mengalami kepailitan, Jika terjadi
demikian Pasal 1131 KUH Perdata menentukan
bahwa semua kebendaan yang menjadi milik
seorang, baik yang sudah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi
perikatannya. Kekosongan norma mengenai
hubungan hukum antara deposan dengan
pemegang deposito akan menimbulkan
ketidakadilan bilamana terjadi keadaan pailitnya
deposan. Kepailitan seorang deposan
mengakibatkan seluruh harta benda deposan baik
yang sudah ada saat pailit maupun baru akan ada
setelah kepailitan akan menjadi budel pailit yang
pengelolaannya dilakukan oleh kurator. Dalam
keadaan demikian adalah tidak adil jika deposito
yang sebelumnya dipegang oleh bank dan
dipergunakan sebagai dasar untuk menimbulkan
keyakinan pemberian kredit akan ditarik untuk
kepentingan para kreditur-kreditur lainnya.
Berdasarkan permasalahan tersebut,
maka saya tertarik untuk melakukan penelitian
dalam bentuk Tesis dengan judul
“PENGATURAN HUBUNGAN HUKUM
PERJAN KREDIT ANTARA BANK
DENGAN DEPOSAN ”
1.2. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dibahas
dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengaturan hubungan
hukum dalam perjanjian kredit antara
bank dengan deposan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum
bagi bank dalam perjanjian kredit
antara bank dengan deposan,
bilamana deposan pailit ?

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 56
1.3. Tujuan Penelitian
a. Tujuan umum
Penelitian ini secara umum bertujuan
untuk mengembangkan ilmu Hukum terkait
dengan paradigma science as a prosess (ilmu
sebagai proses), dengan paradigma ini ilmu tidak
akan pernah mandeg (final) dalam penggaliannya
atas kebenarannya.3 Yaitu terkait dengan
Hubungan hukum pinjam meminjam uang antara
deposan dengan pihak bank .
b. Tujuan khusus
1. Menemukan konsep hubungan
hukum yang digunakan dalam
perjanjian pinjaman uang antara
bank dengan deposan yang
berkedudukan sebagai kreditur dan
debitur.
2. Untuk mengetahui Upaya hukum
yang dapat dilakukan oleh bank
dalam melindungi pinjamannya
kepada deposan dalam hal deposan
pailit.
1.4. Manfaat penelitian
a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan
bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran untuk
menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan
asas-asas yang berkaitan dengan Hubungan
hukum pinjam meminjam uang antara deposan
dengan bank.
b. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
sebagai sumbangan pemikiran untuk membantu
dan memberi masukan serta tambahan
pengetahuan untuk penyelesaian permasalahan
yang sama di dalam praktik.
1.5. Landasan Teoritis
1. Perjanjian
Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang
kemudian diterjemahkan oleh Prof. R, Subekti,
3Pedoman Penulisan Usulan Thesis
Hukum Normatif Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2011, h.52
S.H dan R. Tjitrosudibio menjadi KUH Perdata
bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam
Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut
mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan
yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang
berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu.4
Abdul Kadir Muhammad dalam
bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia”
berpendapat bahwa definisi perjanjian yang
dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata
tersebut memiliki kelemahan yaitu :
1. Hanya menyangkut sepihak saja.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa
konsensus.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas.
4. Dalam menyebut tujuan atau
memiliki tujuan yang jelas.5
Maka hubungan hukum antara perikatan
dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu
menerbitkan perikatan. Hubungan hukum adalah
hubungan yang menimbulkan akibat hukum,
akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak
dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu
kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan
beban. Adapun unsur-unsur yang tercantum
dalam hukum perjanjian dapat dikemukakan
sebagai berikut.6
1. Adanya kaidah hukum
2. Subyek hukum
3. Adanya prestasi
4. Kata sepakat
5. Akibat hukum
2. Teori Perlindungan Hukum
Teori Perlindungan Hukum.
4R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 1996,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek, Cet.28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,h. 323
5 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. H.224-225
6 Salim H.S, 2003, Hukum Perjanjian dan Teknik Penyusunan Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta, h.4.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 57
Teori perlindungan hukum dari Pareto,
jika suatu perjanjian dipandang dari sudut
ekonomi sebagaimana dipaparkan dalam teori
Pareto, suatu transaksi atau aturan adalah sah jika
membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik
dengan tidak seorangpun dibuat menjadi lebih
buruk.7 Dalam penelitian ini, teori ini digunakan
untuk menjamin kedudukan bank sebagai
lembaga penghimpun dana masyarakat agar
mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya
terhadap deposito deposan peminjam uang, dalam
hal deposan jatuh pailit.
3. Teori Kepastian Hukum
Sebagaimana yang diuraikan diatas
untuk memecahkan permasalahan hukum dalam
thesis ini terutama untuk menetapkan hubungan
antara deposan dengan bank pemberi kredit,
dalam perjanjian kredit juga didukung dengan
teori tentang asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang dikemukakan oleh Lon
I, Fuller. Menurut Fuller, agar hukum (peraturan)
berfungsi dengan baik, maka peraturan tersebut
harus memenuhi atau mengikatkan diri secara
ketat kepada 8 (delapan) syarat yang merupakan
asas-asas dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan.
Kepastian kata dasarnya adalah pasti,
yang memiliki arti : Suatu hal yang sudah tentu,
sudah tetap dan tidak boleh tidak.8 Gustaf
Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijber
mengenai kepastian hukum mengemukakan :
Menurut Radbruch dalam pengertian
hukum dapat dibedakan tiga aspek yang
ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai
pada pengertian hukum yang memadai.
Aspek yang pertama ialah keadilan
dalam arti yang sempit. Keadilan ini
berarti kesamaan hak untuk semua orang
7 Niken Saraswati, 2011, Standar Kontrak Dalam Hukum Perjanjian, Kennysiikebby’s Blog Just Another Wordpress. Com Site (11/06/2013), http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/03/07/ standar kontrak dalam hukum perjanjian
8 W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 847.
di depan pengadilan. Aspek yang kedua
ialah tujuan keadilan atau finalitas dan
aspek yang ketiga ialah kepastian hukum
atau legalitas.9
Dari dua teori mengenai kepastian
hukum diatas, teori Radbruch lebih mendekati
untuk dipergunakan sebagai penyelesaian
persoalan mengenai kepastian hukum berkaitan
dengan kedudukan bank sebagai penerima
deposito dengan hanya berdasarkan surat kuasa
yang pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan
sebagai kreditur preferent.
1.6 Metode Penulisan
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data skunder belaka.10
b. Jenis pendekatan
Pendekatan masalah yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach)
pendekatan konsep (conceptual approach),
pendekatan analitis (analytical approach).
c. Sumber bahan hukum
Penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan terhadap bahan hukum primer,
skunder dan tersier.
1. Bahan hukum primer, dalam penelitian
ini menggunakan bahan hukum primer
sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia Lembaran
9 Theo Huijbers, 2007, Filsafat Hukum
dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Cetakan Keempat belas, Yogyakarta, Hal. 163.
10 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2007,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h 13.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 58
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tetang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Adapun yang dimaksud dengan bahan
hukum sekunder dalam penelitian ini
adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal
ilmiah, karya tulis hukum atau
pandangan ahli hukum yang termuat
dalam media massa dan data sebagai
penunjang bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kamus
hukum dan ensiklopedia.
d. Teknik pengumpulan bahan
hukum
Bahan hukum yang relevan dikumpulkan
dengan teknik membaca, mengumpulkan bahan
hukum serta menganalisa bahan hukum dengan
menggunakan sistim kartu (card system)11
.
e. Teknik analisis bahan hukum
Analisis bahan hukum dalam penelitian
ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruktif
hukum dan argumentasi, yang selanjutnya
dilakukan dengan penilaian berdasarkan pada
alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum,
yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-
asas yang ada terkait dengan permasalahan.
II.1 Hubungan hukum
a. Pengertian Hubungan Hukum
Hubungan hukum terdiri dari dua kata
yaitu hubungan dan hukum. Sebelum
membicarakan hubungan hukum perlu dipahami
apa itu hukum, seperti yang dikatakan oleh Prof.
Apeldoorn hukum adalah kekuasaan yang
11 Winarno Surakhmad , 1973, Pengatar
Penelitian Ilmiah,Dasar-dasar Metode & Teknik ,Tarsito, Bandung, h.257.
mengatur dan memaksa, dengan tiada
berkesudahan ia mengatur hubungan-hubungan
yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat
manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan,
keturunan, kerabat darah, ketetanggaan tempat
kediaman, kebangsaan, dari perdagangan dan
pemberian berbagai jasa dan dari perkara-perkara
lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya
dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan
dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap
mereka dengan siapa ia berhubungan.12
Hukum
misalnya mengatur hubungan antara orang yang
meminjamkan uang dengan orang yang
menerimanya dan itu dilakukannya antara lain
dengan membentuk peraturan-peraturan.
Hubungan yang diatur oleh hukum sedemikian
disebut dengan hubungan hukum. Tiap-tiap
hubungan hukum, mempunyai dua segi yakni
pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak
yang lain ia merupakan kewajiban.
b. Jenis Jenis Hubungan Hukum
Sebagaimana telah diuraikan di atas
bahwa hukum mengatur Hubungan antara orang
dengan orang dalam kaitannya hubungan
perkawinan, hubungan keturunan, hubungan
kerabat darah. Jadi hubungan hukum itu tidak lain
adalah hubungan yang meletakkan disatu sisi hak
kepada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain.
Dari uraian mengenai hubungan hukum dapat
dipahami bahwa pada dasarnya hubungan hukum
merupakan yang mempunyai akibat hukum.
Demikian juga hubungan hukum yang disebut
perikatan terjadinya, berubahnya, hapusnya dan
beralihnya mempunyai akibat hukum.
BAB II
PEMBAHASAN
PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK
DENGAN DEPOSAN
III.1 Bentuk Perjanjian Kredit antara
Bank dengan Deposan
12Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h.1

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 59
Berdasarkan uraian Pasal 1 angka 11 UU
Perbankan ditegaskan bahwa kredit adalah suatu
bentuk perjanjian yaitu persetujuan antara
peminjam dan bank. Sebagai suatu perjanjian
menurut KUH Perdata, tidak terikat pada suatu
bentuk, artinya apakah perjanjian tersebut dibuat
secara tertulis atau tidak tertulis perjanjian tetap
memiliki daya mengikat bagi mereka yang
membuatnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 1338
KUH Perdata yang menyatakan :
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,
atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di
atas dapat dipahami bahwa dari segi bentuk
perjanjian undang-undang tidak mengharuskan
perjanjian dibuat dengan bentuk tertulis maupun
tidak tertulis demikian juga dari segi isinya
Undang-undang menyerahkan kepada para pihak
yang membuat perjanjian tersebut, walaupun
demikian didalam beberapa perjanjian asas ini
dikecualikan seperti didalam perjanjian peralihan
hak atas tanah, perjanjian pemberian hak
tanggungan dan fidusia, menurut undang-undang
harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk akta
notaris.
Berdasarkan proses pembuatan
perjanjian kredit antara bank dengan deposan
dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut
menurut ilmu hukum dikenal dengan nama
perjanjian baku atau standard kontrak.
III.2 Hubungan Hukum antara Bank
dengan Deposan dalam Perspektif
Hukum Perjanjian
Pada dasarnya hubungan hukum antara
bank dengan nasabahnya dapat terjadi dua
hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara
bank dengan nasabah penyimpan dana dan
hubungan hukum antara bank dan nasabah
debitur.
A. Hubungan hukum antara bank
dengan nasabah penyimpan dana
Bentuk hubungan hukum antara bank
dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari
hubungan hukum yang muncul dari produk-
produk perbankan, seperti deposito, tabungan,
giro dan sebagainya.
Perjanjian bank dengan nasabah
penyimpan disebut perjanjian simpanan. Dalam
hukum perdata, figur perjanjian simpanan akan
menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak
terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan
identitas hukumnya.13
Jika dicermati terkait objek
dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito,
sertifikat deposito dan tabungan, maka tidak
ditemukan baik dalam KUH Perdata maupun
dalam KUH Dagang. Namun, sebagai perjanjian,
terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1319 yaitu
semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu
nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan
nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan
umum....”
B. Hubungan hukum antara bank
dengan nasabah debitur
Hubungan hukum antara bank dan
nasabah penyimpan serta hubungan hukum antara
bank dan nasabah debitur sangat erat kaitannya.
Kedua hubungan tersebut tidak hanya
dikualifikasikan sebagai hubungan hukum tetapi
penting kiranya untuk menarik pada hubungan
moral. Sebagai hubungan moral, maka
pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata
hukum. Moral ini kemudian dapat menjadi
sumber dan sekaligus jembatan etis dalam
tonggak hukum perbankan. Dengan demikian,
dalam pelaksanaan fungsi perbankan terdapat dua
hubungan hukum dan satu hubungan moral yang
saling terkait.
13 Kamello Tan, 2006, karakter Hukum
Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dan Nasabah, Pidato Guru Besar Usu, h.22

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 60
III.3 Hak dan Kewajiban antara Bank
dengan Deposan dalam Perjanjian
Kredit
Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank
dengan deposan, memberikan hak dan kewajiban
kepada dua belah pihak. Kewajiban bank setelah
perjanjian kredit itu dibuat dengan deposan adalah
:
a. Memberikan sejumlah uang berupa
pinjaman kepada si berutang sesuai
dengan jumlah yang diperjanjikan.
b. Dalam hal hasil pencairan deposito
melebihi jumlah hutang yang timbul
berdasarkan perikatan termaktub telah
dilunasi sebagaimana mestinya, bank
harus menyerahkan kembali simpanan
dalam rekening deposito.
c. Bila seluruh kewajiban si berhutang
yang timbul berdasarkan perikatan telah
dilunasi sebagaimana mestinya, bank
harus menyerahkan kembali simpanan
dalam rekening deposito.
Sedangkan hak-hak dari bank dalam
perjanjian kredit dengan deposan antara lain :
a. Bank berhak mengenakan bunga atas
pinjaman deposan yang besarnya sesuai
dengan yang telah disepakati.
b. Bank bilamana fasilitas kredit yang
dijamin dengan deposito belum dilunasi
sebagaimana mestinya maka bank
berhak mencairkan atau menguangkan
simpanan dalam rekening deposito dan
memindah bukukannya ke rekening
pinjaman si deposan sewaktu-waktu
sebesar sisa fasilitas kredit.
Setelah perjanjian kredit disepakati dan
ditandatangani oleh bank dan deposan, maka
deposan berhak untuk menerima sejumlah uang
sebagai pinjaman (kredit) dari pihak bank.
Kewajiban deposan
a. Membuat surat kuasa untuk kepentingan
bankyang bersifat substitusi.
b. Deposan wajib mengembalikan uang
pinjaman dalam jangka waktu dan
jumlah sesuaai apa yang telah disepakati.
c. Deposan berkewajiban untuk membayar
bunga atas pinjaman kepada bank.
d. Menyerahkan sertifikat deposito sebagai
jaminan kepada bank.
IV.1 Kebersamaan Kreditur terhadap
Kebendaan Debitur
Dalam hubungan hukum keperdataan
hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak
perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh
keseimbangan antara hak dan kewajiban satu
pihak dengan pihak yang lain, agar setiap orang
dapat melakukan hubungan hukum dengan rasa
aman khusunya dalam bidang perikatan maka
berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 1131
KUH Perdata menyatakan bahwa dapat dipahami
adanya asas-asas hubungan ekstern kreditur
sebagai berikut :
a. Seorang kreditur dapat mengambil
pelunasan dari setiap bagian dari harta
kekayaan debitur
b. Setiap bagian kekayaan debitur dapat
dijual guna pelunasan tagihan kreditur
c. Hak tagihan kreditur hanya dijamin
dengan harta benda debitur saja, tidak
dengan ”person debitur”.
Jaminan seperti itu diberikan kepada
setiap kreditur terhadap seluruh harta debitur dan
karenanya disebut jaminan umum. Setiap kreditur
menikmati hak jaminan umum seperti itu.
Hal itu tidak berarti, bahwa kreditur
harus menjual seluruh kekayaan debitur, lalu
mengambil suatu bagian sebanding tertentu dari
hasil penjualan dari tiap-tiap benda yang
membentuk kekayaan tersebut. Penjualan seluruh
harta kekayaan debitur hanya terjadi dalam hal
ada kepailitan dan dalam penerimaan boedel
dengan hak utama untuk mengadakan pencatatan
(penerimaan warisan secara beneficiarvide Pasal
1023, Pasal 1024, dan Pasal 1034 KUH Perdata).

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 61
IV.2 Pembayaran Piutang melalui Proses
Kepailitan dalam Perjanjian Kredit
Pembayaran piutang dari si pailit setelah
adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada
si pailit, jika hak tersebut dilakukan maka tidak
membebaskan utang tersebut. Begitu pula
terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan
kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh
ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan
harus oleh atau kepada kurator. Akan tetapi,
apabila tuntutan tersebut dajukan atau diteruskan
oleh atau terhadap debitur pailit, maka apabila
tuntutan tersebut mengakibatkan suatu
penghukuman terhadap debitur pailit,
penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat
hukum terhadap harta pailit, penghukuman
tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap
harta pailit.
Disamping itu pula, selama
berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk
memperoleh pemenuhan perikatan dari harta
pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit,
hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya
untuk dicocokkan. Sedangkan suatu tuntutan
hukum di pengadilan yang diajukan terhadap
debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh
pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan
perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum
dengan diucapkan putusan pernyataan pailit
terhadap debitur.
IV.3 Perlindungan Hukum bagi Bank
dalam Perjanjian Kredit dalam hal
Deposan Pailit.
Dalam kaitan perjanjian kredit antara
bank dengan deposan walaupun deposan telah
memiliki deposito di bank yang memberi
pinjaman, tetapi tidak cukup menjamin kepastian
pengembalian kredit dari bank, bilamana debitur
atau deposan jatuh pailit. Jika deposan dalam
keadaan pailit, maka berlakulah asas kebersamaan
dari tiap-tiap kreditur untuk mendapatkan
pelunasan piutangnya sebagaimana diatur dalam
psaal 1131 KUH, dari Pasal tersebut dapat
dicermati ada dua jenis kreditur yaitu kreditur
konkuren dan kreditur preferen, kreditur konkuren
adalah kreditur yang memiliki kedudukan yang
sama dengan sistem pembayaran dengan sistem
perseimbangan sesuai dengan jumlah piutangnya
sedangkan yang dimaksud dengan preferen adalah
kreditur yang mempunyai hak didahulukan
pelunasan piutangnya. Sehingga hanya kreditur
preferenlah yang memiliki kepastian akan
pengembalian piutangnya jika jumlah harta
kekayaan debitur kurang dari jumlah piutang yang
dimiliki oleh kreditur. Lembaga jaminan yang
dapat dibebankan pada benda debitur tergantung
pada jenis benda yang dipergunakan sebagai
jaminan. Oleh karena itu lembaga jaminan yang
dapat dibebankan kepada hak deposito hanya
berupa gadai.
IV.4 Akibat Hukum Kepailitan Deposan
terhadap Kebendaan Debitur
Dalam hal deposan pailit, berdasarkan
keputusan kepailitan untuk pembayaran piutang
bagi kreditur deposan berlakulah tingkatan-
tingkatan bagi penggolongan kreditur, sehingga
jika deposito tidak diikat dengan lembaga
jaminan, baik itu gadai atau fidusia maka bank
sebagai pemegang deposito yang telah
memberikan pinjaman kepada deposan akan
mempunyai kedudukan konkuren atau bersaing
dengan kedudukan lain. Jika harta kekayaan
deposan termasuk depositonya mencukupi untuk
membayar utang-utangnya tidaklah muncul
masalah dalam pelunasan-piutang kreditur-
krediturnya, tetapi masalah kedudukan menjadi
kreditur preferent menjadi penting jika jumlah
harta kekayaan deposan kurang dari jumlah utang
yang harus dibayar, sehingga para kreditur
konkuren tidak mendapat jaminan untuk
pembayaran piutangnya secara optimal. Sehingga
untuk menjamin pelunasan piutang bank yang
telah memberikan kredit kepada deposan

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 62
semestinya deposito yang dipergunakan sebagai
jaminan dilanjutkan dengan mengikat deposito itu
dengan lembaga jaminan gadai atau fidusia.
BAB III
PENUTUP
Berdasarkan uraian dalam Bab-bab
sebelumnya, dapat disimpulkan
1. Pengaturan hubungan hukum mengenai
perjanjian kredit antara bank dengan
deposan belum ada pengaturannya, tetapi
berdasarkan hubungan hukum yang
terjadi didalam perjanjian kredit tersebut
dapat dikontruksikan kedalam hubungan
hukum sewa menyewa modal dan
pinjam meminjam.
2. Perlindungan hukum bagi bank pemberi
kredit kepada deposan hanya dengan
kuasa mencairkan deposito bilamana
deposan wanprestasi sangat lemah,
karena dalam penyelesaian hutang
piutang melalui Keputusan Kepailitan,
bank hanya memiliki kedudukan sebagai
kreditur konkuren atau bersaing dengan
kreditur-kreditur yang lainnya.
Saran
1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum
dalam dunia perbankan dan perlindungan
nasabah bank, perlu adanya ketentuan yang
pasti mengenai konsep hubungan hukum
antara bank dengan deposan berkaitan
dengan penyimpanan dana masyarakat.
2. Untuk menjamin perlindungan hukum
terhadap bank sebagai kreditur dalam
perjanjian kredit, antara bank dengan
deposan yang mempergunakan deposito
sebagai jaminan, tidaklah cukup dengan
pemberian kuasa dari deposan kepada bank
untuk memperoleh pelunasan melalui
pelaksanaan keputusan pailit. Oleh karena itu
perlu adanya upaya preventif dengan
perjanjian pengikatan jaminan terhadap
deposito. Mengingat deposito tergolong
kedalam benda bergerak maka lembaga
jaminan gadai atau fidusia yang tepat
dibebankan pada deposito tersebut.
Daftar Pustaka
Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
__________________, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung.
Apeldoorn, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
A. Pitlo, 1952, Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands Burgelijk Wetboek, H.D Tjeeng
&Zoon, NV Harlem.
Algra,1974, inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht, Tjeen Willink, Groningen.
Bambang Sutiyoso,2009, Metode penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan
Berkeadilan,UII. Press, Yogyakarta.
Djumahana, 1996, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
C.H Gatot Wardoyo, 1996, Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
H.F.A. Vollmar, 1984, Studi Hukum Perdata Jilid II, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta,
Rajawali, Jakarta.
H. Budi Untung, 2005, Kredit Perbankan Indonesia, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
H.R Daeng Naja,2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 63
H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2005, Credit Management Handbook (teori,
konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiwa, Bankir dan Nasabah), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Henry Campbell Black, 1979, Black‟s Dictionary, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
Ibrahim R. Perna-Pernik Yuridis dalam Nalar Hukum. 2006 UPT-Penerbit.
Jazim Hamidi,2005, Hemeneutika Hukum Teori penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi
Teks,UII Press, Yogyakarta
Johny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publising,
Malang.
J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
_______, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian-Buku I, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Jerry Hoff, 1999, Indonesian Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta.
Kasmir,2007, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi keenam, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
______,2008, Pemasaran Bank, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
______, 2011, Dasar-dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta.
Kartono, 1982, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Kartini Mulyadi, 2001, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Alumni, Bandung.
_________, Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan , Undang-undang
Kepailitan dan perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-
Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004 : Jakarta26-28 Januari
2004 ( Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
_______, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
Lon, l Fuller,1963, The Morality of Law, New Haven and London Yale University Press
Lukman Santosa, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Mariam Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.
Mariam Darus Badrulzaman,1978, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung.
Mariam Darus Baadrulzaman, et all, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka
Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Mertokusumo, 1987, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta.
_____________, 2005, Mengenal Hukum suatu Pengantar
Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta.
Pedoman Penulisan Usulan Thesis Hukum Normatif Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Udayana, 2011.
Nasrun Yasabari & Nina Kurnia Dewi 2007, Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK mengakses
Pembiayaan, Alumni, Bandung.
Philipus M hadjon,1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 64
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenata Media Group, Jakarta
___________________ , 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan
Burgerlijk Wetboek, Cet.28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
R. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, cetakan 18, Intermasa, Jakarta.
Rony Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi penulisan Hukum, dan Jurimetri, Cet III, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Rachmadi Usman,2003, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Ricardo Simajuntak, 2005, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Pusat Pengkajian
Hukum, Jakarta.
Salim H.S, 2003, Hukum Perjanjian dan Teknik Penyusunan Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta.
________, 2003,Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Subekti, 1976, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2007,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.
Suta Reny Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para
Pihak Kredit Bank, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
Sudirman I Wayan, 2013,Manajemen Perbankan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Suyatno, 1990, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta.
Samsudin, 2004, Prinsip Kehati-hatian dalam Hubungan Kontraktual Nasabah dan Deposan Bank,
Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat.
Thomas Suyatno dkk, 1993, Dasar-Dasar Perkreditan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas PT
Gramedia Pusaka Utama.
Theo Huijbers, 2007, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Cetakan Keempat belas,
Yogyakarta.
Winarno Surakhmad, 1973, Pengatar Penelitian Ilmiah,Dasar-dasar Metode & Teknik Tarsito,
Bandung.
Wiryono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbit
Sumur Bandung, Bandung.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tetang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 65
Bahan Internet :
Niken Saraswati, 2011, Standar Kontrak Dalam Hukum Perjanjian, Kennysiikebby‟s Blog Just
Another Wordpress. Com Site (11/06/2013),
http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/03/07/ standar kontrak dalam hukum perjanjian
W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta
*****
PENGATURAN PENCEGAHAN KEPAILITAN MELALUI KOMBINASI INSOLVENCY TEST,
REORGANISASI PERUSAHAAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Oleh
Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra*, R.A. Retno Murni**, I Made Pria Dharsana***
Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Email: [email protected]
ABSTRACT
Bankruptcy law in Indonesia is obliged to observe and comply with the regulations set out in Law
No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Obligation Payment (PKPU). The
requirements of bankruptcy decision are stipulated in Article 2 paragraph (1). These regulations cause
problems due to the vagueness of norms; that the bankruptcy terms are too simple, so it would cause the
debtor who actually still in good financial state sentenced into the bankruptcy state. A mechanism of
protection for both debtors and creditors is needed so they are not harmed in the bankruptcy process.
Therefore a regulation of bankruptcy prevention through a combination of Insolvency Test, Corporate
Reorganization and PKPU is needed, so that bankruptcy law can be applied in line with the objectives of
national economic development. Based on this, the problems those can be formulated are about what the
major on regulation of combination system of Insolvency Test, Corporate Reorganization and PKPU and
how the prevention regulation of a company tangled on bankruptcy by using combination system of
Insolvency Test, Corporate Reorganization and PKPU.
Keywords : Regulation, Prevention, Bankruptcy, Insolvency Test, Reorganization, PKPU
*Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2012
**Pembimbing I
***Pembimbing II
I. PENDAHULUAN
Pailitnya suatu perusahaan seringkali bukan
merupakan keinginan dari berbagai pihak. Hal ini
disebabkan oleh banyaknya dampak negatif yang
dapat ditimbulkan oleh karena kepailitan ini, yang
tentunya dapat berdampak buruk, tidak hanya
bagi debitur dan kreditur, namun juga distributor,
pembeli, perusahaan retail, juga Negara dapat
kehilangan sumber pendapatannya dari sektor
pajak, konsumen, dan pada tingkat tertentu dapat
menyebabkan meningkatnya tingkat
pengangguran karena terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Secara umum,
meningkatnya kasus kepailitan ini akan
menimbulkan efek buruk bagi perekonomian
nasional.
Apabila kondisi perusahaan sedang ada
dalam kondisi ekonomi tidak baik, akan lebih
menguntungkan apabila dilakukan reorganisasi
terlebih dahulu untuk menghindari pailit.
Pencegahan kepailitan dengan cara reorganisasi
perusahaan dapat menghindarkan perusahaan dari
status dilikuidasi.
Selain dengan menerapkan reorganisasi
perusahaan, perlu juga dilakukan suatu proses
yang disebut dengan Insolvency Test. Menurut

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 66
James Purba, Insolvency test adalah suatu
keadaan untuk menguji kemampuan debitor
dalam membayar kewajiban. Merujuk
ke insolvency test yang diatur dalam mekanisme
kepailitan Amerika Serikat serta negara penganut
common law system lainnya seperti Inggris,
sebuah perusahaan yang dimohonkan pailit harus
melewati mekanisme ini lebih dulu. Artinya,
perusahaan baru bisa dimohonkan pailit jika
perusahaan benar-benar sudah dalam keadaan
bangkrut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor
37 tahun 2004 tentang Kepailitan (selanjutnya
disebut UU Kepailitan) membuka kesempatan
yang cukup luas kepada kreditor untuk
mempailitkan suatu debitor. Asalkan permohonan
kepailitan memenuhi Pasal 2 ayat (1) junctoPasal
8 ayat (4) UU Kepailitan. Keadaan ini merupakan
keadaan Norma Kabur. Alhasil, debitor dapat
diputus pailit tanpa melihat kemampuan untuk
menyelesaikan utang. Jamesmenilai membangun
perusahaan itu tidak cepat dan gampang. Selain
itu, demi kesehatan bisnis dan investasi,
insolvency test perlu dipertimbangkan dalam
revisi UU Kepailitan.1
Apabila Indonesia mengadopsi konsep ini,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu
perlu metode untuk menentukan tingkat kesehatan
suatu perusahaan. Selain itu, syarat permohonan
pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2
UUKepailitan juga perlu diubah, menjadi debitor
yang tidak lagi mampu membayar utang.
Negara-negara di dunia mengenal dua
konsep kepailitan, yaitu insolvency test dan
simply doesn‟t pay. Konsep insolvency test dalam
kepailitan lebih menekankan kepada
ketidakmampuan perusahaan dalam membayar
utang-utangnya. Sedangkan simply doesnt
pay, suatu proses atau cara lain dalam menagih
1 James Purba, sebagaimana dikutip dari
Hukumonline.com (diakses pada tanggal 15
Januari 2013), available from: URL:
http://www.hukumonline.com/be-rita/baca
/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan-untuk-
lindungi-debitor
utang asalkan terpenuhi syarat permohonan
kepailitan. Indonesia menganut konsep yang
kedua.2
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
sekarang ini memiliki kelemahan, yaitu membuka
peluang bagi perusahaan yang masih berpotensi
untuk berkembang untuk dijatuhi putusan pailit.
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya
memberikan pranata hukum dalam kerangka
prinsip debt forgiveness yang berupa moratorium
utang debitor atau yang dikenal dalam Undang-
undang Kepailitan dengan nama Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Sedangkan rehabilitasi dalam Undang-Undang
Kepailitan adalah rehabilitasi setelah seluruh
utang-utang debitor terselesaikan, dan bukan
rehabilitasi yang berbentuk fresh-starting..
Permasalahan kepailitan di Indonesia terkait
dengan pelaksanaan undang-undang kepailitan
masih jauh dari harapan. Justru banyak
permasalahan kepailitan timbul oleh karena
lemahnya formulasi aturan hukum, secara
khususnya undang-undang kepailitan, karena
terdapat kekaburan norma mengenai syarat-syarat
kepailitan, serta keksosongan norma karena tidak
adanya mekanisme filter penghidaran kepailitan
seperti Insolvency Test dan Reorganisasi
Perusahaan.
Hal-hal tersebut di atas-lah yang semakin
memberikan gambaran betapa penting dan
perlunya perubahan terhadap Undang-undang
Kepailitan Indonesia. Menjadi penting dan perlu
oleh karena perkembangan ekonomi Indonesia
yang cenderung cepat memerlukan dukungan
perangkat hukum memadai serta sekaligus dapat
memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.
Sehubungan dengan latar belakang di atas
maka menarik untuk dilakukan penelitian serta
kemudian serta menuangkan dalam bentuk artikel
ilmiah yang berjudul : “Pengaturan Pencegahan
Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test,
2 ibid

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 67
Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang”.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
maka dapat dikemukakan rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi pokok utama dalam
pengaturan sistem kombinasi
Insolvency Test, Reorganisasi
Perusahaan dan PKPU?
2. Bagaimana pengaturan pencegahan
suatu perusahaan terjerat kepailitan
dengan sistem kombinasi Insolvency
Test, Reorganisasi Perusahaan dan
PKPU?
Tujuan umum penelitian atas permasalahan
di atas adalah untuk pengembangan ilmu hukum
khususnya di bidang Hukum Kepailitan yang
berkaitan dengan usaha penyelamatan perusahaan
dari jerat kepailitan. Adapun tujuan khusus yang
ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini, yakni:
a. Untuk mengetahui mekanisme
pengaturan pencegahan suatu
perusahaan terjerat kepailitan dengan
sistem kombinasi Insolvency Test,
Reorganisasi Perusahaan dan PKPU
dalam upaya penyelamatan suatu
perusahaan dari jerat kepailitan;
b. Untuk memberikan pandangan
mengenai alasan perlunya revisi
terhadap Undang-undang Kepailitan
Indonesia dengan menerapkan sistem
gabungan PKPU dengan insolvency
Test dan Reorganisasi Perusahaan;
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah
penelitian hukum normatif (yuridis normatif)
dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian
adalah analisis dari adanya norma kabur dalam
hal sumirnya syarat untuk dapat mengajukan
gugatan kepailitan, serta kekosongan norma oleh
karena tidak adanya perlindungan bagi
perusahaan yang secara finansial masih sehat dari
jerat kepailitan oleh karena ketiadaan suatu sarana
pengujian terlebih dahulu untuk dapat
menentukan apakah suatu perusahaan itu layak
untuk digugat pailit ataukah tidak layak. Salah
satu caranya adalah denga melakukan insolvency
test dengan dikombinasikan PKPU dan
Reorganisasi perusahaan.
II. KERANGKA TEORI
III. Teori Kepailitan: Teori Berdasarkan Nilai
(Value-based Theory)
Donald R. Korobkin3 mengusulkan teori
berbasis nilai ini. Teori berbasis nilai objek
menolak anggapan bahwa debitur hanya sebagai
“kolam aset” belaka, yaitu properti atau benda
mati. Teori ini menekankan bahwa debitur
memiliki kepribadian dan potensi yang dinamis.4
Menurut teori ini, hukum kepailitan merupakan
respon penuh untuk semua masalah yang timbul
dari kesulitan keuangan , tidak hanya ekonomi
tetapi juga moral, politik, pribadi dan sosial.5
Masalah yang timbul dari kesulitan keuangan
yang begitu rumit sehingga jawabannya harus
diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk
menentukan secara bersama jalan keluar dari
permasalahan tersebut. Teori berbasis nilai
menyimpulkan bahwa hukum kepailitan tidak
hanya respon terhadap masalah mengumpulkan
utang , dan tujuan dari hukum kepailitan adalah
untuk mengatasi masalah kesulitan keuangan dan
menciptakan kondisi ideal di mana kondisi
keuangan para pihak mungkin direhabilitasi
menjadi suatu visi yang koheren dan informatif
tentang apa yang mesti dilakukan oleh
perusahaan. Sejalan dengan itu, reorganisasi
dalam hukum kepailitan adalah untuk
merehabilitasi dan membentuk kembali kembali
nilai-nilai dari debitur untuk mencapai suatu
keadaan perusahaan yang lebih baik.
3 Donald R. Korobkin, 1991, “Rehabilitating
Values: A Jurisprudence pf Bankruptcy”,
Columbia Law Review, Vol.91, Mai 1991, No.4,
hal.717 4 Ibid, hal.744 5Ibid, hal. 789

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 68
IV. PEMBAHASAN
A. Pengertian Insolvency Test
Masalah Insolvency merupakan hal yang
esensial dalam hukum kepailitan. Pengadilan baru
dapat menjatuhkan putusan pernyataan pailit
apabila debitor berada dalam keadaan insolvensi.
Pentingnya lnsolvensi dalam hukum kepailitan
oleh karena merupakan salah satu syarat
pernyataan pailit di samping Concursus
Creditorum.
Praktek yang umum dalam dunia bisnis
sering menghubungkan antara Insolvency dan
bankruptcy. Praktisi ekonomi sering
menghubungkan atau menganggap Insolvency
sebagai suatu keadaan terbatasnya liability dari
suatu perusahaan. Kata bankruptcy digunakan
untuk mendiskripsikan prosedur Insolvency.6
Menurut Dictionary of Business
Term7, Insolvency diartikan :
1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi
kewajiban finansial ketika jatuh waktu
seperti layaknya dalam bisnis; atau
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan
dengan asetnya dalam waktu tertentu.
Pengertian insolvency juga dapat ditemukan
dalam kamus hukum. Black‟s Law Dictionary
mengartikan Insolvency sebagai:
The condition of a person who is insolvent;
inability to pay one's debts; lack of means to
pay one's debts. Such a relative condition of
a man's assets and liabilities that the former,
if all made immediately available, would not
be sufficient to discharge the latter. Or the
condition of a person who is unable to pay
his debts as they fall due, or in the usual
course of trade and business.8
(Terjemahan bebasnya: suatu kondisi dari
seseorang yang insolvent; ketidak- mampuan
untuk membayar utang-utang terhadap suatu
6 Barry Cahir et. al., 2003, Insolvency Law;
Professional Practice Guide, Cavedish
Publishing, Ireland, hal.1 7 David L. Scott, 2009, “Insolvency” The
American Heritage Dictionary of Business Term,
Houghton Mifflin Harcourt, Boston, New York,
hal. 1907 8 Henry Campbell Black, 1979,
“Insolvency” Black‟s Law Dictionary, West
Publishing Co., St. Paul Minnasota, hal.
pihak; kurang dalam hal membayar utang-
utangnya. Suatu keadaan yang relatif dari
asset-aset seseorang dan kewajiban-
kewajiban dari yang awal, apabila
keseluruhannya dibuat tersedia segera, tidak
akan mampu untuk melunasi yang
berikutnya. Atau suatu kondisi seseorang
yang tidak dapat membayar utang-utang
sebagaimana telah jatuh tempo, atau dalam
tujuan yang biasa dalam perdagangan dan
bisnis.)
Berikutnya adalah indikasi dan faktor-faktor
penyebab yang dapat mengarahkan suatu
perusahaan untuk kemudian dikategorikan dalam
keadaan insolvent. Yang sudah jelas adalah
keadaan insolvent dapat menjadi indikasi terhadap
perusahaan-perusahaan yang berada dalam
kondisi berhenti membayar utang-utangnya dan
utang-utang tersebut belum lunas. Namun apabila
meminjam teori dalam ilmu ekonomi, dapat
ditemukan ada suatu keadaan perusahaan yang
kemudian sangat memungkinkan sebagai
penyebab perusahaan tersebut menjadi tidak dapat
membayar utang-utangnya dan kemudian
dimasukkan dalam kategori insolvent. Keadaan
tersebut ditandai dengan penurunan tingkat
keuangan perusahaan dan dikenal dengan istilah
Financial Distress. Kondisi financial distress
perusahaan didefinisikan sebagai kondisi di mana
hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk
memenuhi (melunasi) kewajiban (utang-utang)
perusahaan (dalam keadaan Insolvency).9
Insolvency dapat dibedakan dalam kategori,
yaitu10
:
1. Technical Insolvency
Jenis ini bersifat sementara dan
munculnya karena perusahaan
kekurangan kas untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban jangka pendek.
2. Bankruptcy Insolvency
Jenis ini bersifat lebih serius dan
munculnya ketika total nilai hutang
9 David L. Scott, loc.cit.
10 Steven V. Campbell, 1996, “Predicting
Bankruptcy Reorganization for Closely Held
Firms”, Accounting Horizons, Vol 10, 3, hal.12-
25

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 69
melebihi nilai total aset perusahaan atau
nilai ekuitas perusahaan negatif.
Banyak faktor yang dapat menyebabkan
perusahaan menghadapi financial distress yaitu
antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi
berlebihan, ketinggalan teknologi, kondisi
persaingan, kondisi ekonomi, kelemahan
manajemen perusahaan dan penurunan aktifitas
perdagangan industri. Dalam kondisi ekonomi
yang tidak buruk, kebanyakan perusahaan yang
mengalami financial distress adalah akibat dari
kelemahan manajemen.11
Pengertian “Test” dalam Oxford Dictionary
of English 12
, apabila diartikan sebagai kata
benda, maka diartikan sebagai “a procedure
intended to establish the quality, performance, or
reliability of something, especially before it is
taken into widespread use.” (Terjemahan
bebasnya: suatu prosedur yang dimaksud untuk
menentukan kualitas, kemampuan, atau ketahanan
dari sesuatu, secara khusus sebelum hal tersebut
atau sesuatu tersebut digunakan secara luas.), dan
apabila diartikan dalam hubungannya sebagai
suatu frase, seperti kedudukannya pada istilah
Insolvency Test maka Test diartikan sebagai: “find
out how useful, strong, or effective someone or
something is.” (Terjemahan Bebasnya: “untuk
mengetahui seberapa berguna, kuat, efektif
seseorang atau sesuatu.” Tentunya hal ini
mengenai kata yang menjadi pasangannya dalam
membentuk frasa), dalam hal Insolvency Test
maka dapat diartikan sebagai suatu prosedur
untuk menentukan apakah suatu (perusahaan)
memenuhi unsur-unsur tertentu atau kualifikasi
tertentu untuk dapat dikategorikan masuk dalam
keadaan Insolvent.
Michael Quinn dalam bukunya memberikan
dua hal yang menjadi test atau ujian untuk dapat
11
Ibid. hal .36 12
Anonim, 2010, “Test” Oxford Dictionary
of English, Oxford University Press, United
Kingdom, hal.
memasukkan suatu perusahaan dalam kategori
Insolvent.13
There are two tests for establishing
insolvency:
a) The „cash flow‟ test, which require
showing that the company is unable to
pay its debt as they fall due for
payment; and
b) The „balance sheet‟ test, which
depends on showing that the value of
the company‟s assets is insufficient to
meet its liabilities, including (for
certain statutory purposes) contingent
and prospective liabilities.
(Terjemahan Bebasnya: Ada dua tes atau
ujian untuk menentukan keadaan insolvent:
a) Tes „aliran kas‟, yang mana
mewajibkan untuk menunjukkan
bahwa perusahaan tidak dapat
membayar sebagaimana seharusnya
pembayaran pada saat jatuh tempo;
dan
b) Tes „neraca‟, yang mana tergantung
pada waktu menunjukkan bahwa nilai
aset-aset perusahaan tidak mencukupi
untuk melunasi kewajiban-
kewajibannya, termasuk (untuk tujuan
hukum tertentu) kewajiban yang
sifatnya merupakan kesatuan dan
prospektif.
Pelaksanaan dan penerapan insolvency test
di berbagai Negara memiliki variasi istilah
tersendiri. Salah satu istilah lain yang digunakan
adalah solvency test. Tidak jauh dari tujuan
insolvency test, pada hakekatnya solvency test
merupakan suatu metode pengujian yang identik
hanya saja masing-masing melihat dari sudut
yang berbeda. Insolvency test melihat dari sudut
pandang ketidakmampuan membayar utang,
sedangkan solvency test melihat dari sudut
pandang kemampuan membayar. Metode yang
digunakan sama-sama bisa dipakai oleh keduanya
hanya saja kesimpulan yang ingin dicapai berbeda
secara sudut pandang.
J.B. Heaton dalam tulisannya menjabarkan
mengenai pendekatan-pendekatan yang dapat
digunakan untuk melakukan solvency test.
Menurutnya ada tiga bentuk pendekatan yang
dapat digunakan untuk melakukan solvency test
yaitu:
13
Barry Cahir et. al., Op. Cit., hal.2

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 70
a test of whether a firm reasonably can
be expected to pay its debts as they come
due (the ability-to-pay solvency test,
sometimes referred to as cash-flow
solvency or equitable solvency),
a test of whether the fair value of a
firm‟s assets exceed the face value of its
liabilities (the balance-sheet solvency
test, performed on either a going-
concern or liquidation basis), and
a much less well defined test of whether
a firm has adequate capital (the capital-
adequacy solvency test)14
(Terjemahan bebasnya:
tes apakah suatu perusahaan cukup dapat
diharapkan untuk membayar hutangnya
pada saat jatuh tempo (solvency test atau
uji solvabilitas mengenai kemampuan
untuk membayar, kadang-kadang disebut
sebagai uji solvabilitas arus kas atau uji
solvabilitas yang berimbang),
tes apakah nilai wajar aset perusahaan
melebihi nilai nominal kewajiban (uji
solvabilitas neraca, dilakukan pada baik
perusahaan yang masih going concern
atau perusahaan yang pada dasarnya
akan likuidasi), dan
tes yang kurang lebih didefinisikan
sebagai ujian apakah perusahaan
memiliki modal yang memadai (uji
solvabilitas kecukupan modal))
Heaton menambahkan, dalam menerapkan
pendekatan sebagai acuain solvency test tersebut
di atas tidak selalu mudah. Lebih mudah untuk
mendefinisikan daripada menerapkannya dalam
kenyataan. Yang sering kali menjadi pertanyaan
bagi para praktisi hukum adalah apakah ada
metode yang terbaik di antara ketiga jenis
pendekatan tersebut ataupun di luar ketiganya
yang mampu diterapkan, terutama bagi semua
kasus? Jika secara teoritis disimpulkan,
jawabannya adalah tentu saja ada. Yang sering
dianggap merupakan pendekatan yang optimal
adalah pendekatan dengan menggunakan the
ability-to-pay solvency test. Pendekatan ini
dianggap paling mampu menangkap apa yang
menjadi kehendak atau apa yang paling
diharapkan oleh kreditur; dalam hal ini kesesuaian
mengenai piutang mereka yang sudah jatuh tempo
dibandingkan dengan jangka waktu yang
14
J. B. Heaton, 2007, The Bussines Lawyer
Vol.62, Journal Press, London, hal.983
ditetapkan dalam perjanjian. Walaupun demikian,
dalam prakteknya jenis pendekatan lainnya juga
digunakan untuk dapat melengkapi hasil test dari
the ability-to-pay solvency test atau bahkan
digunakan untuk melemahkan kesimpulan hasil
test tersebut. Contohnya, bisa saja dari hasil test
kemampuan membayar dengan melihat jangka
waktu pembayaran dengan keadaan utang yang
sudah jatuh tempo dapat ditarik kesimpulan
bahwa debitur ada dalam keadaan tidak mampu
membayar, namun berdasarkan the balance-sheet
solvency test ternyata debitur tidak mengalami
masalah, malahan mendapatkan profit dalam
usahanya. Berarti permasalahannya bukan pada
kemampuan membayar, mungkin ada
pertimbangan lain atau suatu kesalahan tertentu
dalam manajemen yang memungkinkan hal ini
terjadi.
B. Reorganisasi Perusahaan
Istilah Reorganisasi, dalam bahasa Inggris
disebut Reorganization. Elisabeth Warren dalam
bukunya mengartikan reorganisasi sebagai “a
change in the debt obligation of the business”.15
(Terjemahan bebasnya: suatu perubahan di dalam
ketentuan utang di bidang bisnis). Tentunya
beliau mengartikan reorganization dalam
konteksnya pada Bankuptcy Law.
Pengertian reorganisasi secara umum dapat
ditemukan dalam kamus. Black‟s Law Dictionary
memberikan definisi reorganisasi sebagai: “Act or
process of organizing again or anew.”
(terjemahan bebasnya: usaha atau proses
pengorganisasian kembali atau dengan cara baru).
Lebih jauh lagi Black memberi penjelasan:
As applied to corporations. The carrying
out, by proper agreements and legal
proceedings, of a business plan for winding
up the affairs of or foreclosing a mortgage
or mortgages upon the property of, insolvent
corporations, more frequently railroad
companies. It is usually accomplished by the
judicial sale of the corporate property and
15
Elizabeth Warren, 2008, Essentials
Chapter 11: Reorganizing American Business,
Aspen Publisher, New York, hal.4

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 71
franchises, and the formation by the
purchasers of a new corporation. The
property and franchises are thereupon
vested in the new corporation and its stock
and bonds are divided among such of the
parties interested in the old company as are
parties to the reorganization plan.16
(Terjemahan bebasnya: Seperti diterapkan
pada perusahaan. Pelaksanaan, oleh
perjanjian yang tepat dan proses hukum,
dari rencana bisnis untuk penutupan urusan
atau penyitaan hipotek atau hipotek atas
properti, perusahaan bangkrut, lebih sering
perusahaan kereta api. Hal ini biasanya
dilakukan dengan penjualan berdasarkan
keputusan pengadilan terhadap properti
perusahaan dan waralaba, dan pembentukan
oleh pembeli sebuah perusahaan baru.
Properti dan waralaba yang kemudian
dipegang oleh perusahaan baru serta saham
dan obligasinya dibagi antara para pihak
yang berkepentingan dalam perusahaan
lama sebagaimana kedudukannya sebagai
para pihak dalam rencana reorganisasi.)
Penggunaan istilah reorganisasi di Indonesia
sering dipadankan dengan istilah restrukturisasi.
Kedua istilah ini relatif memiliki makna yang
sama. Secara umum, contoh reorganisasi yang
sering dijumpai adalah reorganisasi atau
restrukturisasi utang. Misalnya, sebuah
perusahaan terikat pada suatu utang jangka
panjang selama jangka waktu 5 tahun dengan
bunga 20 persen per tahun, kemudian
direstrukturisasi atau direorganisasikan menjadi
menjadi utang dengan jangka lebih panjang,
misalnya 8 tahun, namun dengan bunga yang
lebih rendah, yaitu 15 persen per tahun, dengan
nilai agunan yang telah diturunkan juga untuk
lebih mendekati nilai asli dari jaminan tersebut.
Secara singkat, reorganisasi oleh Warren
dimaknai sebagai “how to spread around the pain
for a business that cannot repay its debt in full”17
(terjemahan bebasnya: bagaimana untuk membagi
secara merata kesulitan dari bisnis atau usaha
yang tidak dapat membayar kembali utang-
utangnya secara penuh). Maksud dari pernyataan
itu adalah cara yang ditempuh untuk
16
Henry Campbell Black, 1979,
“Reorganization” Black‟s Law Dictionary, West
Publishing Co., St. Paul Minnasota, hal. 17
Elizabeth Warren, loc. cit.
mengompensasikan setiap kesulitan yang
dihadapi dalam bisnis terutama yang timbul
akibat ketidakmampuan membayar kembali
utang-utang melalui cara lain atau jalan lain.
Reorganisasi di dalam tulisan ini bukan
hanya sekedar reorganisasi dalam obligasi atau
perjanjian utang saja, namun lebih luas lagi
mencangkup reorganisasi perusahaan dan tetap
dalam konteks upaya menanggulangi
permasalahan kesulitan dalam pembayaran utang.
Warren membedakan reorganisasi perusahaan
dalam dua jenis yaitu Reorganisasi Finansial dan
Reorganisasi Operasional.
Reorganisasi Finansial berarti restrukturisasi
yang terjadi adalah murni dalam hal keuangan
saja. Warren menyatakan: “That is, the business
operations remain the same, while the debts are
written down or eliminated and stock in the
business is distributed to unpaid creditors.”18
(Terjemahan bebasnya: bahwasanya, operasional
bisnis perusahaan tersebut tetap sama, hanya saja
utang-utangnya diperjanjikan kembali {diatur
ulang} atau dihapuskan dan saham didistribusikan
kepada kreditor yang piutangnya tidak dilunasi).
Jadi, restrukturisasi utang termasuk di dalam
reorganisasi finansial. Tidak hanya restrukturisasi
utang saja yang terjadi, namun juga dapat
dimungkinkan terjadinya kompensasi dan
konversi terhadap utang baik sebagian maupun
keseluruhan yang tidak dapat dilunasi menjadi
saham dalam perusahaan tersebut. Hal ini
dimungkinkan pada suatu perusahaan yang
berpotensi untuk maju dan berkembang, namun
margin keuntungan yang didapatkan masih tidak
mampu untuk menutupi kewajiban angsuran
utang yang harus dibayarnya.
Tentu akan menjadi pilihan atau langkah
penyelamatan yang sangat baik apabila kreditur
ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham
perusahaan daripada harus mempailitkan
perusahaan tersebut, yang dampak jangka
18
Elizabeth Warren , loc. cit.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 72
panjangnya malahan tidak baik bagi
perkembangan perusahan, dan juga bagi para
pihak lainnya yang berkepentingan terhadap
perusahaan tersebut. Dengan demikian kreditor
bukan hanya mendapat pelunasan terhadap
piutangnya, melainkan pula dapat memperoleh
keuntungan terkait potensi perusahaan yang
mampu meraih profit dalam usahanya.
Reorganisasi finansial ini sering disebut sebagai
balance sheet reorganization, oleh karena pada
hakekatnya reorganisasi atau restrukturisasi ini
hanya terjadi di atas kertas saja, dan tidak
mengubah operasional harian. Di atas kertas,
hutang dihapus dan di anggaran dasar terjadi
perubahan kepemilikan saham.
Selanjutnya adalah Reorganisasi
Operasional. Dari istilahnya saja sudah dapat
memberikan gambaran bahwa yang
terestrukturisasi adalah baik sebagian ataupun
keseluruhan operasional dari suatu perusahaan.
Warren menyatakan bahwa dalam proses
reorganisasi ini “The debtor will use the breathing
room provided by the protection of bankruptcy to
close or to sell money-losing division, trim excess
staff, refocusing product lines, cut back on the
number of company cars, and so forth.”19
(Terjemahan bebasnya: Debitur akan
menggunakan “ruang bernafas” yang disediakan
melalui perlindungan oleh Kebangkrutan {dalam
konteks Indonesia lebih tepat diartikan “oleh
Lembaga Kepailitan”} untuk menutup atau
menjual divisi yang hanya menghabiskan uang,
mengurangi staf yang tidak perlu, memfokuskan
kembali lini produk, mengurangi jumlah mobil
perusahaan, dan sebagainya).
Mengenai Jenis Reorganisasi Operasional,
Warren menambahkan pendapatnya: “This type of
business reorganization usually produces a
smaller, leaner company with a reduced debt (and
interest) burden, once again able to concentrate
19
Elizabeth Warren , op. cit., hal.5
on the core competence of the business.”20
(terjemahan bebasnya: tipe reorganisasi usaha ini
biasanya menghasilkan suatu perusahaan yang
lebih kecil, lebih ramping dengan beban utang
yang lebih rendah (beserta bunganya), sekaligus
kemudian mampu untuk berkonsentrasi dalam
kompetensi inti dari usahanya).
Berdasarkan kedua jenis reorganisasi ini,
dapat dimunculkan suatu bentuk reorganisasi
lainnya, yaitu Reorganisasi Menyeluruh. Dalam
bahasa inggris dapat diterjemahkan menjadi
General Reorganization. Jenis ini
mengkombinasikan baik itu reorganisasi finansial,
maupun reorganisasi operasional. Jenis ini
sebenarnya yang sering kali akan dibutuhkan oleh
suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang
memerlukan reorganisasi, selain mengalami
kelebihan beban oleh karena tanggungan
utangnya, seringkali juga mengalami suatu
kondisi operasional yang kurang optimal. Dengan
demikian, mencermati kebutuhan tiap perusahaan
sangatlah penting, dan ini merupakan kunci
keberhasilan reorganisasi yang akan dilakukan.
C. Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang
Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (selanjutnya disingkat PKPU) di dalam
sistematika Undang-Undang Kepailitan Nomor 4
Tahun 1998, pengaturannya dimuat pada Bab II
mulai pasal 212 sampai dengan pasal 279
sedangkan dalam sistematika Undang-Undang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004
pengaturannya dimuat pada Bab III mulai pasal
222 sampai dengan pasal 264.
PKPU ini dalam bahasa Inggris disebut
dengan Suspension of Payment, atau dalam
bahasa Belanda disebut dengan Sursence van
Betaling. Yang dimaksud dengan PKPU adalah
suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh
undang-undang melalui putusan pengadilan niaga
20
Elizabeth Warren , op. cit., hal.15

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 73
di mana dalam periode waktu tersebut kepada
kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk
memusyawarahkan cara-cara pembayaran
hutangnya dengan memberikan rencana
pembayaran (composition plan) terhadap seluruh
atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila
perlu merestrukturisasikan hutangnya tersebut.
Dengan demikian, PKPU merupakan semacam
moratorium, dalam hal ini legal moratorium.21
Maksud PKPU pada umumnya adalah untuk
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi
tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang
kepada kreditur konkuren. Tujuan PKPU adalah
untuk memungkinkan seorang debitur
meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran
pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.22
Dengan adanya penundaan pembayaran,
maka dapat terjadi beberapa kemungkinan.23
a) Piutang – piutang para kreditur akan
dibayar / dapat dibayar seluruhnya oleh
debitur.
b) Pembayaran piutang kreditur itu dilunasi
sebagian melalui pemberesan tahap demi
tahap;
c) Suatu perdamaian di bawah tangan;
d) Pengesahan perdamaian apabila terjadi
perdamaian yang lazim disebut
gerechteljke accord atau dwang acoord;
e) Penyataan pailit, apabila tujuan yang
hendak dicapai dengan pengunduran
pembayaran itu tidak tercapai.
D. PKPU di Indonesia dibandingkan
dengan Reorganisasi di Amerika
Reorganisasi perusahaan berbeda dengan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU), dimana tujuan dari reorganisasi adalah
21
R. Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Kencana Predana Media Group, Jakarta, hal. 46 22
Rahayu Hartini, 2002, Hukum Kepailitan,
Diretorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional, hal. 17 23
Zainal Asikin, 1994, Hukum Kepailitan
Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 97-98.
untuk menyelamatkan perusahaan yang mana
jangkauannya lebih luas dalam artian tidak hanya
dalam restrukturisasi utang tapi juga dalam hal
penyehatan manajemen.
Sedangkan konteks dari Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanyalah
dalam hal restrukturisasi finansial atau
restrukturisasi utang saja. Sesuai dengan
namanya, maka dengan tundaan pembayaran,
kewajiban membayar semua hutang tetap saja
ada, tetapi untuk sementara ditunda. Ini sebabkan
adanya beberapa alasan sehingga untuk sementara
pembayaran hutang tidak dapat dilaksanakan.
Tetapi, ada perhitungan yang reasonable, bahwa
suatu masa kelak hutang tersebut akan dapat
dilunasi lagi. Misalnya terjadinya musibah berupa
force majeure, yang menyebabkan debitur untuk
sementara tidak sanggup membayar hutang.24
Dalam hal ini dapat kita perbandingkan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di
Indonesia dengan Reorganisasi Perusahaan di
Amerika Serikat :
1. Jangka waktu yang realistis
Jangka waktu yang diberikan oleh
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia
untuk reorganisasi perusahaan debitur
(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /
PKPU) adalah 270 hari dengan ketentuan
PKPU Sementara 45 hari dan PKPU tetap
270 hari.
Bankruptcy Code (Undang-Undang
Kepailitan Amerika Serikat memberik
waktu 120 hari dan 180 hari bagi debitur
hak ekslusif khusus untuk membuat rencana
reorganisasi. Periode ini masih bisa
diperpanjang oleh pengadilan berdasarkan
alasan-alasan yang logis mengingat
kepentingan reorganisasi debitur. Adalah hal
24
Munir Fuandy, 2005, Hukum Pailit dalam
Teori dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan
dengan UU Nomor 37 Tahun 2004, Citra Aditya
Bakti, Bandung, hal. 197.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 74
yang tidak realistis dan memberi kesan
terburu-buru karena debitur dipaksa oleh
undang-undang bahwa selama 270 hari
harus telah ada kesepakatan antara debitur
dan kreditur mengenai PKPU sehingga
pengadilan dapat melegitimasi kesepakatan
tersebut melalui putusan Pengadilan Niaga.
Sementara dalam Restrukturisasi Perbankan
jumlah waktu yang cukup lama diperlukan
oleh auditor dari luar untuk meneliti
portofolio sejumlah bak bermasalah yang
dipinjamkan kepada mereka untuk
kepentingan BPPN.25
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) di Indonesia adalah organisasi yang
minus refinancing.26
Reorganisasi perusahaan bertujuan agar
perusahaan yang berada dalam keadaan
“sakit” disehatkan kembali. Berarti
seharusnya yang menjadi sentral adalah
penyehatan struktural modal yang bertujuan
untuk menyehatkan perusahaan
(refinancing). PKPU tidak menyentuh
perolehan tentang bagaimana rencana
perusahaan debitur untuk memperkuat
struktur modal, karena UU Kepailitan
Indonesia hanya membatasi pengertian
reorganisasi perusahaan sebagai upaya
penjadwalan kembali pembayran hutang
kepada kreditur. Reorganisasi perusahaan di
Amerika Serikat justru berbeda, sebab
reorganisasi perusahaan memang efektif
diarahkan untuk menyehatkan permodalan
dari perusahaan debitur yang sedang “sakit”.
Uang tunai jelas mengubah struktur modal
25
Masyhud Ali, 2002, Restrukturisasi
perbankan & Dunia Usaha. Elex Media
Komputindo, Jakarta, hal 136. 26
Herbert, 2003, Reorganisasi Perusahaan
Dalam Kepailitan. Tesis Pasca Sarjana Ilmu
Hukum, Perpustakaan Universitas Sumater Utara,
Medan, hal 105.
perusahaan sehingga roda bisnis dapat
diputar kembali.27
3. Posisi relatif kreditur
UU Kepailitan Indonesia
memprioritaskan dunia kreditur hanya pada
kreditur terjamin dan kreditur tidak terjamin.
Dalam hubungan antara kreditur struktur
komite kreditur terbatas pada kreditur
konkuren. Oleh karenanya proses PKPU di
Indonesia cenderung untuk menyamaratakan
kepentingan seluruh kreditur. Sebagai
pertandingan, reorganisasi perusahaan di
Amerika Serikat justru diharuskan agar
kreditur dibagi dalam kelas-kelas
kepentingan dari kelas yang paling senior
sampai pada kelas yang paling junior.
4. Pengajuan rencana reorganisasi perusahaan
Menurut UU Kepailitan, Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya
bisa diajukan oleh debitur, atau tidak bisa
diajukan oleh kreditur. Ketentuan ini berbeda
dengan Banruptcy Code yang memuat
bahwa, hak eksklusif debitur untuk
mengajukan rencana reorganisasi
perusahaannya ke pengadilan selama perode
120 hari dan 180 hari. Akan tetapi apabila
tenggang waktu 120 hari dan 180 hari debitur
telah lewat, hak eksklusif debitur gugur maka
kreditur berhak mengajukan rencana
reorganisasi ke pengadilan.
E. Pembaharuan Peraturan Kepailitan
Sebagai Usaha Peningkatan
Perekonomian Indonesia
Berlakunya peraturan perundang-undangan
di Indonesia dalam hal ini secara khusus UU
Kepailitan dan PKPU memiliki tujuan. Pada awal
peraturan kepailitan yang ada tentunya sudah
tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi
masyarakat yang terus berkembang sehingga
dilakukan perubahan. Contoh yang paling nyata
27
Thomas H. Jackson, 2005, The Logic and
Limis of Bankrupcy Law, Harvard University
Press, hal 243.

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 75
terlihat dalam pengaturan Undang-Undang No.4
Tahun 1998 tentang Kepailitan yang mana tujuan
pembuatannya adalah untuk mempercepat proses
penyelesaian utang perusahaan yang insolvent
terkait krisis moneter yang dialami Indonesia.
Karena tujuannya adalah mempercepat karena
banyak sekali perusahaan yang bangkrut pada
waktu itu, maka pengaturannya pun menggunakan
dua variabel sebagai acuan mempailitkan, yakni
adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih, serta adanya lebih dari satu kreditur. Pada
waktu itu memang jenis pengaturan seperti ini
yang dibutuhkan, karena keadaan ekonomi dan
perusahaan-perusahaan pada waktu itu dapat
dikatakan sangat tidak stabil.
Indonesia saat ini terus berkembang,
terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Hanya
saja dalam hal hukum kepailitan walaupun telah
diundangkan Undang-undang terbaru yakni
Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, namun ternyata variabel yang
digunakan sebagai acuan untuk dapat
memailitkan suatu entitas masih tidak berubah
dan hanya dua itu saja. Hal ini tentu tidak sesuai
dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini yang
sedang berkembang maju dengan pesat. Terlalu
sederhana dan sedikitnya variabel sebagai
pertimbangan untuk dapat memailitkan suatu
entitas justru berakibat tidak baik bagi
perkembangan ekonomi Indonesia. Ini sama saja
dengan menutup mata terhadap proyeksi
kemampuan dan potensi masa depan suatu entitas
yang hendak dipailitkan. Entah ia mampu
berkembang di kemudian hari ataupun tidak
seakan-akan oleh Undang-undang Kepailitan dan
PKPU tidak dianggap. Asalkan memenuhi syarat
maka dapat dijatuhkan putusan pailit.
Sistem kombinasi yang ditawarkan dalam
penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi
dari permasalahan pengaturan perundang-
undangan kepailitan yang sekatrang berlaku di
Indonesia. Siatem kombinasi ini diharapkan
mampu memberikan iklim usaha yang lebih baik
di Indonesia yang berimbas pada kemajuan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Berdasarkan penelitian ini maka dapat
disimpulkan bahwa hal yang menjadi
pokok utama dalam pengaturan sistem
kombinasi sebagaimana dimaksud
adalah pengaturan sebagai upaya
pencegahan suatu perusahaan
dipailitkan dengan melihat potensi
serta kemampuan perusahaan yang
sedang mangalami kesulitan keuangan
dan terancam dipailitkan tersebut
untuk dapat bangkit lagi di masa
depan. Sistem ini memberikan
kesempatan baru pula bagi suatu
perusahaan untuk dapat berbenah dan
secara tidak langsung membantu
perekonomian Negara karena
perusahaan adalah salah satu roda
penggerak perekonomian Negara.
2. Pengaturan pencegahan suatu
perusahaan terjerat kepailitan dengan
sistem kombinasi Insolvency Test,
Reorganisasi Perusahaan dan PKPU
dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut. Tahap awal sebagai
penyaring setiap permohonan pailit
yang masuk pengadilan niaga adalah
dengan Insolvency Test; dilakukan
dengan memeriksa persyaratan
ketentuan pailit menurut Undang-
undang kemudian menerapkan tiga
jenis test untuk menentukan status
keuangan perusahaan yaitu The Ability
to Pay Solvency Test yang merupakan
ujian mengenai kemampuan
membayar Debitur, The Balance Sheet

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 76
test yaitu pengujian terhadap rasio
perbandingan antara total
utang/kewajiban dengan total aset
Debitur, dan The Capital Adequacy
test dengan melihat proyeksi nilai
saham perusahaan di masa depan.
Selanjutnya berdasarkan hasil
Insolvency Test maka ditentukanlah
apakah suatu perusahasan yang
dimohonkan pailit perlu untuk
melakukan reorganisasi perusahaan
atau cukup dengan moratorium atau
restrukturisasi utang yaitu dengan
melalui PKPU.
B. Saran
1. Bagi pemerintah hendaknya segera
melakukan revisi terhadap Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU karena
sudah tidak mampu lagi mengimbangi
perkembangan ekonomi negara yang
terus maju; agar Undang-Undang
Kepalitan dapat menjadi alat
mempermudah kemajuan ekonomi.
2. Bagi Debitur hendaknya secara proaktif
melakukan upaya penyelamatan
perusahaannya apabila mengalami
kesulitan keuangan terutama pemenuhan
kewajiban seperti pembayaran utang
agar tidak perlu mengalami proses
kepailitan yang dapat berakibat buruk
bagi masa depan perusahaan ataupun
bisnisnya,
3. Bagi Kred itur hendaknya t idak
menggunakan celah hukum
dalam Undang - Undang
Kepail i tan dan PKPU sebagai
cara untuk mendapatkan
keuntungan dar i Debitur karena
sebenarnya yang mendapat
imbasnya pada jangka panjang
adalah masyasrakat yang
kemudian lebih jauh lagi
ber imbas pada kemunduran
sektoe ekono mi negara.
DAFTAR BACAAN
Buku:
Anonim, 2010, Oxford Dictionary of English, Oxford University Press, United Kingdom
Ali, Masyhud, 2002, Restrukturisasi perbankan & Dunia Usaha. Elex Media Komputindo, Jakarta
Black, Henry Campbell, 1979, Black‟s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul Minnasota.
Cahir, Barry et. al., 2003, Insolvency Law; Professional Practice Guide, Cavedish Publishing, Ireland
Asikin, Zainal 1994, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, RajaGrafindo
Persada, Jakarta
Scott, David L., 2009, The American Heritage Dictionary of Business Term, Houghton Mifflin Harcourt,
Boston, New York
Heaton, J.B., 2007, The Bussines Lawyer Vol.62, Journal Press, London
Warren, Elizabeth, 2008, Essentials Chapter 11: Reorganizing American Business, Aspen Publisher, New
York
Suyatno, R. Anton, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kencana Predana
Media Group, Jakarta
Hartini, Rahayu, 2002, Hukum Kepailitan, Diretorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan
Nasional
Fuady, Munir, 2005, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU Nomor
37 Tahun 2004, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Herbert, 2003, Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan. Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum,
Perpustakaan Universitas Sumater Utara, Medan
Jackson, Thomas H., 2005, The Logic and Limis of Bankrupcy Law, Harvard University Press
Majalah:
Campbell, Steven V., 1996, “Predicting Bankruptcy Reorganization for Closely Held Firms”, Accounting
Horizons, Vol 10, 3

Jurnal I lmiah Prodi Magister Kenotar iatan, 2013 -2014 Page 77
Korobkin, Donald R., 1991, “Rehabilitating Values: A Jurisprudence pf Bankruptcy”, Columbia Law
Review, Vol.91, No.4
Internet:
James Purba, sebagaimana dikutip dari Hukumonline.com, available from: URL:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailita n--untuk-lindungi-
debitor
*****