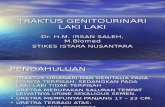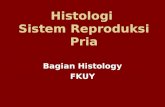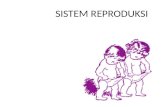F. Budi Hardiman - Kegalauan Identitas Dan Keadilan Gender Pengantar Untuk Buku y769 Manusia,...
-
Upload
simonsapala -
Category
Documents
-
view
99 -
download
8
description
Transcript of F. Budi Hardiman - Kegalauan Identitas Dan Keadilan Gender Pengantar Untuk Buku y769 Manusia,...

1
Makalah Musyawarah Buku | Mei 2013
Makalah
Kegalauan Identitas dan Keadilan Gender Pengantar untuk buku Manusia, Perempuan, Laki-laki1
F. Budi Hardiman2
Sebelum masuk ke dalam kumpulan tulisan yang diberi judul Manusia, Perempuan,
Laki-laki ini, saya akan mulai dengan sebuah cerita kecil. Cerita itu berasal dari sastrawan Jerman, Thomas Mann, yang diberi judul Mario und der Zauberer.3 Di sebuah daerah wisata pantai Torre di Vinere di Italia, diadakan sebuah pertunjukan sulap. Si tukang sulap yang bernama Cavaliere Cipola mahir menghipnosis siapa saja yang diundangnya ke panggung. Tak seorang pun dapat mempertahankan “kesadaran diri” atau—sebutlah—“identitas”nya di hadapan kekuatan sugestinya. Orang muda yang semula menolak, lalu patuh untuk menjulurkan lidah di depan publik. Orang lain lagi disugesti duduk kaku di atas bangku. Seorang nyonya dibuat tertidur dan bermimpi tentang wisata ke India. Seorang tentara dibuatnya tak dapat mengangkat tangannya lagi. Seorang perempuan mematuhi perintah Mario di panggung tanpa dapat dicegah suaminya. Bahkan seluruh penonton dibuatnya menari dalam keadaan trans, sampai datang seorang pelayan restoran bernama Mario kepadanya. Juga pemuda yang sedang mabuk kepayang dengan seorang gadis ini disugesti untuk mencium Cipola, seolah dia adalah gadis itu. Tiba-tiba saja Mario sadar diri, merasa jijik dan ngeri, lalu mengambil pistolnya dan menembak Cipola dengan dua peluru. Ruang pertunjukan menjadi rusuh.
Sesungguhnya Mann sedang bercerita tentang demagog Hitler yang hebat yang sukses menyihir Jerman dan mengubah identitas orang-orang di bawah pengaruhnya. Akan tetapi menurut saya cerita itu bicara lebih daripada itu. Mario und der Zauberer
1 Makalah untuk Musyawarah Buku Subyek yang Dikekang dan Manusia, Perempuan, Laki-laki di Serambi Salihara, 28 Mei 2013, 19:00 WIB. Makalah ini telah disunting.
2 F. Budi Hardiman adalah pengajar di STF Driyarkara, Jakarta, dan Universitas Pelita Harapan, Tangerang. Ia meraih gelar Doktor der Philosophie di Hochschule für Philosophie München, Jerman. Bukunya, antara lain, adalah Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma (Jakarta: Kompas, 2008), Filsafat Fragmentaris: Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi (Yogyakarta: Kanisius, 2007), dan Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
3 Baca Thomas MannTonio Krögerer. Mario und der Zauberer (Frankfurt a.M.: Fischer, 1973), 75 dan seterusnya.

2
Makalah Musyawarah Buku | Mei 2013
membawa kita pada pertanyaan mendasar: Apakah identitas manusia itu, jika hipnosis dapat mengubah dan mempermainkannya, sekalipun hanya sesaat? Ingat bahwa segala perubahan sosial politis yang dibawa oleh globalisasi dan demokratisasi membawa “efek hipnotis” yang serupa pada identitas. Media dan konsumerisme global mereproduksi diskursus yang darinya identitas diseleksi, dieliminasi, direkonstruksi tanpa disadari para pemiliknya. Tapi benarkah ada yang kita sebut identitas itu? Mungkin nama tukang sulap itu dapat sedikit menyingkap. Cipola adalah kata Italia untuk bawang merah. Umbi ini terdiri atas lapisan-lapisan belaka. Orang tidak akan menemukan intinya, karena setelah lapisan terakhir yang ada hanyalah kekosongan. Tidak ada substansi dasariah yang darinya kita dapat menganggapnya sebagai identitas umbi ini selain lapisan-lapisan itu. Cipola, bawang merah, dapat dianggap sebagai ilustrasi untuk pemikiran kontemporer tentang identitas.
Saya tulis “tentang identitas”, bukan “tentang identitas manusia”. Mengapa? Karena “manusia”, sekurangnya menurut filsafat kontemporer, juga suatu konstruksi identitas. Adalah Martin Heidegger, dalam Sein und Zeit, yang menolak memakai kata manusia dan menggantinya dengan Dasein ( yang berada-di sana) karena kata itu sudah dimuati metafisika Barat selama berabad-abad, khususnya filsafat kesadaran dalam modernitas. Di zaman Kekristenan manusia dipahami sebagai “ciptaan” dan dalam modernitas sebagai “subyek”, sebagaimana kemudian dimengerti sebagai “individu” dalam liberalisme Barat. Perubahan makna itu—yang mengikuti perubahan dalam wawasan dunia metafisis—sudah membuktikan bahwa manusia bukanlah suatu substansi tetap dan universal. Karena itu, Heidegger menyebut Dasein kemungkinan belaka (Seinkönnen); kita, Dasein, adalah—seperti dikutipnya dari penyair Hölderlin–suatu “tanda” yang “tetap tinggal tanpa interpretasi”.4 Dengan ungkapan lain, tidak ada identitas tetap untuk Dasein selain bahwa ia ada, yaitu sebagai kemungkinan atau keterbukaan belaka. Di lain tempat Jean-Paul Sartre menyebut manusia “eksistensi mendahului esensi”5. Semua sebutan ini mengacu pada kenyataan bahwa manusia— seperti dilustrasikan dengan cipola—adalah lapisan-lapisan relasi-relasi belaka yang lalu disebut dengan penanda “identitas”.
Berpikir PostmetafisisCairnya atau—bisa juga disebut—“desubstansialisasi” konsep identitas hanyalah
salah satu dari banyak perubahan dalam pemikiran kontemporer yang mengambil jarak dari metafisika dan filsafat kesadaran. Hal-hal lain adalah konsep masyarakat, konsep keadilan, konsep kebenaran dan bahkan konsep pemikiran itu sendiri. Kita dapat menyebut pengambilan jarak itu “strategi berpikir postmetafisis”. Berpikir dengan strategi ini tidak sama dengan berpikir dalam arti lazim. Dalam arti lazim berpikir beroperasi di dalam suatu wawasan dunia, sedangkan strategi berpikir postmetafisis memungkinkan seorang pemikir mengeksplisitkan suatu wawasan dunia dan kritis atasnya. Heidegger adalah guru bagi mereka yang berpikir postmetafisis.
4 Baca Martin Heidegger, “What Calls for Thinking?”, dalam Martin Heidegger, Basic Writings: Nine Key Essays, plus the Introduction to Being and Time (London: Routledge & Keagan Paul, 1978), 351.
5 Baca penjelasan Sartre dalam Jean-Paul Sartre, Existentialism and Humanism (London: Methuen & Co Ltd, 1966), 28.

3
Makalah Musyawarah Buku | Mei 2013
Dari Thomas Kuhn kita tahu bahwa suatu wawasan dunia yang disebutnya “paradigma” tetap implisit, taken for granted, non-tematis sampai terjadi suatu krisis yang membuatnya dikenali. Pemikir postmetafisis menjadi worldview-sensitive. Hal itu menjadi mungkin karena pemikiran kontemporer lahir dari krisis wawasan dunia yang selama berabad-abad telah menjadi presuposisi para filsuf besarnya sejak Descartes. Krisis itu sendiri kemudian diambil menjadi presuposisi berpikir, sehingga strategi berpikir postmetafisis tidak bergerak di dalam, melainkan di pinggiran suatu wawasan dunia. Strategi itu diistilahkan dengan berbagai nama, seperti dekonstruksi (Derrida), genealogi (Nietzsche/Foucault), destruksi metafisika (Heidegger) atau pemikiran postmetafisis (Habermas).
Para pemikir perempuan yang dibahas di dalam buku ini juga mengambil strategi postmetafisis dalam berpikir. Bukan hanya itu, mereka sendiri adalah anak zaman yang berpikir postmetafisis. Keempat tulisan—semua adalah bahan Seri Kuliah Umum di Teater Salihara—berhasil mengomentari bahan mereka secara kritis, meski novum tidak mudah ditemukan di sana. Karena tokohnya juga dari konteks, tradisi intelektual dan bahkan era yang berbeda-beda, sulit menemukan semacam benang merah dari keempat tulisan, selain bahwa mereka mempersoalkan identitas dan keadilan gender.
Hannah Arendt, Seyla Benhabib, Judith Butler dan Ziba Mir-Hoseini bergumul dengan persoalan rumit yang di dalamnya identitas berkelindan dengan tubuh, orientasi nilai, masyarakat dan pada akhirnya juga suatu wawasan dunia metafisis yang disebut modernitas. Selain Butler yang lahir dan besar di Amerika Serikat, para tokoh perempuan ini memiliki latar belakang yang boleh disebut majemuk. Arendt adalah keturunan Yahudi, besar di Jerman dan menjadi imigran di Amerika Serikat. Benhabib juga keturunan Yahudi, besar di Turki dan pindah ke Amerika Serikat. Mir-Hoseini berasal dari orangtua campuran antara Inggris dan Iran, belajar di Inggris dan Iran. Identitas kultural mereka beragam, tetapi sejauh diarahkan oleh keempat komentator mereka di sini, mereka sama dalam satu hal: mengangkat isu identitas dan keadilan gender dalam masyarakat kontemporer.
Identitas dan Keadilan GenderKita mulai dengan pemikiran Arendt sejauh diteropong oleh Edi Riyadi Terre. Tema
yang dipilih di sini, tindakan politis, memiliki alasan yang kuat. Konsep tindakan politis tidak hanya sentral dalam pemikiran Arendt, melainkan juga menjadi locus kelindan antara identitas, tubuh, masyarakat dan akhirnya juga suatu wawasan dunia. Ruang publik dimengerti tidak hanya sebagai ruang-antara (Zwischenraum) yang memungkinkan intersubyektivitas, melainkan juga ruang penampakan (Erscheinungsraum) bagi kesiapaan, maka juga menjadi panggung bagi identitas. Di antara ketiga tipe kegiatan tubuh—bekerja, berkarya dan bertindak—hanya bertindaklah yang mengandaikan kehadiran orang lain dan membebaskan tubuh dari irama survival lahir, kawin dan mati, karena bertindak tidak terkurung dalam penjara tubuh, seperti bekerja, atau memperalat tubuh, seperti berkarya, melainkan memartabatkan tubuh dengan suatu nama dan pengakuan bagi pemiliknya.
Tidak jelas dalam pemikiran Arendt, dan juga tidak jelas dalam ulasan Edi, pemilik tubuh itu laki-laki atau perempuan, namun dapat didugai bahwa Arendt menempatkan tubuh perempuan dalam irama survival reproduksi dalam ruang privat, sementara tubuh laki-laki, jika tidak terkurung dalam irama survival produksi sebagai budak, akan muncul sebagai nama di dalam ruang publik sebagai legislator.

4
Makalah Musyawarah Buku | Mei 2013
Kesiapaan yang tersingkap di ruang publik itu mengandaikan ketersembunyian. Berbeda dari modernitas yang memahami manusia sebagai individu otonom, dengan menempatkan kesiapan dalam dinamika penyingkapan dari ketersembunyian, Arendt memahami ruang publik sebagai arena pluralitas identitas, sejauh identitas tidak dimengerti sebagai substansi universal homogen yang bernama individu, melainkan berkas relasi-relasi atau struktur cipola, bawang merah, dalam cerita Thomas Mann. Melampaui esensialisme Pencerahan Eropa, pemikiran postmetafisis Arendt menempuh strategi desubstansialisasi identitas dengan menempatkannya dalam tegangan permainan antara menyingkap dan menyembunyikan, sebuah strategi postmetafisis yang dipelajari dari fenomenologi gurunya, Heidegger.
Keenam tesis yang diajukan Edi untuk “manusia politis” menjelaskan anthropophani (penyingkapan manusia) itu. Manusia politis tak lain daripada berkas relasi-relasi pada suatu titik yang menyingkap sebagai “kesiapaan” lewat keterlibatan dalam ruang publik, dan titik itu bukanlah suatu poros permanen, melainkan suatu acuan percakapan yang kontingen terhadap komunikasi publik. Politik dalam arti legislasi demokratis ini dalam pemikiran Arendt mencapai tingkat idealisasi yang tinggi. Edi benar, bila ia mengkritik Arendt “mempunyai asumsi terlalu positif terhadap politik”, namun ia luput melihat kemungkinan menilai bahwa idealisasi itu juga diperlukan untuk mendekatkan politik nyata pada makna otentiknya sebagai kebebasan eksistensial. Meski demikian, interpretasi yang dilakukan Edi cukup berani dan kaya akan tilikan yang berharga untuk memahami Arendt.
Tulisan kedua berasal dari Gadis Arivia dan membahas pemikiran seorang tokoh perempuan yang dulu dikenal sebagai komentator Habermas, yaitu Seyla Benhabib. Untuk memahami Benhabib kita perlu lebih dahulu memahami analisis Habermas mengenai pergeseran tema gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat kontemporer, yakni dari isu “distribusi” dalam teori-teori Marxis ke isu “gramatika bentuk-bentuk kehidupan”. Hidup dalam kondisi kosmopolitanisme, perempuan kelahiran Istanbul ini menghadapi persoalan besar dari tradisi besar pemikiran Barat yang menurutnya menyingkirkan liyan konkret, dalam hal ini identitas perempuan. Yang dimaksud adalah liberalisme, suatu pemikiran dominan dalam bidang politik dan hukum yang menyuling identitas dengan alat “veil of ignorance” (Rawls) menjadi identitas abstrak tak bertubuh, tak berkulit, tak berkelamin dan juga tak bersejarah yang disebut “individu otonom”s.
Sebagaimana Heidegger sedikit banyak menginsprasi Arendt, Benhabib sedikit banyak berpijak pada warisan universalisme Pencerahan yang dibela Habermas. Gadis dengan tepat meletakkan Benhabib dalam “posisi tengah antara model konsensus Habermas dan bentuk radikal kontekstualisme”. Posisi ini berguna untuk menghindarkan feminisme jatuh entah pada universalisme abstrak ala liberalisme atau pada relativisme kultural yang pada gilirannya akan memutlakkan kebenaran liyan “semata-mata karena ia ‘lain’”. Seperti ditegaskannya, perempuan juga “harus dapat melakukan konversasi moral” untuk “memformulasi bersama apa yang disebut identitas, keadilan dan kebaikan”. Artinya, demi mengatasi paradoks kesetaraan dalam kemajemukan liyan juga harus diskursif.
Interpretasi Gadis ini sangat membantu untuk menggempur kecenderungan eksklusivisme identitas konkret sebagaimana terdapat dalam sementara gerakan feminis dan tidak terkecuali dalam gerakan fundamentalisme religius. Bagaimanapun perempuan dan identitas-identitas konkret tidak hanya menghendaki respek atas keberlainan mereka, melainkan juga kesetaraan dan keadilan, maka perjuangan

5
Makalah Musyawarah Buku | Mei 2013
perempuan juga didorong oleh sebentuk universalisme. Senada dengan Habermas, Benhabib mencoba mencari jalan agar ruang publik tidak hanya menjadi arena benturan identitas-identitas, melainkan menjadi ruang untuk mencapai pengertian timbal balik. Perjuangan untuk pengakuan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan untuk saling mengerti dalam masyarakat majemuk.
Tulisan ketiga, berasal dari Moh Yasir Alimi, menukik lebih dalam ke tema identitas. Persoalan identitas tidak hanya dibahas dalam konteks komunikasi dalam ruang publik, melainkan juga dalam konteks materialitasnya, yaitu gender dan seks. Tokoh yang dibahas adalah Judith Butler. Sebagaimana jelas dalam tulisan Yasir, Butler ingin melampaui “metafisika” identitas yang berasal dari feminisme yang mengakui “naturalitas seks” sebagai basis gender. Baginya, tak ada yang esensial dari seks. Seks itu bukan substansi, melainkan hasil konstruksi dari relasi-relasi kuasa/pengetahuan yang disebut diskursus. Kita boleh sangsi, apakah Butler seorang feminis atau lebih seorang filsuf poststrukturalis dengan minat teoretis, seperti dikomentari Yasir.
Pemikiran perempuan ini tentang identitas paling mudah diilustrasikan dengan lukisan pelukis Belgia Rene Magritte La trahison des images (pengkhianatan citra-citra), lukisan pipa dengan kalimat Ceci n’est pas une pipe. Seperti Heidegger dan murid-murid Prancisnya—Derrida dan Foucault—Butler berpendapat bahwa tidak ada sesuatu di luar teks, maka petanda (signified), misalnya pipa dalam lukisan Magritte, tunduk di bawah kedaulatan penanda (signifier), yaitu teks di bawahnya. Dengan cara pikir seperti itu, Butler melihat seks dan gender bukan sebagai sesuatu yang “alami”, karena keduanya bukanlah substansi-substansi identitas yang permanen, melainkan hasil—demikian sebutannya—“materialisasi” suatu diskursus.
Dalam arti ini tiada seks/gender yang pra-diskursif Yasir dengan jitu merumuskan pemikiran Butler dengan tesis “tidak ada gender dan seks pradiskursif”. Seks/gender terjadi lewat percakapan, maka adalah nurture dan bukan nature. Dikatakan dengan sederhana: Orang tidak lahir sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan menjadi demikian karena pengakuan akan pertunjukan atau—demikian sebutan Butler—“performativitas”. Contoh yang diberikan Yasir dapat menjelaskan hal itu. Katanya, seperti para waria Thailand dalam pertunjukan drag yang berupaya tampil sedemikian hingga diakui para penonton mereka sebagai perempuan sejati, begitu juga cara kita menjadi laki-laki atau perempuan. Jadi, anda bukan laki-laki atau perempuan sampai orang-orang lain mengakui demikian, maka anda akan terus berupaya mencari pengakuan untuk meneguhkan identitas seksual anda. Heretoseksualitas tidaklah alami, melainkan imitasi.
Namun gagasan Butler juga imitasi dari Foucault dalam Madness and Civilization yang berpendapat bahwa dalam rumah sakit jiwa kewarasan harus terus- menerus meneguhkan diri di hadapan kegilaan sekitarnya. Di sini Butler paling jelas mengambil strategi berpikir postmetafisis dengan memahami identitas, khususnya identitas seksual/gender, bukan sebagai substansi, melainkan relasi-relasi belaka seperti dalam ilustrasi cipola dalam cerita Mann. Kesadaran diri itu kosong dan siap diisi tema-tema diskursif dari luar. Namun berbeda dari empirisme modern (ingat “tabula rasa” Locke), yang mengisi itu bukan sekadar data kognitif, melainkan gumpalan relasi-relasi kognisi, aksi, speech acts dan akhirnya struktur sosial yang oleh Butler diringkas dengan istilah “performativitas”. Butler

6
Makalah Musyawarah Buku | Mei 2013
dan juga Foucault mendapat matriks berpikir postmetafisis dari Heidegger. Guru para poststrukturalis ini pernah menulis bahwa bukan kita yang mengucapkan bahasa, melainkan bahasalah yang mengucapkan kita, dan “bahasa” tidak hanya mengacu pada “bentuk pengetahuan”, melainkan juga “bentuk kehidupan”.
Setelah tiga tulisan yang lebih merupakan—meminjam ungkapan Yasir— “pertunjukkan gagasan filsafat”, tulisan Neng Dara Affiah menutup buku ini dengan mengupas pemikiran Ziba Mir-Hosseini dan mencoba menarik relevansinya untuk hukum keluarga muslim di Indonesia. Tanpa mengabaikan kontribusi ketiga tulisan lain, tulisan keempat inilah yang paling penting untuk realitas sosial di Indonesia. Anda boleh saja bicara soal postmetafisika dan dekonstruksi gender, tetapi semua perbincangan canggih itu kosong saja, bila tidak mendarat ke realitas hukum. Ada jurang yang dalam di antara pemikiran filosofis Barat yang sekarang memasuki tahap postmetafisis dan pemikiran hukum Islam. Arendt, Benhabib dan Butler telah melampaui tidak hanya teosentrisme, melainkan juga antroposentrisme dengan masuk ke dalam logosentrisme, sementara pemikiran hukum Islam masih berkutat dengan teosentrisme yang di Barat sudah lama sekali ditinggalkan. Namun hal itu bukan masalah khas Islam, karena modernitas memang bertegangan dengan norma-norma agama pada umumnya. Hal itu menjadi masalah karena kebanyakan masyarakat muslim belum tersekularisasi seperti Barat, sehingga hukum sakral masih dipercaya sebagai norma politis.
Meringkas sejarah hukum Islam, Affiah, mengacu pada Mir-Hosseini, berpendapat bahwa akar persoalan stagnasi perkembangan hukum Islam ada di abad ke-10. Empat mazhab hukum—Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali—“dianggap telah sempurna, maka pada abad ke-10 terdapat deklarasi bahwa ijtihad telah tertutup”. Apa yang dilakukan oleh Mir-Hosseini adalah—jika kita boleh memakai istilah R. Bultmann—semacam “demitologisasi” tradisi Islam. Demitologisasi adalah bagian wawasan dunia Pencerahan yang mencoba mengasalkan narasi-narasi mitis dan sakral pada penyebab-penyebab empiris dan profan. Dengan ungkapan lain, Mir-Hosseini hendak membuka kembali pintu tafsir rasional atas hukum sakral dengan memahami konteks historis asal-usul hukum itu. Di akhir ulasannya, Affiah menyoroti bagaimana analisis Mir-Hosseini atas praktik hukum zina, khususnya hukuman cambuk, di Aceh dan tegangannya dengan HAM. Dengan tilikan kritis feminis muslim ini, Affiah mengkritik praktik hukum Islam yang memarginalisasi suara perempuan dan mendiskriminasi perempuan, sambil menyayangkan tidak terjadinya saling belajar antara para aktivis HAM dan para feminis di satu sisi dan para sarjana muslim di sisi lain.
PenutupBagaimana mengomentari persoalan yang diangkat oleh buku ini? Tulisan-
tulisan kaum feminis, khususnya yang masuk ke dalam labirin kerumitan perasaan, kebertubuhan dan identitas, secara paling sederhana dapat dilukiskan dalam iklan pembalut: “Karena wanita ingin dimengerti”. Pembaca awam dibuat bingung oleh tulisan-tulisan itu, sehingga berujar: “Perempuan memang sulit dimengerti”.

7
Makalah Musyawarah Buku | Mei 2013
Bahkan laki-laki filsuf abad ke-19, Kierkegaard, pernah mengatakan bahwa perempuan itu sebuah enigma. Ada pesona yang bikin penasaran, tetapi di ujung sana kita akan menjumpai aporia. Akan tetapi keempat perempuan filsuf, sejauh diulas dalam buku ini, mengajukan gugatan yang jelas dan diarahkan kepada masyarakat yang didominasi laki-laki. Gugatan mereka berbunyi seperti judul film komedi yang dibintangi Mel Gibson pada 2000 lalu, “What Women Want”.
Apakah yang diinginkan para perempuan? Pertama, mereka ingin kebebasan. Kedua, mereka ingin kesetaraan. Ketiga, mereka ingin berbela rasa dengan mereka yang mengalami marginalisasi, diskriminasi dan represi. Untuk mengguncang patriarki dan moral agama yang mereka anggap menindas perempuan, kaum feminis tak jarang mekakukan aksi-aksi radikal, seperti yang dilakukan, misalnya, oleh kelompok Femen. Kelompok asal Ukraina pimpinan Inna Schevchenko ini “serangan” topless ke berbagai forum resmi yang dihadiri para tokoh penting, seperti Putin, Merkel dan bahkan Paus, untuk memprotes ortodoksi moral yang membelenggu perempuan. Femen ingin meradikalkan feminisme dengan memakai tubuh, khususnya payudara, bukan sekadar untuk berteori, melainkan sebagai senjata. Tulisan-tulisan yang dihimpun dalam buku ini memang tidak seradikal Femen dalam menyerang patriarki. Tujuan mereka bukan untuk aksi protes, melainkan mengajak berpikir jernih tentang keadilan gender.
Bagaimana persoalan gender dipikirkan dapat dikembalikan pada kultur yang berbeda-beda. Femen mungkin adalah cara yang dapat mengundang perhatian bagi masyarakat liberal, tetapi protes Femen di masyarakat muslim mungkin akan kontraproduktif. Sebaliknya, analisis kritis Mir-Hosseini yang terasa tidak seradikal para feminis Barat mungkin malah dapat membantu masyarakat muslim untuk mereformasi diri. Pada akhirnya, persoalan identitas dan gender dapat dikembalikan pada rasa keadilan yang berkembang di dalam sebuah masyarakat. Namun satu fakta makin jelas: Globalisasi dan liberalisasi dalam masyarakat-masyarakat kompleks dewasa ini akan membuat identitas dan gender kian menjadi persoalan yang penting yang tidak dapat lagi didasarkan semata-mata pada agama. Dalam arti ini pula pemikiran postmetafisis, sebagaimana dipraktikkan Arendt, Benhabib dan Butler, menjadi makin relevan. Buku yang sekarang sedang kita diskusikan ini sungguh merupakan tantangan bagi mentalitas patriarkis yang masih bercokol dalam banyak kepala di dalam masyarakat kita.
Jl. Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Indonesiat: +62 21 7891202 f:+62 21 7818849 www.salihara.org