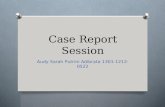CRS Asfiksia Fix
-
Upload
ferdian-el-pulga -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
description
Transcript of CRS Asfiksia Fix
BAB IPENDAHULUANAsfiksia pada BBL menjadi penyebab kematian 19% dari 5 juta kematian BBL setiap tahun. Di Indonesia, angka kejadian asfiksia di rumah sakit provinsi Jawa Barat adalah 25,2 %, dan angka kematian karena asfiksia di rumah sakit pusat rujukan propvinsi di Indonesia sebesar 41,94%. Data mengungkapkan bahwa kira2 10% BBL membutuhkan bantuan untuk mulai bernafas, dari bantuan ringan (langkah awal dan stimulasi untuk bernafas) sampai resusitasi lanjut yang ekstensif. Antara 1% sampai 10% BBL di rumah sakit membutuhkan bantuan ventilasi dan sedikit saja yang membutuhkan intubasi dan kompresi dada. Sebagian besar bayi tidak membutuhkan atau hanya sedikit memerlukan bantuan untuk memantapkan pernapasannya setelah lahir dan akan melalui masa transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin tanpa masalah.Kebutuhan resusitasi dapat di antisipasi pada sejumlah besar BBL. Walaupun demikian, kadang-kadang kebutuhan resusitasi tidak dapat diduga. Oleh karena itu tempat dan peralatan untuk melakkukan resusitasi harus memadai, dan petugas yang sudah dilatih dan terampil harus tersedia setiap saat dan di semua tempat kelahiran bayi. Luaran dari BBL setiap tahun akan menjadi lebih baik dengan penyebaran teknik melakukan resusitasi.
BAB IILAPORAN KASUS
A. DATA DASARI. IDENTITASNama: By. Ny. DTanggal Lahir: 31 Mei 2015Jenis Kelamin: Laki lakiAgama: KristenOrang TuaNama Ayah: Tn. JUmur: 32 TahunPekerjaan: WiraswastaPendidikan: SMANama Ibu: Ny. DUmur: 30 TahunPekerjaan: Ibu Rumah TanggaPendidikan: SMPNo. RM: 799979MRS: 31 Mei 2015
II. ANAMNESISAlloanamnesis dilakukan pada orang tua bayi, pada tanggal 2 juni 2015 Keluhan utama : lahir tidak segera menangis.
Riwayat penyakit sekarangTanggal 31 Mei 2015 pukul 19.00 WIB Ny.D, ibu G1P1A0, usia 30 tahun hamil 28 minggu, melahirkan seorang bayi Laki laki di rumahnya, proses lahir spontan pervaginam ditolong oleh bidan. Riwayat ANC (+) di bidan, riwayat demam (-), riwayat KPD (-), riwayat KWH (-), riwayat minum jamu saat hamil (-), trauma (-), kencing manis (+), darah tinggi (-), minum obat selain resep dari bidan (-).Os lahir secara spontan pervaginam, namun tidak segera menangis. Kemudian os dibawa ke puskesmas, kemudian dirujuk ke RSUD Raden Mattaher. Os datang ke IGD dengan sianosis pada ekstremitas dan bibir, APGAR score 4-5, berat badan lahir 1400 gram, panjang badan 39 sentimeter. Tanda vital, SPO2 95%, HR 141 kali/menit, RR 88 kali/menit. Os menerima terapi oksigen dan pencegahan hipotermi. Kemudian os dirawat di ruang Perinatalogi. Riwayat penyakit dahuluIbu dengan riwayat DM tipe II (+)
Riwayat penyakit keluargaTidak ada keluarga yang mengalami hal seperti ini
Riwayat sosial ekonomiAyah bayi bekerja sebagai wiraswasta, ibu bayi bekerja sebagai IRT. Penghasilan rata-rata tidak menentu, namun menurut ibu bayi penghasilan tersebut sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Riwayat perawatan prenatal dan postnatalPrenatal : ibu os melakukan kontrol kehamilan 4 kali di bidan. Setiap kali periksa ke bidan, ibu diberi vitamin tablet penambah darah sebanyak 9 butir.Postnatal : os tidak segera menangis setelah lahir, os kemudian dibawa ke puskesmas. Kemudian dirujuk ke RSUD Raden Mattaher dan menerima perawatan di IGD dan ruang Perinatalogi.Riwayat KelahiranNoKehamilan dan KelahiranTanggal Lahir / Umur
1Laki laki, preterm, di rumah, bidan, BBL 1,4 kg31 Mei 2015
Riwayat Imunisasi :(-)Riwayat Pemberian Makan :(-)Riwayat Pertumbuhan dan Perkembangan :Belum dapat dinilai
Riwayat Keluarga Berencana Orang Tua :Ibu os menggunakan KB suntik
III. PEMERIKSAAN FISIKTanggal 31 Mei 2015Bayi Laki laki, umur 0 hari, BB 1400 gram, PB 39 cmKesan umum: hipoaktif, merintih, kebiruan (sianosis)Tanda vital: Nadi= 141 x/menit RR= 88 x/menit T= 35,7 oC SpO2= 95 %Kepala: normocephalRambut: penyebaran rambut merata, rambut berwarna hitamKulit: biru kemerahanMata: konjungtiva anemis -/-, sklera ikterik -/-Telinga: simetris kanan dan kiri, daun telinga lunak, lubang (+)Hidung: simetris, nafas cuping hidung (+)Mulut: simetris, tampak sianosis, tidak ada kelainanLeher: pembesaran KGB (-), tortikolis (-)Dada: gerakan dada simetris, retraksi (+), areola jelas menonjol, bunyi vesikuler +/+, rhonki -/-, wheezing -/-Abdomen: supel, benjolan -/-, bising usus (+)Ekstremitas: simetris, kebiruan, akral hangatGenitalia: bersih, labia mayora minora jelasAnus: (+)Kelainan lain: (-)
IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG31 Mei 2015: GDS 54 mg/dlHb: 16,0 g/dlHt: 49,2 %RBC: 4,98 106/mm3WBC: 10,0 103/mm3PLT: 294 103/mm3MCH: 32,1MCV: 99MCHC: 32,6 g/dlB. DIAGNOSISNeonatus kurang bulan, Kecil masa kehamilan, asfiksia sedang + RDSC. PENATALAKSANAANDi IGD : Membebaskan jalan nafas, suction lendir, rangsang taktil. Menjaga kehangatan bayi. O2 Headbox 8 L/m Memberikan injeksi neo K 1 mg IM. IVFD D10% + 2 amp Ca Gluconas Observasi TTV. Saran CPAP : CPAP Penuh keluarga menerima dirawat di IGD tanpa CPAPMasuk PRT jam 23.30 wib tgl 31 Mei 20151. Terapi Terpasang CPAP F1O2 30%, PEEP 6, Flow 8 IVFD D10% + 2 amp Ca Gluconas 4,6 cc /jam Injeksi ampicilin 2x70 mg Injeksi gentamicin 8 mg/36 jam Injeksi aminophiylin 0,3 cc selanjutnya 2x0,15cc Pasang OGT -> coba diit TF 0,5 cc/ 12 jam
BAB IIITINJAUAN PUSTAKA
A. Klasifikasi Bayi Menurut Berat Lahir dan Masa Gestasi
Klasifikasi menurut berat lahir yaitu :a. Bayi berat lahir rendahBayi yang dilahirkan dengan berat lahir < 2500 gram tanpa memandang masa gestasib. Bayi berat lahir cukupBayi yang dilahirkan dengan berat lahir > 2500 4000 gramc. Bayi berat lahir lebihBayi yang dilahirkan dengan berat lahir > 4000 gram
Klasifikasi menurut masa gestasi yaitu :a. Bayi kurang bulanBayi yang dilahirkan dengan masa gestasi < 37 minggub. Bayi cukup bulanBayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37 42 mingguc. Bayi lebih bulanBayi yang dilahirkan dengan masa gestasi > 42 minggu
Klasifikasi menurut hubungan berat lahir dengan masa gestasia. Sesuai masa kehamilanb. Kecil masa kehamilanBayi dilahirkan dengan berat lahir (< 10 persentil) menurut grafik Lubchencoc. Besar masa kehamilanBayi dilahirkan dengan berat lahir (> 10 persentil) menurut grafik LubchencoB. Asifiksia NeonatorumAsfiksia neonatorum adalah keadaan dimana bayi baru lahir yang tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Asfiksia neonatorum ditandai dengan keadaan hipoksemia, hiperkarbia, dan asidosis.Konsekuensi fisiologis yang terutama terjadi pada asfiksia adalah depresi susunan saraf pusat sehingga asfiksia merupakan penyebab kematian pada bayi baru lahir. Keadaan asidosis, gangguan kardiovaskuler serta komplikasinya sebagai akibat langsung dari hipoksia merupakan penyebab utama kegagalan adaptasi bayi baru lahir. Kegagalan ini juga berakibat pada terganggunya fungsi dari masing masing jaringan dan organ yang akan menjadi masalah pada hari-hari pertama setelah lahir.PATOFISIOLOGITransisi dari kehidupan janin intrauterin ke kehidupan bayi ekstrauterin, menunjukkan perubahan sebagai berikut. Alveoli paru janin dalam uterus berisi cairan paru. Pada saat lahir dan bayi mengambil nafas pertama, udara memasuki alveoli paru dan cairan paru diabsorbsi oleh jaringan paru. Pada nafas kedua dan berikutnya, udara yang masuk alveoli bertambah banyak dan cairan paru diabsorpsi sehingga kemudian seluruh alveoli berisi udara yang mengandung oksigen. Aliran darah paru meningkat secara dramatis. Hal ini disebabkan ekspansi paru yang membutuhkan tekanan puncak inspirasi dan tekanan akhir ekspirasi yang lebih tinggi. Ekspansi paru dan peningkatan tekanan oksigen alveoli, ke duanya, menyebabkan penurunan resistensi vaskular paru dan peningkatan aliran darah paru setelah lahir. Aliran intrakardial dan ekstrakardial mulai beralih arah yang kemudian diikuti penutupan dukstus arteriosus. Kegagalan penurunan resistensi vaskuler paru menyebabkan hipertensi pulmonal persisten pada BBL, dengan aliran darah paru yang inadekuat dan hipoksemia relatif. Ekspansi paru yang inadekuat menyebabkan gagal nafas.
FAKTOR RESIKOFaktor resiko antepartumFaktor resiko intrapartum
Diabetes pada ibu Hipertensi dalam kehamilan Hipertensi kronik Anemia janin atau isoimunisasi Riwayat kematian janin atau neonatus Perdarahan pada trimester dua dan tiga Infeksi ibu Ibu dengan penyakit jantung, ginjal, paru, tiroid, atau kelainan neurologi Polihidramnion Oligohidramnion Ketuban pecah dini Hidrops fetalis Kehamilan lewat waktu Kehamilan ganda Berat janin tidak sesuai masa kehamilan Terapi obat seperti magnesium karbonat, beta blocker Ibu pengguna obat bius Malformasi atau anomali janin Tanpa pemeriksaan antenatal Usia < 16 atau > 35 tahun Seksio sesaria darurat Kelahiran dengan ekstraksi forsep atau vakum Letak sungsang atau presentasi abnormal Kelahiran kurang bulan Partus presipitatus Korioamnionitis Ketuban pecah lama (> 18 jam sebelum persalinan) Partus lama (> 24 jam) Kala dua lama (> 2 jam) Makrosomia Bradikardia janin persisten Frekuensi jantung janin yang tidak beraturan Penggunaan anestesi umum Hiperstimulus uterus Penggunaan obat narkotika pada ibu dalam 4 jam sebelum persalinan Air ketuban bercampur mekonium Prolaps tali pusat,Solusio plasenta Plasenta previa Perdarahan intrapartum
DIAGNOSISPada bayi yang mengalami asfiksia neonatorum bisa didapatkan riwayat gangguan lahir, lahir tidak bernafas dengan adekuat, riwayat ketuban bercampur mekonium. Temuan klinis yang didapatkan pada neonatus dengan asfiksia dapat berupa lahir tidak bernafas, denyut jantung < 100 x/menit, kulit sianosis atau pucat, tonus otot lemah.APGAR SCORE Skor012
Frekuensi denyut jantungUpaya bernafas
Tonus Otot
Kepekaan reflexWarna kulitTidak ada
Tidak ada
Lemas
Tidak adaBiru, pucat< 100 x/menit
Lambat, tidak teraturEkstremitas sedikit fleksiMenyeringaiTubuh merah muda, ekstremitas biru (akrosianosis)>100 x/menit
Baik, menangis
Gerakan aktifMenyeringai & Batuk/ bersinSeluruh tubuh merah muda
Interpretasi :a. Asfiksia ringanSkor APGAR 7-10b. Asfiksia sedang Skor APGAR 4-6c. Asfiksia beratSkor APGAR 0-3
RESUSITASI BAYI BARU LAHIR
C. Respiratory Distress SyndromeDistres respirasi atau gangguan nafas adalah suatu keadaan meningkatnya kerja pernafasan yang ditandai dengan:a. Takipnea: frekuensi nafas 60 80 kali/menit.b. Retraksi: cekungan atau tarikan kulit antara iga (intercostal) dan atau di bawah sternum (substernal) selama inspirasi.c. Nafas cupig hidung: kembang kempi lubang hidung selama inspirasi.d. Merintih atau grunting: terdengar merintih atau menangis saat inspirasi.e. Sianosis: sianosis sentral atau warna kebiruan pada bibir
Gangguan nafas yang sering terjadi ialah TTN (Transient Tachypnea of Newborn), RDS (Respiratory Distress Syndrome), atau PMH (Penyakit Membran Hialin) dan Displasia bronkopulmoner. RDS neonatorum terjadi pada bayi baru lahir yang pembentukan paru-paru nya belum sempurna. Penyakit ini terjadi karena gangguan pembentukan surfaktan, yang mana memiliki fungsi untuk mempertahankan alveoli agar tidak kolaps. Gangguan sintesis dan sekresi surfaktan ini dapat menyebabkan ateletaksis, ketidaksesuaian ventilasi-perfusi dan hipoventilasi yang menghasilkan hipoksemia dan hiperkarbia. Analisis gas darah menunjukkan bahwa asidosis metabolik dan respiratorik yang menyebabkan vasokontriksi pulmoner mengakibatkan kerusakan integritas endotel dan epitel dengan pengeluaran eksudat protein dan pembentukan membran hialin.Pada banyak kasus, RDS terjadi pada bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Masalah ini jarang ditemukan pada bayi aterm atau lahir pada usia 40 minggu.
MANAJEMEN Lakukan ventilasi dengan menggunakan balon resusitasi dan sungkup atau melalui pipa ett bila pernafasan bayi tidak adekuat Beri oksigen bila ada indikasi seperti sianosis sentral atau hipoksemia Lanjutkan pemberian oksigen dengan konsentrasi yang diperlukan Pemantauan diperlukan dengan mengambil analisis gas darah serial dan pulse oxymeter untuk memantau saturasi O2. Oksigen merupakan terapi utama RDS sebelum pengenalan CPAP Oksigen melalui headbox masih digunakan untuk mengelola bayi dengan RDS. Untuk mengurangi kebutuhan O2 dapat dilakukan: Jaga kehangatan suhu tubuh bayi Hangatkan dan lembabkan O2 yang dihirup dengan menggunakan pemcampur udara Kurangi minum per oral. Hidrasi atau pemberian cairan dan kebutuhan kalori dapat dipenuhi dengan cairan parenteral
D. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)Respiratory distress pada neonatus, adalah salah satu problem terbesar yang kita temui sehari-hari. Respiratory distress tampak sebagai takipneu atau nafas cepat pada bayi baru lahir. Gajala ini dapat berlangsung dari beberapa jam sampai beberapa hari. Diagnosis dan tatalaksana yang tepat sangat penting untuk diterapkan.Continuos Positive Airway Pressure (CPAP) adalah merupakan suatu alat untuk mempertahankan tekanan positif pada saluran napas neonatus selama pernafasan spontan. CPAP merupakan suatu alat yang sederhana dan efektif untuk tatalaksana respiratory distress pada neenatus. Penggunaan CPAP yang benar terbukti dapat menurunkan kesulitan bernafas, mengurangi ketergantungan terhadap oksigen, membantu memperbaiki dan mempertahankan kapasitas residual paru, mencegah obstruksi saluran nafas bagian atas, dan mecegah kollaps paru, mengurangi apneu, bradikardia, dan episode sianotik, serta mengurangi kebutuhan untuk dirawat di Ruangan intensif. Beberapa efek fisiologis dari CPAP antara lain :1. Mencegah kolapsnya alveoli paru dan atelektasis
2. Mendapatkan volume yang lebih baik dengan meningkatkan kapasitas residu fungsional3. Memberikan kesesuaian perfusi, ventilasi yang lebih baik dengan menurunkan pirau intra pulmonar4. Mempertahankan surfaktan
5. Mempertahankan jalan nafas dan meningkatkan diameternya
6. Mempertahankan diafragma.
INDIKASI DAN KONTRA INDIKASIAda beberapa kriteria terjadinya respiratory distress pada neonatus yang merupakan indikasi penggunaan CPAP. Kriteria tersebut meliputi :1. Frekuansi nafas > 60 kali permenit2. Merintih ( Grunting) dalam derajat sedang sampai parah3. Retraksi nafas4. Saturasi oksigen < 93% (predukt 5. Kebutuhan oksigen > 60%6. Sering mengalami apneu
Semua bayi cukup bulan atau kurang bulan, yang menunjukkan salah satu kriteria tersebut diatas, harus dipertimbangkan untuk menggunakan CPAP.Pada penggunaan CPAP, pernapasan spontan dengan tekanan positif dipertahankan selama siklus respirasi, hal ini yang disebut disebut dengan continuous positive airway pressure. Pada mode ventilasi ini, pasien tidak perlu menghasilkan tekanan negatif untuk menerima gas yang diinhalasi. Hal ini dimungkinkan oleh katup inhalasi khusus yang membuka bila tekanan udara di atas tekanan atmosfer. Keistimewaan CPAP adalah dapat digunakan pada pasien-pasien yang tidak terintubasi. Beberapa gangguan nafas atau respiratory distress yang dapat diatasi dengan mempergunakan CPAP antara lain :1. Bayi kurang bulan dengan Respiratory Distress Syndrom2. Bayi dengan Transient Takipneu of the Newborn (TTN)3. Bayi dengan sindroma aspirasi mekoneum4. Bayi yang sering mengalami apneu dan bradikardia karena kelahiran kurang bulan5. Bayi yang sedang dalam proses dilepaskan dari ventilator mekanis6. Bayi dengan penyakit jalan nafas seperti trakeo malasia, dan bronchitis7. Bayi pasca operasi abdomenAdapun beberapa kondisi respiratory distress pada neonatus, tetapi merupakan kontraindikasi pemasangan CPAP antara lain :1. Bayi dengan gagal nafas, dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan support ventilator2. Respirasi yang irregular3. Adanya anomali congenital4. Hernia diafragmatika5. Atresia choana6. Fistula tracheo-oeshophageal7. Gastroschisis8. Pneumothorax tanpa chest drain9. Trauma pada nasal, yang kemungkinan dapat memburuk dengan pemasangan nasal prong10. Instabilitas cardiovaskuler, yang akan lebih baik apabila memdapatkan support ventilator11. Bayi yang lahir besar, yang biasanya tidak dapat mentoleransi penggunaan CPAP, sehingga menimbulkan kelelahan bernafas, dan meningkatkan kebutuhan oksigen
KOMPLIKASI PEMASANGAN CPAPPemasangan nasal CPAP pada beberapa kasus dapat mengakibatkan komplikasi. Komplikasi pemasangan CPAP antara lain :1. Cedera pada hidung, misalnya erosi pada septal nasi, dan nasal snubbing. Penggunaan nasal prong atau masker CPAP dapat mengakibatkan erosi pasa septal nasi, sedangkan penggunaan CPAP dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan snubbing hidung2. Pneumothorak. Kejadian Pneumothorak dapat terjadi karena proses penyakit dari Respiratory Distress Syndrom ( karena alveolar yang over distensi) , dan angka kejadian tersebut meningkat dengan penggunaan CPAP.3. Impedasi aliran darah paru. Terjadi karena peningkatan resistensi vaskularisasi paru, dan penurunan cardiac output, yang disebabkan oleh peningkatan tekanan inthorakal karena penggunaan CPAP yang tidak sesuai.4. Distensi abdomen. Pada kebanyakan neonatus tekanan spingkter oeshiphagus bagian bawah cukup baik untuk dapat menahan distensi abdomen karena tekanan CPAP. Tetapi distensi abdomen dapat terjadi sebagai komplikasi dari pemaangan CPAP. Resiko terjadinya distensi abdomen dapat berkurang dengan pemasangan orogastric tube (OGT)5. Nasal prong atau masker pada CPAP dapat menyebabkan ketidaknyamanan bayi, yang dapat menyebabkan agitasi dan kesulitan tidur pada bayi.PERLENGKAPAN CPAP
Sistem CPAP sendiri terdiri dari 3 komponen yaitu :
1. Sebuah sirkuit yang mengalirkan gas terus menerus, untuk diisap. Sunber oksigen dan udara bertekanan yang menghasilkan gas untuk dihirup. Pencampur oksigen yang memungkinkan gas dapat diberikan sesuai FiO2 yang sesuai. Sebuah flow meter yang mengkontrol kecepatan aliran terus menerus dari gas yang dihirup ( biasanya dipertahankan pada kecepatan 5-7 liter ). Sebuah humidifier yang melembabkan dan menghangatkan gas yang dihirup.2. Sebuah alat untuk menghubungkan sirkuit ke saluran nafas neonatus. Dalam prosedur ini , nasal prong merupakan metode yang paling banyak digunakan.3. Sebuah alat untuk menghasilkan tekanan positif pada alat sirkuit. Tekanan positif dalam sirkuit dapat dicapai dengan memasukkan pipa ekspirasi bagian distal dalam larutan asam asetat 0,25% sampai kedalaman yang diharapkan ( 5cm) atau katupCPAP
Suatu sistem CPAP yang baik mempunyai karakteristik sebagai berikut :
1. Pipanya fleksibel dan ringan sehingga pasien bisa mengubah posisi dengan mudah
2. Mudah dilepas dan ditempel
3. Resistensinya rendah, sehingga pasien bisa bernafas dengan spontan
4. Relatif tidak invasive5. Sederhana dan mudah dipahami, oleh semua pemakai6. Aman dan efektif dari segi biaya.
Sirkuit CPAP lengkap harus dirangkai dan siap digunakan setiap saat. Jika memerlukan CPAP, seharusnya kita hanya tinggal memnyambungkan CPAP ke nasal prong yang sesuai dan tepat ukurannya, menyalakan alat pengatur kehangatan dan mengisi tabung botol outlet dengan air steril.PENGGUNAAN CPAPCPAP adalah salah satu alat yang digunakan sebagai tatalaksana respiratory distres pada neonatus. Seperti penggunaan alat kesehatan lainnya penggunaan CPAP juga harus memperhatikan standard kebersihan dan keamanan. Menjaga kebersiha jalan nafas bayi merupakan kunci keberhasilan tatalaksana paru yang baik. Mencuci tangan yang benar sebelum menyantuh prong atau pipa CPAP, adalah suatu keharusan. Ujung selalng yang lain yang tidak digunakan juga harus bersih., dan harus dijauhkan dari lantai atau tempat yang tidak bersih lainnya.Cara pemasangan CPAP adalah sebagai berikut :1. Tempelkan selang oksigen dan udara ke pencampur dan flow meter, lalu hubungkan ke alat pengatur kelembapan. Pasang floe meter antara 5-10 liter2. Tempelkan satu selang ringan , lemas dan berkerut ke alat pengatur kelembapan.
Hubungkan probe kelembapan, dan suhu ke selang kerut yang masuk ke bayi. Pastikan probe suhu tetap diluar inkubator atau tidak di dekat sumber panas dari penghangat.3. Siapkan satu botol air steril di dekat alat pengatur kelembapan4. Jaga kebersihan ujung selangUntuk menghubungkan sistem ini ke bayi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :1. Posisikan bayi dan naikkan kepala tempat tidur 30 02. Hisap lendir dari mulut, hidung, dan faring. Pastikan bayi tidak mengalami atresia choana3. Letakkan gulungan kain dibawah bahu bayi, sehingga leher bayi dalam posisi ekstensi untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka.4. Lembabkan prong dengan air steril atau Nacl 0,9% sebelum memasukkannya kedalam hidung bayi. Masukkan dengan posisi lengkungan kebawah. Sesuaikan sudut prong dan kemudian sesuaikan selang kerut dengan posisi yang sesuai.5. Masukkan pipa Orogastrik (OGT) dan lakukan aspirasi isi perut, kita boleh membiarkan pipa lambung tetap ditempatnya untuk mencegah distensi lambung6. Pergunakan topi untuk menjaga kehangatan bayi7. Setelah bayi nyaman dan stabil dengan CPAP, barulah kita melakukan fiksasi agarnasal prong tidak bergeser dari tempatnyaSelama penggunaan CPAP hendaknya kita mengevaluasi tanda vital bayi , sistem kardiovaskuler ( perfusi sentral, perifer, tekanan darah), respon neurologis ( tonus otot, kesadaran dan respon terhadap stimulasi), gastrointestinal ( distensi abdomen, visible loops dan bising usus). Hisap lendir harus selalu dilakukan dari rongga hidung, mulut, faring dan perut setiap 2-4 jam, sesuai dengan kebutuhan. Meningkatnya upaya nafas, kebutuhan oksigen, dan insiden apneu atau bradikardi, dapat disebabkan karena adanya lendir berlebih. Untuk melunakkan konsistemsi lendir dapat digunakan NaCl 0,9%.Selama penggunaan CPAP kita harus selalu memantau apakah alat selalu berfungsi dengan baik, dan tidak terjadi perburukan pada kondisi bayi yang mengharuskan kita menghentikan penggunaan CPAP. Berikut adalah kondisi-kondisi yang mengindikasikan kegagalan penggunaan CPAP dan memerlukan ventilasi mekanis :1. FiO2 > 60 % 2. PaCO2 > 60mmHG3. Asidosis metabolik menetap dengan defisit basa > -84. Terlihat retraksi yang semakin lama semakin meningkat dan menunjukkan kelelahan pada bayi5. Sering mengalami apneu dan bradikardia6. Pernafasan yang irregularApabila terjadi kondisi tersebut, maka kita harus mempertimbangkan untuk melakukan intubasi dan support ventilasi mekanik.PEMBERIAN MINUM SELAMA PENGGUNAAN CPAPPemberian minum dapat diberikan selama penggunaan CPAP nasal. Sebelum memberikan makanan harus dilakukan aspirasi terlebih dahulu untuk menghindari udara yang berlebihan di lambung akibat penggunaan CPAP. Jika kondisinya stabil, bayi dapat minum personde.
15
BAB IVPEMBAHASAN
By. Ny D, perempuan lahir secara spontan pervaginam dari G1P1A0 dengan lahir tidak segera menangis. Nilai apgar score menit pertama 4-5. Kemudian dilakukan penghangatan dan rangsangan taktil, namun bayi hanya merintih. Bayi kemudian dibawa ke puskesmas dan mendapat terapi oksigen nasal kanul 2 lt/menit. Karena keterbatasan alat, bayi dibawa ke RSUD Raden Mattaher yang berjarak tempuh 1 jam dari puskesmas. Bayi sampai di IGD dengan sesak dan akral dan bibir sianosis. Di IGD dilakukan resusitasi yang lebih memadai. Kemudian bayi di rawat di ruang perinatalogi.Terdapat kesalahan pada sistem perujukan bayi tersebut. Selama perjalanan dari puskesmas ke rumah sakit, tidak terpasang oksigen pada bayi, bayi hanya diselimuti dengan selimut untuk mencegah hipotermi. Seharusnya bayi tetap menerima terapi oksigen di puskesmas dan di perjalanan.Terdapat beberapa faktor resiko asfiksia neonatorum pada By. Ny V, antara lain bayi lahir prematur (28 minggu), (BBLSR 1400 gr), dan ibu bayi mengidap DM tipe 2. Semua hal tersebut mempengaruhi kematangan paru bayi sehingga bayi sulit melakukan adaptasi setelah dilahirkan.Bayi mendapat terapi oksigen menggunakan headbox karena bayi tampak sesak dan sianosis. Pada beberapa waktu, bila bayi mengalami retraksi dinding dada, maka terapi diganti dengan menggunakan CPAP. Pada tahap awal bayi menerima diit menggunakan OGT, ketika reflek hisap sudah muncul, diit diberikan peroral dan jumlahnya ditambah secara bertahap.Bayi meninggal setelah delapan hari perawatan dengan keadaan bayi yang semakin lama semakin memburuk.
DAFTAR PUSTAKA
1. Kosim MS, Yunanto A, Dewi R, Sarosa GI, Usman A. Buku Ajar Neonatalogi. Edisi 1. Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jakarta, 2014.2. Dadiyanto DW, Muryawan MH, Anindita. Asfiksia Neonatorum. Buku Ajar Ilmu Kesehatan Anak. Universitas Diponegoro. Semarang, 2011.3. Behrman, Kliegman, Arvin. Nelson Ilmu Kesehatan Anak. Edisi 15, Volume I. Jakarta; EGC, 1999.4. Rudolph AM, Hoffman JIE, Rudolph CD. Buku Ajar Pediatri Rudolph. Edisi 20, Volume I. Jakarta; EGC, 2006.5. Neonatal Respiratory Distress Syndrome. Diakses di m.medlineplus.gov/ency/article/001563.htm, diakses tanggal 3 juni 2015.6. Respiratory Distress Syndrome. Diakses di emedicine.medscape.com/article/976034-overview, diakses tanggal 3 juni 201518