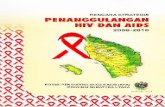Bab 21410160131
-
Upload
carla-rindi-lestari -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of Bab 21410160131

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 1/13
9
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Tentang Hakikat Pembelajaran Biologi
1. Hakikat Belajar Mengajar
Keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan
aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan
pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat
berlangsung secara efektif. Pembelajaran tidak semata-mata menyampaikan
materi sesuai dengan target kurikulum, tanpa memperhatikan kondisi siswa, tetapi
juga terkait dengan unsure manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan
prosedur yang saling mempengaruhi demi mencapai tujuan pembelajaran (Putra,
2013: 15-17). Jadi, pembelajaran adalah interaksi dua arah antara guru dan siswa
serta teori dan praktik.
Belajar dimulai dengan adanya dorongan, semangat dan upaya yang
timbul dalam diri seseorang sehingga orang itu melakukan kegiatan belajar.
Kegiatan belajar yang dilakukan menyesuaikan dengan tingkah lakunya dalam
upaya meningkatkan kemampuan dirinya. Dalam hal ini, belajar adalah prilakumengembangkan diri melalui proses penyesuain tingkah laku. (Majid, 2013:33)
Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah
proses mental yang terjadi dalam diri seseoran, sehingga menyebabkan
munculnya perubahan prilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi
individu dengan lingkungan yang disadari. (Sanjaya, 2010:112). Lebih lanjut lagi,
Majid (2013: 33) menjelaskan bahwa terdapat enam unsur yang dapat
membedakan antara kegiatan belajar dan bukan belajar, yakni mencakup tujuan
belajar yang ingin dicapai, motivasi, hambatan, stimulus dari lingkungan,
persepsi, dan respon peserta didik.
Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai
objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, proses pengajaran tidak lain adalah
kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Belajar pada
hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah
berakhirnya melakukan aktivitas belajar (Djamarah, 2010: 38).

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 2/13
10
Sedangkan menurut Putra (2013: 25-26) dalam bukunya yang berjudul
Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains menyebutkan bahwa
pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa dalam menghadapi kehidupan
masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini, lebih lanjut Putra menjelaskan bahwa
sekolah dan masyarakat adalah suatu integrasi yang dapat menimbulkan suatu
implikasi sebagai berikut:
a.
Tujuan pembelajaran ialah mempersiapkan siswa agar bias hidup dalam
masyarakatnya.
b.
Kegiatan pembelajaran berlangsung dalam hubungan sekolah dan masyarakat.
c. Siswa belajar secara aktif. Artinya, siswa tidak hanya belajar aktif di
laboratorium sekolah dan mencari pengalaman kerja dalam berbagai lapangan
kehidupan, tetapi juga aktif bekerja langsung di masyarakat. Dengan cara ini,
semua potensi siswa dapat berkembang.
d. Guru juga bertugas sebagai komunikator. Maksudnya, guru bertugas sebagai
penghubung antara sekolah dan masyarakat. Guru mempersiapkan rencana
awal pembelajaran, kemudian menyusun rencana lengkap bersama siswa
sebagai persiapan pelaksanaan di lapangan.
Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan
suatu aktivitas yang dilakukan seseorang secara sadar sehingga mengalami
perubahan tingkah laku pada diri individu yang diperoleh dari pengalaman
melalui arahan atau bimbingan dari seorang pendidik sehingga menghasilkan
pengetahuan dan keterampilan.
2. Hakikat Pembelajaran Biologi
Biologi merupakan ilmu yang mengkaji objek dan persoalan gejala alam.
Menurut teori modern, proses pembelajaran tidak tergantung sekali kepada
keberadaan guru (pendidik) sebagai pengelola proses pembelajaran. Hal ini
didasarkan bahwa proses belajar pada hakikatnya merupakan interaksi antara
peserta didik dengan objek yang dipelajari. Berdasarkan hal ini maka peranan
sumber dan media belajar tidak dapat dikesampingkan dalam proses pembelajaran
biologi.
Proses belajar biologi menurut Djohar dalam Sutarsih (2010: 9) merupakan
perwujudan dari interaksi subjek (peserta didik) dengan objek yang terdiri dari
benda, kejadian, proses, dan produk. Pendidikan biologi harus diletakkan sebagai

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 3/13
11
alat pendidikan, bukan sebagai tujuan pendidikan, sehingga konsekuensinya
dalam pembelajaran hendaknya memberi pelajaran kepada subyek belajar untuk
melakukan interaksi dengan obyek belajar secara mandiri, sehingga dapat
mengeksplorasi dan menemukan konsep. Dengan demikian pembelajaran biologi
menekankan adanya interaksi antara subyek dan obyek yang dipelajari. Interaksi
tersebut memberi peluang kepada siswa untuk berlatih belajar dan mengerti
bagaimana belajar, mengembangkan potensi rasional pikir, ketrampilan, dan
kepribadian serta mengenal permasalahan biologi dan pengkajiannya.
Putra (2013: 52-53) menyatakan bahwa sains secara sederhana ialah
pengetahuan yang didapatkan dengan metode tertentu yaitu metode ilmiah,
berbasis penelitian dan penemuan serta berdasarkan fakta-fakta. Lebih lanjunya,
Putra menjelaskan sains bias dianggap sebagai aplikasi, dengan penguasaan
pengetahuan produk sains dapat dipergunakan untuk menjelaskan, mengolah dan
memanfaatkan, memprediksi fenomena alam, serta mengembangkan disiplin ilmu
lainnya dan teknologi.
Dalam pembelajaran Biologi, lingkungan alam sekitar merupakan
laboratorium yang mempunyai peranan penting karena adanya gejala-gejala alam
yang dapat memunculkan persoalan-persoalan sains. Untuk mendapatkan objek
Biologi, alam dengan segenap fenomenanya telah menyediakan informasi yang
dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Djohar
(1987 dalam Suratsih, 2010) menyatakan bahwa terdapat enam syarat-syarat
sumber belajar, yaitu:
a. Kejelasan potensi
b.
Kesesuaian dengan tujuan belajar
c. Kejelasan sasaran
d.
Kejelasan informasi yang dapat diungkap
e.
Kejelasan pedoman eksplorasi
f. Kejelasan perolehan yang diharapkan.
3. Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)
a. Pengertian dan karakteristik PBKL
Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khas
kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi,

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 4/13
12
komunikasi, ekologi dan sebagainya yang menjadi keunggulan suatu daerah,
(Dwitagama, 2007 dalam Asmani, 2012: 29).
Keunggulan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah
merupakan potensi sumber daya spesifik yang dimiliki oleh suatu daerah,
misalnya potensi budidaya apel dan pariwisata yang dimiliki oleh kota Malang,
Jawa Timur. Menurut Ahmad Sudrajat konsep pengembangan keunggulan lokal
diinspirasi dari berbagai potensi, yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber
daya manusia (SDM), potensi geografis, potensi budaya dan potensi historis,
(Asmani, 2012: 29-38).
Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah
agar siswa mengetahui keunggulan lokal daerah tempat mereka tinggal,
memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal tersebut.
Kemudian mampu mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan/jasa atau
kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal, sehingga memperoleh
penghasilan sekaligus melestarikan budaya, tradisi, dan sumber daya yang
menjadi unggulan daerah, serta mampu bersaing secara nasional dan global,
(Asmani, 2012: 41).
Pembelajaran berbasis keunggulan lokal adalah suatu bentuk pembelajaran
yang memadukan sekolah dengan kebudayaan yang berkembang dimasyarakat.
Proses pembelajaran ini melibatkan masyarakat setempat dengan cara
menyesuaikan dan membawa budaya masyarakat setempat dengan bahan ajar di
sekolah. Tujuan pembelajaran dalam konteks ini dirumuskan bersama antara
guru, masyarakat (komite sekolah), pejabat pendidikan setempat dan komponen
lainnya.
Karakteristik utama pembelajaran berbasis keunggulan lokal adalah
dengan dimasukannya unsur-unsur potensi lokal setempat kedalam proses
pembelajaran, mulai dari bahan ajar yang disesuaikan dengan dengan
kebudayaan lokal setempat, metode pengajaran yang menuntut siswa untuk
mampu mengkombinasikan keunggulan lokal dengan konsep pelajaran yag
dipelajarinya, serta berbagai media pembelajaran yang secara tidak langsung
dapat memadukan keunggulan lokal dengan pelajaran yang dilakukan disekolah.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran berbasis keunggulan lokal antara lain: (1)mempersiapkan materi sesuai dengan kondisi budaya masyarakat yang akan

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 5/13
13
diamati; (2) membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan dengan kebudayaan
lokal setempat; (3) merancang skenario pembelajaran yang akan digunakan
selaras dengan tuntunan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan bersama
antara guru, masyarakat (komite sekolah), pejabat pendidikan setempat dan
komponen lainnya; (4) pemilihan metode dan media pengajaran yang menuntut
siswa untuk mampu mengkombinasikan kebudayaan lokal dengan konsep
pelajaran yag dipelajarinya disekolah; (5) pembelajaran dapat dimulai dengan
memberikan tugas yang relevan.
Sedangkan menurut Ahmad (2012: 11) langkah-langkah yang dapat
dilakukan dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah
sebagai beriku:
1.
Penyusunan desain,
2. Kajian konsep,
3. Study literature dan lapangan,
4. Penyusunan model,
5. Uji coba model,
6. Analisis hasil,
7.
Perbaikan/penyempurnaan model,
8.
Seminar (presentasi hasil),
9. Finalisasi model, dan
10. Pelaporan.
Berikut ini adalah strategi implementasi PBKL yang disampaikan oleh
Mursal, 2011 dalam Asmani, 2012: 62-63.
1.
Tahap inventarisasi keunggulan lokal
Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh keunggulan lokal
yang ada di daerah. Keunggulan lokal diinventarisasi dari setiap aspek
sumber daya manusia, sumber daya alam, geografis, sejarah, dan budaya
yang dapat dilakukan melalui teknik observasi, wawancara atau studi
literatur.
2.
Tahap analisis kesiapan satuan pendidikan
Pada tahap ini pendidik atau tim yang ditugaskan sekolah
menganalisis semua kelebihan/keunggulan internal dan eksternal satuan
pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek dengan cara mengelompokkankeunggulan yang saling berkaitan satu sama lain.

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 6/13
14
3.
Tahap penentuan tema dan jenis keunggulan lokal
Tahap ini mempertimbangkan tiga hal, yaitu: 1) hasil inventarisasi
potensi keunggulan lokal yang bernilai komparatif dan kompetitif, 2) hasil
analisis internal dan eksternal satuan pendidikan, serta 3) minat dan bakat
peserta didik.
4. Tahap implementasi lapangan
Tahap implementasi lapangan harus disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing satuan pendidikan, mengacu pada hasil analisis factor
eksternal dan internal, hasil inventarisasi potensi keunggulan lokal, minat
serta bakat peserta didik. Selain itu, harus memperhatikan kompetensi yang
telah dikembangkan atau diterapkan.lebih baik yang dipilih adalah
keunggulan lokal yang dominan pada elemen skill (keterampilan), sehingga
PBKL bias dilaksanakan melalui mata pelajaran keterampilan.
b. Agrowisata Durian Sinapeul sebagai Keunggulan Lokal Kecamatan
Sindangwangi, Majalengka
Dalam rangka mempercepat pencapaian visi Kabupaten Majalengka,
pemerintah Kabupaten Majalengka memuliki rancangan visi untuk
kepariwistaan sesuai dengan Master Plan Kepariwisataan dan Desain ObjekWisata Kabupaten Majalengka 2006 – 2015 adalah “Majalengka sebagai salah
satu daerah tujuan wisata unggulan di Jawa Barat yang berbasis ekowisata dan
agrowisata”. Struktur wilayah pengembangan pariwisata dan satuan kawasan
unggulan di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sindangwangi, Rajagaluh,
Leuwimunding, Sukahaji, Cigasong dan Majalengka termasuk kepada kawasan
pariwisata II tengah yang merupakan kawasan pengembangan antara Utara dan
Selatan yang menyediakan berbagai fasilitas daya tarik wisata alamiyah dan
budaya khusus yang merupaka citra dari pariwisata Kabupaten Majalengka.
Kecamatan Sindangwangi merupakan salah satu daerah di Kabupaten
Majalengkan yang tersohor dengan keunggulan lokal daerahnya yaitu dengan
mengembangkan wisata agro dengan komoditas perlindungan tanaman lokal
durian Sinapeul.
Durian unggul asli Indonesia memiliki jenis yang beragam, diantaranya
adalah sukun, sunan, petruk, sitokong, hepe, perwira dan siriwig. Durian
Sinapeul merupakan salah satu jenis/ ragam durian yang dikembangkan dari

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 7/13
15
durian lokal perwira. Sejak tahun 1993, durian ini telah dikembangkan dengan
menggunakan teknik perbanyakan tanaman yaitu dengan cara okulasi sebanyak
67 pohon yang ditanam pada lahan seluas areal 3/7 Ha untuk dijasikan sebagai
pohon induk.
Teknik okulasi yang dikembangkan dalam perbanyakan tanaman
tersebut, hingga sekarang terus dikembangkan oleh kelompok usaha tani
masyarakat daerah Sinapeul yaitu kelompok usaha Sari Tani. Agrowisata Durian
sinapeul ini sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal baik dengan tujuan
berwisata keluarga maupun dengan tujuan penelitian dalam proses pembelajaran.
B. Hasil Belajar
Peran guru dalam kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual,
menuntut guru mengkreasi lingkungan belajar secara positif (creating positive
learning environment ) dan memberdayakan peserta didik (empowering students).
Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif dan inovatif,
sehingga dihasilkan lulusan yang berwawasan global dan kompehensif (Sudarwan,
2002).
Hasil Belajar merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang
telah melakukan suatu proses dari pengalaman belajar. Hasil belajar ini ditunjukkan
melalui perubahan perilaku yang semakin baik. Kemampuan-kemampuan yang
dimiliki dari hasil belajar ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari
pengetahuan dalam proses belajar. Sehingga seseorang yang melakukan proses belajar
dalam hidupnya akan memiliki pengetahuan intelektual dan kemampuan (life skill )
yang diminatinya.
Menurut Sudjana (2012: 23-31) terdapat tiga ranah yang menjadi Objek
penilaian hasil belajar, yaitu :
1.
Ranah Kognitif
a. Pengetahuan
Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata knowledge
dalam taksonomi Bloom. Pengetahuan hafalan atau untuk diingat seperti rumus,
batasan, definisi, istilah, pasal, nama tokoh, dan nama kota.
b. Pemahaman
Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan adalah pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 8/13
16
yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan,
atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.
c. Aplikasi
Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau situasi
khusus. Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori, atau petunjuk teknis.
d.
Analisis
Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau
bagian-bagian sehingga jelas hirarki dan susunannya. Analisis merupakan
kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe
sebelumnya.
e.
Sintesis
Penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh
disebut sintesis.
f. Evaluasi
Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin
dilihat dari segi tujuan, cara kerja, pemecahan, metode, materi, dll.
2.
Ranah Afektif
Ranah efektif berkenaan dengan sikap dan nilai. ada beberapa jenis kategori
ranah afektif sebagai hasil belajar. Kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar atau
sederhana sampai tingkat yang kompleks, yaitu :
a. Reciving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan
(Stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi,
gejala, dan lain-lain.
b. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap
stimulasi yang datang dari luar.
c. Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilaidan kepercayaan terhadap gejala
atau stimulus.
d. organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi,
termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, dan prioritas nilai
yang telah dimilikinya.
e. karekteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai
yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dantingkah lakunya.

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 9/13
17
3.
Ranah Psikomotor
Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skiil) dan
kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan, yakni :
a.
Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar).
b. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar.
c. Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual,
membedakan auditif, motoris, dan lain-lain.
d. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan.
e.
Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada
keterampilan yang kompleks.
f. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti
gerakan ekspresif dan interpretatif.
Dari berbagai pengertian menurut para tokoh tersebut maka dapat penulis
simpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu sikap yang terbentuk dari proses
pembelajaran yang melibatkan faktor-faktor tertentu seperti kognitif, afektif dan
psikomotor. Selain itu hasil belajar juga bisa berupa kemampuan dan informasi
yang telah didapat selama proses pembelajaran.
C.
Landasan Teori Spermatophyta
Istilah Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, sperma berarti biji dan phyta
berarti tumbuhan. Kelompok tumbuhan ini tubuhnya dapat dibedakan antara akar,
batang, dan daun. Pembuluh angkut berupa pembuluh-pembuluh halus,
memanjang mulai dari akar, melalui batang menuju daun. Ciri khas tumbuhan biji
adalah memiliki biji sebagai alat perkembangbiakan. Kebalikan dari spora yang
merupakan sel tunggal, biji adalah struktur multiseluler dan jauh lebih kompleks.
a.
Perkembangbiakan (reproduksi)
Perkembangbiakan secara generatif/seksual dengan membentuk biji yang
diawali dengan pembentukan gamet ( gametogenesis), penyerbukan ( polinasi),
peleburan gamet jantan dan betina ( fertilisasi) yang menghasilkan Misal, kemudian
menjadi embrio. Perkembangan secara vegetatif/aseksual dengan organ-organ
vegetatif (tunas, tunas adventif, rhizoma, stolon).
b. Klasifikasi Spermatophyta
Berdasarkan bijinya, Spermatophyta dibedakan ke dalam dua sub divisio,yaitu:

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 10/13
18
1)
Gymnospermae (tumbuhan biji terbuka), ciri-cirinya adalah:
- Bunganya berupa strobilus yang mampu menghasilkan sekret berupa tetes
getah yang berisi sel kelamin jantan pada strobilus jantan dan sel telur pada
strobilus betina
- Bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah.
- Merupakan tumbuhan heterospora yaitu menghasilkan dua jenis spora
berlainan.
- Dalam reproduksi terjadi pembuahan tunggal.
-
Manfaat gymnospermae yaitu untuk industri kertas dan korek api, untuk obat-
obatan, untuk makanan, tanaman hias
2)
Angiospermae (tumbuhan biji tertutup)
Golongan tumbuhan berbiji tertutup disebut juga tumbuhan berbunga dan
masuk ke dalam divisi Magnoliophyta. Angiospermae dianggap sebagai
golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tertinggi. Ciri-ciri
tumbuhan Angiospermae adalah sebagai berikut:
- Memiliki bunga yang sesungguhnya
-
Memiliki daun yang pipih, lebar, dengan susunan tulang-tulang yang
beraneka ragam
- Bakal biji atau biji tidak tampak, karena terbungkus dalam suatu badan yang
berasal dari daun buah, yaitu putik.
- Selisih waktu yang relative pendek antara penyerbukan dan pembuahan
- Adanya pembuahan ganda.
Angiospermae digolongkan ke dalam dua kelas, yaitu:
a) Monocotyledon (monokotil)
Ciri-cirinya adalah memiliki kotiledon tunggal dan batang bagian atas
tidak bercabang. Famili yang termasuk pada tumbuhan monokotil adalah
Liliaceae, Amarylidaceae, Poaceae, Zingiberaceae, Musaceae, Orchidaceae,
Arecaceae, Areceae.
b)
Dicotyledon (dikotil)
Ciri utamanya adalah memiliki dua kotiledon (berkeping biji dua).
Famili yang termasuk pada tumbuhan ini adalah Euphorbisceae, Moraceae,
Papilionaceae, Caesa pipiaceae, Mimosaceae, Malvaceae, Born bacaceae, Rutaceae, myrtaceae, Verbenaceae, Rubiaceae.

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 11/13
19
D. Hasil Penelitian yang Relevan
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suratsih (2010) yang berkaitan dengan
keterlaksanaan pembelajaran biologi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
atau Kurikulum 2006, menunjukkan bahwa potensi lokal yang dimiliki sekolah belum
dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran biologi, sedang pemanfaatn
potensi sekolah merupakan salah satu karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan atau Kurikulum 2006. Penyelenggaraan pembelajaran biologi belum
mencerminkan karakteristik satuan pendidikan di tiap sekolah. Pembelajaran biologi
masih menggunakan acuan yang dikembangkan bersama dalam forum MGMP.
Belum banyak perubahan dalam pola pembelajaran biologi menggunakan
kurikulum 2006 dibandingkan dengan pola pembelajaran biologi menggunakan
kurikulum 1994. Artinya, pembelajaran biologi masih didominansi dengan metode
ceramah, interaksi antara subyek belajar dengan objek belajar biologi masih minim,
sedang hakikat pembelajaran biologi adalah terjadinya interaksi yang sesungguhnya
antara subyek belajar dengan objek belajar biologi. Objek belajar biologi berupa
makhluk hidup dan segala aspek kehidupannya.
Sedangkan Eny Winaryati melakukan penelitian mengenai pengembangan
model pembelajaran wisata lokal pada tahun 2010, menyatakan guru sains dituntut
untuk mengkreasi pembelajaran agar dapat memberikan pengalaman mendalam bagi
siswanya. Potensi daerah dengan segala kelebihan dan permasalahannya, dapat
dijadikan sumber belajar dan laboratorium bagi pembelajaran sains. Model
pembelajaran wisata lokal menjadi sangat relevan untuk meningkatkan pembelajaran
sains menjadi lebih bermakna. Potensi daerah menjadi sangat penting untuk
didayagunakan melalui suatu konsep pembelajaran bermakna. Maka menjadi suatu
kebutuhan bagi lembaga pedidikan untuk mendesaian suatu model pembelajaran
berpendekatan potensi daerah. Model pembelajaran yang didesain dan dikembangkan
dengan memanfaatkan kebutuhan daya saing global.
Berdasarkan hasil penelitian I Wayan Suastra dan Ketut Tika (2011) diperoleh
bahwa model pembelajaran berbasis budaya dapat memberikan pengaruh yang lebih
baik terhadap peningkatan prestasi belajar sains siswa dibandingkan dengan
menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini disebabkan karena beberapa
alasan, pertama, model pembelajaran berbasis budaya dapat membantu siswa dalam
menjembatani antara pengetahuan budaya mereka dengan sains di sekolah. Kedua, pembelajaran berbasis budaya membuat siswa lebih mandiri dan memberikan peluang

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 12/13
20
siswa untuk lebih mengeksplor kemampuannya sendiri. Ketiga, model pembelajaran
berbasis budaya didesain berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme
dimana pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa ( student centered ), sedangkan guru
hanya sebagai fasilitator dan mediator.
E. Kerangka Pemikiran
Di dalam proses belajar mengajar di kelas sudah seharusnya guru memiliki
gaya mengajar yang baik, dimana guru harus memilki keterampilan dalam hal meramu
materi pembelajaran dengan mengaitkannya dengan konsep nyata dalam kehidupan
siswa sehari-hari di masyarakat, terutama dengan sains-sains lokal daerahnya sendiri.
Kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar
siswa adalah dengan mengajak siswa untuk belajar dari potensi atau keunggulan lokal
yang ada disekitarnya. Keunggulan lokal yang berkaitan langsung dengan konsep
ekosistem adalah potensi yang dimiliki daerah agraris Majalengka khususnya Desa
Ujungberung Kecamatan Sindangwangi,yakni agrowisata durian yang dikelola oleh
kelompok usaha tani daerah setempat. Lokasi ini dapat dijadikan sebagai laboratorium
alam yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran biologi pada konsep
plantae.
Berawal dari alasan di atas, maka peneliti mencoba menyusun pembelajaran
biologi yang diterapkan dengan cara memasukkan keunggulan lokal agrowisata
sebagai refleksi konkrit pada sub konsep Spermatophyta di kelas X MAN Rajagaluh.
Secara skematis, kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

7/23/2019 Bab 21410160131
http://slidepdf.com/reader/full/bab-21410160131 13/13
21
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran
F. Hipotesis Penelitian
Terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara yang diterapkan
pembelajaran biologi berbasis keunggulan lokal agrowisata durian Sinapeul dengansiswa yang tidak diterapkan pembelajaran biologi berbasis keunggulan lokal
agrowisata durian Sinapeul pada sub konsep Spermatophyta di kelas X MA Negeri
Rajagaluh.
Solusi
Pembelajaran berbasis
keunggulan lokal
GuruSiswa
Peningkatan hasil belajar
siswa
Analisis
Evaluasi
Kesimpulan
Permasalahan
Interaksi
Pembelajaran konvensional(hanya berfokus pada buku
teks)